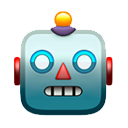Kendati aku dan Boni hanya berbincang hal yang sepele, aku merasa ia tahu apa yang terjadi di dalam diriku. Ia tahu aku limbung, tetapi ia melihatnya bukan sebagai kehancuran tapi kelahiran.
Tanpa kusangka Boni menelponku malam sepulang dari rumah sakit, ragu-ragu kuangkat telponnya.
“Lagi ngapain lo?” kudengar suara Boni dari gagang telpon.
Boni diam sejenak, ada suara bising di dekatnya.
“Keluar yuk, gue lagi bosen di apartemen. Lagi pengen makan sembarangan juga, lo siap-siap sana.”
Aku terkesiap, “Sabar, bung. Main tembak aja, belum tentu gue bisa.”
Aku mengernyit, ternyata suara bising itu adalah suara mesin mobilnya.
“Udah, pokoknya sepuluh menit lagi lo udah siap.” Sergah Boni lalu menutup telponnya.
Aku panik, tak tahu apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu.
“Abis mandi wajib?” Boni berkomentar sembari tertawa.
“Lain kali gue laporin ke polisi lo, ini namanya penculikan dengan paksa.” Balasku.
Boni meneruskan tawanya sampai di mobil, aku duduk di sebelahnya memandangi jalan di luar jendela.
“Kita mau ke mana nih?” aku menoleh ke Boni.
Boni tersenyum kecil, “Sebagai penculik yang baik gue pasti memberi makan target gue, kalo sampe mati gue gak dapet duit dong.”
Kami berdua masuk ke dalam sebuah warung pecel tenda biru di pinggiran jalan.
“Kenapa?” Boni bertanya balik seperti orang tak berdosa.
“Makanan di sini enak, kok. Lagian pikiran lo sempit banget, emangnya kalo makan di resto lebih enak? Enggak, kan?”
“Tapi tetep aja, gak sesuai sama pembawaan lo.” Kilahku.
Aku mendengus.
“Emang lo maunya apa? Sosialis? Apa-apa ngarep disubsidi?” tukasku.
“Enggak juga, gue sih fleksibel. Kalo lagi pengen hedonis ya gue akan jadi hedonis, kalo pengen sosialis lain cerita.
Aku harus mengakui bahwa Boni benar, makanan warung itu enak dan tentunya murah.
“Enak, kan?” ejek Boni.
Aku tak menjawab, hanya mengangguk sembari mendumel.
Bangku plastik yang kududuki berderit, pantatku mulai pegal. Di hadapanku Boni masih memerthatikan, aku merasakan ada sesuatu di matanya.
“Kenapa lo tanya itu?”
Boni berdehem, pita suaranya macet. “Jati diri seseorang banyak terpengaruh sama hubungan dengan orangtua, terutama ibu.”
“Lo gak mesti jawab pertanyaan gue.” Lanjut Boni.
“Hubungan gue sama Mamak sebenernya baik-baik aja, dia tipe ibu yang baik dan menyayangi anaknya. Tapi..” aku berhenti,aku mendengar mamak berbisik.
“Entah kenapa gue merasakan hal yang aneh, kadang gue merasa dekat sama Mamak di satu sisi tapi jauh di sisi lain.” Aku menerawang ke depan.
“Gue gak pernah membicarakan Mamak semenjak gue liat dia di peti mati, baru sekarang gue membicarakannya lagi,” perkataanku ditangkap sebagai sanjungan oleh Boni, dan memang itu adanya. Berbeda dengan orang lain, aku tidak menutup diri pada Boni.
“Di balik sosoknya yang selalu tenang dan mudah bersosialisasi, ada sesuatu yang tidak stabil di dalam dirinya. Ia bisa jadi Ibu bersuara lembut yang menidurkanku dengan dongeng yang ia karang sendiri...
Aku merasakan kepedihan merangakak di dalam suaraku yg lirih,&Boni menangkap kegetiran di wajahku. Ia mencoba memahami dan terus mendengarkan.
“Dengan cara keras, punishment and reward. Dia juga ngajarin gue untuk selalu terlihat sempurna di depan saudara dan teman-temannya, di setiap pertemuan keluarga dia selalu bilang gue akan jadi dokter.”
“Dan dia benar,” Boni menyela.
Boni bertepuk tangan, “Di balik seorang dokter ada ibu bertangan besi.”
“Dan itu lo rasakan sampai sekarang?”
Aku mengangguk.
“Sekarang semuanya jelas.” Boni berkata.
“Apanya yang jelas?”
Boni memberikan senyum samarnya, “kekosongan di mata lo.”
“Curiga kenapa?”
“Dari semenjak ulang tahun Frans, dia gak ada kabarnya.”
“Emangnya dia belum pulang dari tugas luar kotanya?”
“Frans udah jenguk dia ke rumahnya?”
Boni tersenyum sebelah bibir, “Udah, katanya sih emang sakit.”
Ada banyak hal yang mungkin ingin diutarakan Boni, tetapi ia memilih untuk tidak membahasnya.
“Mungkin cuma firasat enggak enak doang kali, tapi ya bisa aja gue salah. Mungkin gue terlalu curigaan.” Boni mengangkat bahu.
“Gue cerita ke ibu tentang elo, dan dia kayaknya tertarik sama elo. Katanya belum pernah ada yang berani bertanya tentang keadaan gue langsung di depan gue, jadi siapapun yang melakukan itu pasti dia deket sama gue.”
Boni menepuk pundakku, “Gue udah bilang kalo gue gak tersinggung, malah kalo lo mau ngelanjutin juga gak apa-apa.
Dadaku langsung nyeri, seperti disundut dengan rokok menyala dari dalam.
Rupanya benar Boni tahu apa yang aku pikirkan semenjak hari itu, aku berusaha tenang tapi kegelisahanku sudah keburu terdeteksi.
Aku tak bersuara.
“Setelah ayah meninggal, ibu adalah orang yang paling berarti buat gue.
Aku merasa tersudut, tidak ada pilihan yang dapat kuambil. Aku harus menerimanya.
“Oke, gue akan dateng. Tapi dengan syarat lo juga ajak Frans.” Jawabku.
“Beres.” Sahut Boni.