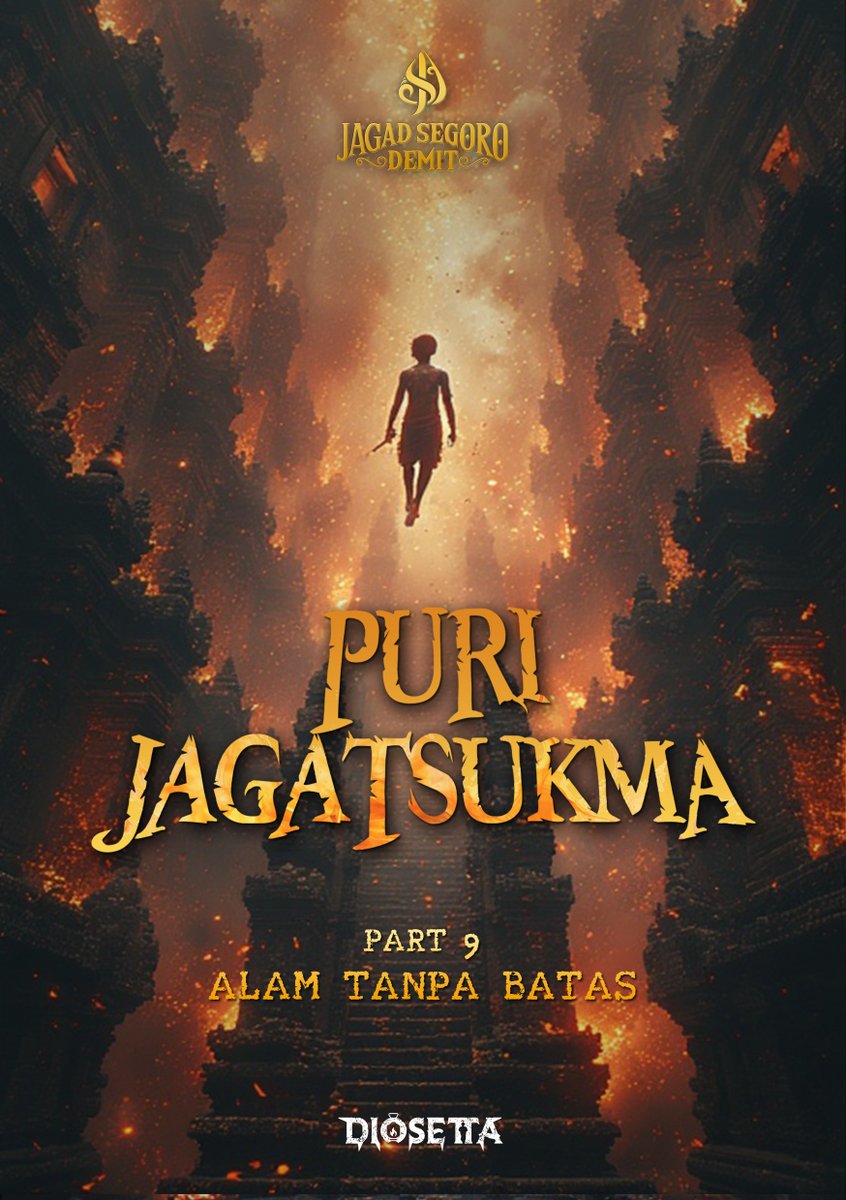Sumur Pemakan Tumbal
Satu-satunya sumber air di desa tak pernah berhenti meminta tumbal
@bacahorror @IDN_Horor @bagihorror @qwertyping @ceritaht @Penikmathorror
Disclaimer : Nama desa dan tokoh bukan nama sebenarnya
Satu-satunya sumber air di desa tak pernah berhenti meminta tumbal
@bacahorror @IDN_Horor @bagihorror @qwertyping @ceritaht @Penikmathorror
Disclaimer : Nama desa dan tokoh bukan nama sebenarnya

Kejadian ini terjadi di suatu desa perbatasan jawa tengah dan jawa timur , tepatnya di era 80an ketika pembangunan belum menyeluruh hingga ke kepelosok pelosok desa.
Sebuah desa , sebut saja namanya desa Jatialas merupakan sebuah desa yang dikenal dengan hasil kerajinan tangan yang menjadi komoditas desa.
Perkenalkan , aku Rani .. salah satu warga desa Jatialas yang hidup sangat berkecukupan di desa ini.
Perkenalkan , aku Rani .. salah satu warga desa Jatialas yang hidup sangat berkecukupan di desa ini.
Mungkin dengan segala sesuatu yang kami punya, keluarga kami dianggap sebagai salah satu keluarga yang terpandang.
“ Rani.. belum ke sumur? “ tanya salah seorang warga yang lewat di depan rumahku.
“ini sebentar lagi bu… nanti saya nyusul “ jawabku.
“ Rani.. belum ke sumur? “ tanya salah seorang warga yang lewat di depan rumahku.
“ini sebentar lagi bu… nanti saya nyusul “ jawabku.
Untuk memenuhi kebutuhan air di desa ini , kami harus menimba air dari sumur yang terdapat di ujung perbatasan desa , sebenarnya tidak jauh hanya saja untuk keperluan air di rumah , kami harus setidaknya 2 kali bolak balik sumur.
“ Eh.. Rani, katanya Bapakmu nambah karyawan lagi ya? “ Tanya seorang ibu yang sedang ikut mengantri menimba sumur.
“Iya bu… pesenan dari kota tambah banyak biar bisa diambil semua” Jawabku menjelaskan kepada mereka.
“Iya bu… pesenan dari kota tambah banyak biar bisa diambil semua” Jawabku menjelaskan kepada mereka.
“Wah… makin kaya ya keluarga kamu , harusnya kamu ga usah nimba ke sumur ini lagi.. kan bisa nyuruh anak buah Bapakmu” lanjut ibu itu.
“ hihi… jangan bu, nanti aku jadi males… Bapak yang nyuruh, harus aku yang ke sumur” jawabku.
“ hihi… jangan bu, nanti aku jadi males… Bapak yang nyuruh, harus aku yang ke sumur” jawabku.
Giliranku datang, aku memenuhi jerigen dengan air , segera kembali ke rumah , dan kembali lagi ke sumur hingga bak di rumah terisi penuh. Rutinitas inilah yang terjadi di setiap pagi, Siangnya aku membantu untuk membuat kerajinan.
Semua berjalan seperti rutinitas desa lainya , namun malam ini terjadi hal yang tidak biasa… suara kentongan berbunyi , jumlah kentongan itu menandakan ada orang yang meninggal.. wargapun keluar dari rumah dan berkumpul..
“ mas… siapa yang meninggal? Kejadianya dimana?” tanyaku kepada mas anto yang lewat depan rumahku.
“ Itu , Pak Tardi… katanya jasadnya ditemukan di dalam sumur , ini saya mau ke sana” jawabnya dengan buru-buru.
Aku mengenakan sandalku dan menyusul ke sana.
“ Itu , Pak Tardi… katanya jasadnya ditemukan di dalam sumur , ini saya mau ke sana” jawabnya dengan buru-buru.
Aku mengenakan sandalku dan menyusul ke sana.
Benar yang diceritakan mas anto , jasad Pak Tardi terlihat tebaring di sisi sumur dengan wajah yang sudah ditutup selembar kain, terlihat perangkat desa sedang sibuk memeriksa kondisi jasad dan lokasi.
Aku pulang dan menceritakan ke Bapak dan ibu , namun sepertinya mereka tidak terlalu pedulli. Padahal dulunya Pak Tardi pernah bekerja pada Bapak sebelum akhirnya mengundurkan diri.
Setelah kematian Pak Tardi warga takut menggunakan sumur tersebut mungkin karena merasa kurang bersih juga. Dengan kondisi itu , warga mendesak perangkat desa untuk membuat aliran air dari PDAM .
akhirnya dalam waktu sebulan semua itu terealisasi dan sumur itu jarang digunakan lagi.
Seluruh warga sudah bisa menikmati air bersih dari pam, namun entah mengapa Bapak masih menyuruhku untuk menimba dari sumur tersebut. Sebenarnya aku tidak masalah,
Seluruh warga sudah bisa menikmati air bersih dari pam, namun entah mengapa Bapak masih menyuruhku untuk menimba dari sumur tersebut. Sebenarnya aku tidak masalah,
hanya saja terkadang aku merasa ada sesuatu mengawasiku dari suatu tempat.
Malam ini suara kentongan kembali terdengar, seorang anak kecil hilang seharian dan ternyata ditemukan lagi di dalam sumur.
Malam ini suara kentongan kembali terdengar, seorang anak kecil hilang seharian dan ternyata ditemukan lagi di dalam sumur.
Warga kembali heboh dan menuntut untuk menutup sumur itu , namun yang mengherankan.. Bapak tidak setuju , dengan alasan sumur sebagai cadangan air saat pdam bermasalah.
Karena Bapak adalah orang berpengaruh , warga dan perangkat desa tidak dapat berbuat apa-apa ,
Karena Bapak adalah orang berpengaruh , warga dan perangkat desa tidak dapat berbuat apa-apa ,
namun warga sudah sama sekali tidak ada yang menggunakan sumur itu.
…
..
Sudah sebulan bisnis Bapak tidak berjalan dengan baik, akhrinya Bapak memutuskan untuk memberhentikan beberapa karyawan.
…
..
Sudah sebulan bisnis Bapak tidak berjalan dengan baik, akhrinya Bapak memutuskan untuk memberhentikan beberapa karyawan.
Hal ini terus berlanjut , sesekali aku mendengar perbincangan Bapak dan ibu di kamar..
“ Jangan pak.. udah cukup apa yang kita punya” ucap ibu sayup-sayup dari dalam kamar.
“ Jangan pak.. udah cukup apa yang kita punya” ucap ibu sayup-sayup dari dalam kamar.
“Nggak buk.. kita ga bisa jatuh miskin lagi , dari awal kita sudah siap akan resikonya” ucap Bapak dari dalam kamar.
Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan , namun setelahnyapun mereka masih berdebat.
Esoknya aku membantu membuat kerajinan bersama pekerja yang lain.
Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan , namun setelahnyapun mereka masih berdebat.
Esoknya aku membantu membuat kerajinan bersama pekerja yang lain.
Terlihat dari jauh Bapak menghampiriku dengan membawa sebuah kendi.
“ Nduk… nanti malam kamu mampir ke sumur ya.. bawa kendi ini dan isi sampai penuh” ucap Bapak dengan menyerahkan sebuah kendi tua.
“u.. untuk apa pak?” tanyaku bingung.
“ Nduk… nanti malam kamu mampir ke sumur ya.. bawa kendi ini dan isi sampai penuh” ucap Bapak dengan menyerahkan sebuah kendi tua.
“u.. untuk apa pak?” tanyaku bingung.
“sudah , ga usah tanya-tanya… “ ucapnya dengan raut wajat yang serius.
Aku menuruti perintah Bapak , setelah langit mulai gelap , sebuah kendi tua kubawa menuju sumur. Walaupun sudah terbiasa tapi aku merasa ada yang aneh dari semua ini.
Aku menuruti perintah Bapak , setelah langit mulai gelap , sebuah kendi tua kubawa menuju sumur. Walaupun sudah terbiasa tapi aku merasa ada yang aneh dari semua ini.
Sebuah sumur tua terlihat di hadapanku , tidak ada penerangan yang selain lampu minyak yang kubawa. Sedikit demi sedikit aku menimba sumur dan mengisi kendi tua pemberian Bapak, namun sebelum sempat penuh tali dan emberku tersangkut , sebuah benda ikut terbawa..
Aku menariknya sekuat tenaga hingga benda itu terangkat ke atas dan terjatuh di samping sumur. Lampu minyak kudekatkan ke benda itu dan yang terlihat sungguh mengerikan.
Jasad bayi yang sudah membusuk dengan bau menyengat tergeletak di pinggir sumur..
Jasad bayi yang sudah membusuk dengan bau menyengat tergeletak di pinggir sumur..
Aku menutup mulut dan hidung menahan bau busuk yang muncul dari jasad itu , segera kuangkat lampu minyak dan bersiap berlari meninggalkan sumur.
Belum sempat berdiri , badanku tertahan dengan sesosok makhluk yang muncul dari belakangku.
Belum sempat berdiri , badanku tertahan dengan sesosok makhluk yang muncul dari belakangku.
Makhluk perempuan dengan wajah yang membusuk dengan rambut putih yang disanggul berantakan berdiri tepat di depan wajahku.
“ mau kemana nduk… sekarang di sini tempatmu” ucap makhluk itu kepadaku.
“ mau kemana nduk… sekarang di sini tempatmu” ucap makhluk itu kepadaku.
“to.. tolong!!!” aku mencoba berteriak , namun sepertinya tidak ada yang mendengar.
“ Bapakmu sudah menyerahkanmu pada kami untuk ditukar dengan kekayaanya… sekarang kamu milik kami” ucap makhluk itu.
“ Bapakmu sudah menyerahkanmu pada kami untuk ditukar dengan kekayaanya… sekarang kamu milik kami” ucap makhluk itu.
Beberapa makhluk lain mulai muncul dari semak-semak di sekitar sumur dan bersiap menghampiriku.
“nggak.. gak mungkin, Bapak ga mungkin ngelakuin itu! “ bantahku dengan air mata yang mulai menetes.
“nggak.. gak mungkin, Bapak ga mungkin ngelakuin itu! “ bantahku dengan air mata yang mulai menetes.
“ hihihi… disebelahmu itu adalah jasad adikmu , dan jasad ibumu sudah lenyap terlebih dulu” makhluk itu semakin mendekat dan mencengkramkan tanganya ke tubuhku.
Aku menghindarinya dengan kaki yang lemas.
Aku menghindarinya dengan kaki yang lemas.
“Ibu ada di rumah… ga mungkin aku percaya sama demit laknat seperti kamu” teriaku kepada makhluk itu.
“ Ibumu, adikmu, dan kamu adalah tumbal yang dijanjikan ayahmu untuk bisa menjadi kaya dan hidup bersama wanita sundal yang mengaku sebagai ibumu… khikhihi..” ucap demit itu.
“ Ibumu, adikmu, dan kamu adalah tumbal yang dijanjikan ayahmu untuk bisa menjadi kaya dan hidup bersama wanita sundal yang mengaku sebagai ibumu… khikhihi..” ucap demit itu.
Tanpa terasa , setan dari balik semak sudah mencapai tubuhku dan mencengkram dengan erat.
“Ba.. pak! Gak mungkin.. Bapak.. tolong Rani pak!” aku berteriak sambil meronta. Namun tenaga setan itu terlalu kuat.
“Ba.. pak! Gak mungkin.. Bapak.. tolong Rani pak!” aku berteriak sambil meronta. Namun tenaga setan itu terlalu kuat.
Rasa sakit yang tak tertahankan mulai muncul , selama semalaman setan-setan itu mencabik-cabik tubuhku dan menjilati semua darah yang menetes dari lukaku. Setan-setan baru bermunculan melakukan hal yang sama hingga mereka puas dan mengangkatku.
Suara gemericik air terdengar, itu adalah darahku yang menetes ke dalam air di lubang sumur . suara itu terdengar beberapa kali hingga tubuhku menyusul tetesan darahku kedalam lubang itu sebagai tumbal perjanjian Bapak dengan setan-setan ini..
Tamat
#sumurpemakantumbal
Tamat
#sumurpemakantumbal
Semoga cerita ini bisa cukup bikin merinding sambil menunggu #gendingalasmayit part6 di upload besok.
Terima kasih dan selamat membaca
Terima kasih dan selamat membaca
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh