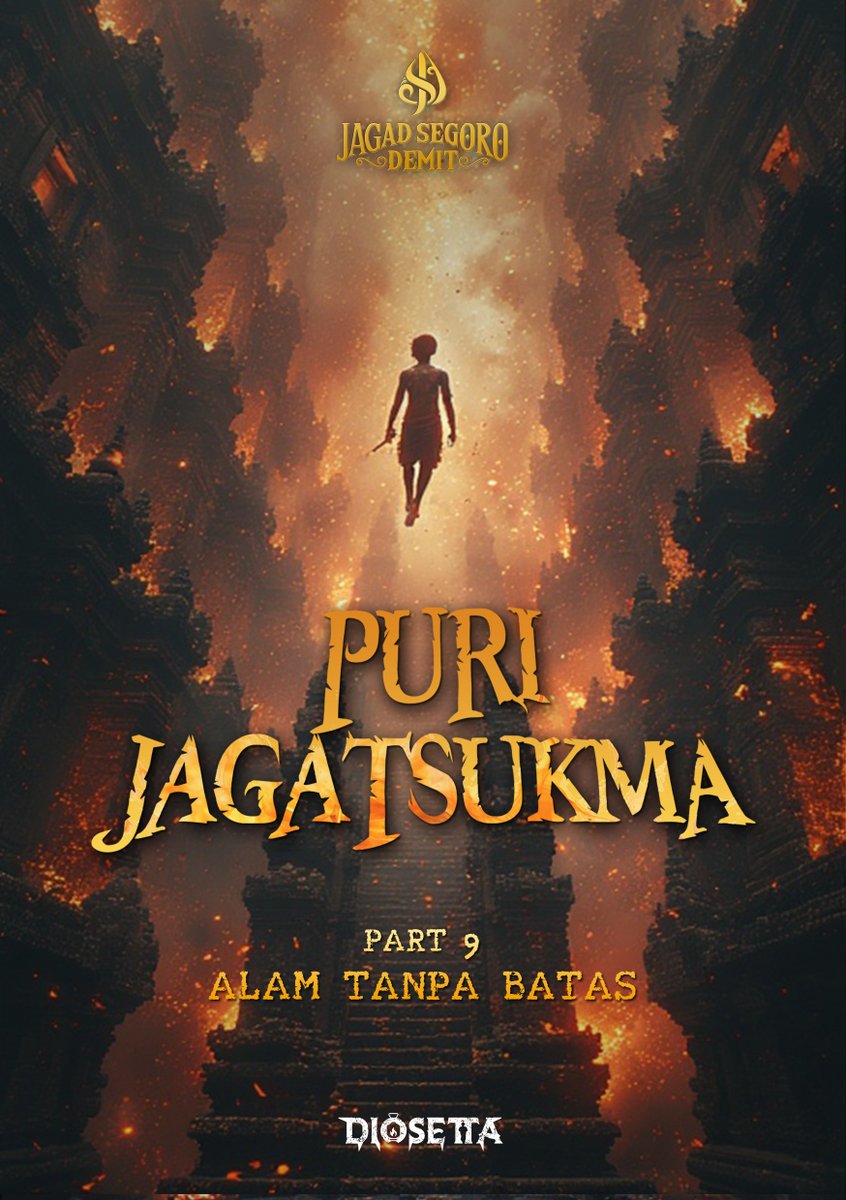Index Cerita Horror by
@diosetta
Selamat Membaca..
Note : untuk share cerita selain Retweet mohon ijin by DM dulu ya..
#ceritahorror #index #diosetta
@diosetta
Selamat Membaca..
Note : untuk share cerita selain Retweet mohon ijin by DM dulu ya..
#ceritahorror #index #diosetta

MAKHLUK DI POHON BERINGIN ASRAMA
(1 Part) Tamat
(1 Part) Tamat
https://twitter.com/diosetta/status/1419590467717537796
LUDRUK TOPENG IRENG
https://twitter.com/diosetta/status/1423094396874985474
PAGELARAN LUDRUK IRENG
https://twitter.com/diosetta/status/1424563556775723016
TRAGEDI PERANG ROJOPATI
https://twitter.com/diosetta/status/1426384059169611782
SANTET BALUNG IRENG
https://twitter.com/diosetta/status/1428952313243201542
SENANDUNG SEDU LEMBAYUNG SENJA Vol. 1
https://twitter.com/diosetta/status/1425752419313487872
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh