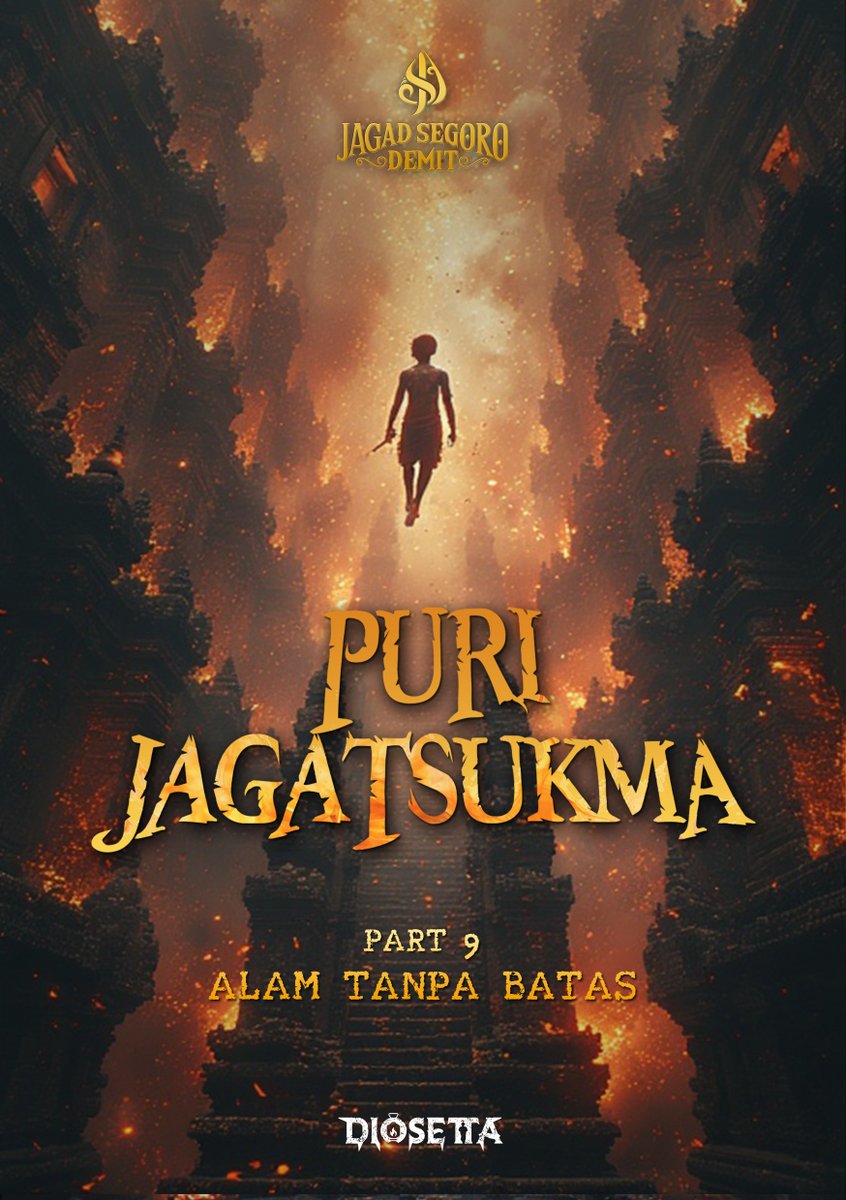PENGHUNI SISI LAIN SEKOLAH
#hipweepremium @hipwee
“Dia … yang kamu cari … terjebak di alam kami ...”
Tiba-tiba terdengar seperti suara seorang nenek dari belakangku.
#hipweepremium @hipwee
“Dia … yang kamu cari … terjebak di alam kami ...”
Tiba-tiba terdengar seperti suara seorang nenek dari belakangku.

Aku menoleh dan hampir saja terjatuh saat melihat seorang nenek mengenakan kebaya hitam dengan wajah yang sudah sangat tua, yang begitu saja berdiri di belakangku.
Dengan kemunculan dan wujud yang seperti itu tidak perlu kemampuan khusus untuk memastikan nenek itu bukanlah manusia biasa. Namun, aku berusaha tetap bersikap sopan kepadanya.
“Maksud Nenek?” tanyaku dengan memberanikan diri.
“Maksud Nenek?” tanyaku dengan memberanikan diri.
“Setelah langit gelap, kamu bisa bertemu dengan temanmu bersama kemunculan mereka. Hanya di waktu itu kamu bisa membawanya kembali.”
Nenek itu berbalik dan meninggalkanku. Perlahan wujudnya menghilang seolah ia memang tidak pernah ada di tempat ini.
Nenek itu berbalik dan meninggalkanku. Perlahan wujudnya menghilang seolah ia memang tidak pernah ada di tempat ini.
“Te—terima kasih, Nek!” ucapku yang sepertinya sudah terlambat untuk didengar olehnya.
Sudah ada sedikit petunjuk. Sepertinya aku harus menunggu lebih lama di sekolah untuk membuktikan apa yang dibilang oleh Nenek itu.
Sudah ada sedikit petunjuk. Sepertinya aku harus menunggu lebih lama di sekolah untuk membuktikan apa yang dibilang oleh Nenek itu.
Aku menunggu di sudut kelasku, sambil melihat sosok roh ibu dan anak yang kemarin membuat kekacauan di sini. Ketika langit mulai memerah, aku mendengar suara gerbang yang sepertinya ditutup oleh Bu Ratna.
Di tengah lamunanku, samar-samar terdengar suara seperti segerombolan orang yang memasuki kelas yang tidak jauh dari kelasku berada. Aku segera keluar untuk mengecek arah suara itu di tengah gelapnya suasana malam sekolah ini...
Tuh kan! udah muncul aja Chapter ke 2!
Ni platform sih keren.. @hipwee ngerangkul penulis penulis Favorit untuk bisa berkarya di sana.
dan yang penting memudahkan pembaca hanya dengan Rp 14.900,-
bisa baca cerita ini sampe tamat + cerita penulis lainya selama sebulan!
Ni platform sih keren.. @hipwee ngerangkul penulis penulis Favorit untuk bisa berkarya di sana.
dan yang penting memudahkan pembaca hanya dengan Rp 14.900,-
bisa baca cerita ini sampe tamat + cerita penulis lainya selama sebulan!
Cara langganannya gimana?
cek di gambar ini ya #hipweepremium
Hipwee premium menyajikan konten2 exclusive dari penulis favorit lho!
untuk membaca bisa klik atau link yang tersedia di Bio ya
bitl.ly/DiosettaHP
#hipwee
#hipweepremium
#diosetta
cek di gambar ini ya #hipweepremium
Hipwee premium menyajikan konten2 exclusive dari penulis favorit lho!
untuk membaca bisa klik atau link yang tersedia di Bio ya
bitl.ly/DiosettaHP
#hipwee
#hipweepremium
#diosetta

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh