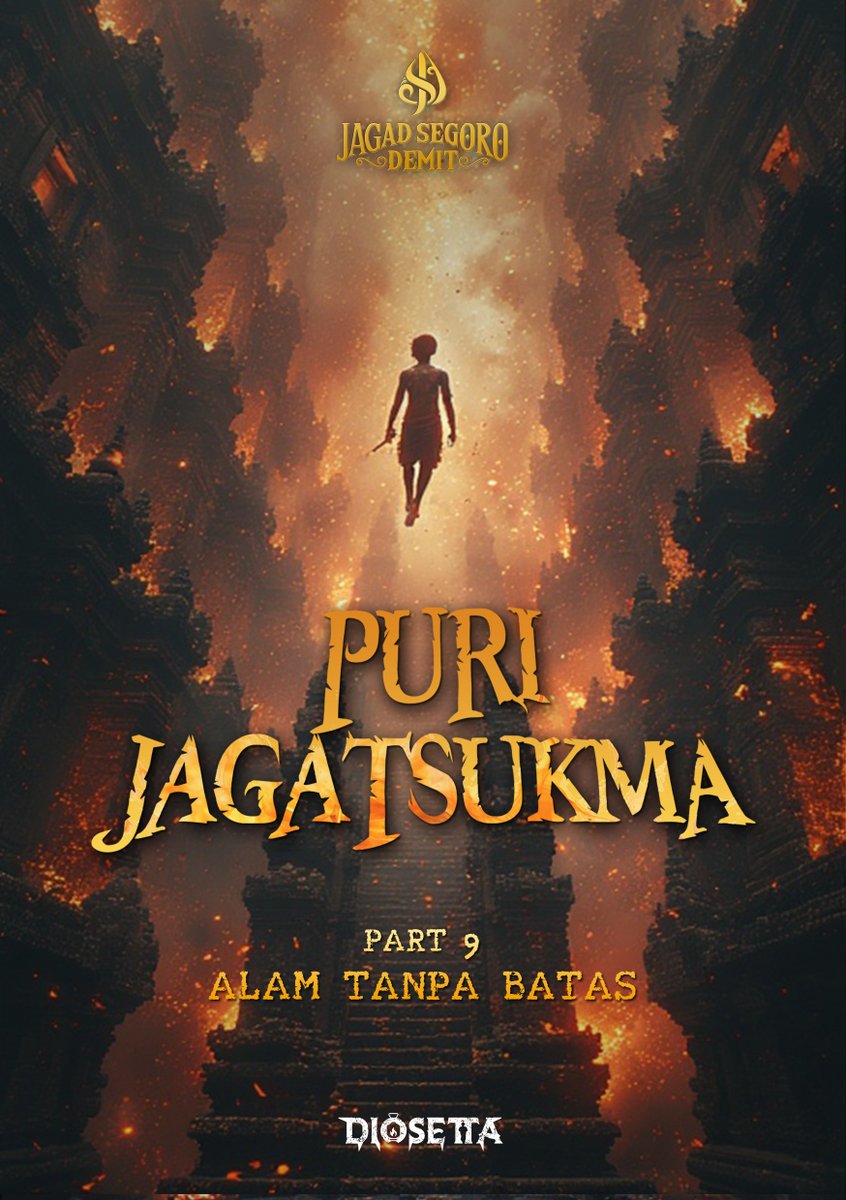Catatan Kecil Kehadiran Mereka
cerita dari narasumber warga twitter yang kental dengan kehadiran mereka yang tak jarang menimbulkan tragedi.
@IDN_Horor
@bacahorror
@qwertyping
@ceritaht
@bagihorror
@HorrorTweetID
cerita dari narasumber warga twitter yang kental dengan kehadiran mereka yang tak jarang menimbulkan tragedi.
@IDN_Horor
@bacahorror
@qwertyping
@ceritaht
@bagihorror
@HorrorTweetID

Yang mau dengerin di youtube bisa mampir ke channel saya ya..
Kenalin namaku Nadia, Aku tinggal di kota Malang yang terletak di propinsi Jawa Timur. Sebagian dari cerita ini mungkin akan didominasi dengan masa kecilku yang sangat kental dengan hal ghaib.
Indigo?
Bukan , aku sendiri tidak bisa menilai mengenai ini.
Indigo?
Bukan , aku sendiri tidak bisa menilai mengenai ini.
Mungkin lebih bisa dikatakan kalau aku termasuk orang yang peka atau sensitif.
Semua kejadian yang ingin kuceritakan ini bermula ketika Mbahkungku meninggal. Yang kumaksud adalah Mbahkung dari almarhumah mamaku.
Semua kejadian yang ingin kuceritakan ini bermula ketika Mbahkungku meninggal. Yang kumaksud adalah Mbahkung dari almarhumah mamaku.
MBAHKUNG
Beliau meninggal kurang lebih Tahun 2010, aku sedikit lupa. Tapi aku selalu mengingat jelas tanggal dan bulan meninggalnya mbahkung karena itu juga mirip dengan tanggal lahirku.
Beliau meninggal kurang lebih Tahun 2010, aku sedikit lupa. Tapi aku selalu mengingat jelas tanggal dan bulan meninggalnya mbahkung karena itu juga mirip dengan tanggal lahirku.
Aku lahir di tanggal satu bulan tujuh. Sedangkan mbahkung lahir di tanggal satu bulan satu dan meninggal di tanggal tujuh bulan tujuh. Entah apa ada yang aneh dengan hal ini? mungkin kita akan tahu nanti.
Mbahkungku ini sebenarya orang yang sangat sabar dan sayang dengan anak dan cucunya. Tapi semua itu akan berubah pada saat ada Mbahti di dekatnya. Seketika Mbahkung akan semakin tegas dan keras dengan cucu-cucunya.
Sejak kecil hingga berumur lima tahun aku tinggal di rumah Mbahkung. Beliau termasuk salah satu tokoh yang dikenal banyak orang.
Yang aku tahu orang-orang sekitar menganggap mbahkung sebagai tukang nyembuhin orang.
Yang aku tahu orang-orang sekitar menganggap mbahkung sebagai tukang nyembuhin orang.
Aku kurang mengerti secara jelas karena saat itu aku masih kecil. Namun yang aku ingat di hari-hari tertentu mbahkung kedatangan banyak tamu dari segala kalangan yang minta ‘tombo’ atau kesembuhan.
Saat kecil dulu aku termasuk anak yang usil. Aku sering mengintip saat mbahkung kedatangan tamu. Disana aku melihat mbahkung selalu duduk bersimpuh dan bersuara dengan suara yang tidak kukenal.
Mbahkung bersuara seperti seorang nenek – nenek tua dengan tubuhnya yang membungkuk sangat rendah. Di sebelahnya ada mbahti yang menjaga dan mempersiapkan kebutuhan mbahkung.
Selain itu aku juga sering melihat mereka membeli dupa dan kembang yang saat itu aku sama sekali tidak mengerti kegunaanya. Bahkan sesekali aku pernah iseng menyalakan dupa itu karena kukira dupa itu adalah kembang api.
Saat mulai beranjak besar aku tidak lagi tinggal serumah dengan mbahkung, namun sesekali aku tetap sering bermain ke sana. Menurut saudara-saudaraku aku adalah cucu kesayangan mbahkung dan anak kesayanganya kebetulan juga adalah mamaku.
Saat aku duduk di bangku sekolah dasar aku sering mengingat tentang teman masa kecilku dulu.
Aku sangat dekat denganya, namun saat bermain denganya aku hampir tidak pernah besama dengan teman yang lain. Dia hanya menghampiriku saat aku sedang sendirian.
Aku sangat dekat denganya, namun saat bermain denganya aku hampir tidak pernah besama dengan teman yang lain. Dia hanya menghampiriku saat aku sedang sendirian.
Aku juga sering menceritakan hal ini ke mbahkung , tapi hanya tersenyum mendengar ceritaku.
Setelah cukup besar aku mulai tahu dari warg bahwa beliau ternyata dikenal sebagai keturunan Kyai sakti yang disegani di daerahnya.
Setelah cukup besar aku mulai tahu dari warg bahwa beliau ternyata dikenal sebagai keturunan Kyai sakti yang disegani di daerahnya.
Makanya orang-orang kampung dulu sering berobat ke mbah.
Aku sangat ingat kisah saat seorang ibu yang membawa anaknya dengan panik yang ternyata anak itu menjadi sakit karena dipukul oleh genderuwo.
Aku sangat ingat kisah saat seorang ibu yang membawa anaknya dengan panik yang ternyata anak itu menjadi sakit karena dipukul oleh genderuwo.
Mbahkung berusaha semampunya untuk menolong namun karena terlambat ditangani akhirnya anak itu meninggal.
Hal inilah yang sedikit membuka mataku mengenai bahayanya makhluk-makhluk ghaib yang ada di sekitar kami.
Hal inilah yang sedikit membuka mataku mengenai bahayanya makhluk-makhluk ghaib yang ada di sekitar kami.
Beliau juga pernah menolong dokter yang “diganggu” orang. Di situpun awalnya aku heran, bahkan seorang dokter yang seharusnya mengobati orang lain malah datang ke Mbahkung yang notabene pendidikanya tidak setinggi mereka untuk meminta bantuan.
Ternyata memang ada faktor lain yang tidak bisa ditangani secara medis dan hanya dapat dibantu oleh orang seperti Mbahkungku ini.
Hihi, satu lagi yang aku suka. saat aku mau ujian , Mbahkung pasti sering memberikan minuman yang telah dibacakan doa-doa. Entah fungsinya untuk apa, tapi setelahnya aku selalu bisa menyelesaikan ujianku dengan lancar.
RUMAH KETINTANG
Saat memasuki kelas empat sekolah dasar papa pindah kerja ke kota surabaya. Saat itu juga kami ikut pindah ke sana dan saat itu aku sudah memiliki seorang adik laki-laki.
Aku pindah di daerah ketintang pada tahun dua ribuan.
Saat memasuki kelas empat sekolah dasar papa pindah kerja ke kota surabaya. Saat itu juga kami ikut pindah ke sana dan saat itu aku sudah memiliki seorang adik laki-laki.
Aku pindah di daerah ketintang pada tahun dua ribuan.
Rumahnya cukup tua namun sangat luas. Rumah ini hanya emiliki satu lantai damun ada empat kamar tidur , dua kamar mandi dan sebuah garasi yang cuup besar. Ada juga taman di dalam dan luar rumah. Yang di dalam rumah seperti bekas kolam ikan.
Langit-langitnya cukup tinggi dan los tanpa penutup hanya menggunakan ram-raman. Bagusnya kalau malam masih bisa melihat langit, tapi kalau hujan rumah kami bisa jadi air terjun.. haha.
Di dekat taman ada ruang tamu dan ruang keluarga.
Di dekat taman ada ruang tamu dan ruang keluarga.
Selain itu di dekat dapur ada sebuah sumur yang baunya sangat mengganggu pada saat itu.
“Ojo Pak… ojo tinggal ning kene. Hawane singup”
(Jangan pak, jangan tinggal di sini. Hawanya tidak enak)
“Ojo Pak… ojo tinggal ning kene. Hawane singup”
(Jangan pak, jangan tinggal di sini. Hawanya tidak enak)
Aku mendengar perbincangan ibu yang tidak setuju untuk tinggal dirumah ini. namun bapak merasa keadaan sudah mendesak dan kita harus segera pindah, jadi pendapat ibu harus mengalah.
Walaupun begitu mbahkung sudah memantau rumah ini dan memasang “pagar” untuk melindungi rumah ini.
Saat tinggal dirumah ini aku sering mendengar suara burung hantu dari atas,
Saat tinggal dirumah ini aku sering mendengar suara burung hantu dari atas,
pernah saat adiku bermain di atap bersama teman-temanya ternyata mereka menemukan burung-burung itu membuat sarang dia atas rumahku. Dan katanya ternyata mereka dan tetangga lain mengenal rumahku ini sebagai rumah yang angker.
Keangkeran rumah ini dipertegas dengan pengakuan dari anak pemilik rumah. Rumah ini adalah rumah warisan tapi anak-anak pemilik rumah tidak ada yang mau menempati rumah ini.
Walaupun mereka bercerita seperti itu, kami yang tinggal di rumah ini tidak pernah mendapat gangguan yang berarti bahkan hingga adiku keduaku lahir.
Adik pertamaku biasa dipangil Pindi dan adik keduaku biasa dipanggil Saka. Saat saka lahir aku sudah kelas enam sekolah dasar.
Adik pertamaku biasa dipangil Pindi dan adik keduaku biasa dipanggil Saka. Saat saka lahir aku sudah kelas enam sekolah dasar.
Dengan kelahiranya keluarga ini bertambah besar dan mama terlihat semakin sibuk hingga akhirnya kami memutuskan untuk mencari pembantu.
MBAK IDAH
Pembantu kami bernama Zubaidah yang berasal dari daerah Dampit kabupaten malang. Mbak Idah ini menempati kamar belakang yang memang lama tidak digunakan. Tidak ada yang aneh selama awal-awal bekerja.
Pembantu kami bernama Zubaidah yang berasal dari daerah Dampit kabupaten malang. Mbak Idah ini menempati kamar belakang yang memang lama tidak digunakan. Tidak ada yang aneh selama awal-awal bekerja.
Namun sejak kedatanganya kami mulai menyadari hal-hal aneh yang ada di rumah ini ketika kami sudah memiliki tenaga pembantu untuk benar-benar bersih-bersih seluruh bagian rumah yang selama ini kami hiraukan.
Kami akhirnya mengetahui mengenai kamar mandi belakang yang ternyata menjadi sarang kelabang. Hal itu baru diketahui saat mbak Idah membersihkanya. Ukuran kelabang di sana sangat besar. Malah kata ibu kalau banyak hewan seperti itu biasanya tempat itu ada penunggunya.
Dengan adanya pembantu kami mencoba untuk menguras sumur di dekat dapur. Sayangnya walaupun sudah beberapa kali di kuras sumur itu tetap mengeluarkan bau yang mengganggu.
Adalagi hal aneh di garasi. Lampu di garasi hampir tidak pernah awet. Setiap kami memasang lampu pasti selalu mati. Kami mencoba memeriksa kelistrikan dan bolak balik mengganti lampu tapi tidak ditemukan permasalahanya.
Akhirnya kami memutuskan tidak menggunakan lampu sama sekali di garasi.
Suatu ketika seorang teman bapak yang bisa melihat hal ghaib mampir ke rumah dan ia berkata di beberapa tempat dirumah kami ada yang menempati.
Suatu ketika seorang teman bapak yang bisa melihat hal ghaib mampir ke rumah dan ia berkata di beberapa tempat dirumah kami ada yang menempati.
Yang cukup jelas ada di di sumur tapi teman bapak tidak bilang mengenai wujudnya. Ia hanya menyuruh memasukan ikan di sumur itu dan kami mengikuti saranya.
Entah apa alasanya Mbak Idah tidak pernah mau bila ditinggal sendirian di rumah, dia juga tidak pernah mau menggunakan kamar mandi belakang. Alasanya karena takut. Tapi dia tidak pernah mau menjelaskan ia takut karena apa.
Sampai akhirnya suatu saat mbak idah minta pulang dengan alasan kangen anaknya yang ada di desa. Kami berusaha mengerti keinginanya dan mengantarkanya kembali ke desanya di kabupaten Malang.
Jaman itu daerah rumah mbak idah masih sepi. Hanya hutan-hutan dan sawah sawah yang terlihat sepanjang perjalanan. Jarak dari satu rumah ke rumah lainpun saling berjauhan.
Kami sampai di rumah Mbak Idah sekitar jam tujuh malam. Sehingga kami memutuskan untuk tidak lama berada di sana dan segera kembali ke kota malang.
Karena sudah malam, aku yang saat itu masih kecil tertidur saat perjalanan pulang.
Karena sudah malam, aku yang saat itu masih kecil tertidur saat perjalanan pulang.
Namun samar-samar aku mendengar perbincangan diantara bapak dan ibu.
“Papa.. itu ada orang.. perempuan.. kok larinya kenceng, hampir nyamain mobil kita” Tanya ibu yang melihat sesuatu dari spion mobil di sisinya. Namun bapak hanya diam dan fokus menyetir.
“Papa.. itu ada orang.. perempuan.. kok larinya kenceng, hampir nyamain mobil kita” Tanya ibu yang melihat sesuatu dari spion mobil di sisinya. Namun bapak hanya diam dan fokus menyetir.
“Pa.. tambah banter pa, kok tambah banter iku mlayu e.. ati-ati pa” (Pak tambah kenceng, kok tambah kenceng itu larinya) Ucap ibu yang mulai merasa aneh.
“Wis ma ojo diliat, doa wae” (Sudah ma , jangan dilihat.. doa saja) Ucap bapak yang juga seperti sedang membaca doa.
“Wis ma ojo diliat, doa wae” (Sudah ma , jangan dilihat.. doa saja) Ucap bapak yang juga seperti sedang membaca doa.
“Pa… Iku uwonge di sebelah kaca papa” (Pa itu orangnya di sebelah kaca papa)
“Wis Jarno ma” (Sudah ma, diemin aja)
“Uwonge mesem pa, ayu…” (Orangnya senyum pa, cantik)
“Wis Jarno ma” (Sudah ma, diemin aja)
“Uwonge mesem pa, ayu…” (Orangnya senyum pa, cantik)
Saat itu ibu melihat seorang wanita berkerudung putih dan berbaju putih tersenyum menyeringai di kaca sebelah bapak.
“Wis biarin” Bapak berusaha tidak merespon kemunculan orang itu.
“Wis biarin” Bapak berusaha tidak merespon kemunculan orang itu.
Setelah itu wanita itu terlihat berlari lebih cepat dan masuk ke sebuah rumah besar sebelum akhirnya menghilang.
“kok ilangnya cepet banget pak” Tanya ibu heran.
“wis ma.. uwis, sudah.. nanti tak kasi tau” Balas bapak.
“kok ilangnya cepet banget pak” Tanya ibu heran.
“wis ma.. uwis, sudah.. nanti tak kasi tau” Balas bapak.
Sesampainya di kota saat keadaan sudah mulai ramai bapak mulai bercerita ke ibu.
“Ma.. yang tadi itu kuntilanak. Papa udah liat di spion. Orangnya jelek, wajahnya hancur berdarah-darah. “ cerita bapak.
“Ma.. yang tadi itu kuntilanak. Papa udah liat di spion. Orangnya jelek, wajahnya hancur berdarah-darah. “ cerita bapak.
“Itu tadi nggak ada rumah ma, tadi makhluk itu berlari ke arah pohon-pohon. Dia masuk ke situ lalu hillang”
Seketika wajah ibu menjadi pucat dan berkali-kali membaca istighfar.
Setelah itu kami memutuskan untuk mampir ke rumah mbahkung sebelum kembali ke surabaya.
Seketika wajah ibu menjadi pucat dan berkali-kali membaca istighfar.
Setelah itu kami memutuskan untuk mampir ke rumah mbahkung sebelum kembali ke surabaya.
Mbak Idah akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat kami dengan alasan tidak bisa jauh dari anak. Padahal kami sudah cocok dan mengijinkanya mengajak anaknya ke rumah kami tapi mbak idah tetap ga mau. Entah apa alasan yang sebenarnya ia sembunyikan.
Setelah Mbak Idah ada pembantu lagi yang bekerja di keluargaku, seorang janda. Ia tinggal di rumah kami dengan membawa seorang anaknya juga. Aku memanggilnya mbak Rom.
Berbeda dengan Mbak idah, Mbak Rom ini jauh lebih pemberani. Ia menempati kamar belakang di bawah tangga jemuran di samping kamar mandi.
Pernah aku menanyakan pada Mbak Rom apa dia tidak takut di tempat itu
“Sudah biasa , Yang penting dia tidak mengganggu saya juga berusaha tidak mengganggu” Jawabnya dengan santainya.
“Sudah biasa , Yang penting dia tidak mengganggu saya juga berusaha tidak mengganggu” Jawabnya dengan santainya.
Sesekali aku penasaran dan bertanya kembali apa benar tidak pernah di ganggu sampai akhirnya Mbak Rom cerita.
“Kadang ada yang aneh, kayak ada orang merokok. Ada yang naik turun tangga pas rumah sedang kosong . ada juga yang lempar-lempar batu.
“Kadang ada yang aneh, kayak ada orang merokok. Ada yang naik turun tangga pas rumah sedang kosong . ada juga yang lempar-lempar batu.
Tapi saya berusaha biasa saja”
Dia sungguh berani dan hampir tidak pernah mengeluh. Sayangnya Mbak Rom tidak lama tinggal di rumahku.
Mbak Rom ketahuan sering (maaf) ‘mencuri’ baju –baju adikku, mungkin karena anaknya sama-sama laki-laki.
Dia sungguh berani dan hampir tidak pernah mengeluh. Sayangnya Mbak Rom tidak lama tinggal di rumahku.
Mbak Rom ketahuan sering (maaf) ‘mencuri’ baju –baju adikku, mungkin karena anaknya sama-sama laki-laki.
Saat sudah ketahuan kami terpaksa memberhentikan dia. Padahal tidak jarang kami juga sering membelikan baju dan mainan juga untuk anaknya.
Singkat cerita kami sudah berganti pembantu sampai empat kali selain mbak idah dan mbak rom dua pembantu lainya masih muda.
Singkat cerita kami sudah berganti pembantu sampai empat kali selain mbak idah dan mbak rom dua pembantu lainya masih muda.
Tapi mereka menghilang sendiri dan tidak kembali lagi ke rumah tanpa mau menceritakan sama sekali apa alasan kepergian mereka.
Untungnya saat itu Saka sudah cukup besar dan bisa disambi.
Untungnya saat itu Saka sudah cukup besar dan bisa disambi.
Jadi kami memutuskan untuk ridak sewa pembantu lagi dan aku yang lebih banyak membantu mama untuk beres-beres.
Sayangnya setelah itu sebuah permasalahan menimpa keluarga kami. Tepatnya pada saat aku menginjak kelas satu SMP.
Sayangnya setelah itu sebuah permasalahan menimpa keluarga kami. Tepatnya pada saat aku menginjak kelas satu SMP.
Saat itu karir papa melejit diumurnya yang cukup muda. Sayangnya bukan hanya hal baik saja yang datang pada saat itu tapi sebuah musibah yang sama sekali tidak pernah kusangka.
Dengan karirnya yang sukses banyak wanita yang tertarik dengan papa dan akhirnya entah kenapa Papa bisa kepincut dengan seorang perempuan entah dari mana asalnya.
PELET
Di umurku yang masih belum mengerti dengan permasalahan keluarga aku menyaksikan tak jarang Papa dan Mama bertengkar dengan masalah yang tidak kuketahui sampai aku mendengar kabar mengenai papa yang dekat dengan seorang perempuan.
Di umurku yang masih belum mengerti dengan permasalahan keluarga aku menyaksikan tak jarang Papa dan Mama bertengkar dengan masalah yang tidak kuketahui sampai aku mendengar kabar mengenai papa yang dekat dengan seorang perempuan.
Itu adalah salah satu ujian terbesar untuk keluarga kami. Saat itu Pindi menginja kelas satu SD dan Saka berumur satu tahun.
Keadaan di rumah mulai tidak nyaman , apalagi Papa sempat tidak pernah pulang selama kurang lebih tiga bulan lamanya.
Keadaan di rumah mulai tidak nyaman , apalagi Papa sempat tidak pernah pulang selama kurang lebih tiga bulan lamanya.
Papa yang selama ini aku kenal sebagai sosok panutan kini berubah drastis dan tega meninggalkan kami dan Saka yang masih berumur satu tahun.
Hampir tiap hari aku melihat mama menangis. Namun setiap aku mendekat mama selalu berusaha terlihat tegar di depan anak-anaknya.
Hampir tiap hari aku melihat mama menangis. Namun setiap aku mendekat mama selalu berusaha terlihat tegar di depan anak-anaknya.
“Ma… Papa kok nggak pulang-pulang?”
Seringkali aku menanyakan keberadaan papa ke mama.
“Papa lagi kerja Nadia..”
Hanya itu jawaban dari Mama, namun aku baru sadar bahwa setiap pertanyaanku waktu itu pasti semakin menambah luka di hati Mama.
Seringkali aku menanyakan keberadaan papa ke mama.
“Papa lagi kerja Nadia..”
Hanya itu jawaban dari Mama, namun aku baru sadar bahwa setiap pertanyaanku waktu itu pasti semakin menambah luka di hati Mama.
Ketika sudah mulai tidak mampu menahan permasalahan ini akhirnya mama menghubungi keluarga Papa dan menceritakan semua masalah ini. Hal ini membuat mereka kaget hingga akhirnya memutuskan untuk mendatangi ke rumh kami.
Saat itu mama sangat sulit untuk bercerita seolah semua bebanya sudah menumpuk begitu besar hingga mama hanya bisa menangis. Melihat Mama menangis seketika juga kami anak-anaknya juga ikut menangis.
Sebenarnya Pakde dan Bude sempat blang, kalau mau cerai mereka tidak akan menghalangi karena memang sudah tiga bulan kami tidak diberi nafkah lahir dan batin. namun mereka akan tetap berusaha membantu masalah ini.
Saat itu yang banyak membantu kami adalah Almarhum Pakde Hardi. Beliau benar-benar orang yang sangat baik.
(Alfatihah..mohon doanya untuk beliau)
Banyak hal yang terjadi, dan selama itu Pakdelah yang membantu kami baik secara finansial hingga kebutuhan kami.
(Alfatihah..mohon doanya untuk beliau)
Banyak hal yang terjadi, dan selama itu Pakdelah yang membantu kami baik secara finansial hingga kebutuhan kami.
Dan ternyata mereka juga membantu untuk mencari keberadaan papa dengan bantuan dari seorang Kyai.
Berdasarkan petunjuk dari Kyai itu akhirnya keluarga Papa berhasil menemukan keberadaan perempuan itu di daerah Sepanjang, Sidoarjo.
Berdasarkan petunjuk dari Kyai itu akhirnya keluarga Papa berhasil menemukan keberadaan perempuan itu di daerah Sepanjang, Sidoarjo.
Di sanalah rumah Lina, perempuan yang membuat papa tega meninggalkan keluarganya.
Menurut Kyai yang membatu kami, Perempuan bernama Lina itu menggunakan baju Papa untuk menarik perhatian Papa dengan menggunakan ilmu Pelet.
Menurut Kyai yang membatu kami, Perempuan bernama Lina itu menggunakan baju Papa untuk menarik perhatian Papa dengan menggunakan ilmu Pelet.
Ibunya Lina sendirilah yang melakukan ritual itu seolah memang sudah berniah jahat sejak awal.
keluarga papa datang ke rumah Lina dengan bantuan perangkat desa sekitar yang memang sudah curiga dan mendengarkan cerita dari keluarga Papa.
keluarga papa datang ke rumah Lina dengan bantuan perangkat desa sekitar yang memang sudah curiga dan mendengarkan cerita dari keluarga Papa.
Mereka melakukan penggeledahan dan akhirnya menemukan barang-barang Papa di rumah perempuan itu.
Dengan bantuan dari Kyai tersebut dan beberapa orang yang memang mengerti, Akhirnya Papa kembali ke rumah dengan sendirinya.
Apakah masalah selesai?
Dengan bantuan dari Kyai tersebut dan beberapa orang yang memang mengerti, Akhirnya Papa kembali ke rumah dengan sendirinya.
Apakah masalah selesai?
Tidak,
masalah baru mulai bermunculan .
Entah ada hubunganya dengan perempuan bernama Lina itu atau tidak, akhirnya papa mendapat masalah dengan bossnya yang mengakibatkan Papa dipindah kerjakan ke Kota Makasar. Dan kami berempat tetap tinggal di Surabaya.
masalah baru mulai bermunculan .
Entah ada hubunganya dengan perempuan bernama Lina itu atau tidak, akhirnya papa mendapat masalah dengan bossnya yang mengakibatkan Papa dipindah kerjakan ke Kota Makasar. Dan kami berempat tetap tinggal di Surabaya.
Setelah ditinggal oleh Papa rumah yang kami tinggali terasa berbeda.
Rumah yang sebelumnya nyaman kini mulai terasa menakutkan.
Hampir semua anggota keluarga merasakan kejadian-kejadian yang mengerikan.
Rumah yang sebelumnya nyaman kini mulai terasa menakutkan.
Hampir semua anggota keluarga merasakan kejadian-kejadian yang mengerikan.
Aku akan menceritakan semuanya kisah yang kami alami, teror-teror mengerikan yang kami dapat setelah kepergian Papa..
semua akan kuceritakan di catatan berikutnya..
(Bersambung…)
semua akan kuceritakan di catatan berikutnya..
(Bersambung…)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh