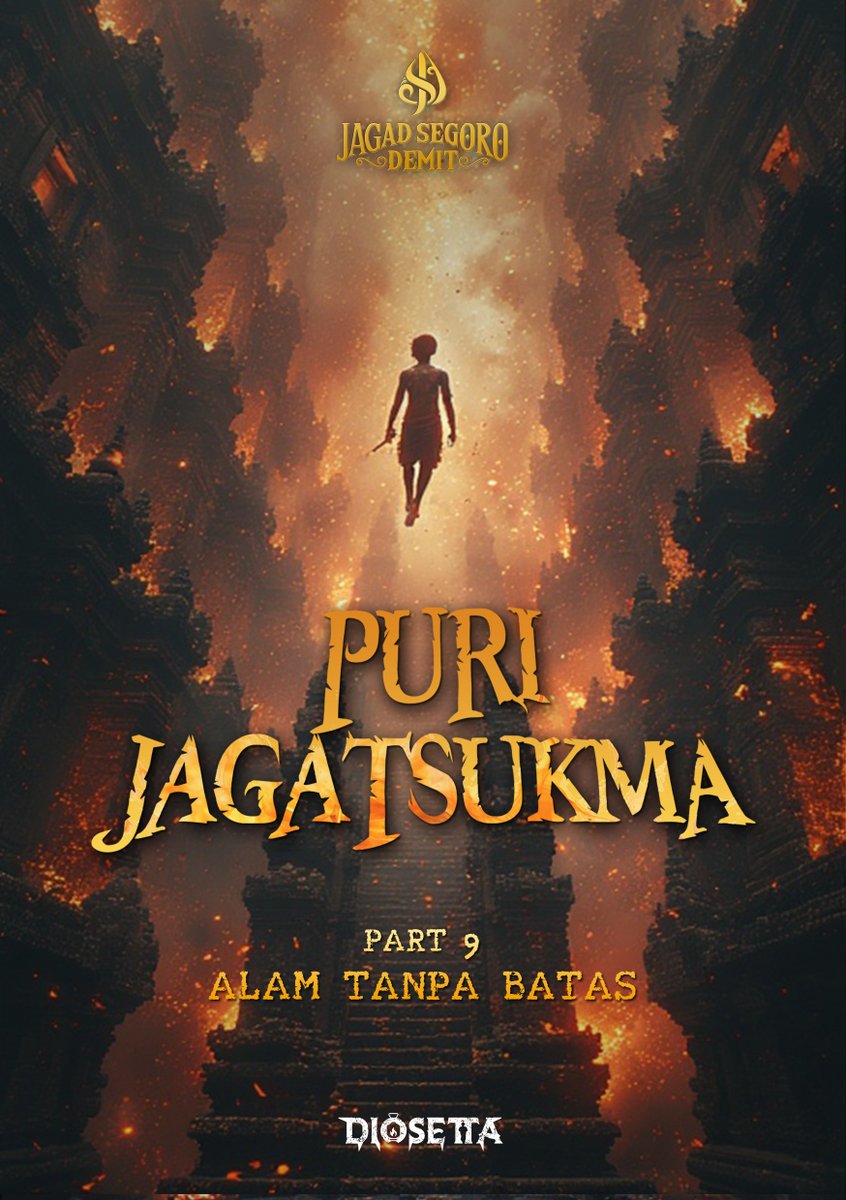SABDA PANGIWA II
- Warisan Jenazah -
"Tak ada satu pun yang berani menyentuhmu atau keluargamu... selama jenazah itu tetap kau simpan."
@bacahorror #bacahorror @IDN_Horor @bagihorror
- Warisan Jenazah -
"Tak ada satu pun yang berani menyentuhmu atau keluargamu... selama jenazah itu tetap kau simpan."
@bacahorror #bacahorror @IDN_Horor @bagihorror

PROLOG
"Tak ada satu pun yang berani menyentuhmu atau keluargamu... selama jenazah itu tetap kau simpan."
Suara itu terdengar lirih namun berat, seolah menyatu dengan malam yang mencekam. Di tengah remang cahaya obor yang berkedip, seorang pria melangkah berat menuju sebuah jasad. Jenazah itu dibungkus kain kafan kusam bertuliskan aksara merah—seperti coretan darah yang tak mengering.
Di samping jasad, berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya dipenuhi kerutan, sorot matanya tak menunjukkan belas kasihan—ia hanya menunggu.
"Jadi… ini jawabannya?" suara pria itu pecah, goyah. Ia menahan napas, bau busuk dari jenazah membuat perutnya mual. Ia bahkan tak tahu siapa mayat itu.
Tapi ia bisa merasakan sesuatu... sesuatu yang jauh dari kematian biasa.
"Bawalah pulang," ujar lelaki tua itu, "Minta apa pun padanya. Perlakukan ia seperti Tuhan. Kau tak akan menyesal."
Pria itu diam, lalu mendengarkan tata caranya:
Jenazah harus digendong, tak boleh menyentuh tanah. Harus dibaringkan di atas keranda bambu dan dimandikan setiap tengah malam, menggunakan bunga-bunga tertentu.Dan yang terpenting... setiap seribu hari, seorang gadis perawan harus tidur di sampingnya.
Putus asa. Dendam. Rasa malu yang telah dipendam bertahun-tahun. Semua itu menutup mata pria itu dari logika dan nurani.
…
"Tak ada satu pun yang berani menyentuhmu atau keluargamu... selama jenazah itu tetap kau simpan."
Suara itu terdengar lirih namun berat, seolah menyatu dengan malam yang mencekam. Di tengah remang cahaya obor yang berkedip, seorang pria melangkah berat menuju sebuah jasad. Jenazah itu dibungkus kain kafan kusam bertuliskan aksara merah—seperti coretan darah yang tak mengering.
Di samping jasad, berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya dipenuhi kerutan, sorot matanya tak menunjukkan belas kasihan—ia hanya menunggu.
"Jadi… ini jawabannya?" suara pria itu pecah, goyah. Ia menahan napas, bau busuk dari jenazah membuat perutnya mual. Ia bahkan tak tahu siapa mayat itu.
Tapi ia bisa merasakan sesuatu... sesuatu yang jauh dari kematian biasa.
"Bawalah pulang," ujar lelaki tua itu, "Minta apa pun padanya. Perlakukan ia seperti Tuhan. Kau tak akan menyesal."
Pria itu diam, lalu mendengarkan tata caranya:
Jenazah harus digendong, tak boleh menyentuh tanah. Harus dibaringkan di atas keranda bambu dan dimandikan setiap tengah malam, menggunakan bunga-bunga tertentu.Dan yang terpenting... setiap seribu hari, seorang gadis perawan harus tidur di sampingnya.
Putus asa. Dendam. Rasa malu yang telah dipendam bertahun-tahun. Semua itu menutup mata pria itu dari logika dan nurani.
…
BRAK!!
Pintu rumah terbuka dengan keras, disusul deru petir dan hujan deras yang mengguyur. Di ambang pintu, pria itu berdiri dengan pakaian basah kuyup, menggendong sesuatu yang mengeluarkan bau amis menusuk. Di belakangnya, kegelapan menggantung seperti ancaman.
Istri dan anak perempuannya terkejut, bingung sekaligus takut.
“Cepat! Siapkan bambu! Buatkan keranda!” teriak sang suami, matanya merah, napasnya berat.
“Pak… itu… apa?” istrinya bertanya dengan suara gemetar.
“Ini... adalah jalan keluar kita. Tuhan kita yang baru! CEPAT!!”
Di tengah hujan dan malam yang pekat, mereka membuat keranda dari bambu. Tak satu pun dari mereka berani menolak. Menjelang tengah malam, jenazah itu dibaringkan di atas keranda, dimandikan, lalu diselimuti kain kafan bertuliskan aksara darah.
Pria itu berlutut di depan jenazah.
“Aku ingin... seluruh keluarga Prawiryo mati!”
Istri dan anaknya ikut berlutut. Mata sang anak berkaca-kaca.
“Anak laki-laki tertua mereka… dia memperkosaku di lumbung padi. Dia membuangku seperti sampah... kematiannya harus paling menyakitkan.”
Petir menyambar lagi. Kilat menerangi ruangan, dan bayangan hitam muncul dari jasad itu. Tingginya nyaris mencapai langit-langit. Wujudnya kabur, hanya tampak senyum bengis dari mulut berlumuran darah.
Mereka bertiga gemetar.
Tapi makhluk itu hanya lewat... dan keluar rumah tanpa suara.
Malam itu, keluarga Prawiryo ditemukan tewas di rumah mereka. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka.
Namun yang paling mengerikan adalah kematian sang anak sulung...
Tubuhnya terpotong menjadi tujuh bagian, dan kepalanya tertancap di atap rumah—menghadap ke langit.
Kematian keluarga Prawiryo, sebagai keluarga paling terpandang dan kaya di desa, mengguncang semua orang. Namun suatu hal yang tak diduga terjadi. Tak lama kemudian, satu keluarga yang dulu dihina, dipermalukan, dan ditindas... bangkit.
Mereka membangun rumah besar, menguasai tanah dan harta keluarga Prawiryo.
Orang-orang mulai menyebut nama mereka dengan hormat, juga dengan takut:... Trah Wisesa.
***
Pintu rumah terbuka dengan keras, disusul deru petir dan hujan deras yang mengguyur. Di ambang pintu, pria itu berdiri dengan pakaian basah kuyup, menggendong sesuatu yang mengeluarkan bau amis menusuk. Di belakangnya, kegelapan menggantung seperti ancaman.
Istri dan anak perempuannya terkejut, bingung sekaligus takut.
“Cepat! Siapkan bambu! Buatkan keranda!” teriak sang suami, matanya merah, napasnya berat.
“Pak… itu… apa?” istrinya bertanya dengan suara gemetar.
“Ini... adalah jalan keluar kita. Tuhan kita yang baru! CEPAT!!”
Di tengah hujan dan malam yang pekat, mereka membuat keranda dari bambu. Tak satu pun dari mereka berani menolak. Menjelang tengah malam, jenazah itu dibaringkan di atas keranda, dimandikan, lalu diselimuti kain kafan bertuliskan aksara darah.
Pria itu berlutut di depan jenazah.
“Aku ingin... seluruh keluarga Prawiryo mati!”
Istri dan anaknya ikut berlutut. Mata sang anak berkaca-kaca.
“Anak laki-laki tertua mereka… dia memperkosaku di lumbung padi. Dia membuangku seperti sampah... kematiannya harus paling menyakitkan.”
Petir menyambar lagi. Kilat menerangi ruangan, dan bayangan hitam muncul dari jasad itu. Tingginya nyaris mencapai langit-langit. Wujudnya kabur, hanya tampak senyum bengis dari mulut berlumuran darah.
Mereka bertiga gemetar.
Tapi makhluk itu hanya lewat... dan keluar rumah tanpa suara.
Malam itu, keluarga Prawiryo ditemukan tewas di rumah mereka. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka.
Namun yang paling mengerikan adalah kematian sang anak sulung...
Tubuhnya terpotong menjadi tujuh bagian, dan kepalanya tertancap di atap rumah—menghadap ke langit.
Kematian keluarga Prawiryo, sebagai keluarga paling terpandang dan kaya di desa, mengguncang semua orang. Namun suatu hal yang tak diduga terjadi. Tak lama kemudian, satu keluarga yang dulu dihina, dipermalukan, dan ditindas... bangkit.
Mereka membangun rumah besar, menguasai tanah dan harta keluarga Prawiryo.
Orang-orang mulai menyebut nama mereka dengan hormat, juga dengan takut:... Trah Wisesa.
***
SABDA PANGIWA 2 - Warisan Jenazah
“Tiiiin!”
Suara klakson bus yang melengking membuyarkan tidur Tegar. Ia tersentak bangun dari mimpinya yang entah apa, hanya untuk mendapati dirinya masih di dalam bus yang penuh sesak.
Bau minyak angin menyengat dari ibu-ibu yang sedang menahan mabuk perjalanan, suara obrolan penumpang bersahut-sahutan, dan bulu ayam beterbangan dari keranjang penumpang di dekatnya.
Ia menarik napas panjang, mencoba kembali bersandar, tapi kenyamanan di bus ekonomi seperti itu memang lebih seperti harapan ketimbang kenyataan.
“Cangcimen, cangcimen! Kacang, kuaci, permen!” suara pedagang asongan menggema dari lorong sempit bus. Di tengah desak-desakan penumpang yang berdiri, pedagang itu tetap memaksa masuk, menjajakan dagangannya dengan semangat.
Tegar menyelipkan tangan ke saku celana, merogoh uang dua ribu rupiah.
“Eh! Mas Tegar!” seru si pedagang asongan, “Tumben jauh-jauh naik bus!”
Tegar tersenyum kecut. “Ada urusan,” jawabnya singkat.
“Halah, gaya. Naik bus keluar kota... emang punya duit?” goda si pedagang sambil tertawa kecil.
Ucapan itu langsung mengubah ekspresi Tegar. Wajahnya cemberut. Ia pun menarik kembali uangnya dan menyimpannya ke saku.
“Lho, itu duit dua ribuan? Mau beli cangcimen, toh?” tanya pedagang itu lagi, heran.
“NGGAK JADI! NGGAK PUNYA DUIT!” jawab Tegar kesal, matanya melotot sebal. Pedagang itu hanya terkekeh sebelum turun di halte berikutnya.
Tak lama kemudian, kernet bus berseru dari depan. “Terminal! Terminal! Tempat rusuh, minum-minum, sama nakal! Terminal!!”
Seorang ibu-ibu menepuk lengan kernet itu sambil mencubit ringan, “Ngawur kamu, Mas…”
“Hehe, becanda, Bu. Biar nggak tegang,” ujar si kernet sambil nyengir lebar.
Bus berhenti. Tegar ikut turun, menjejakkan kakinya di terminal yang ramai. Ia membuka lembaran koran yang ia bawa sejak berangkat, matanya tertuju pada satu berita utama:
"ARAK-ARAKAN GAIB: Warga Mengaku Melihat Rombongan Obor dan Keranda Mayat Sebelum Terjadi Kesurupan Massal."
“Tiiiin!”
Suara klakson bus yang melengking membuyarkan tidur Tegar. Ia tersentak bangun dari mimpinya yang entah apa, hanya untuk mendapati dirinya masih di dalam bus yang penuh sesak.
Bau minyak angin menyengat dari ibu-ibu yang sedang menahan mabuk perjalanan, suara obrolan penumpang bersahut-sahutan, dan bulu ayam beterbangan dari keranjang penumpang di dekatnya.
Ia menarik napas panjang, mencoba kembali bersandar, tapi kenyamanan di bus ekonomi seperti itu memang lebih seperti harapan ketimbang kenyataan.
“Cangcimen, cangcimen! Kacang, kuaci, permen!” suara pedagang asongan menggema dari lorong sempit bus. Di tengah desak-desakan penumpang yang berdiri, pedagang itu tetap memaksa masuk, menjajakan dagangannya dengan semangat.
Tegar menyelipkan tangan ke saku celana, merogoh uang dua ribu rupiah.
“Eh! Mas Tegar!” seru si pedagang asongan, “Tumben jauh-jauh naik bus!”
Tegar tersenyum kecut. “Ada urusan,” jawabnya singkat.
“Halah, gaya. Naik bus keluar kota... emang punya duit?” goda si pedagang sambil tertawa kecil.
Ucapan itu langsung mengubah ekspresi Tegar. Wajahnya cemberut. Ia pun menarik kembali uangnya dan menyimpannya ke saku.
“Lho, itu duit dua ribuan? Mau beli cangcimen, toh?” tanya pedagang itu lagi, heran.
“NGGAK JADI! NGGAK PUNYA DUIT!” jawab Tegar kesal, matanya melotot sebal. Pedagang itu hanya terkekeh sebelum turun di halte berikutnya.
Tak lama kemudian, kernet bus berseru dari depan. “Terminal! Terminal! Tempat rusuh, minum-minum, sama nakal! Terminal!!”
Seorang ibu-ibu menepuk lengan kernet itu sambil mencubit ringan, “Ngawur kamu, Mas…”
“Hehe, becanda, Bu. Biar nggak tegang,” ujar si kernet sambil nyengir lebar.
Bus berhenti. Tegar ikut turun, menjejakkan kakinya di terminal yang ramai. Ia membuka lembaran koran yang ia bawa sejak berangkat, matanya tertuju pada satu berita utama:
"ARAK-ARAKAN GAIB: Warga Mengaku Melihat Rombongan Obor dan Keranda Mayat Sebelum Terjadi Kesurupan Massal."
Tegar membaca ulang paragraf demi paragraf dengan serius. Nama sebuah desa tertera jelas di sana: Desa Tegalwurung.
Ia lalu menghampiri salah satu petugas terminal untuk bertanya. Sayangnya, desa itu tak dilewati kendaraan umum—satu-satunya cara mencapainya hanyalah dengan berjalan kaki.
Tegar mengangguk. Ia tak keberatan, tapi perutnya mulai meronta minta diisi. Perjalanan panjang dari kota membuatnya lapar, dan dua ribu rupiah tadi rasanya mulai terasa menyesal tak digunakan.
Dengan koran terlipat di tangan, dan niat yang belum pudar, Tegar melangkah pelan, menyusuri jalanan terminal menuju desa yang menyimpan cerita... dan rahasia.
Perut Tegar sudah mulai berteriak minta diisi sejak turun dari bus tadi. Ia menyisir deretan warung nasi di sekitar terminal, tapi sayangnya hampir semua penuh sesak oleh penumpang yang baru saja turun.
Suara sendok beradu, aroma lauk pauk mengepul, dan obrolan ramai membuat perutnya makin meronta.
Ia berjalan sedikit menjauh hingga matanya tertumbuk pada satu warung kecil yang... sepi.
Tak ada satu pun pembeli. Tapi terlihat bersih dan cukup rapi.
“Bu, nasi sayur berapa?” tanya Tegar sambil mendekat.
“Lima ribu, Mas. Air putihnya gratis, gelasnya di situ,” jawab ibu penjaga warung sambil menunjuk rak gelas.
“Ya udah, nasi sayurnya satu ya, Bu,” Tegar duduk dan mulai bersiap makan.
Sembari menunggu, ia celingukan. Heran juga. Tempat ini nggak kelihatan menyeramkan, bahkan cukup nyaman dibanding warung lain. “Kok sepi, Bu? Warung lain rame lho,” tanyanya penasaran.
Sang ibu menghela napas. “Yah, beginilah jualan di terminal. Sama aja kayak di pasar. Kalau kalah penglaris, ya sepi begini...” katanya, sambil menyajikan sepiring nasi dengan sayur dan tempe orek.
Ia lalu menghampiri salah satu petugas terminal untuk bertanya. Sayangnya, desa itu tak dilewati kendaraan umum—satu-satunya cara mencapainya hanyalah dengan berjalan kaki.
Tegar mengangguk. Ia tak keberatan, tapi perutnya mulai meronta minta diisi. Perjalanan panjang dari kota membuatnya lapar, dan dua ribu rupiah tadi rasanya mulai terasa menyesal tak digunakan.
Dengan koran terlipat di tangan, dan niat yang belum pudar, Tegar melangkah pelan, menyusuri jalanan terminal menuju desa yang menyimpan cerita... dan rahasia.
Perut Tegar sudah mulai berteriak minta diisi sejak turun dari bus tadi. Ia menyisir deretan warung nasi di sekitar terminal, tapi sayangnya hampir semua penuh sesak oleh penumpang yang baru saja turun.
Suara sendok beradu, aroma lauk pauk mengepul, dan obrolan ramai membuat perutnya makin meronta.
Ia berjalan sedikit menjauh hingga matanya tertumbuk pada satu warung kecil yang... sepi.
Tak ada satu pun pembeli. Tapi terlihat bersih dan cukup rapi.
“Bu, nasi sayur berapa?” tanya Tegar sambil mendekat.
“Lima ribu, Mas. Air putihnya gratis, gelasnya di situ,” jawab ibu penjaga warung sambil menunjuk rak gelas.
“Ya udah, nasi sayurnya satu ya, Bu,” Tegar duduk dan mulai bersiap makan.
Sembari menunggu, ia celingukan. Heran juga. Tempat ini nggak kelihatan menyeramkan, bahkan cukup nyaman dibanding warung lain. “Kok sepi, Bu? Warung lain rame lho,” tanyanya penasaran.
Sang ibu menghela napas. “Yah, beginilah jualan di terminal. Sama aja kayak di pasar. Kalau kalah penglaris, ya sepi begini...” katanya, sambil menyajikan sepiring nasi dengan sayur dan tempe orek.
“Nggak semua soal penglaris, Bu…” ujar Tegar, setengah menenangkan, setengah mencoba sopan.
“Yah, tapi nggak bisa bohong, Mas. Liat aja tuh, warung sebelah udah kayak kondangan tiap hari. Saya? Nungguin nyamuk dateng beli nasi,” keluh si ibu sambil duduk menemani.
Tegar mulai makan pelan-pelan sambil mendengar curhat ibu itu. “Kalau Masnya punya info penglaris yang manjur, bisik-bisik ya! Saya juga mau laris kayak mereka.”
BRAKK!!
Tiba-tiba Tegar menggebrak meja. “Ibu beneran mau penglaris?”
“I—iya...?” jawab sang ibu, kaget.
Tanpa banyak bicara, Tegar berdiri dan kabur keluar dari warung. Meninggalkan makanannya, bahkan tasnya masih di bangku. Ibu itu melongo bingung.
Beberapa menit kemudian, Tegar kembali. Ia membawa plastik kresek kecil dan meletakkannya dengan khidmat di atas meja.
“Nah! Ini penglaris yang ibu butuhin!”
“Yah, tapi nggak bisa bohong, Mas. Liat aja tuh, warung sebelah udah kayak kondangan tiap hari. Saya? Nungguin nyamuk dateng beli nasi,” keluh si ibu sambil duduk menemani.
Tegar mulai makan pelan-pelan sambil mendengar curhat ibu itu. “Kalau Masnya punya info penglaris yang manjur, bisik-bisik ya! Saya juga mau laris kayak mereka.”
BRAKK!!
Tiba-tiba Tegar menggebrak meja. “Ibu beneran mau penglaris?”
“I—iya...?” jawab sang ibu, kaget.
Tanpa banyak bicara, Tegar berdiri dan kabur keluar dari warung. Meninggalkan makanannya, bahkan tasnya masih di bangku. Ibu itu melongo bingung.
Beberapa menit kemudian, Tegar kembali. Ia membawa plastik kresek kecil dan meletakkannya dengan khidmat di atas meja.
“Nah! Ini penglaris yang ibu butuhin!”
Sang ibu membuka plastik itu—isi dalamnya? Sachet micin, kaldu bubuk, dan bumbu dapur.
“I—ini mah micin?” tanya ibu itu bingung.
“Iya! Masalah warung ibu bukan kalah penglaris. Masakan ibu nggak enak!”
Tegar kembali duduk, melanjutkan makan dengan lahap.
“Eh? Kurang ajar kamu! Kalau nggak enak, kenapa dimakan selahap itu?!” protes si ibu, jengkel.
“Laper, Bu. Laper!” jawab Tegar santai.
Ibu itu masih bingung. Tapi penasaran juga. Ia menyuap makanannya sendiri... dan ekspresinya? Datar.
“Enak kok,” gumamnya.
Tegar tersenyum nyengir. “Coba deh cobain nasi warung sebelah. Masih berani bilang itu enak atau nggak?”
Kesal, si ibu pun meninggalkan warungnya sebentar dan kembali membawa satu bungkus nasi rames dari warung yang tadi ramai. Ia mulai makan... dan baru satu suap, ia diam. Tertegun.
“Enak to, Bu?” goda Tegar sambil tersenyum jahil.
Si ibu melirik tajam, tapi tak bisa menolak rasa gurih di mulutnya. Ia terus makan hingga nasi rames itu habis tanpa sisa.
“Gimana? Pedas gurihnya sambal, oseng buncis yang masih krenyes, telur dadar lembut dengan jejak micin... Cinta pertama tuh, Bu,” cengir Tegar puas.
BRAK!!
Ibu itu menggebrak meja kali ini. “Lha piye? Laper kok!” serunya, ikut kesal tapi juga... pasrah.
Tegar tertawa. “Sudahlah, Bu. Terima saja penglarisnya. Tenang! Ini penglaris halal kok!” Ia menunjuk logo halal di sachet dengan gaya ala promosi produk di TV.
Namun tiba-tiba, wajah ibu itu berubah. Merah. Matanya berkaca-kaca... dan tak lama, air matanya menetes.
“I—ini mah micin?” tanya ibu itu bingung.
“Iya! Masalah warung ibu bukan kalah penglaris. Masakan ibu nggak enak!”
Tegar kembali duduk, melanjutkan makan dengan lahap.
“Eh? Kurang ajar kamu! Kalau nggak enak, kenapa dimakan selahap itu?!” protes si ibu, jengkel.
“Laper, Bu. Laper!” jawab Tegar santai.
Ibu itu masih bingung. Tapi penasaran juga. Ia menyuap makanannya sendiri... dan ekspresinya? Datar.
“Enak kok,” gumamnya.
Tegar tersenyum nyengir. “Coba deh cobain nasi warung sebelah. Masih berani bilang itu enak atau nggak?”
Kesal, si ibu pun meninggalkan warungnya sebentar dan kembali membawa satu bungkus nasi rames dari warung yang tadi ramai. Ia mulai makan... dan baru satu suap, ia diam. Tertegun.
“Enak to, Bu?” goda Tegar sambil tersenyum jahil.
Si ibu melirik tajam, tapi tak bisa menolak rasa gurih di mulutnya. Ia terus makan hingga nasi rames itu habis tanpa sisa.
“Gimana? Pedas gurihnya sambal, oseng buncis yang masih krenyes, telur dadar lembut dengan jejak micin... Cinta pertama tuh, Bu,” cengir Tegar puas.
BRAK!!
Ibu itu menggebrak meja kali ini. “Lha piye? Laper kok!” serunya, ikut kesal tapi juga... pasrah.
Tegar tertawa. “Sudahlah, Bu. Terima saja penglarisnya. Tenang! Ini penglaris halal kok!” Ia menunjuk logo halal di sachet dengan gaya ala promosi produk di TV.
Namun tiba-tiba, wajah ibu itu berubah. Merah. Matanya berkaca-kaca... dan tak lama, air matanya menetes.
“Eh, Bu?! Kok malah nangis? Saya cuma bercanda lho!” Tegar panik, langsung gelagapan.
“Kenapa... nggak ada yang pernah bilang masakan saya nggak enak...” ucap ibu itu lirih sambil terisak.
“Waduh! Ini bahaya!” gumam Tegar cepat-cepat merogoh saku. “Bu, ini lima ribunya! Saya pamit ya!”
Tanpa pikir panjang, Tegar mengambil tasnya dan... kabur lagi.
Belum sempat melangkah keluar dari terminal, langkah Tegar terhenti. Suara riuh membuatnya menoleh. Ada kerumunan. Orang-orang berkumpul, saling dorong, menatap ke satu titik di tanah dengan wajah ngeri.
Sebuah mobil hitam melintas cepat, meninggalkan sesuatu di tepi terminal. Lalu pergi begitu saja.
“Mayat… itu mayat!” bisik seseorang, suaranya gemetar.
Tegar ikut mendekat. Di hadapannya, dua tubuh tergeletak kaku, dibungkus selimut lusuh. Bau busuk menusuk hidung. Orang-orang menutup hidung, bergidik, dan perlahan mundur.
Tapi Tegar justru melangkah maju. Tatapannya tajam menembus selimut.
“Minggir! Itu bukan mayat!”
Dengan sigap ia membuka selimut itu. Sontak kerumunan mundur serempak.
Bukan mayat. Tapi dua perempuan. Masih muda. Tubuh mereka kaku dan pucat, penuh borok dan nanah, mata melotot tak berkedip. Mereka masih bernapas... tapi nyaris tak terasa hidup.
“Santet… pasti santet…” bisik seseorang.
Yang lain hanya berdiri diam, takut, jijik, enggan mendekat.
“Tolong bawa mereka ke tempat aman!” pinta Tegar. Tak ada yang bergerak. Bahkan beberapa mulai menjauh dan pergi satu persatu.
“Ayo, bantu saya!” desaknya lagi.
Namun yang ia dapat hanya tatapan was-was dan kalimat pelan:
“Jangan bawa ke tempat saya…”
“Nanti kita ikut-ikutan jadi korban…”
Tegar menggigit bibir. Ia paham. Korban santet bukan hanya menakutkan—mereka dianggap bencana yang bisa menular.
Ia menunduk. Kecewa. Marah. Bingung harus ke mana membawa mereka.
Hingga sebuah suara terdengar dari belakang. Ada satu orang yang tersisa dari kerumunan yang pergi meninggalkan tempat itu.
“Bawa ke warung saja…”
Tegar menoleh. Itu ibu warung sepi tadi—yang nasi sayurnya masih lebih hambar dari air cucian beras. Tapi kini, ia berdiri di antara kerumunan yang perlahan bubar.
“Baik, Bu…” Tegar mengangguk, lega.
“Kenapa... nggak ada yang pernah bilang masakan saya nggak enak...” ucap ibu itu lirih sambil terisak.
“Waduh! Ini bahaya!” gumam Tegar cepat-cepat merogoh saku. “Bu, ini lima ribunya! Saya pamit ya!”
Tanpa pikir panjang, Tegar mengambil tasnya dan... kabur lagi.
Belum sempat melangkah keluar dari terminal, langkah Tegar terhenti. Suara riuh membuatnya menoleh. Ada kerumunan. Orang-orang berkumpul, saling dorong, menatap ke satu titik di tanah dengan wajah ngeri.
Sebuah mobil hitam melintas cepat, meninggalkan sesuatu di tepi terminal. Lalu pergi begitu saja.
“Mayat… itu mayat!” bisik seseorang, suaranya gemetar.
Tegar ikut mendekat. Di hadapannya, dua tubuh tergeletak kaku, dibungkus selimut lusuh. Bau busuk menusuk hidung. Orang-orang menutup hidung, bergidik, dan perlahan mundur.
Tapi Tegar justru melangkah maju. Tatapannya tajam menembus selimut.
“Minggir! Itu bukan mayat!”
Dengan sigap ia membuka selimut itu. Sontak kerumunan mundur serempak.
Bukan mayat. Tapi dua perempuan. Masih muda. Tubuh mereka kaku dan pucat, penuh borok dan nanah, mata melotot tak berkedip. Mereka masih bernapas... tapi nyaris tak terasa hidup.
“Santet… pasti santet…” bisik seseorang.
Yang lain hanya berdiri diam, takut, jijik, enggan mendekat.
“Tolong bawa mereka ke tempat aman!” pinta Tegar. Tak ada yang bergerak. Bahkan beberapa mulai menjauh dan pergi satu persatu.
“Ayo, bantu saya!” desaknya lagi.
Namun yang ia dapat hanya tatapan was-was dan kalimat pelan:
“Jangan bawa ke tempat saya…”
“Nanti kita ikut-ikutan jadi korban…”
Tegar menggigit bibir. Ia paham. Korban santet bukan hanya menakutkan—mereka dianggap bencana yang bisa menular.
Ia menunduk. Kecewa. Marah. Bingung harus ke mana membawa mereka.
Hingga sebuah suara terdengar dari belakang. Ada satu orang yang tersisa dari kerumunan yang pergi meninggalkan tempat itu.
“Bawa ke warung saja…”
Tegar menoleh. Itu ibu warung sepi tadi—yang nasi sayurnya masih lebih hambar dari air cucian beras. Tapi kini, ia berdiri di antara kerumunan yang perlahan bubar.
“Baik, Bu…” Tegar mengangguk, lega.
Dengan susah payah, ia menggendong satu per satu perempuan itu ke warung. Sang ibu sudah menggelar tikar pandan, dan menutup sebagian pintu warungnya.
Tegar menuangkan air putih, membacakan doa perlahan, lalu meminumkannya ke mulut para perempuan yang terbujur.
Ibu warung hanya bisa membantu seadanya—mengambil air hangat, membasuh darah dan borok yang masih mengalir.
Deg!
Tubuh salah satu perempuan itu mengejang. Nafasnya terputus-putus… lalu tenang. Yang satunya menyusul.
“Nak, mereka kenapa?” tanya si ibu, suaranya pelan.
“Mereka masih hidup, Bu. Tapi... belum pulih. Ini baru permulaan.” Tegar menempelkan jarinya di hidung salah satu perempuan, memastikan nafas masih ada.
Ibu itu memandang Tegar dengan heran.
“Sebenarnya Masnya ini siapa, to?”
“Saya Tegar, Bu. Di pasar desa, saya cuma kuli panggul.” jawabnya sambil tersenyum tipis. “Maaf, saya belum tahu nama ibu?”
Raut wajah ibu itu langsung berubah.
“Belum tahu nama saya?” tanyanya, setengah tersinggung.
“Ya belum, Bu! Ibu aja belum ngasih tahu!” Tegar mulai kesal.
Sang ibu menunjuk ke arah dinding warung dengan wajah kecut.
“Lha itu, Mas! Masa nggak kelihatan?”
Spanduk besar terpampang jelas:
“WARUNG NASI IBU PARTINI”
“Masih kurang besar?” tegurnya.
Tegar menggaruk kepala sambil nyengir.
“Hehe... ya mana tahu, Bu. Kirain itu nama pemilik lama. Atau nama ibunya ibu...”
“Ngawur! Saya sendiri yang masak, saya yang jual! Saya Ibu Partini!”
“Iya, Bu... iya… yang ada lagunya itu, kan? Ibu kita Partini... Putri sejati…”
“KARTINI, MAS!! ITU KARTINI!!” teriak Bu Partini, nyaris melempar sendok.
***
Tegar menuangkan air putih, membacakan doa perlahan, lalu meminumkannya ke mulut para perempuan yang terbujur.
Ibu warung hanya bisa membantu seadanya—mengambil air hangat, membasuh darah dan borok yang masih mengalir.
Deg!
Tubuh salah satu perempuan itu mengejang. Nafasnya terputus-putus… lalu tenang. Yang satunya menyusul.
“Nak, mereka kenapa?” tanya si ibu, suaranya pelan.
“Mereka masih hidup, Bu. Tapi... belum pulih. Ini baru permulaan.” Tegar menempelkan jarinya di hidung salah satu perempuan, memastikan nafas masih ada.
Ibu itu memandang Tegar dengan heran.
“Sebenarnya Masnya ini siapa, to?”
“Saya Tegar, Bu. Di pasar desa, saya cuma kuli panggul.” jawabnya sambil tersenyum tipis. “Maaf, saya belum tahu nama ibu?”
Raut wajah ibu itu langsung berubah.
“Belum tahu nama saya?” tanyanya, setengah tersinggung.
“Ya belum, Bu! Ibu aja belum ngasih tahu!” Tegar mulai kesal.
Sang ibu menunjuk ke arah dinding warung dengan wajah kecut.
“Lha itu, Mas! Masa nggak kelihatan?”
Spanduk besar terpampang jelas:
“WARUNG NASI IBU PARTINI”
“Masih kurang besar?” tegurnya.
Tegar menggaruk kepala sambil nyengir.
“Hehe... ya mana tahu, Bu. Kirain itu nama pemilik lama. Atau nama ibunya ibu...”
“Ngawur! Saya sendiri yang masak, saya yang jual! Saya Ibu Partini!”
“Iya, Bu... iya… yang ada lagunya itu, kan? Ibu kita Partini... Putri sejati…”
“KARTINI, MAS!! ITU KARTINI!!” teriak Bu Partini, nyaris melempar sendok.
***
KELUARGA PEWARIS JENAZAH
Langit menjingga di ujung hari, tapi di dalam warung sempit milik Bu Partini, senja terasa lebih kelabu. Hening. Sunyi. Aroma anyir darah dan luka masih menggantung di udara.
Dua perempuan asing terbaring kaku di atas tikar pandan. Tubuh mereka pucat, luka-luka bernanah masih tampak segar. Bu Partini terus merawat mereka dengan telaten, meski rasa takut masih menyelusup dalam hati.
Pintu warung terbuka tiba-tiba.
“Dapet, Bu!” seru Tegar sambil menaruh segenggam daun bidara, garam krasak, dan benda-benda yang ia bungkus dengan kain mori tipis.
Bu Partini memandang dengan ragu.
“Kamu serius bisa nyembuhin mereka?”
Tegar tak langsung menjawab. Ia menatap dua tubuh yang masih diam seperti mayat hidup itu.
“Saya nggak bisa, Bu… Saya cuma perantara. Yang nyembuhin, ya Yang Nyiptain saya.”
Tanpa banyak bicara, Tegar mulai menyiapkan ritual. Ia mengucapkan doa lirih, lalu menyiramkan air campuran daun bidara dan garam dari ujung kaki, ke tangan, lalu ke kepala masing-masing perempuan.
Air dalam baskom perlahan habis, mengalir membasuh luka-luka membusuk yang menyelimuti tubuh dua perempuan asing itu. Doa Tegar telah selesai, tapi keheningan belum benar-benar berlalu.
Ia duduk kembali, menyeruput kopi panas buatan Bu Partini. Suasana warung terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena malam yang mulai turun, atau karena sesuatu yang belum pergi dari tubuh mereka.
Lalu… satu jari bergerak. Disusul oleh tarikan napas berat—seperti seseorang yang kembali dari jurang kematian.
Langit menjingga di ujung hari, tapi di dalam warung sempit milik Bu Partini, senja terasa lebih kelabu. Hening. Sunyi. Aroma anyir darah dan luka masih menggantung di udara.
Dua perempuan asing terbaring kaku di atas tikar pandan. Tubuh mereka pucat, luka-luka bernanah masih tampak segar. Bu Partini terus merawat mereka dengan telaten, meski rasa takut masih menyelusup dalam hati.
Pintu warung terbuka tiba-tiba.
“Dapet, Bu!” seru Tegar sambil menaruh segenggam daun bidara, garam krasak, dan benda-benda yang ia bungkus dengan kain mori tipis.
Bu Partini memandang dengan ragu.
“Kamu serius bisa nyembuhin mereka?”
Tegar tak langsung menjawab. Ia menatap dua tubuh yang masih diam seperti mayat hidup itu.
“Saya nggak bisa, Bu… Saya cuma perantara. Yang nyembuhin, ya Yang Nyiptain saya.”
Tanpa banyak bicara, Tegar mulai menyiapkan ritual. Ia mengucapkan doa lirih, lalu menyiramkan air campuran daun bidara dan garam dari ujung kaki, ke tangan, lalu ke kepala masing-masing perempuan.
Air dalam baskom perlahan habis, mengalir membasuh luka-luka membusuk yang menyelimuti tubuh dua perempuan asing itu. Doa Tegar telah selesai, tapi keheningan belum benar-benar berlalu.
Ia duduk kembali, menyeruput kopi panas buatan Bu Partini. Suasana warung terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena malam yang mulai turun, atau karena sesuatu yang belum pergi dari tubuh mereka.
Lalu… satu jari bergerak. Disusul oleh tarikan napas berat—seperti seseorang yang kembali dari jurang kematian.
“Mas Tegar! Mereka sadar!” seru Bu Partini, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Dua pasang mata perlahan terbuka. Bola matanya merah, kering, seperti lama tak digunakan. Keduanya saling melihat, bingung, gemetar.
“I—ini… di mana?” tanya salah satu dengan suara parau.
“Diminum dulu, Mbak… pelan-pelan saja. Jangan dipaksakan,” ucap Tegar sambil menyerahkan dua gelas air putih.
Brak!!
Kedua perempuan itu serempak mundur saat melihat Tegar, tubuh mereka kaku. Tatapan penuh teror tertuju pada Tegar, seolah tubuh kurus gondrongnya menyimpan bahaya.
“Nggak usah takut, Mbak. Biar gondrong begini, Mas Tegar ini yang nolongin kalian, lho…” sahut Bu Partini mencoba menenangkan.
Mereka masih saling pandang, ragu… tapi perlahan, satu tangan terulur mengambil gelas. Lalu yang lain menyusul. Mereka minum—pelan, gemetar, seperti tubuh mereka sendiri tak percaya bahwa cairan itu bisa masuk kembali.
“Kalian dibuang di terminal ini…” ucap Tegar lirih, seolah tak ingin menyakiti dengan kenyataan.
Air mata langsung menetes tanpa suara. Tangan gemetar memeluk diri sendiri. Bu Partini buru-buru memberikan sekotak tisu, meski hatinya ikut tercekat.
Dua pasang mata perlahan terbuka. Bola matanya merah, kering, seperti lama tak digunakan. Keduanya saling melihat, bingung, gemetar.
“I—ini… di mana?” tanya salah satu dengan suara parau.
“Diminum dulu, Mbak… pelan-pelan saja. Jangan dipaksakan,” ucap Tegar sambil menyerahkan dua gelas air putih.
Brak!!
Kedua perempuan itu serempak mundur saat melihat Tegar, tubuh mereka kaku. Tatapan penuh teror tertuju pada Tegar, seolah tubuh kurus gondrongnya menyimpan bahaya.
“Nggak usah takut, Mbak. Biar gondrong begini, Mas Tegar ini yang nolongin kalian, lho…” sahut Bu Partini mencoba menenangkan.
Mereka masih saling pandang, ragu… tapi perlahan, satu tangan terulur mengambil gelas. Lalu yang lain menyusul. Mereka minum—pelan, gemetar, seperti tubuh mereka sendiri tak percaya bahwa cairan itu bisa masuk kembali.
“Kalian dibuang di terminal ini…” ucap Tegar lirih, seolah tak ingin menyakiti dengan kenyataan.
Air mata langsung menetes tanpa suara. Tangan gemetar memeluk diri sendiri. Bu Partini buru-buru memberikan sekotak tisu, meski hatinya ikut tercekat.
Lalu, salah satu dari mereka bersuara. “Saya Darsih… ini adik saya, Ninih.” Suaranya pecah di ujung kata. “Santet ini… sudah menyerang kami sejak kecil.”
Ninih mengangguk pelan. “Waktu borok-borok itu muncul, saya bahkan belum mengerti apapun… Bau amis dari tubuh saya bikin orang-orang takut. Cuma Mbak Darsih yang mau ngerawat saya…”
Cerita mereka mengalir dalam nada mengerikan—tentang tubuh yang perlahan membusuk, malam-malam yang dipenuhi ketindihan, bisikan-bisikan tak kasat mata, dan saat-saat kesurupan yang membuat mereka hampir dicekik oleh tangan mereka sendiri.
“Puncaknya… beberapa tahun lalu. Kami membatu. Kaku. Seperti batang pohon. Tapi kami masih bisa mendengar semuanya. Kami bisa melihat… waktu itu…” Suara Darsih mulai bergetar. “…orangtua kami memilih pergi. Mereka membuang kami.”
Hening menggantung. Tak ada kata yang cukup untuk membalas pengkhianatan semacam itu.
Tegar hanya bisa menghela napas. Bu Partini, yang biasanya cerewet, kini hanya bisa menatap lantai dengan wajah muram.
“Kalian sudah tidak mungkin pulang ke rumah…” ucap Tegar dengan sorot mata yang berat.
“Iya, Mas… Mereka sudah membuang kami…” sahut Darsih pelan, menunduk.
“Bukan karena itu.”
Tegar menatap mereka tajam. Suaranya berubah serius. Dalam. “Apa yang kalian alami… bukan santet.”
“Maksud Mas?” Darsih dan Ninih saling menatap, kebingungan.
“Kalian adalah… tumbal.”
Ruangan mendadak terasa sesak. Tegar melanjutkan dengan suara yang dingin. “Orang di rumah kalianlah yang menjadikan kalian begini.”
Ninih mengangguk pelan. “Waktu borok-borok itu muncul, saya bahkan belum mengerti apapun… Bau amis dari tubuh saya bikin orang-orang takut. Cuma Mbak Darsih yang mau ngerawat saya…”
Cerita mereka mengalir dalam nada mengerikan—tentang tubuh yang perlahan membusuk, malam-malam yang dipenuhi ketindihan, bisikan-bisikan tak kasat mata, dan saat-saat kesurupan yang membuat mereka hampir dicekik oleh tangan mereka sendiri.
“Puncaknya… beberapa tahun lalu. Kami membatu. Kaku. Seperti batang pohon. Tapi kami masih bisa mendengar semuanya. Kami bisa melihat… waktu itu…” Suara Darsih mulai bergetar. “…orangtua kami memilih pergi. Mereka membuang kami.”
Hening menggantung. Tak ada kata yang cukup untuk membalas pengkhianatan semacam itu.
Tegar hanya bisa menghela napas. Bu Partini, yang biasanya cerewet, kini hanya bisa menatap lantai dengan wajah muram.
“Kalian sudah tidak mungkin pulang ke rumah…” ucap Tegar dengan sorot mata yang berat.
“Iya, Mas… Mereka sudah membuang kami…” sahut Darsih pelan, menunduk.
“Bukan karena itu.”
Tegar menatap mereka tajam. Suaranya berubah serius. Dalam. “Apa yang kalian alami… bukan santet.”
“Maksud Mas?” Darsih dan Ninih saling menatap, kebingungan.
“Kalian adalah… tumbal.”
Ruangan mendadak terasa sesak. Tegar melanjutkan dengan suara yang dingin. “Orang di rumah kalianlah yang menjadikan kalian begini.”
“Yang benar, Mas?” Bu Partini spontan menyela, matanya membelalak. “Tapi luka-luka tadi? Borok itu?”
Tegar menarik napas panjang.
“Aku sangat paham tentang santet, Bu. Tapi ini beda. Luka mereka bukan luka dari kiriman… Tubuh mereka dihuni. Dijadikan tempat bermain setan peliharaan.
Saat tubuhnya rusak, mereka dibuang seperti bangkai.”
Tegar memandang kedua perempuan itu. “Kalian masih punya adik?”
“A—ada… Uni. Dia masih lima tahun…” suara Ninih lirih, nyaris tak terdengar.
“Dia… pengganti kalian.”
Deg.
Jantung Darsih dan Ninih seolah berhenti berdetak. Napas tercekat. Di benak mereka, wajah mungil Uni terbayang, polos, tak tahu apa-apa.
“Katakan di mana rumah kalian. Saya akan ke sana.” Tegar berdiri, meraih tasnya. Ia berusaha menahan emosinya atas kenyataan ini.
“Ta-tapi, Mas…” Darsih menahan. “Bapak bukan orang sembarangan. Dia disegani di desa. Dihormati…”
“Saya nggak peduli!” potong Tegar, nadanya naik.
“Rumah itu dijaga, Mas… Banyak orang yang babak belur karena coba melawan. Termasuk… keluarga kami sendiri.”
BRAK!! Tegar mengepalkan tinjunya di atas meja.
“SAYA. TIDAK. PEDULI!”
“…Agung Wisesa. Rumah paling besar di Desa Tegalwurung,” gumam Ninih.
“NINIH!” Darsih menatap adiknya, panik.
Tegar menarik napas panjang.
“Aku sangat paham tentang santet, Bu. Tapi ini beda. Luka mereka bukan luka dari kiriman… Tubuh mereka dihuni. Dijadikan tempat bermain setan peliharaan.
Saat tubuhnya rusak, mereka dibuang seperti bangkai.”
Tegar memandang kedua perempuan itu. “Kalian masih punya adik?”
“A—ada… Uni. Dia masih lima tahun…” suara Ninih lirih, nyaris tak terdengar.
“Dia… pengganti kalian.”
Deg.
Jantung Darsih dan Ninih seolah berhenti berdetak. Napas tercekat. Di benak mereka, wajah mungil Uni terbayang, polos, tak tahu apa-apa.
“Katakan di mana rumah kalian. Saya akan ke sana.” Tegar berdiri, meraih tasnya. Ia berusaha menahan emosinya atas kenyataan ini.
“Ta-tapi, Mas…” Darsih menahan. “Bapak bukan orang sembarangan. Dia disegani di desa. Dihormati…”
“Saya nggak peduli!” potong Tegar, nadanya naik.
“Rumah itu dijaga, Mas… Banyak orang yang babak belur karena coba melawan. Termasuk… keluarga kami sendiri.”
BRAK!! Tegar mengepalkan tinjunya di atas meja.
“SAYA. TIDAK. PEDULI!”
“…Agung Wisesa. Rumah paling besar di Desa Tegalwurung,” gumam Ninih.
“NINIH!” Darsih menatap adiknya, panik.
Tegar mendadak terdiam. Nama itu… desa itu… Tegalwurung. Itulah tempat yang sejak awal menjadi tujuannya. Tempat yang menyimpan arak-arakan jenazah tak wajar di malam buta. Tempat ia tahu ada sesuatu yang harus diselesaikan.
“Nggak bisa dibiarkan, Mbak,” ucap Ninih pelan tapi tegas. “Harus ada yang hentikan Bapak. Kita ini cuma korban kecil. Banyak yang sudah mati gara-gara dia…”
Wajah Tegar mengeras.
“Tenang. Aku punya cara untuk menghadapi pengabdi iblis seperti dia.” Ia menyeringai samar. Matanya membara. “Bukan aku yang akan mendatangi mereka… Tapi mereka yang akan mendatangiku.”
Darsih menggigit bibirnya. “Mas… hati-hati. Keluarga Wisesa dilindungi jasad keramat. Yang Mas hadapi… bukan cuma manusia.”
Tegar langsung menoleh. Jasad keramat. Kata itu menusuk pikirannya. Ia teringat pada iring-iringan jenazah di desanya—penuh asap kemenyan, bunga busuk, dan suara gamelan yang berbalik arah. Ia tahu, semua benang merah mengarah ke satu tempat.
“Kalian tinggallah di sini bersama Bu Partini sampai aku kembali,” ujar Tegar.
“Apa tidak apa-apa, Bu?” tanya Darsih, ragu.
“Warung ini sepi, kok. Nggak ada yang terganggu.
Selama masih bisa bantu, Ibu bantu…” jawab Bu Partini sambil menepuk bahu mereka pelan.
Tegar mengangguk. Ia tahu waktunya tak banyak. Dengan air doa yang ia tinggalkan, luka dan bau amis di tubuh Darsih dan Ninih akan menghilang dalam dua hari. Tapi.. luka di hati mereka… mungkin tak akan pernah hilang.
“Saya pamit, Bu…”
Dan dengan langkah pasti, Tegar meninggalkan warung itu. Menuju Desa Tegalwurung—desa yang tak pernah ia lupakan. Desa yang menyimpan kutukan. Dan sebuah mayat yang tak mau diam di dalam tanah.
***
“Nggak bisa dibiarkan, Mbak,” ucap Ninih pelan tapi tegas. “Harus ada yang hentikan Bapak. Kita ini cuma korban kecil. Banyak yang sudah mati gara-gara dia…”
Wajah Tegar mengeras.
“Tenang. Aku punya cara untuk menghadapi pengabdi iblis seperti dia.” Ia menyeringai samar. Matanya membara. “Bukan aku yang akan mendatangi mereka… Tapi mereka yang akan mendatangiku.”
Darsih menggigit bibirnya. “Mas… hati-hati. Keluarga Wisesa dilindungi jasad keramat. Yang Mas hadapi… bukan cuma manusia.”
Tegar langsung menoleh. Jasad keramat. Kata itu menusuk pikirannya. Ia teringat pada iring-iringan jenazah di desanya—penuh asap kemenyan, bunga busuk, dan suara gamelan yang berbalik arah. Ia tahu, semua benang merah mengarah ke satu tempat.
“Kalian tinggallah di sini bersama Bu Partini sampai aku kembali,” ujar Tegar.
“Apa tidak apa-apa, Bu?” tanya Darsih, ragu.
“Warung ini sepi, kok. Nggak ada yang terganggu.
Selama masih bisa bantu, Ibu bantu…” jawab Bu Partini sambil menepuk bahu mereka pelan.
Tegar mengangguk. Ia tahu waktunya tak banyak. Dengan air doa yang ia tinggalkan, luka dan bau amis di tubuh Darsih dan Ninih akan menghilang dalam dua hari. Tapi.. luka di hati mereka… mungkin tak akan pernah hilang.
“Saya pamit, Bu…”
Dan dengan langkah pasti, Tegar meninggalkan warung itu. Menuju Desa Tegalwurung—desa yang tak pernah ia lupakan. Desa yang menyimpan kutukan. Dan sebuah mayat yang tak mau diam di dalam tanah.
***
Di atas atap pos ronda, Tegar duduk bersila, memandangi rumah terbesar di desa itu. Rumah megah berwarna kelabu dengan pagar besi tinggi, halaman yang rapi, dan lampu temaram yang tetap menyala walau sudah larut malam.
Rumah keluarga Agung Wisesa.
Nama itu sudah berkali-kali ia dengar. Bukan hanya karena kekayaan dan pengaruhnya, tapi karena… sesuatu yang lebih gelap.
“Mas, kacangnya dimakan lagi nggak? Kalau nggak, aku habisin ya?”
Suara seorang anak kecil memecah lamunan Tegar. Anak itu duduk di bawah, di pos ronda yang dinaiki Tegar tadi.
“Heh! Jangan! Itu uang terakhirku!”
Tegar langsung turun, wajahnya panik.
Anak kecil itu bernama Gigih, warga lokal yang baru dikenalnya sore tadi. Polos, cerewet, dan sangat suka kacang rebus.
“Gigih, itu bener rumahnya Agung Wisesa?” tanya Tegar sambil menatap rumah besar itu lagi.
“Bener, Mas. Tapi kalo mau minta sumbangan, jangan malam-malam gini, ya.”
Plakk!
Tegar memukul pelan kepala Gigih. “Enak aja! Siapa yang mau minta sumbangan?”
“Lah, terus kenapa gembel kayak Mas-nya nyariin rumah orang kaya?”
Rumah keluarga Agung Wisesa.
Nama itu sudah berkali-kali ia dengar. Bukan hanya karena kekayaan dan pengaruhnya, tapi karena… sesuatu yang lebih gelap.
“Mas, kacangnya dimakan lagi nggak? Kalau nggak, aku habisin ya?”
Suara seorang anak kecil memecah lamunan Tegar. Anak itu duduk di bawah, di pos ronda yang dinaiki Tegar tadi.
“Heh! Jangan! Itu uang terakhirku!”
Tegar langsung turun, wajahnya panik.
Anak kecil itu bernama Gigih, warga lokal yang baru dikenalnya sore tadi. Polos, cerewet, dan sangat suka kacang rebus.
“Gigih, itu bener rumahnya Agung Wisesa?” tanya Tegar sambil menatap rumah besar itu lagi.
“Bener, Mas. Tapi kalo mau minta sumbangan, jangan malam-malam gini, ya.”
Plakk!
Tegar memukul pelan kepala Gigih. “Enak aja! Siapa yang mau minta sumbangan?”
“Lah, terus kenapa gembel kayak Mas-nya nyariin rumah orang kaya?”
Tegar nyaris memukul lagi, tapi urung. Bocah ini terlalu polos untuk dimarahi serius.
“Aku ke sana bukan buat minta sumbangan. Aku mau… cari demit,” ucap Tegar cuek.
“Oohh… Kalau demit, di sana banyak. Mau kuntilanak, pocong, nenek ular, semua ada.”
Tegar menatapnya curiga. “Kamu becanda?”
“Nggak. Banyak warga yang liat. Malah ada yang ngimpiin nenek ular tiga malam berturut-turut, terus tiba-tiba rumahnya tumbuh tanaman berduri dari tembok.”
Tegar mengangguk-angguk. Kacang rebus yang ia belikan untuk Gigih ternyata tidak sia-sia. Anak ini bisa jadi informan yang lumayan.
Malam itu, Tegar mengitari rumah Wisesa tiga kali. Ia membawa sebuah kendi kecil berisi air doa, dan memercikannya ke sudut-sudut yang hanya ia pahami maknanya. Setelah selesai, ia melangkah pelan meninggalkan halaman rumah itu, tanpa jejak.
***
“Aku ke sana bukan buat minta sumbangan. Aku mau… cari demit,” ucap Tegar cuek.
“Oohh… Kalau demit, di sana banyak. Mau kuntilanak, pocong, nenek ular, semua ada.”
Tegar menatapnya curiga. “Kamu becanda?”
“Nggak. Banyak warga yang liat. Malah ada yang ngimpiin nenek ular tiga malam berturut-turut, terus tiba-tiba rumahnya tumbuh tanaman berduri dari tembok.”
Tegar mengangguk-angguk. Kacang rebus yang ia belikan untuk Gigih ternyata tidak sia-sia. Anak ini bisa jadi informan yang lumayan.
Malam itu, Tegar mengitari rumah Wisesa tiga kali. Ia membawa sebuah kendi kecil berisi air doa, dan memercikannya ke sudut-sudut yang hanya ia pahami maknanya. Setelah selesai, ia melangkah pelan meninggalkan halaman rumah itu, tanpa jejak.
***
Pagi harinya…
Brakk!! Brakkk!! Suasana desa mendadak riuh. Warga berkerumun, melihat seorang pria gagah dengan wajah merah padam mengamuk keliling desa.
Agung Wisesa.
“Keluar kau!! Siapapun kau!! Keluar!!”
Warga saling tatap, bingung dan ketakutan. Tak ada yang tahu siapa yang ia cari. Tapi saat orang sebesar Agung Wisesa berteriak seperti itu, jelas ada sesuatu yang tidak beres.
Dari kejauhan, Tegar menyaksikan semua itu sambil menyeruput kopi dari cangkir seng, tersenyum tipis.
“Kamu udah taburin garam di halaman rumahmu?” tanya Tegar pada Gigih yang duduk di sampingnya.
“Udah, Mas. Kendinya juga udah saya kubur di halaman depan, kayak Mas Tegar bilang.”
“Ibumu udah nggak gatal-gatal lagi, kan?”
Gigih menoleh kaget. “Kok Mas Tegar tahu?”
Tegar tertawa kecil. “Sekarang gantian istrinya Pak Agung yang gatal-gatal.”
Gigih melongo. “I—itu… santet? Mas Tegar yang balikin ke Bu Agung?”
“Ngawur! Yang nyebar garam siapa? Yang tanam kendi siapa?” Tegar menunjuk Gigih.
“I—Iya, aku…”
“Nah, berarti kamu yang balikin santetnya! Sana, tanggung jawab!”
Tegar mendorong Gigih ke arah kerumunan di mana Agung Wisesa masih mengamuk.
“E—enak aja! Aku masih anak kecil! Aku nggak ikut-ikutan!!” Gigih langsung ngumpet di balik punggung Tegar, sementara Tegar tertawa terpingkal-pingkal.
Brakk!! Brakkk!! Suasana desa mendadak riuh. Warga berkerumun, melihat seorang pria gagah dengan wajah merah padam mengamuk keliling desa.
Agung Wisesa.
“Keluar kau!! Siapapun kau!! Keluar!!”
Warga saling tatap, bingung dan ketakutan. Tak ada yang tahu siapa yang ia cari. Tapi saat orang sebesar Agung Wisesa berteriak seperti itu, jelas ada sesuatu yang tidak beres.
Dari kejauhan, Tegar menyaksikan semua itu sambil menyeruput kopi dari cangkir seng, tersenyum tipis.
“Kamu udah taburin garam di halaman rumahmu?” tanya Tegar pada Gigih yang duduk di sampingnya.
“Udah, Mas. Kendinya juga udah saya kubur di halaman depan, kayak Mas Tegar bilang.”
“Ibumu udah nggak gatal-gatal lagi, kan?”
Gigih menoleh kaget. “Kok Mas Tegar tahu?”
Tegar tertawa kecil. “Sekarang gantian istrinya Pak Agung yang gatal-gatal.”
Gigih melongo. “I—itu… santet? Mas Tegar yang balikin ke Bu Agung?”
“Ngawur! Yang nyebar garam siapa? Yang tanam kendi siapa?” Tegar menunjuk Gigih.
“I—Iya, aku…”
“Nah, berarti kamu yang balikin santetnya! Sana, tanggung jawab!”
Tegar mendorong Gigih ke arah kerumunan di mana Agung Wisesa masih mengamuk.
“E—enak aja! Aku masih anak kecil! Aku nggak ikut-ikutan!!” Gigih langsung ngumpet di balik punggung Tegar, sementara Tegar tertawa terpingkal-pingkal.
“Heh, kau! Ngapain ketawa-ketawa?!”
Suara lantang itu memecah keramaian. Agung Wisesa, pria paling disegani di desa Tegalwurung, melotot tajam ke arah seseorang di kerumunan.
Tegar, yang sedang menikmati suasana, menoleh sambil menunjuk dirinya sendiri. “Saya?”
“Siapa lagi? Kau bukan orang sini, kan?”
“Bu—bukan…”
“Kau pelakunya! Pasti kau yang…!” desis Agung, suaranya tertahan namun jelas terdengar.
Tegar mengangkat alis wajahnya berubag serius. “Pelaku? Pelaku ini, maksudnya?”
Dengan santai, ia melempar sebuah koran ke tanah. Koran itu terbuka, menampilkan artikel:
“Arak-arakan Jenazah Misterius: Kesurupan Massal, Korban Jiwa”.
“Itu… bukannya kejadian minggu lalu?” bisik seorang warga.
“Kesurupan massal, sampai ada yang mati…” tambah lainnya. Suasana jadi riuh oleh gumaman penuh rasa ingin tahu.
“Dua perempuan dibuang di terminal,” ucap Tegar tegas. “Mereka bilang, jasad keramat disimpan di rumah ayahnya. Rumahmu. Kau yang memanfaatkannya, kan?!”
Wajah Agung memerah. Suara warga makin ribut.
“Bener juga ya, yang mati dan kerasukan itu musuh-musuh Pak Agung…”
“Iya, aneh banget ya…”
Agung Wisesa mengangkat tongkat kayu kebangganyanya, wajahnya menegang. “Bukan aku! Besok… kalian boleh periksa rumahku! Silakan cari jasad itu! Kalau berani!”
Tegar hanya menyipitkan mata. Semalam, ia sudah menerawang rumah megah itu dan melihat sendiri jasad aneh berbalut kain tua. Tapi… kalau begitu, kenapa Agung Wisesa begitu percaya diri?
“Baiklah,” celetuk salah satu warga, “mumpung besok libur, kita rame-rame ke rumah Pak Agung sekalian silaturahmi.”
Suara lantang itu memecah keramaian. Agung Wisesa, pria paling disegani di desa Tegalwurung, melotot tajam ke arah seseorang di kerumunan.
Tegar, yang sedang menikmati suasana, menoleh sambil menunjuk dirinya sendiri. “Saya?”
“Siapa lagi? Kau bukan orang sini, kan?”
“Bu—bukan…”
“Kau pelakunya! Pasti kau yang…!” desis Agung, suaranya tertahan namun jelas terdengar.
Tegar mengangkat alis wajahnya berubag serius. “Pelaku? Pelaku ini, maksudnya?”
Dengan santai, ia melempar sebuah koran ke tanah. Koran itu terbuka, menampilkan artikel:
“Arak-arakan Jenazah Misterius: Kesurupan Massal, Korban Jiwa”.
“Itu… bukannya kejadian minggu lalu?” bisik seorang warga.
“Kesurupan massal, sampai ada yang mati…” tambah lainnya. Suasana jadi riuh oleh gumaman penuh rasa ingin tahu.
“Dua perempuan dibuang di terminal,” ucap Tegar tegas. “Mereka bilang, jasad keramat disimpan di rumah ayahnya. Rumahmu. Kau yang memanfaatkannya, kan?!”
Wajah Agung memerah. Suara warga makin ribut.
“Bener juga ya, yang mati dan kerasukan itu musuh-musuh Pak Agung…”
“Iya, aneh banget ya…”
Agung Wisesa mengangkat tongkat kayu kebangganyanya, wajahnya menegang. “Bukan aku! Besok… kalian boleh periksa rumahku! Silakan cari jasad itu! Kalau berani!”
Tegar hanya menyipitkan mata. Semalam, ia sudah menerawang rumah megah itu dan melihat sendiri jasad aneh berbalut kain tua. Tapi… kalau begitu, kenapa Agung Wisesa begitu percaya diri?
“Baiklah,” celetuk salah satu warga, “mumpung besok libur, kita rame-rame ke rumah Pak Agung sekalian silaturahmi.”
Drap. Drap. Drap. Agung Wisesa menghentakkan tongkatnya tiga kali ke tanah, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa, meninggalkan kerumunan.
Tegar memandang punggung Agung dengan mata tajam.
“Mas… berarti dia yakin nggak ada mayat di sana?” bisik Gigih, anak kecil yang selalu menempel pada Tegar sejak tadi.
Tegar menggeleng, wajahnya serius. “Bukan. Dia yakin, karena sebelum besok… kita yang ada di sini akan mati.”
Deg.
Gigih langsung pucat. Tapi warga mulai membubarkan diri, menganggap semua itu sekadar drama tengah malam.
“Mas Tegar, bercanda kan?” tanya Gigih pelan.
Tegar hanya menjawab dengan gelengan kepala.
“Dia manusia biadab, Gigih. Dan dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk desa ini.”
Sebelum Tegar menjawab, seorang pria tua mendekati mereka. Rambutnya putih, sorot matanya tajam tapi penuh ketenangan. “Maksud Masnya apa?”
“Eh, Mbah Setyo!” seru Gigih. Ia langsung mencium tangan orang tua itu.
“Ini Mbah Setyo, sesepuh desa. Waktu kejadian kesurupan, beliau yang bantuin warga,” jelas Gigih pada Tegar.
Tegar menunduk sopan. “Saya Tegar, Mbah. Cuma numpang lewat.”
“Numpang lewat kok bikin keluarga Wisesa kalang kabut,” sahut Mbah Setyo sambil tersenyum.
Tegar hanya garuk-garuk kepala, malu.
“Mampir ke rumah, yuk. Ngobrol di rumah lebih enak.,” tawar Mbah Setyo ramah.
“Wah, ngga usah, Mbah. Nanti merepotkan…”
Mendengar balasan Tegar, Gigih memicingkan matanya..
“Yakin? Singkong Mbah Setyo enak lho. Panenan sendiri,” goda Gigih.
***
(Bersambung Sabda Pangiwa II - Warisan Jenazah Part 2)
Tegar memandang punggung Agung dengan mata tajam.
“Mas… berarti dia yakin nggak ada mayat di sana?” bisik Gigih, anak kecil yang selalu menempel pada Tegar sejak tadi.
Tegar menggeleng, wajahnya serius. “Bukan. Dia yakin, karena sebelum besok… kita yang ada di sini akan mati.”
Deg.
Gigih langsung pucat. Tapi warga mulai membubarkan diri, menganggap semua itu sekadar drama tengah malam.
“Mas Tegar, bercanda kan?” tanya Gigih pelan.
Tegar hanya menjawab dengan gelengan kepala.
“Dia manusia biadab, Gigih. Dan dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk desa ini.”
Sebelum Tegar menjawab, seorang pria tua mendekati mereka. Rambutnya putih, sorot matanya tajam tapi penuh ketenangan. “Maksud Masnya apa?”
“Eh, Mbah Setyo!” seru Gigih. Ia langsung mencium tangan orang tua itu.
“Ini Mbah Setyo, sesepuh desa. Waktu kejadian kesurupan, beliau yang bantuin warga,” jelas Gigih pada Tegar.
Tegar menunduk sopan. “Saya Tegar, Mbah. Cuma numpang lewat.”
“Numpang lewat kok bikin keluarga Wisesa kalang kabut,” sahut Mbah Setyo sambil tersenyum.
Tegar hanya garuk-garuk kepala, malu.
“Mampir ke rumah, yuk. Ngobrol di rumah lebih enak.,” tawar Mbah Setyo ramah.
“Wah, ngga usah, Mbah. Nanti merepotkan…”
Mendengar balasan Tegar, Gigih memicingkan matanya..
“Yakin? Singkong Mbah Setyo enak lho. Panenan sendiri,” goda Gigih.
***
(Bersambung Sabda Pangiwa II - Warisan Jenazah Part 2)
Terima kasih sudah membaca part ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata atau bagian cerita yang menyinggung.
Buat temen-temen yang mau baca duluan part 2nya bisa mampir ke @karyakarsa_id ya :
karyakarsa.com/diosetta69/tam…
Buat temen-temen yang mau baca duluan part 2nya bisa mampir ke @karyakarsa_id ya :
karyakarsa.com/diosetta69/tam…
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh