MISTERI ANAK-ANAK PAK JAWI
CHAPTER 2 DAN 3
@bacahorror @IDN_Horor
#threadhorror #bacahorror #timurtrilogi
CHAPTER 2 DAN 3
@bacahorror @IDN_Horor
#threadhorror #bacahorror #timurtrilogi
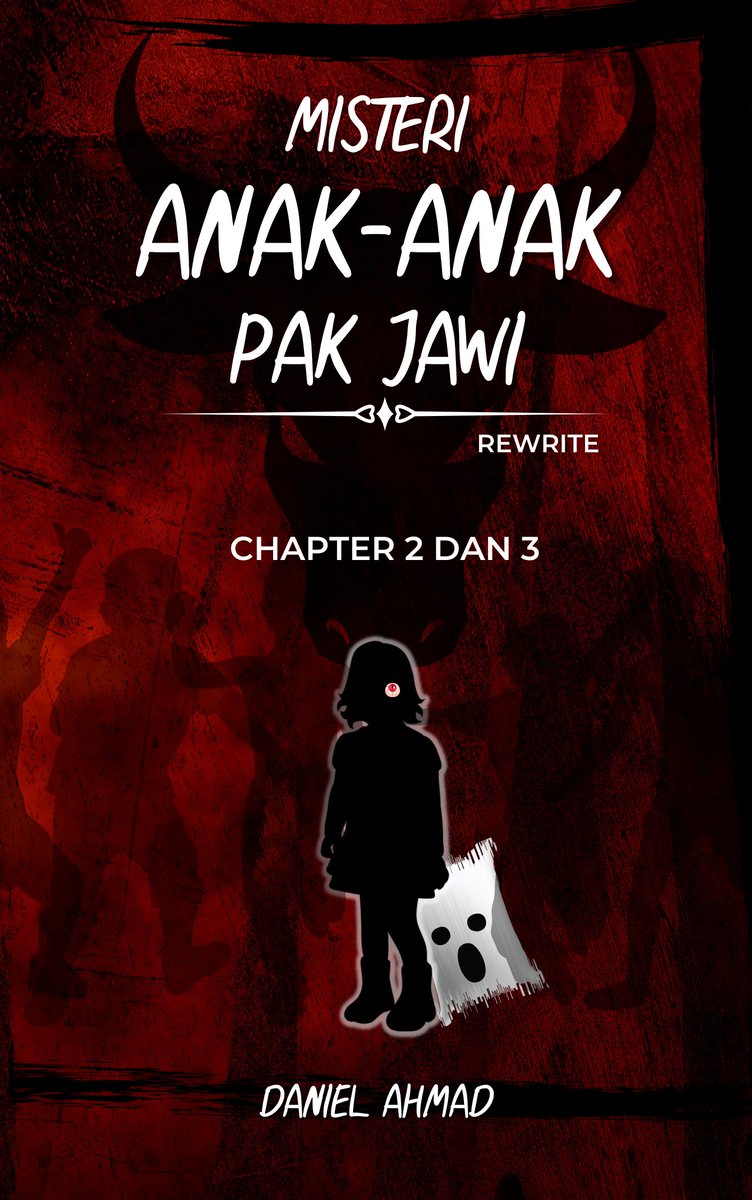
Buat yang belum baca Chapter 1
https://twitter.com/DanieloAhmad/status/1539959491911127044?s=20&t=XeMnXEeZZbrHtoOmVnsfZw
Salah satu adab dalam bertamu adalah, tahu kapan waktunya berkunjung, dan kapan waktunya pulang, tapi Pak Edi sudah ada di rumah sejak azan magrib selesai dikumandangkan, hingga bertemu dengan azan isya.
Dia bahkan belum pulang saat kakek pamit salat, dan masih betah duduk di ruang tamu sampai sekarang. Sepenting apa pun maksud kedatangannya, bagiku tetap saja menyebalkan.
Sedikit menguping pembicaraan kakek dan Pak Edi di ruang tamu. Mereka membahas tentang persiapan pemilihan kepala desa. Kakek memang bukan aparat desa, tapi bisa dibilang beliau adalah tokoh masyarakat yang sangat disegani di Sumbergede—
meski aku sendiri heran kenapa orang seperti kakek bisa disegani—Mungkin alasan itulah yang membuat Pak Edi yang ketua RT datang ke rumah untuk berdiskusi dengan kakek.
"Kenapa Sampean tidak mencalonkan diri saja?" usul kakek. Terdengar bercanda dan cenderung mengolok.
"Yang benar saja, Kang, saya belum banyak berkiprah dalam pembangunan desa ini. Mana mungkin ada yang mau milih," jawab Pak Edi, tersipu.
"Yang benar saja, Kang, saya belum banyak berkiprah dalam pembangunan desa ini. Mana mungkin ada yang mau milih," jawab Pak Edi, tersipu.
"Iya, ya! Saya juga tidak mau milih Sampean."
Kakek terbahak-bahak.
Saat lantunan ayat suci di masjid berhenti, percakapan hangat mereka juga berhenti. Aku dapat mendengar cukup jelas dari ruang televisi. Saat itulah diskusi mereka yang penuh canda hangat berubah menjadi serius
Kakek terbahak-bahak.
Saat lantunan ayat suci di masjid berhenti, percakapan hangat mereka juga berhenti. Aku dapat mendengar cukup jelas dari ruang televisi. Saat itulah diskusi mereka yang penuh canda hangat berubah menjadi serius
"Mengenai isu santet yang sedang ramai dibicarakan warga saat ini, saya sudah melakukan yang Kang Saleh sarankan," tutur Pak Edi. Cara bicaranya mulai serius.
"Terus?"
"Terus?"
"Sayangnya sampai hari ini saya belum menerima laporan dari para petugas, padahal ini sudah hari kelima." Pak Edi berdeham. "Kalau sampai hari ketujuh masih normal, maka saya ambil kesimpulan bahwa ini hanya isu semata," pungkasnya.
"Bagus. Seorang tukang santet tinggal di lingkungan pesantren, isu seperti itu sangat tidak bagus untuk nama baik desa kita. Terutama nama baik pesantren."
Percakapan itu berlanjut pada sesuatu yang tidak lagi menarik. Aku berhenti memperhatikan dan kembali merebah di kasur lantai, di depan televisi. Perlahan-lahan aku mulai larut dalam lamunan.
Hampir semua rangkuman kejadian hari ini lewat di pikiran. Ada banyak yang kusyukuri, sebanyak yang aku sesali. Lalu aku terpejam, saat itulah bayangan rumah Pak Ahsan muncul di kepala. Mataku terbuka lagi lalu melihat jam dinding.
"Ini sudah setengah 8!" pekikku.
Tepat saat itu, kudengar suara Pak Edi sedang berpamitan. Masih disertai canda basa-basi yang membuat pamitannya jadi lebih lama.
Tepat saat itu, kudengar suara Pak Edi sedang berpamitan. Masih disertai canda basa-basi yang membuat pamitannya jadi lebih lama.
Aku keluar kamar dan menghampiri kakek yang sedang berdiri di pintu melepas kepulangan sang tamu, tamu yang menurutku tidak tahu diri.
"Kenapa wajahmu kusut begitu?" tanya kakek.
"Pak Edi lama banget bertamunya. Masa dari magrib sampai isya nggak pulang-pulang," protesku.
"Pak Edi lama banget bertamunya. Masa dari magrib sampai isya nggak pulang-pulang," protesku.
"Jangan gitu sama tamu. Pak Edi selalu menyambut dengan baik kalau kakek bertamu ke rumahnya. Jadi, kita pun harus begitu. Tapi emang ngerepotin, sih." Tutur kakek. "Ngomong-ngomong, mana obat yang tadi kakek pesan?"
"Ah, iya. Ini saya mau berangkat, Kek"
"Ah, iya. Ini saya mau berangkat, Kek"
Cepat aku pergi sambil menggaruk kepala, sebelum kakek sadar kalau sebenarnya aku lupa. Aku juga tidak menceritakan tentang saran Pak Ahsan yang melarang datang terlalu malam.
CHAPTER 3
Kembali ke gang tanpa nama. Malam ini aku bawa motor butut bapak yang biasa dipakai ke ladang. Aku tidak seberani itu mengayuh sepeda di jalan gelap, becek, tanpa lampu, dan ternyata keputusanku tepat.
Gang tanpa nama ini sama sekali tidak punya penerangan. Kuharap siapa pun kepala desa yang baru nanti, mau menyisihkan sedikit dana untuk memasang lampu.
Kupacu sepeda butut bapak. Ngebut, tapi tetap konsentrasi. Jalan becek ini bisa saja membuatku terpeleset, terjungkal, lalu meluncur bebas di atas lumpur. Memang jatuh di tempat sepi tidak akan membuat malu, kecuali diam-diam ada kuntilanak di atas pohon mangga yang menertawakan.
Sampailah di rumah Pak Ahsan, dan untuk sebuah alasan, gubuk kumuh itu membuatku tercengang.
Kuparkir motor di dekat pintu masuk halaman, di tempat yang sama seperti tadi sore. Kulangkahkan kaki menuju ke rumah Pak Ahsan. Celingak-celinguk karena suasana yang menurutku unik, atau bisa dibilang aneh.
Desa ini tentu sudah dialiri listrik secara menyeluruh, tapi Pak Ahsan seperti menolak lampu. Penerangan di gubuk ini masih mengandalkan lampu minyak, dan beberapa obor yang digantung di pohon mangga.
Satu lampu petromax besar di kandang sapi. Kombinasi klasik dan mengerikan itulah yang membuatku tercengang.
Segala keanehan yang kulihat tadi sore jadi makin mencolok saat malam. Tiga dari enam ayunan di pohon mangga itu berayun pelan. Entah tertiup angin, atau baru saja digunakan.
Rumput segar di tempat pakan sapi juga menghilang, membuatku bertanya-tanya, kalau tidak ada sapi, terus rumput itu siapa yang makan?
Ada satu hal lagi yang menarik perhatianku. Di bawah salah satu pohon mangga, kulihat enam anak kecil duduk jongkok di tanah sedang mengelilingi sesuatu. Seperti sedang bermain gundu. Keenamnya menunduk, dan tidak peduli akan kedatanganku.
Aku pun tidak punya alasan mempedulikan mereka karena sudah sampai di depan rumah. Tampak Pak Ahsan sedang berada di teras, duduk di bangku kayu menghadap ke arah anak-anak bermain. Terlihat sedang mengawasi.
"Assalamualaikum," ucapku.
"Waalaikumsalam."
Pak Ahsan menjawab, kemudian menyipitkan mata, mencoba memastikan siapa yang datang. Wajar, di usia seperti itu, penglihatannya pasti sudah tidak baik.
"Waalaikumsalam."
Pak Ahsan menjawab, kemudian menyipitkan mata, mencoba memastikan siapa yang datang. Wajar, di usia seperti itu, penglihatannya pasti sudah tidak baik.
"Oh, Sampean. Mari duduk dulu, Nak. Mau jemput obat, kan?"
"Iya, Mbah. Maaf terlambat. Soalnya masih ada tamu di rumah."
"Oh, ndak apa-apa, kok, ndak apa-apa," katanya.
"Iya, Mbah. Maaf terlambat. Soalnya masih ada tamu di rumah."
"Oh, ndak apa-apa, kok, ndak apa-apa," katanya.
Setelah mempersilakan aku duduk, Pak Ahsan masuk ke dalam rumahnya. Ia menyibak kain merah dengan pelan, lalu menghilang di kegelapan. Dari semua cahaya api di luar, bagian dalam rumahnya dibiarkan tetap gelap.
Aku duduk di kursi yang tempat duduk dan sandarannya terbuat dari tali karet berwarna merah. Sebagian sudah putus dan bergelantungan ke bawah. Persis seperti punyaku di rumah. Aku merenung.
Rumah Pak Ahsan ini sebenarnya tidak berbeda dengan beberapa warga Sumbergede yang hidupnya kurang beruntung. Mungkin aku terbuai hidup yang nyaman, hingga kemiskinan jadi terasa menakutkan.
Ya, keluargaku pun bukan orang kaya, tapi setidaknya kami hidup lebih berada dari Pak Ahsan.
Cukup lama aku menunggu, dan sekarang jadi bosan. Untuk menghilangkan jenuh, iseng kudekati anak-anak yang sedang bermain di halaman itu. Sepertinya asyik sekali. Sejak tadi mereka tergeming seolah sangat menikmati permainannya.
Kupasang senyum ramah. Berharap tidak terlalu menganggu mereka. Usia mereka tampak tidak jauh berbeda satu sama lain. Mungkin sebaya dengan sepupuku yang baru masuk sekolah dasar.
Dari dekat kulihat mereka sedang jongkok mengelilingi gambar kotak-kotak permainan Engklek yang kulihat tadi sore. Ada sebuah benda tergeletak tak jauh dari tempat mereka duduk. Seperti sebuah bantal dengan kain putih yang warnanya hampir kecoklatan.
"Wah, lagi main apa, nih?" Sapaku ramah, mempertahankan senyum.
Lama-kelamaan, senyumku jadi terlihat canggung. Anak-anak itu sama sekali tidak menggubris. Mereka masih saja asyik sendiri.
Lama-kelamaan, senyumku jadi terlihat canggung. Anak-anak itu sama sekali tidak menggubris. Mereka masih saja asyik sendiri.
Sedikit kesal, tapi aku coba sabar sambil batin ini mengulang-ulang kalimat sakti, namanya juga anak-anak.
Mereka masih menunduk, hanya tangannya saja yang bergerak mencoreti tanah dengan ujung jari. Tiba-tiba kudengar mereka berbisik, serempak, dan walaupun terdengar lumayan nyaring, tapi aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, karena mereka memang tidak bicara apa-apa,
hanya membisikkan bunyi-bunyian tak berarti yang makin lama makin nyaring dan intonasinya pun makin meninggi.
Merasa tidak nyaman, aku pun menyerah. Mereka terlalu aneh. Tidak hanya sikap, bermain di halaman jam segini saja bagiku sudah tidak wajar. Anak seumuran mereka di kampung ini pasti sudah tidur.
Aku berniat kembali ke teras rumah, tapi tak sengaja menginjak bantal putih di tanah, dan seketika itu juga mereka serempak menoleh ke arahku.
"Ya, Tuhan."
Aku terhenyak dan nyaris teriak. Mungkin reaksiku terasa berlebihan, tapi itu sepadan dengan apa yang kulihat. Keenam anak itu menatap sinis, salah satu dari mereka tampak akan menangis. Sisanya sudah memasang wajah marah dan mulai mendesis.
Aku terhenyak dan nyaris teriak. Mungkin reaksiku terasa berlebihan, tapi itu sepadan dengan apa yang kulihat. Keenam anak itu menatap sinis, salah satu dari mereka tampak akan menangis. Sisanya sudah memasang wajah marah dan mulai mendesis.
Namun, yang paling tidak bisa aku lupakan adalah, keenam anak itu ternyata tidak normal. Cahaya obor yang digantung di pohon mangga; di dekat mereka duduk, memperjelas semuanya.
Mereka tidak tampak bersaudara. Tidak ada yang serupa. Salah satunya ada yang berbadan kurus, dan kedua matanya melirik arah yang berbeda. Yang kanan melirik ke kanan, dan yang kiri melirik ke kiri.
Dia berada di barisan depan dengan sikap melindungi, seolah menegaskan bahwa si juling itulah yang paling tua.
Di belakang si juling sedang berlindung seorang anak perempuan. Rambutnya panjang dan menutupi sebagian besar wajah. Hanya mata kanannya saja yang kelihatan, memelototiku penuh benci. Ada yang aneh dengan mulut anak itu.
Kalau kuperhatikan sekilas, mulut anak itu berada di posisi yang salah. Sedikit ke kanan dan ujungnya hampir sampai ke pipi. Dialah yang kelihatan paling sedih. Ia mendekap bantal putih yang tak sengaja kuinjak.
Bantal itu ternyata adalah sebuah boneka. Maksudku, itu benar-benar bantal tapi sengaja diberi gambar mata, mulut, dan hidung layaknya sebuah boneka.
"Ma-maaf," kataku, gugup.
Baru kali ini aku minta maaf pada anak kecil dengan tulus karena benar-benar takut.
Baru kali ini aku minta maaf pada anak kecil dengan tulus karena benar-benar takut.
Dua anak mendesis lebih keras, pertanda permintaan maafku ditolak. Keduanya maju dan berdiri di samping si Juling. Salah satunya berbadan kurus dengan kepala botak.
Mata dan mulutnya masih normal jika dibandingkan si Juling dan si Mencong, tapi di dahinya ada sebuah benjolan lumayan besar. Belum lagi setelah kuperhatikan, anak botak itu tidak punya tangan. Dia buntung. Tangannya seolah berhenti tumbuh sampai di siku.
Yang maju bersama si Buntung barusan adalah si Gendut. Aku juluki begitu karena anak itulah yang paling gemuk. Sekilas dia tidak tampak cacat, justru seolah-olah dialah yang paling sehat.
Begitu pikirku sampai kulihat tatapan kosong si Gendut dan mulutnya yang selalu menganga. Air liur pun mengalir deras dari mulut yang sejak tadi mendengung dengan suara parau.
Kemudian, yang paling mencolok dari keenamnya adalah kedua anak itu. Anak yang paling tinggi. Tinggi yang tidak wajar untuk anak seusianya. Dia berkulit hitam dengan rambut ikal kemerahan.
Sekilas punya gangguan penglihatan. Bisa kulihat mata putih dengan kelopak merah bengkak yang sedang menatap keji ke berbagai arah, seolah ia tidak tahu di mana posisiku berada. Kendati melenceng dalam tatapan, dia tetap seragam dalam desis dan kemarahan.
Si Jangkung itu sedang menggendong seorang anak lagi yang tidak punya kaki. Sama seperti si Buntung tadi, kaki anak yang digendong itu hanya sampai lutut, tapi amarahnya sudah sampai ubun-ubun.
Si Pincang itulah yang pertama kali melempariku dengan batu. Ia membidik dari atas bahu si Jangkung, hingga batu itu nyaris membentur wajahku, andai saja aku tidak menghindar.
Sebutlah aku berdosa karena merasa ngeri dengan anak cacat, tapi situasi saat itu sungguh berbeda. Pakaian mereka yang compang-camping, gerak-gerik yang tidak wajar, bicaranya yang tidak normal,
serta didukung suasana sekitar yang sejak awal sudah tidak nyaman, pantaslah kalau aku ketakutan. Aku mundur, mencoba jaga jarak dari mereka yang makin mendekat. Tetiba mereka mengambil batu, pecahan genting, keramik, dan benda apapun yang ada di tanah.
"Eh, tunggu dulu!" Kataku panik.
Aku memang salah, tapi tidakkah reaksi mereka berlebihan.
Aku memang salah, tapi tidakkah reaksi mereka berlebihan.
Tepat sebelum mereka lemparkan hasil pungutannya barusan, terdengarlah suara lonceng. Suara itu sangat familier bagiku. Suara lonceng sapi yang selalu terdengar saat pedati pengangkut pasir lewat.
Ya, tidak salah lagi itu adalah suara klontong, begitulah orang-orang desa menyebut lonceng sapi. Namun, bukankah Pak Ahsan tidak punya sapi?
Ajaibnya, keenam anak itu terdiam. Genggaman tangannya melemah dan benda-benda yang mereka pungut berjatuhan ke tanah. Gilanya, salah satu dari benda itu adalah sebuah paku besar berkarat. Tidak terpikir olehku anak seumuran mereka berniat mencelakai orang dengan benda tajam.
Aku bersyukur mereka jadi tenang kembali. Semua itu berkat bunyi klontong yang masih terdengar. Penasaran akan asal suara itu, aku pun menoleh ke belakang. Rupanya suara itu berasal dari klontong sapi yang dibunyikan oleh Pak Ahsan.
Kakek itu sedang berdiri di teras rumah, tangan kanannya masih membunyikan klontong seraya mengayun-ayunkan ke arah rumah seolah menggiring anak-anak untuk masuk.
Mungkin ini sedikit tidak masuk akal bagiku, tapi suara klontong itu seolah menghipnotis anak-anak. Mereka berjalan pelan mendekati Pak Ahsan dengan wajah... bahagia?
Entahlah, setidaknya mereka tidak tampak seberingas tadi. Kusaksikan semua itu sambil bergeming dan tak banyak berkomentar.
Pak Ahsan meraih tas plastik merah di atas lemari kayu, kemudian ia masukkan botol besar ke dalamnya.
"Ini obatnya, sekarang lekaslah pulang!" kata Pak Ahsan, dengan segala keramahannya yang pudar. Ia bahkan memberikan pesanan kakek dengan cara dilempar.
"Ini obatnya, sekarang lekaslah pulang!" kata Pak Ahsan, dengan segala keramahannya yang pudar. Ia bahkan memberikan pesanan kakek dengan cara dilempar.
Terdengar tidak bersahabat dan sedikit mengusir, tapi aku setuju. Aku pun tidak ingin berlama-lama di sini. Kutangkap kantong plastik berisi obat itu, lalu berpamitan.
"Terima kasih, Mbah. Maaf kalau saya—"
"Terima kasih, Mbah. Maaf kalau saya—"
"Ndak apa-apa. Maklumi anak-anak saya juga. Mereka memang begitu kalau sedang bermain."
Anak? Mereka berenam anak-anak Pak Ahsan? Jarak usia mereka saja sudah sangat jauh, belum lagi kondisi Pak Ahsan yang seperti itu, rasanya mustahil punya anak.
Anak? Mereka berenam anak-anak Pak Ahsan? Jarak usia mereka saja sudah sangat jauh, belum lagi kondisi Pak Ahsan yang seperti itu, rasanya mustahil punya anak.
"Sa-saya pamit, Mbah, salam sama ibunya anak-anak."
Itu adalah kalimat terakhirku sebelum memutuskan untuk tutup mulut. Entah apa yang salah? Lagi-lagi aku membuat keenam anak itu marah. Mereka yang sudah di ambang pintu serempak menoleh, melotot, lalu berteriak dengan sangat keras. Suaranya melengking.
"Cepat pergi!" perintah Pak Ahsan, kali ini dia benar-benar mengusirku.
Aku tergopoh pergi. Begitu sampai di motor, segera kupacu dengan cepat melewati gang tanpa nama yang gelap. Di pikiranku hanyalah rumah. Aku ingin segera sampai di sana, dan berharap ini adalah yang terakhir. Aku tidak mau kembali ke tempat ini lagi.
Lagipula, ada yang aneh dari Pak Ahsan malam ini. Seingatku, dia bungkuk dan susah berjalan, tapi malam ini badannya tegap, sehat, bahkan sanggup menjangkau tas plastik di atas lemari yang lumayan tinggi.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh










