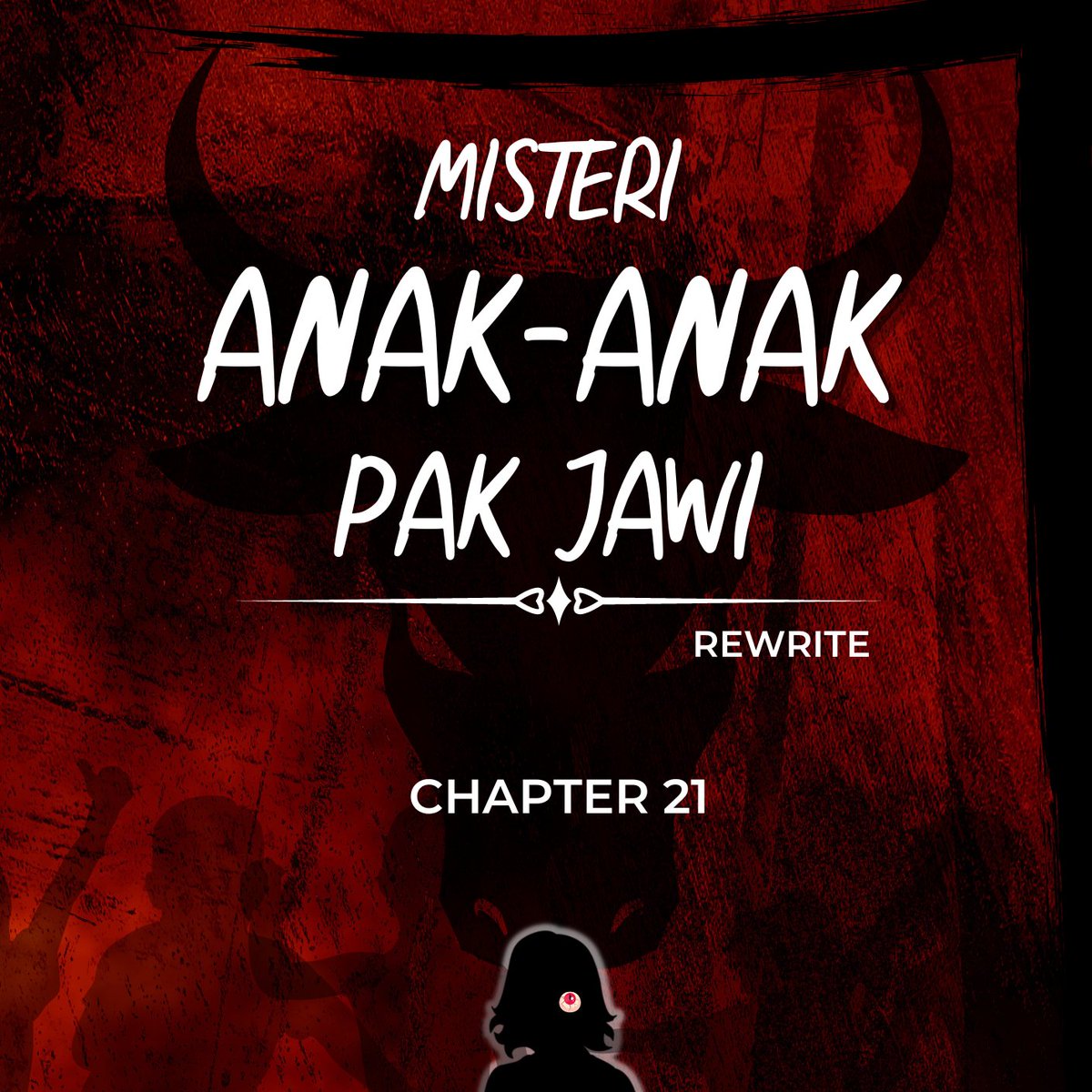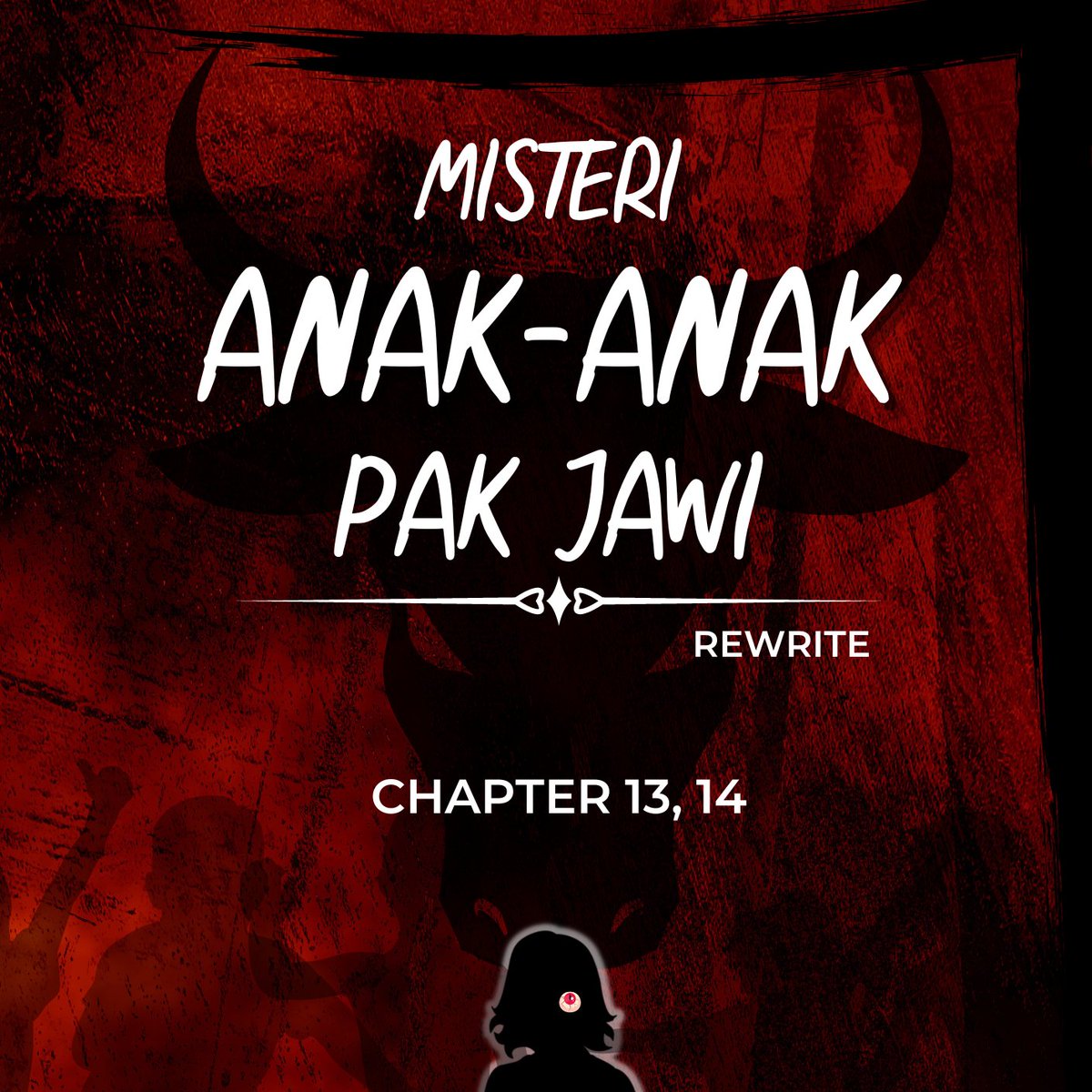MISTERI ANAK-ANAK PAK JAWI
CHAPTER 22, 23
@bacahorror @IDN_Horor
#threadhorror #bacahorror #timurtrilogi
CHAPTER 22, 23
@bacahorror @IDN_Horor
#threadhorror #bacahorror #timurtrilogi
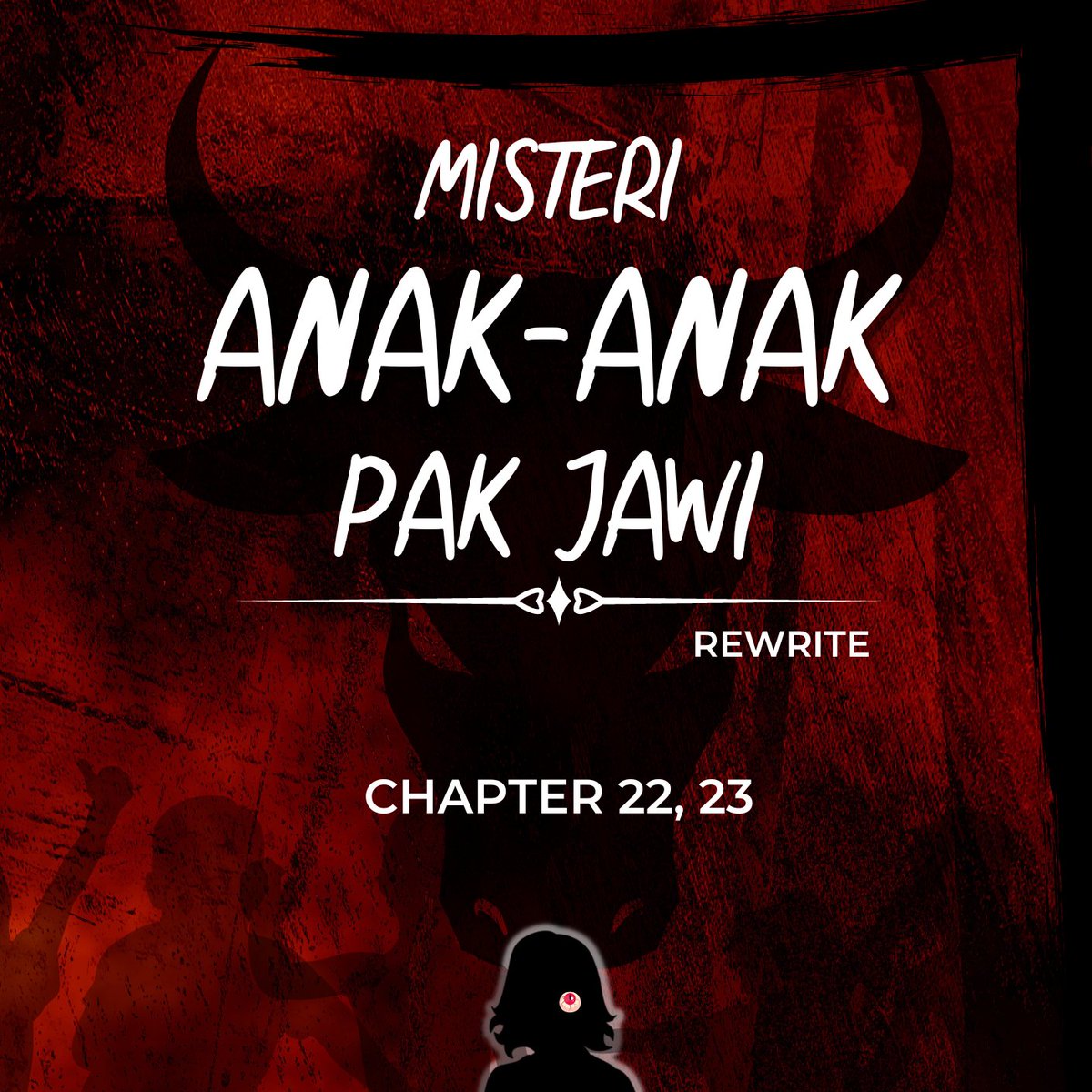
CHAPTER 22
Tengah malam tidak pernah seramai ini. Aku terpaksa memelankan laju motor, karena kerumunan orang di setiap rumah yang kulewati hampir menutupi separuh jalan.
Tengah malam tidak pernah seramai ini. Aku terpaksa memelankan laju motor, karena kerumunan orang di setiap rumah yang kulewati hampir menutupi separuh jalan.
Di pemukiman yang padat, dan punya jalan sempit seperti ini, harusnya aku turun dari motor, kudorong sambil menyapa setiap orang, terus begitu sampai ke jalan beraspal.
Namun, situasi ini memaksaku untuk tidak menggunakan seratus persen sopan santun. Motor tetap kukendarai, dan alih-alih menyapa setiap orang, aku terpaksa membunyikan klakson serta menggeber agar diberi jalan.
Buat teman-teman yang belum baca dari awal
https://twitter.com/DanieloAhmad/status/1539969843646312449?s=20&t=KiUGKj3UPIELC_nkdSbXlQ
Mulai terdengar lantunan ayat suci di musala terdekat, dan segera disusul oleh musala lainnya. Orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi, pun tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Berdoa adalah satu-satunya jalan, karena aku pun merasa ada hal tak kasatmata yang sedang bermain di balik layar.
Sampai ke jalan beraspal, aku segera menambah kecepatan. Kebut-kebutan melewati jalan sepi yang diapit sawah dan kebun pisang, hingga akhirnya sampai ke Sumbergede bagian tengah, melewati kawasan pesantren yang mulai sepi karena para santri sudah harus berada di asrama.
Barulah ketika memasuki bagian selatan desa, di mana pemukiman warga mulai terbagi menjadi beberapa gang, termasuk gang Kadal, aku merasakan atmosfer yang sama seperti di rumah Erik.
Rumah-rumah di pinggir jalan ramai oleh warga, dan sepertinya rumah di dalam gang juga demikian. Kupacu motor Erik lebih cepat lagi. Tak sabar untuk segera sampai ke rumah.
Namun, terpaksa aku injak penuh rem motor saat melewati Gang Kadal. Nyaris saja aku hilang keseimbangan. Roda berdecit menggaruk aspal, hingga motor berubah haluan, dan berhenti di tengah jalan.
“Yang ba-barusan itu, apa?” gumamku seraya terengah-engah. Debar jantung masih sangat cepat karena baru saja selamat dari kecelakaan.
Tiba-tiba saja sesuatu yang besar melintas di hadapanku. Sesuatu yang hitam, gelap, berjalan dengan empat kaki, lalu hilang di bawah tiang lampu jalan.
Kemudian, di bawah tiang lampu yang sama, kulihat tiga orang anak sedang berdiri. Mereka adalah Si Gendut, si Juling, dan si Mencong.
Persetan dengan mereka, aku tak mau menunggu degup jantung mereda, kembali kutarik tuas gas motor, lalu melanjutkan sisa perjalanan dengan kecepatan penuh,--
--berharap tidak ada lagi kejutan dari anak-anak itu, karena akan sulit meminta maaf pada Erik kalau motor peninggalan bapaknya sampai lecet karena kubawa meluncur di aspal.
KAK!
Dapat kurasakan seseorang duduk di jok belakang, berbisik tepat di belakang telinga. Rasanya semua bulu halus di tubuhku berdiri, tapi saat kuperiksa melalui kaca spion, tidak ada siapa pun di sana.
Selama ini aku selalu menganggap mereka hanya anak kecil, tapi kalau begini cara mereka mengajak bermain, maka aku harus menanggapi mereka dengan cara seharusnya.
“Bismillah”
“Bismillah”
Kubaca ayat suci. Mulut merapal, mata sebisa mungkin fokus pada jalan. Telinga masih mendengar sayup suara mereka, dan badan berkeringat dingin meski sudah diterpa angin. Doaku tak pernah putus hingga akhirnya sampai di gapura Sumbergede, barulah semua gangguan itu hilang.
Aku berhenti sejenak. Mencari celah masuk ke jalan besar di antara bus dan truk yang lewat. Dapat kudengar tukang becak mengobrol dengan intonasi yang gawat.
Sepertinya mereka sedang membahas tentang sesuatu yang terjadi di desa. Aku pun tak sabar sampai rumah untuk segera membahas ini bersama kakek, dan kali ini aku harus memaksanya mendengar serta menanggapi dengan serius.
Sesampainya di rumah, kudapati kakek dan Mbah Sopet sedang duduk kelelahan di ruang tamu. Mereka tidak terlalu peduli akan kedatanganku. Kakek pun hanya bertanya dari mana, lalu kembali memejamkan mata saat kujawab.
Ini tidak sesuai perkiraan. Harusnya kakek marah karena rumah aku tinggal, atau setidaknya marah karena aku pulang terlalu malam. Namun, dua orang ini seolah baru kembali dari medan perang. Napasnya ngos-ngosan, keringatnya masih mengembun di kening dan leher.
Melihat tidak satu pun minuman yang tersaji di meja, aku berinisiatif pergi ke dapur membuatkan kopi untuk mereka, dan tentunya untuk diri sendiri.
“Ngapain kamu di sini?” tanyaku pada gadis bercadar merah yang sedang menyeduh kopi di dapur.
“Bikin kopi,” jawabnya, tanpa rasa sungkan atau sekadar menoleh padaku yang merupakan tuan rumah.
“Bikin kopi,” jawabnya, tanpa rasa sungkan atau sekadar menoleh padaku yang merupakan tuan rumah.
Kendati beralasan membuat kopi, gadis ini tampak kikuk dan canggung. Ia memasak air dengan panci besar yang biasa aku pakai membuat sup sayur, lalu menuangkan lima sendok bubuk kopi ke dalam satu cangkir kecil, disusul satu sendok gula pasir.
Aku masih memperhatikannya dengan heran, barulah saat dia menuangkan air panasnya ke masing-masing cangkir, aku merasa harus menghentikan kegilaan ini.
“Stop!” seruku saat melihat air panas melubar ke berbagai arah, membuat kopi buatan gadis itu tumpah membanjiiri meja.
“Kamu ... kamu nggak pernah bikin kopi, kan?” tanyaku.
“Kamu ... kamu nggak pernah bikin kopi, kan?” tanyaku.
Gadis itu menunduk, tidak menjawab, tapi bisa kuterka kalau dia sedang malu. Aku pun tidak asal menuduh. Perbandingan takaran kopi dan gulanya saja sudah bikin sakit perut, cara dia menuang air juga seperti anak kecil bermain masak-masakan.
Kalau sampai kakek dan Mbah Sopet minum kopi buatan gadis ini, bisa-bisa mereka tidak tidur sampai lebaran.
“Kamu dari mana?” tanya gadis itu.
Ini pertama kalinya dia mengajakku ngobrol.
“Dari rumah teman, di Sumbergede utara.”
“Apa di sana juga lagi gawat?” tanyanya lagi.
Ini pertama kalinya dia mengajakku ngobrol.
“Dari rumah teman, di Sumbergede utara.”
“Apa di sana juga lagi gawat?” tanyanya lagi.
Sembari mengulang kopi buatannya yang berantakan, kupikir tidak ada salahnya bercerita. Kujelaskan apa yang sedang terjadi di sana, tidak peduli gadis ini mau percaya atau tidak.
“Sepertinya kejadian ini hampir merata di seluruh desa, terutama di rumah warga yang punya anak kecil,” ucap gadis itu.
“Ya, pas pulang barusan, aku juga ngelihat kondisi yang sama di beberapa rumah.”
“Ya, pas pulang barusan, aku juga ngelihat kondisi yang sama di beberapa rumah.”
Selagi menunggu air mendidih, aku putuskan untuk memperpanjang obrolan ini. Lagipula gadis itu tampaknya tidak mau pergi, malah duduk di kursi meja makan sambil memperhatikan setiap tahapan proses pembuatan kopi seolah sedang mempelajari.
“Menurutmu, apa ini ada hubungannya dengan Pak Jawi?” tanyaku.
Gadis bercadar itu menggigit jari telunjuknya, menampakkan lekukan bibir yang tertutup kain merah.
“Pak Ahsan sudah meninggal.”
“Kalau gitu, gimana sama anak-anaknya?”
“Pak Ahsan sudah meninggal.”
“Kalau gitu, gimana sama anak-anaknya?”
Rupanya ia menunjukkan sikap yang sama seperti kakek dan Mbah Sopet. Aku tidak keberatan kalau diabaikan oleh orang tua, tapi diremehkan gadis yang lebih muda dariku seolah aku belum cukup dewasa untuk terlibat, membuatku sebal.
“Tadi anak-anak itu datang ke sini. Kemarin juga, kemarinnya lagi juga. Aku juga ngelihat mereka di pinggir jalan, aku bisa ceritakan yang lebih gila lagi tentang mereka kalau kamu mau.”
“Mereka hilang,” jawab gadis itu.
“Hilang?”
“Ya, beberapa warga masih berusaha mencarinya, tapi sepertinya mereka sudah nggak ada di desa.”
“Nggak ada di desa? Aku lihat dengan mata kepala sendiri, mereka—”
“Hilang?”
“Ya, beberapa warga masih berusaha mencarinya, tapi sepertinya mereka sudah nggak ada di desa.”
“Nggak ada di desa? Aku lihat dengan mata kepala sendiri, mereka—”
“—yang hilang cuma keenam anak cacat itu,” sela si gadis bercadar.
“Terus?” tanyaku sambil melongo, heran.
“Ada satu yang masih bertahan di sini, dan sepertinya nggak mau pergi.”
“Siapa?”
Gadis itu berdiri, mendekatiku, lalu membisikkan sesuatu.
“Terus?” tanyaku sambil melongo, heran.
“Ada satu yang masih bertahan di sini, dan sepertinya nggak mau pergi.”
“Siapa?”
Gadis itu berdiri, mendekatiku, lalu membisikkan sesuatu.
ANAK KETUJUH
CHAPTER 23
Pembahasan tentang Pak Jawi aku bawa ke ruang tamu, melibatkan kakek dan Mbah Sopet, dan tentu saja si gadis bercadar. Di luar dugaan, kali ini kakek bersikap lebih terbuka.
Pembahasan tentang Pak Jawi aku bawa ke ruang tamu, melibatkan kakek dan Mbah Sopet, dan tentu saja si gadis bercadar. Di luar dugaan, kali ini kakek bersikap lebih terbuka.
Mulai dari mengakui bahwa Pak Jawi memang punya anak, serta mempercayai segala ceritaku tentang kunjungan keenam anak itu ke rumah ini. Mbah Sopet juga tidak lagi menampik dugaan bahwa yang dialami Sugik bukanlah kecelakaan biasa, melainkan ada campur tangan gaib di sana.
Obrolan kami mulai mengendur ketika membahas hilangnya keenam anak itu. Tidak lagi lancar dan bersahutan, semua sibuk berpikir dan bertanya, sementara tidak satu pun dari kami yang punya jawabannya.
Kesaksianku yang pernah bertemu dengan mereka pasca kebakaran sepertinya tidak cukup membantu, karena langsung dipatahkan oleh teori munculnya anak ketujuh.
“Anak ketujuh ini yang mana? Setahu saya, mereka cuma berenam. Si Mencong, si Gendut, si Buntung, si Pincang, si Jangkung, dan si Juling.”
“Kamu yang menamai mereka?” tanya kakek.
“Nggak, sih. Cuma manggil berdasarkan ciri-cirinya.”
“Kamu yang menamai mereka?” tanya kakek.
“Nggak, sih. Cuma manggil berdasarkan ciri-cirinya.”
Gadis bercadar yang dari tadi berdiri di samping Mbah Sopet—ya, untuk sebuah alasan yang entah apa, dia tidak mau duduk—akhirnya pindah ke sampingku karena Mbah Sopet mulai menyalakan rokok.
“Kamu bilang kalau anak-anak itu yang menyerang Pak Muhadi dan kawan-kawannya, apa waktu itu mereka cuma berenam?” tanya Mbah Sopet. Asap rokok menembak-nembak dari mulutnya.
“Ya,” jawabku.
“Anak ketujuh itu tidak mungkin ikutan, setidaknya tidak secara langsung,” ujar kakek.
“Maksudnya?” tanyaku.
“Soalnya, bisa jadi dia bukan manusia.”
“Anak ketujuh itu tidak mungkin ikutan, setidaknya tidak secara langsung,” ujar kakek.
“Maksudnya?” tanyaku.
“Soalnya, bisa jadi dia bukan manusia.”
Kali ini si gadis bercadar yang menjawab.
“Bukan manusia?” gumamku, tak percaya.
“Bukan manusia?” gumamku, tak percaya.
Tidak ada yang menjawab pertanyaan terakhirku. Akhirnya kucari jawabannya sendiri berdasarkan apa yang aku lihat, dan aku alami selama ini. Jika memang ada makhluk gaib yang tinggal di rumah itu, atau secara sengaja dipelihara oleh Pak Jawi,--
--maka hal itu membuat beberapa kejanggalan terasa masuk akal. Lonceng sapi misterius, lembu hitam, lalu satu lagi yang akhirnya muncul di ingatanku, yakni sosok hitam yang beberapa kali kulihat bersama keenam anak itu.
Sosok bertubuh pendek seperti anak-anak yang muncul di tempat menjemur pakaian, dan berdiri di teras rumah Pak Jawi saat keenam anak itu mengamuk. Mungkinkah dia yang dimaksud dengan anak ketujuh?
“Saya pulang dulu.”
Mbah Sopet pamit sambil menguap berkali-kali. Kakek juga sepertinya sudah lelah sekali. Diskusi di ruang tamu pun bubar dengan tetap menyisakan banyak pertanyaan.
“Maulida, kamu perlu diantar pulang?” tanya kakek pada gadis bercadar.
Mbah Sopet pamit sambil menguap berkali-kali. Kakek juga sepertinya sudah lelah sekali. Diskusi di ruang tamu pun bubar dengan tetap menyisakan banyak pertanyaan.
“Maulida, kamu perlu diantar pulang?” tanya kakek pada gadis bercadar.
Oh, namanya Maulida, gumamku.
“Nggak usah, aku bawa sepeda sendiri,” ucap Maulida.
“Nggak usah, aku bawa sepeda sendiri,” ucap Maulida.
Dia pun pamit, kakek juga beranjak pergi ke kamar, tinggallah aku sendirian di ruang tamu memandangi tiga cangkir kopi yang sama sekali tidak mereka sentuh, merenung memikirkan liburanku yang tidak seru.
Desa ini sedang tidak tenang, dan tanpa sadar aku terseret masuk dalam konflik mereka. Sejujurnya, aku mulai menyesal. Jika tahu akan seperti ini, aku pasti memilih liburan di pesantren saja.
Selepas sarapan, kakek minta diolesin obat dari Pak Jawi. Aku mulai terbiasa dengan baunya yang menyengat, jadi tidak lagi ada drama mual yang membuat kakek sebal.
Hebatnya, sebagian luka di punggung kakek sudah mulai mengering. Hampir tidak kulihat ada nanah, pinggiran lukanya juga tidak lagi merah, kakek juga tidak meringis perih. Obat dari Pak Jawi benar-benar bekerja dengan baik.
Berkali-kali kakek menguap. Sepertinya kantuknya belum tuntas. Kakek selalu pergi malam, pulang pagi, kemudian sibuk sampai siang, kadang tembus ke sore.
Aku tidak tahu urusan apa yang membuat kakek serasa lebih sibuk dari kepala desa, tapi kurasa tidak ada salahnya bertanya, terlebih saat ini kakek cenderung lebih terbuka.
“Kek, menurut kakek, kebakaran di rumah Pak Jawi apa ada hubungannya sama Pak Muhadi?”
“Gimana?” tanya kakek.
“Maksudku, gimana kalau ternyata Pak Muhadi dendam, terus nyuruh anak buahnya buat bakar rumah Pak Jawi.”
“Gimana?” tanya kakek.
“Maksudku, gimana kalau ternyata Pak Muhadi dendam, terus nyuruh anak buahnya buat bakar rumah Pak Jawi.”
“Jangan berprasangka buruk!”
“Lah, aku kan nanya, kali aja kakek tahu, soalnya kakek kayak yang sibuk banget ngurusin kasus itu.”
“Lah, aku kan nanya, kali aja kakek tahu, soalnya kakek kayak yang sibuk banget ngurusin kasus itu.”
Kakek memberi isyarat cukup. Aku pun berhenti mengoleskan obat. Kututup kembali botol tempat obat dari Pak Jawi, lalu mencuci tangan di keran air.
“Pelaku pembakaran rumah Pak Ahsan itu bukan urusan kakek,” jawab kakek.
“Terus?” tanyaku.
“Pelaku pembakaran rumah Pak Ahsan itu bukan urusan kakek,” jawab kakek.
“Terus?” tanyaku.
Kami duduk berdua di halaman belakang, menunggu obat di punggung kakek kering, sekaligus menunggu telepon berdering. Aku mau mengembalikan motor Erik, tapi terlebih dahulu harus memastikan Erik ada di rumah agar bisa mengantar aku pulang.
“Ya, tindakan kriminal seperti itu sudah jadi tugas polisi, tugas kakek cuma mengurusi hal-hal yang nggak bisa polisi sentuh.”
“Maksudnya?”
“Anak ketujuh,” sahut kakek singkat, tapi cukup membuatku mengerti maksudnya.
“Tentang anak misterius itu, sepertinya aku pernah melihatnya.”
“Loh, di mana?” tanya kakek.
“Anak ketujuh,” sahut kakek singkat, tapi cukup membuatku mengerti maksudnya.
“Tentang anak misterius itu, sepertinya aku pernah melihatnya.”
“Loh, di mana?” tanya kakek.
Kuceritakan dua kejadian di mana aku melihat sosok hitam bermata merah itu. Satu di rumah ini, satu lagi di rumah Pak Jawi saat penyerangan pada Pak Muhadi terjadi. Aneh, aku merasa bersemangat menceritakannya.
Mungkin karena ini pertama kalinya kakek mendengarkan dengan serius. Kakek juga merespon ceritaku dengan beberapa pertanyaan. Aku merasa kakek tidak lagi menganggapku anak kecil, dan memperhitungkan pendapatku layaknya orang yang sudah setara, sudah dewasa.
“Ya, itu dia,” sahut kakek.
“Jadi benar, anak yang satu itu bukan manusia?”
“Kalau kamu tanya sudut pandang kakek, iya! Bisa jadi anak satu itu berasal dari bangsa jin dan sejenisnya, tapi kalau dari sudut pandang warga, semua anak Pak Jawi bukanlah manusia.”
“Semuanya?”
“Jadi benar, anak yang satu itu bukan manusia?”
“Kalau kamu tanya sudut pandang kakek, iya! Bisa jadi anak satu itu berasal dari bangsa jin dan sejenisnya, tapi kalau dari sudut pandang warga, semua anak Pak Jawi bukanlah manusia.”
“Semuanya?”
Pertanyaanku yang bertubi-tubi telah memaksa kakek untuk bercerita panjang dan lebar tentang asal-usul Pak Jawi, setidaknya selama ia berada di desa ini.
“Pak Ahsan sudah pindah ke sini sejak enam atau tujuh tahun yang lalu—kakek lupa pastinya—yang jelas waktu itu kamu masih SD. Dia seorang perantau dari luar pulau. Alasannya pergi ke Jawa, terutama Sumbergede juga masih misterius.
Nama Pak Ahsan mulai dikenal warga karena kepiawaiannya dalam menyembuhkan penyakit. Dia seorang tabib, sekaligus dukun pijat untuk anak kecil. Banyak warga Sumbergede yang jadi pasiennya.”
Aku manggut-manggut mendengarkan. Tidak tahu kenapa riwayat hidup Pak Jawi terdengar cukup menarik, padahal aku selalu mengantuk saat guru sejarah menceritakan riwayat hidup salah seorang presiden.
“Beberapa tahun lalu, ada sebuah tragedi besar di kecamatan Banyusirih. Sumbergede jadi salah satu desa yang terdampak tragedi itu.”
“Tragedi?”
“Masih ingat kasus munculnya orang-orang misterius, serta penemuan mayat-mayat tanpa identitas di seantero Banyusirih yang sempat geger waktu itu?”
“Oh, iya!” jawabku.
“Masih ingat kasus munculnya orang-orang misterius, serta penemuan mayat-mayat tanpa identitas di seantero Banyusirih yang sempat geger waktu itu?”
“Oh, iya!” jawabku.
“Peristiwa itu oleh warga disebut Polong Mayit. Dari saking banyaknya yang harus mereka evakuasi, hingga terasa sedang memanen mayat. Bersamaan dengan tragedi itu,--
--warga Banyusirih terutama Sumbergede dilanda wabah penyakit—waktu itu kamu sudah berangkat ke pesantren, jadi mungkin nggak banyak tahu—nah, sakit di punggung kakek adalah sisa-sisa dari wabah itu.”
“Aku dengar ceritanya dari Abah. Itu juga yang jadi alasan aku tidak boleh pulang saat libur ramadan,” ucapku.
“Pak Ahsan banyak berjasa dalam menangani wabah itu. Untuk warga desa yang cenderung enggan pergi ke rumah sakit, Pak Ahsan adalah penyelamat mereka. Dia dikagumi, dielu-elukan, disanjung-sanjung, karena setiap pasien yang datang berkunjung padanya sudah pasti sembuh.”
“Itu karena pasien Pak Jawi nggak ada yang meminum obatnya,” sindirku.
“Mau dilanjut tidak?” Kakek meradang.
“Iya, iya, maaf.”
“Mau dilanjut tidak?” Kakek meradang.
“Iya, iya, maaf.”
“Tragedi Polong Mayit rupanya tidak hanya meninggalkan wabah, tapi juga banyak tragedi. Di tahun yang sama, kasus santet kembali naik, padahal selama ini Sumbergede jauh dari hal-hal seperti itu.--
--Belum lagi pencurian dan perampokan. Sumbergede yang dikenal tentram di bawah lindungan pengasuh pesantren Sokogede, akhirnya jadi rusuh selama tiga tahun terakhir.”
Cerita kakek mulai masuk ke tahap yang menegangkan. Aku jadi tidak bisa lagi mendengarkan sambil duduk santai.
“Di saat yang bersamaan, banyak laporan warga yang sering melihat anak kecil bermain di halaman rumah Pak Ahsan saat malam. Hal ini tentu terasa janggal karena mereka tahu Pak Ahsan tinggal sendiri, tanpa istri, dan dengan kondisinya yang sekarang,--
--sepertinya mustahil untuk punya anak lagi. Desas-desus tentang Pak Ahsan mulai menyebar ke seluruh desa. Mulanya dia dicurigai menculik anak, tapi selama ini tidak satu pun ditemukan kasus penculikan anak di Kecamatan Banyusirih.”
“Jadi orang-orang sudah tahu tentang anak-anak itu?” tanyaku, sedikit kesal.
“Tidak semua. Sebagian saja.”
“Terus kenapa kakek bersikap seolah-olah keenam anak itu nggak ada? Waktu aku belanja ke warung Cak Imam, orang-orang di warung juga seperti menghindari anak Pak Jawi?”
“Tidak semua. Sebagian saja.”
“Terus kenapa kakek bersikap seolah-olah keenam anak itu nggak ada? Waktu aku belanja ke warung Cak Imam, orang-orang di warung juga seperti menghindari anak Pak Jawi?”
“Karena warga pernah memberi kesempatan untuk keenam anak itu, tapi berujung penyesalan.”
“Penyesalan?”
“Penyesalan?”
“Didorong rasa hormat serta balas budi pada Pak Ahsan, warga mencoba bersikap baik pada keenam anak itu, terlepas asal-usulnya yang misterius. Warga memberi makan, minum, pakaian, kadang uang, tapi ternyata hal itu justru jadi bumerang buat mereka.--
--Entah karena tidak tahu caranya berterima kasih, atau memang karena cacat mentalnya, anak-anak itu mengunjungi setiap warga yang pernah membantu mereka. Malam hari. Masuk rumah tanpa permisi. Membangunkan warga untuk mengajak bermain.”
Aku tercengang. Hal pertama yang aku pikirkan setelah mendengar cerita kakek adalah, kebaikan apa yang sudah aku lakukan pada keenam anak itu sampai-sampai mereka tidak pernah berhenti mengunjungiku? Lalu aku teringat kejadian di depan warung Kak Imam.
“Aku... aku pernah membantu si Gendut memungut beras yang dilemparkan pemilik warung padanya. Apa mungkin karena itu mereka sering datang ke sini kalau malam. Mereka juga pernah ninggalin ubi rebus di teras.”
“Bisa jadi,” jawab kakek.
“Bisa jadi,” jawab kakek.
“Kakek sudah tahu semua ini, tapi kenapa nggak cerita dari kemarin? Malah pura-pura nggak ngerti,” protesku.
Kakek terbahak-bahak.
Kakek terbahak-bahak.
“Soalnya kamu tidak akan lama di sini. Abis itu balik ke pondok. Kakek tidak mau kamu terlibat lebih jauh dalam masalah ini.--
--Lagian, sejauh ini keenam anak itu tidak pernah mencuri apalagi melukai orang, tapi setelah kasus Pak Muhadi, dan anak-anak desa yang semalam menangis ketakutan, kakek pikir masalah ini mulai berbahaya buat kamu.”
“Dari awal sudah bahaya, kek!” sahutku, kesal.
“Makanya, besok kamu balik aja ke pondok! Kakek sudah bicara sama abahmu, dia sudah setuju.”
“Makanya, besok kamu balik aja ke pondok! Kakek sudah bicara sama abahmu, dia sudah setuju.”
Sejujurnya, aku mulai merasa liburan ini tidak lagi sehat. Namun, entah kenapa aku merasa berat kembali ke pesantren sekarang.
Di satu sisi, aku tidak mungkin meninggalkan kakek yang sedang sakit sendirian, di sisi lain—dan aku sendiri heran kenapa berpikiran seperti ini—aku merasa sayang jika tidak mengikuti cerita ini sampai tuntas.
Siapa yang membakar rumah Pak Jawi, di mana keenam anak itu bersembunyi, serta kemunculan anak ketujuh yang masih jadi misteri. Rasanya aku tidak akan tenang kalau tidak mengungkap semuanya.
Bersambung kamis depan, yak.
Terima kasih udah baca sampai sini, kita udah di pertengahan cerita. Setelah ini, alur akan menukik tajam.
Untuk Chapter 24, 25, dan 26 akan tayang lebih dulu di Karya Karsa besok.
Mator sakalangkong.
Mator sakalangkong.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh