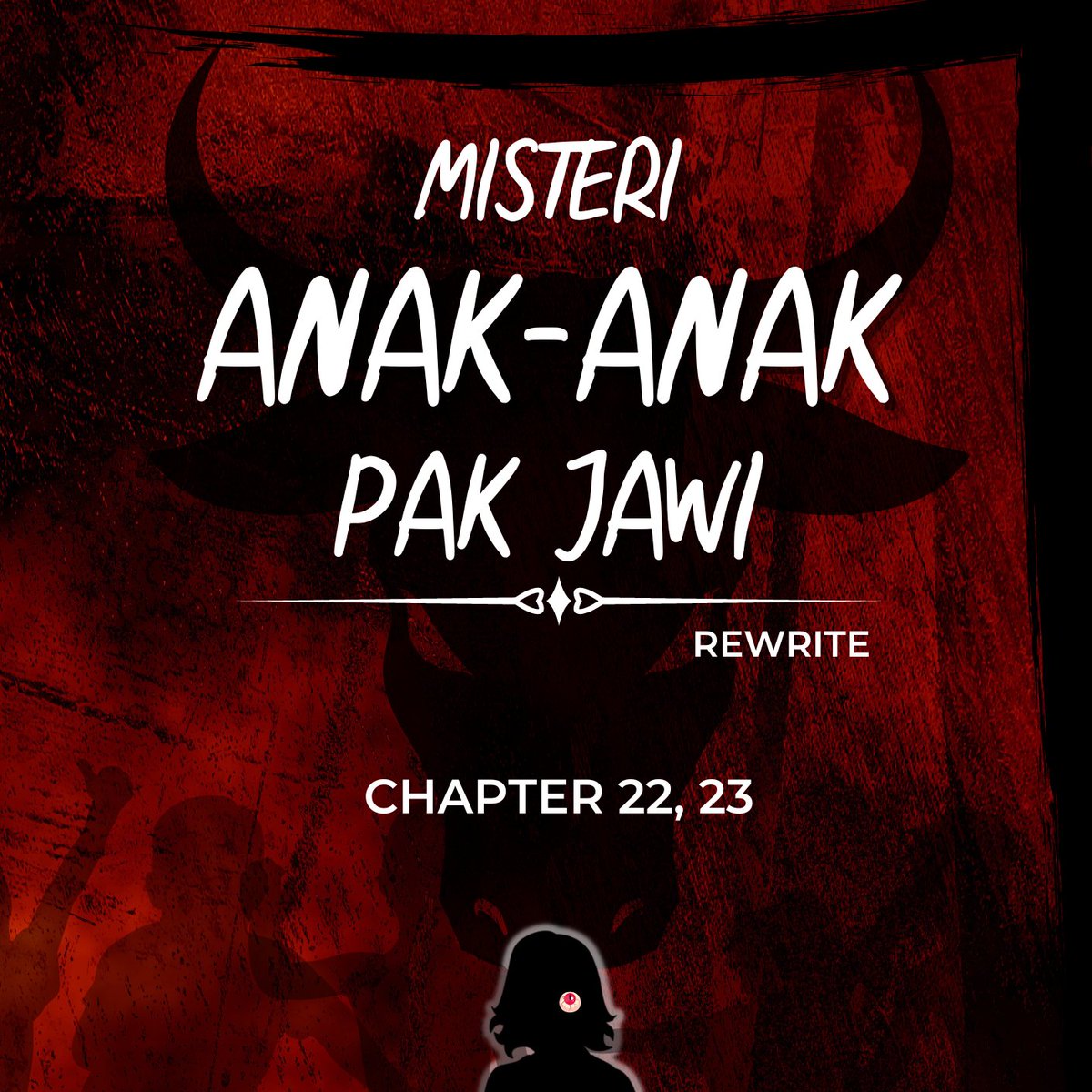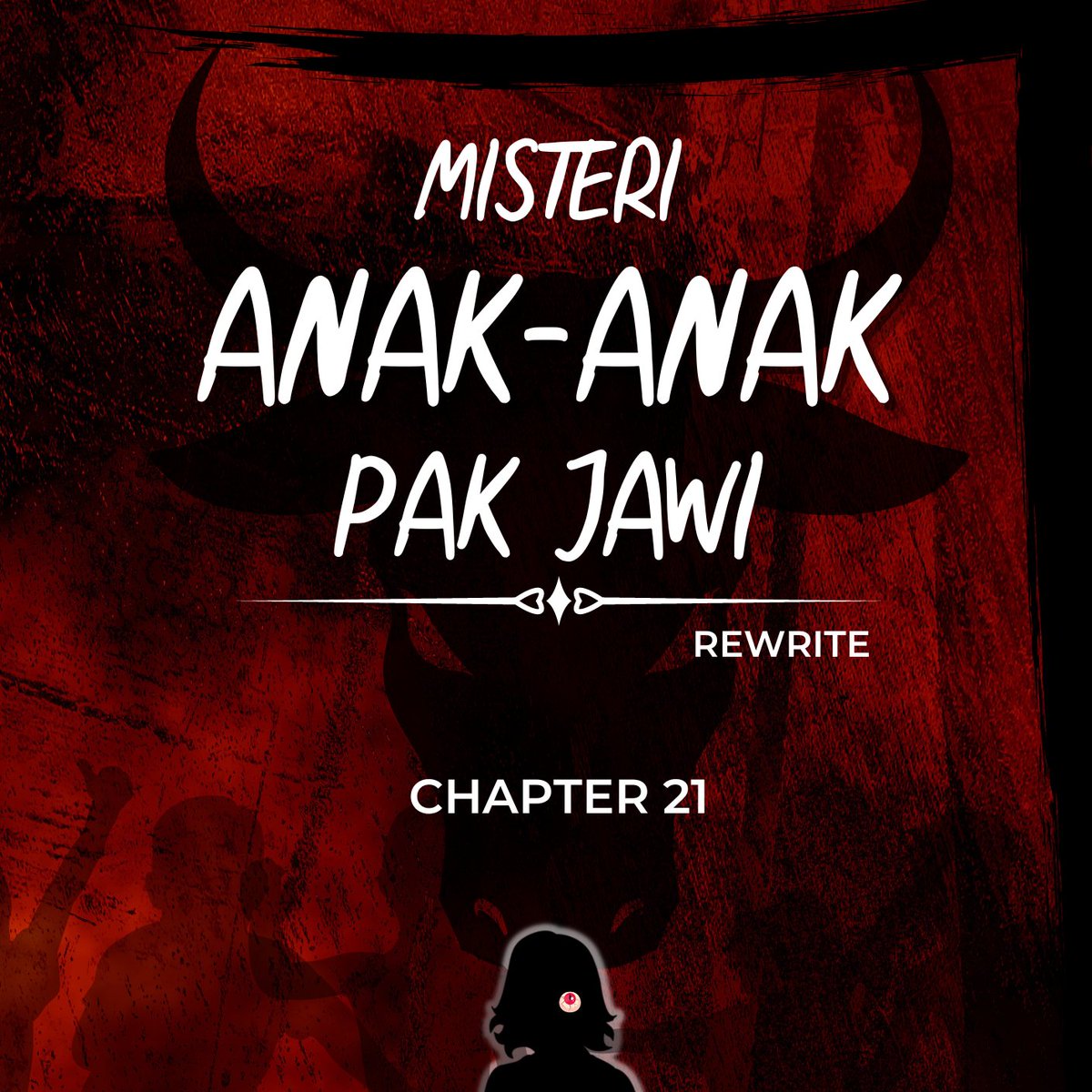MISTERI ANAK-ANAK PAK JAWI
CHAPTER 24, 25, 26
@bacahorror @IDN_Horor
#threadhorror #bacahorror #timurtrilogi
CHAPTER 24, 25, 26
@bacahorror @IDN_Horor
#threadhorror #bacahorror #timurtrilogi

Buat teman-teman yang belum baca, atau sudah baca tapi lupa ceritanya gara-gara saya lama nggak nongol, silakan cek pinned.
https://twitter.com/DanieloAhmad/status/1539969843646312449?s=20&t=1u0n21eaToCeLUpYjL8agg
CHAPTER 24
Sesuai dugaanku, rumah Pak Jawi pasti masih ramai. Hanya saja, bukan keramaian seperti ini yang aku bayangkan. Banyak anak kecil berlarian di halaman, ada yang asyik bermain ayunan dan memanjat pohon mangga,--
Sesuai dugaanku, rumah Pak Jawi pasti masih ramai. Hanya saja, bukan keramaian seperti ini yang aku bayangkan. Banyak anak kecil berlarian di halaman, ada yang asyik bermain ayunan dan memanjat pohon mangga,--
--ada juga yang mengais puing-puing kayu dan arang untuk dijadikan pedang-pedangan. Garis polisi sudah dibongkar, dan rumah nahas yang baru saja menghanguskan seorang pria tua, kini tak ubahnya taman bermain anak-anak.
Selain anak-anak, ada juga beberapa warga dan aparat. Memang tidak ada lagi yang berseragam, tapi pria tegap berjaket kulit hitam itu sudah pasti adalah polisi. Dia tampak sedang berdiskusi dengan tiga orang warga desa, dan salah satunya adalah Pak Edi.
Lagi-lagi Pak Edi. Mereka berada di pinggir sumur, di belakang rumah Pak Jawi yang kini terlihat jelas dari halaman karena rumah Pak Jawi telah hangus membumi.
Tidak seperti kelompok anak-anak yang seragam dalam permainan, para dewasa justru membentuk kubu-kubu yang satu sama lainnya seperti sedang membahas hal berbeda.
Bila di pinggir sumur ada Pak Edi dan polisi, kakek, Mbah Sopet, dan Kang Yudis justru berkumpul di kandang sapi milik Pak Jawi.
“Fatah,” sapa Mbah Sopet.
Aku mengangguk, “Mau jemput kakek,” ucapku.
Kakek belum merespons kehadiranku selain dengan gerakan tangan sebagai isyarat tunggu dulu. Tampaknya obrolan kakek dan Kang Yudis belum selesai.
Aku mengangguk, “Mau jemput kakek,” ucapku.
Kakek belum merespons kehadiranku selain dengan gerakan tangan sebagai isyarat tunggu dulu. Tampaknya obrolan kakek dan Kang Yudis belum selesai.
“Berarti ini sudah diputuskan kalau yang terbakar itu memang jenazah Pak Ahsan?” tanya kakek, dengan suara yang pelan.
“Menurut polisi, sih, begitu,” jawab Kang Yudis. “Tapi ada satu lagi yang saya dengar dari bisik-bisik mereka.”
“Menurut polisi, sih, begitu,” jawab Kang Yudis. “Tapi ada satu lagi yang saya dengar dari bisik-bisik mereka.”
Kang Yudis melirik kubu Pak Edi. Suaranya jadi lebih pelan seolah sedang berhati-hati.
“Apa?” tanya Mbah Sopet.
“Apa?” tanya Mbah Sopet.
“Katanya, mereka sudah menemukan keenam anak Pak Ahsan.”
“Mustahil!” sela Mbah Sopet, lantang, yang langsung membuat kakek dan Kang Yudis serempak berdesis.
“Mustahil!” sela Mbah Sopet, lantang, yang langsung membuat kakek dan Kang Yudis serempak berdesis.
“Kita nggak bisa ngeremehin polisi. Mereka punya semua sumberdaya yang mumpuni untuk mencari orang hilang, apalagi cuma anak kecil, enam lagi,” tutur Kang Yudis.
“Yang bikin aku heran bukan bisa atau tidaknya mereka menemukan anak-anak itu, tapi kenapa mereka repot-repot mencari mereka?”
“Saleh benar. Setahuku, polisi baru bergerak cepat kalau kasusnya besar, atau minimal uangnya banyak,” celetuk Mbah Sopet.
Di tengah-tengah diskusi, sebuah balok kayu melayang cepat melewatiku, Mbah Sopet, Kang Yudis, lalu mendarat tepat di pelipis Kakek. Balok itu jatuh ke tanah. Baru kulihat kalau ujungnya tajam, membuatku langsung mencemaskan kakek.
“Kek?”
Cemasku seolah sia-sia, karena kakek seperti tidak merasakan apa-apa. Tidak ada satu goresan pun di wajahnya. Ia masih santai bicara meski perhatian Kang Yudis dan Mbah Sopet sudah tidak lagi padanya.
Cemasku seolah sia-sia, karena kakek seperti tidak merasakan apa-apa. Tidak ada satu goresan pun di wajahnya. Ia masih santai bicara meski perhatian Kang Yudis dan Mbah Sopet sudah tidak lagi padanya.
“Cong, jangan main lempar-lemparan!” tegur Kang Yudis pada anak-anak yang tanpa sengaja melemparkan balok kayu itu hingga menghantam kakek.
Alih-alih minta maaf, kedua anak yang sedang bermain pedang-pedangan justru kabur lalu sembunyi di balik pohon mangga.
Alih-alih minta maaf, kedua anak yang sedang bermain pedang-pedangan justru kabur lalu sembunyi di balik pohon mangga.
“Sudah, biarkan saja,” ucap Mbah Sopet.
“Dibiarkan gimana, Kang? Kalau sampai kena mata, bisa cacat.”
“Dibiarkan gimana, Kang? Kalau sampai kena mata, bisa cacat.”
Kakek memungut kayu yang tergeletak di tanah, lalu membuangnya jauh melewati pagar rumah, seolah tidak merasakan apa-apa. Ia kemudian berdiri, memperbaiki kopiah, lalu mengajakku pulang.
“Kamu balik aja ke sana, jangan sering ngumpul sama kami, nanti kamu dijauhi,” nasihat kakek pada Kang Yudis.
Hari sudah mulai petang. Beberapa orangtua datang menjemput anaknya yang sedang bermain di rumah Pak Jawi. Ini sudah jamnya mereka mandi, lalu bersiap mengaji di musala.
Kecuali Kang Yudis yang kini bergabung dengan Pak Edi dan kawan-kawan, Aku, kakek, dan Mbah Sopet memutuskan untuk pulang.
Keenam ayunan di halaman rumah Pak Jawi kini punya kesan berbeda. Tidak lagi misterius seperti saat pertama aku melihatnya. Anak-anak bermain dengan riang. Mungkin sebagai pelampiasan karena selama ini orangtua mereka melarang pergi ke rumah Pak Jawi.
Beberapa anak kecil menyapa kami yang hendak pulang, ada juga yang mengajakku ikut bermain ayunan. Andai mereka mengajakku sepuluh tahun lebih awal,--
--aku tidak akan segan-segan melepas sandal dan ikut berebut ayunan. Benar kata Ustaz, anak kecil dibatasi orangtua, tapi orang dewasa dibatasi oleh kenyataan.
Saat sudah sampai di motor, kudengar suara berdebum dari arah sumur. Kami bertiga menoleh, mendapati Pak Edi dan warga lainnya telah berhasil membuka papan kayu penutup sumur.
Aku tidak tahu mana yang lebih cepat antara cahaya, atau suara, yang jelas, saat setelah telingaku mendengar debum barusan, hidungku dengan cepat menangkap bau yang sangat dahsyat.
Mulai terdengar suara mual di sana-sini. Mereka yang berada di pinggir sumur pun bergegas menjauh seraya menutup hidung. Luasnya halaman rumah Pak Jawi seolah tak jadi jarak yang berarti,--
--karena dari balik pagar pun, bau menyengat itu bisa kuendus dengan sempurna, turun dengan cepat ke lambung, bergejolak di perut, lalu mengantarkan reaksi mual yang kuat ke tenggorokan, hingga aku nyaris muntah.
Kakek menutup hidung dan mulutnya dengan serban, Mbah Sopet mengoleskan wangi-wangian ke lubang hidungnya. Mereka yang semula sepakat untuk pulang, kini justru bergegas mendekati sumur.
Rasanya ingin segera pergi dari sini, karena bau busuk ini mulai membuatku pusing. Namun, melihat anak-anak kecil yang sedari tadi asyik bermain kini mulai jongkok sambil muntah-muntah,--
--aku akan merasa bersalah kalau jadi satu-satunya orang dewasa yang kabur. Para orangtua yang datang juga tidak bisa berbuat banyak, karena mereka pun berusaha keras menahan mual.
Kudekati seorang anak perempuan yang yang sedang muntah sambil berpegangan pada pohon mangga. Kulihat wajahnya mulai pucat, tangannya pun gemetar. Dia salah satu anak yang tidak dijemput oleh orangtuanya, dan sedang bingung ke mana harus mengadukan rasa sakitnya.
“Dek, masih kuat jalan?” tanyaku.
Gadis kecil itu mengangguk, lemah. Kupapah ia keluar dari halaman rumah, lalu kutitipkan pada salah seorang ibu-ibu yang datang menjemput anaknya.
Gadis kecil itu mengangguk, lemah. Kupapah ia keluar dari halaman rumah, lalu kutitipkan pada salah seorang ibu-ibu yang datang menjemput anaknya.
“Bu, adek ini dibawa juga!”
Ibu itu menggangguk, ia bergegas menggandeng si gadis kecil seraya menggendong anaknya sendiri yang sudah lemas.
Ibu itu menggangguk, ia bergegas menggandeng si gadis kecil seraya menggendong anaknya sendiri yang sudah lemas.
Usai membantu anak-anak pergi dari rumah Pak Jawi, aku menyusul kakek dan Mbah sopet meski harus menghemat napas. Jangankan anak kecil, warga yang tadi semangat menggeser penutup sumur,--
--kini malah selonjoran di tanah sambil muntah-muntah, dan Pak Edi adalah yang paling parah. Dia bukan hanya selonjoran, tapi sudah terlentang di tanah dengan wajah pucat dan napas berat.
“Ini, pakai ini.”
Mbah Sopet menyodorkan kain miliknya yang sudah ia olesi dengan minyak wangi. Meski sempat risih, tapi kain ini sangat berguna. Setidaknya bisa menyaring bau busuk hingga lima puluh persen.
Mbah Sopet menyodorkan kain miliknya yang sudah ia olesi dengan minyak wangi. Meski sempat risih, tapi kain ini sangat berguna. Setidaknya bisa menyaring bau busuk hingga lima puluh persen.
Karena penasaran dengan asal bau menyengat ini, aku pun mendekat ke bibir sumur, melongok ke dasar, dan menemukan bahwa sumur di rumah Pak Jawi telah kering.
Sumur mati. Tidak ada air, hanya tumpukan benda dibungkus plastik gelap yang kami pun masih menebak-nebak isinya. Belatung berpesta, lalat-lalat menari, dan kecoa menjalar di dinding sumur.
“Mungkin bangkai hewan, kalau sampah daun-daunan tidak mungkin sampai ada belatungnya.” tebak Kang Yudis. Kedua lubang hidungnya sudah disumbat tisu.
“Terus ini mau diapakan?” tanya salah seorang warga.
“Terus ini mau diapakan?” tanya salah seorang warga.
“Dibakar saja!” usul seorang pria berjaket kulit hitam yang kemungkinan besar seorang polisi. Sepertinya cuma dia saja yang betah dengan bau menyengat ini.
Polisi itu tidak mengenakan penutup hidung, dan masih bisa bernapas dengan normal meski sekali-kali menutup mulut dengan tangan dan meludah.
“Kita tidak tahu ukuran sumur ini. Kalau dalamnya sama seperti sumur di rumah saya, artinya sampah ini sudah sangat banyak. Mengeluarkannya semua bisa butuh waktu yang lama, dan bisa jadi baunya malah makin kesebar,” tutur kakek.
“Saleh benar. Ini saja sampahnya sudah hampir sampai ke permukaan,” Mbah Sopet membenarkan.
“Kalau dibakar di sumurnya langsung gimana?” usul Pak Edi.
“Kalau dibakar di sumurnya langsung gimana?” usul Pak Edi.
Pak RT itu sudah seperti mayat yang bangkit dari kematian, wajahnya pucat, berdirinya tidak lagi tegak. Melihatnya seperti itu aku merasa kasihan.
Warga mengangguk setuju, kecuali kakek dan Mbah Sopet. Sayangnya, mereka berdua tidak punya ide tandingan, dan memutuskan untuk ikut arus.
Suara orang muntah makin nyaring terdengar. Kulihat masih ada beberapa anak kecil bersandar di pohon mangga. Para orangtua yang datang hanya peduli pada anak mereka sendiri, tidak sedikit pun berpikir untuk membawa semua anak-anak ini pergi.
“Mungkin sebelum dibakar, kita harus tolong mereka dulu,” gerutu Pak Saleh. “Dani, kamu bawa motor, kan?"
“I-iya,” jawabku, kikuk.
“Bagus, bantu yang lain bawa anak-anak pulang.”
“I-iya,” jawabku, kikuk.
“Bagus, bantu yang lain bawa anak-anak pulang.”
“Sebaiknya dibawa ke Puskesmas saja dulu,” usul Kang Yudis.
“Kalau gitu, saya ikut," sambung Pak Edi.
“Kalau gitu, saya ikut," sambung Pak Edi.
Satu jam sebelum magrib. Tak ada lagi tanda-tanda aktivitas di Puskesmas Sumbergede. Delapan orang anak yang dibawa ke sini terpaksa tidur di teras beralas kain dan selimut.
Orangtua mereka sempat panik anaknya tidak segera dapat pertolongan, karena setelah berada cukup jauh dari rumah Pak Jawi pun, mereka masih saja muntah-muntah.
Kang Yudis yang datang bersama Pak Edi langsung mengunjungi rumah kecil di samping Puskesmas, masih di satu halaman, hanya dipisahkan oleh garasi tempat sebuah ambulans terparkir.
Setelah Kang Yudis mengetuk pintu rumah itu dengan gawat, seorang perempuan berkacamata yang masih mengenakan mukenah keluar.
Kulihat Kang Yudis menunjuk ke arah teras Puskesmas, membuat perempuan itu terkejut, lalu kembali menutup pintu. Tak berselang lama, perempuan itu keluar membawa kotak bergambar palang merah.
Baru kutahu dia adalah seorang dokter setelah Kang Yudis menyapanya dengan senyum yang sangat lebar dan mata yang berbinar. Namanya Dokter Eva. Ya, dokter itu memang cantik, aku yakin bukan hanya Kang Yudis yang berpikir demikian, tapi jelas hanya dia yang tampak paling mengagumi
“Adik-adik ini habis makan apa?” tanya dokter Eva.
Pak Edi menjelaskan kronologi kejadian. Kang Yudis mengambil alih penjelasan Pak Edi yang baru memasuki pembukaan. Sepertinya, Kang Yudis tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas untuk mengobrol dengan dokter Eva.
Pak Edi menjelaskan kronologi kejadian. Kang Yudis mengambil alih penjelasan Pak Edi yang baru memasuki pembukaan. Sepertinya, Kang Yudis tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas untuk mengobrol dengan dokter Eva.
Setelah cukup mengamati dari atas motor, aku mulai memikirkan apa yang sekarang harus kulakukan. Pulang, karena tugasku ke sini cuma mengantar, atau tetap tinggal karena tidak ingin dianggap acuh dan kurang peduli pada anak-anak.
Saat sibuk menimbang keputusan, seorang gadis keluar dari rumah Dokter Eva. Ia mengenakan kerudung putih, dan langsung berbaur di keramaian, membantu Dokter Eva menangani pasien. Tidak ada yang aneh dari gadis itu, kecuali aku merasa pernah bertemu dengannya di suatu tempat.
“Oh, ya, itu kan gadis yang kemarin beli gorengan,” gumamku.
Satu hal yang mencolok dari gadis itu adalah, semua orang menyapa dengan hormat, bahkan ibu-ibu bersalaman dengan mencium tangan, meski gadis itu segera menarik tangannya karena merasa tak pantas.
Satu hal yang mencolok dari gadis itu adalah, semua orang menyapa dengan hormat, bahkan ibu-ibu bersalaman dengan mencium tangan, meski gadis itu segera menarik tangannya karena merasa tak pantas.
“Dani, tolong ambilkan tempat sampah di sana!” pinta Pak Edi.
Aku menurut, turun dari motor, mengambil tempat sampah besar yang dimaksud, lalu meletakkannya di samping Pak Edi.
Aku menurut, turun dari motor, mengambil tempat sampah besar yang dimaksud, lalu meletakkannya di samping Pak Edi.
Segera tempat sampah itu terisi oleh kantong plastik bekas muntahan anak-anak yang sekarang hanya berupa cairan bening. Isi perut mereka nyaris terkuras, tak heran jika anak-anak ini terkulai lemas.
Gadis itu melihatku sekilas, lalu membuang muka. Entah karena dia mengingatku, atau dia lupa dan menganggapku hanya tukang ambil tempat sampah yang tidak punya kontribusi berarti dalam musibah ini.
“Sumur tua memang jangan sembarangan dibuka, Pak. Apalagi seperti yang Mas Yudis bilang, isinya kotoran” Dokter Eva menasihati, “Bisa jadi di dalamnnya ada gas beracun.
Sama kasusnya seperti petugas—maaf—kebersihan kamar mandi pesantren yang meninggal karena masuk ke dalam lubang kakus sedalam dua meter, dan secara langsung menghirup gasnya.”
Pak Edi manggut-manggut, kemudian seolah menemukan alasan tandingan yang membuatnya tidak terlalu disalahkan, ia pun mendebat.
“Apa boleh buat, Dok. Itu juga demi kepentingan penyelidikan, toh. Tadi juga nggak sendirian, ada petugas dari kepolisian yang mengawasi.”
“Apa boleh buat, Dok. Itu juga demi kepentingan penyelidikan, toh. Tadi juga nggak sendirian, ada petugas dari kepolisian yang mengawasi.”
“Dan ke mana petugas itu sekarang?”
“Pu-pulang,” ucap Pak Edi.
“Ya, benar, akhirnya anak-anak jadi korban, dan para orangtua ini kerepotan.”
“Pu-pulang,” ucap Pak Edi.
“Ya, benar, akhirnya anak-anak jadi korban, dan para orangtua ini kerepotan.”
Pak Edi cuma garuk-garuk kepala. Dengan pengetahuannya yang terbatas, mustahil dia menang berdebat dengan dokter, apalagi kalau topiknya tentang kesehatan. Pak Edi sendiri saja hampir pingsan di samping sumur tadi.
Hari mulai benar-benar gelap. Puskesmas yang sudah tutup, terpaksa dibuka meski nyaris tidak ada petugas di sana, kecuali dokter Eva, dan seorang sopir ambulans yang memang tinggal di dekat Puskesmas.
Dengan bantuan Pak Edi serta para orangtua, anak-anak yang kondisinya mulai membaik akhirnya dibiarkan istirahat di dalam.
Tentu saja aku ikut membantu, dan tentu saja Kang Yudis yang paling banyak aksi. Dia sangat semangat menggendong anak-anak ke tempat tidur pasien. Tampak sekali ingin dipuji atau dikagumi seseorang.
Saat aku merasa sudah waktunya pulang, dan sudah siap menyalakan mesin motor, Pak Edi duduk di jok belakang tanpa permisi, lalu minta diantar pulang tanpa sungkan.
“Saya ke sini ikut Yudis, tapi dia tidak mau pulang. Masih betah di Puskesmas,” ujarnya beralasan.
Meski sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak, serta tidak rugi juga karena rumah kami satu arah ke selatan, tetap saja aku merasa tidak nyaman membonceng orang ini.
Meski sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak, serta tidak rugi juga karena rumah kami satu arah ke selatan, tetap saja aku merasa tidak nyaman membonceng orang ini.
Kubalut ketidakihklasanku dengan senyuman terpaksa, dan berharap selama perjalanan Pak Edi tidak mengajakku bicara.
Saat melewati Gang Kadal, selawat tarhim sudah mulai terdengar di masjid. Musala-musala di pinggir jalan mulai benderang, dan anak-anak kecil sudah berlarian sambil menenteng sejadah dan sarung. Seperti biasa, Gang Kadal tetaplah sebuah gang sepi.
Serupa terowongan gelap yang tak tersentuh cahaya. Gilanya, meski hanya sekelebat, aku masih bisa mencium bau busuk itu. Aku yakin kakek dan yang lainnya sudah pulang. Hanya berharap mereka tidak lupa menutup kembali sumur pembawa sial itu.
Rumah Pak Edi berada di ujung Gang Seroja. Satu gang sebelum Gang Kadal. Sesuai dugaanku, bau dari sumur itu juga tercium sampai ke rumahnya. Tidak sampai menyengat, tapi cukup mengganggu tiap embusan napas.
“Masuk dulu, sudah magrib. Salat di sini saja,” ujar Pak Edi, ramah.
“Masuk dulu, sudah magrib. Salat di sini saja,” ujar Pak Edi, ramah.
“Nggak usah, Pak. Saya mau langsung pulang, soalnya—”
“—Masuk dulu, ada yang mau saya omongin sama kamu,” katanya, tegas.
“—Masuk dulu, ada yang mau saya omongin sama kamu,” katanya, tegas.
CHAPTER 26
Terpaksa. Akhirnya aku mampir juga. Rumah Pak Edi tidak terlalu besar. Ada musala di halaman rumahnya yang luas, dan di halaman itu berjejer dua rumah lainnya yang menurut Pak Edi adalah milik saudara. Usai salat di musala, Pak Edi mengajakku masuk.
Terpaksa. Akhirnya aku mampir juga. Rumah Pak Edi tidak terlalu besar. Ada musala di halaman rumahnya yang luas, dan di halaman itu berjejer dua rumah lainnya yang menurut Pak Edi adalah milik saudara. Usai salat di musala, Pak Edi mengajakku masuk.
Kami duduk di ruang tamu, menikmati kopi dan kue kering yang sama sekali tidak kusentuh. Saat Pak Edi pamit ke kamarnya sebentar, aku memperhatikan beberapa benda yang terpajang di ruang tamu.
Satu hal yang paling mencolok adalah, ruangan ini punya banyak sekali foto yang dipajang di atas lemari hias, digantung di dinding, dan semuanya merupakan potret dari orang yang sama, yakni seorang anak perempuan.
Usianya mungkin masih tujuh sampai sepuluh tahun. Aku bisa menebak karena di salah satu foto anak perempuan itu mengenakan seragam sekolah dasar,--
--dan kalau tidak salah menebak lagi, anak perempuan ini adalah orang yang sangat spesial bagi Pak Edi, karena ada sebuah lukisan besar di dinding yang didedikasikan khusus untuknya.
“Namanya Ratih, anak pertama saya,” ujar Pak Edi, seolah tahu aku sedang memperhatikan foto anaknya.
“Oh, nggak heran. Anak pertama selalu punya tempat spesial di hati orangtua, kadang namanya juga dijadikan tanda di piring, sendok dan garpu,” ucapku.
“Oh, nggak heran. Anak pertama selalu punya tempat spesial di hati orangtua, kadang namanya juga dijadikan tanda di piring, sendok dan garpu,” ucapku.
“Kamu juga pasti spesial buat Haji Karim. Kalau tidak salah, kamu anak satu-satunya, kan?”
“Iya, Pak. Dik Ratih sekarang sudah kelas berapa?”
“Ratih meninggal tiga tahun lalu, tepat di usianya yang kedelapan.”
“Iya, Pak. Dik Ratih sekarang sudah kelas berapa?”
“Ratih meninggal tiga tahun lalu, tepat di usianya yang kedelapan.”
Aku kehilangan nafsu mengobrol. Biasanya aku selalu menegur Erik kalau dia melontarkan pertanyaan konyol, sekarang malah aku yang menanyakan hal bodoh. Ramah tamah Pak Edi yang baru dimulai, seketika selesai karena aku telah mengingatkannya pada luka lama.
Tidak, tiga tahun bukan waktu yang lama. Luka itu pasti masih basah dan perih, dan tanpa sengaja aku mengoyaknya lagi. Duka orangtua yang kehilangan anaknya, tidak akan sembuh sampai mereka mati.
“Maaf, Pak, saya nggak tahu,” ucapku.
“Ah, tidak apa-apa.”
Niatnya tidak ingin menyentuh kopi, tapi terpaksa kuseruput juga sebagai upaya menghilangkan saling diam yang canggung antara aku dan Pak Edi.
“Ah, tidak apa-apa.”
Niatnya tidak ingin menyentuh kopi, tapi terpaksa kuseruput juga sebagai upaya menghilangkan saling diam yang canggung antara aku dan Pak Edi.
“Ratih sakit keras. Dia berhenti sekolah sejak kelas lima SD, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk pergi belajar, juga bermain,” tutur Pak Edi.
Mendengar intonasinya dalam menjeda kalimat, sepertinya cerita Pak Edi akan panjang. Kuletakkan kopi di meja, lalu memperbaiki posisi duduk.
“Kami sudah berkali-kali membawa Ratih ke rumah sakit. Sudah berkali-kali juga Ratih dirawat inap. Setiap kali di rumah sakit, Ratih selalu menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Dokter juga bilang kalau Ratih cuma kecapekan, dan butuh istirahat. Awalnya, kami senang mendengar diagnosis itu, sampai akhirnya kami pulang, penyakit Ratih malah tambah parah.”
“Sakit apa ya, Pak?” tanyaku.
“Sakit apa ya, Pak?” tanyaku.
“Saya juga menanyakan hal yang sama, bahkan sampai sekarang tidak tahu jawabannya. Ratih tidak demam, tidak ada gangguan buang air besar, tapi anaknya pucat, lemas, dan gampang jatuh seolah tubuhnya hilang keseimbangan.--
--Anehnya setiap kali ke rumah sakit, dokter selalu ngasih kesimpulan yang sama, Ratih kecapean. Kurang makanan bergizi,--
--padahal kalau kamu tahu, kami rela cuma makan singkong rebus selama sebulan agar bisa membelikan Ratih makanan yang lezat. Sakit Ratih tambah parah sejak dia mulai muntah darah.”
“Muntah darah?”
“Ya, tapi tidak seperti orang mual pada umumnya, Ratih muntah seolah di tenggorokannya ada sesuatu yang menyangkut. Kadang seperti tersedak.--
“Ya, tapi tidak seperti orang mual pada umumnya, Ratih muntah seolah di tenggorokannya ada sesuatu yang menyangkut. Kadang seperti tersedak.--
--Kami bawa Ratih ke rumah sakit lagi, tapi sama seperti sebelumnya, sampai di rumah sakit, penyakit Ratih seolah lenyap, dan kami kembali dijejali dengan omong kosong dokter kalau Ratih kelelahan, anemia, dan macam diagnosis yang tidak memuaskan.”
Aku hanya menundukkan wajah, karena Pak Edi mulai bercerita sambil mendongak, dengan mata sayu dan suara bergetar. Sepertinya bapak ini sedang mencegah agar air matanya tidak jatuh. Oleh sebab itu aku menunduk, agar kalaupun tak sengaja menangis, Pak Edi tidak malu.
“Akhirnya kami memutuskan untuk membawa Ratih ke pengobatan alternatif. Semua orang pintar dari seluruh kabupaten sudah kami datangi.--
--Kami juga sowan ke banyak Kiyai, meminta didoakan, tapi nihil. Tahun kedua Ratih sakit, anak itu jadi kurus sekali. Perubahan yang paling mencolok, sekaligus mengkhawatirkan adalah, perut Ratih mulai membesar, kembung, keras, dan ...”
Sejujurnya aku tidak ingin Pak Edi melanjutkan. Dia seperti tidak sanggup menggambarkan kondisi almarhumah anaknya, dan rasanya aku pun tidak sanggup mendengar.
“Seperti ada sesuatu yang menyembul dari dalam. Banyak benjolan keras, dan hitam. Ratih juga mulai sering teriak, dan mengigau. Dia takut air, dia takut lampu, dia takut suara azan, ada saat di mana Ratih juga takut melihat saya.--
--Seharian Ratih mengurung diri di kamar, menangis, teriak. Di sini, kami sudah bingung, tidak tahu lagi harus bagaimana mengobati Ratih.--
--Saat saya merasa sudah tidak ada harapan, saat itulah saya teringat akan seseorang. Dia seorang tabib, perantau dari luar pulau. Usianya sudah tua, jauh lebih tua dari saya.”
Pak Ahsan? tebakku.
“Namanya Ahsan, mungkin kamu mengenalnya sebagai Pak Jawi.”
Aku berusaha untuk pura-pura terkejut. Mengangguk-angguk sambil menggumamkan huruf o.
“Namanya Ahsan, mungkin kamu mengenalnya sebagai Pak Jawi.”
Aku berusaha untuk pura-pura terkejut. Mengangguk-angguk sambil menggumamkan huruf o.
“Selain sebagai tabib, Pak Ahsan juga dikenal sebagai tukang pijat anak kecil. Banyak anak warga desa ini yang dibawa pijat ke sana. Kata orang-orang, sakit apa pun pasti sembuh kalau berobat ke Pak Ahsan.--
--Mereka bahkan lebih memilih Pak Ahsan daripada dokter. Ya, saya akui, saya ragu, dan cenderung meremehkan beliau karena hanya seorang tabib desa.--
--Lagipula, sebagai seorang ayah, saya ingin memberi putri saya pengobatan terbaik bahkan kalau harus menguras seluruh harta saya yang sebenarnya tidak banyak. Karena itulah Pak Ahsan sempat terlewat dari pikiran saya waktu itu.”
“Harus saya akui, obat dari Pak Jawi—maksud saya Pak Ahsan memang manjur, Pak.”
“Memang, saya mengundang Pak Ahsan secara khusus ke sini. Beliau biasanya tidak pernah mau dijemput, tapi mungkin karena kami sama-sama orang Minang, jadi beliau memberi pelayanan khusus buat saya.”
“Memang, saya mengundang Pak Ahsan secara khusus ke sini. Beliau biasanya tidak pernah mau dijemput, tapi mungkin karena kami sama-sama orang Minang, jadi beliau memberi pelayanan khusus buat saya.”
“Orang Minang? Sumatera?”
“Ya, saya juga perantau. Sama seperti Pak Ahsan. Hanya saja, saya sampai ke sini dua puluh tahun lebih awal dari Beliau,” Pak Edi terkekeh.
“Ya, saya juga perantau. Sama seperti Pak Ahsan. Hanya saja, saya sampai ke sini dua puluh tahun lebih awal dari Beliau,” Pak Edi terkekeh.
“Saya baru tahu,” ucapku, “Terus gimana pengobatannya?”
“Hari pertama Pak Ahsan mengungkap sesuatu yang mengejutkan tentang penyakit anak saya. Beliau bilang, sakitnya Ratih adalah pengaruh sihir.”
“Hari pertama Pak Ahsan mengungkap sesuatu yang mengejutkan tentang penyakit anak saya. Beliau bilang, sakitnya Ratih adalah pengaruh sihir.”
“Sihir?” tanyaku, terkejut.
“Santet,” jawab Pak Edi. “Dan saya tidak heran. Setelah diagnosis kedua, saya dan keluarga sudah menduga adanya campur tangan gaib dalam penyakit Ratih,--
“Santet,” jawab Pak Edi. “Dan saya tidak heran. Setelah diagnosis kedua, saya dan keluarga sudah menduga adanya campur tangan gaib dalam penyakit Ratih,--
--hanya saja sebagai orang awam dalam hal seperti itu, dugaan tersebut justru membuat kami tambah khawatir. Tidak hanya pada penyakit Ratih, tapi juga pada kemungkinan adanya musuh dalam selimut.
“Santet bukan hanya ilmu hitam, tapi sebuah pesan, sebuah peringatan dari seseorang yang entah iri, atau benci pada keluarga saya karena suatu hal, dan hasil pemeriksaan Pak Ahsan telah membuktikan bahwa itu benar.”
“Pak Ahsan tahu pelakunya?”
“Pak Ahsan tahu pelakunya?”
“Tidak, tapi dia tahu alasannya dari Ratih, ya, tidak tahu kenapa, Ratih hanya mau bicara pada Pak Ahsan. Saat itu, kalaupun Ratih bicara pada saya, belum tentu saya mengerti.--
--Ratih seperti lumpuh sehingga cara bicaranya pun seperti orang gagu, tapi entah kenapa Pak Ahsan mengerti semuanya meski Ratih hanya menggumamkan beberapa kata."
“Menurut Pak Ahsan, pesan yang dikirimkan pelaku ada kaitannya dengan pencalonan saya sebagai kepala desa.”
“Apa hubungannya?” tanyaku sambil melongo karena cerita Pak Edi mulai terdengar kompleks.
“Apa hubungannya?” tanyaku sambil melongo karena cerita Pak Edi mulai terdengar kompleks.
“Tidak ada yang suka bila seorang pendatang menjadi pemimpin. Sebaik dan sebagus apa pun pengabdian saya bagi warga, selalu saja ada sekelompok orang yang membenci, menolak dipimpin oleh orang yang warna darahnya mungkin berbeda dari mereka.”
“Oh, makanya tahun ini pun Bapak tidak mau mencalonkan diri?”
“Ya. Jabatan adalah amanah, bila saya tidak diinginkan, saya tidak akan memaksa, cuma yang bikin saya geram adalah,--
--kenapa harus melibatkan Ratih? Kenapa tidak saya saja? Bukan saya sok kuat, saya pun pasti akan tersiksa kalau dikasih cobaan semacam itu, tapi itu lebih baik daripada melihat anak gadis satu-satunya kehilangan masa kecil, dan ... nyawa.”
“Maaf, pengobatan Pak Ahsan, nggak berhasil ya, Pak?”
Pak Edi menggeleng lesu. Aku merasa tidak enak hati, tapi Pak Edi yang memilih tema percakapan ini. Aku hanya berusaha menjadi pendengar yang baik, dengan memberi respons yang terkesan antusias tapi tidak terlalu menyakiti.
Pak Edi menggeleng lesu. Aku merasa tidak enak hati, tapi Pak Edi yang memilih tema percakapan ini. Aku hanya berusaha menjadi pendengar yang baik, dengan memberi respons yang terkesan antusias tapi tidak terlalu menyakiti.
“Pak Ahsan seorang tabib, hal semacam sihir dan santet bukanlah bidangnya. Setidaknya itu menurut dia,” ucap Pak Edi, ia terdengar sangat marah. Beberapa kalimat diucapkan dengan gigi terkatup rapat,--
--“Tapi setidaknya berkat pengobatan beliau, Ratih masih diberi kesempatan bicara pada kami. Dia sempat bisa bangkit dari tempat tidurnya,
--duduk di kursi, dan berkeliling halaman rumah dengan menggunakan kursi roda. Kami tidak bisa minta lebih dari itu. Sesakti apapun, Pak Ahsan tetap tidak bisa melawan takdir. Setidaknya begitu menurut dia.”
Lagi, kalimat terakhir Pak Edi seolah menjadi penutup yang terkesan klimaks, tapi diucapkan dengan ekspresi yang seolah mengisyaratkan kalau cerita itu belum selesai.
Tidak menampik kalau aku prihatin dengan Pak Edi, tapi kenapa sengaja mengundangku ke rumahnya hanya untuk menceritakan ini? Bagian mana dari cerita Pak Edi barusan yang penting untuk aku ketahui?
“Dani.”
“Eh, ya, Pak.”
“Eh, ya, Pak.”
“Malam itu, kamu dan temanmu melihat sendiri apa yang dilakukan keenam anak itu sama Pak Muhadi dan kawan-kawannya, kan?”
“I-iya,” jawabku. Entah kenapa aku merasa takut. Pak Edi di hadapanku sekarang, jadi seperti orang yang berbeda.
“I-iya,” jawabku. Entah kenapa aku merasa takut. Pak Edi di hadapanku sekarang, jadi seperti orang yang berbeda.
“Jujur sama saya, apa waktu itu kamu melihat hal yang aneh?”
Pak Edi mencondongkan tubuhnya ke depan.
“Ma-maksudnya?”
Pak Edi mencondongkan tubuhnya ke depan.
“Ma-maksudnya?”
“Apa kamu lihat seseorang selain keenam anak itu? Apa Pak Jawi melakukan sesuatu yang tidak biasanya?”
Pak Edi mencecarku dengan pertanyaan, dan setiap selesai bertanya, dia makin mendekat, menyeberangi meja yang memisahkan kami, wajahnya sudah sejengkal di depan wajahku, dan matanya mendelik,--
--dia ingin mengorek informasi yang untuk sebuah alasan aku jadi takut memberikannya. Pak Edi pun berhenti basa-basi dan mulai memberiku pertanyaan pemungkas.
“Apa kamu melihat anak Pak Ahsan yang satu lagi?”
Bersambung minggu depan
CHAPTER 27, 28, 29 sudah saya tempel di Karyakarsa. Silakan teman-teman yang mau mampir.
karyakarsa.com/ahmaddanielo/m…
karyakarsa.com/ahmaddanielo/m…
Terima kasih sudah membaca, terima kasih juga sudah setia menunggu, hehe. Maaf kalau saya liburnya kelamaan, banyak tugas lain yang harus dikerjakan, dan ada gangguan kesehatan juga. Insya Allah setelah ini saya akan kembali bercerita rutin seperti biasanya.
Kita ketemu malam jumat lagi, yak.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh