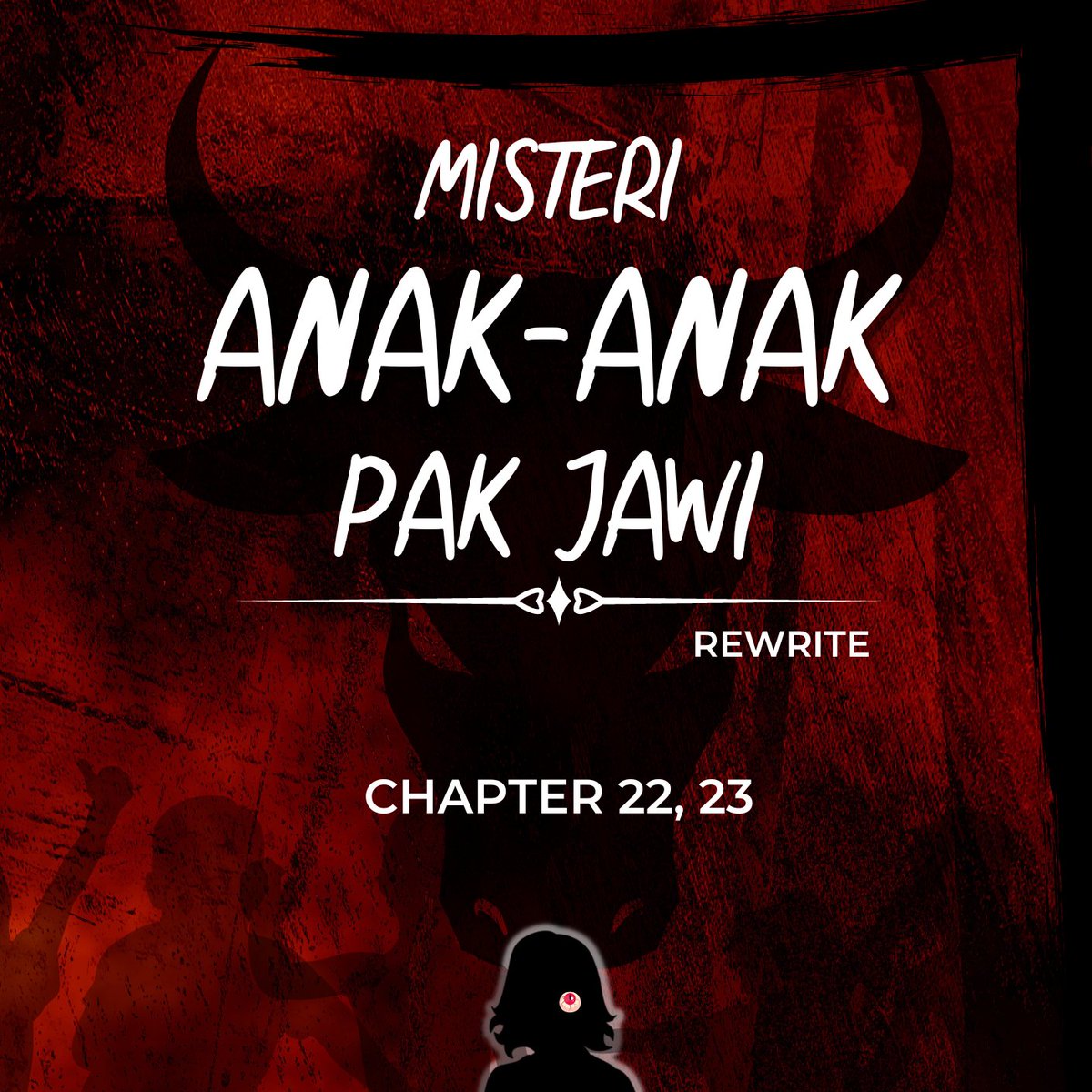MISTERI ANAK-ANAK PAK JAWI
CHAPTER 35, 36
@bacahorror @IDN_Horor
#threadhorror #bacahorror #timurtrilogi #MisteriAnakAnakPakJawi
CHAPTER 35, 36
@bacahorror @IDN_Horor
#threadhorror #bacahorror #timurtrilogi #MisteriAnakAnakPakJawi

Mau baca dari awal? Silakan mampir ke sini.
https://twitter.com/DanieloAhmad/status/1539969843646312449?s=20&t=pMQ635iWZzToJIUCbGOcBQ
CHAPTER 35
Butuh waktu untuk memproses perkataan Pak Edi agar terdengar masuk akal. Ada sebagian kalimat yang tidak jelas kutangkap, tapi sesuatu tentang menghidupkan anak yang sudah mati,--
Butuh waktu untuk memproses perkataan Pak Edi agar terdengar masuk akal. Ada sebagian kalimat yang tidak jelas kutangkap, tapi sesuatu tentang menghidupkan anak yang sudah mati,--
--yang benar saja! Hanya beberapa penyihir hebat yang bisa melakukannya, dan mereka hanya ada di drama televisi.
Pak Edi lanjut bicara. Kali ini suaranya sangat pelan. Aku tidak bisa mendengar sepatah kata pun, meski sudah mencorongkan tangan ke telinga. Barulah kuingat siapa yang sedang bersamaku sekarang. Si mencong masih berusaha menahanku untuk tidak keluar dari persembunyian.
Aneh. Ke mana perginya rasa takut itu? Melihat si mencong di hadapanku, dekat dengan mataku yang biasanya mendelik takut akan wujud gadis kecil ini, sekarang rasanya biasa saja. Dia seperti anak kecil pada umumnya.
Tidak mengerikan. Jauh dalam hatiku justru mengiba. Sungguh, seolah semua tampilan misterius dan mengerikan dari gadis kecil ini lenyap.
Entah terungkapnya masa lalu mereka yang mengenaskan telah membuatku luluh, atau aku hanya memikirkan bagaimana nasib mereka selanjutnya setelah Pak Jawi tiada.
“Kenapa kamu di sini?” tanyaku.
Si mencong mengangkat wajahnya. Ia juga mengangkat telunjuknya, mengarahkan jari mungil itu pada Pak Edi, atau mungkin secara khusus menunjuk benda yang Pak Edi pegang.
Si mencong mengangkat wajahnya. Ia juga mengangkat telunjuknya, mengarahkan jari mungil itu pada Pak Edi, atau mungkin secara khusus menunjuk benda yang Pak Edi pegang.
“Lonceng itu?” tanyaku.
Si mencong mengangguk.
“Penting? Maksudku, apa lonceng itu sangat penting?"
Lagi-lagi si mencong mengangguk.
Si mencong mengangguk.
“Penting? Maksudku, apa lonceng itu sangat penting?"
Lagi-lagi si mencong mengangguk.
“Sekarang, andai kamu bisa jelaskan sama aku, kenapa lonceng itu jadi rebutan, mungkin aku bisa pertimbangkan buat bantu kakek merebutnya dari Pak Edi,” tuturku.
Si mencong tampak bingung. Bisa jadi dia mengerti maksud perkataanku, hanya saja kemampuan dan kosa katanya terbatas untuk menjawab. Aku tidak memaksa.
Kubiarkan dia duduk di sampingku, sementara aku kembali memata-matai pergerakan Pak Edi. Pria itu tampak menjelakan sesuatu, tapi kali ini suaranya pelan dan aku sama sekali tidak bisa mendengar. Hal menarik apa yang ia bicarakan sampai wajahnya terlihat semringah.
“Ka-kakak … ma …."
“Oh, ayolah, berhenti manggil kakak. Kalaupun cuma itu yang bisa kamu katakan, setidaknya simpan buat nanti. Tahu nggak, aku masih sering gemetar setiap kali dengar suaramu manggil kakak.”
“Kakak … marah …."
“Oh, ayolah, berhenti manggil kakak. Kalaupun cuma itu yang bisa kamu katakan, setidaknya simpan buat nanti. Tahu nggak, aku masih sering gemetar setiap kali dengar suaramu manggil kakak.”
“Kakak … marah …."
“Aku nggak marah, maksudku, ya, aku marah, tapi nggak marah. Lihat! Aku sampai bingung harus ngomong apa.”
Si mencong meraih kedua tanganku, ia mendongak, rambut panjangnya tersibak dan wajahnya terlihat dengan jelas. Bibirnya yang miring itu bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Perlahan mulutnya terbuka.
“Kakak kami … marah. Kakak kami marah.”
“Kakak kalian? Siapa yang kalian maksud?”
BODOH!
“Kakak kalian? Siapa yang kalian maksud?”
BODOH!
Itu suara kakek. Terlepas sifatnya yang sering membuat kesal, kakek termasuk orang yang jarang mengumpat. Setidaknya secara terang-terangan. Sepertinya Pak Edi mengatakan sesuatu yang sangat bodoh sampai-sampai kakek tidak sempat menyusun sarkasme andalan.
“Mungkin,” jawab Pak Edi.
Kulihat ia mendekati kakek. Saat itu juga Pak Muhadi dan orang bertopeng itu berdiri. Mereka meraih sekop, dan bersiap-siap di samping kuburan.
Kulihat ia mendekati kakek. Saat itu juga Pak Muhadi dan orang bertopeng itu berdiri. Mereka meraih sekop, dan bersiap-siap di samping kuburan.
“Saya sama sekali tidak ada niatan memusuhi sampean, Kang Saleh. Jadi tolonglah, pulang. Biarkan kami selesaikan semua ini, lagipula kami tidak merugikan orang lain. Sejauh ini tidak ada orang yang terluka, tapi akan ada satu kalau sampean masih ikut campur.”
Kakek tolah-toleh, kanan, kiri, atas, bawah.
“Siapa?” tanya kakek, berlagak bingung.
“Siapa?” tanya kakek, berlagak bingung.
Pak Edi tidak menjawab. Bahkan dalam posisi terikat, ia tidak menang berdebat melawan kakek. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Kakek cuma sekolah sampai SD, tidak lancar membaca,--
--ia tidak pandai bicara dalam acara formal, karena itu jarang diundang rapat. Namun, dalam perdebatan, bahkan sekelas Pak Camat pun bisa mendadak bodoh serta kehabisan kata-kata melawan kakek.
Pak Edi meninggalkan kakek. Ia bergabung dengan Pak Muhadi dan orang bertopeng yang mulai bersiap menggali kuburan.
“Mau dia apakan kuburan anaknya?” gumamku.
“Mau dia apakan kuburan anaknya?” gumamku.
Layaknya menyambung benang merah di atas meja abu-abu, dalam ruangan yang gelap. Apa yang kualami, kulihat, dan kudengar telah membentuk sebuah garis lurus.
Aku mulai tahu tujuan Pak Edi. Aku hanya tidak memahami jalan pikirannya. Selain tujuannya adalah hal yang mustahil, hasil akhir apa yang ia harapkan dari sebuah sihir?
Aku menoleh ke belakang, berharap Mbah Sopet dan Maulida telah selesai. Seketika angin malam berembus kencang menerpa wajahku, membawa serta daun-daun dan kelopak cempaka yang mulai mengering.
Dingin menjalari tubuhku, terutama setelah kudengar suara yang tak asing. Suara lonceng. Benda itu bergetar di tangan Pak Edi.
“Kakak …” ucap si mencong.
Tangan gadis kecil itu bergetar hebat. Matanya menatap nanar.
Tangan gadis kecil itu bergetar hebat. Matanya menatap nanar.
KAKAK DATANG
Ada empat tiang lampu di pemakaman Lindung. Menerangi pintu masuk, tempat keranda, tengah pemakaman, dan satu di tempat kakek. Malam ini aku jadi saksi bagaimana hal mistis mengalahkan sains.
Keempat lampu itu mati bersama embusan angin. Mencipatakan kegelapan menyeluruh. Membutakan mata yang sejak awal sudah tidak bisa melihat secara utuh.
Dalam gelap yang aneh ini, suasana pemakaman terasa berbeda. Tiba-tiba saja aku merasa sedang dalam bahaya. Bunyi lonceng sapi juga tak mau berhenti.
Kudengar gaduh di sisi Pak Edi. Kedengarannya mereka pun sedang panik. Aku hendak keluar dari persembunyian, tapi lagi-lagi si mencong menahanku.
“Dengar, aku nggak ngerti kamu kenapa, tapi aku harus ke sana. Orang-orang itu bisa saja mencelakai kakek."
Kulihat kepala si mencong bergeleng cepat sembari menarik tanganku kembali ke balik semak-semak.
Kulihat kepala si mencong bergeleng cepat sembari menarik tanganku kembali ke balik semak-semak.
Tiba-tiba muncul cahaya di tempat kakek berada. Pak Muhadi sedang menyalakan lampu petromaks. Ia meletakkannya di dekat kuburan yang hendak digali. Namun, perhatian ketiga orang di sana bukan lagi pada sekop dan gundukan tanah, melainkan pada tiang lampu di mana kakek terikat.
Ketiganya melongo, tercengang, persis seperti wajahku saat ini, sebab kami menyaksikan kakek sudah berdiri bebas sambil melakukan peregangan, layaknya pemain cadangan yang hendak dilepas ke lapangan.
“Silakan kalau mau lari, bawa sekop kalian, tapi tinggalkan lonceng itu di sini,” ucap kakek.
Kelihatannya Pak Edi dan kawan-kawan menolak tawaran kakek.
Kelihatannya Pak Edi dan kawan-kawan menolak tawaran kakek.
Alih-alih pergi, mereka mengambil sekop dan bergerak menyerang kakek secara bersamaan. Kecuali orang bertopeng, ia maju sambil menghunus goloknya.
Aku sering dengar tentang kehebatan kakek, tapi melawan tiga orang bersenjata, di usia kakek sekarang, tetap saja membuatku khawatir.
Hanya saja, kekhawatiranku luruh manakala kakek dengan mudahnya menangkap serangan sekop Pak Muhadi, mematahkan kayunya, dan mengirim Pak Muhadi telungkup di atas kuburan hanya dengan sekali pukulan.
Berbeda dengan Pak Edi. Tampaknya kakek sengaja bermain-main dengannya. Pak Edi mengayunkan sekop ke segala arah, tapi tak sedikit pun mengenai kakek, dan sepertinya kakek juga tidak berniat menyerang. Ia terus mengelak, bahkan saat pria bertopeng ikut menyerang bersamaan.
Sebuah serangan kuat dilayangkan Pak Edi dengan sekopnya dan lagi-lagi dihindari kakek. Sekop itu menghantam tanah, ujungnya terbenam. Kakek menginjak senjata Pak Edi itu hingga ia kesulitan menarik.
Dirasa waktu bermain-main sudah selesai, kakek menendang dada Pak Edi hingga mental dan tubuhnya membentur tiang lampu. Belum sempat kaki kakek turun, pria bertopeng mencuri kesempatan dengan menusukkan goloknya ke punggung kakek.
“Kakek!”
Sontak aku menjerit dan keluar dari persembunyian. Kakek tampak heran dengan kehadiranku hingga sama sekali tak hiraukan sebuah golok sedang menancap di punggungnya. Kakek menoleh ke belakang, pada pria bertopeng yang masih menekan senjatanya ke punggung kakek.
Sontak aku menjerit dan keluar dari persembunyian. Kakek tampak heran dengan kehadiranku hingga sama sekali tak hiraukan sebuah golok sedang menancap di punggungnya. Kakek menoleh ke belakang, pada pria bertopeng yang masih menekan senjatanya ke punggung kakek.
“Sudah?" tanya kakek pada pria bertopeng yang mulai mundur perlahan karena merasa senjatanya tumpul oleh reaksi kakek yang biasa saja.
Golok itu jatuh ke tanah, dan pria bertopeng pun lari tunggang-langgang. Merasa situasi sudah aman, aku pun berlari menghampiri kakek.
Golok itu jatuh ke tanah, dan pria bertopeng pun lari tunggang-langgang. Merasa situasi sudah aman, aku pun berlari menghampiri kakek.
“Kakek nggak apa-apa?” tanyaku.
“Ngapain kamu di sini?” kakek balas bertanya.
“Ngapain kamu di sini?” kakek balas bertanya.
Aku belum mau menjawab sebelum memastikan kondisi kakek. Kulihat senjata tajam yang tergeletak di tanah.
Logamnya kotor oleh tanah basah, tapi bersih dari noda darah. Begitu kuperiksa punggung kakek, yang kudapati hanyalah baju robek segaris, dan kulit punggung kendor yang sama sekali tidak terluka.
“Kok bisa?”
Kakek meraih pundakku, mengguncang-guncangkannya dengan keras sambil mencecarku dengan pertanyaan.
Kakek meraih pundakku, mengguncang-guncangkannya dengan keras sambil mencecarku dengan pertanyaan.
“Kamu kenapa ke sini? Anak-anak itu sudah ketemu? Mana Maulida? Gimana di hutan?”
Tak sempat aku menjawab, percakapan kami terganggu oleh suara tawa Pak Edi. Tawa yang putus asa, tapi tetap terdengar mengejek.
Tak sempat aku menjawab, percakapan kami terganggu oleh suara tawa Pak Edi. Tawa yang putus asa, tapi tetap terdengar mengejek.
“Masih hidup?” tanya kakek.
kulihat Pak Muhadi tidak bergerak. Masih tengkurap lelap di atas kuburan. Hanya Pak Edi yang masih bisa bicara, itu pun dengan kondisi menyedihkan dan mulut berdarah. Giginya pun tampak merah disorot cahaya petromaks.
kulihat Pak Muhadi tidak bergerak. Masih tengkurap lelap di atas kuburan. Hanya Pak Edi yang masih bisa bicara, itu pun dengan kondisi menyedihkan dan mulut berdarah. Giginya pun tampak merah disorot cahaya petromaks.
“Kenapa … kenapa kalian bertindak sejauh ini cuma demi enam anak cacat itu?” tanya Pak Edi.
“Karena ada orang bodoh yang bertindak sejauh ini untuk sesuatu yang mustahil," jawab kakek.
“Karena ada orang bodoh yang bertindak sejauh ini untuk sesuatu yang mustahil," jawab kakek.
“Sampean terlalu ikut campur, Kang Saleh. Harusnya usia tua seperti itu--uhuk--gunakan saja untuk istirahat.”
Pak Edi terbatuk-batuk. Sepertinya tendangan kakek sangat keras mencederai dadanya. Namun, orang keras kepala ini masih saja ingin bicara.
Pak Edi terbatuk-batuk. Sepertinya tendangan kakek sangat keras mencederai dadanya. Namun, orang keras kepala ini masih saja ingin bicara.
“Saya tahu ini mustahil, tapi saya tidak bisa hidup tenang kalau belum mencoba semua cara yang ada. Ratih--uhuk--meskipun cuma bayangannya saja yang bisa saya hadirkan, saya akan jadi ayah yang paling bahagia di dunia.”
“Sayangnya, sampean jadi ayah yang paling egois di dunia,” ucapku.
Aku tahu, aku tidak dalam posisi bisa menasihati orang tua. Aku bahkan tidak tahu rasanya kehilangan orang tersayang. Namun, setidaknya aku bisa memberi Pak Edi sebuah pendapat yang tak sempat kuutarakan di rumahnya waktu itu.
“Ratih sudah bahagia di sana. Kenapa susah payah membawanya kembali ke dunia kalau Ratih harus hidup bersama ayah yang rusak, egois, dan … maaf, BODOH!"
Kakek terbelalak melihatku sambil menutup mulutnya dengan tangan.
“Heh, kamu pikir saya mau dengar nasihat dari anak kecil yang naif seperti kamu?” ucap Pak Edi, sinis.
Meski berkata demikian, kulihat raut wajah Pak Edi mulai melunak. Matanya sayu. Kuharap kata-kataku masuk ke kepalanya walaupun hanya sedikit.
Meski berkata demikian, kulihat raut wajah Pak Edi mulai melunak. Matanya sayu. Kuharap kata-kataku masuk ke kepalanya walaupun hanya sedikit.
CHAPTER 36
“Saleh!"
Mbah Sopet dan Maulida berlari menghampiri kami. Mereka juga menuntun si mencong yang sejak tadi bersembunyi. Sepertinya urusan mereka dengan anak buah Pak Muhadi telah selesai.
“Saleh!"
Mbah Sopet dan Maulida berlari menghampiri kami. Mereka juga menuntun si mencong yang sejak tadi bersembunyi. Sepertinya urusan mereka dengan anak buah Pak Muhadi telah selesai.
Tidak sedikit pun aku membayangkan mereka akan kalah, tapi melihat mereka baik-baik saja, tetap saja membuatku lega. Kakek dan Mbah Sopet bersila di tanah. Maulida memijati mereka satu persatu, meski kulihat dia pun sebenarnya sangat letih.
Kini situasi mulai tenang. Pak Edi dan Pak Muhadi pingsan. Namun, tidak satu pun dari kami yang berinisiatif membawa mereka ke rumah sakit.
“Ini kenapa jadi gelap-gelapan gini?” tanya Mbah Sopet.
“Sepertinya penghuni pemakaman ini menunggak tagihan," kelakar kakek.
“Ini kenapa jadi gelap-gelapan gini?” tanya Mbah Sopet.
“Sepertinya penghuni pemakaman ini menunggak tagihan," kelakar kakek.
Mbah Sopet menampar lengan kakek pakai kopiahnya.
“Mumpung di pemakaman, kenapa mereka gak langsung dikubur aja?” celoteh Maulida.
“Gila!" sahutku.
“Gusafar?” tanya kakek.
“Mumpung di pemakaman, kenapa mereka gak langsung dikubur aja?” celoteh Maulida.
“Gila!" sahutku.
“Gusafar?” tanya kakek.
“Dia lagi jagain anak-anak yang lain di hutan. Sugik juga sudah mengantar sisanya ke sana, tapi …." Mbah Sopet melirik pada si mencong yang langsung bersembunyi di belakangku. “Siapa sangka masih ada satu lagi.”
“Gimana ceritanya mereka bisa sampai sini?” tanyaku.
“Gimana ceritanya mereka bisa sampai sini?” tanyaku.
“Muhadi merampas sesuatu dari mereka, dan tiga anak ini nekat mengikutinya. Bahkan yang kudengar, mereka bahkan nekat melawan. Sayangnya, kali ini Muhadi dan kawan-kawan sudah lebih siap. Tiga anak kecil sama sekali bukan tandingan," tutur kakek.
Mbah Sopet membuka kopiah, mengacak-acak rambutnya yang tipis, hingga helai demi helai ubannya saling silang di kulit kepala yang terlihat lapang.
“Edi dan antek-anteknya tahu kita sedang mencari mereka, makanya sengaja memisahkan keenam anak ini, jadi meski kita berhasil menemukan yang di hutan, kita masih harus mencari tiga anak lainnya,” katanya.
“Yang aku heran, kalau memang yang Pak Edi butuhkan cuma benda itu, kenapa repot-repot membawa anak-anak ke pemakaman ini?" tanyaku.
“Untuk ukuran seorang seperti Edi, bisa merencanakan ini dengan sangat baik saja sudah aneh," sambung Maulida.
“Untuk ukuran seorang seperti Edi, bisa merencanakan ini dengan sangat baik saja sudah aneh," sambung Maulida.
Sejujurnya, aku pun berpikir demikian. Semua terlalu rapi untuk sebuah rencana bodoh, dengan hasil yang menurutku tidak seberapa.
Maksudku, Pak Muhadi terkenal pelit dan gila harta, sementara Pak Edi miskin dan tidak punya jabatan. Tidak mungkin mereka berada di satu tim tanpa motivasi yang kuat, serta nominal yang tepat.
“Orang bertopeng yang kabur tadi, kira-kira siapa, Kek?"
Maulida dan Mbah Sopet serempak melihatku. Mereka baru datang saat orang yang kumaksud sudah lari tunggang-langgang.
“Bertopeng?” tanya Mbah Sopet.
Maulida dan Mbah Sopet serempak melihatku. Mereka baru datang saat orang yang kumaksud sudah lari tunggang-langgang.
“Bertopeng?” tanya Mbah Sopet.
“Ya, dia satu-satunya yang bawa golok, tapi satu-satunya yang kabur. Gendeng," ujar kakek seraya terbahak-bahak.
Kakek berdiri, menghampiri kuburan Ratih, memungut lonceng milik Pak Jawi yang tergeletak di tanah. Sejenak ia perhatikan, lalu kakek bunyikan lonceng itu dengan pelan.
Melihat apa yang kakek lakukan, si mencong yang sejak tadi bersembunyi di belakangku jadi makin ketakutan. Tangan mungilnya mememegang lenganku erat, dan wajahnya terbenam di punggungku sambil ia menceracau.
“Tidak seorang pun bisa melawan takdir Tuhan, bahkan jika harus bersekutu dengan iblis sekalipun,” tutur kakek. “Namun, kita harus tetap waspada. Muslihat dan godaan mereka kuat, lagipula aku merasakan sesuatu yang tidak biasa dari benda ini.”
Kami semua memperhatikan lonceng di tangan kakek. Entah bagaimana isi kepala Maulida dan Mbah Sopet saat ini, tapi karena ini bukan pertama kali aku melihatnya,--
--sering mendengar bunyinya di rumah, serta menyaksikan sendiri bagaimana suara lonceng itu punya pengaruh kuat bagi anak-anak Pak Jawi, di mataku lonceng itu jadi terlihat menyeramkan.
“Kita tidak bisa terus nongkrong di sini. Lihat, Kakeh mukul mereka berdua sampai babak belur, sampai pingsan. Di jalan juga ada beberapa orang yang semaput--”
“--ada yang tangan sama kakinya patah juga,” potong Maulida dengan bangga, seolah yang ia sebutkan adalah sebuah prestasi.
“--be-betul itu. Apapun alasannya, yang kita lakukan ini bisa masuk tindak pidana."
“Tapi mereka juga kriminal, kan? Aku yakin mereka semua adalah otak di balik kebakaran rumah Pak Jawi,” sahutku.
“Tapi mereka juga kriminal, kan? Aku yakin mereka semua adalah otak di balik kebakaran rumah Pak Jawi,” sahutku.
"Kamu butuh bukti untuk menuduh, Kalaupun tidak punya, setidaknya kamu harus jadi orang yang pintar bicara."
“Cuma bicara saja, sih, aku bisa, Pet,” celetuk kakek.
“Cuma bicara saja, sih, aku bisa, Pet,” celetuk kakek.
“Pintar bicara, Leh! Pintar! Kakeh gendeng!" geram Mbah Sopet. "Kita butuh tempat aman untuk anak-anak ini. Gusafar bisa diandalkan kalau mengasuh monyet, tapi aku ragu kalau anak manusia.”
Mbah Sopet benar. Sejak tadi aku berpikir bagaimana nasib anak-anak ini selanjutnya. Mereka sudah tidak punya orangtua, tidak pula rumah, dan dengan kondisi mereka yang terbatas, mustahil meninggalkan mereka hidup sendirian.
“Pesantren,” kata kakek.
“Pesantren,” kata kakek.
“Yakin Kiyai masih mau menerima anak-anak ini? Bukannya tahun kemarin kita juga menitipkan enam orang anak di sana?” sahut Mbah Sopet.
“Kalau yang Sampean maksud adalah anak-anak buangan, mereka tidak lagi tinggal di pesantren," sahut Maulida. "Setelah berkali-kali aparat datang dan memaksa bertemu dengan mereka, Kiyai meminta Dokter Eva untuk membawa anak-anak itu ke luar kota.”
Entah apa yang mereka bicarakan. Namun, sepertinya ini bukan kali pertama mereka berurusan dengan kasus anak-anak yang dibuang.
“Bicara soal tempat aman, sepertinya ini juga harus diamankan."
Kakek menyodorkan lonceng itu pada Mbah Sopet.
“Bicara soal tempat aman, sepertinya ini juga harus diamankan."
Kakek menyodorkan lonceng itu pada Mbah Sopet.
“Kenapa harus aku?”
“Kamu hobi ngoleksi barang rongsokan--”
“--BARANG ANTIK!" sergah Mbah Sopet.
“Ya, itu, sekalian saja ini bawa. Lagian ini lonceng sakti," bujuk kakek.
“Kamu hobi ngoleksi barang rongsokan--”
“--BARANG ANTIK!" sergah Mbah Sopet.
“Ya, itu, sekalian saja ini bawa. Lagian ini lonceng sakti," bujuk kakek.
“Kalau lonceng itu bisa manggil perempuan cantik, aku mau, tapi kalau yang datang malah siluman sapi, mending kasih Gusafar saja!”
Kakek berpikir sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sepertinya sedang bingung mau diapakan lonceng sapi itu. Sementara kakek mencari ide, kami bersiap-siap pergi. Tidak lama lagi tempat ini akan ramai oleh orang, dan saat mereka datang, kami tidak boleh ada di sini.
“Maulida!” panggil kakek. “Bawa ini ke Kiyai Ilyas. Beliau pasti tahu apa yang harus dilakukan dengan benda ini.”
Mulanya kulihat Maulida sedikit ragu, tapi akhirnya ia pun menerima lonceng itu. Menurutku, membawa benda keramat seperti itu pada seorang Kiyai adalah langkah yang tepat.
Kiyai Ilyas adalah salah satu pengasuh pesantren Sokogede yang disegani tidak hanya warga kecamatan, tapi seantero Tapal Kuda.
Pundakku terasa ringan karena masalah telah selesai. Orang-orang jahat tertidur pulas, anak-anak malang akan punya tempat tinggal baru,--
--siluman terkutuk tidak lagi bebas berkeliaran, dan yang pasti, aku tidak harus satu tim lagi dengan Maulida. Sekarang waktunya pulang dan beristirahat.
“Oh, ya, karena kamu tidak bawa motor, sebaiknya ajak Dani saja!" ucap kakek.
“APA?”
“APA?”
Bersambung minggu depaaaaan.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh