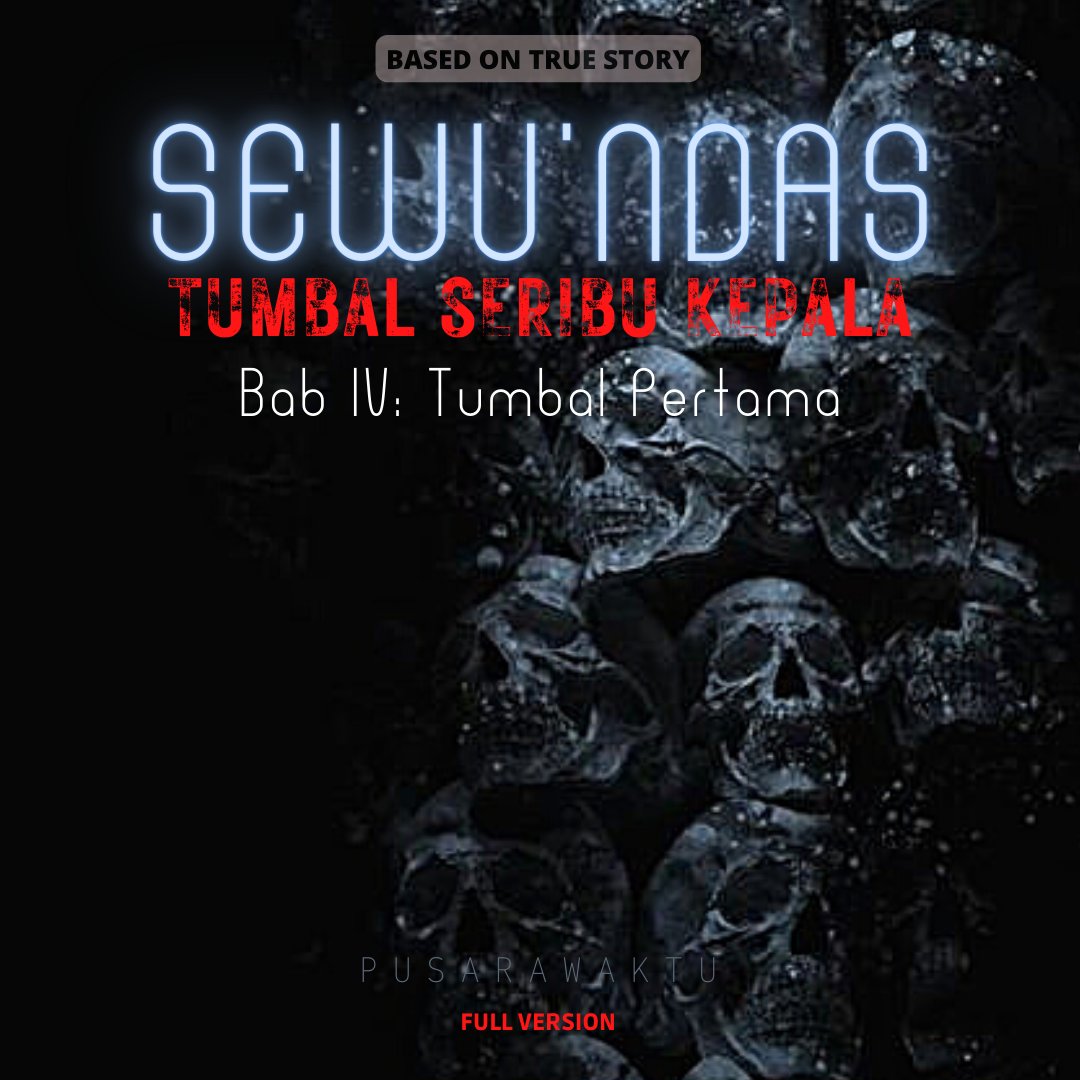JAREK TANGKUP
(Tolakan Pengundang Bala)
- HOROR THREAD -
@issssss___
@autojerit
@Penikmathorror
@ceritaht
@IDN_Horor
#horor #kisahnyata #bacahoror
(Tolakan Pengundang Bala)
- HOROR THREAD -
@issssss___
@autojerit
@Penikmathorror
@ceritaht
@IDN_Horor
#horor #kisahnyata #bacahoror

Hallo PWers~
Kita mulai berkisah lagi ya :D
Oh ya sebelumnya, kisah ini akan sedikit slow updatenya, bahkan malam ini pun, baru sebatas teaser dulu sampai agak senggang waktuna nanti :D
Yuk langsung mulai~
Kita mulai berkisah lagi ya :D
Oh ya sebelumnya, kisah ini akan sedikit slow updatenya, bahkan malam ini pun, baru sebatas teaser dulu sampai agak senggang waktuna nanti :D
Yuk langsung mulai~
"Sampeyan wes roh, Yu. Kang Sakir muleh?" (Kamu sudah tau, Yu. Kang Sakir pulang?)
"Sopo seng ngabari?" (Siapa yang memberi tau?) Ucap Menik, seorang wanita berumur 43 tahunan, balik bertanya kepada Asti, tetangganya.
"Sopo seng ngabari?" (Siapa yang memberi tau?) Ucap Menik, seorang wanita berumur 43 tahunan, balik bertanya kepada Asti, tetangganya.
"Gak roh aku, Yu. Saiki wonge gone Kang Ugik." (Tidak tau saya, Yu. Sekarang orangnya di rumah Kang Ugik.) Jawab Asti sambil berlalu, meninggalkan Menik di dalam kamar sendirian.
Menik perlahan membuka jendela, menatap lurus keluar, tertuju pada sebuah rumah kecil beratap papan yang tinggal separo. Membayang dalam pikirannya tujuh tahun silam, dimana masa-masa bahagia ia lalui bersama Sakir dan putrinya, Lika.
Namun, sebuah keputusan sepihak yang diambil oleh Sakir, membuatnya harus hidup hanya berdua saja bersama Lika. Menik masih tak mengerti, untuk apa dan karena apa Sakir yang sangat bertanggung jawab dulunya, bisa pergi begitu saja tanpa memberi alasan yang jelas.
Padahal dirinya sendiri yang lahir dari keluarga mampu rela menjadi istrinya, meski ditentang oleh seluruh keluarga besarnya.
"Buk, Sampeyan mikir opo?" (Buk, Kamu memikirkan apa?)
"Buk, Sampeyan mikir opo?" (Buk, Kamu memikirkan apa?)
Lamunan Menik seketika buyar, mendengar suara lembut yang berasal dari belakang. Senyum tipisnya mengembang menutupi keresahan, dihadapan sosok gadis yang dalam dua hari lagi akan melangsungkan pernikahan.
"Ora, Nduk. Ibu gak mikir opo-opo. Ibu ngitung waktu kok cepet temen. Delok eneh awakmu wes dadi bojone Fajar." (Tidak, Nduk. Ibu tidak mikirin apa-apa. Ibu hanya menghitung waktu yang begitu cepat sekali. Sebentar lagi kamu akan menjadi istri Fajar.) Jawab Menik menutupi.
"Masio aku wes dadi bojone Mas Fajar, neng aku iseh dadi siji mbek Ibu. Dadi Ibu ora bakal dewean." (Walaupun aku sudah menjadi istri Mas Fajar, tapi aku tetap jadi satu bersama Ibu. Jadi Ibu tidak akan sendiri.) sahut Lika menghibur.
Menik meraih kepala Lika, membenamkan dalam dadanya seraya mengusap lembut rambut hitam sebahu anak semata wayangnya itu, hasil buah cintanya bersama Sakir. Dera napas sesak beberapa kali keluar dari dada Menik.
Ia tak ingin kebahagiaan Lika terganggu dengan kehadiran Bapaknya, yang sangat dibencinya sebab telah meninggalkan dirinya.
***
Suasana semakin ramai di halaman belakang, depan rumah tembok milik Menik yang ia bangun dari hasil perkebunan pemberian orang tuannya.
***
Suasana semakin ramai di halaman belakang, depan rumah tembok milik Menik yang ia bangun dari hasil perkebunan pemberian orang tuannya.
Para tetangga, saudara, bahu membahu mempersiapkan sebuah pesta pernikahan Lika, sesuai adat istiadat wilayah sekitar.
Sementara, dari sebuah rumah, tepat berada di samping kanan rumah Menik yang hanya ber-gang sebuah rumah papan berantakan, sepasang mata mengawasi dari balik horden jendela.
Sorot mata milik lelaki berkulit hitam yang berumur 46-an itu nampak tajam.
Sorot mata milik lelaki berkulit hitam yang berumur 46-an itu nampak tajam.
Selaras dengan rambut pendek kaku, serta otot-otot mengular tersembul dari kulit kasarnya. Dadanya begitu cepat naik turun, tarikan napasnya terkadang berat, seperti menyimpan sebuah beban yang sangat besar.
Lama sosok laki-laki itu berdiri mematung, sembari terus mengawasi semua kegiatan yang ada di rumah Menik. Ia baru beranjak dan menghenyak di kursi sofa, saat seorang lelaki yang sedikit lebih muda darinya, datang dari halaman depan.
"Piye, Gik?" (Gimana, Gik?) Tanyanya tak sabar, setelah lelaki yang baru datang itu, duduk di hadapannya.
"Wali nikahe Lika, Wali Hakim, Kang Sakir. " (Wali nikahnya Lika, Wali Hakim, Kang.) Jawab pelan lelaki yang biasa dipanggil Gik, atau Ugik.
"Wali nikahe Lika, Wali Hakim, Kang Sakir. " (Wali nikahnya Lika, Wali Hakim, Kang.) Jawab pelan lelaki yang biasa dipanggil Gik, atau Ugik.
"Lakok iso!?"(Kok bisa!?) Sahut Sakir, dengan wajah tegang.
"Sampeyan dipatekne, Kang. Aku wes ngomong karo Ketipe, nek Sampeyan iseh urep. Neng wes kadung nang formulir pendaftaran, Lika karo Yu Menik matekne, Sampeyan."
"Sampeyan dipatekne, Kang. Aku wes ngomong karo Ketipe, nek Sampeyan iseh urep. Neng wes kadung nang formulir pendaftaran, Lika karo Yu Menik matekne, Sampeyan."
(Kamu dimatikan, Kang. Saya sudah bicara sama penghulunya, kalau Sampeyan masih hidup. Tapi sudah terlanjur tertulis di formulir pendaftaran, Lika dan Mbak Menik mematikan status sampeyan.)
Sambung besok ya temen2. Mau lanjut nguli dulu :D
Yuk lanjut, mumpung lagi break bentar :D
Sakir terhenyak, merasai sakit dan nyeri pada dadanya. Kepalanya menyandar, tangannya meremas sebuah bungkusan plastik hitam yang ia letakan di sampingnya.
"Wes benci tenan anak karo bojoku. Masio aku salah, neng kok tegel temen sampek aku di matekne."
"Wes benci tenan anak karo bojoku. Masio aku salah, neng kok tegel temen sampek aku di matekne."
(Sudah benci sekali anak dan istriku. Walaupun aku memang salah, tapi kok tega sekali sampai aku dianggapnya Mati.) Ucap Sakir lirih penuh rasa sesal.
"Terus arep piye, Sampeyan Kang?" (Terus mau bagaimana, sampeyan, Kang?) Tanya Ugik pelan.
"Terus arep piye, Sampeyan Kang?" (Terus mau bagaimana, sampeyan, Kang?) Tanya Ugik pelan.
Sakir hanya diam. Matanya menatap langit-langit rumah milik Ugik. Pikiranya kosong, jiwanya terguncang, mendapati kenyataan yang terasa sangat pahit harus dirinya terima, setelah tujuh tahun meninggalkan anak dan istri, oleh karena suatu sebab.
"Aku numpang kene sak bubare nikahane Lika, Gik. Gak opo-opo to?" (Aku menumpang di sini sampai acara pernikahan Lika, Gik. Tidak apa-apa kan?) Ucapnya kemudian penuh harap.
Ugik menghela napas berat dan mengiyakan permintaan Sakir.
Ugik menghela napas berat dan mengiyakan permintaan Sakir.
Bukan persoalan Sakir menumpang di rumahnya yang dirinya pikir berat, tetapi keadaan yang bakal terjadi nanti, setelah semua orang tau bahwa Sakir, orang tua kandung Lika hadir dalam acara resepsi, terutama keluarga besar dari Menik.
Beranjak sore, suasana di rumah Menik semakin meriah. Alunan musik dangdut terdengar menggema dari beberapa sound system yang dipasang para pemuda. Meski acara resepsi masih dua hari lagi, sudah menjadi tradisi penduduk setempat, keramaian dimulai dari tiga hari sebelumnya.
Pada keesokan hari, jelang malam tiba, kesibukan semakin terlihat. Tawa ceria, bahagia, terpancar dari wajah-wajah muda mudi, terutama Lika. Sebab malam itu, dirinya bakal melangsungkan Ijab Qabul bersama lelaki yang sangat ia cintai, Fajar, pemuda yang berasal dari desa sebelah.
Berbeda dengan Menik. Ulasan senyum dari bibirnya, terlihat kaku. Matanya menyirat kecemasan dan ketakutan, ketika menyadari jika Sakir,
Bapak kandung Lika, suami yang belum terputus secara sah, akan datang menyaksikan acara sakral yang tinggal menunggu waktu hitungan jam saja.
Dirinya tau jika Sakir sedang berada di rumah Ugik, untuk itu Menik khawatir akan terjadi keributan bila Sakir nanti nekat datang.
Dirinya tau jika Sakir sedang berada di rumah Ugik, untuk itu Menik khawatir akan terjadi keributan bila Sakir nanti nekat datang.
Apalagi saat itu semua anggota keluarga besarnya datang, terutama ke empat kakaknya yang sedari dulu tak pernah menyukai Sakir.
Sementara Sakir sendiri tampak rapi, bercelana dasar hitam, berbaju batik lengan panjang, serta kopiah hitam yang terlihat sedikit lusuh. Semua itu ia lakukan setelah mendengar dari Ugik, jika malam nanti Lika dan Fajar bakal melangsungkan Ijab Qabul pernikahan.
"Sampeyan yakin tenan, Kang. Arep moro runu?" (Sampeyan yakin benar, Kang. Mau datang ke acara itu?) Tanya Ugik yang melihat penampilan rapi Sakir.
"Tenan, Gik." (Benar, Gik.) Jawab Sakir, mantap.
"Tenan, Gik." (Benar, Gik.) Jawab Sakir, mantap.
"Aku kwater nek kakang-kakange Yu Menik ngerti Sampeyan, dadi ribut, Kang."(Saya khawatir kalau kakak-kakaknya Mbak Menik tau sampeyan, jadi ribut, Kang.)
Kali ini ucapan Ugik merubah raut wajah Sakir. Bagaimana pun, kata-kata Ugik Ia benarkan.
Kali ini ucapan Ugik merubah raut wajah Sakir. Bagaimana pun, kata-kata Ugik Ia benarkan.
Apalagi diantara semua rekan, teman bahkan saudaranya sendiri, Ugik adalah orang yang paling tau semua persoalannya.
Bukan hanya karena rumah mereka yang dulu berdekatan, tetapi sering dan lamanya keduanya bergaul, membuat Sakir yakin dan percaya untuk selalu bercerita tentang masalahnya dulu.
"Tapi aku kudu tetep teko, Gik. Aku ora arep golek ribut, malah aku pingin dadi apik meneh karo Menik, karo Lika. Aku pengen nyambung omah-omahku." (Tapi aku harus tetap datang, Gik.
Aku tidak akan mencari masalah, bahkan aku ingin jadi baik lagi dengan Menik, dengan Lika. Aku mau menyambung rumah tanggaku.) Ujar Sakir mantap.
Kini giliran Ugik yang diam menghela napas. Dalam batin ia meragukan keinginan Sakir bisa terwujud.
Kini giliran Ugik yang diam menghela napas. Dalam batin ia meragukan keinginan Sakir bisa terwujud.
Dirinya tahu betul siapa Menik, Lika dan juga saudara-saudara sekandung Menik. Tak akan segampang itu untuk menerima Sakir, walaupun dirinya mengakui jika Sakir tak bersalah, atas masalah dalam rumah tangga mereka.
Ugik pun tak kuasa mencegah untuk mencegah keinginan Sakir, ia hanya menatap kepergian Sakir ke rumah gedong milik Menik. Rasa tak tega pun menggurat pada wajahnya, memikirkan Sakir nantinya.
Di dalam ruangan berukuran 4x5 meter, ruang tamu rumah Menik, tampak puluhan orang sudah berkerumun, mengitari dua pasang anak manusia yang akan berikrar janji.
Didampingi seorang wanita berkebaya dan empat orang lelaki 50-60an. Lika, gadis cantik anak kandung Sakir dan Menik terlihat semringah. Wajahnya memancarkan kebahagiaan, berdampingan dengan lelaki pujaan yang lama ia kenal.
Namun, suasana hikmad itu tiba-tiba berubah gaduh manakala beberapa saudara jauh Menik melihat kedatangan Sakir. Hal itu membuat Penghulu menghentikan sejenak kalimat-kalimat nasehat, yang ia berikan sebelum memulai Ijab.
"Menik, aku ijeh urep. Aku jek nduwe hak dadi waline Lika." (Menik, saya masih hidup. Saya masih punya hak jadi walinya Lika.) Ucap Sakir yang berdiri di belakang Menik.
"Aku yo jek pingin mbangun nikah meneh. Aku pengen iso urep bareng meneh." (Saya juga masih ingin rujuk kembali. Saya ingin bisa hidup bersama lagi.) Sambung Sakir sedikit bergetar.
"Aku wes ora nduwe bapak. Bapakku wes mati!"
"Aku wes ora nduwe bapak. Bapakku wes mati!"
(Saya sudah tidak punya Bapak. Bapakku sudah mati!) Sengit dan keras kalimat yang keluar dari bibir Lika.
Suasana pun semakin gaduh manakala kedua lelaki yang duduk di samping Lika ikut berdiri, memelototkan mata pada Sakir.
Suasana pun semakin gaduh manakala kedua lelaki yang duduk di samping Lika ikut berdiri, memelototkan mata pada Sakir.
"Menik, iki bukti omonganku, tondo tali tresnoku." (Menik, ini bukti ucapanku, tanda ikatan cintaku.) Ucap Sakir sembari meletakkan bungkusan plastik hitam yang ia bawa sedari awal datang.
Sakir tak peduli dengan pelototan mata-mata sinis, yang mengisyaratkan kebenciam mendalam dari saudara-saudara Menik maupun Lika, anaknya sendiri.
Sejenak ruangan tempat acara sakral, hening. Semua terdiam menunggu reaksi serta ucapan dari Menik yang kini terlihat tertunduk.
Sejenak ruangan tempat acara sakral, hening. Semua terdiam menunggu reaksi serta ucapan dari Menik yang kini terlihat tertunduk.
Sampai satu menitan kemudian Menik bangkit. Menatap tajam pada Sakir, sebelum berjalan menuju ke dalam tanpa mengucap kalimat apapun.
"Wes ngerti jawabane saiki Koe!" (Sudah tau jawabannya sekarang lamu!) Seru seorang lelaki, salah satu kakak Menik, Hadi.
"Wes ngerti jawabane saiki Koe!" (Sudah tau jawabannya sekarang lamu!) Seru seorang lelaki, salah satu kakak Menik, Hadi.
Walau terdengar sengak dan sengit hardikan dari Hadi, tetapi bukan itu yang membuat denyutan di dada Sakir sakit. Tetapi sikap penolakan Menik lah, yang membuat wajah Sakir merah. Ia pun segera bangkit, melangkah keluar dengan penuh kekecewaan.
Belum sampai kakinya menjangkau pintu, satu cengkraman tangan menahan pundaknya.
"Iki bondomu gawanen!" (Ini bawaanmu bawa kembali) Ujar seorang lelaki bertubuh tambun.
Sakir menundukkan tubuhnya, mengambil bungkusan yang berserakan setelah dilempar di sisi kirinya.
"Iki bondomu gawanen!" (Ini bawaanmu bawa kembali) Ujar seorang lelaki bertubuh tambun.
Sakir menundukkan tubuhnya, mengambil bungkusan yang berserakan setelah dilempar di sisi kirinya.
Beberapa mata terbelalak, melihat isi dalam kantong. Ucapan Istighfar pun terucap bersahutan, dari beberapa orang tua, menandakan ada sesuatu yang tak main-main dibalik isi bungkusan yang dibawa oleh Sakir.
Bersambung ...
Lanjut Yuk~
Sepeninggalan Sakir, Ijab dan Qabul kembali dilanjutkan. Tanpa didampingi, Menik, Sakir, selaku orang tua kandung. Banyak yang meragukan ke-absahan dari pernikahan tersebut, tetapi mereka hanya bisa menahan, berbisik dengan yang lain tanpa berani mengingatkan.
Kegaduhan yang sempat menunda acara, telah tergantikan kembali dengan gegap gempita suara tawa dan deru musik. Semuanya tampak bahagia, bersuka ria. Hanya ada beberapa orang yang berwajah mempias cemas, setelah melihat kejadian saat Sakir datang.
Salah satunya seorang lelaki tua berkopiah putih yang duduk bersama Ugik.
"Mugo-mugo wae ra ono opo-opo karo Sakir." (Moga-moga saja tidak ada apa-apa dengan Sakir.) Ucapnya pada Ugik.
"Enek opo, Mbah?" (Ada apa, Mbah?) Sahut Ugik penasaran.
"Mugo-mugo wae ra ono opo-opo karo Sakir." (Moga-moga saja tidak ada apa-apa dengan Sakir.) Ucapnya pada Ugik.
"Enek opo, Mbah?" (Ada apa, Mbah?) Sahut Ugik penasaran.
"Angen-angenku ki gak kepenak." (Perasaanku tidak enak.) Ucap kembali, sosok lelaki tua, yang dipercaya warga, sebagai sesepuh kampung.
"La nopo, to Mbah?"(La kenapa, to Mbah?) Tanya Ugik penasaran.
Mbah Diyo, warga memanggil. Menarik napasnya dalam-dalam.
"La nopo, to Mbah?"(La kenapa, to Mbah?) Tanya Ugik penasaran.
Mbah Diyo, warga memanggil. Menarik napasnya dalam-dalam.
Wajahnya yang mulai dipenuhi kerutan, nampak datar. Tangannya lalu merogoh kantong baju sampingnya, mengeluarkan sebungkus rokok berbungkus warna merah dan mengambilnya sebatang.
"JAREK TANGKUP!" Ucapnya sebelum menyelipkan sebatang rokok pada bibir dan membakar ujungnya.
"JAREK TANGKUP!" Ucapnya sebelum menyelipkan sebatang rokok pada bibir dan membakar ujungnya.
Terlihat Ugik mengangguk beberapa kali. Ia tak mengerti tentang maksud dari Jarek Tangkup yang baru saja diucapkan oleh Mbah Diyo. Tetapi, melihat wajah dan getaran pada suara Mbah Diyo, ia yakin bahwa Jarek Tangkup bukanlah perkara baik.
"Opo iku, Jarek Tangkup, Mbah?" (Apa itu, Jarek Tangkup, Mbah?) Tanya Ugik, tak lagi mampu menahan rasa penasarannya.
"Aku ora wani njabarne, mergo iku sek gor firasat. Seng jelas gak apik nolak, opo meneh ngguwak Jarek tondo katresnan. Arepo gak di tompo tresnone, kudune di tompo jarik e, maleh di balekne meneh apek-apek."
(Saya tidak berani menceritakan, karena itu baru firasat. Yang pasti tidak baik menolak, apa lagi sampai membuang kain Jarek sebagai tanda cinta rujukan. Walaupun tidak diterima cintanya, harusnya diterima dulu Jariknya, setelahnya baru dikembalikan secara baik-baik.)
Setelah sedikit menjawab rasa penasaran Ugik, Mbah Diyo kemudian bangkit. Membuat Ugik yang akan kembali bertanya mengurungkan.
***
***
Hawa dingin dirasai Ugik ketika sayup lembut terpaan angin malam, menyapu kulit. Menyadarkan Ugik jika malam berangsur larut. Ia pun segera meninggalkan rumah Menik, di mana dirinya menjadi salah satu rewang dalam pesta resepsi Lika dan Fajar.
Satu menitan Ugik tempuh untuk sampai di rumahnya. Melewati jalan berkerikil dan bekas rumah Menik serta Sakir saat masih bersama. Sampai di belokan halaman rumahnya, Ugik terdiam sebentar.
Menajamkan pandangan ke arah bekas rumah Sakir, yang tinggal dinding papan separo dan puing rapuh tiang penyangga.
Kening Ugik semakin berkerut, kala semakin jelas matanya mendapati bayangan di bagian belakang bekas rumah.
Kening Ugik semakin berkerut, kala semakin jelas matanya mendapati bayangan di bagian belakang bekas rumah.
Bayangan itu semakin jelas, saat bergerak, berjalan pelan ke arah bekas sumur yang telah ditumbuhi ilalang setinggi lutut orang dewasa.
Sempat berpikir untuk menghampiri, namun tertahan oleh suara ramai dari arah rumah Menik.
Sempat berpikir untuk menghampiri, namun tertahan oleh suara ramai dari arah rumah Menik.
Ugik pun menduga jika bayangan itu adalah salah satu pemuda atau tetangga yang masih rewang di rumah Menik.
Ugik terkejut saat tangannya meraih handle pintu, yang ternyata tak terkancing. Sedikit dorongan, daun pintu kayu berukir garis putus itu pun terbuka lebar.
Ugik terkejut saat tangannya meraih handle pintu, yang ternyata tak terkancing. Sedikit dorongan, daun pintu kayu berukir garis putus itu pun terbuka lebar.
Beberapa kali ia memanggil pelan Sakir, namun tak ada jawaban. Saat itu, Ugik hanya menduga jika Sakir tengah keluar rumah, atau main ke tempat saudaranya yang berada di desa sebelah, desa tempat lahirnya.
Rasa lelah membuat tubuh serta mata Ugik tak mampu bertahan. Ia pun tertidur, tanpa menunggu kedatangan Sakir. Sekira waktu sudah masuk dini hari, Ugik tetiba terjaga. Memasang baik-baik telinganya, memastikan dengan apa sedang ia dengar.
Lirih ... Lirih, semakin lirih suara tangisan benar-benar didengarnya dari balik kamar, atau tepat berada di ruang tamu. Ugik segera bangkit, tanpa ragu melangkah keluar, ingin memastikan dengan apa yang tengah didengarnya itu.
"Kang, Sampeyan ko ngendi?" (Kang, Sampeyan dari mana?) Tanya Ugik, saat melihat Sakir duduk dengan sesenggukan.
"Gik, maturnuwon yo, wes oleh numpang. Salam kanggo anak bojomu, di ngapuro salahku." (Gik, terima kasih sudah boleh saya numpang.
"Gik, maturnuwon yo, wes oleh numpang. Salam kanggo anak bojomu, di ngapuro salahku." (Gik, terima kasih sudah boleh saya numpang.
Salam buat anak dan istrimu, mohon dimaafkan kesalahanku.) Ucap Sakir.
Ugik terdiam. Alisnya bertaut mencoba mencerna ucapan Sakir.
"Lha, sampeyan arep nandi, Kang?" (Lha, sampeyan itu mau kemana?) tanya Ugik tak mengerti.
"Aku arep muleh, Gik." (Saya mau pulang, Gik.)
Ugik terdiam. Alisnya bertaut mencoba mencerna ucapan Sakir.
"Lha, sampeyan arep nandi, Kang?" (Lha, sampeyan itu mau kemana?) tanya Ugik tak mengerti.
"Aku arep muleh, Gik." (Saya mau pulang, Gik.)
"Lha kapan, Kang? Po gak sido ngenteni rampong acarane Lika?" (Lha kapan, Kang? Apa gak jadi nunggu sampai selesai acaranya Lika?)
"Ora, Gik. Aku muleh wengi iki." (Tidak, Gik. Saya pulang malam ini.) Jawab Sakir.
"Ora, Gik. Aku muleh wengi iki." (Tidak, Gik. Saya pulang malam ini.) Jawab Sakir.
Ugik semakin bingung mendengar perkataan Sakir yang berpamitan malam itu. Dirinya tau, bila selama ini Sakir bekerja di luar kota. Tetapi, untuk pulang ke tempat kerjanya, harus pada tengah hari, sebab mobil yang menuju kesana hanya berangkat di jam-jam itu.
"Lakyo sisok awan to, Kang? Saiki opo yo ono bis lewat arah gon kerjomu?" (Tapikan besok siang, Kang? Sekarang apa ya ada bus lewat ke arah tempat kerjamu?)
Sakir berganti diam. Wajahnya tertunduk, menatapi kain Jarek yang ada di pangkuannya. Selang satu menit, Sakir bangkit.
Sakir berganti diam. Wajahnya tertunduk, menatapi kain Jarek yang ada di pangkuannya. Selang satu menit, Sakir bangkit.
Menatap datar Ugik, sebelum melangkah keluar tanpa mengucap apapun.
Ugik berusaha mencegah, ia berniat menyusul dan memintanya untuk kembali. Tetapi aneh. Di mana, Sakir yang belum ada setengah menit keluar, tiba-tiba sudah tak terlihat.
Ugik berusaha mencegah, ia berniat menyusul dan memintanya untuk kembali. Tetapi aneh. Di mana, Sakir yang belum ada setengah menit keluar, tiba-tiba sudah tak terlihat.
Sampai antara batas jalan dan halaman rumah Ugik mengejar Sakir. Tetap saja tak tersusul, bahkan tak menemukan bayangan Sakir. Ugik akhirnya memilih untuk masuk, beristirahat merebahkan kembali tubuhnya yang sempat terganggu.
***
***
Bersambung ...
Mohon maaf ya temen2. Kisahnya saya hold dulu, sampai nanti kondisinya memungkinkan untuk melanjutkan kisah ini 🙏
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh