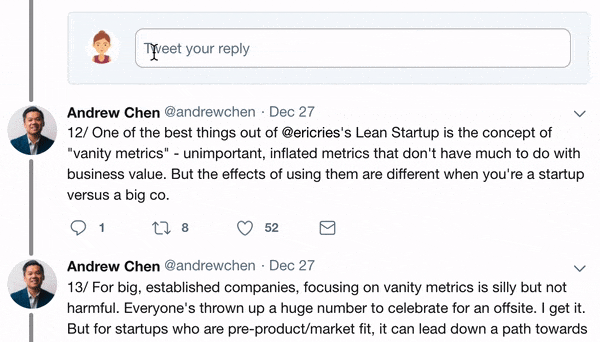Tidak sepenuhnya setuju tentang hal ini, tapi masih bisa memaklumi kenapa logika (dan sains) dan kepercayaan (dogma) dianggap tidak memiliki hubungan epistemologis.
Quraish Shihab berada di posisi ini, yaitu dogma hanya bisa jadi landasan etis semata (bukan epistemologis).
Quraish Shihab berada di posisi ini, yaitu dogma hanya bisa jadi landasan etis semata (bukan epistemologis).
https://twitter.com/andrywaseso/status/1474027885514035201
Seseorang yang beriman memerlukan penjelasan kenapa ia bisa memercayai sesuatu. Begitupun orang yang memeluk agama memerlukan penjelasan kenapa ia memeluknya.
Bisa jadi penjelasan itu untuk dirinya sendiri, atau diberikan pada orang lain sebagai penjelasan.
Bisa jadi penjelasan itu untuk dirinya sendiri, atau diberikan pada orang lain sebagai penjelasan.
Ikhtiar ini (menjelaskan kenapa ia bisa memiliki kepercayaan & memeluk sebuah agama) biasa dikenal dengan:
((( saintifikasi dogma )))
Secara mendasar keduanya (saind & dogma) sangatlah berbeda. Sains menerima falsifikasi (dikelirukan), sementara dogma tidak mengenal kekeliruan.
((( saintifikasi dogma )))
Secara mendasar keduanya (saind & dogma) sangatlah berbeda. Sains menerima falsifikasi (dikelirukan), sementara dogma tidak mengenal kekeliruan.
Saya sempat mengalami kebingungan sewaktu menelaah “islamisasi ilmu pengetahuan” yang didorong oleh Naquib Alatas (yang diteruskan Osman Bakar).
Ternyata, dari beberapa jurnal, disertasi, dan tesisnya, Sidi Naquib memang tidak berupaya untuk me-sains-kan Islam.
Ternyata, dari beberapa jurnal, disertasi, dan tesisnya, Sidi Naquib memang tidak berupaya untuk me-sains-kan Islam.
Saya bukannya skeptis bahwa dogma & sains itu dua perkara yang bertentangan (falsifikasi & dogmatik), oleh karenanya dua hal itu berbeda.
Tapi setelah membaca hikayat bagaimana ilmu kalam, saya cenderung bergeser sikap:
…bisa saja kepercayaan dogmatis di-sains-kan!
Tapi setelah membaca hikayat bagaimana ilmu kalam, saya cenderung bergeser sikap:
…bisa saja kepercayaan dogmatis di-sains-kan!
Hal ini terjadi ketika saya ngobrol dengan intelektual NU yang berkarir di Eropa. Bahkan di kampus-kampus Katholik & Kristen kian ke sini makin menghilangkan sikap skeptis bahwa sains & dogma tidak bisa bertemu dalam epistemologi.
Kenapa?
Faith seeking understanding!
Kenapa?
Faith seeking understanding!
Sama seperti sains yang—di satu sisi—memiliki muatan keimanan (falsifikatif), dogma—sebagai iman—juga akan mencari jalan keluarnya sendiri untuk lebih masuk akal (tentu saja: lebih saintifik).
Masalahnya bukan pada “bagaimana”, tapi “siapa” yang akan memulainya?!
😬
Masalahnya bukan pada “bagaimana”, tapi “siapa” yang akan memulainya?!
😬
Dulu, pernah terjadi saintifikasi iman sehingga melahirkan ilmu kalam.
Meski harus diakui logika (manthiq) dalam ilmu kalam adalah mak ketiplek (persis!) dengan logika tradisional Aristotelian, namun diakui pula bahwa keimanan ternyata bisa dijelaskan dengan sains.
Meski harus diakui logika (manthiq) dalam ilmu kalam adalah mak ketiplek (persis!) dengan logika tradisional Aristotelian, namun diakui pula bahwa keimanan ternyata bisa dijelaskan dengan sains.
Jika waktu itu monoteisme Islam hanya bisa dijelaskan dengan keyakinan (sementara sains berangkat dari keraguan & pertanyaan), ternyata ilmu Kalam lahir sebagai tanda bahwa “iman tidak berhenti soal percaya saja”.
Jika akhirnya muncul keraguan bahwa iman tidak bisa mendorong ilmu (secara epistemologis), ternyata sejarah ilmu kalam membuktikan sebaliknya; akidah (teologi) dibuktikan dengan dalil-dalil rasional (logika Aristotelian).
Meski tidak sepenuhnya dogma tadi jadi dasar epistemologi, paling tidak keimanan (dan kepercayaan dogmatik) mampu mendorong pada ilmu (dan sains).
Masalahnya, kan, siapa yang akan membuka tabir itu.
Sialnya, di antara saintis Islam yang meraih nobel tidak sepenuhnya Sunni (ada Ahmadi dan Syiah).
Sementara saintis Sunni ketika mampu membuka tabir saintifikasi Islam justru ganti profesi jadi da'i.
😬
Sialnya, di antara saintis Islam yang meraih nobel tidak sepenuhnya Sunni (ada Ahmadi dan Syiah).
Sementara saintis Sunni ketika mampu membuka tabir saintifikasi Islam justru ganti profesi jadi da'i.
😬
Saya pernah bincang-bincang di Fesbuk dengan Ismail A’lam, mahasiswa Paramadina yang pernah meneliti gagasan Naquib Alatas.
Waktu itu saya tidak terlalu menganggap islamisasi sains ini masuk akal. Begini uraianku setelah membaca jurnal Sidi Naquib.
facebook.com/postakof/posts…
Waktu itu saya tidak terlalu menganggap islamisasi sains ini masuk akal. Begini uraianku setelah membaca jurnal Sidi Naquib.
facebook.com/postakof/posts…
Ismail menjawab keraguanku pada Sidi Naquib (bagaimana mungkin sains di-Islam-kan?) dengan baik.
facebook.com/ismail.a.alam/…
Dari sini saya mulai berpikir bahwa pertemuan dogma & sains dalam epistimelogi itu mungkin-mungkin saja (dan tidak mustahil).
facebook.com/ismail.a.alam/…
Dari sini saya mulai berpikir bahwa pertemuan dogma & sains dalam epistimelogi itu mungkin-mungkin saja (dan tidak mustahil).
Masalahnya: siapa yang akan membuka tabirnya? Atau lebih spesifik: Syaikh Einstein mana yang akan menjelaskannya?!
Ini, kan, seperti menjodohkan dua “jenis kelamin” yang berbeda.
Hanyasaja, problem umat muslim itu rentan jadi da’i.
Ini, kan, seperti menjodohkan dua “jenis kelamin” yang berbeda.
Hanyasaja, problem umat muslim itu rentan jadi da’i.
Ada dokter yang sempat membuka tabir sains-dogma. Tapi alih-alih bikin jurnal & melanjutkan penelitian, dia malah sibuk safari dari masjid ke masjid sebagai pendakwah.
Kemana-mana bicara tentang “Islam itu masuk akal”. Padahal, sains itu berkembang, dan masjid tidak.
Kemana-mana bicara tentang “Islam itu masuk akal”. Padahal, sains itu berkembang, dan masjid tidak.
Tapi tak apa, itu kan tentang pilihan dan keputusannya sebagai manusia. Aku bukannya menentang sikap itu—justru aku hormati alih profesinya.
Aku hanya menyayangkan saja.
Dia punya kesempatan belajar sains lebih awal & lebih lama, tapi dihentikan di majelis taklim.
😬
Aku hanya menyayangkan saja.
Dia punya kesempatan belajar sains lebih awal & lebih lama, tapi dihentikan di majelis taklim.
😬
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh