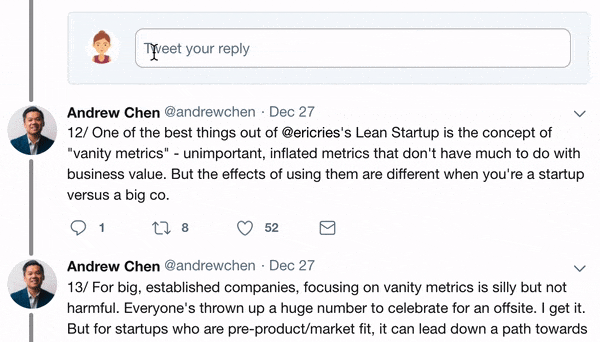KONSISTENSI, KATA ITU LEBIH MUDAH KITA UCAPKAN DIBANDING DENGAN MENJADIKANNYA SEBAGAI MILIK MELEKAT.
.
.
ITU BARANG MAHAL
.
.
.
.
.
ITU BARANG MAHAL
.
.
.

Bila Budiman Sudjatmiko terlihat selalu konsisten berdiri pada sisi sebarang "jalan milik" Soeharto, Fadli Zon melakukannya pada Jokowi. Keduanya adalah sedikit dari banyak politikus negeri ini yang tahu apa itu makna konsisten.
Keduanya berani berdiri pada sisi benderang sebuah pilihan. Bukan abu-abu warna sebagai iya dan tidak. Bisa kanan bisa kiri. Bisa menjadi siapa saja tergantung ke mana arah angin bertiup. 

Bahkan, kadang, seorang politisi pun tak ragu berbicara bahwa dirinya sedang berjalan ke kanan padahal tubuhnya jelas-jelas sedang terlihat mengarah ke kiri. Demi suara, mereka mau menjadi apa saja.
Tidak dengan Budiman dan Fadli.
Tidak dengan Budiman dan Fadli.
Bukan pada sosok bernama Soeharto, Budiman tak mau berdamai, pada cara otoriter pemerintahan Orde Baru yang dipimpinnya lah dia mengambil jarak. Dia melawan. Hingga kini, sikapnya tak pernah berubah. 

Pada Fadli, ini agak berbeda. Kebalikan dengan Budiman, Fadli justru lebih terlihat tak senang dengan sosoknya belaka. Pilihan kata plonga plongo yang seolah adalah bentuk personifikasi pada sosok tak dia suka adalah bukti.
Anehnya, Fadli tak pernah bermasalah dengan sistem pemerintahan Jokowi. Buktinya adalah partai di mana dia lahir dan besar kini menjadi partai pendukung pemerintah. 

Bahwa setelah partainya bergabung dengan pemerintahan Jokowi namun Fadli tetap senang mencacinya, ini tentu konsistensi pada makna yang lain. Dia konsisten untuk tetap tidak konsisten.
"Loh koq??"
"Loh koq??"
Konsistensinya hanya berjalan pada ruang pribadinya. Pada ruang yang lebih besar, dia tak mampu menalar makna itu. Kapasitas nalar yang dia miliki, tak cukup besar bahkan bila hanya untuk dapat menampung logika dasar seperti itu.
"Terlalu bolot, gitu maksudnya?"
"Terlalu bolot, gitu maksudnya?"

Hingga kini, hampir tak pernah kita mendengar Budiman berbicara miring apalagi menghina sosok Soeharto. Musuhnya adalah otoriter caranya memerintah saat beliau berkuasa selama 32 tahun. Konsistensinya terjaga, bahkan hingga saat ini.
Politik adalah keindahan, begitu tuturnya pada suatu saat dulu. Dan maka, tak ada sedikitpun alasan benar bagi masuknya paham kebencian pada caranya berpolitik.
.
.
.
.
.
.

• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh