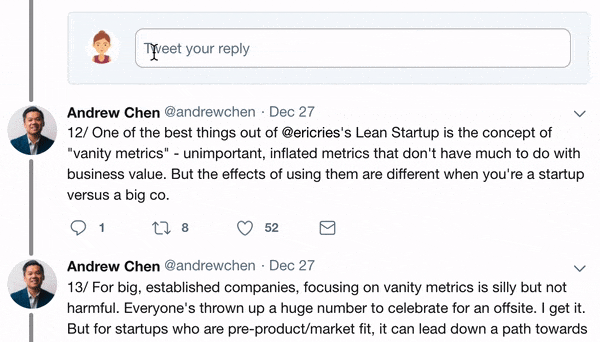Mungkin tidak sedikit dari kita bertanya-tanya, kenapa Indonesia mengimplementasikan Co-Firing? Kenapa sekarang? Bahan bakarnya dari mana saja? Bagaimana dampaknya?
-A Thread-
-A Thread-

Co-Firing sudah digunakan sejak akhir 1990-an di sejumlah negara. Namun, Indonesia baru akan mulai menjadikan Co-Firing sebagai salah satu cara untuk menurunkan emisi karbon. Sayangnya masih banyak hal tentang Co-Firing yang belum dirasa jelas.
Co-Firing di Indonesia akan menggunakan sampah & limbah hasil perkebunan, seperti akasia, sawit, dan sengon dijadikan sebagai bahan baku co-firing. Bahan tersebut merupakan jenis tanaman yang membutuhkan banyak lahan. Artinya bisa menjadi celah tindakan deforestasi lagi dan lagi.
Dalam rangka mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% di tahun 2025, melalui RUPTL 2021-2030 pemerintah telah menghitung estimasi kebutuhan biomassa untuk 52 lokasi dimana mencapai 8 juta ton/tahun HTE (Hutan tanaman energi) dan 900 ribu ton/tahun sampah.
Artinya butuh pasokan bahan baku biomassa yang cukup besar & stabil untuk keberlangsungan co-firing.
(Sumber: RUPTL 2021-2030)
(Sumber: RUPTL 2021-2030)

Kendala kebutuhan bahan baku biomassa bahkan sudah terasa dalam tahap uji coba co-firing. Salah satunya yakni pada PLTU Jeranjang NTB akibat sekam padi bersifat musiman yang bahkan belum bisa memenuhi kebutuhan 3% kadar campuran yang setara 15 ton/hari/unit pembangkit.
Pemanfaatan cangkang sawit sebagai biomassa juga menunjukkan adanya peluang untuk menambah pembukaan lahan sawit. Selama ini sawit telah menghasilkan jejak karbon yang cukup besar di Indonesia bahkan menjadi penyebab utama deforestasi yang memperburuk tingkat emisi.
Penggunaan sampah sebagai salah satu campuran co-firing harus dibarengi dengan teknologi air pollution control (APC) yang bagus. Jika tidak, risiko polutan beracun harus dihadapi oleh masyarakat.
Co-firing juga tidak memberikan kontribusi penurunan emisi GRK yang signifikan. Porsi biomassa hanya 1-5% dan sisanya 95% tetap menggunakan batubara. Perlakuan tersebut pada PLTU batubara hanya akan mengurangi emisi GRK sebesar 5,4%.
Padahal menurut perhitungan PLN, dibutuhkan 5 juta ton/tahun wood pellet atau 738.000 ton/tahun pellet sampah untuk memenuhi 1% co-firing per tahun pada 18.000 MW PLTU batubara yang sudah ada.
Di sisi lain, biaya investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai energi bersih sudah lebih murah dibanding PLTU batubara.
(Sumber: ESDM, 2020 dalam webinar Katadata)
(Sumber: ESDM, 2020 dalam webinar Katadata)

Vietnam telah membuktikan bahwa potensi PLTS sangat tinggi. Vietnam berhasil meningkatkan kapasitas PLTS-nya dari 2015-2020 hingga mencapai 3.300 kali lipat. 

Tantangan co-firing lainnya juga terletak pada kelayakan ekonomi. Klaim bahwa biomassa dapat diperoleh dengan harga lebih rendah cukup sulit, mengingat:
- Membutuhkan volume lebih besar yang meningkatkan biaya transportasi
- Adanya potensi penurunan efisiensi boiler
- Membutuhkan volume lebih besar yang meningkatkan biaya transportasi
- Adanya potensi penurunan efisiensi boiler
Dengan segenap tantangannya, biaya co-firing akan lebih mahal dibanding batubara. Hal ini bisa kembali menjadi beban PLN. Yang perlu kita waspadai jika pada akhirnya berdampak pada harga listrik dan kembali dibebankan ke masyarakat. 

Jika melihat kontribusi Co-Firing terhadap krisis iklim dengan skema yang dibuat oleh pemerintah, co-firing merupakan solusi semu untuk memenuhi komitmen iklim Indonesia. Dan hal ini akan berlangsung selama PLTU masih dipertahankan dan menjadi sumber emisi GRK.
Mari kita bayangkan, apa kira-kira yang akan terjadi jika program Co-Firing ini betul-betul bergulir? Pemerintah seharusnya betul-betul beralih ke energi bersih dan terbarukan, bukan pada solusi keliru yang penuh resiko dan membutuhkan investasi lebih besar.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh