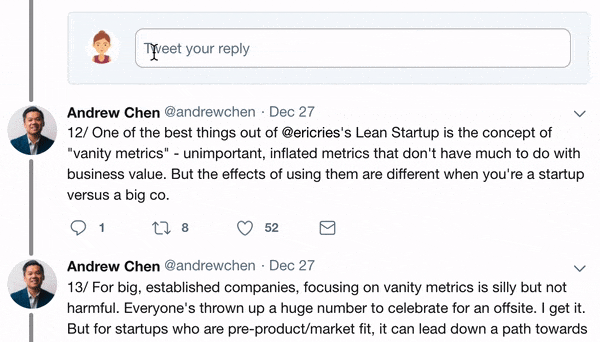Gus Dur dan Wayang
A Thread
Salah satu kegemaran #GusDur ketika sekolah di Yogyakarta adalah menonton wayang. Baginya, wayang sebagai medium komunikasi dan medium pembentuk perilaku memiliki bermacam fungsi.
A Thread
Salah satu kegemaran #GusDur ketika sekolah di Yogyakarta adalah menonton wayang. Baginya, wayang sebagai medium komunikasi dan medium pembentuk perilaku memiliki bermacam fungsi.

Pertama, sebagai penghibur, yaitu membuat masyarakat terhibur, memperoleh makanan rohani atau memperoleh kepuasan psikologis.
Karena dengan begitu mereka bisa melarikan diri dari dera kehidupan sehari-hari atau rutinitas harian yang menjemukan.
Karena dengan begitu mereka bisa melarikan diri dari dera kehidupan sehari-hari atau rutinitas harian yang menjemukan.

Wayang dalam fungsi seperti ini tidak boleh disepelakan, karena sebagaimana jenis hiburan yang lain, di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat menghubungkan sesama warga masyarakat.
Bahkan jika sudah diakui secara universal seperti wayang, sebuah karya seni bisa menghubungkan sesama umat manusia. Bagi yang belum pernah menonton wayang, kalau diterangkan wayang dengan penggambarannya saja sudah menjadi paham.
Karena itu, kehadiran wayang penting sekali sebagai alat untuk hiburan (entertainment).
Sementara itu, ada yang melihat fungsi wayang lebih jauh lagi, yaitu sebagai alat untuk penularan nilai, dari satu ke lain generasi.
Sementara itu, ada yang melihat fungsi wayang lebih jauh lagi, yaitu sebagai alat untuk penularan nilai, dari satu ke lain generasi.
Dari sini wayang lebih serius menjadi bagian dari proses pelestarian masyarakat oleh masyarakat itu sendiri. Berbagai cara telah ditempuh oleh masyarakat untuk melestarikan diri, di antaranya melalui cara yang paling umum, yaitu cerita dongeng-dongeng (mitologi).
Mitologi bagi masyarakat yang masih primitif dituturkan hanya seperti dongeng biasa. Dari ibu ke anak, dari kakak ke adik, dia menjadi proses ketika semua anggota warga kongkow-kongkow di sekitar api unggun, dan hal itu menjadi bagian dari sistem kepercayaan.
Karena dengan sistem seperti itulah, kepercayaan kita tentang Tuhan, tentang segala macam itu terbentuk melalui proses penularan nilai-nilai itu.
Perilaku masyarakat dibentuk melalui cara penularan nilai tersebut.
Perilaku masyarakat dibentuk melalui cara penularan nilai tersebut.
Semakin kompleks dan rumit bentuk penularan nilainya, maka sebuah masyarakat akan semakin dikatakan tinggi cita rasa peradabannya. Wayang ini menjadi bagian dari proses masyarakat yang paling rumit yang terdapat dalam masyarakat yang sudah berperadaban tinggi.
Bagi orang Jawa, tidak peduli yang senang atau yang tidak senang wayang, mereka sudah terikat dengan nilai-nilai yang ada dalam wayang itu. Bisa jadi seseorang tidak bisa menikmati wayang, tapi sebagai orang Jawa dia harus baca, mendengarkan sana-sini.
Meskipun belum pernah menonton wayang seumur hidup, yang dia gunakan acuan untuk melakukan nilai-nilai tetap wayang. Misalnya nilai-nilai kesetiaan, keberanian, keikhlasan, keadilan dan seterusnya.
Contoh lain, Bung Karno kalau pidato sering mengutip wayang. Dia katakan kepada publik, kita ini jadi orang harus seperti Gatotkaca, padahal orang-orang di Jakarta tidak bisa membedakan mana yang Gatotkaca, mana yang tokoh lain. 

Tapi yang tertanam di benak publik, Gatotkaca pemberani. Inilah yang dikatakan wayang sebagai wahana penularan atau pemeliharaan nilai-nilai dari generasi ke generasi.
Penularan dan pemeliharaan nilai ini tidak gampang prosesnya, karena di dalam proses seperti itu harus terjadi perubahan-perubahan yang tidak bisa ditahan atau ditolak. Para dalang dan para penggemar wayang sama-sama harus mampu melakukan pilihan-pilihan;
mana yang harus dilestarikan dan mana yang diubah. Justru karena itulah muncul istilah pakem dan carangan. Karena dalam melakukan perubahan-perubahan itu kita harus merubah cerita dari pakemnya semula.
Selain untuk mentransfer nilai-nilai masyarakat, wayang juga dapat dipakai sebagai medium untuk meninjau hubungan antara negara dan warganya. Kewajiban-kewajiban warga negara, kewajiban-kewajiban para penyelenggara pemerintahan, semuanya mendapatkan tempat dalam cerita wayang.
Karena isi cerita wayang sebenarnya perihal perebutan tahta, yang berujung pada Mahabaratha atau Barathayuda.
Bahkan dalam cerita yang paling tidak terkait dengan keaslian wayang, yakni cerita Ramayana, di sanapun ada kisah seorang penyelenggara pemerintahan yang angkara murka
Bahkan dalam cerita yang paling tidak terkait dengan keaslian wayang, yakni cerita Ramayana, di sanapun ada kisah seorang penyelenggara pemerintahan yang angkara murka
berhadapan dengan ksatria yang membela kebenaran. Kalau cerita Ramayana saja sudah memasukkan hubungan antara penguasa dan yang dikuasai, maka Mahabaratha jelas sekali menyangkuat kekuasaan; bagaimana kekuasaan itu diselenggarakan.
Dari situlah lalu muncul kerangka kekuasaan. Siapa yang menonton lakon Parikesit (putra Abimanyu atau cucu Arjuna yang menjadi raja Astina pasca Mahabarata, red.), maka akan kenyang dengan nasihat-nasihat dan petuah-petuah tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang adil
Bagaimana menyelenggaraan pemerintahan yang bersih, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, membela yang lemah, dan menahan yang kuat agar jangan sewenang-wenang. Bagaimana memerintah dengan ikhlas mengabdikan diri.
Tapi ternyata, untuk mewujudkan pemerintahan yang seperti itu harus didahului dengan perjuangan. Perjuangan sang Abimanyu yang menceburkan diri ke dalam lautan pertarungan batin dan akal yang intensif guna nanti melahirkan sang Parikesit.
Dengan demikian, kita dapat melihat keseluruhan wayang dari sudut hubungan antara negara dan warganya. Dalam hal ini kita bisa melihat juga bahwa pada akhirnya wayang dapat juga dipakai untuk melakukan koreksi jangka panjang terhadap penyelenggaraan sebuah kekuasaan.
Wayang sebagai alat budaya dalam jangka panjang membentuk budaya politik.
Budaya politik yang secara lambat tapi pasti membentuk pendapat umum mengenai penyelenggaraan kekuasaan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat.
Budaya politik yang secara lambat tapi pasti membentuk pendapat umum mengenai penyelenggaraan kekuasaan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh