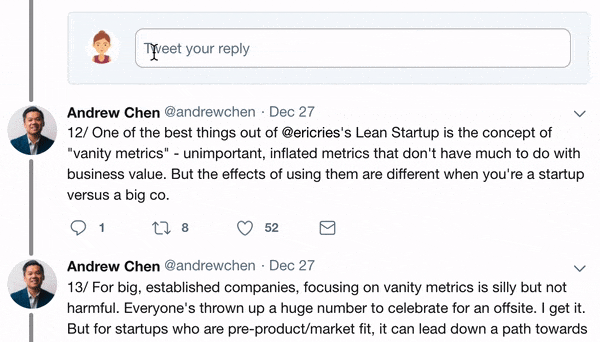Punya harapan untuk melihat tidak ada lagi polusi plastik yang terjadi di sekitar kita? Kita selangkah lebih dekat!
Baru-baru ini, pertemuan United Nation Environmental Assembly 5.2 di Nairobi, Kenya menghasilkan resolusi untuk perjanjian plastik global. Simak yuk.
Baru-baru ini, pertemuan United Nation Environmental Assembly 5.2 di Nairobi, Kenya menghasilkan resolusi untuk perjanjian plastik global. Simak yuk.

Pertemuan yang disingkat UNEA 5.2 ini diikuti oleh delegasi berbagai negara dan menjadi wadah untuk menyepakati berbagai prioritas kebijakan lingkungan hidup global, serta acuan pengembangan hukum lingkungan internasional.
Kabar baiknya: UNEA 5.2 menghasilkan resolusi untuk perjanjian plastik global yang berjudul “End Plastic Pollution: Toward an international legally binding instrument” yang diadopsi dari draft resolusi Peru-Rwanda.
greenpeace.org/africa/en/pres…
greenpeace.org/africa/en/pres…
Sebuah pengakuan yang jelas bahwa seluruh siklus hidup plastik, mulai dari ekstraksi bahan bakar fosil untuk produksi s/d pembuangan, telah menciptakan polusi yang berbahaya.
Juga dibahas tentang masalah konsumsi, desain kemasan daur ulang, ekonomi sirkular, hingga mikroplastik.
Juga dibahas tentang masalah konsumsi, desain kemasan daur ulang, ekonomi sirkular, hingga mikroplastik.
Resolusi ini tidak hanya mencakup polusi plastik di laut, tapi polusi plastik yang telah mencemari lingkungan secara lebih luas.
Mengakui bahwa polusi plastik berdampak negatif secara sosial dan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan, serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
Mengakui bahwa polusi plastik berdampak negatif secara sosial dan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan, serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

Momen penting untuk mengatasi polusi plastik belum selesai.
Resolusi dari UNEA 5.2 belum mengikat secara hukum & masih dinegosiasikan dalam forum negosiasi yang lebih tinggi, sebelum akhirnya menjadi perjanjian plastik global yang mengikat secara hukum pada tahun 2024.
Resolusi dari UNEA 5.2 belum mengikat secara hukum & masih dinegosiasikan dalam forum negosiasi yang lebih tinggi, sebelum akhirnya menjadi perjanjian plastik global yang mengikat secara hukum pada tahun 2024.
Sampai perjanjian global yang kuat ditandatangani, disegel, dan disampaikan, Greenpeace dan koalisi akan terus mendorong dunia yang bebas dari polusi plastik, demi mewujudkan dunia dengan udara bersih dan iklim yang stabil 💪
Mintalah para pemimpin dunia untuk mendukung #PlasticsTreaty global yang kuat. Kunjungi act.greenpeace.org/page/98946/pet…
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh