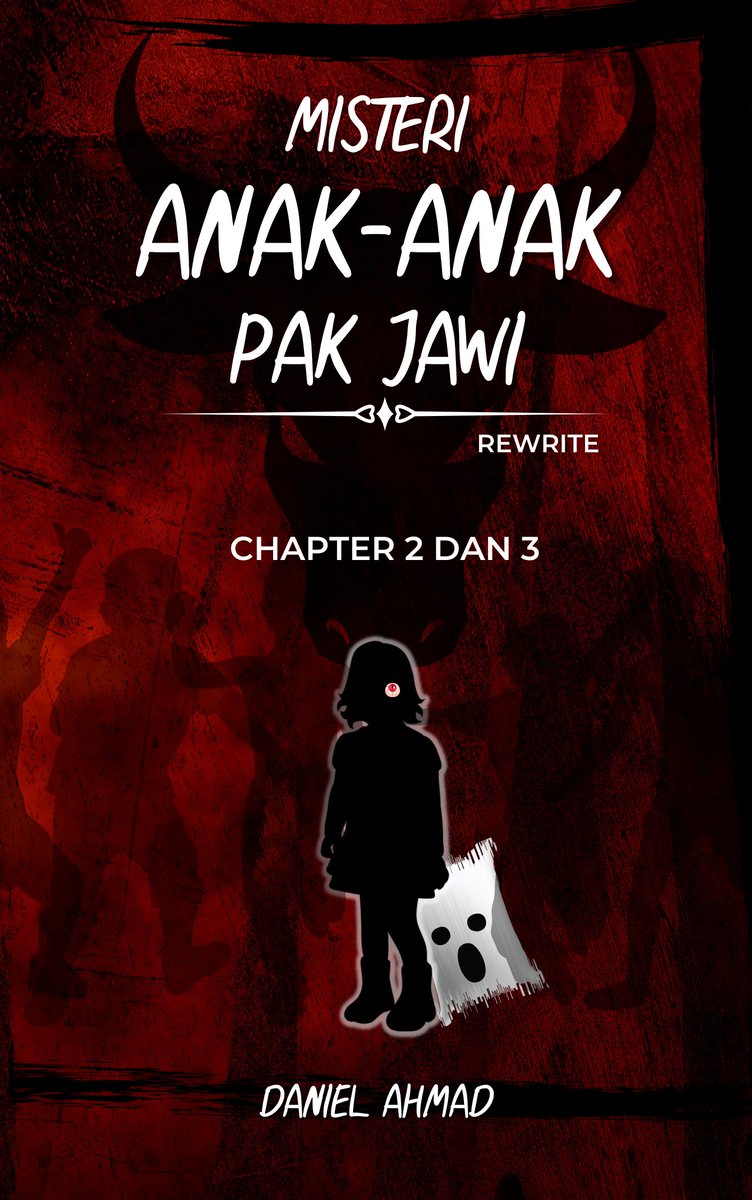MISTERI ANAK-ANAK PAK JAWI
CHAPTER 11 DAN 12
@bacahorror
@IDN_Horor
#threadhorror #bacahorror #timurtrilogi
CHAPTER 11 DAN 12
@bacahorror
@IDN_Horor
#threadhorror #bacahorror #timurtrilogi

Buat teman-teman yang belum baca Chapter sebelumnya.
https://twitter.com/DanieloAhmad/status/1539969843646312449?s=20&t=7AQuPkZsBMSNWESi6MG1tA
CHAPTER 11
Salah satu yang membuat kakek disegani warga adalah, dia seorang guru silat, meski tidak bisa dibilang begitu karena tidak punya murid. Aku malah baru tahu tentang ini setelah berada di pesantren. Salah seorang ustaz kenal dengan kakek.
Salah satu yang membuat kakek disegani warga adalah, dia seorang guru silat, meski tidak bisa dibilang begitu karena tidak punya murid. Aku malah baru tahu tentang ini setelah berada di pesantren. Salah seorang ustaz kenal dengan kakek.
Dia menceritakan pengalamannya yang pernah ditolak menjadi murid, karena tidak lulus ujian tahap pertama. Ustaz tidak bilang apa ujiannya.
Aku juga tidak sempat bertanya karena sampai sekarang pun tidak bisa membayangkan orang seperti kakek yang sering bertingkah kekanak-kanakan mengajar bela diri.
Selama ini juga aku hanya sering melihat kakek berkelahi dengan bapak, itu juga cuma saling pukul, tendang, banting, sama sekali tidak ada seni beladirinya.
Karena itulah aku tak habis pikir sore ini tiba-tiba saja ada seorang perempuan—lebih tepatnya gadis—yang datang ke rumah mengaku sebagai murid kakek.
Bukan hanya usianya yang janggal, penampilan gadis ini juga tidak biasa. Dia mengenakan baju hitam, celana silat hitam, kerudung hitam, dan bercadar merah.
Selain wajah yang tertutup, orangnya juga hemat bicara. Aku jadi kesulitan menebak usianya. Mungkin masih SMP, atau sudah SMA tapi orangnya memang pendek.
Berkali-kali aku suruh masuk, karena kakek masih salat asar, tapi tetap tidak mau. Sebagai tuan rumah, tidak elok kalau aku biarkan tamu duduk di undakan teras, sementara aku tinggal ke dalam.
Jadilah aku berdiri di ambang pintu, menunggu tamu aneh itu mau masuk, atau kakek yang lebih dulu keluar.
"Kakek kalau salat biasanya lama, mending nunggu di dalam," ucapku, ramah.
Gadis itu cuma mengangguk, tanpa bicara, tanpa menoleh, tanpa peduli kalau aku jadi jengkel dibuatnya.
Gadis itu cuma mengangguk, tanpa bicara, tanpa menoleh, tanpa peduli kalau aku jadi jengkel dibuatnya.
Akhirnya setelah hampir sepuluh menit, kakek keluar dari kamar. Pakaiannya tidak menunjukkan kalau sedang bersiap pergi ke acara penting. Rambutnya juga dibiarkan tidak terikat.
Putih kusam, gondrong sampai pundak. Kakek cuma mengenakan kaus putih berlengan pendek, dengan celana kain hitam, dan sandal jepit karet. Seperti hendak pergi ke ladang.
"Sudah lama nunggu?" tanya kakek pada tamunya di teras, tanpa mempedulikan aku yang sejak tadi duduk sebal di ambang pintu.
"Baru satu jam, Kak Tuan," ucap gadis itu.
"Baru satu jam, Kak Tuan," ucap gadis itu.
Akhirnya aku mendengar suaranya. Jelas dia lebih muda dariku. Lantas ada urusan apa seorang gadis seperti dia sama kakek?
"Dani, kakek pulangnya agak malam. Mau beres-beres rumah dulu. Kalau ada tamu, jangan kasih tahu kakek ada di mana."
"Dani, kakek pulangnya agak malam. Mau beres-beres rumah dulu. Kalau ada tamu, jangan kasih tahu kakek ada di mana."
"Iya," jawabku.
"Oh, ya, satu lagi. Obat dari Pak Ahsan sudah habis. Mungkin tinggal sekali minum—ma-maksud kakek, sekali pakai—Nanti kamu pesanin lagi ke sana, ya."
"Iya," jawabku, ketus.
"Oh, ya, satu lagi. Obat dari Pak Ahsan sudah habis. Mungkin tinggal sekali minum—ma-maksud kakek, sekali pakai—Nanti kamu pesanin lagi ke sana, ya."
"Iya," jawabku, ketus.
Kakek pergi bersama gadis itu. Jalan kaki. Kalau benar kakek mau pergi ke rumahnya yang ada di hutan, berarti mereka harus jalan kaki hampir satu kilometer.
Aku tahu kakek tidak bisa bawa motor, tapi kan ada sepeda. Ah, aku cuma bisa menghela napas. Delapan belas tahun, dan masih belum bisa memetakan jalan pikiran kakek yang rumit.
Tiba-tiba aku sadar akan sesuatu.
“Eh? APA? Aku disuruh ke rumah Pak Jawi lagi?”
***
“Eh? APA? Aku disuruh ke rumah Pak Jawi lagi?”
***
Sesuai permintaan kakek, aku terpaksa kembali ke rumah Pak Jawi. Kalau bukan karena khawatir dengan luka mengerikan di punggung kakek itu, tentu aku tidak mau disuruh.
Kakek pasti kesakitan. Apalagi selama ini dia tinggal sendiri dan tidak ada yang merawat. Karena itu, selagi kakek masih di rumah, aku ingin merawatnya dengan sungguh-sungguh.
Aku berangkat sesegera mungkin, selagi masih pukul setengah empat sore, dan masih ada cukup cahaya matahari. Kali ini aku bawa motor butut bapak agar cepat sampai, dan cepat juga kaburnya. Padahal hanya mau memesan obat, tapi rasanya seperti mau berangkat perang.
Gang tanpa nama sudah kelihatan, atau haruskah aku menyebutnya Gang Kadal? Entah kenapa disebut demikian. Padahal tidak ada papan nama, tidak ada gambar kadal. Benar-benar nama yang aneh untuk sebuah gang.
Tidak seperti kemarin, kali ini aku langsung berbelok masuk tanpa harus berhenti di mulut gang hanya untuk menyiapkan mental. Aku tahu apa yang harus aku hadapi, dan karena ini masih siang, aku tahu tidak ada yang perlu ditakuti.
Akhirnya kembali ke sini lagi; rumah Pak Jawi. Kejadian malam itu telah mengubah cara pandangku pada gubuk tua ini. Hampir tidak ada lagi perasaan iba melihat kondisi hunian si tabib yang bobrok.
Bagiku, tempat ini adalah keramat yang setiap sisinya tidak bisa sembarangan kusentuh, serta tidak bisa sembarangan bicara apalagi mengungkit soal anak dan ibu.
Kulewati keenam ayunan yang bergeming di bawah pohon mangga. Di salah satunya terdapat bantal putih pembawa sial yang melihatnya saja aku langsung terbayang wajah anak-anak itu, terutama wajah si mencong.
Bantal putih itu adalah mainannya. Ia bahkan membawanya waktu berkunjung ke rumah. Memeluk bantal itu seperti boneka kesayangan, tersenyum aneh padaku yang ketakutan di balik dinding kaca. Membayangkan itu saja, rasanya aku ingin segera pulang.
Aku menoleh ke belakang, karena tiba-tiba salah satu dari keenam ayunan itu bergerak. Maju mundur sendiri tanpa ada yang duduk, tanpa ada yang dorong.
Angin adalah terkaan paling positif yang pertama kali terpikir olehku. Namun, ayunan yang bergerak adalah yang ada bantal putihnya. Benar-benar kebetulan yang mengerikan. Bahkan angin pun seolah ingin menakutiku.
Hal selanjutnya yang kuperhatikan adalah kandang sapi. Sore ini tidak lagi ada rumput di tempat pakannya, dan seperti biasa, tidak ada sapinya. Ke mana perginya rumput itu? Siapa yang makan? Kalau tidak dimakan, lantas untuk apa?
Aku sempat membayangkan rumput itu dikonsumsi oleh anak-anak Pak Jawi karena terlalu miskin untuk membeli beras, tapi tebakan itu terlalu liar. Terlepas dari semua keanehan keluarga Pak Jawi, tidak seharusnya aku memandang mereka serendah ini.
Dari halaman, kulihat Pak Jawi sedang duduk di teras rumahnya. Kakek itu sudah menyadari kedatanganku. Ia letakkan segala kesibukannya dan berdiri menyambut.
Aku nyaris tercengang melihat Pak Jawi berdiri dengan postur bungkuknya lagi, padahal jelas-jelas malam itu dia bisa berdiri tegap.
Kakek itu cukup tinggi untuk meraih kantong plastik yang terselip di salah satu tiang rumah. Sekarang, aku seolah melihat persona yang berbeda. Pak Jawi yang tegap dan dingin saat malam hari, dan kakek ringkih dan ramah di siang hari.
"Assalamualaikum, Mbah."
"Waalaikumsalam, mari masuk."
"Waalaikumsalam, mari masuk."
Pak Jawi menyambutku dengan dengan ramah tamah seperti biasa, tersenyum di balik lebatnya kumis dan jenggot putih. Tuan rumah seperti ini membuat tamunya merasa dihargai, hingga kursi karet pun terasa nyaman diduduki.
Berbeda dengan beberapa rumah orang kaya yang pernah ku kunjungi. Tuan rumah yang tidak bersahabat, senyum yang dipaksakan, dan nada bicara yang seolah-olah ingin aku segera pulang. Yang seperti itu, walau semewah apa pun ruang tamunya, tidak akan ada yang betah duduk lama-lama.
"Gimana kabar Kang Saleh?" tanya Pak Jawi.
"Alhamdulillah, Kakek sehat, Mbah, tapi, ya itu, luka di punggungnya belum juga sembuh."
"Alhamdulillah, Kakek sehat, Mbah, tapi, ya itu, luka di punggungnya belum juga sembuh."
Pak Jawi menundukkan wajah. Mendesah, lesu, seperti orang kecewa. Ia mencoba duduk dengan susah payah. Aku yang lebih dulu duduk sempat mengangkat pantat lagi untuk membantunya, tapi tangan Pak Jawi seolah memberi isyarat; tidak usah! Saya bisa melakukannya sendiri.
Ia pun duduk dengan santai pada kursi karet di depanku yang hampir patah. Kakinya berkarat dan berderik, membuatku ngeri membayangkan kakek tua ini jatuh dari kursi.
"Obat yang kemarin masih ada?" tanya Pak Jawi.
"Sudah habis," jawabku.
"Sudah habis," jawabku.
Pak Jawi mengerutkan kening. Sepertinya dia heran kenapa obat kakek cepat habis. Ia lalu memainkan jenggotnya. Membuang pandangan jauh ke samping seperti sedang memikirkan sesuatu.
"Kang Saleh tidak pernah mau disuruh datang ke sini. Padahal mau saya periksa langsung, biar pengobatannya lebih manjur, gitu. Soalnya, orang-orang yang kena penyakit seperti itu cuma habis satu-dua botol, besoknya sudah sembuh."
Ya, jelas. Mereka, kan tidak minum obatnya. Cuma kakek saja yang aneh, batinku. Sebaiknya aku tidak memberitahu Pak Jawi soal ini. Malu.
"Akhir-akhir ini sudah jarang yang berobat. Saya juga jarang sekali meracik obat. Kalau dulu, biasanya sehari bisa sampai sepuluh pasien lebih," tutur Pak Jawi.
Mendengarnya membuatku kasihan. Tapi, terlalu dini bagiku untuk bertanya lebih jauh karena kami tidak seakrab itu. Sejauh ini, obrolan kami hanya sebatas basa-basi seorang tabib dengan pasiennya,--
--dan di sela basa-basi itu, sesekali aku mencuri pandang ke dalam rumah, melalui celah kain yang tertiup angin. Seperti biasa, di dalam gelap.
Aku masih menaruh curiga kalau keenam anak itu ada di dalam, dan hanya boleh keluar saat malam. Namun, gubuk ini bahkan sangat sempit untuk Pak Jawi seorang. Bagaimana bisa dia berbagi tempat dengan enam anak itu?
Muncul sepercik keberanian untuk bertanya, sekaligus mengadukan kelakuan anak-anak Pak Jawi yang menurutku sudah melewati batas. Baru juga hendak memulai, Pak Jawi mendahuluiku bicara.
"Seperti biasa, Nak. Saya harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Kali ini bisa memakan waktu seharian. Kamu datang saja besok sore, atau habis salat magrib, tapi jangan lewat dari jam 8 malam."
"Baik, Mbah. Di rumah juga masih ada sisa, kok, mungkin cukup untuk sehari."
Tidak ada alasan untuk berlama-lama di rumah Pak Jawi. Aku pun pamit pergi. Kutelan kembali semua rencana untuk memperpanjang obrolan.
Tidak ada alasan untuk berlama-lama di rumah Pak Jawi. Aku pun pamit pergi. Kutelan kembali semua rencana untuk memperpanjang obrolan.
Meski gundah karena keluhanku tak tersampaikan, tapi ada rasa lega karena tidak jadi membahas sesuatu yang menurutku berisiko menyakiti perasaan orang tua ini.
Pak Jawi hendak mengantar kepergianku. Dia bangun dari tempat duduknya, dan tanpa sengaja kaki Pak Jawi tersandung kaki meja hingga nyaris terjungkal. Beruntung aku sempat memeganginya, memapahnya sebelum ambruk, barulah aku merasa ada yang tidak beres dengan tubuh kakek ini.
"Sa-Sampean nggak apa-apa, Mbah?" tanyaku.
"Iya, ti-tidak apa-apa."
"Iya, ti-tidak apa-apa."
Kubimbing Pak Jawi kembali ke tempat duduknya. Kursi karet itu sampai berdecit. Terdengar sedikit bunyi retak dari keempat kaki kursi tua yang makin mempertegas dugaan di kepala.
"Nggak usah diantar, Mbah. Sampean duduk saja. Saya pamit dulu, Assalamulaikum."
"Waalaikumsalam."
"Nggak usah diantar, Mbah. Sampean duduk saja. Saya pamit dulu, Assalamulaikum."
"Waalaikumsalam."
Kalau dipikir-pikir, setiap kali pulang dari tempat ini, langkahku selalu terburu-buru. Ada saja sesuatu yang membuatku ingin segera pergi dari rumah Pak Jawi. Waktu itu ingin cepat pulang karena merasa diawasi, lalu ingin cepat sampai rumah karena diancam anak-anak Pak Jawi,--
--sekarang setelah sempat bingung dengan postur Pak jawi yang kadang bungkuk dan kadang tegap, aku kembali dibuat bingung oleh berat badan Pak Jawi yang tidak wajar. Kakek itu ... dia jauh lebih berat dari yang ku kira. Bahkan kursinya hampir patah karena menahan beban tubuhnya.
CHAPTER 12
Malam datang membawa serta awan-awan mendung yang memperkelam langit hitam dan menyembunyikan bintang. Aroma embusan angin mulai berbau tanah, pertanda hujan akan turun. Segera kuselamatkan semua pakaian yang masih tergantung di kawat jemuran,--
Malam datang membawa serta awan-awan mendung yang memperkelam langit hitam dan menyembunyikan bintang. Aroma embusan angin mulai berbau tanah, pertanda hujan akan turun. Segera kuselamatkan semua pakaian yang masih tergantung di kawat jemuran,--
--serta memasukkan semua alas kaki yang ada di teras. Dalam kesendirian, sambil merengkuh kebosanan, kubiarkan televisi membuat keributan, dan berpikir kalau ini adalah waktu yang buruk untuk liburan.
Aku mulai sedikit menyesal karena tidak ikut bapak dan ibu ke rumah saudara. Kupikir mereka tidak akan lama, ternyata mereka harus tinggal sampai lebih dari sepekan.
Salah satu alasan aku tidak ikut, dan memilih tinggal di rumah adalah, agar bisa melepas kangen dengan teman-teman masa kecil. Gerombolan bocah berbau kecut telanjang dada yang dulu sering berlarian di desa saat pulang dari madrasah,--
--mengejar layangan putus hingga nyaris ditabrak becak, mengotori teras tetangga, bermain di sungai dan pulang sambil berkompetisi serdawa, menunggu dengan setia kedatangan tukang mainan, walaupun tidak pernah beli karena tidak punya uang.
Naifnya, aku tak menyadari bahwa terlalu lama kami terpisah, hingga waktu telah mengikis keakraban. Banyak dari teman-temanku telah pergi merantau. Mereka yang masih tinggal pun telah menjadi orang asing.
Sebagian sudah berkeluarga, tentu mereka lebih memilih bermain dengan anak dan istri daripada duduk mengobrol denganku tentang masa kecil.
Cukup lama aku termenung, hingga nyaris saja tertidur di depan televisi. Film kungfu ini membuatku mengantuk, dialognya membosankan dan adegan berantemnya terlalu berlebian.
Ceritanya juga mudah ditebak; maksudku, orang-orang berbaju hitam, berjenggot dan bersuara serak itu akhirnya pasti mati. Tipikal penjahat di film-film laga. Pahlawan selalu menang, gadis dan keluarga yang diculik selalu bisa diselamatkan, dan ....
PADAM?
Rumah mendadak gelap. Lampu indikator televisi pun perlahan redup dan hilang. Bersamaan dengan itu, suara hujan di luar mulai jelas terdengar.
Beruntung aku sudah mempersiapkan datangnya hujan, hanya padam ini saja yang luput dari perkiraan, dan aku sama sekali tidak punya persiapan.
Aku bangun sambil berpegangan pada dinding. Badan sedikit pegal karena tidur di lantai beralaskan kasur tipis. Sebelum pergi mencari lilin, kupastikan televisi sudah dalam keadaan mati.
Tidak ingin kaget tengah malam karena televisi yang tiba-tiba hidup saat listrik kembali menyala nanti. Sekarang, di mana kakek menyimpan senternya?
“Oh, iya. Senternya dibawa kakek buat ronda keliling. Bagus, sekarang aku harus berjalan seperti orang buta,” gerutuku.
Kucari lilin yang aku sendiri tidak tahu di mana, pun ada atau tidaknya di rumah ini. Langkahku penuh kehati-hatian agar tidak menyenggol perabotan keramik, atau salah-salah jempol kakiku kesandung kaki lemari.
“Aduh! Sial, baru saja aku bilang sudah kesandung beneran”
Sebentar kuberhenti untuk menghilangkan nyeri. Lemari yang kutendang barusan ada di samping pintu kamar kakek. Setidaknya berkat kecelakaan kecil itu, aku jadi menemukan lilin meski cuma sebatang. Tinggal berharap padamnya tidak terlalu lama.
Lilin ini tidak akan bertahan melewati tengah malam. Belum lagi, aku hanya punya sebatang, dan sedang bingung di mana pelita ini harus kuletakkan.
Kunyalakan lilin menggunakan korek, dengan segera cahaya menerangi sebagian ruang televisi. Kuncup apinya bergoyang-goyang karena tertiup angin yang masuk melalui jendela di ruang televisi. Kuteteskan lelehan lilin pada tutup stoples, kurekatkan batangnya agar bisa kubawa.
Kututup jendela yang terbuka agar air hujan tidak bertempasan ke dalam. Sesaat kulihat betapa gelapnya di luar. Untuk sebuah rumah yang berada di dekat hutan, padam saat malam adalah sebenar-benarnya cobaan,--
--sedangkan aku hanyalah sosok lemah yang sedang meratapi sunyi dan gelapnya kesendirian. Suara kendaraan besar yang bising saat siang, terasa jadi berkah di situasi seperti ini.
Setidaknya masih ada suara selain bunyi tetes hujan di atap, dan setidaknya kendaraan yang lalu-lalang itu membuatku tidak merasa tinggal di antah berantah.
Di antara paduan suara hujan dan kendaraan di jalan besar, ada satu suara yang seharusnya tidak kudengar. Tidak di rumah, tidak di sekitar sini, tidak pula malam-malam begini.
“Itu suara lonceng sapi?”
Kami tidak memelihara sapi. Di sekitar rumah pun tidak ada sapi, karena tidak ada tetangga. Rumah terdekat dari sini berjarak hampir tiga ratus meter. Kalaupun mereka memelihara sapi, tidak mungkin hewan itu main sampai ke sini, malam-malam begini.
Kami tidak memelihara sapi. Di sekitar rumah pun tidak ada sapi, karena tidak ada tetangga. Rumah terdekat dari sini berjarak hampir tiga ratus meter. Kalaupun mereka memelihara sapi, tidak mungkin hewan itu main sampai ke sini, malam-malam begini.
Aku merasa sedikit konyol karena terlalu memikirkan sapi di saat harusnya memikirkan listrik. Namun, setelah semua yang kualami, lonceng sapi adalah hal terakhir yang ingin kudengar dalam situasi seperti ini.
Tidak banyak yang bisa kulakukan selain menunggu padam selesai. Tinggal memikirkan apa yang harus kuperbuat agar proses menunggu ini tidak membosankan. Televisi yang merupakan satu-satunya sumber hiburan mati.
Tidak bisa membaca buku karena tidak ada lampu. Tidak bisa tidur karena waswas. Hanya berharap padam ini tidak berlangsung lama, karena aku bisa gila kalau harus bengong dalam gelap selama lebih dari satu jam.
Bunyi lonceng itu terdengar kembali, dan kali ini tidak bisa kuabaikan karena bunyinya seperti berasal dari dalam rumah. Perasaanku mulai tak keruan.
Pikiranku langsung tertuju pada satu hal, dan aku benci membayangkannya. Bebunyian yang tak seharusnya terdengar seram, jadi punya kesan berbeda buatku. Belum lagi sekarang telingaku menangkap suara lain yang berasal dari dapur.
Ada sesuatu yang jatuh, berdebum cukup keras, terlalu keras untuk seekor tikus. Api kecil di lilinku bergoyang-goyang seirama dengan gemetarnya tangan. Kaki kananku melangkah maju untuk memeriksa, tapi kaki kiri ini seolah jadi pecundang yang memilih kabur.
Konflik batin ini makin kuat antara menjadi tuan rumah yang bertanggungjawab dan memastikan suara itu bukan berasal dari maling, atau tetap menjadi pengecut yang sadar akan situasi dan memilih tidak peduli.
SA... KIT....
Aku terbelalak. Itu suara manusia. Lebih tepatnya anak kecil. Merintih, lirih, seperti sedang menahan sakit. Tebakanku benar, suara itu berasal dari dapur, dan suara itu jadi pemicu langkahku yang sempat tertunda.
Setengah tak sadar aku sudah berjalan meninggalkan ruang televisi untuk menuju dapur. Membawa serta satu-satunya sumber penerangan.
Dapur di rumahku lebih luas dari ruang mana pun. Lilin yang kubawa tak langsung menjamah semua sudut. Bahkan setelah berdiri hampir di tengah ruangan, masih saja ada beberapa titik gelap.
Di sebelah kananku ada tiga lemari besar tempat ibu menyimpan piring, gelas, dan semua peralatan makan. Di depanku ada dinding yang digantung banyak sekali peralatan masak.
Di sebelah kiri ada meja makan, dan di sudutnya ada dua kamar mandi, tepat di samping pintu tripleks yang saat ini sedang terbuka lebar, menegaskan dugaanku bahwa seseorang sudah masuk ke dapur.
SA ... KIT ...
Sekarang aku bisa mendengar dengan jelas, suara itu berasal dari bawah meja makan. Pelan kudekati. Gemetar tak tertahan. Aku punya gambaran jelas siapa yang akan aku temui di bawah meja, tapi tetap tidak bisa meredam ketakutan.
Begitu di depan meja, aku duduk jongkok. Seketika lilin di tanganku menyorot sosok di bawah meja makan. Seorang anak kecil sedang duduk sambil membenamkan wajahnya ke bantal putih yang dia peluk. Benar dugaanku, anak ini adalah si Mencong. Satu-satunya anak perempuan Pak Jawi.
"Nga-ngap-ngapain kamu di sini?” tanyaku sedikit membentak.
Alih-alih menjawab. Anak ini malah makin tersedu-sedu sambil berkali-kali mengeluhkan sakit.
Aku mulai meraih kembali sedikit keberanian, dan semuanya kugunakan untuk melampiaskan kekesalan.
Alih-alih menjawab. Anak ini malah makin tersedu-sedu sambil berkali-kali mengeluhkan sakit.
Aku mulai meraih kembali sedikit keberanian, dan semuanya kugunakan untuk melampiaskan kekesalan.
“Kamu nggak boleh masuk rumah orang sembarangan! Apalagi malam-malam gini. Sekarang, pulang!” tandasku sambil mengacungkan jari telunjuk ke arah pintu. Anak itu berhenti menangis.
Pelan ia mengangkat wajah, lalu tampaklah separuh wajahnya yang tertutup rambut lepek itu sedang berlumur darah. Aku pun terhenyak. Jatuh duduk di lantai.
Si Mencong merangkak ke luar dari bawah meja makan. Makin dekat dia ke lilin yang kupegang, makin jelas bagaimana wajahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, si Mencong pergi sambil menyeret bantal putihnya yang penuh bercak darah.
Ia melewati pintu tripleks, menuju ke lorong tempat menjemur pakaian. Penasaran karena di sana tidak ada pintu keluar, aku mengikutinya sampai ke ambang pintu, dan tercengang karena si Mencong yang baru saja keluar, kini sudah hilang tak kasat wujudnya.
Tidak hanya itu. Lamat-lamat di ujung lorong, di samping tiang jemuran, ada sosok lain yang sedang berdiri. Dari ambang pintu hanya tampak seperti bayangan, hitam, dan karena posturnya pendek, aku asumsikan itu sosok anak-anak.
Hanya saja, lambat laun sosok itu menghilang, tak membekas, tak meninggalkan apa pun selain bunyi lonceng sapi yang perlahan terdengar menjauh.
Sudah cukup. Pintu tripleks aku tutup. Kuraih kembali lilin yang tergeletak di lantai, lalu berjalan cepat menuju kamar sambil mengusap wajah yang basah karena berdiri di pintu saat hujan deras masih menggempur desa.
Selanjutnya, kuterima nasib sial malam ini. Aku tidur di ruang tamu, sembunyi di balik selimut, menggigil dingin, gemetar takut, terus begitu sampai listrik kembali menyala sekitar pukul dua dini hari.
Bersambung minggu depan, yak. Terima kasih sudah membaca sampai sejauh ini.
Terima kasih juga untuk yang sudah mendukung di Karyakarsa. Di sana, kisah ini sudah sampai Chapter 14.
karyakarsa.com/ahmaddanielo/m…
karyakarsa.com/ahmaddanielo/m…
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh