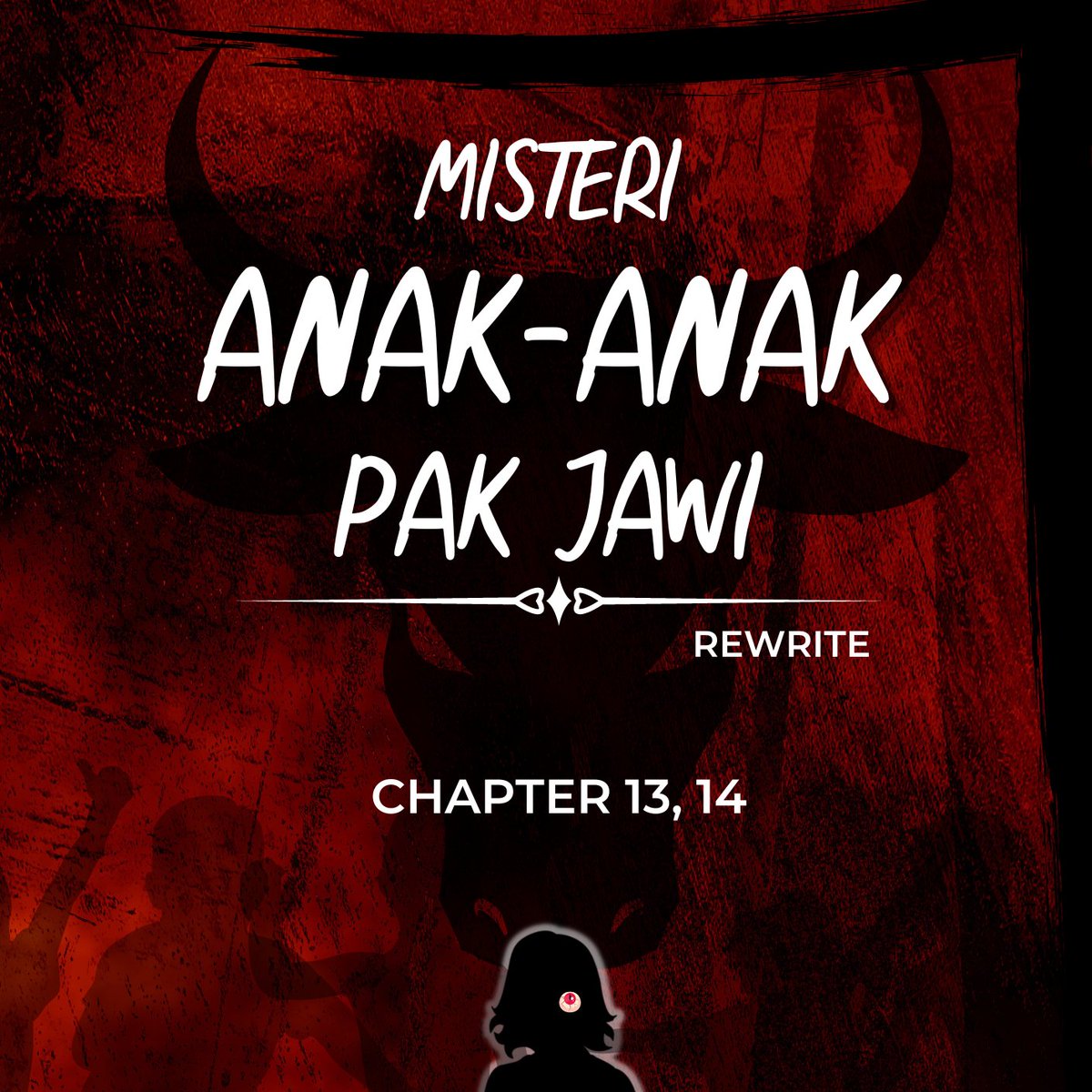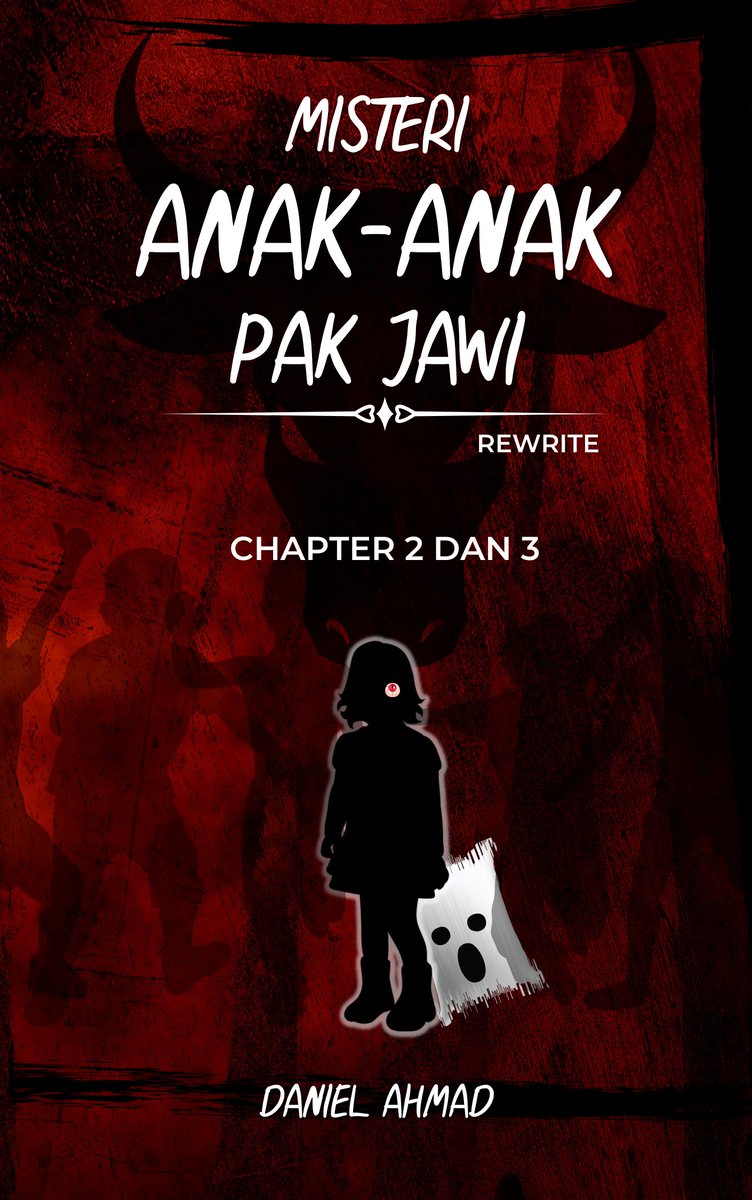Buat teman-teman yang belum baca chapter sebelumnya
https://twitter.com/DanieloAhmad/status/1539969843646312449?s=20&t=GR4MYyzAs_cxfA7TBu5VBw
CHAPTER 13
Pagi ini rumah Pak Mursid sedang ramai dikunjungi warga. Mereka berdesakan masuk ke halaman rumah demi menyaksikan sendiri peristiwa yang jadi sumber keramaian. Tadi malam, tepat ketika listrik padam, seekor sapi milik Pak Mursid raib dicuri.
Pagi ini rumah Pak Mursid sedang ramai dikunjungi warga. Mereka berdesakan masuk ke halaman rumah demi menyaksikan sendiri peristiwa yang jadi sumber keramaian. Tadi malam, tepat ketika listrik padam, seekor sapi milik Pak Mursid raib dicuri.
Kabarnya, kasus pencurian ternak di Sumbergede meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dan sapi Pak Mursid adalah yang ketiga di bulan Februari ini. Ditambah lagi isu santet yang belum reda, membuat warga Sumbergede makin resah.
Selain polisi, kulihat ada beberapa tokoh dari pesantren Sokogede yang juga hadir, tapi tidak lama, setelah itu mereka pulang. Biasanya pesantren jarang turun tangan menangani kasus pencurian,
kecuali kasus kali ini sudah terlalu besar dan berpotensi membuat kekacauan yang lebih parah. Pesantren Sokogede tidak sekadar tempat menimba ilmu. Faktanya, Desa Sumbergede ada dan berkembang seperti sekarang juga berkat pengaruh besar pesantren Sokogede.
Dulunya daerah ini adalah hutan belantara, sebelum seorang ulama kharismatik datang membabat hutan untuk mendirikan sebuah pesantren, yang kemudian menjadi besar, dan akhirnya melahirkan Desa Sumbergede. Hutan di samping rumahku adalah sisa-sisa dari hutan tersebut.
Bicara tentang hutan, selain Hutan Sumbergede yang jadi batas bagian barat desa, sekitar tujuh kilometer ke arah timur juga terdapat Hutan Tambalur yang membentang luas, memisahkan kabupaten Patokan dengan kabupaten Gandrung. Mungkin,--
--letak geografis Sumbergede—dan beberapa desa di kecamatan yang sama—yang diapit dua hutan inilah yang membuat pencurian ternak makin marak. Sering kudengar para pencuri ternak kabur lalu menghilang di hutan.
Namun, kasus yang menimpa Pak Mursid bisa dibilang aneh, tak lazim, bahkan cenderung mengerikan. Alih-alih membawa kabur sapi curiannya, pencuri kali ini justru memakannya mentah-mentah dan meninggalkan bangkai sapi tersebut di tengah hutan Sumbergede.
Kini aku berada di antara kumpulan para petinggi desa. Kami bermusyawarah di dalam rumah Pak Mursid. Sebisa mungkin merahasiakannya dari warga yang masih gaduh di halaman.
Mengenai bagaimana aku bisa tergabung dalam kelompok elit ini, ya, itu karena kakek menyeretku masuk ke dalam rumah Pak Mursid, setelah memaksaku bangun pagi, dan minta diantarkan ke sini, karena kakekku tidak bisa bawa motor sendiri.
“Pas ketemu di hutan Sumbergede, sapinya sudah mati, tapi kondisinya yang sangat janggal. Dua kakinya patah, lidahnya terpotong, bola matanya dicungkil, isi perutnya terburai, dan sebagian besar daging sudah habis,” tutur Pak Mursid.
Perutku bergejolak, karena Pak Mursid mendeskripsikannya terlalu detail.
“Jadi, sapinya dimangsa hewat buas begitu?” tanya salah satu aparat desa. Dia yang waktu itu pergi ke rumah mencari bapak, dan yang datang menjenguk Sugik bersama Pak Edi.
“Jadi, sapinya dimangsa hewat buas begitu?” tanya salah satu aparat desa. Dia yang waktu itu pergi ke rumah mencari bapak, dan yang datang menjenguk Sugik bersama Pak Edi.
Sekarang aku ingat, Namanya kalau tidak salah, Yudis.
“Beda, Le’,”(Ale’/Alek, berarti adik dalam bahasa madura) sanggah Pak Mursid. “Saya sering keluar masuk Hutan Tambalur dan Sumbergede, saya tahu persis gimana bangkai hewan yang habis dimangsa.
Nah, ndak tanda-tanda seperti itu di sapi saya. Luka-lukanya rapi, sama sekali tidak seperti dicabik taring, malah seperti dipotong pakai pisau atau benda tajam lainnya.”
“Sampean masih ngotot kalau pelakunya adalah manusia?” tanya Mbah Sopet.
“Lah, jelas! Saya juga yakin pencurinya bukan cuma satu, tapi berkelompok. Lagian di hutan Sumbergede ndak ada hewan buas.” Pak Mursid terdengar sangat yakin.
“Lah, jelas! Saya juga yakin pencurinya bukan cuma satu, tapi berkelompok. Lagian di hutan Sumbergede ndak ada hewan buas.” Pak Mursid terdengar sangat yakin.
“Pak Mursid benar. Ada banyak jejak kaki di sekitar kandang sapi,” tutur Pak Edi.
Lagi-lagi Pak Edi. Kenapa setiap kali ada kasus di desa ini, dia selalu ikutan. Aku mengerti dia adalah ketua RT, tapi Pak Mursid tinggal di RT yang berbeda dengannya. Bisa dibilang, ini di luar tanggung jawab Pak Edi.
Sepertinya benar dugaanku, orang ini ambisi sekali menjadi kepala desa, makanya sebelum pemilihan dimulai, dia sengaja cari panggung biar dianggap orang yang punya banyak kiprah di masyarakat.
“Tadi sudah diperiksa polisi?” tanya Mbah Sopet.
“Tadi sudah diperiksa polisi?” tanya Mbah Sopet.
“Kayaknya sudah, tapi karena mereka datangnya lambat, jejak kaki itu sudah bercampur sama jejak kaki warga yang datang menonton, tapi saya sempat lihat jejak kakinya. Percaya atau tidak, jejak kakinya kecil. Seperti jejak kaki anak-anak,” pungkas Pak Edi.
Setelah penuturan Pak Edi, hampir semua yang hadir di rumah Pak Mursid saling berbisik, seolah mereka menemukan sebuah petunjuk. Gelagat orang-orang ini membuatku lagi-lagi mencurigai seseorang.
Aku berhenti konsentrasi, tidak lagi mengikuti arah diskusi. Lagipula, sejak tadi hanya kakek saja yang tidak bicara. Tidak sekadar memberi tanggapan atau solusi, kakek justru sibuk makan dan minum kopi.
Bikin malu saja, gerutuku dalam batin.
“Apa?” tanya kakek saat sadar bahwa aku memperhatikannya dengan wajah sinis. Mulutnya sedang sibuk mengunyah pisang goreng.
“Apa?” tanya kakek saat sadar bahwa aku memperhatikannya dengan wajah sinis. Mulutnya sedang sibuk mengunyah pisang goreng.
Benar-benar bikin malu, Pikirku seraya membuang muka. Saat itulah aku lihat ada seekor monyet sedang duduk di hadapanku, di depan sepiring kue yang sejak tadi tidak kusentuh. Monyet kecil ini melihatku lalu menampakkan barisan giginya seperti sedang mengejek.
Tidak ada yang keberatan dengan kehadiran seekor monyet, karena semuanya tahu kalau ini bukan primata sembarangan. Pemilik monyet ini adalah orang yang sejak tadi diam memainkan jenggot tipisnya.
Pria tua yang punya wajah sangar, berkulit gelap dengan bekas luka di pipi, dan mengenakan ikat kepala bercorak loreng macan. Orang itu juga yang kemarin malam datang ke rumah bersama Mbah Sopet. Oh, aku ingat sekarang, namanya Gusafar. Dia salah satu sahabat kakek.
“Yang aku heran,” Pak Edi menyambung kembali. “Bukannya di hutan Sumbergede ada Kang Gusafar, kok bisa itu maling kabur ke sana tapi tidak ketahuan? Apalagi kalau lihat kondisi sapinya Pak Mursid, butuh waktu lama untuk melakukannya. Harusnya Kang Gusafar melihat pelakunya, kan?”
Kang Gusafar yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara karena namanya disebut. Monyet di hadapanku pun langsung berlari ke pangkuannya.
“Hujan deras menyegarkan pepohonan di hutan. Angin membelai dedaunan, membuatnya berayun santai. Setelah itu, hutan seperti mati, damai, dan tak ada bising geraman kera-kera liar.”
Orang-orang dibuat melongo oleh komentar Kang Gusafar. Aku pun demikian. Bukannya menjawab pertanyaan Pak Edi yang terkesan menyudutkan, dia malah berpuisi sambil membelai kepala monyetnya.
“Ma-maksudnya?” tanya Pak Yudis.
“Ma-maksudnya?” tanya Pak Yudis.
“Maksudnya, semalam dia tertidur, soalnya habis hujan bikin ngantuk,” jawab Mbah Sopet, kesal.
Kakek pun terbahak-bahak dibuatnya.
“Terus apa hubungannya sama kera-kera liar?” tanya Pak Edi, dongkol.
“Ya, keranya itu sampean,” celetuk kakek seraya menyambung tawa.
Kakek pun terbahak-bahak dibuatnya.
“Terus apa hubungannya sama kera-kera liar?” tanya Pak Edi, dongkol.
“Ya, keranya itu sampean,” celetuk kakek seraya menyambung tawa.
Konferensi orang-orang tua yang sedang membahas maling pun kocar-kacir karena semuanya tertawa, kecuali Pak Edi yang cemberut memandang kakek. Ya, di ruangan ini cuma kakek yang berani terang-terangan menghina orang, dan tidak ada satu pun yang berani protes.
“Kamu jangan ikut ketawa, Gus!” tegur Mbah Sopet. “Rumahmu kan di hutan, harusnya kamu lebih tanggap sama kejadian seperti ini, bukannya malah tidur!”
Kang Gusafar menunjuk kakek. Mungkin bermaksud membela diri, karena bukan cuma dirinya yang punya rumah di hutan, tapi kakek juga.
“Saleh sudah beberapa hari ini tinggal di rumah Karim, jadi jangan nyalahin dia!” bela Mbah Sopet.
Butuh beberapa saat sampai diskusi kembali kondusif. Tampaknya setelah ini orang-orang akan mempertimbangkan mengajak kakek, Mbah Sopet, dan Kang Gusafar dalam rapat serius. Terutama Pak Edi, dia tidak lagi cerewet setelah dibilang monyet.
Rapat berlanjut dan selesai tanpa keputusan yang jelas. Pak Mursid bilang akan menyerahkannya pada polisi, tapi di balik itu, aku merasa orang-orang sedang merencanakan sesuatu. Rencana yang sangat penting sampai-sampai kakek menyuruhku menunggu di luar.
***
“Kenapa mukamu kusut begitu?” tanya kakek, setibanya kami di rumah.
“Nggak tahu. Mungkin gara-gara barusan ada orang tua yang kerjaannya cuma makan melulu.”
“Nggak tahu. Mungkin gara-gara barusan ada orang tua yang kerjaannya cuma makan melulu.”
Tawa Kakek meledak. Dia benar-benar tidak merasa malu apalagi berdosa. Tangannya menepuk-nepuk punggungku dengan keras sampai aku kesal dibuatnya.
“Jangan terlalu serius,” kata Kakek menyudahi tawanya, “Yang banyak bicara belum tentu bekerja,” lanjutnya.
Sebelum kakek masuk ke kamar untuk tidur siang, aku rasa ada hal penting yang harus kutanyakan lebih dulu. Aku berniat menyembunyikannya dari kakek, tapi setelah kejadian yang menimpa Pak Mursid, entah kenapa aku jadi sangat khawatir.
“Kek.”
“Ya?”
Kakek berhenti tepat di pintu kamar.
“Ngomong-ngomong soal maling, sudah dua malam ada orang yang diam-diam masuk ke rumah.”
“Ya?”
Kakek berhenti tepat di pintu kamar.
“Ngomong-ngomong soal maling, sudah dua malam ada orang yang diam-diam masuk ke rumah.”
Aku ceritakan semuanya dengan gamblang. Bagaimana situasinya, seperti apa mencekamnya suasana semalam saat padam, dan apa yang aku lihat di bawah meja makan.
Kakek mendengarkan dengan serius. Kali ini benar-benar menyimak semua ceritaku tanpa disela lelucon basi yang seringkali membuatku kesal. Ia bahkan mengurungkan niatnya untuk tidur dan kembali ke ruang tamu untuk duduk bersamaku sampai ceritaku selesai.
Wajah kakek serius sekali. Jarang kulihat dia begitu. Sepertinya Kakek mengerti sesuatu. Aku bisa saja mengungkapkan spekulasi di kepala ini, tentang kecurigaanku pada anak-anak Pak Jawi.
Tidak hanya pada kasus yang kualami semalam, tapi mungkin saja anak-anak Pak Jawi adalah dalang di balik maraknya pencurian ternak warga.
“Jadi karena itu semalam kamu tidur di ruang tamu?” tanya kakek.
Aku mengangguk. Kakek pulang sekitar pukul tiga dini hari, saat listrik sudah menyala. Ia membangunkanku yang tertidur di ruang tamu.
Aku mengangguk. Kakek pulang sekitar pukul tiga dini hari, saat listrik sudah menyala. Ia membangunkanku yang tertidur di ruang tamu.
“Kenapa kamu tidak coba pergi ke rumah teman-teman lamamu. Main ke sungai, atau jalan-jalan ke kota.”
“Apa?”
Aku tercengang, solusi dari kakek benar-benar sembarangan.
“Apa?”
Aku tercengang, solusi dari kakek benar-benar sembarangan.
“Kamu ke sini mau liburan, kan? Kenapa malah mikirin sesuatu yang rumit.”
“Gimana nggak kepikiran, rumah ini bisa saja kemalingan. Lagian anak-anak itu sudah cukup meresahkan!”
“Gimana nggak kepikiran, rumah ini bisa saja kemalingan. Lagian anak-anak itu sudah cukup meresahkan!”
“Karena tidak ada barang yang hilang di rumah ini, maka kakek simpulkan kita tidak kemalingan,” kata kakek sembari pergi ke kamar, meninggalkanku yang terdiam karena kesal, bingung, dan… entahlah.
CHAPTER 14
Lagi-lagi hujan deras mulai pukul empat sore, dan belum juga reda sampai azan isya. Aku tidak pernah menyayangkan turunnya hujan, tapi kali ini benar-benar menjadi penghalang.
Lagi-lagi hujan deras mulai pukul empat sore, dan belum juga reda sampai azan isya. Aku tidak pernah menyayangkan turunnya hujan, tapi kali ini benar-benar menjadi penghalang.
Aku ada janji menjemput obat di rumah Pak Jawi, yang seharusnya bisa kutunda besok, tapi karena kondisi kakek makin memburuk, mau tidak mau aku tetap harus berangkat.
Karena itu, malam ini aku tidak pergi sendiri. Di ruang tamu sudah ada Erik. Satu-satunya sahabat yang bisa kuandalkan saat ini. Bisa kulihat senyumnya yang dipaksakan mengembang, dan keringat yang tidak kalah deras dengan hujan di luar.
“Aku suka tantangan seperti ini, Sob,” katanya, sambil tersenyum cemas.
Sepertinya Erik masih memikirkan ceritaku tentang anak-anak Pak Jawi, terutama apa yang kualami di dapur tadi malam. Ia yang semula selalu berpikir positif, dan cenderung skeptis, kini pertahanannya mulai runtuh dan tubuhnya menggeligis.
Lama-lama aku jadi kasihan sama orang ini, batinku.
“Santai aja, Sob. Kita nggak lagi uji nyali, nggak mau cari gara-gara juga. Kita cuma mau jemput obat pesanan kakek, habis itu langsung pulang,” ujarku, menenangkan.
“Santai aja, Sob. Kita nggak lagi uji nyali, nggak mau cari gara-gara juga. Kita cuma mau jemput obat pesanan kakek, habis itu langsung pulang,” ujarku, menenangkan.
Erik mengangguk. Mencoba membuatku percaya bahwa dia tidak takut.
“Ngomong-ngomong, Mbah Saleh mana, Sob?” tanya Erik.
“Ada di kamarnya, lagi istirahat. Abis salat magrib tadi, dia ngeluh kulit punggungnya perih. Badannya juga sedikit demam. Makanya aku bela-belain pergi ke rumah Pak Jawi meski sebenarnya takut.”
“Ada di kamarnya, lagi istirahat. Abis salat magrib tadi, dia ngeluh kulit punggungnya perih. Badannya juga sedikit demam. Makanya aku bela-belain pergi ke rumah Pak Jawi meski sebenarnya takut.”
“Nggak dibawa ke dokter aja?”
“Aku takut, Rik.”
“Lah, kok kamu yang takut?”
“Aku takut, Rik.”
“Lah, kok kamu yang takut?”
“Dulu kakek pernah sakit, dan harus berantem dulu sama Abah biar mau dibawa ke rumah sakit. Sayangnya Abahku kalah, jadi kakek terpaksa dibawa ke tukang pijat. Alhamdulillah nggak lama sembuh juga.”
Erik melongo. Ia kenal dengan kakek sejak kami sama-sama duduk di bangku madrasah Ibtida’iyah, tapi masih saja terkejut dengan tingkah polah kakek yang unik dan cenderung merepotkan.
“Kenapa harus gitu?” tanya Erik.
“Soalnya kakek takut jarum suntik.”
“Soalnya kakek takut jarum suntik.”
Bunyi telapak tangan membentur kening keras sekali. Erik benar-benar tidak bisa menahan geli dan herannya lagi. Ia bahkan masih geleng kepala sambil tersenyum jenaka.
“Terakhir kali aku ketemu Mbah Saleh, waktu itu beliau lagi menangani kasus pembunuhan di desa Lindung.”
“Terakhir kali aku ketemu Mbah Saleh, waktu itu beliau lagi menangani kasus pembunuhan di desa Lindung.”
“Pembunuhan?”
“Ya, satu keluarga dibantai habis sama perampok. Semua barang-barang berharganya ludes. Kamu masih ingat kasus mayat-mayat tanpa identitas yang sering ditemukan warga di pinggir jalan?”
“Ya, waktu itu satu kabupaten geger.”
“Ya, satu keluarga dibantai habis sama perampok. Semua barang-barang berharganya ludes. Kamu masih ingat kasus mayat-mayat tanpa identitas yang sering ditemukan warga di pinggir jalan?”
“Ya, waktu itu satu kabupaten geger.”
“Nah, sejak saat itu kecamatan Banyusirih mulai rusuh. Pembunuhan, pencurian, santet, tawuran antar desa, semua itu terjadi hampir dalam waktu yang berdekatan. Karena itu, dibentuklah semacam tim khusus buat meredam keributan ini. Nah, salah satu anggota tim itu ya Mbah Saleh.”
“Macam nggak ada polisi saja,” aku menyeletuk.
“Kalau cuma maling dan rampok sih, polisi masih bisa diandalkan, tapi kalau urusannya sudah santet, ceritanya lain lagi. Korban berjatuhan, tapi bukti nggak bisa ditemukan. Kalau pun ditemukan, siapa yang bisa menjelaskan gimana caranya paku sama silet masuk ke perut orang?”
Erik mengembuskan napas panjang, lalu mengusap-usap dahi lebarnya.
“Kok kita malah asyik ngobrol, ya? Bukannya katamu kita nggak boleh ke rumah Pak Jawi di atas jam 8? Ini sudah jam setengah 8, lho!”
“Oh iya!” ucapku.
“Kok kita malah asyik ngobrol, ya? Bukannya katamu kita nggak boleh ke rumah Pak Jawi di atas jam 8? Ini sudah jam setengah 8, lho!”
“Oh iya!” ucapku.
Kulihat hujan mulai sedikit reda. Rintiknya mulai jarang, dan gemuruh di langit juga sudah berkurang. Setelah percakapan barusan selesai, wajah Erik kembali tampak cemas. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran sahabatku ini. Seperti orang yang ingin ikut, tapi tidak ingin pergi.
“Ja-jadi berangkat?” tanya Erik sambil nyengir cemas.
“Ya. Jangan lupa bawa payung!
“Ya. Jangan lupa bawa payung!
***
Rumah pak jawi terlihat menyedihkan sehabis hujan lebat, terutama bagian atapnya yang nyaris rubuh akibat diterpa rintik air bertubi-tubi. Masih tersisa sedikit gerimis, hingga tak banyak lampu minyak yang menyala di sekitar rumah, membuat rumah Pak Jawi lebih gelap dari biasanya
Air hujan yang lolos dari lebatnya daun-daun mangga, tampak menggenang di tempat duduk ayunan yang terbuat dari ban bekas. Halaman rumahnya becek, setiap langkah kami penuh kehati-hatian.
“Kalau tahu gini, aku pakai sandal jepit aja. Sayang sandal baruku jadi ko—Woy! Ngapain di situ?”
Erik masih mematung di luar pagar, di samping motor. Ini kali pertama dia pergi ke rumah Pak Jawi di malam hari. Terlebih ia sudah lebih dulu mendengar ceritaku tentang keenam anak itu. Wajar kalau takut.
Pandangannya melayang ke segala arah,persis seperti ketika pertama kali aku datang ke rumah ini. Mungkin karena kali ini rumah Pak Jawi dan sekitar Gang Kadal cenderung lebih gelap, jadi kesan pertama Erik juga jauh lebih buruk.
“Dani, kok serem gini, ya, kalau malam?” bisik Erik dari belakang. Sembunyi seperti anak kecil di hari pertama masuk sekolah.
“Jangan nyaring-nyaring ngomongnya!” tegurku.
“Jangan nyaring-nyaring ngomongnya!” tegurku.
Sambil berjalan, sambil aku memikirkan kalimat yang pantas untuk meminta maaf. Sudah dua kali Pak Jawi memperingatkan agar tidak datang malam.
Semoga kali ini masih dimaafkan, karena telat lima menit dari waktu yang ia sarankan. Namun, sepertinya kunjunganku malam ini akan cepat, karena Pak Jawi sedang mondar-mandir di halaman rumahnya.
Ada yang aneh dengan Pak Jawi malam ini, beliau seperti kebingungan mencari sesuatu. Ia mendongak ke atas pohon mangga di halaman rumahnya, memeriksanya satu persatu.
“Assalamualaikum,” ucapku.
“Assalamualaikum,” ucapku.
“Waalaikumsalam,” jawab Pak Jawi sambil menilik saksama, mencoba mengenali wajahku dalam remang. “Ah, kamu,”
Pak Jawi memandangi Erik lebih lama, membuat sahabatku itu canggung dan takut secara bersamaan.
“Mari masuk dulu.”
Pak Jawi memandangi Erik lebih lama, membuat sahabatku itu canggung dan takut secara bersamaan.
“Mari masuk dulu.”
Kami mengikuti sang tuan rumah menuju teras rumahnya. Aku berjalan perlahan karena tidak mungkin mendahului tuan rumah di depan, dan juga tidak mungkin meninggalkan teman yang sedang gemetaran di belakang.
Seperti biasa, Pak Jawi selalu ramah pada tamunya, dan malam ini pun demikian. Hanya saja, gelagatnya seperti sedang gelisah. Sesekali Pak Jawi menoleh ke halaman, ke pintu pagar rumahnya, seperti menunggu kedatangan seseorang, atau mencari seseorang yang sedang tidak ada.
Kami duduk dengan sungkan, karena sandal dan pakaian kami sedikit basah terkena gerimis. Kuperhatikan Pak Jawi yang juga basah kuyup. Tangan kirinya gemetar, langkahnya pun bergetar.
Sepertinya kakek ini kedinginan karena terlalu lama mondar-mandir di tengah hujan.
Satu hal yang bisa kupastikan malam ini adalah, postur Pak Jawi yang benar-benar tegap, tidak lagi bungkuk seperti saat siang dan sore. Aku tidak tahu apa penyebabnya, tapi jadi sedikit lega karena ternyata aku tidak salah lihat.
“Maaf, Mbah, saya ke sininya kemaleman, soalnya nunggu hujan reda,” ucapku sambil manggut-manggut.
“Oh, tidak apa-apa. Sebentar, saya ambilkan obatnya dulu,” katanya, lalu masuk ke dalam, melewati kain merah penutup pintu.
“Oh, tidak apa-apa. Sebentar, saya ambilkan obatnya dulu,” katanya, lalu masuk ke dalam, melewati kain merah penutup pintu.
Kendati Pak Jawi bilang tidak apa-apa, tetap saja ia terkesan terburu-buru mengambil obat. Mungkin agar aku dan Erik bisa cepat pulang, atau ada hal lain yang membuat orang tua ini gelisah sejak tadi.
“Te-ternyata benar katamu, Dan. Kalau malam Pak Jawi bisa berdiri tegap, sama sekali nggak bungkuk,” bisik Erik.
“Sudah kubilang, jangan nyaring-nyaring!” tegurku.
Tidak lama bagi Pak Jawi untuk kembali ke teras membawa sebotol besar obat yang sama. Kuterima obat yang dibungkus kantong plastik berwarna merah, kuletakkan di meja, lalu menyiapkan uang lima ratus rupiah.
Tidak lama bagi Pak Jawi untuk kembali ke teras membawa sebotol besar obat yang sama. Kuterima obat yang dibungkus kantong plastik berwarna merah, kuletakkan di meja, lalu menyiapkan uang lima ratus rupiah.
Pak jawi duduk lalu menyuguhi kami kue kering yang sejak tadi ada di meja; di depan kami. Aku tidak punya nafsu makan, kupikir Erik pun begitu.
Kami hanya manggut-manggut menolak secara halus, sehalus suara gerimis yang tiba-tiba makin keras, makin deras. Rasanya hujan sengaja mereda untuk membiarkan kami lewat, dan kembali lebat seolah ingin kami terjebak di sini.
“Lah, hujan lagi, Dan,” kata Erik.
“Ya, sudah, tunggu saja di sini sampai reda,” ucap Pak Jawi dengan intonasi sedikit terpaksa, dan raut wajah yang sama sekali tidak menampakkan keikhlasan.
“Ya, sudah, tunggu saja di sini sampai reda,” ucap Pak Jawi dengan intonasi sedikit terpaksa, dan raut wajah yang sama sekali tidak menampakkan keikhlasan.
Kami tidak punya pilihan lain. Sebuah payung tidak akan cukup melindungi dua orang dari gempuran air yang bahkan ranting besar pohon mangga saja menunduk diterpanya. Akhirnya terpaksa menerima tawaran tuan rumah, meski tak enak hati dan sedikit ngeri.
Beruntung Pak Jawi tidak membiarkan dinginnya udara malam membekukan suasana. Ia memulai obrolan basa-basi tentang hujan, tentang kesehatan, dan tentang cinta.
Sungguh, saat sedang mendongeng, seluruh aura misterius kakek ini luruh. Perawakannya yang ramah, dan murah senyum begitu jelas terpancar. Erik yang sejak tadi tegang pun mulai sedikit melemas syarafnya.
Pak jawi bercerita tentang tetangganya yang cantik, yang bahkan tidak seorang pun di desa ini mampu menandingi kecantikannya.
Obrolan tentang perempuan membuat Erik yang awalnya takut menjadi lebih berani, dan sudah tidak segan menunjukkan tingkah kocaknya, sampai pak jawi ikut tertawa terbahak-bahak.
Dalam hangatnya perbincangan, kuperhatikan kursi yang diduduki Pak Jawi. Kursi yang kemarin patah itu sudah diperbaiki lagi dengan lakban yang kali ini lebih tebal dari sebelumnya.
Mungkin kursi itu sudah berkali-kali patah, dan mungkin juga ada hubungannya dengan berat badan Pak Jawi yang tidak biasa. Hanya saja, malam ini ia duduk dengan sangat mudah. Kursinya pun seolah menerima Pak Jawi tanpa beban, tanpa tekanan hebat, tidak berdecit seperti waktu itu.
“Nggak ada niatan menikah lagi, Pak?”tanya Erik.
EH, SI GOBLOK! batinku.
EH, SI GOBLOK! batinku.
Ingin sekali kupukul mulutnya karena sudah bertanya sembarangan. Padahal tadi sore sudah kuperingatkan untuk tidak banyak bertanya,--
--karena terakhir kali aku bertanya tentang keluarga Pak jawi, keenam anaknya mengamuk, berteriak mengusirku dari rumah ini. Bahkan mungkin, kalau saat itu tidak ada Pak Jawi, anak-anaknya sudah melemparku dengan batu dan paku.
Kutendang kaki Erik sebagai isyarat untuk diam,lalu kupalingkan wajah pada Pak Jawi yang rupanya tidak bereaksi seperti dugaanku. Kakek itu cuma tersenyum sambil menyisir jenggot putihnya dengan jemari.
Sama sekali tidak marah. Saat itu pikirannya seperti sedang tidak pada kami. Pak Jawi kembali celingak-celinguk ke halaman. Sikapnya benar-benar seperti orang kehilangan.
Hujan mulai reda. Gerimis jadi penutup obrolan kami malam ini. Aku dan Erik pun pamit pulang. Untuk kali ini saja aku bisa pulang dengan perasaan tenang.
Hujan mulai reda. Gerimis jadi penutup obrolan kami malam ini. Aku dan Erik pun pamit pulang. Untuk kali ini saja aku bisa pulang dengan perasaan tenang.
Tidak ada hal yang aneh terjadi, tidak satu pun dari anak-anak itu menampakkan diri. Pak jawi berbaik hati mengantar kami sampai ke halaman meski sudah berkali-kali kami bilang tidak perlu.
Hati-hati, jalannya lagi becek,”kata Pak Jawi.
Belum sempat Erik menyalakan motor, terdengar bunyi motor lain dari kejauhan. Suara mesin yang menyentak-nyentak, seolah dikendarai dengan ugal-ugalan. Motor itu mendekat dengan cepat.
Belum sempat Erik menyalakan motor, terdengar bunyi motor lain dari kejauhan. Suara mesin yang menyentak-nyentak, seolah dikendarai dengan ugal-ugalan. Motor itu mendekat dengan cepat.
Tidak hanya satu, tapi tiga. Lampunya mulai terlihat berbelok masuk ke gang, melaju tanpa ragu, tanpa takut terpeleset oleh jejak-jejak hujan. Suara mesinnya mengganggu telinga, dan lampu-lampunya menyilaukan kami yang sedang berdiri di depan pagar rumah Pak Jawi.
Dua dari tiga motor tersebut dikendarai oleh dua orang pria berboncengan. Satu motor lagi tampak membawa sesuatu di jok belakang yang diikat dengan tali tampar.
Aku dan Erik geser memberi jalan, karena tidak satu pun dari orang ini yang mau menurunkan kecepatan, tidak pula saat masuk ke halaman rumah orang.
“Songong banget, pakai gebar-geber segala!” gerutu Erik.
Meski tak terucap, aku dan Erik sama-sama sepakat untuk tidak pulang dulu. Entah apa yang kami tunggu, tapi sepertinya ada hal gawat yang sedang terjadi.
Meski tak terucap, aku dan Erik sama-sama sepakat untuk tidak pulang dulu. Entah apa yang kami tunggu, tapi sepertinya ada hal gawat yang sedang terjadi.
Dari cara lima orang itu datang, cara mereka turun, dan wajah-wajah beringas itu membuatku sedikit khawatir.
“Ada apa ya, Dan?” tanya Erik.
“Nggak tahu,” jawabku.
“Ada apa ya, Dan?” tanya Erik.
“Nggak tahu,” jawabku.
Begitu mesin motor dimatikan, dan suara ribut itu menghilang, barulah kudengar suara tangis seseorang. Lima pria turun dari motor.
Mereka menurunkan dengan kasar karung gula yang terikat di jok, lalu melemparkannya ke tanah hingga membuat dentuman keras yang bercampur suara cipratan air genangan hujan.
Pak Jawi yang sejak tadi berdiri kebingungan kini terbelalak. Tangannya lemas, lampu minyak yang dibawanya pun jatuh ke tanah. Bisa kulihat dengan jelas seseorang merangkak ke luar dari karung gula yang baru saja komplotan itu lempar ke tanah, dan sejujurnya, akupun mulai geram.
“Dan, jangan-jangan itu ….”
“Ya, itu salah satu anak Pak Jawi.”
SI GENDUT
Apapun alasan dan motif orang-orang ini, memperlakukan anak kecil seperti itu tetap bertentangan dengan nuraniku.
“Ya, itu salah satu anak Pak Jawi.”
SI GENDUT
Apapun alasan dan motif orang-orang ini, memperlakukan anak kecil seperti itu tetap bertentangan dengan nuraniku.
Aku tahu Erik pun merasa begitu. Tanpa kusadari, tangan ini mengepal dan kaki ini sudah selangkah lebih maju. Kalaupun ada yang menahan kami, itu hanya kesadaran bahwa sebagai tetangga, kami tidak berhak terlalu ikut campur, sebelum tahu akar permasalahannya.
Pak Jawi menghampiri anaknya yang menangis dan merintih di tanah basah. Kedua tangannya terikat ke belakang, dan bocah itu hanya mampu merayap di lumpur, mendekati Pak Jawi yang tidak bisa berjalan cepat, secepat Pak Jawi ingin memeluk si Gendut.
“Kamu tidak apa-apa?” tanya Pak Jawi, seraya mencoba melepas ikatan di tangan anaknya.
Betapa pemandangan itu sangat memilukan sekaligus mengharukan. Dengan semua prasangka buruk tentang Pak Jawi dan anak-anaknya, aku merasa jadi orang tak berperasaan yang termakan khayalan.
Betapa pemandangan itu sangat memilukan sekaligus mengharukan. Dengan semua prasangka buruk tentang Pak Jawi dan anak-anaknya, aku merasa jadi orang tak berperasaan yang termakan khayalan.
Mereka hanyalah keluarga miskin yang butuh perhatian lebih dari tetangga-tetangganya, dan alih-alih membantu meringankan beban, aku justru mencurigai mereka.
“Sudah cukup pura-puranya!” hardik salah seorang dari lima pria yang datang.
“Sudah cukup pura-puranya!” hardik salah seorang dari lima pria yang datang.
Melihat dari cara mereka berkelompok, orang yang berdiri paling depan itu adalah pemimpinnya. Ia berperawakan kasar, gemuk, bercelana pendek dengan sarung melingkar dari bahu ke pinggang.
Kuperhatikan dari jauh, seperti pernah bertemu orang itu. Selain pemimpinnya, empat orang lainnya tampak standar mengenakan kaus lengan pendek dan celana panjang.
“Anak kurang ajar! Di sini saja kamu nangis-nangis, padahal sudah berkali-kali kamu bikin saya rugi. Bikin rugi orang satu desa!” tukas si pemimpin gerombolan bermotor.
Tak ada sungkan ataupun takut, pria tambun itu mendekati si gendut lalu menendang punggungnya sampai bocah itu menjerit kesakitan, di depan Pak Jawi yang berusaha melindungi anaknya.
“Tolong, maafkan anak saya,” isak Pak Jawi.
“Hei!” aku menyenggak.
“Tolong, maafkan anak saya,” isak Pak Jawi.
“Hei!” aku menyenggak.
Persetan dengan tidak ikut campur, yang mereka lakukan itu sudah keterlaluan. Menendang anak kecil di depan ayahnya yang sudah tua. Orang waras tidak akan pernah melakukannya.
“Apa?” balas salah satu dari gerombolan itu dengan lebih galak.
“Apa?” balas salah satu dari gerombolan itu dengan lebih galak.
“Mole, Cong! Jek rok nurok, mak tak epatappor bik engkok!” (Pulang! Jangan ikut campur, atau saya tampar kamu!) ancam pria botak yang wajahnya penuh lubang bekas jerawat. Bahkan dengan penerangan yang kurang, tekstur wajahnya masih terlihat jelas.
Dari dekat, aku mulai mengenali wajah pemimpin mereka yang ternyata bukan orang asing. Dia adalah Pak Muhadi, salah satu orang terkaya di Sumbergede. Dia terkenal dermawan dan juga pelit di waktu yang bersamaan.
Dia bisa menyumbang ratusan nasi bungkus, berkarung-karung beras dan semen, dan apapun yang dibutuhkan untuk pembangunan desa, kecuali uang. Pak Muhadi cinta mati pada uang-uangnya. Karena itu, menurut yang aku dengar, tidak sepeser pun uangnya disimpan di Bank.
Cinta butanya pada uang membuat ia kerap kali melakukan berbagai cara agar jumlahnya berlipat ganda, termasuk memberi bunga besar pada warga yang datang berutang. Gilanya, bunga itu seringkali lebih besar dari jumlah utangnya sendiri.
Si Gendut menangis menahan sakit dalam dekapan Pak Jawi. Bocah yang selalu terlihat tetesan air liurnya itu, sekarang memperlihatkan tetes air matanya.
Sepertinya Pak Jawi tidak ingin aku terlibat lebih jauh dalam masalah ini, Pak Jawi memberi isyarat tangan agar aku dan Erik segera pulang.
“Ini sudah kesekian kalinya, Wi, anakmu masuk halaman rumah saya,” hardik Pak Muhadi, sambil kakinya menyenggol punggung si Gendut.
“Ini sudah kesekian kalinya, Wi, anakmu masuk halaman rumah saya,” hardik Pak Muhadi, sambil kakinya menyenggol punggung si Gendut.
"Dani, pulang!” seru Erik yang masih duduk di motor, enggan tercebur dalam masalah.
“Sekarang sudah kepergok, dan ini bisa jadi bukti kalau kecurigaan kami selama ini benar. Dalang di balik pencurian ternak, ya anak-anakmu ini!” sambung Pak Muhadi, dengan nada bicara yang makin meninggi.
“Sa-saya berani jamin, Pak, anak-anak saya, tidak—“
“—Kamu mau jamin pakai apa, hah?”
Pak Muhadi meludah ke tanah, nyaris mengenai muka si Gendut.
“Iyo, ambil itu!”
“—Kamu mau jamin pakai apa, hah?”
Pak Muhadi meludah ke tanah, nyaris mengenai muka si Gendut.
“Iyo, ambil itu!”
Perintah Pak Muhadi pada orang bernama Iyo, anak buahnya yang botak dan berjerawat, sekaligus yang tadi membonceng dan melempar si Gendut.
Iyo mengambil kantung plastik berwarna hitam yang tergantung di motor bebek.
Iyo mengambil kantung plastik berwarna hitam yang tergantung di motor bebek.
Entah apa isinya, tapi bisa kulihat Iyo sedikit jijik membawanya. Kantung plastik itu dijinjing pakai tangan kiri lalu diletakkan di tanah, di depan Pak Muhadi dan Pak Jawi. Iyo menyenggol kantung plastik yang tidak diikat itu dengan kaki, hingga memuntahkan semua isinya.
Bangkai ayam menggelundung keluar, kulihat masih ada satu lagi di dalam.
“Lihat! Ini korban hari ini,” ucap Pak Muhadi.
Bangkai ayam itu dicabik, dipotong, dan dicabuti bulunya. Kuperhatikan hewan malang itu masih bersimbah darah segar, pertanda matinya belum lama.
“Lihat! Ini korban hari ini,” ucap Pak Muhadi.
Bangkai ayam itu dicabik, dipotong, dan dicabuti bulunya. Kuperhatikan hewan malang itu masih bersimbah darah segar, pertanda matinya belum lama.
Sebagian besar lehernya terputus, dan isi perutnya terburai.
“Maaf, Pak, saya benar-benar tidak tahu soal ayam-ayam Sampean yang mati. Saya juga yakin itu bukan perbuatan anak saya.”
Pak Muhadi duduk jongkok sejajar dengan Pak Jawi dan si Gendut.
“Maaf, Pak, saya benar-benar tidak tahu soal ayam-ayam Sampean yang mati. Saya juga yakin itu bukan perbuatan anak saya.”
Pak Muhadi duduk jongkok sejajar dengan Pak Jawi dan si Gendut.
“Ayolah, jangan buat perkara ini jadi makin rumit. Bukti sudah ada. Mau mengelak gimana lagi kamu ini, Wi, Wi! Sekarang kamu mau ganti rugi, atau saya bawa kasus ini ke polisi?”
Pak Muhadi bersikeras menuntut ganti rugi untuk ayam-ayamnya yang ditengarai sudah dimakan si Gendut, atau lebih tepatnya dibantai. Aku tahu cara menyembelih dan memotong ayam.
Aku juga paham bagian mana saja yang layak dimakan, atau yang sebaiknya dibuang, tapi bangkai ayam yang kulihat ini sama sekali tidak mengindikasikan niat untuk dimakan.
“Saya minta maaf kalau anak saya sudah lancang masuk ke halaman rumah Sampean, ini, ini, saya ada uang. Saya tahu ini tidak cukup,tapi saya tidak punya uang lagi. Ini satu-satunya yang saya dapat hari ini.”
Uang kertas yang sedang diupayakan Pak Jawi untuk menyelesaikan masalah ini adalah uang pemberianku barusan. Seketika itu juga hatiku merasa sakit. Erik juga sudah jengah. Kami sudah berada pada tingkat muak tertinggi yang akan meledak bila disentuh sedikit lagi.
“Bukan saya… Bukan saya…” isak si Gendut.
Karena memang punya masalah dalam berbicara, kata-katanya barusan jadi terdengar tidak jelas.
Pak Muhadi hanya memandang uang lima ratus itu dengan raut heran bercampur marah.
Karena memang punya masalah dalam berbicara, kata-katanya barusan jadi terdengar tidak jelas.
Pak Muhadi hanya memandang uang lima ratus itu dengan raut heran bercampur marah.
Mungkin saja orang kaya itu merasa terhina dengan jumlah yang Pak Jawi suguhkan.
“Jangan bercanda, kamu, Wi!”
Pak Muhadi mengambil uang itu, lalu menepis tangan Pak Jawi. Kakinya seolah gatal ingin menendang kembali.
“Jangan bercanda, kamu, Wi!”
Pak Muhadi mengambil uang itu, lalu menepis tangan Pak Jawi. Kakinya seolah gatal ingin menendang kembali.
“Kalian geledah rumahnya! Gubuk ini pasti tidak banyak barang berharganya, tapi setidaknya ini bisa jadi pelajaran buat mereka.”
Atas perintah Pak Muhadi, Iyo dan kawan-kawannya bergerak untuk menjarah rumah Pak Jawi, padahal, cukup dengan melihat saja, siapa pun akan tahu bagaimana isi rumah kumuh itu. Tidak banyak harta yang bisa mereka dapatkan, kecuali niat mereka memanglah untuk merusak.
“Woi!” hardikku.
Tidak, aku tidak seberani itu. Aku tidak se-kesatria itu. Terbukti saat mereka semua menoleh, nyaliku langsung menciut.
Tidak, aku tidak seberani itu. Aku tidak se-kesatria itu. Terbukti saat mereka semua menoleh, nyaliku langsung menciut.
Aku hanya merasa perlu untuk menyuarakan protes, karena kalau tidak, aku tidak bisa pulang dengan tenang setelah melihat yang Pak Muhadi dan komplotannya lakukan.
“Kenapa kalian masih di sini?” Tanya Pak Muhadi.
“Kenapa kalian masih di sini?” Tanya Pak Muhadi.
“Be-berapa total kerugian Sampean, Lik? (Pak Lik) Biar kami coba diskusikan dengan Pak Jawi,” aku coba bernegosiasi.
“Pulang sana!” sembur Pak Muhadi, mengakhiri negosiasi kami yang belum sempat dimulai.
“Dani, kita pulang saja,” ajak Erik.
“Pulang sana!” sembur Pak Muhadi, mengakhiri negosiasi kami yang belum sempat dimulai.
“Dani, kita pulang saja,” ajak Erik.
Entah kenapa aku merasa bahwa sejak awal niat Pak Muhadi bukan untuk meminta ganti rugi. Mungkin berdasar kebencian, ataukah ada sesuatu yang memang ia cari di dalam rumah Pak Jawi?
Kulihat Iyo dan teman-temannya membawa senjata tajam. Barang yang sangat tidak perlu untuk dibawa pada situasi tersebut. Maksudku, Pak Jawi tidak mungkin melawan.
Di dalam rumah itu pun mungkin hanya ada anak-anak, lantas kenapa mereka kelihatan bengis seolah siap untuk berperang?
Si Gendut memegangi kaki Iyo. Pria itu berhenti melangkah dan menghentak-hentakkan kakinya dengan jijik, mencoba melepaskan diri dari belenggu si Gendut.
Si Gendut memegangi kaki Iyo. Pria itu berhenti melangkah dan menghentak-hentakkan kakinya dengan jijik, mencoba melepaskan diri dari belenggu si Gendut.
“Lepas, Cong!” bentaknya.
Kesal sudah di ubun-ubun, Iyo menghantam muka si Gendut pakai pegangan parang, hingga samar-samar kudengar bunyi retak, disusul bunyi tubuh si Gendut yang ambruk ke tanah, dan setelah itu…
Kesal sudah di ubun-ubun, Iyo menghantam muka si Gendut pakai pegangan parang, hingga samar-samar kudengar bunyi retak, disusul bunyi tubuh si Gendut yang ambruk ke tanah, dan setelah itu…
SUASANA MENDADAK HENING
***
***
Bersambung minggu depan, yak. Terima kasih sudah membaca sampai sejauh ini. Terima kasih juga untuk yang sudah mendukung di Karyakarsa.
Seperti biasa, Chapter 15, 16 dan 17 terbit lebih awal di Karyakarsa. Silakan.
karyakarsa.com/ahmaddanielo/m…
karyakarsa.com/ahmaddanielo/m…
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh