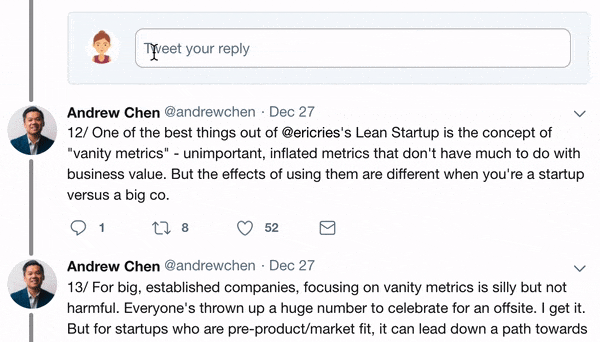CATATAN:
Di antara para ekonom Indonesia yang memperhatikan kenaikan harga beras waktu itu, muncul kelegaan karena harga beras bisa terkendali akibat stok yang cukup.
Indonesia beruntung karena bisa duluan borong beras di pasar internasional sehingga harga bisa stabil.
Di antara para ekonom Indonesia yang memperhatikan kenaikan harga beras waktu itu, muncul kelegaan karena harga beras bisa terkendali akibat stok yang cukup.
Indonesia beruntung karena bisa duluan borong beras di pasar internasional sehingga harga bisa stabil.
https://twitter.com/hotradero/status/1431129332160757760
Hal seperti ini tidak mudah dikomunikasikan kepada masyarakat - karena ada pemahaman umum: "impor pasti buruk", "kita harus bisa swasembada pangan" dll.
Padahal swasembada bisa sangat mahal ongkos ekonominya kalau harga beras naik terlampau tajam. Yang jadi korban: daya beli.
Padahal swasembada bisa sangat mahal ongkos ekonominya kalau harga beras naik terlampau tajam. Yang jadi korban: daya beli.
"Bukankah harga beras yang tinggi menguntungkan petani?"
Kata siapa? Nilai Tukar Petani di Indonesia nggak pernah nyambung dengan harga beras di pasar. Mengapa? Karena rantainya sampai ke pasar sangat panjang. Dan tiap mata rantai punya marjin laba tersendiri.
Kata siapa? Nilai Tukar Petani di Indonesia nggak pernah nyambung dengan harga beras di pasar. Mengapa? Karena rantainya sampai ke pasar sangat panjang. Dan tiap mata rantai punya marjin laba tersendiri.
Akibat panjangnya rantai ini, maka kenaikan harga beras lebih dulu mengisi marjin laba komponen-komponen rantai ini - sebelum bisa sampai ke petani.
Rantai terpendek? Beras impor. Itu sebabnya beras impor efektif menurunkan harga beras dari lonjakan berlebihan.
Rantai terpendek? Beras impor. Itu sebabnya beras impor efektif menurunkan harga beras dari lonjakan berlebihan.
Maka opsi impor sebenarnya harus tetap dibuka, supaya harga di pasar masih terjangkau. Kalau keadaan sudah membaik dan stok dalam negeri sudah pulih, keran impor bisa ditutup kembali.
Atau lebih ideal lagi: automatic stabilizer. Keran impor otomatis terbuka bila harga kemahalan.
Atau lebih ideal lagi: automatic stabilizer. Keran impor otomatis terbuka bila harga kemahalan.
Untuk bisa menciptakan automatic stabilizer maka perlu ada pasar komoditas berjangka atas beras. Di mana kontrak harga beras sampai sekian bulan ke depan diperdagangkan saat ini.
Kalau harga 3-4 bulan lagi melewati titik tertentu - keran impor otomatis terbuka.
Kalau harga 3-4 bulan lagi melewati titik tertentu - keran impor otomatis terbuka.
Begitu keran terbuka, maka harga beras dalam negeri diharapkan bisa stabil kembali.
Lalu kenapa ini nggak jalan? Karena infrastruktur pasar komoditasnya berantakan. Berbulan-bulan dicoba diperbaiki: nggak ada hasil. Sampai akhirnya masa jabatan kabinet pertama Jokowi berakhir.
Lalu kenapa ini nggak jalan? Karena infrastruktur pasar komoditasnya berantakan. Berbulan-bulan dicoba diperbaiki: nggak ada hasil. Sampai akhirnya masa jabatan kabinet pertama Jokowi berakhir.
Sesudah menteri-menteri berganti, tentu birokrasi akan menyesuaikan pada "selera" menteri yang baru. Maka ide automatic stabilizer terhenti.
Buat apa? Toh harga beras stabil dan dunia sedang mengalami La Nina 2020 yang akan bersambung La Nina 2022.
Buat apa? Toh harga beras stabil dan dunia sedang mengalami La Nina 2020 yang akan bersambung La Nina 2022.
Mungkin kita perlu menunggu sampai El Nino suatu saat muncul kembali, sebelum ide tentang automatic stabilizer bisa dihidupkan kembali.
Mudah-mudahan El Nino-nya nanti nggak terlalu berat. Atau orang Indonesia sukses mengurangi makan nasi secara ekstreme.
SEKIAN.
Mudah-mudahan El Nino-nya nanti nggak terlalu berat. Atau orang Indonesia sukses mengurangi makan nasi secara ekstreme.
SEKIAN.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh