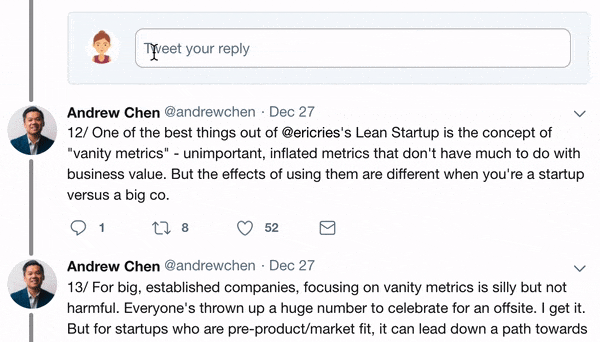"Wulan"
Rewrite berdasarkan ijin dari sang penulis :)
Author : @gunawanindra4
Thread : kask.us/iH3sn
Selamat menikmati.
@bacahorror @ceritaht @IDN_Horor #threadhorror #dendam #ceritahorror
Rewrite berdasarkan ijin dari sang penulis :)
Author : @gunawanindra4
Thread : kask.us/iH3sn
Selamat menikmati.
@bacahorror @ceritaht @IDN_Horor #threadhorror #dendam #ceritahorror
"Ada apa gerangan sampai Eyang mendatangiku? Bukankah malam purnama masih beberapa hari lagi?"
"Aku datang bukan untuk menagih janji, tapi untuk mengajukan sebuah penawaran!"
"Penawaran?"
"Kau ingin harta lebih banyak lagi?"
"Eh, tentu saja, Eyang."
"Aku datang bukan untuk menagih janji, tapi untuk mengajukan sebuah penawaran!"
"Penawaran?"
"Kau ingin harta lebih banyak lagi?"
"Eh, tentu saja, Eyang."
"Bagus! Aku menginginkan anak istimewa itu untuk tumbalku di malam purnama kali ini!"
"Anak istimewa?"
"Kau pasti tau yang kumaksud!"
"Eh, tapi Eyang ...."
"AKU MAU ANAK ITU!!!"
"Bb .... Ba .... Baik Eyang."
"Anak istimewa?"
"Kau pasti tau yang kumaksud!"
"Eh, tapi Eyang ...."
"AKU MAU ANAK ITU!!!"
"Bb .... Ba .... Baik Eyang."
"Bagus! Dapatkan anak itu, maka akan kuberikan harta yang lebih banyak lagi dari yang sebelumnya telah aku berikan. Tapi kalau sampai gagal, akan kuambil lagi semua yang telah kuberikan, ditambah dengan nyawamu, dan seluruh keluargamu!" 

Gadis kecil itu berjalan berjingkat jingkat sambil bersenandung pelan. Rambut kepang duanya bergoyang goyang, mengikuti irama langkah kakinya. Begitu juga dengan tas selempang yang tergantung di pundaknya.
Wajahnya terlihat sangat ceria, meski sengatan sinar matahari musim kemarau membakar kulitnya. Keringat membanjir di sekujur tubuhnya, membasahi seragam putih merah yang dikenakannya.
"Maaakkk!!! Wulan pulaaaannnggg ...!!!" seru gadis itu saat memasuki pintu sebuah pondok kayu sederhana di tengah ladang singkong itu.
"Wulan! Kebiasaan kamu ya! Pulang sekolah bukannya mengucap salam malah teriak teriak begitu," terdengar seruan sang ibu dari arah dapur.
"Wulan! Kebiasaan kamu ya! Pulang sekolah bukannya mengucap salam malah teriak teriak begitu," terdengar seruan sang ibu dari arah dapur.
"Hehe, lupa Mak!" gadis itu tertawa, melemparkan tas sekolahnya ke atas kursi, lalu menyambar sepotong tempe goreng yang terhidang di atas meja dan mengunyahnya dengan rakus.
"Lapar Mak!"
"Lapar Mak!"
"Wulan! Bukannya ganti baju dulu,..." Romlah, emak dari si gadis kecil itu muncul dari arah dapur.
"Dan kenapa bajumu lecek begitu? Kamu berantem lagi di sekolah?"
"Enggak Mak," jawab Wulan seenaknya, sambil duduk di kursi dan melepas sepatunya.
"Dan kenapa bajumu lecek begitu? Kamu berantem lagi di sekolah?"
"Enggak Mak," jawab Wulan seenaknya, sambil duduk di kursi dan melepas sepatunya.
"Jangan bohong sama Emak!" seru Romlah lagi sambil meletakkan sepanci sayur yang dibawanya diatas meja.
"Iya iya," lagi lagi gadis itu menjawab sekenanya.
"Tapi bukan Wulan yang bikin masalah Mak. Mereka duluan yang menganggu Wulan."
"Iya iya," lagi lagi gadis itu menjawab sekenanya.
"Tapi bukan Wulan yang bikin masalah Mak. Mereka duluan yang menganggu Wulan."
"Wulan, kamu ini anak perempuan lho nduk," Romlah menatap sang anak sambil menggeleng gelengkan kepalanya. "Mbok ya jangan suka berkelahi gitu. Ini sudah yang kelima kalinya lho, kamu berantem di sekolah."
"Mereka duluan yang mulai Mak," gadis kecil itu masih tetap membela diri.
"Mereka duluan yang mulai Mak," gadis kecil itu masih tetap membela diri.
"Masa Wulan diam saja kalau mereka berani mendorong dan menjambak rambut Wulan."
"Ada saja alasan kamu!" Romlah ikut duduk disamping anak gadisnya itu.
"Ada saja alasan kamu!" Romlah ikut duduk disamping anak gadisnya itu.
"Pokoknya emak nggak suka kalau kamu suka berantem gitu. Sudah empat kali lho, bapakmu dipanggil ke sekolah gara gara kamu. Apa kamu ndak kasihan? Kali ini sama siapa lagi kamu berantem?"
"Tomy Mak," sahut anak itu sambil melepas baju seragamnya dan menggantinya dengan kaos oblong dan celana pendek sebatas lutut.
"Tomy anaknya Pak Darsa?" Romlah mengernyitkan keningnya.
"Iya kali," sahut anak itu singkat.
"Tomy anaknya Pak Darsa?" Romlah mengernyitkan keningnya.
"Iya kali," sahut anak itu singkat.
Seolah tak memperdulikan kecemasan sang emak, gadis kecil itu justru segera bangkit dan meraih piring, mengisinya dengan nasi dan lauk pauk yang telah terhidang di atas meja.
Piring berukuran besar itu nyaris tak muat menampung semua makanan yang diambil oleh si gadis kecil itu.
Piring berukuran besar itu nyaris tak muat menampung semua makanan yang diambil oleh si gadis kecil itu.
Sambil duduk dan mengangkat sebelah kakinya keatas kursi, gadis kecil itu makan dengan lahapnya.
"Wulan! Yang sopan kalau makan!" lagi lagi Romlah menghardik anak semata wayangnya itu.
"Hehe, iya. Maaf Mak," gadis itu terkekeh dan segera menurunkan kakinya.
"Wulan! Yang sopan kalau makan!" lagi lagi Romlah menghardik anak semata wayangnya itu.
"Hehe, iya. Maaf Mak," gadis itu terkekeh dan segera menurunkan kakinya.
Lagi lagi Romlah hanya bisa geleng geleng kepala melihat tingkah anak semata wayangnya itu.
****
"Wulaaannn...!!! Main yuk!" sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari luar pondok.
****
"Wulaaannn...!!! Main yuk!" sebuah suara yang sangat familiar terdengar dari luar pondok.
Wulan segera menjejalkan suapan terakhir kedalam mulutnya, meletakkan piring yang kini telah kosong, lalu mengelap tangannya dengan ujung kaos yang dipakainya.
"Mak! Wulan main ya," lagi lagi gadis kecil itu berteriak kepada emaknya yang masih sibuk di dapur.
"Mak! Wulan main ya," lagi lagi gadis kecil itu berteriak kepada emaknya yang masih sibuk di dapur.
"Wulan! Mau ..., Astaghfirullahhaladziiiimmmm...!" Romlah kembali hanya bisa geleng geleng kepala saat menyadari bayangan sang anak telah lenyap entah kemana.
"Jangan jauh jauh mainnya! Dan jangan bermain di dekat kali!" entah teriakan Romlah kali ini masih didengar atau tidak oleh Wulan, karena gadis kecil itu kini telah berada diluar pondok.
"Lan, main yuk," seorang anak laki laki berbadan gempal telah duduk di bangku kayu yang ada di teras pondok itu.
"Main kemana? Masih panas gini, males aku!" gadis itu ikut duduk disebelah si anak laki laki.
"Main kemana? Masih panas gini, males aku!" gadis itu ikut duduk disebelah si anak laki laki.
"Kerumahku saja. Aku punya mainan baru, baru dibelikan sama emakku kemarin," kata Lintang, si anak laki laki bertubuh gempal itu.
.
.
"Males ah, emakmu galak! Aku ndak suka main kerumahmu. Mending kita main ke kali Salahan saja. Panas panas gini kan enak mandi di kali sambil nyari ikan," kata gadis cilik itu.
"Eh, tapi kan emakmu tadi bilang ...."
"Eh, tapi kan emakmu tadi bilang ...."
"Alaaahhh, ndak usah di dengerin. Toh emak juga ga bakalan tau kalau kita main di kali. Berangkat yuk, keburu sore," gadis kecil itu melompat turun dari bangku bambu yang didudukinya, lalu dengan riangnya ia berjalan berjingkat jingkat meninggalkan Lintang.
Lintang hanya geleng geleng kepala melihat tingkah sahabatnya itu. Wulan memang anak yang lincah. Lihat saja cara berjalannya, berjingkat jingkat begitu, setengah berlari setengah melompat lompat.
"Pelan pelan dong jalannya," seru Lintang sambil mengikuti langkah Wulan.
"Pelan pelan dong jalannya," seru Lintang sambil mengikuti langkah Wulan.
Gadis itupun menghentikan langkahnya, lalu berbalik dan menatap ke arah Lintang dengan mata melebar galak.
"Hey, kamu ngapain? Kamu ndak boleh ikut! Aku ndak mau main sama kamu! Kamu jorok! Badanmu bau! Wajahmu jelek! Dan kamu telanjang gitu! Jijik aku melihatmu!" suara Wulan yang meninggi itu sukses membuat Lintang juga menghentikan langkahnya.
"Eh, kenapa ...."
"Eh, kenapa ...."
"Bukan kamu Lintaanngg, tapi dia!" Wulan menunjuk kearah belakang Lintang, lalu mengambil sebongkah batu berukuran sekepalan tangan yang tergeletak di pinggir jalan.
"Pergi nggak? Kulempar pakai batu nih kalau nggak mau pergi!"
"Pergi nggak? Kulempar pakai batu nih kalau nggak mau pergi!"
Ah, pasti anak itu melihat sesuatu yang aneh lagi, batin Lintang sambil mengusap tengkuknya yang tiba tiba merinding. Bukan sekali dua kali Wulan bertingkah aneh begitu. Kalau bukan Lintang, pasti sudah berpikir kalau gadis kecil itu tak waras. Tapi Lintang sudah paham.
Sahabatnya yang satu ini memang bukan anak yang biasa biasa saja. Dia istimewa.
"Yuk, kita jalan lagi. Anak aneh itu sudah pergi," Wulan membuang batu yang dipegangnya, lalu kembali melangkah dengan cara berjalannya yang unik.
"Yuk, kita jalan lagi. Anak aneh itu sudah pergi," Wulan membuang batu yang dipegangnya, lalu kembali melangkah dengan cara berjalannya yang unik.
Lagi lagi Lintang hanya bisa geleng geleng kepala sambil mengikuti langkah gadis kecil itu, menyusuri jalanan berbatu yang berdebu itu menuju ke arah utara.
Tak lama, keduanya sudah asyik bermain main di kali kecil itu, tanpa memperdulikan orang orang yang memperhatikan mereka.
Tak lama, keduanya sudah asyik bermain main di kali kecil itu, tanpa memperdulikan orang orang yang memperhatikan mereka.
Kalau bukan Wulan, pasti orang orang itu sudah mengusir jauh jauh siapapun yang berani datang ke kali itu di siang hari bolong. Bukan karena tak suka, tapi justru karena mereka peduli. Kali kecil itu sudah sangat terkenal dengan keangkerannya.
Ada waktu waktu tertentu yang dianggap pamali untuk datang ke kali itu. Salah satunya disaat tepat tengah hari seperti sekarang ini. Namun orang orang itu tahu siapa Wulan. Jadi mereka mengacuhkannya begitu saja saat Wulan asyik bermain di kali kecil yang terkenal angker itu.
Wulan lebih angker daripada dedhemit penghuni kali itu, begitu sering orang orang berseloroh.
Sedang asyik asyiknya kedua anak itu bermain di kali, datang segerombolan anak laki laki yang sepertinya ingin bermain bola di areal sawah yang mengering di pinggir kali itu.
Sedang asyik asyiknya kedua anak itu bermain di kali, datang segerombolan anak laki laki yang sepertinya ingin bermain bola di areal sawah yang mengering di pinggir kali itu.
Melihat Wulan yang bermain di kali, muncul sifat usil dari anak anak itu.
"Eh, lihat, ada si nenek sihir sama kacungnya lagi berendam di kali," celetuk salah seorang dari anak itu. Anak anak lainnya menyambut celetukan itu dgn tawa berderai, membuat telinga Wulan panas seketika.
"Eh, lihat, ada si nenek sihir sama kacungnya lagi berendam di kali," celetuk salah seorang dari anak itu. Anak anak lainnya menyambut celetukan itu dgn tawa berderai, membuat telinga Wulan panas seketika.
"Hei, siapa yang kau sebut nenek sihir?!" gadis kecil itu bertolak pinggang.
Huuuuu ...!!! Takuuuuuttttt ...!!! Ada yang marah nih sepertinya!" seru anak itu lagi, membuat telinga Wulan semakin panas.
"Sialan!" Wulan meradang.
Huuuuu ...!!! Takuuuuuttttt ...!!! Ada yang marah nih sepertinya!" seru anak itu lagi, membuat telinga Wulan semakin panas.
"Sialan!" Wulan meradang.
Dengan cepat gadis itu melompat naik keatas tanggul sungai, lalu menghampiri gerombolan anak laki laki itu. "Coba kaubilang sekali lagi, siapa yang nenek sihir dan siapa yang jadi kacung?!"
"Wulan! Tunggu!" Lintang dengan susah payah mencoba melerai pertengkaran itu.
"Wulan! Tunggu!" Lintang dengan susah payah mencoba melerai pertengkaran itu.
"Wah, si kacung membela tuannya nih."
"Kacung katamu?!" Wulan semakin meradang.
"Kacung katamu?!" Wulan semakin meradang.
"Nggak pernah ngaca kamu ya? Siapa yang pantas disebut kacung? Nggak sadar kalau kamu sendiri lebih mirip kacung. Sudah wajah item kayak pantat kuali. Pasti pantatmu lebih item lagi, lebih item daripada pantat wajan gosong!"
"Eh, nenek sihir! Berani kamu ...!"
"Eh, nenek sihir! Berani kamu ...!"
"Plak!!!" ucapan anak laki itu terhenti saat dengan tiba tiba tangan Wulan terayun menampar wajahnya.
"Berani kau menamparku?!" bentak anak itu, sambil mengusap usap pipinya pipinya yang memerah.
"Berani kau menamparku?!" bentak anak itu, sambil mengusap usap pipinya pipinya yang memerah.
"Kenapa enggak? Jangankan menamparmu, menghajarmu sampai babak belurpun aku berani!" sentak Wulan, sambil tetap berkacak pinggang.
"Brengsek!!!" anak laki laki itu meradang. Tangannya terjulur, mencoba meraih rambut ekor kuda milik Wulan. Namun ia kalah gesit.
"Brengsek!!!" anak laki laki itu meradang. Tangannya terjulur, mencoba meraih rambut ekor kuda milik Wulan. Namun ia kalah gesit.
Tangan Wulan segera menyambar dan memelintir tangan anak itu, membuat anak itu menjerit kesakitan.
"Aawwww ...!!!"
"Mau aku patahin tanganmu hah?!"
"Wulaaannn ...!!!"
"Aawwww ...!!!"
"Mau aku patahin tanganmu hah?!"
"Wulaaannn ...!!!"
"Hei hei, ada apa ini? Kenapa pada berkelahi hah?" sebuah sepeda motor yang kebetulan melintas berhenti di dekat mereka. Pengendaranya turun dan segera melerai yang sedang berkelahi.
Wulan melepaskan cengkeraman tangannya pada lengan anak itu, lalu mendorong tubuh si anak laki laki itu sampai jatuh tersungkur.
"Dia yang mulai Pak!" dengus Wulan sambil menunjuk wajah anak itu.
"Dia yang mulai Pak!" dengus Wulan sambil menunjuk wajah anak itu.
"Sudah sudah! Bubar! Nggak malu kalian berantem sama anak perempuan?!" bentak bapak bapak itu. Gerombolan anak laki laki itu segera bubar. Sedang Wulan masih menatap mereka dengan pandangan garang.
"Pengecut!" desis Wulan, masih sambil bertolak pinggang.
"Pengecut!" desis Wulan, masih sambil bertolak pinggang.
"Sudah Lan, kita pulang saja yuk," ajak Lintang.
"Terima kasih ya Pak, sudah dipisahin. Kalau enggak ...."
"Iya. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Nggak baik berantem gitu, apalagi sama teman sendiri," ujar laki laki itu.
"Terima kasih ya Pak, sudah dipisahin. Kalau enggak ...."
"Iya. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Nggak baik berantem gitu, apalagi sama teman sendiri," ujar laki laki itu.
"Oh ya, kamu Wulan kan? Anaknya Pak Joko yang tinggal diatas tanjakan sana?"
"Darimana bapak tahu?" tanya Wulan heran.
"Hahaha, siapa yang tak mengenal cucunya mbah Kendhil yang tersohor itu. Sebentar, aku punya sesuatu buat kalian,"
"Darimana bapak tahu?" tanya Wulan heran.
"Hahaha, siapa yang tak mengenal cucunya mbah Kendhil yang tersohor itu. Sebentar, aku punya sesuatu buat kalian,"
laki laki itu mengambil bungkusan kantong plastik yang tergantung di stang motornya.
"Ini untuk kalian." laki laki itu menyodorkan bungkusan plastik di tangannya, yang segera disambut oleh Lintang.
"Apa ini Pak?" Lintang buru buru menerima bungkusan itu dan mengintip isinya.
"Ini untuk kalian." laki laki itu menyodorkan bungkusan plastik di tangannya, yang segera disambut oleh Lintang.
"Apa ini Pak?" Lintang buru buru menerima bungkusan itu dan mengintip isinya.
"Wah, ayam panggang! Terima kasih banyak ya Pak."
"Iya. Ya sudah, kalian pulang saja sana. Nanti disini malah berantem lagi sama mereka," ujar laki laki itu sambil menyalakan mesin motornya.
"Iya. Ya sudah, kalian pulang saja sana. Nanti disini malah berantem lagi sama mereka," ujar laki laki itu sambil menyalakan mesin motornya.
"Kenapa kau ambil makanan itu? Kita kan tidak kenal sama orang itu?!" tegur Wulan saat mereka berjalan pulang.
"Rejeki nggak boleh ditolak Lan. Kapan lagi bisa makan ayam panggang secara cuma cuma," jawab Lintang.
"Rejeki nggak boleh ditolak Lan. Kapan lagi bisa makan ayam panggang secara cuma cuma," jawab Lintang.
"Huuuuu ...! Dasar gembul! Kalau lihat makanan enak, matanya langsung ijo!" sungut Wulan, yang disambut dengan tawa terkekeh oleh Lintang.
***
***
Bu Ratih menghenyakkan pantatnya diatas kursi. Guru muda itu menghela nafas sejenak, lalu menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Wajahnya sedikit mendongak, dengan kelopak mata terpejam.
Bagian belakang kepalanya terasa sedikit berdenyut, menahan rasa pening yang tiba tiba menyerang.
Ah, kenapa harus aku? Batinnya mendesah. Baru beberapa menit yang lalu ia menghadap Pak Slamet, Kepala Sekolah di Sekolah Dasar tempat ia mengabdi itu.
Ah, kenapa harus aku? Batinnya mendesah. Baru beberapa menit yang lalu ia menghadap Pak Slamet, Kepala Sekolah di Sekolah Dasar tempat ia mengabdi itu.
Bu Ratih sudah menduga, bahwa ia dipanggil sehubungan dengan keributan kecil yang baru saja terjadi di gerbang sekolah tadi. Memang, sumber keributan itu adalah salah satu murid yang menjadi tanggung jawabnya.
Tapi ia tak habis mengerti, kenapa Pak Slamet memberikan tugas itu padanya. Tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Bu Anna, guru pembimbing di sekolah itu.
"Wulan anak yang istimewa Bu, jadi harus ditangani oleh orang yang istimewa juga. Lagipula ia murid Bu Ratih bukan?" demikian alasan Pak Slamet tadi.
Ia tak habis mengerti dengan alasan Kepala Sekolah itu. Apanya yang istimewa? Ia memang sedikit memiliki kelebihan.
Ia tak habis mengerti dengan alasan Kepala Sekolah itu. Apanya yang istimewa? Ia memang sedikit memiliki kelebihan.
Tapi kelebihan itu tak ada sangkut pautnya dengan profesinya sebagai tenaga pendidik. Dan anak bernama Wulan itu, anak itu lebih tepat disebut mengerikan daripada istimewa.
Pelan guru muda itu menegakkan punggungnya. Sebelah tangannya membuka sebuah map yang tadi diberikan oleh Pak Slamet. Sedang tangan sebelahnya lagi meraih kacamata minus yang tergelerak diatas meja, lalu mengenakannya.
Ia semakin terlihat cantk jika mengenakan kacamata, begitu kata orang orang. Bu Ratih sendiri tidak pernah menyadarinya. Ia memakai kacamata bukan semata mata karena ingin tampil cantik, melainkan karena matanya memang sedikit mengalami kelainan.
Dari balik lensa, mata guru muda itu mulai sibuk menelusuri kata demi kata yang tertulis diatas kertas itu. Wulan, Ratih Wulansari, nama depan anak itu sama persis dengan namanya. Anak berusia sebelas tahun itu memang salah satu murid di kelasnya.
Lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, orang tua bla bla bla, empat kali terpaksa harus pindah sekolah karena kasus yang hampir sama. Kasus yang sama juga dengan yang tadi terjadi di gerbang sekolah.
Bertengkar dengan sesama siswa, hingga melukai dan bahkan diduga secara tidak langsung ia menyebabkan teman bertengkarnya itu .... meninggal!
Bu Ratih mengerutkan dahinya saat membaca kata yang terakhir itu.
Bu Ratih mengerutkan dahinya saat membaca kata yang terakhir itu.
Rasanya terlalu berlebihan jika seorang anak perempuan berusia dibawah sepuluh tahun disebut sebagai pembunuh.
Kasus pertama, guru muda itu melanjutkan membaca. Terjadi satu setengah tahun yang lalu. Wulan terlibat percekcokan dengan teman sekelasnya, hanya karena masalah sepele
Kasus pertama, guru muda itu melanjutkan membaca. Terjadi satu setengah tahun yang lalu. Wulan terlibat percekcokan dengan teman sekelasnya, hanya karena masalah sepele
Saling meledak dan berujung dengan pertengkaran. Kenakalan khas anak seusianya. Sampai akhirnya Wulan kehilangan kendali dan meneriakkan kata kata kutukan.
Kutukan? Kembali dahi Bu Ratih berkerut. Siapa yang menulis laporan dengan kata kata ngawur seperti ini?
Kutukan? Kembali dahi Bu Ratih berkerut. Siapa yang menulis laporan dengan kata kata ngawur seperti ini?
"Mudah mudahan perutmu robek dan habis dimakan belatung!" demikian kata kata yang diucapkan Wulan saat itu, saat ia mengetahui bahwa salah seorang teman sekelasnya menyembunyikan bekal makan siang miliknya.
Entah kebetulan atau bagaimana, dua hari kemudian ucapan Wulan itu benar benar menjadi kenyataan. Rudi, anak yang disumpahi Wulan itu mengalami kecelakaan tragis. Ia terjatuh saat sedang memanjat pohon mangga milik tetangganya.
Lagi lagi kenakalan khas anak kecil, mencuri mangga milik tetangga.
Sebenarnya tidak terlalu tinggi anak itu memanjat, dan secara logika kalaupun sampai jatuh tak akan berakibat fatal. Namun sepertinya Rudi salah memilih lokasi untuk mendaratkan tubuhnya.
Sebenarnya tidak terlalu tinggi anak itu memanjat, dan secara logika kalaupun sampai jatuh tak akan berakibat fatal. Namun sepertinya Rudi salah memilih lokasi untuk mendaratkan tubuhnya.
Pohon mangga yang dipanjatnya itu tumbuh persis di sebelah pagar besi yang memiliki ujung ujung yang runcing. Saat terjatuh, bagian perutnya tersangkut diujung pagar yang runcing itu, dan ....
Bu Ratih tak berani melanjutkan membaca. Sampai di kalimat itu, ia jadi paham kenapa Wulan sampai dibilang mengucapkan kata kata kutukan. Guru muda itu mengusap tengkuknya yang tiba tiba meremang. Segera dibaliknya kertas di tangannya itu.
Kasus berikutnya, hampir sama, namun terjadi di sekolah yang berbeda. Pertengkaran kecil berubah menjadi sumpah serapah, yang diakhiri dengan meninggalnya salah seorang siswa karena tercebur kedalam kolam ikan, beberapa hari setelah pertengkaran itu. Anak itu tak bisa berenang.
Dan saat ditemukan mayatnya sudah membengkak, sama persis seperti sumpah serapah yang diucapkan Wulan saat mereka bertengkar beberapa hari sebelumnya. Begitu juga kasus yang ketiga dan keempat.
Semuanya melibatkan pertengkaran, sumpah serapah, dan diakhiri dengan melayangnya satu nyawa anak manusia.
Ditambah dengan kejadian di gerbang sekolah tadi, total sudah lima kasus yang dikantongi anak bernama Wulan ini.
Ditambah dengan kejadian di gerbang sekolah tadi, total sudah lima kasus yang dikantongi anak bernama Wulan ini.
Meski di kejadian kali ini, Wulan tak sempat mengucapkan kata kata 'kutukan.' Seorang anak laki laki bernama Lintang berhasil membekap mulutnya, sebelum gadis kecil itu benar benar meradang.
Lintang? Bukan anak laki laki itu yang tadi bermasalah dengan Wulan.
Lintang? Bukan anak laki laki itu yang tadi bermasalah dengan Wulan.
Ia justru teman dekat Wulan, bahkan bisa dibilang kalau Lintang ini satu satunya teman yang dimiliki oleh Wulan. Lalu kenapa?
Bu Ratih berpikir keras, dan satu kesimpulanpun ia dapat. Lintang teman dekat Wulan, sudah pasti ia paham betul soal tabiat Wulan.
Bu Ratih berpikir keras, dan satu kesimpulanpun ia dapat. Lintang teman dekat Wulan, sudah pasti ia paham betul soal tabiat Wulan.
Tapi, apakah ia juga paham dengan kata kata 'kutukan' milik Wulan, sehingga dengan sigap ia segera membekap mulut Wulan sebelum kutukan itu terlanjur diucapkan?
Kutukan. Kutukan. Kutukan. Bu Ratih menggeleng pelan. Ia berusaha membuang jauh jauh kata kata itu.
Kutukan. Kutukan. Kutukan. Bu Ratih menggeleng pelan. Ia berusaha membuang jauh jauh kata kata itu.
Sebagai seorang tenaga pendidik, ia harus bisa berpikir logis. Ia tak boleh terpancing rumor yang tak bisa dipertanggungjawabkan itu. Namun semakin ia berusaha mengesampingkan kata kata itu, justru ia semakin yakin, bahwa kata kata itu bukan sekedat rumor belaka.
Otaknya berpikir untuk menolak, tapi hati nuraninya justru semakin meyakini. Mungkin ini yang dimaksud keistimewaan oleh Pak Slamet tadi.
Kembali guru muda itu melepas kacamatanya, lalu menyandarkan punggungnya di sandaran kursi.
Kembali guru muda itu melepas kacamatanya, lalu menyandarkan punggungnya di sandaran kursi.
Pelan dipijitnya pangkal hidungnya, sekedar untuk mengurangi rasa pening yang tiba tiba datang menyerang.
Aku seorang guru. Tugasku mengajar dan mendidik semua anak murid yang menjadi tanggung jawabku.
Aku seorang guru. Tugasku mengajar dan mendidik semua anak murid yang menjadi tanggung jawabku.
Pun jika ada anak muridku yang terlibat masalah, aku harus menuntunnya untuk kembali ke jalan yang benar. Ini semua harus segera diakhiri. Anak bernama Wulan itu butuh bimbingan, bukan hukuman, batin guru muda itu.
"Belum pulang Bu?" sebuah suara mengejutkan guru muda itu.
"Belum pulang Bu?" sebuah suara mengejutkan guru muda itu.
Suara khas yang sangat dikenalnya, membuat Bu Ratih segera memperbaiki posisi duduknya.
"Eh, sebentar lagi Pak," gugup Bu Ratih menjawab, sambil menoleh kearah pintu, tempat dimana Pak Slamet berdiri menatapnya.
"Mau saya antar?" ujar laki laki itu lagi.
"Eh, sebentar lagi Pak," gugup Bu Ratih menjawab, sambil menoleh kearah pintu, tempat dimana Pak Slamet berdiri menatapnya.
"Mau saya antar?" ujar laki laki itu lagi.
"Ah, terimakasih Pak. Tapi sepertinya tidak perlu. Saya bisa pulang sendiri, dan ..., masih ada sedikit tugas yang harus saya selesaikan," tolak Bu Ratih sopan.
"Ya sudah kalau begitu, saya pulang duluan ya," ada sedikit gurat kekecewaan di wajah Pak Slamet saat mengucapkan kalimat itu. Bu Ratih bukannya tak tahu. Tapi ia pura pura tidak tahu. Biar bagaimanapun, ia tak ingin ada rumor tak sedap menyebar tentang dirinya.
Pak Slamet masih lajang, meski usianya sudah tak lagi muda. Sedangkan dirinya, sampai saat ini juga masih sendiri. Jika orang melihat ia sering bersama laki laki itu, maka mulut mulut usil pasti akan segera sibuk memberikan komentar miring.
Joko baru saja pulang dari ladang, saat sepeda motor itu berbelok memasuki halaman pondoknya. Pengemudinya turun, lalu bergegas menghampirinya.
"Pak Darsa?" gumam Joko lirih. Ia kenal betul dengan laki laki berpakaian necis itu.
"Pak Darsa?" gumam Joko lirih. Ia kenal betul dengan laki laki berpakaian necis itu.
Orang terkaya sekecamatan, tengkulak yang biasa membeli hasil panen para warga.
"Dimana anakmu?" tanya laki laki berpakaian necis itu tanpa basa basi.
"Eh, ada perlu apa ya Pak mencari anak saya?" Joko meletakkan cangkulnya, lalu mempersilahkan tamunya duduk.
"Dimana anakmu?" tanya laki laki berpakaian necis itu tanpa basa basi.
"Eh, ada perlu apa ya Pak mencari anak saya?" Joko meletakkan cangkulnya, lalu mempersilahkan tamunya duduk.
"Saya mau minta ganti rugi," kata laki laki itu ketus.
"Ganti rugi?" tanya Joko heran.
"Ganti rugi?" tanya Joko heran.
"Anakmu memukuli anak saya tadi di sekolah. Sampai babak belur. Kakinya lecet lecet, dahinya benjol, dan pergelangan tangannya terkilir! Saya nggak mau tau, saya minta ganti rugi untuk biaya pengobatan!" laki laki itu menyebutkan nominal angka rupiah yang lumayan besar.
"Sebanyak itu ya Pak?" Joko menelan ludah. Pahit. Lagi lagi Wulan bikin ulah. Dan dia sebagai orang tua yang harus menanggung akibatnya.
" Kau pikir biaya berobat ke dokter murah? Mahal! Tapi pantas kalau orang kampung seperti kalian tidak tahu. Biasa berobat ke dukun sih..."
" Kau pikir biaya berobat ke dokter murah? Mahal! Tapi pantas kalau orang kampung seperti kalian tidak tahu. Biasa berobat ke dukun sih..."
"..Pokoknya saya minta ganti rugi. Kalau tidak, urusannya akan jadi panjang. Saya bisa ...."
"Baik Pak," potong Joko cepat. Ia tak mau lagi mendengar kata kata orang kaya yang sombong itu. Terlalu pedas dan menyakitkan. "Tunggu sebentar, biar saya ambilkan uangnya."
"Baik Pak," potong Joko cepat. Ia tak mau lagi mendengar kata kata orang kaya yang sombong itu. Terlalu pedas dan menyakitkan. "Tunggu sebentar, biar saya ambilkan uangnya."
Joko segera masuk kedalam bilik, dimana Romlah istrinya, ternyata sedang menguping pembicaraannya tadi.
"Bang," bisik Romlah saat Joko membuka lemari dan mengambil beberapa lembar uang simpanan mereka.
"Bang," bisik Romlah saat Joko membuka lemari dan mengambil beberapa lembar uang simpanan mereka.
"Abang percaya dengan laki laki itu? Dia bohong Bang. Aku lihat sendiri tadi, anaknya sehat wal afiat. Jangankan luka, lecetpun ia tidak. Dan Abang akan memberikan uang kita begitu saja pasa laki laki itu?"
"Tak apa," Joko tersenyum menatap sang istri.
"Tak apa," Joko tersenyum menatap sang istri.
"Uang bisa dicari lagi. Abang cuma tak mau ribut dengan orang itu."
Romlah memberengut. Tapi ia tak bisa berbuat banyak. Perempuan itu tahu betul sifat sang suami. Ia hanya bisa pasrah melihat punggung sang suami yang melangkah keluar dari bilik.
Romlah memberengut. Tapi ia tak bisa berbuat banyak. Perempuan itu tahu betul sifat sang suami. Ia hanya bisa pasrah melihat punggung sang suami yang melangkah keluar dari bilik.
"Ini Pak, sesuai dengan yang bapak minta," Joko memberikan lembaran lembaran uang itu kepada tamunya. Pak Darsa segera menghitungnya, lalu memasukkan kedalam saku rompi kulit yang dikenakannya.
"Ingat, didik baik baik anakmu itu, jangan sampai mencelakai anak orang lagi. Anak perempuan kok sukanya berantem!" tanpa permisi apalagi berterimakasih, laki laki itu langsung pergi dengan langkah yang angkuh.
"Pembohong!" sungut Romlah yang tiba tiba muncul dari dalam bilik.
"Pembohong!" sungut Romlah yang tiba tiba muncul dari dalam bilik.
Joko tersenyum kecut sambil menatap sang istri. "Biarkan sajalah, capek aku kalau harus lama lama meladeni orang seperti itu."
"Tapi uang kita Bang, teganya dia menipu kita. Orang tadi aku lihat anaknya sehat sehat saja kok. Bisa bisanya dia ..."
"Tapi uang kita Bang, teganya dia menipu kita. Orang tadi aku lihat anaknya sehat sehat saja kok. Bisa bisanya dia ..."
"Sudahlah, lebih baik kita kehilangan uang daripada harus meladeni orang licik seperti dia. Kamu tahu sendiri kan orang seperti apa dia. Lebih baik sekarang cepat siapkan makan. Aku sudah lapar nih."
Meski masih cemberut, toh Romlah akhirnya beranjak juga ke dapur, menyiapkan makan siang untuk sang suami yang sudah kelaparan karena semenjak pagi bekerja di ladang.
"Maaakkk ...!!! Wulan pulaaannngggg ...!!!" suara cempreng Wulan terdengar nyaring, disusul dengan kemunculan bocah itu diambang pintu.
"Darimana Lan? Kenapa bajumu basah kuyup begitu? Main di kali ya?" hardik Joko menyambut kedatangan sang anak.
"Darimana Lan? Kenapa bajumu basah kuyup begitu? Main di kali ya?" hardik Joko menyambut kedatangan sang anak.
"Hehe, iya Pak. Lihat nih, Wulan dapat ikan banyak," seru anak itu sambil menunjukkan serenteng ikan yang dibawanya.
"Ya sudah, kasih ikan itu ke emakmu, setelah itu ganti baju, dan makan bareng bapak," ujar Joko sambil tersenyum melihat tingkah sang anak.
"Ya sudah, kasih ikan itu ke emakmu, setelah itu ganti baju, dan makan bareng bapak," ujar Joko sambil tersenyum melihat tingkah sang anak.
"Kamu juga ya Lintang, sekalian saja ikut makan disini."
"Eh, iya Pakdhe, terimakasih," Lintang tampak malu malu duduk di kursi yang ada di ruangan itu.
"Bawa apa itu?" tanya Joko melihat Lintang menenteng bungkusan plastik di tangannya.
"Eh, iya Pakdhe, terimakasih," Lintang tampak malu malu duduk di kursi yang ada di ruangan itu.
"Bawa apa itu?" tanya Joko melihat Lintang menenteng bungkusan plastik di tangannya.
"Ini pakdhe, tadi dikasih ayam panggang sama orang dijalan," jawab Lintang.
"Wah, baik betul orang itu, sampai ....," Joko tak melanjutkan kata katanya, karena dari arah dapur terdengar suara istrinya yang mengomel panjang pendek.
"Wah, baik betul orang itu, sampai ....," Joko tak melanjutkan kata katanya, karena dari arah dapur terdengar suara istrinya yang mengomel panjang pendek.
Sepertinya perempuan itu sedang mengomeli anak semata wayang mereka.
"Romlah!" serunya.
"Iya Bang, sebentar!" sahut Romlah dari arah dapur.
"Eh, pak, barusan ada tamu ya?" tanya Wulan yang tiba tiba muncul dari arah dapur.
"Iya," sahut Joko pendek.
"Siapa tamunya Pak?"
"Romlah!" serunya.
"Iya Bang, sebentar!" sahut Romlah dari arah dapur.
"Eh, pak, barusan ada tamu ya?" tanya Wulan yang tiba tiba muncul dari arah dapur.
"Iya," sahut Joko pendek.
"Siapa tamunya Pak?"
"Pak Darsa."
"Siapa itu Pak Darsa?"
"Kamu nggak kenal Pak Darsa?"
Wulan menggeleng.
"Itu lho Lan, orang yang tadi ngasih ayam bakar ke kita," sahut Lintang.
"Owh," Wulan memonyongkan bibirnya.
"Siapa itu Pak Darsa?"
"Kamu nggak kenal Pak Darsa?"
Wulan menggeleng.
"Itu lho Lan, orang yang tadi ngasih ayam bakar ke kita," sahut Lintang.
"Owh," Wulan memonyongkan bibirnya.
"Kata emak dia minta duit ya sama bapak, gara gara anaknya tadi berantem sama Wulan di sekolah?"
"Jadi benar, tadi kamu berantem di sekolah?" tanya Joko menyelidik.
"Wulan hanya membela diri Pak. Tomy itu jahat, sama kayak bapaknya." kilah Wulan.
"Jadi benar, tadi kamu berantem di sekolah?" tanya Joko menyelidik.
"Wulan hanya membela diri Pak. Tomy itu jahat, sama kayak bapaknya." kilah Wulan.
"Kamu itu anak perempuan lho Lan, mbok jangan suka berkelahi begitu."
Wulan hanya nyengir mendengar nasehat sang bapak. Gadis itu justru mengalihkan perhatiannya kepada Lintang.
"Tang, kesinikan bungkusan itu," Wulan menyambar bungkusan plastik di tangan Lintang.
Wulan hanya nyengir mendengar nasehat sang bapak. Gadis itu justru mengalihkan perhatiannya kepada Lintang.
"Tang, kesinikan bungkusan itu," Wulan menyambar bungkusan plastik di tangan Lintang.
"Eh, tapi ...."
"Sudah sini," Wulan segera membuka bungkusan plastik berisi ayam panggang itu, lalu menyantap isinya dengan rakus.
"Sudah sini," Wulan segera membuka bungkusan plastik berisi ayam panggang itu, lalu menyantap isinya dengan rakus.
"Ayam panggang ini buatku saja ya, kamu makan ayam goreng yang dimasak emakku saja. Enak kok, lebih enak malah kalau dibandingkan dengan ayam panggang ini."
Lintang hanya bisa melongo, sambil melihat Wulan dengan rakusnya mengunyah ayam panggang itu sampai habis tak tersisa.
Lintang hanya bisa melongo, sambil melihat Wulan dengan rakusnya mengunyah ayam panggang itu sampai habis tak tersisa.
"GUBRAKKK!!!" Tubuh Lintang terhempas. Anak laki laki bertubuh gempal itu mengaduh lirih sambil mengusap usap jidatnya yang terbentur kaki ranjang kayu jati itu.
"Asem! ternyata cuma mimpi," gumam anak itu sambil tangannya meraba raba permukaan dinding, mencari saklar lampu.
"Asem! ternyata cuma mimpi," gumam anak itu sambil tangannya meraba raba permukaan dinding, mencari saklar lampu.
"Cklek!" suasana kamar yang awalnya gelap, berubah jadi terang benderang. Lintang tersenyum kecut melihat keadaan kamarnya. Ternyata bukan hanya tubuhnya yang barusan terhempas dari atas tempat tidur. Tapi bantal, guling, dan selimutnyapun kini telah berceceran dilantai.
Anak itu lalu duduk di sisi ranjang, setelah membereskan bantal gulingnya yang berantakan. Ia mencoba mengingat ingat mimpi yang baru saja ia alami. Mimpi yang sangat buruk. Juga menyeramkan. Ia bersyukur, semua itu hanyalah sebuah mimpi.
"Baru jam dua, lebih baik aku tidur kembali," gumam anak itu sambil menepuk nepuk bantalnya. Namun belum juga kepalanya menyentuh bantal, anak itu tertegun. Ada hawa hangat yang menjalar di sekitar lehernya. Wajah anak itu menegang.
Tangannya meraba kalung benang lawe dengan bandul bungkusan kain putih kumal yang dikenakannya.
"Jangan! Jangan lagi! Jangan sampai terjadi lagi! Aku harus mencegahnya!" Lintang terlihat panik.
"Jangan! Jangan lagi! Jangan sampai terjadi lagi! Aku harus mencegahnya!" Lintang terlihat panik.
Niatnya untuk kembali tidur diurungkannya. Ia justru membuka lemari dengan terburu buru, mengambil jaket, mengenakannya sambil melangkah kearah pintu.
"Bruk!!!" sangking terburu burunya, Lintang tak menyadari bahwa Mbak Patmi, sang ibu, telah berdiri di depan pintu kamarnya.
"Bruk!!!" sangking terburu burunya, Lintang tak menyadari bahwa Mbak Patmi, sang ibu, telah berdiri di depan pintu kamarnya.
Alhasil, tubuh gempalnya menabrak tubuh sang ibu.
"Lintang! Ngapain sih malam malam gedubrag gedabrug di kamar? Berisik banget tau! Dan itu ..., kamu pakai jaket mau kemana?!" seru Mbak Patmi.
"Eh, anu Mak, tolong dong anterin Lintang kerumah Wulan," jawab Lintang cepat.
"Lintang! Ngapain sih malam malam gedubrag gedabrug di kamar? Berisik banget tau! Dan itu ..., kamu pakai jaket mau kemana?!" seru Mbak Patmi.
"Eh, anu Mak, tolong dong anterin Lintang kerumah Wulan," jawab Lintang cepat.
"Kerumah Wulan?! Kamu ini ngigau apa gimana? Kau pikir sekarang jam berapa hah?!" sentak Mbak Patmi sambil menunjuk jam yang tersangkut di dinding.
"Lintang serius Mak, ini darurat, penting! Kalau emak nggak mau nganterin, Lintang akan kesana sendiri," tanpa memperdulikan omelan sang emak, Lintang bergegas membuka pintu dan menghambur keluar.
"Lintang! Tunggu! Dasar Bocah gendheng!" mau tak mau Mbak Patmipun bergegas mengikuti sang anak sambil mulutnya tak henti hentinya mengomel. Semenjak bergaul dengan bocah Salahan itu, sifat Lintang memang berubah menjadi sedikit aneh.
***
***
Sementara itu dirumah Wulan.
Suara berisik dari ranting dan dedaunan yang saling bergesekan dipermainkan angin diluar pondok membangunkan Romlah. Perempuan itu menggeliat, lalu turun dari tempat tidurnya.
Suara berisik dari ranting dan dedaunan yang saling bergesekan dipermainkan angin diluar pondok membangunkan Romlah. Perempuan itu menggeliat, lalu turun dari tempat tidurnya.
Dilihatnya Joko, sang suami, masih terlelap dalam tidurnya, seolah tak merasa terganggu oleh suara berisik diluar pondok.
"Tumben malam ini anginnya kencang banget. Apakah akan turun hujan?" gumam Romlah sambil beranjak keluar dari bilik.
"Tumben malam ini anginnya kencang banget. Apakah akan turun hujan?" gumam Romlah sambil beranjak keluar dari bilik.
Tenggorokannya terasa kering. Ia bermaksud untuk kedapur, sekedar mengambil air minum untuk membasahi tenggorokannya.
"Wulan! Kebiasaan anak itu. Pasti dia lupa menutup pintu kamarnya lagi," gerutu Romlah saat melihat pintu kamar sang anak terbuka lebar.
"Wulan! Kebiasaan anak itu. Pasti dia lupa menutup pintu kamarnya lagi," gerutu Romlah saat melihat pintu kamar sang anak terbuka lebar.
Niatnya untuk ke dapur ia urungkan. Ia justru melangkah ke arah kamar sang anak, bermaksud untuk menutup pintu itu.
"Lho, Wulan?!" Romlah terperanjat saat mendapati ranjang sang anak kosong. Romlah menutup pintu kamar itu, lalu melangkah menuju ke pintu depan. Sedikit terbuka.
"Lho, Wulan?!" Romlah terperanjat saat mendapati ranjang sang anak kosong. Romlah menutup pintu kamar itu, lalu melangkah menuju ke pintu depan. Sedikit terbuka.
Ah, mungkin Wulan ke kamar mandi, batin Romlah. Kamar mandi di pondok itu memang terletak di luar. Tepatnya disamping kiri pondok, menyatu dengan bangunan sumur dan dapur.
"Wulaaannn!" seru Romlah sambil membuka pintu dan keluar. Hembusan angin kencang segera menyambutnya, disertai hawa dingin yang menggigit kulit.
"Wulan, kamu ngapain di ...." Romlah tercekat saat mendapati sang anak berdiri mematung di halaman pondok.
"Wulan, kamu ngapain di ...." Romlah tercekat saat mendapati sang anak berdiri mematung di halaman pondok.
Angin yang bertiup kencang mempermainkan rambut panjangnya.
"Diam disitu Mak! Ada orang jahat yang mau mencelakai Wulan!" teriak Wulan tanpa menoleh sedikitpun kearah emaknya.
"Wulan ..."
"Wulan benci orang jahat! Wulan nggak suka!"
"Diam disitu Mak! Ada orang jahat yang mau mencelakai Wulan!" teriak Wulan tanpa menoleh sedikitpun kearah emaknya.
"Wulan ..."
"Wulan benci orang jahat! Wulan nggak suka!"
"Wulan ...!" Romlah segera menghampiri anak itu. Nalurinya mengatakan, ada sesuatu yang tidak beres dengan sang anak. Dan benar saja, begitu ia sampai di hadapan sang anak, Romlah terkejut bukan kepalang.
Wajah Wulan, wajah anak itu terlihat meringis bengis. Tak ada lagi rona ceria yang biasanya selalu menghiasi wajah Wulan. Dan matanya, mata anak itu mendelik lebar, dengan hanya memperlihatkan bagian putihnya saja.
"Baaaannggg ...!!!" sontak Romlah menjerit memanggil sang suami.
"Baaaannggg ...!!!" sontak Romlah menjerit memanggil sang suami.
"Ada ap ...?!" Joko yang muncul di pintu juga terkesiap melihat pemandangan yang tak wajar itu.
"Wulan Bang, Wulan ...."
Joko segera menghampiri kedua emak beranak itu. Angin bertiup semakin kencang. Udara juga terasa semakin dingin.
"Wulan Bang, Wulan ...."
Joko segera menghampiri kedua emak beranak itu. Angin bertiup semakin kencang. Udara juga terasa semakin dingin.
Awan hitam berarak diatas sana, menelan bintang bintang dan rembulan yang sejak tadi menerangi malam.
"Wulan benci orang jahat! Wulan nggak suka! Orang jahat harus dihukum!" Wulan mendesis tajam.
"Wulan, sadar nak. Ini emak sama bapak. Bukan orang jahat!" seru Romlah.
"Wulan benci orang jahat! Wulan nggak suka! Orang jahat harus dihukum!" Wulan mendesis tajam.
"Wulan, sadar nak. Ini emak sama bapak. Bukan orang jahat!" seru Romlah.
"Sadar Wulan! Sadar!"
"Disana Mak. Orang jahat itu mengintip dari balik pohon. Dia mau mencelakai Wulan!"
"Wulan! Hentikan!!!" dari arah jalan desa muncul Lintang yang berlari kearah Wulan, diikuti oleh Mbak Patmi yang juga berlari sambil mengangkat roknya tinggi tinggi.
"Disana Mak. Orang jahat itu mengintip dari balik pohon. Dia mau mencelakai Wulan!"
"Wulan! Hentikan!!!" dari arah jalan desa muncul Lintang yang berlari kearah Wulan, diikuti oleh Mbak Patmi yang juga berlari sambil mengangkat roknya tinggi tinggi.
"Orang jahat harus dihukum! Orang jahat harus dihukum! Harus dihukum! Dihukum!"
"Wulaaannn!!!"
"Kau harus dihukum!!!" Wulan menunjuk kearah pohon sengon besar yang tumbuh tak jauh di depan mereka.
"Wulaaannn!!!"
"Kau harus dihukum!!!" Wulan menunjuk kearah pohon sengon besar yang tumbuh tak jauh di depan mereka.
Angin bertiup semakin kencang, seolah menahan langkah Lintang yang mencoba mendekati Wulan. Hawa hangat yang sejak tadi dirasakan oleh Lintang di bagian lehernya, pelan pelan berubah menjadi hawa panas.
"Wulan! Hentikaann!!!" terseok seok Lintang terus berusaha mendekat.
"Wulan! Hentikaann!!!" terseok seok Lintang terus berusaha mendekat.
Namun sepertinya ia terlambat. Angin semakin kencang. Awan hitam semakin tebal. Udara semakin dingin. Sementara hawa panas di leher Lintang terasa membakar kulit.
"MATILAH KAU ORANG JAHAT!!!" Wulan menjerit kencang, disusul dengan kilatan petir dan dentuman guntur yang menggelegar, menyambar pohon sengon besar yang ditunjuk oleh Wulan.
"BLAAARRRRR...!!!" Ledakan dahsyat terdengar. Pohon itu terbelah dan tumbang. Begitu juga dengan Wulan.
"BLAAARRRRR...!!!" Ledakan dahsyat terdengar. Pohon itu terbelah dan tumbang. Begitu juga dengan Wulan.
Tubuh anak itu tiba tiba ambruk. Lintang jatuh terduduk. Dari bibirnya meluncur kalimat penyesalan.
"Aku terlambat!!!" Anak bertubuh gempal itu meninju tanah dengan keras.
***
"Aku terlambat!!!" Anak bertubuh gempal itu meninju tanah dengan keras.
***
"Eh, ada apa ini Mak? Kok pada ngumpul disini?" Wulan menatap bingung kearah orang orang yang mengelilinginya. Ada emak dan bapaknya, ada juga Lintang dan Budhe Patmi.
"Ah, syukurlah, kau sudah sadar," Romlah memeluk anak semata wayangnya itu.
"Ah, syukurlah, kau sudah sadar," Romlah memeluk anak semata wayangnya itu.
"Ada apa Mak?" lagi lagi Wulan bertanya heran.
"Ndak ada apa apa kok. Kamu tidur lagi ya, hari masih malam ini," kata Joko.
"Malam? Kamu ngapain malam malam kesini Tang?" Wulan menatap kearah Lintang yang sejak tadi hanya diam membisu.
"Ndak ada apa apa kok. Kamu tidur lagi ya, hari masih malam ini," kata Joko.
"Malam? Kamu ngapain malam malam kesini Tang?" Wulan menatap kearah Lintang yang sejak tadi hanya diam membisu.
"Ndak papa kok. Tadi Budhe yang minta agar Lintang nganterin Budhe kesini. Budhe ada perlu sama emakmu," Mbak Patmi yang menjawab pertanyaan Wulan itu, karena Lintang masih saja diam seribu bahasa. "Lah, sebaiknya kau temani anakmu tidur. Aku pamit pulang dulu ya," lanjutnya.
"Iya Mbak. Makasih banyak ya, Mbak Patmi sudah banyak membantu," ujar Romlah.
"Iya, ndak papa. Kita kan tetangga, sudah sewajarnya kalau saling membantu. Ya sudah, kami pamit ya. Ayo Tang, kita pulang."
Mbak Patmipun menggandeng tangan anaknya.
"Iya, ndak papa. Kita kan tetangga, sudah sewajarnya kalau saling membantu. Ya sudah, kami pamit ya. Ayo Tang, kita pulang."
Mbak Patmipun menggandeng tangan anaknya.
Tersaruk saruk mereka menyusuri jalanan yang gelap itu. Mbak Patmi tak sempat membawa senter tadi, karena terlalu terburu buru.
"Tang, kenapa kamu tiba tiba tadi mengajak kerumah Wulan? Sepertinya kamu tau kalau akan terjadi sesuatu?" tanya Mbak Patmi.
"Tang, kenapa kamu tiba tiba tadi mengajak kerumah Wulan? Sepertinya kamu tau kalau akan terjadi sesuatu?" tanya Mbak Patmi.
"Lintang mimpi Mak," jawab Lintang pendek.
"Mimpi? Mimpi apa?" tanya Mbak Patmi lagi.
"Mimpi buruk."
"Mimpi buruk? Mimpi buruk yang seperti apa?"
"Wulan berkelahi dengan monyet besar. Monyet itu dibunuhnya. Dan setelah mati, monyet itu berubah menjadi ...."
"Menjadi apa?"
"Mimpi? Mimpi apa?" tanya Mbak Patmi lagi.
"Mimpi buruk."
"Mimpi buruk? Mimpi buruk yang seperti apa?"
"Wulan berkelahi dengan monyet besar. Monyet itu dibunuhnya. Dan setelah mati, monyet itu berubah menjadi ...."
"Menjadi apa?"
"Ah, entahlah Mak. Kita lihat saja besok. Mudah mudahan tidak terjadi sesuatu yang buruk," Lintang melangkah lebih cepat, mendahului sang emak. Mbak Patmi paham, Lintang tak mau lagi membicarakan soal mimpi buruknya.
Hari minggu. Seharusnya menjadi hari yang menyenangkan buat Bu Ratih. Sekolah libur, otomatis ia juga libur mengajar. Biasanya di hari Minggu begini ia menghabiskan waktu luangnya bersama keluarga kecilnya. Pak Soleh sang ayah, dan Ramadhan, adik semata wayangnya.
Ibunya memang telah lama tiada. Jadi otomatis hanya kedua orang itulah yang kini menjadi keluarganya.
Namun hari Minggu kali ini ada yang sedikit berbeda. Pagi pagi sekali guru muda itu sudah berdandan rapi.
Namun hari Minggu kali ini ada yang sedikit berbeda. Pagi pagi sekali guru muda itu sudah berdandan rapi.
Dandanan yang sederhana sebenarnya, hanya sedikit polesan bedak di wajah, dan olesan lipstik berwarna cerah di bibir tipisnya. Pakaian yang dikenakannyapun cukup sederhana.
Namun dasarnya Bu Ratih memang sudah cantik, dandanan yang sederhana itu sudah lebih dari cukup untuk memunculkan aura kecantikannya.
Setelah berpamitan dengan sang ayah, Bu Ratih segera menjalankan pelan pelan sepeda motor bebeknya, menyusuri jalanan desa yang berdebu karena telah lama tak tersiram hujan.
Sesekali ia melempar senyum dan sapa saat berpapasan dengan para penduduk desa yang hendak berangkat ke ladang.
Tempat yang pertama kali ia tuju adalah rumah Uwaknya, Wak Dul atau yang biasa dipanggil Pak Modin oleh para warga desa.
Tempat yang pertama kali ia tuju adalah rumah Uwaknya, Wak Dul atau yang biasa dipanggil Pak Modin oleh para warga desa.
Tugas dari Pak Slametlah yang mengantarkan guru muda itu untuk mengunjungi kakak dari ayahnya itu.
"Lebih baik kamu temui dulu Uwakmu. Dia yang tau banyak soal keluarga Joko yang tinggal di Tegal Salahan itu," demikian saran sang ayah tadi sebelum ia berangkat.
"Lebih baik kamu temui dulu Uwakmu. Dia yang tau banyak soal keluarga Joko yang tinggal di Tegal Salahan itu," demikian saran sang ayah tadi sebelum ia berangkat.
Bukan tanpa alasan ia bermaksud untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum menemui Wulan. Tugas yang diembannya memang lumayan berat, meski hanya sekedar menemui seorang anak usia sebelas tahun yang juga adalah anak didiknya.
Entah mengapa, ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan anak bernama Wulan itu. Bukan semata mata karena kenakalannya. Tapi hati kecilnya mengatakan kalau anak itu menyimpan sesuatu yang sulit untuk diterima oleh akal sehatnya.
"Harusnya, sebagai gurunya kamu lebih tau. Kenapa kau malah bertanya padaku?" jawaban sang Uwak ternyata sedikit mengecewakan.
"Entahlah Wak. Aku merasa anak itu berbeda. Bahkan untuk menatap matanya terlalu lamapun aku tak berani," desah guru muda itu.
"Entahlah Wak. Aku merasa anak itu berbeda. Bahkan untuk menatap matanya terlalu lamapun aku tak berani," desah guru muda itu.
"Lalu, apa yang sudah bisa kau lihat dari anak itu?" tanya Wak Dul lagi.
"Masih gelap Wak. Tapi aku yakin itu adalah sesuatu yang sangat besar, semacam kekuatan yang akan menjadi sangat berbahaya jika anak itu tak bisa mengendalikannya.."
"Masih gelap Wak. Tapi aku yakin itu adalah sesuatu yang sangat besar, semacam kekuatan yang akan menjadi sangat berbahaya jika anak itu tak bisa mengendalikannya.."
"..Itu yang membuatku sedikit ragu untuk mendekatinya." ujar Bu Ratih pelan.
"Itu tidak sepenuhnya salah," Wak Dul menghembuskan asap rokoknya. "Mengingat anak itu adalah cucu dari Mbah Kendhil, jadi tidak mustahil kalau ia mewarisi apa yang dulu dimiliki oleh sang kakek."
"Itu tidak sepenuhnya salah," Wak Dul menghembuskan asap rokoknya. "Mengingat anak itu adalah cucu dari Mbah Kendhil, jadi tidak mustahil kalau ia mewarisi apa yang dulu dimiliki oleh sang kakek."
"Jadi rumor yang sering dikatakan oleh orang orang itu benar Wak?" tanya Bu Ratih.
"Rumor apa?" Wak Dul menatap lekat lekat wajah keponakannya itu.
"Soal kata kata kutukan dan ...."
"Bisa benar, bisa juga tidak," sanggah Wak Dul.
"Rumor apa?" Wak Dul menatap lekat lekat wajah keponakannya itu.
"Soal kata kata kutukan dan ...."
"Bisa benar, bisa juga tidak," sanggah Wak Dul.
"Tapi kamu tak perlu terlalu memikirkan soal itu. Kamu seorang guru. Tugasmu mendidik dan membimbing murid muridmu."
"Lalu aku harus bagaimana Wak?"
"Lalu aku harus bagaimana Wak?"
"Bagaimana? Ya kamu lakukan saja tugasmu dengan sebaik mungkin. Apa yang sudah menjadi kewajibanmu, maka harus kamu tunaikan dengan sebaik mungkin."
"Tapi tugas ini terlalu berat untukku Wak."
"Lalu, kamu mau menyerah begitu saja?"
"Tak bisakah Uwak membantuku?"
"Tapi tugas ini terlalu berat untukku Wak."
"Lalu, kamu mau menyerah begitu saja?"
"Tak bisakah Uwak membantuku?"
"Lho, bukankah aku sudah banyak membantu dengan nasehatku tadi?"
"Ah, maksud Ratih, bisakah Uwak menemaniku untuk menemui anak itu?"
"Ratih, Ratih, kapan kamu akan dewasa kalau masih terus terusan bergantung pada orang tua?"
"Ratih masih ragu Wak."
"Ah, maksud Ratih, bisakah Uwak menemaniku untuk menemui anak itu?"
"Ratih, Ratih, kapan kamu akan dewasa kalau masih terus terusan bergantung pada orang tua?"
"Ratih masih ragu Wak."
"Buang jauh jauh keraguanmu itu. Uwak yakin, dengan sedikit kemampuan yang kamu miliki, cepat atau lambat kamu pasti bisa membimbing anak itu. Temui anak itu, ajak dia bicara dari hati ke hati.."
"..Sebagai seorang guru, tak ada salahnya kalau kamu juga memposisikan dirimu sebagai seorang ibu untuk murid muridmu. Terutama untuk anak itu.."
"..Dan seperti yang kamu bilang tadi, kekuatan besar yang dimiliki anak itu akan menjadi sangat berbahaya kalau ia tidak bisa mengendalikannya. Itu berarti menjadi tugas tambahan untukmu.."
"..Bimbing dia, agar kekuatan yang ia miliki kelak bisa berguna tanpa harus membahayakan orang lain."
"Baiklah Wak," bu guru muda itu menghela nafas panjang.
"Akan Ratih coba. Tapi ...."
"Baiklah Wak," bu guru muda itu menghela nafas panjang.
"Akan Ratih coba. Tapi ...."
Ucapan Rarih terhenti saat tiba tiba seorang warga datang tergopoh gopoh memasuki halaman rumah Wak Dul.
"Ada apa Jo? Kenapa kamu lari lari kayak dikejar setan begitu?" tanya Wak Dul kepada orang itu.
"Anu Pak, ada kabar duka. Saya diutus Pak Bayan untuk menjemput Pak Modin,"
"Ada apa Jo? Kenapa kamu lari lari kayak dikejar setan begitu?" tanya Wak Dul kepada orang itu.
"Anu Pak, ada kabar duka. Saya diutus Pak Bayan untuk menjemput Pak Modin,"
jawab orang itu dengan nafas kembang kempis.
"Innalillahi! Siapa yang meninggal Jo?"
"Keluarga Pak Darsa Pak!"
"Keluarganya yang mana?"
"Semuanya Pak!"
"Semuanya?!"
"Innalillahi! Siapa yang meninggal Jo?"
"Keluarga Pak Darsa Pak!"
"Keluarganya yang mana?"
"Semuanya Pak!"
"Semuanya?!"
"Iya Pak. Istrinya, kedua anaknya, dan juga Pak Darsa sendiri!"
"Innalillahi wa innailaihi roji'un. Bagaimana ceritanya sampai bisa sekeluarga meninggal ...."
"Panjang ceritanya Pak. Dan sepertinya mereka meninggal dengan cara yang tak wajar.."
"Innalillahi wa innailaihi roji'un. Bagaimana ceritanya sampai bisa sekeluarga meninggal ...."
"Panjang ceritanya Pak. Dan sepertinya mereka meninggal dengan cara yang tak wajar.."
"..Pak Bayan sudah ke kantor polisi untuk melaporkannya."
"Ya sudah kalau begitu. Ayo kita kesana."
"Aku ikut ya Wak," sela Bu Ratih.
"Ayolah," sahut Wak Dul.
****
"Ya sudah kalau begitu. Ayo kita kesana."
"Aku ikut ya Wak," sela Bu Ratih.
"Ayolah," sahut Wak Dul.
****
Rumah besar di ujung desa itu telah ramai dipadati oleh warga desa. Petugas polisi dari kecamatan juga sudah datang. Pita kuning dipasang mengelilingi pagar rumah itu. Membuat warga yang penasaran harus rela gigit jari karena tak bisa menyaksikan apa yang ingin mereka ketahui.
Wak Dul bersama Pak Bayan telah masuk kedalam rumah itu bersama beberapa orang anggota polisi berseragam. Bu Ratih tak dizinkan untuk ikut masuk, meski ia sangat ingin tahu.
Akhirnya ia hanya bisa melihat dari kejauhan proses penyelidikan itu, sambil memasang telinga lebar lebar, menguping pembicaraan para warga yang masih berkerumun di sekitar rumah itu.
"Jangan jangan kena santet."
"Jangan jangan kena santet."
"Semuanya mati. Sekeluarga. Mayatnya gosong seperti habis dipanggang."
"Mungkin jadi tumbal pesugihannya."
"Aneh!
"Mengerikan!"
"Kasihan ya!"
"Kualat tuh, jadi orang kaya tapi pelit.!"
"Mungkin jadi tumbal pesugihannya."
"Aneh!
"Mengerikan!"
"Kasihan ya!"
"Kualat tuh, jadi orang kaya tapi pelit.!"
Simpang siur ocehan para warga, membuat kepala Bu Ratih menjadi pening. Pusing bukan kepalang. Ia mengerjapkan matanya, berusaha mengusir rasa pening itu. Namun bukannya hilang, kepalanya justru semakin berdenyut hebat. Pandangan matanya mulai mengabur.
Lalu tiba tiba semua menjadi gelap.
Tak ada lagi kerumunan orang. Tak terdengar lagi suara suara gaduh yang simpang siur. Bahkan suasana berubah menjadi sangat sepi. Sunyi dan gelap.
Tak ada lagi kerumunan orang. Tak terdengar lagi suara suara gaduh yang simpang siur. Bahkan suasana berubah menjadi sangat sepi. Sunyi dan gelap.
Bu Ratih merasa benar benar sendiri, berdiri mematung di depan rumah besar yang juga gelap dan sepi itu.
"Wulan?!" guru muda itu terkesiap saat mendapati gadis kecil itu telah berdiri di seberang jalan. Segera ia beranjak untuk mendekati anak itu.
"Wulan?!" guru muda itu terkesiap saat mendapati gadis kecil itu telah berdiri di seberang jalan. Segera ia beranjak untuk mendekati anak itu.
"Apa yang ...," langkah Bu Ratih terhenti, begitu juga dengan kalimat yang hendak diucapkannya.
Anak itu. Ada yang tak wajar dengan anak itu. Dengan jelas Bu Ratih bisa melihat, wajah anak itu terlihat sangat bengis.
Anak itu. Ada yang tak wajar dengan anak itu. Dengan jelas Bu Ratih bisa melihat, wajah anak itu terlihat sangat bengis.
Matanya mendelik lebar dan hanya menampakkan bagian putihnya saja. Bibirnya tersenyum sinis. Sebelah tangannya terangkat, menunjuk tepat kearah rumah Pak Darsa.
Angin tiba tiba bertiup kencang, mempermainkan rambut ekor kuda milik Wulan. Juga gaun putih yang dikenakannya.
Angin tiba tiba bertiup kencang, mempermainkan rambut ekor kuda milik Wulan. Juga gaun putih yang dikenakannya.
Awan hitam bergulung diatas sana, disertai kilatan cahaya petir dan suara guruh yang menggelegar.
"KALIAN SEMUA JAHAT! ORANG JAHAT HARUS DIHUKUM!"
"BLLAAAARRRRR ....!!!"
"AAAAAARRRGGHHH ...!!!"
"KALIAN SEMUA JAHAT! ORANG JAHAT HARUS DIHUKUM!"
"BLLAAAARRRRR ....!!!"
"AAAAAARRRGGHHH ...!!!"
Bu Ratih terjajar mundur beberapa langkah sambil menutup mulutnya, saat tiba tiba Wulan meneriakkan kata kata bernada mengancam itu, yang disusul dengan sambaran petir yang mengarah tepat ke rumah Pak Darsa, dan jerit kematian yang menyayat hati dari dalam rumah besar itu.
"Bu Ratih, anda tidak apa apa?" sebuah tangan menepuk bahu guru muda itu.
"Eh, Pak Slamet," gugup guru muda itu saat menyadari bahwa Pak Slamet telah berdiri di sebelahnya. "Enggak Pak, saya nggak papa."
"Eh, Pak Slamet," gugup guru muda itu saat menyadari bahwa Pak Slamet telah berdiri di sebelahnya. "Enggak Pak, saya nggak papa."
"Saya perhatikan sejak tadi Bu Ratih seperti melamun. Dan wajah ibu juga agak pucat. Ibu sakit?" tanya Pak Slamet lagi.
"Enggak Pak. Saya nggak papa kok," jawab Bu Ratih sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu.
"Enggak Pak. Saya nggak papa kok," jawab Bu Ratih sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu.
Tak didapatinya sosok Wulan yang tadi dilihatnya berdiri di seberang jalan. Tak ada awan hitam yang bergulung di atas sana. Tak ada kilatan cahaya petir dan suara guruh yang menggelegar. Yang ada hanya kerumunan warga yang semakin menyemut di tempat itu.
"Wulan, mungkinkah dia?"
"Wulan, mungkinkah dia?"
"Sepertinya ibu kurang sehat. Mari saya antar pulang. Lagipula tak baik seorang perempuan berada di tempat dan situasi yang seperti ini," lagi lagi suara Pak Slamet membuyarkan lamunan guru muda itu.
"Ah, terimakasih sebelumnya Pak. Tapi saya masih menunggu Uwak saya. Beliau lagi di dalam sekarang," ujar Bu Ratih pelan.
"Oh, kalau begitu kenapa tidak kita tunggu saja disana? Disini terlalu ramai, dan suasananya juga kurang mengenakkan," kata Pak Slamet lagi, sambil menunjuk ke sebuah warung kecil yang ada di seberang jalan.
Bu Ratih mendesah pelan.
Bu Ratih mendesah pelan.
Sebenarnya ia masih ingin menguping lebih banyak lagi kasak kusuk para warga yang ada disitu. Tapi untuk terus terusan menolak niat baik Pak Slamet rasanya kurang enak juga. Akhirnya mereka berduapun melangkah menyeberang jalan, menuju ke sebuah warung kecil yang ada disana.
"Bu Ratih mau minum? Saya pesankan teh hangat ya?" tawar Pak Slamet begitu mereka telah sampai di warung itu. Bu Ratih hanya mengangguk, lalu duduk di bangku kayu yang ada di warung itu.
Pikiran guru muda itu masih terfokus pada pengelihatan yang tadi dialaminya.
Pikiran guru muda itu masih terfokus pada pengelihatan yang tadi dialaminya.
Namun perhatiannya kini tertuju pada sekelompok warga yang ada di warung itu, yang masih serius membicarskan soal kematian keluarga Pak Darsa yang tak wajar. Segera Bu Ratih memasang baik baik indera pendengarannya.
Kebanyakan warga itu berpendapat bahwa kematian keluarga Pak Darsa ini masih berkaitan erat dengan desas desus pesugihan yang memang telah lama beredar. Pak Darsa yang dikenal sebagai orang paling kaya di Kecamatan itu memang diisukan memiliki pesugihan. Entah benar atau tidak.
Tapi kabar tak sedap itu telah lama menjadi buah bibir di tengah masyarakat desa Kedhung Jati.
Namun bukan soal pesugihan itu yang menarik minat Bu Ratih, melainkan celetukan salah satu warga yang mengaitkan soal kematian keluarga Pak Darsa ini dengan salah satu warga desa Kedhung Jati. Mas Joko.
"Kudengar kemarin Pak Darsa itu sempat datang ke rumah Mas Joko yang ada di Tegal Salahan itu," kata salah seorang warga yang ada di warung itu.
"Lalu?" tanya Warga yang lain.
"Lalu?" tanya Warga yang lain.
"Saya kok jadi curiga ya. Jangan jangan kematian keluarga Pak Darsa itu masih ada hubungannya denga Mas Joko," jawab warga yang pertama.
"Jangan asal kamu kalau ngomong, salah salah nanti bisa jadi fitnah," timpal warga yang lain.
"Jangan asal kamu kalau ngomong, salah salah nanti bisa jadi fitnah," timpal warga yang lain.
"Bukan asal ngomong, tapi kita semua tau kan anak siapa Mas Joko itu. Dan kemarin itu, Pak Darsa datang kesana bukan dengan niat yang baik."
"Maksudmu?"
"Maksudmu?"
"Iya. Kudengar Pak Darsa kesana sambil marah marah. Ia tidak terima karena sebelumnya salah satu anaknya itu berkelahi dengan anaknya Mas Joko di sekolahan. Dan tidak hanya marah marah, Pak Darsa juga minta sejumlah uang untuk ganti rugi biaya pengobatan anaknya itu.."
"..Padahal setahuku anaknya Pak Darsa itu tidak apa apa. Lecetpun tidak saat berkelahi dengan si Wulan itu."
"Lalu apa yang dilakukan oleh Mas Joko?"
"Mas Joko sih katanya tak terlalu menanggapi sikap Pak Darsa itu.
"Lalu apa yang dilakukan oleh Mas Joko?"
"Mas Joko sih katanya tak terlalu menanggapi sikap Pak Darsa itu.
Ia juga memberikan uang yang diminta oleh Pak Darsa itu tanpa banyak bertanya."
"Lha, itu kan malah bagus."
"Lha, itu kan malah bagus."
"Bagus apanya? Justru mencurigakan. Coba kamu pikir, uang yang diminta Pak Darsa itu jumlahnya tak sedikit. Dan Mas Joko itu memberikannya begitu saja, tanpa bertanya ini itu lagi. Bukankah itu aneh?"
"Ah, biasa saja itu. Setahuku Mas Joko itu kan memang orang yang baik. Ia tak pernah mau ribut ribut. Selama pindah ke desa ini juga tak pernah macam macam."
"Memang, kalau Mas Joko sih aku percaya. Tapi apa kalian lupa dengan anaknya?."
"Memang, kalau Mas Joko sih aku percaya. Tapi apa kalian lupa dengan anaknya?."
"..Sudah berapa kali coba si Wulan itu bikin masalah? Dan satu lagi, ada yang bilang kalau kemarin Pak Darsa sempat ngasih sesuatu ke Wulan, saat ia tak sengaja bertemu anak itu di kali Salahan. "
Obrolan para warga itu masih terus berlanjut.
Obrolan para warga itu masih terus berlanjut.
Kali ini topik obrolan mereka berganti dengan cerita tentang si Wulan. Bu Ratih mengalihkan pandangan ke arah sebelah kiri. Dimana tadi dalam pengelihatannya, Wulan berdiri di situ.
Ah, Wulan. Benarkah ini semua adalah ulahmu? Bu Ratih mencoba membuang jauh jauh prasangkanya.
Ah, Wulan. Benarkah ini semua adalah ulahmu? Bu Ratih mencoba membuang jauh jauh prasangkanya.
Namun semakin ia berusaha, justru ia semakin percaya dengan sesuatu yang tak ingin dipercayainya. Kutukan!
"Tehnya Bu," lagi dan lagi, suara Pak Slamet membuyarkan lamunan Bu Ratih.
"Tehnya Bu," lagi dan lagi, suara Pak Slamet membuyarkan lamunan Bu Ratih.
"Terimakasih Pak," ujar Bu Ratih sambil membetulkan posisi duduknya.
"Sepertinya penyelidikan para polisi itu sudah selesai Bu," Pak Slamet ikut duduk di sebelah Bu Ratih.
Guru muda itu mengarahkan pandangannya ke rumah besar di depan mereka. Benar kata Pak Slamet.
"Sepertinya penyelidikan para polisi itu sudah selesai Bu," Pak Slamet ikut duduk di sebelah Bu Ratih.
Guru muda itu mengarahkan pandangannya ke rumah besar di depan mereka. Benar kata Pak Slamet.
Dari dalam rumah itu keluar beberapa anggota polisi sambil menggotong empat kantong mayat yang segera dinaikkan ke sebuah mobil bak terbuka yang sejak tadi terparkir di halaman rumah itu. Sementara petugas yang lain mencoba menyibak kerumunan warga.
Nampak juga Pak Bayan dan Uwaknya. Lalu disusul oleh seorang laki laki tua bertubuh kurus dengan pakaian serba hitam dan ikat kepala yang juga berwarna hitam.
Sejenak Bu Ratih tertegun. Gelas teh yang sudah nyaris sampai di depan mulutnya, ia letakkan kembali.
Sejenak Bu Ratih tertegun. Gelas teh yang sudah nyaris sampai di depan mulutnya, ia letakkan kembali.
Matanya tak lepas memperhatikan sosok laki laki tua itu. Entah mengapa, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk memperhatikan orang itu.
Dan, seperti telah sadar kalau sedang diperhatikan, laki laki tua itu juga menatap ke arah Bu Ratih. Pandangan mata mereka bertemu, lalu ..
Dan, seperti telah sadar kalau sedang diperhatikan, laki laki tua itu juga menatap ke arah Bu Ratih. Pandangan mata mereka bertemu, lalu ..
"Ah," Bu Ratih segera mengalihkan tatapan matanya. Ada getaran halus yang menyengat ia rasakan saat tatapan matanya beradu dengan pandangan laki laki tua itu. Seolah laki laki tua itu mencoba mengintimidasinya dengan peringatan keras. Jangan ikut campur!
"Kenapa Bu?" sekali lagi suara Pak Slamet mengagetkan Bu Ratih.
"Ah, nggak papa Pak. Laki laki itu siapa ya Pak?" tanya Bu Ratih.
"Laki laki yang mana Bu?"
Itu, yang memakai pakaian dan ikat kepala serba hitam."
Pak Slamet mengikuti arah pandangan Bu Ratih.
"Ah, nggak papa Pak. Laki laki itu siapa ya Pak?" tanya Bu Ratih.
"Laki laki yang mana Bu?"
Itu, yang memakai pakaian dan ikat kepala serba hitam."
Pak Slamet mengikuti arah pandangan Bu Ratih.
"Sepertinya bukan warga sini Bu. Baru kali ini saya melihatnya."
Benar dugaanku, batin Bu Ratih. Aku harus mencari tahu siapa laki laki itu. Sepertinya masih ada hubungannya dengan keluarga Pak Darsa. Mungkin Wak Dul tahu. Aku harus menanyakannya.
Benar dugaanku, batin Bu Ratih. Aku harus mencari tahu siapa laki laki itu. Sepertinya masih ada hubungannya dengan keluarga Pak Darsa. Mungkin Wak Dul tahu. Aku harus menanyakannya.
Tapi sebelum itu, aku harus menemui Wulan terlebih dahulu. Anak itu, aku harus bisa mengorek keterangan darinya. Dan kalau benar ini semua ada hubungannya dengan anak itu, aku harus menyelamatkannya.
***
***
"Lah, aku berangkat dulu ya," ujar Joko sambil merapikan kemeja hitam yang dipakainya.
"Abang serius mau kesana?" tanya Romlah dari arah dapur.
"Abang serius mau kesana?" tanya Romlah dari arah dapur.
"Iya. Tak enak kalau abang tak datang. Biar bagaimanapun Pak Darsa itu kan tetangga kita, dan dia sedang dilanda musibah. Semua warga juga pasti datang kesana. Apa kata orang nanti kalau aku tidak datang?"
"Perasaanku tak enak Bang," Romlah keluar dari dapur dan mendekat ke arah suaminya itu.
"Kamu masih memikirkan omongan para warga desa itu?" Joko menatap wajah istrinya.
"Iya Bang. Tega sekali mereka menuduh kita sekeji itu."
"Kamu masih memikirkan omongan para warga desa itu?" Joko menatap wajah istrinya.
"Iya Bang. Tega sekali mereka menuduh kita sekeji itu."
"Sudahlah, tak perlu terlalu kau pikirkan. Sudah biasa kan. Warga disini memang paling suka bergosip. Yang penting, apa yang mereka tuduhkan itu kan tidak benar. Kita tak melakukan apa apa, jadi kenapa mesti takut?"
"Wulan Bang, itu yang aku pikirkan. Jika anak itu sampai tau apa yang ..."
"Lah, percaya pada suamimu ini. Semua pasti akan baik baik saja. Soal Wulan, biar nanti aku yang bicara dengannya."
"Tapi Bang ..."
"Lah, percaya pada suamimu ini. Semua pasti akan baik baik saja. Soal Wulan, biar nanti aku yang bicara dengannya."
"Tapi Bang ..."
Kalimat Romlah terputus saat terdengar deru mesin mobil berhenti di halaman pondok itu. Dua orang berseragam turun, diikuti oleh Pak Jagabaya, perangkat desa yang bertanggungjawab atas keamanan desa.
"Selamat siang. Benar dengan saudara Joko?" sapa salah satu petugas itu.
"Selamat siang. Benar dengan saudara Joko?" sapa salah satu petugas itu.
"Iya, saya sendiri Pak," sahut Joko ramah, sambil mempersilahkan tamu tamunya itu masuk.
"Maaf kalau menganggu waktunya. Tapi kami butuh sedikit informasi dan keterangan dari bapak. Ini menyangkut soal ..., emm, Pak Darsa." kata petugas yang satunya lagi.
"Maaf kalau menganggu waktunya. Tapi kami butuh sedikit informasi dan keterangan dari bapak. Ini menyangkut soal ..., emm, Pak Darsa." kata petugas yang satunya lagi.
"Oh, iya Pak. Saya paham. Dengan senang hati Pak, kalau ada yang bisa saya bantu, pasti akan saya bantu."
"Baiklah kalau begitu, bisa ikut kami ke kantor sekarang?"
"Tunggu!" Wulan yang sejak tadi nampak asyik bermain di sudut teras tiba tiba berdiri dan menghampiri petugas itu
"Baiklah kalau begitu, bisa ikut kami ke kantor sekarang?"
"Tunggu!" Wulan yang sejak tadi nampak asyik bermain di sudut teras tiba tiba berdiri dan menghampiri petugas itu
"Mau kalian bawa kemana bapakku?" tanya anak itu ketus.
Salah seorang dari petugas itu melotot. Belum pernah ia disentak oleh anak kecil seperti itu. Namun petugas yang satunya lagi justru tersenyum.
"Anak bapak?" bisik petugas itu pada Joko. Joko hanya mengangguk.
Salah seorang dari petugas itu melotot. Belum pernah ia disentak oleh anak kecil seperti itu. Namun petugas yang satunya lagi justru tersenyum.
"Anak bapak?" bisik petugas itu pada Joko. Joko hanya mengangguk.
"Anak cantik," petugas itu mendekat dan sedikit membungkuk di hadapan Wulan. "Siapa namamu nak?"
"Bapakku mau dibawa kemana?" bukannya menjawab, Wulan justru kembali bertanya dengan nada yang masih ketus.
"Bapakku mau dibawa kemana?" bukannya menjawab, Wulan justru kembali bertanya dengan nada yang masih ketus.
"Om pinjam bapaknya sebentar ya. Om butuh bantuan bapak. Nanti kalau sudah selesai, Om janji, Om akan mengantar bapak pulang lagi."
Wulan menatap ke arah sang ayah. Joko mengangguk dan tersenyum.
"Wulan pegang janji Om," sungut Wulan pada petugas itu.
Wulan menatap ke arah sang ayah. Joko mengangguk dan tersenyum.
"Wulan pegang janji Om," sungut Wulan pada petugas itu.
"Terimakasih cantik," petugas itu mengusap rambut Wulan.
"Baiklah kalau begitu, kami pamit dulu ya Bu," petugas itu mengangguk ke arah Romlah yang masih tertegun di depan pintu. Apa yang ia khawatirkan akhirnya terjadi juga.
"Baiklah kalau begitu, kami pamit dulu ya Bu," petugas itu mengangguk ke arah Romlah yang masih tertegun di depan pintu. Apa yang ia khawatirkan akhirnya terjadi juga.
Perempuan itu hanya bisa menatap kepergian sang suami sambil menghela nafas panjang.
Mudah mudahan semua akan baik baik saja, batin perempuan itu.
***
Mudah mudahan semua akan baik baik saja, batin perempuan itu.
***
"Lintang, kamu mau kemana?" Mbak Patmi berseru saat melihat anak semata wayangnya itu keluar dari dalam kamar dengan tas sekolah menggantung di pundak.
"Mau kerumah Wulan Mak, ngerjain PR," jawab anak itu.
"Mau kerumah Wulan Mak, ngerjain PR," jawab anak itu.
"Ngerjain PR saja kok harus ke rumah Wulan lho, memang nggak bisa dikerjakan sendiri di rumah?" tanya Mbak Patmi.
"PR-nya banyak Mak, susah susah lagi."
"PR-nya banyak Mak, susah susah lagi."
"Makanya, jadi anak tuh yang rajin belajarnya. Biar pinter. Masa kamu kalah pinter sama Wulan? Padahal kamu kan lebih besar dari dia. Sudah SMP lho kamu itu kalau nggak tinggal kelas sampai dua kali!"
"Hehe, makanya aku mau belajar sama Wulan Mak, biar ketularan pinter."
"Hehe, makanya aku mau belajar sama Wulan Mak, biar ketularan pinter."
"Halah! Bisa saja kamu alesannya. Ya sudah sana kalau mau belajar. Tapi ingat, kerumah Wulan saja, jangan turun ke desa Kedhung Jati. Lagi ada orang yang meninggal disana!"
"Eh, siapa yang meninggal Mak?" rona keceriaan di wajah Lintang sirna seketika begitu sang emak mengatakan ada orang yang meninggal di desa Kedhung Jati.
"Pak Darsa!"
Deg! Jantung Lintang seolah berhenti berdetak begitu nama Pak Darsa disebut oleh emaknya.
"Pak Darsa!"
Deg! Jantung Lintang seolah berhenti berdetak begitu nama Pak Darsa disebut oleh emaknya.
Berarti kejadian yang semalam itu? Dan mimpi buruk yang dialaminya? Aku harus segera menemui Wulan!
"Lintang berangkat Mak," bergegas anak itu menyalami dan mencium tangan emaknya, lalu dengan setengah berlari meninggalkan sang emak yang hanya terbengong bengong menyaksikan tingkah sang anak.
***
***
Wulan nampak duduk mencangkung seorang diri di atas balai balai bambu di teras rumahnya saat Lintang datang. Anak itu seolah mengacuhkan kedatangan sang sahabat itu.
"Kok sepi Lan?" anak laki laki bertubuh gempal itu ikut duduk di sebelah Wulan.
"Kok sepi Lan?" anak laki laki bertubuh gempal itu ikut duduk di sebelah Wulan.
"Emak lagi nyuci ke kali," jawab Wulan pendek.
"Ayahmu?"
"Pergi dibawa polisi."
"Eh, kenapa?"
Gadis kecil itu hanya mengangkat bahunya. Lintang terdiam. Pantas saja Wulan terlihat murung, batinnya.
"Kita main yuk?" ajak Lintang mencoba mencairkan suasana.
"Ayahmu?"
"Pergi dibawa polisi."
"Eh, kenapa?"
Gadis kecil itu hanya mengangkat bahunya. Lintang terdiam. Pantas saja Wulan terlihat murung, batinnya.
"Kita main yuk?" ajak Lintang mencoba mencairkan suasana.
"Males ah," jawab Wulan tanpa menoleh.
Kembali Lintang terdiam. Wulan juga diam. Keduanya saling membisu. Suasanapun kembali menjadi sepi. Hanya suara desiran angin yang terdengar mempermainkan daun kacang panjang yang tumbuh subur di ladang depan pondok itu.
Kembali Lintang terdiam. Wulan juga diam. Keduanya saling membisu. Suasanapun kembali menjadi sepi. Hanya suara desiran angin yang terdengar mempermainkan daun kacang panjang yang tumbuh subur di ladang depan pondok itu.
"Eh, itu siapa?" seru Lintang tiba tiba, saat ia melihat ada seorang nenek tua nampak sedang sibuk ditengah ladang.
"Siapa?" Wulan ikut memandang ke tengah ladang. Benar saja, nampak seorang nenek nenek yang sepertinya sedang sibuk mencari sesuatu di tengah ladang.
"Siapa?" Wulan ikut memandang ke tengah ladang. Benar saja, nampak seorang nenek nenek yang sepertinya sedang sibuk mencari sesuatu di tengah ladang.
Bukan, bukan di tengah ladang, tapi di tepi ladang, tepat disamping pokok pohon sengon yang telah tumbang. Pohon sengon yang semalam menjadi korban sambaran petir akibat amarah Wulan yang tak terkendali.
"Jangan jangan ..." Lintang tak melanjutkan kata katanya.
"Jangan jangan ..." Lintang tak melanjutkan kata katanya.
"Kita samperin yuk," Wulan melompat turun dari atas balai balai, lalu melangkah cepat menghampiri nenek itu.
"Tunggu Lan," Lintang berseru dan berlari mengejar Wulan.
"Hei, lagi ngapain Nek?" seru Wulan begitu sampai di dekat nenek itu.
"Tunggu Lan," Lintang berseru dan berlari mengejar Wulan.
"Hei, lagi ngapain Nek?" seru Wulan begitu sampai di dekat nenek itu.
"Nyari cucuku!" nenek itu berbalik, memperlihatkan wajah tuanya yang penuh keriput.
"Cucumu tidak ada disini!" sentak Wulan. Entah mengapa, melihat sosok di nenek itu, tiba tiba ada rasa benci yang dirasakan oleh Wulan.
"Cucumu tidak ada disini!" sentak Wulan. Entah mengapa, melihat sosok di nenek itu, tiba tiba ada rasa benci yang dirasakan oleh Wulan.
"Cucuku! Semalam dibunuh disini! Kau yang membunuhnya!" tiba tiba nenek itu menyambar tangan Wulan dan menariknya dengan kasar.
"Dasar orang gila! Lepaskan!" Wulan berteriak sambil mengibaskan tangannya, berusaha melepaskan cengkeraman tangan si nenek.
"Dasar orang gila! Lepaskan!" Wulan berteriak sambil mengibaskan tangannya, berusaha melepaskan cengkeraman tangan si nenek.
Namun rupanya tangan nenek yang terlihat keriput dan lemah itu ternyata begitu kuat.
"Kau yang membunuh cucuku! Aku akan membalasnya! Kau akan ....!"
"LEPASKAAAANNNN ....!!!"
"Kau yang membunuh cucuku! Aku akan membalasnya! Kau akan ....!"
"LEPASKAAAANNNN ....!!!"
"LEPASKAAANNNN ...!!!" jeritan Wulan yang melengking tinggi itu seolah mampu menggetarkan hati dan jantung siapapun yang mendengarnya.
Nenek tua itu sampai terjajar mundur beberapa tindak. Otomatis peganganan tangannya pada lengan Wulanpun terlepas.
Nenek tua itu sampai terjajar mundur beberapa tindak. Otomatis peganganan tangannya pada lengan Wulanpun terlepas.
Kesempatan itu digunakan oleh Wulan untuk menyambar sepotong dahan kayu seukuran lengan yang tergeletak di dekatnya.
"Dasar orang gila! Pergi kamu, atau kupukul dengan kayu ini!" Wulan mengacungkan kayu yang dipegangnya ke arah nenek itu.
"Dasar orang gila! Pergi kamu, atau kupukul dengan kayu ini!" Wulan mengacungkan kayu yang dipegangnya ke arah nenek itu.
"Bocah kurang ajar!" nenek itu terlihat sangat marah. Ia melangkah maju dan bermaksud kembali menyerang Wulan.
"Wulan! Jangan!" Lintang yang telah berhasil menyusul Wulan segera menarik lengan anak itu ke belakang, lalu berdiri tepat di depan Wulan.
"Wulan! Jangan!" Lintang yang telah berhasil menyusul Wulan segera menarik lengan anak itu ke belakang, lalu berdiri tepat di depan Wulan.
Kedua tangannya terentang, berusaha melindungi Wulan dari serangan nenek itu.
"Pergilah Nek, dan tolong jangan ganggu kami," Lintang meringis.
"Pergilah Nek, dan tolong jangan ganggu kami," Lintang meringis.
Bukan karena takut dengan si nenek yang tiba tiba tertegun menatap ke arahnya, tapi ia mulai merasakan hawa panas yang sangat menyengat di sekitar lehernya.
"Kamu?" nenek itu nampak terkejut, saat melihat kalung benang lawe yang digunakan Lintang.
"Kamu?" nenek itu nampak terkejut, saat melihat kalung benang lawe yang digunakan Lintang.
"Tak kusangka kita bertemu lagi cah bagus. Sudah lama aku mencarimu."
"Apa maksudmu Nek?" tanya Lintang heran. Ia merasa tak mengenal nenek itu, tapi kenapa nenek itu bilang kalau sudah lama mencarinya?
"Apa maksudmu Nek?" tanya Lintang heran. Ia merasa tak mengenal nenek itu, tapi kenapa nenek itu bilang kalau sudah lama mencarinya?
"Hehehe, sekarang belum waktunya. Nanti kita pasti akan bertemu lagi cah bagus, dan juga kamu cah ayu," nenek itu tertawa terkekeh, lalu berbalik melangkah pergi dengan langkah yang tertatih tatih.
"Dasar orang gila," sungut Lintang.
"Yuk, kita kembali ke pondok Lan."
"Dasar orang gila," sungut Lintang.
"Yuk, kita kembali ke pondok Lan."
"Kamu yakin dia orang gila Tang?" Wulan mengikuti langkah Lintang kembali ke pondok.
"Sepertinya sih begitu. Lihat saja pakaiannya yang compang camping dan bertambal tambal itu. Badannya juga bau banget. Pasti sudah lama tak pernah mandi tuh." jawab Lintang.
"Sepertinya sih begitu. Lihat saja pakaiannya yang compang camping dan bertambal tambal itu. Badannya juga bau banget. Pasti sudah lama tak pernah mandi tuh." jawab Lintang.
"Aneh! Kenapa tiba tiba ada nenek nenek gila di sini? Setahuku cuma si Klanthung itu orang gila yang suka berkeliaran di desa ini." gumam Wulan. Mereka telah sampai kembali di pondok. Keduanya lalu duduk di balai balai bambu yang ada di teras itu.
"Kamu tuh yang aneh. Tadi kamu kelihatan marah banget, sampai sampai mau memukul nenek itu dengan kayu. Kenapa sekarang jadi kalem begitu? Biasanya kamu kalau sudah marah susah sembuhnya."
"Enak saja! Justru kamu tuh yang aneh! Kamu habis megang apa sih?"
"Enak saja! Justru kamu tuh yang aneh! Kamu habis megang apa sih?"
"Megang apa? Aku nggak habis megang apa apa kok."
"Tanganmu dingin banget pas megang tanganku tadi, kayak habis megang es batu. Aku sampai merinding saat kau pegang tadi."
"Ah, perasanmu saja kali. Aku nggak habis megang apa apa kok. Kan dari tadi aku disini sama kamu."
"Tanganmu dingin banget pas megang tanganku tadi, kayak habis megang es batu. Aku sampai merinding saat kau pegang tadi."
"Ah, perasanmu saja kali. Aku nggak habis megang apa apa kok. Kan dari tadi aku disini sama kamu."
Wulan terdiam. Ia benar benar merasakan hal yang aneh tadi saat Lintang menarik tangannya. Tangan anak itu benar benar terasa sangat dingin saat memegang tangannya, dan rasa dingin itu seolah olah menjalar ke seluruh tubuhnya.
Membuat rasa marahnya pada si nenek aneh itu tiba tiba menghilang.
"Oh ya, kata emakku di desamu ada orang meninggal ya?" suara Lintang mengejutkan Wulan.
"Iya," jawab Wulan pendek.
"Oh ya, kata emakku di desamu ada orang meninggal ya?" suara Lintang mengejutkan Wulan.
"Iya," jawab Wulan pendek.
"Siapa?"
"Pak Darsa."
"Pak Darsa yang kemarin ngasih ayam panggang ke kita itu?"
"Iya."
"Kenapa meninggalnya? Kemarin kayaknya dia sehat sehat saja tuh."
"Entahlah, aku juga nggak tau Tang. Katanya sih bukan cuma Pak Darsa yang meninggal. Tapi istri dan anaknya juga."
"Pak Darsa."
"Pak Darsa yang kemarin ngasih ayam panggang ke kita itu?"
"Iya."
"Kenapa meninggalnya? Kemarin kayaknya dia sehat sehat saja tuh."
"Entahlah, aku juga nggak tau Tang. Katanya sih bukan cuma Pak Darsa yang meninggal. Tapi istri dan anaknya juga."
"Aneh," gumam Lintang.
"Halah, kamu ini lho, semua kok dibilang aneh."
"Ya aneh saja sih, kok tiba tiba begitu meninggalnya. Mana satu keluarga lagi."
"Kata orang mereka dimakan sama pesugihannya sendiri."
"Ah, masa sih?" Lintang mulai teringat dengan mimpinya semalam.
"Halah, kamu ini lho, semua kok dibilang aneh."
"Ya aneh saja sih, kok tiba tiba begitu meninggalnya. Mana satu keluarga lagi."
"Kata orang mereka dimakan sama pesugihannya sendiri."
"Ah, masa sih?" Lintang mulai teringat dengan mimpinya semalam.
Masih ia ingat dengan jelas mimpi itu. Monyet besar yang dibunuh Wulan dalam mimpinya itu, tiba tiba wajahnya berubah menjadi wajah Pak Darsa.
"Kata orang sih begitu," jawab Wulan.
"Seperti apa ya pesugihan Pak Darsa itu?"
"Kata orang sih begitu," jawab Wulan.
"Seperti apa ya pesugihan Pak Darsa itu?"
"Mana ku tahu. Kamu tanya saja sendiri sana sama Pak Darsa."
"Gendheng! orang sudah mati kok suruh nanyain." sungut Lintang.
Wulan tergelak. Kedua anak itu seolah memiliki dunia mereka sendiri. Mereka sama sama terkucilkan di desa masing masing.
"Gendheng! orang sudah mati kok suruh nanyain." sungut Lintang.
Wulan tergelak. Kedua anak itu seolah memiliki dunia mereka sendiri. Mereka sama sama terkucilkan di desa masing masing.
Wulan, tak ada anak yang mau berteman dengannya, karena ia dianggap sebagai anak yang aneh. Sementara Lintang, ia juga tak memiliki banyak teman. Hanya Wulan satu satunya teman yang benar benar bisa akrab dengannya.
Keduanya terus asyik mengobrol hingga Romlah pulang dari kali.
Keduanya terus asyik mengobrol hingga Romlah pulang dari kali.
"Orang yang tadi ikut masuk kedalam rumah Pak Darsa tadi siapa Wak?" tanya Bu Ratih pada Uwaknya. Mereka telah kembali dari rumah Pak Darsa. Duduk di teras rumah Wak Dul sambil menikmati teh hangat buatan Bu Ratih.
"Orang yang mana?" Wak Dul balik bertanya.
"Orang yang mana?" Wak Dul balik bertanya.
"Orang tua yang memakai baju dan ikat kepala serba hitam tadi."
"Oh, itu Mbah Suryo, kerabatnya Pak Darsa."
Bukan warga sini ya Wak, sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelum ini."
"Memang, dia tinggal di desa Ngantiyan sana." Wak Dul menyalakan rokok kreteknya.
"Oh, itu Mbah Suryo, kerabatnya Pak Darsa."
Bukan warga sini ya Wak, sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelum ini."
"Memang, dia tinggal di desa Ngantiyan sana." Wak Dul menyalakan rokok kreteknya.
"Kenapa sih? Kok tiba tiba kamu menanyakan orang itu?"
"Nggak papa sih Wak, cuma pengen tau saja" ujar Bu Ratih.
"Kamu pasti melihat ada yang beda kan dengan orang itu?"
"Emm, sedikit sih Wak, cuma merasa agak aneh saja penampilannya."
"Nggak papa sih Wak, cuma pengen tau saja" ujar Bu Ratih.
"Kamu pasti melihat ada yang beda kan dengan orang itu?"
"Emm, sedikit sih Wak, cuma merasa agak aneh saja penampilannya."
"Dia memang bukan orang sembarangan Tih. Ya semacam dukun atau orang pintar gitu. Dan kata orang sih, dia ini yang ada dibalik semua kesuksesan Pak Darsa. Bisa dibilang, dia ini selain masih kerabat juga sekaligus guru dari Pak Darsa."
"Guru?"
"Guru?"
"Ya kamu tau sendiri lah, orang sekaya Pak Darsa begitu, pasti ada orang orang 'ngerti' yang ada dibelakangnya. Semacam guru kebatinan atau spirirual gitu."
"Oh, begitu ya Wak. Pantas saja tadi aku melihat pandangan matanya agak sedikit lain gitu."
"Oh, begitu ya Wak. Pantas saja tadi aku melihat pandangan matanya agak sedikit lain gitu."
"Kalau bisa sih, kamu hindari orang itu Tih. Dia berbahaya. Kata orang sih ilmunya lumayan tinggi, dan juga sedikit kurang ramah orangnya."
"Enggak kok Wak, aku cuma ..."
Ucapan Bu Ratih terhenti saat dari kejauhan nampak dua orang berlari lari menuju ke rumah itu.
"Enggak kok Wak, aku cuma ..."
Ucapan Bu Ratih terhenti saat dari kejauhan nampak dua orang berlari lari menuju ke rumah itu.
"Pak Modin, gawat Pak ...!" seru orang itu begitu melihat Wak Dul yang duduk di teras.
"Gawat kenapa to Man?" tanya Wak Dul heran.
"Anu Pak, ada ..., ada mayat di kali Salahan!"
"Hah, Mayat?!"
"Gawat kenapa to Man?" tanya Wak Dul heran.
"Anu Pak, ada ..., ada mayat di kali Salahan!"
"Hah, Mayat?!"
Raga tanpa nyawa itu meringkuk diam di tepian sungai. Sebagian tubuhnya terendam dalam air, sebagian lagi nyaris terbenam dalam lumpur di tepian sungai. Jemari tangannya yang telah kaku masih mencengkeram rerumputan yang tumbuh di tebing tanggul sungai.
Separuh wajahnya yang tak terbenam di dalam lumpur nampak membiru kehitaman. Dengan mata yang membeliak lebar dan mulut menganga, membuat wajah itu nampak sangat menyeramkan.
Urat urat lehernya menegang, menandakan bahwa sebelum ajal menjelang, si pemilik tubuh kaku itu merasakan siksaan yang teramat sangat menyakitkan.
Orang orang yang berkerumun hanya menyaksikan dari atas tanggul sungai. Tak ada yang berani mendekat.
Orang orang yang berkerumun hanya menyaksikan dari atas tanggul sungai. Tak ada yang berani mendekat.
Kasak kusuk mulai terdengar. Hingga saat sebuah sepeda motor datang dan berhenti di dekat buk, bisik bisik itu mereda dengam sendirinya.
Pak Modin berjalan menyusuri tanggul kali, diikuti oleh Bu guru Ratih yang mengekor di belakangnya. Kerumunan orang itu tersibak, seolah memberi jalan kepada kedua orang yang baru datang itu.
"Kamu disini saja Tih, jangan ikut mendekat. Sepertinya kondisi mayat itu kurang enak buat dilihat," ujar Pak Modin pelan. Laki laki setengah baya itu segera menuruni tanggul sungai dan mendekati mayat itu untuk memeriksanya.
Hanya memeriksa, memastikan itu mayat siapa, tanpa berani menyentuhnya.
Bu Ratih sendiri, sama sekali tak mengindahkan larangan uwaknya. Ia justru ikut menuruni tanggul sungai dengan susah payah dan berdiri di samping Pak Modin.
Bu Ratih sendiri, sama sekali tak mengindahkan larangan uwaknya. Ia justru ikut menuruni tanggul sungai dengan susah payah dan berdiri di samping Pak Modin.
"Doni," lirih Bu Ratih mendesah sambil mendekap mulutnya. Ia kenal betul dengan sosok mayat itu, yang tak lain adalah salah satu muridnya di sekolah.
"Sudah kubilang jangan mendekat!" hardik Pak Modin pelan.
"Apa yang kau lihat?"
"Sudah kubilang jangan mendekat!" hardik Pak Modin pelan.
"Apa yang kau lihat?"
"Sepertinya ular Wak, ular yang sangat berbisa," bisik Bu Ratih. Ia sengaja memelankan suaranya agar tak didengar oleh orang orang yang berkerumun diatas tanggul sungai.
"Ular? Kenapa di wajah?" tanya Pak Modin heran, sambil menatap wajah sang mayat yang telah membiru.
"Ular? Kenapa di wajah?" tanya Pak Modin heran, sambil menatap wajah sang mayat yang telah membiru.
Cukup janggal kalau orang sampai terkena gigitan ular di bagian wajah.
Bu Ratih memejamkan matanya sejenak. Sebuah bayangan melintas di benaknya. Guru muda itu lalu kembali membuka matanya, dan mendongak ke atas.
Bu Ratih memejamkan matanya sejenak. Sebuah bayangan melintas di benaknya. Guru muda itu lalu kembali membuka matanya, dan mendongak ke atas.
"Dari sana Wak, ular itu jatuh dari ranting pohon akasia diatas sana, lalu menimpa kepala anak ini yang sedang buang hajat."
"Kamu yakin?" tanya Pak Modin lagi.
Bu Ratih mengangkat bahu. "Itu tugas polisi Wak. Itu juga kalau ...."
"Kamu yakin?" tanya Pak Modin lagi.
Bu Ratih mengangkat bahu. "Itu tugas polisi Wak. Itu juga kalau ...."
"DONIII ...!!! ANAKKUUU ...!!!" sebuah jeritan memecah kebisuan, disusul dengan munculnya seorang laki laki yang berlari menyibak kerumunan. Sepertinya dia ayah dari si mayat itu.
Laki itu segera menghambur menuruni tanggul sungai sambil berteriak teriak histeris.
Laki itu segera menghambur menuruni tanggul sungai sambil berteriak teriak histeris.
Mungkin karena kurang hati hati, tubuh laki laki itu justru terguling dan menggelinding jatuh kedalam sungai.
"Doniiii....!!! Kenapa kamu nak? Apa yang terjadi? Siapa yang tega membunuhmu?" tanpa memperdulikan tubuh dan pakaiannya yang basah kuyup laki laki itu kembali bangun,
"Doniiii....!!! Kenapa kamu nak? Apa yang terjadi? Siapa yang tega membunuhmu?" tanpa memperdulikan tubuh dan pakaiannya yang basah kuyup laki laki itu kembali bangun,
dan menghambur memeluk jasad sang anak yang telah kaku.
Kembali terdengar bisik bisik ditengah kerumunan warga yang semakin menyemut. Pak Modin terlihat kesal. Ditengah suasana yang seperti ini, tak ada satupun dari para warga yang berusaha untuk bertindak.
Kembali terdengar bisik bisik ditengah kerumunan warga yang semakin menyemut. Pak Modin terlihat kesal. Ditengah suasana yang seperti ini, tak ada satupun dari para warga yang berusaha untuk bertindak.
Mereka hanya menjadi penonton sambil sesekali berkomentar.
"Kasihan Pak Marto."
"Iya. Padahal itu anak satu satunya."
"Meninggalnya dengan cara yang seperti itu lagi."
"Kenapa anak itu tiba tiba mati disini?"
"Mungkin digigit ular."
"Atau dicekik hantu penghuni sungai ini?"
"Kasihan Pak Marto."
"Iya. Padahal itu anak satu satunya."
"Meninggalnya dengan cara yang seperti itu lagi."
"Kenapa anak itu tiba tiba mati disini?"
"Mungkin digigit ular."
"Atau dicekik hantu penghuni sungai ini?"
Kemarin kulihat anak itu masih bermain bola di sawah Mbah Mo sana. Nggak nyangka kalau sekarang tiba tiba mati begitu."
"Iya. Kemarin aku juga melihat, sebelum bermain bola sempat ribut dengan anaknya Mas Joko."
"Si Wulan maksudmu?"
"Iya. Siapa lagi."
"Iya. Kemarin aku juga melihat, sebelum bermain bola sempat ribut dengan anaknya Mas Joko."
"Si Wulan maksudmu?"
"Iya. Siapa lagi."
"Jangan jangan bocah aneh itu yang ...."
"Bapak bapak, tolong ya jangan ...."
"Pembunuh!!!" tiba tiba Pak Marto yang tadi memeluk jasad sang anak berdiri dan berteriak lantang. Matanya menatap tajam kearah kerumunan warga.
"Bapak bapak, tolong ya jangan ...."
"Pembunuh!!!" tiba tiba Pak Marto yang tadi memeluk jasad sang anak berdiri dan berteriak lantang. Matanya menatap tajam kearah kerumunan warga.
Tepatnya kearah dua orang bocah yang juga ikut berkerumun di atas tanggul.
"Kau pembunuh! Akan kubalas kau!" rupanya bisik bisik para warga tadi sampai juga ke telinga laki laki itu. Mendengar nama Wulan disebut, laki laki itu meradang.
"Kau pembunuh! Akan kubalas kau!" rupanya bisik bisik para warga tadi sampai juga ke telinga laki laki itu. Mendengar nama Wulan disebut, laki laki itu meradang.
Apalagi dilihatnya anak perempuan itu juga ikut berkerumun disitu.
Bergegas laki laki itu melompat menaiki tanggul sungai dan menuju kearah Wulan. Pak Modin dan Bu Ratih yang melihat gelagat tak baik itu berusaha mencegah.
Bergegas laki laki itu melompat menaiki tanggul sungai dan menuju kearah Wulan. Pak Modin dan Bu Ratih yang melihat gelagat tak baik itu berusaha mencegah.
Namun apa daya, tenaga seorang laki laki tua dan perempuan itu kalah gesit.
"Kau yang membunuh anakku!" dengan kasar Pak Marto mendorong tubuh kecil Wulan hingga jatuh terjengkang ke belakang. Lintang yang datang bersama anak itu, mencoba menolong sang teman.
"Kau yang membunuh anakku!" dengan kasar Pak Marto mendorong tubuh kecil Wulan hingga jatuh terjengkang ke belakang. Lintang yang datang bersama anak itu, mencoba menolong sang teman.
Sedang Pak Modin dan Bu Ratih nampak masih bersusah payah menaiki tanggul sungai.
"Bodoh!!! Kenapa kalian hanya diam saja?!" bentak Pak Modin kepada orang orang yang berkerumun di situ.
Bentakan Pak Modin seolah olah menyadarkan warga.
"Bodoh!!! Kenapa kalian hanya diam saja?!" bentak Pak Modin kepada orang orang yang berkerumun di situ.
Bentakan Pak Modin seolah olah menyadarkan warga.
Mereka segera menahan Pak Marto yang sudah kalap dan siap menendang tubuh kecil Wulan yang masih terkapar diatas tanah.
"Lepaskan aku! Biar kuhajar anak setan ini!" Pak Marto masih meronta ronta, mencoba melepaskan diri dari para warga yang menahannya.
"Lepaskan aku! Biar kuhajar anak setan ini!" Pak Marto masih meronta ronta, mencoba melepaskan diri dari para warga yang menahannya.
"Sabar Pak. Istighfar!" Pak Modin yang sudah berhasil naik ke tanggul sungai mencoba menyabarkan laki laki yang sedang kalap itu. Sedangkan Bu Ratih bergegas mendekat ke arah Wulan yang masih jatuh terlentang diatas tanah.
Sungguh ajaib.
Sungguh ajaib.
Anak perempuan itu terlihat sangat tenang setelah mendapat perlakuan yang sangat kasar dari Pak Marto. Tak ada rasa takut sedikitpun yang terlihat di wajahnya. Gadis itu hanya diam. Namun sorot matanya nampak sangat tajam menatap ke arah Pak Marto.
Sesaat pandangan Bu Ratih beradu dengan sorot mata itu. Bu Ratih tertegun. Langkahnya terhenti. Sorot mata anak itu, memancarkan kebencian yang teramat sangat. Bahkan ada nafsu untuk membunuh yang samar samar terpancar dari mata anak itu.
"Kenapa? Kenapa aku dibilang pembunuh?! Kenapa kalian semua membenciku?! Apa salahku?! Kalian semua jahat! Kalian jahat kepadaku! Aku nggak suka sama orang jahat! Orang jahat ....!!!"
Wulan tiba tiba berteriak teriak histeris, sebelum akhirnya teriakannya terhenti karena Lintang yang tiba tiba membekap mulutnya.
Bu Ratih yang mendengar teriakan Wulan refleks menutup kedua telinganya dengan telapak tangan.
Bu Ratih yang mendengar teriakan Wulan refleks menutup kedua telinganya dengan telapak tangan.
Suara anak itu seolah menusuk gendang telinganya, membuat kepalanya tiba tiba pusing bukan kepalang. Pandangan matanya mengabur, tubuhnya limbung dan nyaris terjatuh kalau saja tidak segera ditahan oleh salah seorang warga yang berdiri tak jauh darinya.
"Bu Ratih kenapa?" kata orang yang menolongnya itu.
"Eh, Pak Slamet?! Sejak kapan bapak disini?" sedikit kaget Bu Ratih saat menyadari bahwa yang menolongnya ternyata adalah Pak Slamet.
"Eh, Pak Slamet?! Sejak kapan bapak disini?" sedikit kaget Bu Ratih saat menyadari bahwa yang menolongnya ternyata adalah Pak Slamet.
"Sudah dari tadi Bu, sebelum ibu datang saya sudah disini kok. Ibu sakit?" Pak Slamet memapah Bu Ratih menjauh dari kerumunan itu.
"Nggak papa Pak.Hanya sedikit pusing," bu Ratih menjawab sambil matanya tak lepas memandang Lintang yang menyeret tangan Wulan dan memaksanya pulang
"Nggak papa Pak.Hanya sedikit pusing," bu Ratih menjawab sambil matanya tak lepas memandang Lintang yang menyeret tangan Wulan dan memaksanya pulang
pulang. Aneh, sepertinya tak ada seorangpun yang peduli dengan kedua bocah itu. Seolah semua warga yang berkumpul disitu sama sekali tak menganggap kehadiran kedua bocah itu.
"Ibu duduk disini saja dulu ya. Saya akan membantu Pak Modin untuk mengarahkan warga.."
"Ibu duduk disini saja dulu ya. Saya akan membantu Pak Modin untuk mengarahkan warga.."
"..Mayat anak itu harus segera diurus," kata Pak Slamet sambil membantu Bu Ratih untuk duduk di sebuah batu besar yang berada agak jauh dari kerumunan warga.
Bu Ratih hanya mengangguk.
Bu Ratih hanya mengangguk.
Matanya tak lepas dari bayangan Lintang dan Wulan yang nampak semakin menjauh dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Pelan guru muda itu melepas kacamatanya, lalu memijit mijit pangkal hidungnya, mencoba untuk mengurangi rasa pening yang dirasakannya.
Pikirannya masih tertuju pada anak perempuan itu. Apa yang dilihatnya tadi saat ia menatap mata Wulan, sungguh sangat mengerikan. Belum pernah ia merasakan hawa kemarahan sebesar itu dari seorang anak yang baru berusia sebelas tahun.
Guru muda itu mendesah, lalu kembali mengenakan kacamatanya. Dilihatnya sang Uwak dan Pak Slamet nampak kerepotan mengarahkan warga untuk mengurus jasad Doni dan menenangkan Pak Marto yang masih histeris. Bu Ratih tersenyum, lalu berdiri.
Sepertinya kedua laki laki setengah tua itu sangat membutuhkan bantuannya.
***
***
Hari sudah hampir maghrib saat Joko pulang dari kantor polisi. Kedatangannya langsung disambut dengan berondongan pertanyaan oleh Romlah. Seharian mencemaskan sang suami yang dibawa oleh polisi membuat perempuan itu seolah kehilangan akal sehatnya.
"Nggak papa. Abang cuma dimintai keterangan saja kok sama polisi. Tak ada yang perlu dikhawatirkan," Joko menjawab semua pertanyaan sang istri dengan santainya.
"Aneh! Kenapa juga harus abang yang dimintai keterangan?" sungut Romlah kesal.
"Aneh! Kenapa juga harus abang yang dimintai keterangan?" sungut Romlah kesal.
"Ya kan sehari sebelum meninggal Pak Darsa itu sempat kemari dan marah marah sama kita.Mungkin ada warga yang bercerita, hingga polisi merasa perlu untuk mencari penjelasan dari abang." jelas Joko.
"Jahat betul orang itu!Pasti mereka mencurigai abang!" Romlah masih nampak kesal
"Jahat betul orang itu!Pasti mereka mencurigai abang!" Romlah masih nampak kesal
"Jangan berburuk sangka begitu. Ada benarnya juga kalau orang curiga, karena kematian Pak Darsa itu memang tak wajar, dan sehari sebelumnya sempat bermasalah dengan kita."
"Justru mereka yang berburuk sangka sama kita Bang. Dikiranya kita ini yang membunuh keluarga Pak Darsa.."
"Justru mereka yang berburuk sangka sama kita Bang. Dikiranya kita ini yang membunuh keluarga Pak Darsa.."
"..Aku heran, kenapa warga desa itu sepertinya kurang suka dengan kita. Asal abang tau ya, tadi sore, Wulan juga diperlakukan kasar sama Pak Marto di pinggir kali sana. Dikiranya anak kita yang menyebabkan kematian anaknya. Apa itu nggak keterlaluan namanya?!"
Joko hanya tersenyum mendengar ucapan sang istri itu. Laki laki itu sebenarnya juga merasa sedikit kesal dengan kelakuan warga terhadap keluarganya. Tapi ia tak mau ribut ribut hanya karena masalah seperti itu.
"Abang mau kemana lagi?" kembali Romlah merepet melihat Joko sudah berpakaian rapi.
"Lho, kan ada acara tahlilan di rumah Pak Marto. Tak enak kalau abang tak datang. Bisa bisa nanti warga semakin curiga kalau abang tak datang."
Romlah menghela nafas.
"Lho, kan ada acara tahlilan di rumah Pak Marto. Tak enak kalau abang tak datang. Bisa bisa nanti warga semakin curiga kalau abang tak datang."
Romlah menghela nafas.
"Ya sudah. Abang hati hati ya, dan nanti pulangnya jangan malam malam."
"Iya. Ya sudah, abang berangkat dulu. Jangan lupa nanti pntu sama jendelanya dikunci." Joko segera beranjak keluar.
"Iya. Ya sudah, abang berangkat dulu. Jangan lupa nanti pntu sama jendelanya dikunci." Joko segera beranjak keluar.
Wulan yang mendengar percakapan kedua orang tuanya itu dari dalam kamarpun juga merasa kesal. Ternyata seperti itu perlakuan warga desa terhadap keluarganya. Rasa bencinya kepada warga desa semakin menggunung. Ia tidak terima kedua orang tuanya diperlakukan seperti itu oleh warga
***
Bau pepak asap kemenyan bercampur dengan aroma aneka rempah dan bunga setaman yang menguar memenuhi ruangan sempit itu, seolah tak mengganggu konsentrasi laki laki tua bertubuh kurus yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam di tengan tengah ruangan.
Bau pepak asap kemenyan bercampur dengan aroma aneka rempah dan bunga setaman yang menguar memenuhi ruangan sempit itu, seolah tak mengganggu konsentrasi laki laki tua bertubuh kurus yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam di tengan tengah ruangan.
Mulutnya komat kamit menggumamkan kata kata yang tak jelas kedengaran. Dihadapannya masih menyala dupa beserta beraneka ragam perlengkapannya.
Sesaat suasana hening, lalu terasa hawa sejuk dan angin lembut berkesiur disertai aroma wangi bunga kenanga, menandakan bahwa sudah saatnya laki laki itu mengakhiri ritualnya. Pelan laki laki tua itu membuka matanya, lalu melirik sebuah dipan kecil yang berada di sudut ruangan.
Benar saja, di tepi dipan itu kini telah duduk sesosok bayangan perempuan cantik berambut panjang dengan gaun putih tipis yang membungkus tubuhnya.
"Kau datang Nyai," sapa laki laki tua itu.
"Kau ceroboh Suryo. Dan karena kecerobohanmu, aku harus kehilangan anak kesayanganku!"
"Kau datang Nyai," sapa laki laki tua itu.
"Kau ceroboh Suryo. Dan karena kecerobohanmu, aku harus kehilangan anak kesayanganku!"
"Aku kecewa padamu!" perempuan itu mendengus marah.
"Maafkan aku Nyai, ini semua bukan murni kesalahanku, tapi putra Nyai sendiri yang menginginkan anak itu. Dan soal kehilangan, aku juga kehilangan saudaraku berikut dengan keluarganya,"
"Maafkan aku Nyai, ini semua bukan murni kesalahanku, tapi putra Nyai sendiri yang menginginkan anak itu. Dan soal kehilangan, aku juga kehilangan saudaraku berikut dengan keluarganya,"
laki laki itu masih tetap bergeming di tempatnya.
"Jadi kau menyalahkan putraku hah?! Dan soal saudaramu itu, dia memang pantas mati karena keserakahannya!" nada suara perempuan itu semakin meninggi.
"Tapi Nyai ...."
"Jadi kau menyalahkan putraku hah?! Dan soal saudaramu itu, dia memang pantas mati karena keserakahannya!" nada suara perempuan itu semakin meninggi.
"Tapi Nyai ...."
"Cukup Suryo! Aku tak mau terima apapun alasanmu! Kau harus bisa membalas semua ini! Sudah sejak lama anak perempuan itu menjadi duri dalam dagingku! Aku sudah muak! Andai saja aku bisa menyentuhnya!."
"..Tapi aku tak bisa Suryo, apalagi anak sialan yang satunya lagi itu juga selalu ikut campur!" geram perempuan itu.
"Lalu apa yang harus kulakukan Nyai?" tanya Ki Suryo.
"Lalu apa yang harus kulakukan Nyai?" tanya Ki Suryo.
"Apalagi! Habisi anak perempuan itu! Agar aku bisa kembali ke kerajaanku! Aku sudah muak selama ini tinggal dengan monyet monyet jelek di Alas Tawengan itu!"
"Oh, jadi selama ini Nyai tinggal disana?" nada suara Ki Suryo terdengar seperti mengejek.
"Oh, jadi selama ini Nyai tinggal disana?" nada suara Ki Suryo terdengar seperti mengejek.
"Si Sadiyo keparat itu menendangku hingga terpental kesana saat dulu duel di Kali Rampeng! Beruntung aku tak sampai tewas! Dan sialnya lagi, laki laki keparat itu masih sempat meninggalkan walatnya pada cucu perempuannya itu, hingga aku tak bisa kembali ke kerajaanku!"
Laki laki tua bernama Suryo itu nyaris tak bisa menahan tawanya mendengar ucapan berapi api si perempuan.
"Kenapa kamu tertawa he?!" sentak perempuan itu.
"Kenapa kamu tertawa he?!" sentak perempuan itu.
"Ah, tidak Nyai. Kenapa Nyai tidak mengerahkan para monyet siluman Alas Tawengan itu saja untuk membalaskan dendam Nyai?" goda Ki Suryo.
"Dan kau tinggal ongkang ongkang menikmati hasilnya? Sifat licikmu itu sepertinya memang sudah mendarah daging Suryo! Tapi tidak, aku tak sudi berhubungan dengan monyet monyet rendahan itu! Tinggal dekat dengan mereka saja sudah cukup membuatku muak,
apalagi harus bekerjasama dengan mereka!"
"Hahaha, baiklah! Aku akan sedikit berbaik hati padamu Nyai. Melenyapkan anak perempuan itu, bukan soal yang sulit buatku."
"Hahaha, baiklah! Aku akan sedikit berbaik hati padamu Nyai. Melenyapkan anak perempuan itu, bukan soal yang sulit buatku."
"Jangan terlalu jumawa Suryo! Kau tak ingat, kurang hebat apa bapakmu dulu? Toh dia akhirnya mampus juga di tangan si Sadiyo keparat itu! Apalagi kau yang masih anak kemarin sore!"
"Jangan bawa bawa bapakku Nyai! Bapakku mungkin lebih hebat dalam soal ilmu kanuragan.."
"Jangan bawa bawa bapakku Nyai! Bapakku mungkin lebih hebat dalam soal ilmu kanuragan.."
"..Tapi kamu jangan lupa, aku punya ini yang lebih berguna daripada sekedar ilmu kanuragan," dengus Ki Suryo sambil menunjuk pelipisnya sendiri.
"Aku percaya dengan kelicikanmu Suryo. Tapi itu bisa kau banggakan nanti, setelah berhasil melenyapkan anak itu.."
"Aku percaya dengan kelicikanmu Suryo. Tapi itu bisa kau banggakan nanti, setelah berhasil melenyapkan anak itu.."
"..Sekarang, kau masih punya satu kewajiban yang harus kau tunaikan padaku."
Cih! Ki Suryo mendecih. Ini hal yang paling ia tidak suka dari perempuan itu.
"Kenapa Suryo? Kau sudah bosan padaku heh?!"
"Ah, tidak Nyai."
Cih! Ki Suryo mendecih. Ini hal yang paling ia tidak suka dari perempuan itu.
"Kenapa Suryo? Kau sudah bosan padaku heh?!"
"Ah, tidak Nyai."
"Kalau begitu, tunggu apalagi?! Cepatlah kemari dan tunaikan kewajibanmu!"
Sial! Dengan malas Ki Suryo bangkit dan mendekat ke arah dipan, menghampiri perempuan cantik yang kini telah telentang diatas dipan dengan posisi yang sangat menantang.
Sial! Dengan malas Ki Suryo bangkit dan mendekat ke arah dipan, menghampiri perempuan cantik yang kini telah telentang diatas dipan dengan posisi yang sangat menantang.
Andai saja Ki Suryo tak tau wujud yang sebenarnya dari perempuan itu, tentu ia akan melaksanakan kewajiban itu dengan senang hati. Tapi sayangnya, Ki Suryo tahu wujud sebenarnya dari perempuan cantik itu yang sebenarnya.
Sangat menjijikkan! Dan ia terpaksa harus menggaulinya malam ini.
***
***
Hari itu, tak seperti biasanya, Bu Ratih mengajar murid muridnya tanpa semangat sama sekali. Selain karena peristiwa di kali Salahan kemarin yang masih menghantuinya, juga karena salah satu muridnya yang hari ini tak masuk sekolah.
Wulan, anak itu hari ini izin untuk tak mengikuti pelajaran, tanpa alasan yang jelas.
Hingga lonceng tanda istirahat berdentang, guru muda itu hanya memberi sedikit tugas untuk murid muridnya.
Hingga lonceng tanda istirahat berdentang, guru muda itu hanya memberi sedikit tugas untuk murid muridnya.
Dan begitu murid murid itu berhamburan keluar untuk menikmati jam istirahat, Bu Ratih juga melangkah tanpa semangat meninggalkan kelas menuju ke ruang guru.
Saat melintasi halaman sekolah, langkah guru muda itu terhenti.
Saat melintasi halaman sekolah, langkah guru muda itu terhenti.
Ekor matanya menangkap beberapa laki laki yang keluar dari ruang kepala sekolah. Bu Ratih mengenal mereka. Warga desa ini juga, yang memiliki anak yang bersekolah disini. Salah satunya adalah Pak Marto, orang tua Doni Yang meninggal kemarin.
Tapi apa tujuan mereka menemui kepala sekolah secara beramai ramai begitu?
Rasa penasaran mengubah arah langkah Bu Ratih. Guru muda itu mengurungkan niatnya untuk masuk ke ruang guru, lalu sedikit bergegas melangkah menuju ruang kepala sekolah.
Rasa penasaran mengubah arah langkah Bu Ratih. Guru muda itu mengurungkan niatnya untuk masuk ke ruang guru, lalu sedikit bergegas melangkah menuju ruang kepala sekolah.
"Boleh saya masuk Pak?" kata Bu Ratih sambil mengetuk pintu yang tak tertutup itu.
"Oh, Bu Ratih," Pak Slamet nampak sedikit terkejut melihat kedatangan Bu Ratih. "Silahkan Bu. Ada yang bisa saya bantu?"
"Oh, Bu Ratih," Pak Slamet nampak sedikit terkejut melihat kedatangan Bu Ratih. "Silahkan Bu. Ada yang bisa saya bantu?"
"Terima kasih Pak," Bu Ratihpun masuk dan duduk di hadapan kepala sekolah itu. "Kalau boleh tau, bapak bapak yang tadi itu, ada perlu apa ya Pak sampai datang beramai ramai menemui bapak? Emm, maaf kalau saya lancang ...."
"Tak apa Bu," Pak Slamet menghela nafas, lalu menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Sepertinya ada hal berat yang membebani pikiran kepala sekolah itu.
"Justru saya ingin membicarakan masalah ini dengan ibu."
"Justru saya ingin membicarakan masalah ini dengan ibu."
Bu Ratih diam, ia menunggu laki laki yang duduk di depannya itu melanjutkan kata katanya.
"Mereka mendesak saya untuk mengeluarkan Wulan dari sekolah ini Bu," desah Pak Slamet akhirnya.
"Mengeluarkan Wulan?! Kenapa Pak?" Bu Ratih nampak terkejut.
"Mereka mendesak saya untuk mengeluarkan Wulan dari sekolah ini Bu," desah Pak Slamet akhirnya.
"Mengeluarkan Wulan?! Kenapa Pak?" Bu Ratih nampak terkejut.
"Sama seperti kasus kasus sebelumnya, yang membuat Wulan harus pindah sekolah sampai tiga kali," jawab Pak Slamet.
"Lalu?" Bu Ratih mengerutkan keningnya.
"Lalu?" Bu Ratih mengerutkan keningnya.
"Tentu saja saya menolak, apalagi dengan alasan yang tak masuk akal seperti itu. Dan sepertinya para warga kecewa. Mereka pergi begitu saja tanpa pamit."
Kini Bu Ratih yang menghenyakkan punggungnya ke sandaran kursi. Ia memahami beratnya masalah yang dialami oleh Pak Slamet.
Kini Bu Ratih yang menghenyakkan punggungnya ke sandaran kursi. Ia memahami beratnya masalah yang dialami oleh Pak Slamet.
Bukan hal mudah menghadapi warga yang sedang tersulut emosi seperti itu.
"Kalau tidak keberatan, saya juga mohon bantuan ibu," suara Pak Slamet kembali memecah keheningan.
"Apa yang bisa saya bantu Pak?" tanya Bu Ratih.
"Kalau tidak keberatan, saya juga mohon bantuan ibu," suara Pak Slamet kembali memecah keheningan.
"Apa yang bisa saya bantu Pak?" tanya Bu Ratih.
"Setahu saya, Uwaknya Bu Ratih itu sangat disegani oleh warga desa sini. Jadi kalau boleh ...."
"Akan saya usahakan Pak. Selepas mengajar nanti biar saya menemui Wak Dul."
"Ah, terima kasih Bu."
"Sama sama Pak. Kalau begitu saya permisi dulu." Bu Ratih mohon pamit dan berdiri.
"Akan saya usahakan Pak. Selepas mengajar nanti biar saya menemui Wak Dul."
"Ah, terima kasih Bu."
"Sama sama Pak. Kalau begitu saya permisi dulu." Bu Ratih mohon pamit dan berdiri.
Namun baru beberapa langkah ia berjalan, kembali terdengar suara Pak Slamet yang memanggilnya.
"Bu Ratih sudah makan siang?"
"Eh, ini saya baru mau ke kantin Pak."
"Kebetulan. Saya juga belum makan siang. Bagaimana kalau kita makan siang bersama?"
"Bu Ratih sudah makan siang?"
"Eh, ini saya baru mau ke kantin Pak."
"Kebetulan. Saya juga belum makan siang. Bagaimana kalau kita makan siang bersama?"
Bu Ratih nampak berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan.
***
***
Siang yang terik, tak menyurutkan niat Bu Ratih untuk menemui Uwaknya. Sepulang mengajar, ia hanya singgah sebentar ke rumah untuk berganti pakaian, lalu kembali memacu motor bebeknya menyusuri jalanan berdebu menuju rumah sang Uwak.
Amanat dari Pak Slamet harus segera ia sampaikan. Semakin cepat akan semakin baik. Ia tahu betul sifat warga disitu. Mereka tidak akan menyerah meski dengan sangat jelas Pak Slamet telah menolak keinginan mereka.
Bukan hal yang mustahil jika nantinya para warga itu akan bertindak lebih nekat lagi.
Namun, Bu Ratih harus menelan kekecewaan saat sampai di rumah sang Uwak. Orang yang dicarinya ternyata sedang tidak berada di rumah.
Namun, Bu Ratih harus menelan kekecewaan saat sampai di rumah sang Uwak. Orang yang dicarinya ternyata sedang tidak berada di rumah.
Lagi ada urusan ke desa sebelah, begitu kata Wak Karni, istri dari Wak Dul.
Bu Ratih menepuk jidat. Beginilah akibatnya kalau mengerjakan sesuatu secara terburu buru.
Bu Ratih menepuk jidat. Beginilah akibatnya kalau mengerjakan sesuatu secara terburu buru.
Seharusnya ia tahu akan hal itu, karena kemarin sang Uwak memang sempat berkata kalau siang ini ada urusan di desa tetangga.
Guru muda itupun segera pamit kepada Wak Karni. Masih ada satu tempat lagi yang harus ia tuju. Rumah Wulan.
Guru muda itupun segera pamit kepada Wak Karni. Masih ada satu tempat lagi yang harus ia tuju. Rumah Wulan.
Ia ingin tahu kenapa hari ini anak itu tak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Sekaligus ia juga ingin membahas masalah keinginan para warga itu dengan Mas Joko, ayah dari Wulan.
Kali ini ia tak mau terburu buru.
Kali ini ia tak mau terburu buru.
Selain karena tak ingin kecele lagi, ia juga harus menata hatinya terlebih dahulu. Bukan hal mudah untuk menemui Wulan. Rasa pening di kepalanya akibat kemarin sempat bersitatap dengan Wulan waktu di kali Salahan saja sampai sekarang belum sepenuhnya hilang.
Belum lagi jika harus menyampaikan keinginan para warga itu kepada Mas Joko. Ia hanya mengenal sekilas laki laki itu. Tapi ia tahu, ayah dari Wulan ini termasuk orang yang baik dan karismatik. Sedikit pendiam namun murah senyum dan ..., juga sedikit tampan.
Ups. Kenapa aku jadi berpikiran melantur begini? Batin Bu Ratih sambil tersenyum simpul. Teringat dulu saat pertama kali melihat laki laki itu, ia sempat sedikit terpesona, sampai akhirnya ia malu sendiri karena ternyata laki laki itu sudah memiliki seorang istri.
Intinya, mudah saja untuk bicara dengan Mas Joko. Laki laki itu pasti dengan mudah bisa diajak berdiskusi mengenai masalah ini. Tapi istrinya itu, kabar yang ia dengar, Mbak Romlah itu, meski cantik tapi lumayan judes.
Semakin mendekati pondok kayu ditengah ladang itu, Bu Ratih semakin mengurangi kecepatan motornya. Kali ini nasib baik sepertinya berpihak padanya. Dari kejauhan dilihatnya Lintang berjalan seorang diri. Anak itu masih mengenakan seragam sekolah dan menyangklong tas.
Sepertinya ia juga baru pulang dari sekolah. Segera Bu Ratih menghentikan motornya di dekat anak itu.
"Eh, Bu Ratih?" seru anak itu kaget, lalu menyalami dan mencium tangan sang guru.
"Belum sampai rumah Tang?" sapa Bu Ratih. Anak itu memang tinggal di desa Kedhungsono.
"Eh, Bu Ratih?" seru anak itu kaget, lalu menyalami dan mencium tangan sang guru.
"Belum sampai rumah Tang?" sapa Bu Ratih. Anak itu memang tinggal di desa Kedhungsono.
Jarak rumahnya paling jauh dari sekolahan yang letaknya di desa Kedhung Jati.
"Belum Bu," Lintang menjawab sambil mengusap peluh yang mengalir di pelipisnya.
"Bareng sama ibu yuk," ajak Bu Ratih.
"Eh ..., emm ..., terimakasih Bu, tapi ...."
"Belum Bu," Lintang menjawab sambil mengusap peluh yang mengalir di pelipisnya.
"Bareng sama ibu yuk," ajak Bu Ratih.
"Eh ..., emm ..., terimakasih Bu, tapi ...."
"Ayolah! Sekalian ibu mau minta tolong sama kamu." ujar Bu Ratih lagi, memotong keraguan Lintang.
Akhirnya dengan segan anak itupun naik ke boncengan motor sang guru. Bu Ratih segera melajukan motornya kembali.
Akhirnya dengan segan anak itupun naik ke boncengan motor sang guru. Bu Ratih segera melajukan motornya kembali.
"Lintang habis ini mau kemana?" tanya Bu Ratih disela deru suara motornya.
"Nggak kemana mana Bu, paling kalau jadi mau nengokin Wulan. Tadi dia nggak masuk sekolah, jadi..."
"Kebetulan dong, barusan ibu juga mau minta tolong sama kamu buat nemenin ibu ke rumah Wulan."
"Nggak kemana mana Bu, paling kalau jadi mau nengokin Wulan. Tadi dia nggak masuk sekolah, jadi..."
"Kebetulan dong, barusan ibu juga mau minta tolong sama kamu buat nemenin ibu ke rumah Wulan."
"Ibu juga mau menjenguk Wulan?"
Iya. Nanti kita sama sama kesana ya?"
"Iya Bu. Tapi Lintang boleh kan pulang dulu, buat ganti baju dan pamit sama emak?"
"Tentu saja. Ibu akan mengantarmu sampai rumah dulu, habis itu kita sama sama ke rumah Wulan ya."
"Terimakasih Bu."
Iya. Nanti kita sama sama kesana ya?"
"Iya Bu. Tapi Lintang boleh kan pulang dulu, buat ganti baju dan pamit sama emak?"
"Tentu saja. Ibu akan mengantarmu sampai rumah dulu, habis itu kita sama sama ke rumah Wulan ya."
"Terimakasih Bu."
"Aku yang seharusnya berterimakasih padamu Tang," Bu Ratih tersenyum. Ia sedikit lega. Paling tidak, ia akan sedikit tenang nanti jika berhadapan dengan Wulan jika ditemani Lintang.
***
***
Di rumah Wulan.
Joko dan Romlah nampak terkejut melihat kedatangan Bu Ratih ke pondok mereka. Buru buru mereka mempersilahkan guru muda itu masuk. Sedikit lega Bu Ratih mendapat sambutan yang hangat seperti itu.
Joko dan Romlah nampak terkejut melihat kedatangan Bu Ratih ke pondok mereka. Buru buru mereka mempersilahkan guru muda itu masuk. Sedikit lega Bu Ratih mendapat sambutan yang hangat seperti itu.
Ternyata keluarga ini cukup ramah, tak seperti yang ia dengar selama ini dari para penduduk.
Setelah berbasa basi sebentar, Bu Ratihpun segera mengutarakan maksud kedatangannya ke pondok itu. Joko nampak menghela nafas berat, sebelum menanggapi ucapan Bu Ratih.
Setelah berbasa basi sebentar, Bu Ratihpun segera mengutarakan maksud kedatangannya ke pondok itu. Joko nampak menghela nafas berat, sebelum menanggapi ucapan Bu Ratih.
"Mohon maaf sebelumnya Bu, saya tak sempat memberi kabar kalau Wulan tadi nggak bisa masuk sekolah. Dari semalam anak itu ngambek dan nggak mau keluar kamar. Sepertinya Wulan masih sedikit syok dengan kejadian di kali Salahan kemarin," ujar Joko.
"Memang keterlaluan Pak Marto itu. Bisa bisanya dia bicara begitu sama Wulan. Pakai didorong dorong segala lagi sampai jatuh begitu. Beruntung saya tak ada waktu itu. Kalau saya lihat, sudah saya ...."
"Romlah!" Joko memotong ucapan sang istri. "Jaga bicaramu!"
"Romlah!" Joko memotong ucapan sang istri. "Jaga bicaramu!"
"Kesal aku Bang. Seenaknya saja ..."
"Ssstttt! Sudah! Ndak baik bicara begitu di depan Bu guru!"
"Nggak papa kok Mas, Mbak," Bu Ratih hanya tersenyum simpul melihat kelakuan suami istri itu.
"Ssstttt! Sudah! Ndak baik bicara begitu di depan Bu guru!"
"Nggak papa kok Mas, Mbak," Bu Ratih hanya tersenyum simpul melihat kelakuan suami istri itu.
"Saya hanya khawatir kalau Wulan sakit. Nggak biasanya dia tak masuk sekolah begitu kalau bukan karena sakit, karena setahu saya Wulan memang anak yang rajin."
"Saya juga bingung Bu, harus bagaimana lagi untuk membujuk anak itu. Di sedikit keras kepala, dan, dia juga bilang kalau nggak mau sekolah lagi, karena ia merasa semua orang membencinya."
Bu Ratih terdiam. Tak mau sekolah lagi? Sampai sejauh itukah pemikiran bocah sebelas tahun itu? batin Bu Ratih. Namun kata kata ayahnya Wulan barusan melintaskan sebuah ide di benaknya.
Wulan tak mau sekolah lagi, dan warga menginginkan Wulan dikeluarkan dari sekolah, itu berarti aku bisa .....
"Tapi saya akan mencoba membujuknya lagi Bu, mudah mudahan besok Wulan sudah mau masuk sekolah lagi," ucapan Joko membuyarkan lamunan Bu Ratih.
"Tapi saya akan mencoba membujuknya lagi Bu, mudah mudahan besok Wulan sudah mau masuk sekolah lagi," ucapan Joko membuyarkan lamunan Bu Ratih.
"Ya mudah mudahan saja Mas. Saya sebagai gurunya juga akan berusaha untuk membantu Wulan. Dia anak yang cerdas Mas, sayang kalau sampai ketinggalan pelajaran terlalu lama."
"Ah, terimakasih Bu, dan maaf kalau anak saya sampai merepotkan bu guru."
"Ah, terimakasih Bu, dan maaf kalau anak saya sampai merepotkan bu guru."
"Tak apa Mas. Itu kan memang sudah menjadi kewajiban saya sebagai gurunya."
Obrolan itu terus berlanjut. Sampai tak terasa sore hampir menjelang. Bu Ratih segera pamit pulang, setelah keinginannya untuk bertemu Wulan ditolak mentah mentah oleh anak itu.
Obrolan itu terus berlanjut. Sampai tak terasa sore hampir menjelang. Bu Ratih segera pamit pulang, setelah keinginannya untuk bertemu Wulan ditolak mentah mentah oleh anak itu.
Namun Bu Ratih sudah cukup puas. Dari obrolan dengan keluarga Wulan tadi, ia mendapat sebuah ide yang cemerlang. Meski ide itu sedikit tak biasa, tapi mungkin bisa mengatasi masalah yang pelik ini. Tinggal menunggu persetujuan dari Pak Slamet sebagai kepala sekolah.
Hari semakin sore saat Bu Ratih sampai di rumah. Ia segera mandi dan berberes, menyiapkan makan malam untuk ayah dan adiknya, lalu makan malam bersama, sebelum akhirnya masuk ke kamar untuk beristirahat. Penat sekujur tubuhnya setelah seharian tak sempat beristirahat sama sekali.
Dan malam ini, sepertinya ia bisa tidur dengan nyenyak, tanpa perlu ada masalah yang harus ia pikirkan lagi.
***
***
Malam semakin larut. Suasana desa juga semakin sepi. Hanya ada beberapa bapak bapak yang bertugas ronda di poskamling yang masih terjaga. Itupun mereka tak sepenuhnya berjaga. Ada sebagian yang justru meringkuk tidur berselimut sarung di dalam poskamling.
Sebagian lagi asyik main kartu sambil ngopi ngopi cantik.
Kondisi desa memang cenderung aman belakangan ini, jadi apa lagi yang harus mereka jaga. Namun kewajiban tetaplah kewajiban, harus dilaksanakan meski tidak dengan sepenuh hati.
Kondisi desa memang cenderung aman belakangan ini, jadi apa lagi yang harus mereka jaga. Namun kewajiban tetaplah kewajiban, harus dilaksanakan meski tidak dengan sepenuh hati.
Mereka tidak menyadari, bahwa saat mereka tengah lengah dengan kewaspadaan mereka untuk berjaga, seseorang memanfaatkan kelengahan itu.
Di sudut desa, tepatnya di jalan setapak yang menghubungkan desa Kedhung Jati dan desa Ngantiyan, nampak sesosok bayangan hitam yang berjalan mengendap endap di keremangan malam.
Sesekali sosok itu menyelinap diantara semak semak saat sinar bulan meneranginya, lalu kembali berjalan saat awan tipis menghalangi sinar sang rembulan.
Sampai di tepi desa Kedhung Jati, sosok itu berbelok ke arah utara, tetap menyusuri jalan setapak yang di kiri kanannya ditumbuhi lebatnya semak belukar. Langkahnya semakin cepat, seiring dengan hari yang juga semakin malam.
Sudah jelas, tempat mana yang akan dituju oleh sosok itu. Karena jalan setapak itu hanya mengarah ke satu tempat, kompleks pemakaman desa Kedhung Jati.
Kaki kurus kecil tanpa alas itu seolah memiliki mata. Dengan lincahnya menyusuri jalan setapak yang gelap dan sunyi itu.
Kaki kurus kecil tanpa alas itu seolah memiliki mata. Dengan lincahnya menyusuri jalan setapak yang gelap dan sunyi itu.
Sesekali berjingkat, lalu sesekali sedikit melompat, menghindari bebatuan dan ranting kering yang berserakan.
Si pemilik kaki, laki laki tua dengan tubuh kecil kurus kering, seolah memaksa sang kaki untuk terus melangkah. Mulut keriputnya tak henti hentinya berkomat kamit.
Si pemilik kaki, laki laki tua dengan tubuh kecil kurus kering, seolah memaksa sang kaki untuk terus melangkah. Mulut keriputnya tak henti hentinya berkomat kamit.
Sekejap menggumam, sekejap mengumpat, lalu sekejap kemudian tertawa lirih.
"Kalau bukan karena nenek tua peot itu, tak sudi aku kelayapan di tengah malam begini! Seenaknya saja dia menyuruh nyuruh, dikiranya aku budaknya apa!" gumam laki laki itu sambil terus berjalan.
"Kalau bukan karena nenek tua peot itu, tak sudi aku kelayapan di tengah malam begini! Seenaknya saja dia menyuruh nyuruh, dikiranya aku budaknya apa!" gumam laki laki itu sambil terus berjalan.
"Tapi tak apa. Aku juga punya urusan tersendiri dengan bocah itu. Si Sadiyo Kendhil keparat itu yang dulu menghabisi bapakku! Jadi tak ada salahnya kalau aku membalaskan kematian bapakku pada anak keturunannya! Hanya seorang bocah ingusan ini, apa susahnya!"
sungutnya lagi, masih terus sambil berjalan.
"Tapi sebelumnya aku harus bisa mengambil apa yang dimiliki anak itu! Si nenek tua peot itu sepertinya sangat takut dengan apa yang dimiliki anak itu.."
"Tapi sebelumnya aku harus bisa mengambil apa yang dimiliki anak itu! Si nenek tua peot itu sepertinya sangat takut dengan apa yang dimiliki anak itu.."
"..Kalau aku bisa merebutnya, nenek peot itu tak akan berani lagi menjadikanku budak nafsu setannya itu! Aku bisa bebas merdeka, hahaha ...."
Tawanya membuncah saat langkahnya telah memasuki gerbang pemakaman. Sejenak laki laki itu berhenti.
Tawanya membuncah saat langkahnya telah memasuki gerbang pemakaman. Sejenak laki laki itu berhenti.
Mulutnya kembali komat kamit dengan mata terpejam beberapa saat. Setelah itu ia kembali melangkah. Dengan lincah kedua kaki kurusnya menghindari batu nisan yang terletak tak beraturan. Meski malam begitu gelap, namun sepertinya ia sudah tau pasti makam mana yang akan ia tuju.
Empat gundukan tanah merah, dengan taburan kembang setaman yang masih terlihat segar di atasnya. Laki laki itu lalu duduk bersila di depan keempat makam baru itu, lalu membuka bungkusan kain kumal yang dibawanya. Dupa kemenyan segera ia nyalakan.
Tangan bersidekap di depan dada, mata terpejam, dan mulut komat kamit merapalkan mantra.
Entah mantra apa yang diucapkan laki laki tua itu. Yang jelas, suasana malam yang awalnya sunyi dan sepi berubah menjadi gaduh.
Entah mantra apa yang diucapkan laki laki tua itu. Yang jelas, suasana malam yang awalnya sunyi dan sepi berubah menjadi gaduh.
Angin tiba tiba bertiup kencang, menggoyangkan pucuk pucuk pepohonan yang mengelilingi kompleks pemakaman itu, menimbulkan suara gemerisik, dan membubarkan burung burung malam yang semenjak tadi mengintai dari balik rimbunnya dedaunan.
Rembulan di atas sanapun seolah merasa enggan menerangi malam, semakin dalam menyembunyikan sinar pucatnya di balik kelamnya awan hitam. Suara lolongan anjing saling bersahutan terdengar dari kejauhan, ditingkahi suara burung hantu yang mengalun sendu seolah ingin menyayat kalbu.
Laki laki tua itu seolah tak merasa terganggu. Ia masih terus saja berkomat kamit dengan mata terpejam dan tangan besidekap di dada. Hingga saat suasana kembali tenang, laki laki itu membuka matanya. Sebelah tangannya meraih sesuatu dari dalam bungkusan kain kumalnya.
Welat! Sayatan kulit bambu wulung yang dikenal sangat tajam setajam silet. Kembali laki laki itu berkomat kamit sambil menjulurkan pergelangan tangan kirinya keatas keempat makam didepannya.
Tangan kanannya yang memegang welat bergerak pelan, menempelkan sayatan kulit bambu wulung itu di pergelangan tangan kanannya, lalu menggoreskannya dengan sekuat tenaga.
Kulit keriput di pergelangan tangan itu tersayat sangat dalam. Darah kental mengucur dengan derasnya.
Kulit keriput di pergelangan tangan itu tersayat sangat dalam. Darah kental mengucur dengan derasnya.
Segera laki laki tua itu mengucurkan darahnya yang membanjir itu keatas keempat makam yang ada dihadapannya.
"BANGKIT!!! DAN JADILAH BUDAK SETIAKU!!!" tiba tiba laki laki tua itu berteriak lantang, sambil menghentakkan telapak tangannya yang terbuka ke permukaan tanah.
"BANGKIT!!! DAN JADILAH BUDAK SETIAKU!!!" tiba tiba laki laki tua itu berteriak lantang, sambil menghentakkan telapak tangannya yang terbuka ke permukaan tanah.
Tanah bergetar. Angin kembali bertiup kencang. Keempat gundukan tanah merah dengan taburan kembang setaman diatasnya itu pelan pelan ikut bergetar. Bergerak meretak, semakin melebar, untuk selanjutnya terbelah menjadi dua bagian, menampakkan rongga memanjang yang gelap dan dalam.
Asap tipis mengepul dari rongga itu. Semakin lama semakin tebal, lalu berkesiut terbawa angin dan berkumpul di sisi rongga yang pelan pelan kembali merapat. Pelan namun pasti juga, gumpalan gumpalan asap itu membentuk suatu siluet tubuh transparan.
Semakin lama semakin jelas, lalu berubah menjadi empat sosok bayangan hitam legam yang berdiri mematung seolah menunggu perintah. Bau sangit daging terbakar bercampur aroma busuk menguar menusuk indera penciuman.
"Hehehe ....!!!" laki laki tua itu terkekeh sambil mengusap luka bekas sayatan kulit bambu wulung di pergelangan tangannya. Ajaib! Sekali usap luka itu lenyap tanpa meninggalkan bekas sama sekali.
"Kalian sudah tau kan apa tugas kalian?
"Kalian sudah tau kan apa tugas kalian?
LAKSANAKAN!" kembali suara laki laki tua itu terdengar lantang. Keempat sosok hitam legam itupun tiba tiba lenyap dalam sekejap mata.
"Hahaha ...!!! Hehe ...!!! Uhuk ...!!! Uhuk ..!!! Khoeekk ...!!! Cuih...!!!" laki laki tua itu terkekeh, lalu terbatuk batuk sambil melangkah sempoyongan meninggalkan area pemakaman.
"Sial! Aku sudah terlalu tua untuk melakukan ini!"
***
"Sial! Aku sudah terlalu tua untuk melakukan ini!"
***
Sementara itu diwaktu yang hampir bersamaan, namun di lokasi yang berbeda, Mas Yudi, salah satu warga desa Kedhung Jati, berjalan tersaruk saruk menyusuri jalan berbatu Tegal Salahan. Ia baru saja pulang dari menengok mertuanya yqng sedang sakit di desa Kedhungsono.
"Asem! kalau saja motor nggak ngadat, tentu nggak harus pulang jalan kaki begini," gerutu laki laki itu sambil menyorotkan senternya ke jalanan berbatu yang dilaluinya.
"Coba besok nggak harus berangkat kerja pagi pagi, aku nginep saja tadi dirumah bapak," lanjutnya lagi setelah menyalakan sebatang rokoknya.
Bukan tanpa alasan kalau Mas Yudi sampai harus menggerutu. Jarak desa Kedhungsono ke Kedhung Jati memang tak begitu jauh.
Bukan tanpa alasan kalau Mas Yudi sampai harus menggerutu. Jarak desa Kedhungsono ke Kedhung Jati memang tak begitu jauh.
Tak sampai satu jam jika ditempuh dengan berjalan kaki. Namun harus melewat area Tegal Salahan yang terkenal angker itulah yang membuat bapak satu anak ini sedikit segan.
Sebagai warga asli Kedhung Jati, Mas Yudi memang sudah sering menjadi korban keisengan penghuni Tegal Salahan itu. Tapi tetap saja, meski sudah terbiasa, rasa merinding itu tetap ada setiap melewati area Tegal Salahan. Apalagi di tengah malam buta begini.
Laki laki itu terus melangkah, sambil sesekali bersenandung kecil untuk mengusir rasa sepi. Sorot lampu senternya menari nari menerangi jalanan berbatu yang dilaluinya. Sesekali ia juga mengarahkan senternya ke semak semak di pinggir jalan, saat mendengar suara gemerisik
yang terinjak oleh entah musang atau binatang malam lainnya.
Mas Yudi terus berjalan. Sampai saat memasuki turunan jalan Tegal Salahan, Mas Yudi tertegun, lalu menghentikan langkahnya. Dari arah yang berlawanan, tepatnya di jalan turunan yang dari arah Kedhung Jati,
Mas Yudi terus berjalan. Sampai saat memasuki turunan jalan Tegal Salahan, Mas Yudi tertegun, lalu menghentikan langkahnya. Dari arah yang berlawanan, tepatnya di jalan turunan yang dari arah Kedhung Jati,
nampak empat orang berjalan beriringan menuju ke arahnya.
Ah, mungkin para petugas ronda yang sedang berkeliling, kebetulan, aku jadi ada teman, pikir Mas Yudi sambil mempercepat langkahnya.
Ah, mungkin para petugas ronda yang sedang berkeliling, kebetulan, aku jadi ada teman, pikir Mas Yudi sambil mempercepat langkahnya.
Sampai saat melewati buk yang ada di antara tanjakan dan turunan jalan Salahan, Mas Yudi kembali tertegun.
Tunggu, kalau itu petugas ronda, kenapa mereka berjalan gelap gelapan gitu, tanpa membawa senter?
Tunggu, kalau itu petugas ronda, kenapa mereka berjalan gelap gelapan gitu, tanpa membawa senter?
Dan juga tak terdengar suara tabuhan kentongan yang biasa mereka bunyikan saat sedang berkeliling ronda. Dan ...
Mas Yudi mengendus endus. Bau apa ini? Seperti bau daging panggang? Sangit, dan dan agak busuk. Eh, jangan jangan ....
Mas Yudi mengendus endus. Bau apa ini? Seperti bau daging panggang? Sangit, dan dan agak busuk. Eh, jangan jangan ....
Mas Yudi mengarahkan sorot senternya ke arah keempat sosok yang berjalan beriringan itu, dan ....
"WHUUAAAAAAA ....!!!!"
"WHUUAAAAAAA ....!!!!"
"Whuannnccuukkk!!!" laki laki itu buru buru mematikan senternya, lalu berbalik dan mengambil langkah seribu menaiki jalan tanjakan yang menuju ke arah desa Kedhungsono.
"Hosh ...! Hosh ...! Hosh ...! Wedhus! Makhluk apa itu tadi?! Seluruh tubuhnya gosong begitu! Baru kali ini aku melihat dhemit yang seperti itu!" umpat Mas Yudi saat sudah sampai diatas tanjakan.
Ia berhenti sebentar untuk mengatur nafasnya, sambil berpikir, apa yang harus dilakukannya sekarang. Kembali ke rumah mertuanya? Tak mungkin. Bisa habis jadi bahan olok olokan dia kalau kembali kesana. Lagipula besok ia harus berangkat kerja pagi pagi.
Tak mungkin ia berangkat dari rumah mertuanya.
Ah, iya. Ke pondok Mas Joko saja. Kan deket tuh. Dia pasti mau mengantarku pulang. Segera laki laki itu berbelok menuju ke arah pondok kayu yang ada di tengah ladang singkong itu.
Ah, iya. Ke pondok Mas Joko saja. Kan deket tuh. Dia pasti mau mengantarku pulang. Segera laki laki itu berbelok menuju ke arah pondok kayu yang ada di tengah ladang singkong itu.
Namun saat sampai di teras pondok itu, ia kembali tertegun. Sudah jam segini, tak enak juga rasanya kalau harus mengetuk pintu rumah orang hanya karena ingin minta tolong untuk diantar pulang.
Sial! Kenapa sih aku selalu mengalami nasib seperti ini?
Sial! Kenapa sih aku selalu mengalami nasib seperti ini?
Mas Yudi menggaruk kepalanya yang tak gatal. Hidungnya kembali mengendus endus. Bau sangit itu kembali tercium. Makhluk itu, pasti sudah semakin dekat. Jangan jangan mereka mengikutiku? Bagaimana ini?
Tanpa pikir panjang Mas Yudi segera menerobos rimbunan pohon singkong yang ada di depan pondok itu. Ia berjongkok untuk menyembunyikan diri. Sementara dari arah jalan, keempat sosok bertubuh gosong itu juga berbelok ke arah pondok kayu milik Mas Joko.
"Sial! Sepertinya mereka benar benar mengikutiku!" batin Mas Yudi. Ia merebahkan tubuhnya, menelungkup diatas rerumputan yang basah oleh embun.
"Eh, Sepertinya mereka tak melihatku," gumam Mas Yudi saat melihat keempat sosok bertubuh gosong itu justru mengarah ke teras pondok.
"Eh, Sepertinya mereka tak melihatku," gumam Mas Yudi saat melihat keempat sosok bertubuh gosong itu justru mengarah ke teras pondok.
"Mau apa mereka ke pondok Mas Joko? Apa jangan jangan ...? Sebentar! Sepertinya aku mengenali mereka. Meski sekujur tubuhnya sudah gosong begitu, tapi postur tubuh dan ..., Ah, iya, Pak Darsa, juga istri dan anaknya. Tapi apa mungkin? Mereka kan sudah mati?!
Apa jangan jangan ...? Lalu apa hubungannya sama Mas Joko? Kenapa mereka mendatangi pondoknya? Oh, iya, desas desus yang kudengar dari warga desa ..., tapi tak mungkin! Mustahil kalau ..., eh, mereka ..."
Mas Yudi sampai membekap mulutnya sendiri saat melihat keempat sosok yang sepertinya berusaha untuk memaksa masuk ke dalam pondok. Namun usaha mereka sepertinya sia sia. Beberapa kali mereka membenturkan tubuh ke arah pintu, seolah berusaha untuk menembus pintu kayu itu.
Namun pintu pondok itu tak bergeming sama sekali. Sampai pada akhirnya ...
"Whuuuussssshhhh ....!!!" keempat sosok itu tiba tiba terlempar ke segala arah. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghempaskan mereka.
"Whuuuussssshhhh ....!!!" keempat sosok itu tiba tiba terlempar ke segala arah. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghempaskan mereka.
Sialnya, salah satu dari keempat sosok itu terlempar dan jatuh tepat di depan wajah Mas Yudi, dengan wajah gosongnya yang meringis tepat menghadap ke arahnya.
"Wedhus! As*! Jaran!" sontak Mas Yudi melompat dan berlari secepat yang ia bisa sambil mengumpat panjang pendek.
"Wedhus! As*! Jaran!" sontak Mas Yudi melompat dan berlari secepat yang ia bisa sambil mengumpat panjang pendek.
Samar samar ia masih mendengar suara bentakan dari arah pondok Mas Joko.
"Dasar tukang ngintip! Pergi kalian! Atau kalian akan kubakar untuk kedua kalinya!"
***
"Dasar tukang ngintip! Pergi kalian! Atau kalian akan kubakar untuk kedua kalinya!"
***
Sementara itu, di poskamling desa Kedhung Jati, suasana terlihat lebih ramai dari biasanya. Selain bapak bapak yang mendapat tugas ronda, ada juga beberapa warga yang ikut nimbrung di poskamling itu. Salah satunya adalah Pak Marto.
Laki laki yang baru saja kehilangan anak semata wayangnya itu menumpahkan segala keluh kesahnya kepada orang orang yang sedang berkumpul di poskamling itu.
"Sudahlah Pak, ikhlaskan saja kepergian anakmu itu, biar dia juga tenang di alam sana," ujar salah seorang peronda mencoba menasehati.
"Ngomong sih gampang Jo, kamu belum pernah merasakan sih, bagaimana rasanya kehilangan anak yang kita sayangi,"
"Ngomong sih gampang Jo, kamu belum pernah merasakan sih, bagaimana rasanya kehilangan anak yang kita sayangi,"
Pak Marto menyandarkan punggungnya pada dinding poskamling. "Ini semua gara gara anak setan itu! Dia yang sudah membunuh anakku!"
"Jangan asal nuduh Pak, ndak baik itu. Nanti jatuhnya bisa jadi fitnah kalau menuduh orang tanpa bukti," peronda yang lain mencoba mengingatkan.
"Jangan asal nuduh Pak, ndak baik itu. Nanti jatuhnya bisa jadi fitnah kalau menuduh orang tanpa bukti," peronda yang lain mencoba mengingatkan.
"Tanpa bukti bagaimana? Sudah jelas sehari sebelumnya anak setan itu mengata ngatai anakku mukanya gosong! Dan kalian lihat sendiri kan, keadaan wajah anakku seperti apa saat meninggal?! Gosong! Kayak pantat kuali!" nada suara Pak Marto meninggi.
"Itu hanya kebetulan Pak. Kan sudah jelas, kata polisi, anakmu itu mati karena digigit ular."
"Kebetulan bagaimana? Kebetulan itu kalau cuma sekali dua kali! Lha ini, sudah berkali kali lho! Lagain mana ada orang digigit ular kok di bagian wajah!"
"Kebetulan bagaimana? Kebetulan itu kalau cuma sekali dua kali! Lha ini, sudah berkali kali lho! Lagain mana ada orang digigit ular kok di bagian wajah!"
"Kalian ndak lupa kan sama anak desa sebelah yang beberapa tahun lalu mati jatuh dari pohon mangga dan perutnya robek tersangkut ujung pagar besi? Lalu anak yang mati tenggelam di kolam sampai badannya melembung itu?"
"Dan kemarin itu, keluarga Pak Darsa, mati gosong tanpa sebab begitu?! Mereka semua mati setelah bermasalah dengan anak setan itu! Mereka mati dikutuk!" sentak Pak Marto penuh emosi.
"Jangan ngawur sampeyan Pak. Keluarga Pak Darsa itu mati karena kesetrum listrik, bukan karena dikutuk. Polisi sendiri yang bilang begitu. Jaman sekarang mana ada yang namanya kutukan begitu. Lagipula Wulan itu kan cuma anak anak.."
"..Bisa apa dia. Wajar kalau sering ribut sama teman temannya. Wajar kalau suka mengata ngatai temannya, namanya juga anak anak."
"Halah! Kalian ini memang ndak ada yang peduli sama aku! Kalian ndak setia kawan! Ndak soliper! Nanti kalau anak kalian sendiri yang jadi korban, baru kalian tau rasa!" sungut Pak Marta kesal.
Sangking kesalnya sampai ngomongnyapun jadi kesrimpet. Entah apa yang dia maksud dengan soliper itu.
Para peronda hanya bisa tersenyum kecut mendengar ucapan Pak Marta itu. Jika ditanggapi, mungkin hanya akan membuat laki laki itu semakin kesal.
Para peronda hanya bisa tersenyum kecut mendengar ucapan Pak Marta itu. Jika ditanggapi, mungkin hanya akan membuat laki laki itu semakin kesal.
Merekapun akhirnya mencoba mengalihkan pembicaraan. Sampai akhirnya, pembicaraan mereka terhenti saat tiba tiba Mas Yudi datang berlari lari dari arah selatan sambil mengomel tak jelas.
"Hei, kenapa Yud? Malam malam kok lari lari kayak dikejar setan gitu?" tanya salah seorang peronda.
"Ho-oh Lik! Memang aku dikejar setan! Setan gosong!" jawab Mas Yudi setelah menyambar cangkir kopi yang entah milik siapa dan menenggak isinya sampai ludes.
"Ho-oh Lik! Memang aku dikejar setan! Setan gosong!" jawab Mas Yudi setelah menyambar cangkir kopi yang entah milik siapa dan menenggak isinya sampai ludes.
"Halah! Ada ada saja kamu ini. Kalau mau guyon mbok ya kira kira. Mana ada setan kok gosong. Memangnya singkong bakar, gosong," sahut peronda yang lain sambil tertawa.
"Ini beneran Lik! Aku ndak lagi bercanda. Sampeyan ndak lihat apa aku sampai keringetan gini gara gara lari dari Tegal Salahan!"
"Lha itu salahmu sendiri! Sudah tau Salahan itu sarangnya dhemit. Ngapain kamu malam malam keluyuran kesana?"
"Lha itu salahmu sendiri! Sudah tau Salahan itu sarangnya dhemit. Ngapain kamu malam malam keluyuran kesana?"
"Aku habis dari Kedhungsono Lik, nengokin mertuaku yang lagi sakit. Kebetulan motor lagi ngadat. Terpaksa deh aku jalan kaki. Lha kok malah sampai di Salahan ketemu sama yang begituan," Mas Yudi lalu menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya.
Para peronda hanya tergelak, mentertawakan kesialan Mas Yudi yang memang dikenal sebagai orang paling konyol di desa Kedhung Jati itu. Namun tidak dengan Pak Marto. Laki laki itu nampak serius mendengarkan cerita Mas Yudi.
"Eh, Yud, tadi kamu bilang kalau setan gosong itu menuju ke pondok si Joko itu. Lalu apa yang terjadi?" tanya Pak Marto serius.
"Sepertinya mereka mau menakut nakuti keluarga Mas Joko Pak. Tapi gagal. Mereka justru mental. Dan tau nggak? Lagi lagi aku yang ketiban sial.."
"Sepertinya mereka mau menakut nakuti keluarga Mas Joko Pak. Tapi gagal. Mereka justru mental. Dan tau nggak? Lagi lagi aku yang ketiban sial.."
"..Salah satu dari setan gosong itu jatuh tepat di depan wajahku yang lagi ngumpet. Coba bayangkan, wajah gosong meringis itu hanya beberapa senti di depan wajahku, gimana aku nggak lari tunggang langgang" Kembali para peronda itu tertawa mendengar penuturan Mas Yudi itu.
"Nah! Ini! Sudah jelas ini! Sekarang kalian percaya kan?" sentak Pak Marto keras.
"Percaya apa Pak?" tanya salah seorang peronda.
"Percaya apa Pak?" tanya salah seorang peronda.
"Kalian belum paham juga? Empat setan gosong! Siapa lagi kalau bukan keluarga Pak Darsa yang kemarin mati gosong itu. Ini sudah jelas. Kematian mereka memang ada hubungannya sama keluarga si Joko itu. Dan mereka sekarang gentayangan mau menuntut balas!"
"Halah! Sudah sudah! Dari tadi kok itu saja yang diomongin! Sudah malam nih, waktunya kita keliling. Kita cek juga ke pondok Mas Joko itu, takutnya mereka kenapa kenapa. Biar bagaimanapun dia kan warga desa kita juga," tukas salah seorang peronda,
yang segera diamini oleh teman temannya, kecuali oleh Pak Marto yang terlihat masih sangat kesal.
***
***
Kabar tentang adanya teror setan gosong itu dengan cepat menyebar ke seantero desa, bahkan sampai ke desa desa tetangga. Entah benar atau hanya sekedar latah, mulai ada beberapa orang yang mengaku melihat atau bertemu dengan sosok setan gosong ini. Terutama kaum ibu.
Saat sedang belanja sayur di warung, saat bekerja di sawah, saat sedang sama sama mencuci baju di kali, saat sedang duduk bergerombol mencari kutu, yang mereka bicarakan tak lain dan tak bukan adalah adanya teror setan gosong ini.
Suasana desa yang semula adem ayem kini menjadi sedikit keruh. Pak Bayan yang tanggap akan situasi, segera mengambil tindakan. Kegiatan ronda malam ditingkatkan. Jumlah petugas ronda juga ditambah.
Dan beliau juga menghimbau kepada warganya agar tak terlalu membesar besarkan masalah ini. Kalau ada yang ketahuan menyebarkan cerita bohong soal setan gosong ini, akan saya tindak tegas, demikian kata Pak Bayan.
Namun himbauan itu hanya dianggap angin lalu oleh para warga. Berita tentang setan gosong semakin ramai menyebar. Dibumbui dengan cerita cerita yang kadang terdengar seperti mengada ada, membuat warga menjadi enggan untuk keluar malam.
Sedikit banyak kabar tentang adanya setan gosong ini berimbas pada keluarga Joko. Tak sedikit yang mengait ngaitkan kemunculan setan gosong ini dengan keluarga tersebut. Terutama kepada Wulan. Dia dianggap sebagai biang keladi dari semua masalah ini.
Apalagi orang orang yang memang sudah lama kurang suka dengan anak itu. Mereka seperti menyiramkan bensin ke dalam kobaran api. Kemunculan setan gosong ini mereka manfaatkan. Mereka jadikan senjata untuk semakin memojokkan Wulan.
Bu Ratih resah. Ini sudah hari keempat Wulan tak masuk sekolah. Jika terus dibiarkan begini, anak itu bisa banyak ketinggalan pelajaran. Dan ujian kelulusan sudah semakin dekat. Bu Ratih tak mau kalau sampai ada anak muridnya yang sampai tidak lulus.
Ide yang kemarin sempat terlintas di kepalanya, memang masih ia simpan. Guru muda itu belum sempat mengutarakannya kepada Pak Slamet. Ia berharap, Wulan kembali bersedia masuk sekolah lagi, dan ide itu tak sampai harus ia jalankan.
Namun sepertinya harapan guru muda itu tak terkabul. Sampai di hari yang ke empat Wulan tak juga menampakkan batang hidungnya di sekolah. Bu Ratih mulai berpikir untuk mulai membicarakan masalah ini dengan Pak Slamet.
"Bu Ratih yakin?" itu tanggapan pertama yang diberikan oleh kepala sekolah itu, saat Bu Ratih mengutarakan niatnya.
"Saya yakin Pak. Biar bagaimanapun, Wulan murid saya. Dan dia anak yang sangat cerdas. Sangat disayangkan kalau sampai anak itu berhenti sekolah."
"Saya yakin Pak. Biar bagaimanapun, Wulan murid saya. Dan dia anak yang sangat cerdas. Sangat disayangkan kalau sampai anak itu berhenti sekolah."
jawab Bu Ratih mantap.
"Saya belum pernah mendengar sistem pembelajaran yang seperti ini, dan itu juga berarti akan sangat merepotkan Bu Ratih. Mengajar di sekolah ini saja sudah banyak menyita waktu ibu. Apalagi ditambah nanti kalau ibu juga harus mengajar Wulan di rumahnya.."
"Saya belum pernah mendengar sistem pembelajaran yang seperti ini, dan itu juga berarti akan sangat merepotkan Bu Ratih. Mengajar di sekolah ini saja sudah banyak menyita waktu ibu. Apalagi ditambah nanti kalau ibu juga harus mengajar Wulan di rumahnya.."
"..Apalagi letak rumah Wulan yang sedikit terpencil dan berada di tempat yang katanya angker itu. Ditambah pula sikap dari beberapa warga terhadap keluarga Wulan yang kurang bersahabat. Apa kata mereka nanti kalau melihat Bu Ratih mengajar Wulan di rumahnya.."
"..Mereka bisa iri, dan menganggap Bu Ratih pilih kasih terhadap murid murid yang lain. Jujur, saya sedikit mengkhawatirkan keselamatan ibu." ujar Pak Slamet.
"Saya pindah ke desa ini semenjak saya masih kecil Pak, bersama kedua orang tua saya.."
"Saya pindah ke desa ini semenjak saya masih kecil Pak, bersama kedua orang tua saya.."
"..Jadi desa ini sudah seperti tanah kelahiran saya sendiri. Seluk beluk desa ini sudah saya hafal. Begitu juga dengan kehidupan masyarakatnya. Soal keangkeran Tegal Salahan itu, itu hanya omong kosong buat saya. Dan soal warga nanti mau bilang apa, saya tak terlalu peduli.."
"..Saya seorang guru, tugas saya mendidik murid murid saya. Soal waktu juga, bapak tak perlu terlalu merisaukan, saya akan dengan senang hati melakukannya kok, jadi tak ada rasa keterpaksaan yang akan saya rasakan," jelas Bu Ratih, mencoba mempertahankan usulnya.
Kepala sekolah itu nampak berpikir sejenak, lalu sambil tersenyum dia berkata," baik kalau begitu, tak ada salahnya kalau cara itu kita coba Bu."
"Jadi bapak setuju?" rona bahagia terpancar dari wajah cantik Bu Ratih, membuat Pak Slamet menjadi sedikit jengah.
"Jadi bapak setuju?" rona bahagia terpancar dari wajah cantik Bu Ratih, membuat Pak Slamet menjadi sedikit jengah.
"Ya, dan sebagai kepala sekolah, saya juga ikut merasa bertanggung jawab. Jadi untuk awal awalnya nanti, saya akan mendampingi ibu mengajar Wulan di rumahnya. Mungkin dalam beberapa hari saja, untuk menjaga ibu dari pandangan negatif para warga."
"Ah, saya rasa itu tak perlu Pak. Saya bisa menjaga diri kok."
"Tak apa Bu, saya juga melakukannya dengan senang hati kok. Itung itung saya juga ingin lebih dekat lagi dengan murid di sekolah ini, terutama Wulan."
"Tak apa Bu, saya juga melakukannya dengan senang hati kok. Itung itung saya juga ingin lebih dekat lagi dengan murid di sekolah ini, terutama Wulan."
Lega hati Bu Ratih. Masalah yang dia hadapi akhirnya mendapat jalan keluar. Dan mulai hari itu juga ia mulai mengajar Wulan di rumah. Siang selepas mengajar di sekolah, ia pulang sebentar untuk sekedar berganti pakaian dan makan siang,
lalu segera menuju pondok Mas Joko di Tegal Salahan.
Tanggapan keluarga itupun cukup ramah. Mereka sangat berterimakasih dengan kesediaan Bu Ratih untuk mengajar Wulan di rumah. Di hari hari awal, memang sedikit kaku. Wulan sepertinya masih enggan bertemu dengan Bu Ratih.
Tanggapan keluarga itupun cukup ramah. Mereka sangat berterimakasih dengan kesediaan Bu Ratih untuk mengajar Wulan di rumah. Di hari hari awal, memang sedikit kaku. Wulan sepertinya masih enggan bertemu dengan Bu Ratih.
Namun dengan kesabaran dan kesungguhan guru muda itu, sikap Wulan akhirnya sedikit luluh juga. Apalagi selalu ada Pak Slamet yang setia mendampingi.
Sambil mengajar, sesekali Bu Ratih mencuri curi pandang ke arah anak itu, mencoba menyelami apa yang ada di pikiran anak itu.
Sambil mengajar, sesekali Bu Ratih mencuri curi pandang ke arah anak itu, mencoba menyelami apa yang ada di pikiran anak itu.
Pun begitu, guru muda itu masih tetap belum berani menatap mata Wulan secara langsung. Masih ada getaran getaran aneh yang ia rasakan saat menatap mata anak itu.
Apa yang dikatakan Pak Slametpun menjadi kenyataan.
Apa yang dikatakan Pak Slametpun menjadi kenyataan.
Kasak kusuk warga mulai terdengar kurang sedap melihat kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ratih itu. Tapi mereka hanya berani bicara di belakang. Mengingat Bu Ratih adalah keponakan dari Pak Modin, orang yang dituakan dan dihormati di desa itu.
Sementara di desa Ngantiyan, Ki Suryo juga tersenyum puas. Langkah pertama yang ia buat berjalan dengan lancar. Warga mulai terpengaruh dengan keberadaan setan gosong ciptaannya. Mereka semakin membenci anak itu.
Tinggal melancarkan serangan selanjutnya.
Tinggal melancarkan serangan selanjutnya.
Tapi ada yang sedikit mengganjal di hatinya. Guru muda itu, dia justru semakin dekat dengan anak itu. Dan itu berarti bisa menjadi batu sandungan untuknya.
"Hmm, sepertinya aku harus memberi sedikit peringatan kepada guru muda itu,"
"Hmm, sepertinya aku harus memberi sedikit peringatan kepada guru muda itu,"
gumam laki laki tua itu sambil menghembuskan asap rokoknya kuat kuat.
***
***
Hari itu, seperti biasa, sepulang mengajar di sekolah, bu Ratih langsung menuju ke pondok Mas Joko di Tegal Salahan. Banyak tugas sekolah yang harus diselesaikan oleh Wulan.
Sambil menemani Wulan mengerjakan tugas, guru muda itu asyik mengobrol dengan si empunya rumah.
Sambil menemani Wulan mengerjakan tugas, guru muda itu asyik mengobrol dengan si empunya rumah.
Mas Joko, laki laki yang dikenal pendiam itu ternyata cukup enak untuk diajak ngobrol. Demikian juga dengan Mbak Romlah, istrinya.
Perempuan yang masih terlihat cantik di usianya yang sudah tak lagi muda itu sibuk menyiapkan minuman dan makanan kecil untuk menemani sang guru mengajar.
Hal ini membuat Bu Ratih menjadi betah berlama lama di pondok itu, sampai tak terasa hari semakin sore. Bu Ratihpun segera pamit pulang.
"Sudah hampir maghrib Bu, apa tidak sebaiknya biar diantar saja sama bapaknya Wulan?" kata Mbak Romlah saat Bu Ratih pamit.
"Sudah hampir maghrib Bu, apa tidak sebaiknya biar diantar saja sama bapaknya Wulan?" kata Mbak Romlah saat Bu Ratih pamit.
Memang ini hari pertamanya ia mengajar di rumah Wulan tanpa ditemani oleh Pak Slamet.
"Terima kasih Mbak, tapi saya rasa nggak perlu. Saya bisa pulang sendiri kok. Lagian saya kan bawa motor," tolak Bu Ratih halus.
"Terima kasih Mbak, tapi saya rasa nggak perlu. Saya bisa pulang sendiri kok. Lagian saya kan bawa motor," tolak Bu Ratih halus.
"Ya sudah kalau begitu, hati hati ya Bu, dan terima kasih banyak lho, sudah bersedia mengajar Wulan di rumah," ujar Mbak Romlah lagi.
Bu Ratihpun segera menjalankan sepeda motor bebeknya pelan pelan, menyusuri jalan berbatu Tegal Salahan.
Bu Ratihpun segera menjalankan sepeda motor bebeknya pelan pelan, menyusuri jalan berbatu Tegal Salahan.
Matahari sudah hampir tenggelam di ufuk barat sana. Angin sore bertiup lembut mengusap wajah cantiknya. Terasa sangat menyejukkan.
Namun rasa sejuk itu tiba tiba berubah menjadi sedikit gerah saat sepeda motor yang dikendarai guru muda itu mendekati buk yang ada diantara tanjakan dan turunan jalan itu.
Guru muda itu menhentikan motornya. Inderanya yang lebih tajam dari orang kebanyakan menangkap adanya sesuatu yang tak wajar. Ada yang sedang memperhatikannya, atau lebih tepatnya menghalangi perjalanannya.
Bu Ratih mengedarkan pandangannya, mencoba mencari sesuatu yang sedang menganggunya. Hidung mungilnya menangkap aroma yang tak sedap. Bau sangit bercampur busuk menusuk indera penciumannya.
"Bau ini ..." batin Bu Ratih sambil masih tetap memperhatikan situasi di sekelilingnya.
"Bau ini ..." batin Bu Ratih sambil masih tetap memperhatikan situasi di sekelilingnya.
Ada rasa merinding yang ia rasakan. Biar bagaimanapun dia seorang perempuan. Berada di tempat sepi seperti ini, disaat hari mulai menjelang gelap, dengan sesuatu yang entah apa sedang berusaha menganggunya, membuat bulu kuduk perempuan cantik itu merinding.
"Ah, mungkin hanya perasaanku saja," batin Bu Ratih sambil berusaha menjalankan motornya kembali. Namun sial. Mendadak mesin motor itu justru mati. Beberapa kali ia coba menhidupkannya kembali, tapi gagal.
"Sial, kenapa di saat seperti ini ..." Bu Ratih tertegun, saat mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Kembali rasa takut menjalar di hatinya. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Hati kecilnya mengatakan, jangan menoleh ke belakang. Tapi nalurinya berkata lain.
Pelan pelan guru muda itu menoleh ke belakang. Dan ....
"Lho, Wulan? Kamu ...?" Bu Ratih menghela nafas lega. Tak disangkanya kalau yang menghampirinya itu adalah Wulan, anak muridnya sendiri.
"Lho, Wulan? Kamu ...?" Bu Ratih menghela nafas lega. Tak disangkanya kalau yang menghampirinya itu adalah Wulan, anak muridnya sendiri.
"Bu Ratih kenapa? Kok berhenti disini?" tanya anak itu sambil memperhatikan motor sang guru.
"Enggak kok. Ini lho, motor ibu tiba tiba mogok. Nggak tau kenapa. Wulan sendiri mau kemana? Ini sudah hampir maghrib lho." ujar guru muda itu sambil mengotak atik motornya.
"Enggak kok. Ini lho, motor ibu tiba tiba mogok. Nggak tau kenapa. Wulan sendiri mau kemana? Ini sudah hampir maghrib lho." ujar guru muda itu sambil mengotak atik motornya.
"Nggak kemana mana kok Bu. Kebetulan tadi keluar dan lihat ibu berhenti disini seperti lagi kebingungan. Wulan bantu dorong motornya ya Bu," Wulan memegang bagian belakang motor itu.
Tapi sepertinya bantuan Wulan tak dibutuhkan lagi, karena saat Bu Ratih mencoba menghidupkan mesin motornya untuk yang kesekian kalinya, motor itu kembali menyala dengan sangat mudahnya.
"Sudah nyala lagi nih motor ibu. Wulan pulang saja ya, sudah sore lho, nanti dicariin emak. Ibu juga mau buru buru pulang nih," kata Bu Ratih sambil naik ke jok motornya.
"Ya sudah kalau begitu, hati hati ya Bu," kata anak itu sambil tersenyum.
"Ya sudah kalau begitu, hati hati ya Bu," kata anak itu sambil tersenyum.
Bu Ratih membalas senyum itu, lalu menjalankan motornya pelan pelan. Wulan menatap kepergian sang guru sampai menghilang di tikungan jalan.
Anak itu kembali tersenyum, melirik sekilas ke arah semak semak yang ada di pinggir jalan, lalu berbalik dan melangkah pulang.
Anak itu kembali tersenyum, melirik sekilas ke arah semak semak yang ada di pinggir jalan, lalu berbalik dan melangkah pulang.
Waktu maghrib sudah lewat saat Bu Ratih sampai di rumah. Ia segera mandi dan menyiapkan makan malam untuk sang ayah, lalu masuk ke kamar. Masih banyak tugas yang harus ia selesaikan malam ini.
Ditemani oleh alunan musik lembut yang mengalun dari radio, perempuan itu mulai asyik mengoreksi hasil ulangan murid muridnya.
Tanpa terasa, hari semakin larut. Namun Bu Ratih masih sibuk dengan pekerjaannya. Diluar sepertinya ada tamu. Dari suaranya, ia tahu itu Pak Slamet.
Tanpa terasa, hari semakin larut. Namun Bu Ratih masih sibuk dengan pekerjaannya. Diluar sepertinya ada tamu. Dari suaranya, ia tahu itu Pak Slamet.
Belakangan ini, laki laki itu semakin sering datang ke rumahnya, sekedar ngobrol atau main catur dengan ayahnya.
Hubungan Pak Slamet dengan ayahnya memang sangat dekat, mengingat Pak Sholeh, sang ayah, dulu adalah juga seorang guru sekaligus seniornya Pak Slamet.
Hubungan Pak Slamet dengan ayahnya memang sangat dekat, mengingat Pak Sholeh, sang ayah, dulu adalah juga seorang guru sekaligus seniornya Pak Slamet.
Namun baru belakangan ini saja Pak Slamet jadi rajin datang ke rumah. Biasanya ia datang kalau memang lagi ada perlu saja.
Tanpa sadar guru muda itu tersenyum. Ia bukannya tak tahu kalau selama ini Pak Slamet menaruh sedikit perhatian padanya.
Tanpa sadar guru muda itu tersenyum. Ia bukannya tak tahu kalau selama ini Pak Slamet menaruh sedikit perhatian padanya.
Tapi sampai detik ini, belum pernah sekalipun laki laki itu mengungkapkan perasaannya. Entah karena masih ragu atau memang tak punya keberanian, laki laki itu hanya berani menunjukkan perhatian yang sedikit lebih kepadanya.
Ah, kenapa aku jadi memikirkan dia? Gumam Bu Ratih sambil tersenyum dikulum. Ia lalu kembali tenggelam dengan kesibukannya. Malampun kian merambat semakin larut. Suasana semakin sepi. Hanya terdengar suara obrolan sang ayah dengan Pak Slamet dari arah ruang tamu.
Tinggal beberapa lembar kertas lagi tugas yang harus ia selesaikan, saat tiba tiba ia merasa udara di dalam kamarnya menjadi sedikit gerah. Guru muda itu menghentikan sejenak kesibukannya, lalu meraih gelas yang ada di sampingnya.
Diteguknya isi gelas itu hingga tandas, berharap itu bisa sedikit mengurangi rasa gerah yang ia rasakan.
Namun, air putih itu sepertinya tak berpengaruh untuk mengusir rasa gerahnya. Ia lalu beranjak dari kursi yang didudukinya, dan melangkah menuju ke jendela.
Namun, air putih itu sepertinya tak berpengaruh untuk mengusir rasa gerahnya. Ia lalu beranjak dari kursi yang didudukinya, dan melangkah menuju ke jendela.
Dibukanya daun jendela itu lebar lebar, hingga udara segar dari luar bisa leluasa masuk ke dalam kamarnya.
Hembusan angin malam menyapu lembut wajah cantiknya. Terasa sangat menyegarkan.
Hembusan angin malam menyapu lembut wajah cantiknya. Terasa sangat menyegarkan.
Sengaja ia berdiri berlama lama di depan jendela yang terbuka, untuk merasakan sejuknya angin malam.
Suasana di luar sedikit temaram. Cahaya bulan menerobos di sela sela dedaunan pohon mangga yang tumbuh di samping kamarnya.
Suasana di luar sedikit temaram. Cahaya bulan menerobos di sela sela dedaunan pohon mangga yang tumbuh di samping kamarnya.
Suara nyanyian jengkerik dan belalang kayu terdengar begitu merdu. Sungguh suasana malam yang begitu sempurna. Membuat Bu Ratih sedikit enggan untuk beranjak dari depan jendela.
Namun suasana indah itu tak bertahan lama. Hidung perempuan cantik itu tiba tiba mengendus aroma yang tak sedap. Bau sangit bercampur dengan aroma busuk yang menusuk! Sama dengan aroma yang tadi sore ia cium di area Tegal Salahan.
Segera perempuan itu meraih daun jendela, bermaksud untuk menutupnya.
Namun gerakan tangannya terhenti, saat tiba tiba muncul wajah gosong menyeramkan tepat di depan mukanya. Hanya beberapa senti jaraknya dari wajah perempuan itu.
Namun gerakan tangannya terhenti, saat tiba tiba muncul wajah gosong menyeramkan tepat di depan mukanya. Hanya beberapa senti jaraknya dari wajah perempuan itu.
Wajah hitam gosong itu meringis, menampakkan gigi geliginya yang juga menghitam. Bau busuk menguar hebat menusuk indera penciuman perempuan itu.
Bu Ratih tercekat. Sekujur tubuhnya gemetar hebat. Ingin rasanya ia berteriak, tapi mulut terasa tersumbat.
Bu Ratih tercekat. Sekujur tubuhnya gemetar hebat. Ingin rasanya ia berteriak, tapi mulut terasa tersumbat.
Ia hanya bisa terpaku dengan wajah memucat untuk beberapa saat, sampai akhirnya tubuh perempuan itu ambruk tak sadarkan diri.
"Gubraaakkkk ...!!!" suara berderak akibat tubuh Bu Ratih yang jatuh menimpa meja,
"Gubraaakkkk ...!!!" suara berderak akibat tubuh Bu Ratih yang jatuh menimpa meja,
mengejutkan Pak Sholeh dan Pak Slamet yang sedang asyik bermain catur di ruang tamu. Kedua laki laki itu segera menhambur menuju ke kamar Bu Ratih, disusul oleh Ramadhan yang sepertinya juga belum tidur.
"Astaghfirullah! Ratih!" seru Pak Sholeh begitu mendapati sang anak telah tergeletak di lantai kamar. Pak Slamet segera mengangkat tubuh perempuan itu dan membaringkannya di atas ranjang.
"Ramadhan, tolong ambilkan minyak kayu putih," seru Pak Sholeh pada anak bungsunya itu.
"Ramadhan, tolong ambilkan minyak kayu putih," seru Pak Sholeh pada anak bungsunya itu.
Alih alih melaksanakan perintah sang ayah, anak laki laki itu justru terpaku menatap ke arah jendela yang terbuka dengan wajah pucat pasi.
"Ramadhan!" seru Pak Sholeh lagi.
"Se ..., se ..., setaaaannnn!!!" anak laki laki itu berteriak sambil berlari kembali ke kamarnya.
"Ramadhan!" seru Pak Sholeh lagi.
"Se ..., se ..., setaaaannnn!!!" anak laki laki itu berteriak sambil berlari kembali ke kamarnya.
"Bocah edan!" gerutu Pak Sholeh sambil berjalan ke arah jendela dan menutupnya. Sedang Pak Slamet masih sibuk menyadarkan Bu Ratih.
Pak Sholeh lalu membuka lemari, mencoba mencari balsem, minyak kayu putih, atau apa saja yang sekiranya bisa dipakai untuk menyadarkan sang anak.
Pak Sholeh lalu membuka lemari, mencoba mencari balsem, minyak kayu putih, atau apa saja yang sekiranya bisa dipakai untuk menyadarkan sang anak.
Beruntung, ia bisa segera menemukan benda itu.
Segera Pak Sholeh membantu Pak Slamet. Dioleskan minyak kayu putih di hidung sang anak. Pelan tubuh Bu Ratih menggeliat, lalu membuka matanya. Wajah yang pertama kali dilihatnya adalah wajah Pak Slamet.
Segera Pak Sholeh membantu Pak Slamet. Dioleskan minyak kayu putih di hidung sang anak. Pelan tubuh Bu Ratih menggeliat, lalu membuka matanya. Wajah yang pertama kali dilihatnya adalah wajah Pak Slamet.
Spontan perempuan itu menghambur memeluk laki laki itu.
"Pak, saya takut Pak," isak perempuan itu.
"Sudah Bu. Tenang. Ada apa sebenarnya, sampai ibu ketakutan dan pingsan begitu?" Pak Slamet mencoba melepaskan diri dari pelukan Bu Ratih.
"Pak, saya takut Pak," isak perempuan itu.
"Sudah Bu. Tenang. Ada apa sebenarnya, sampai ibu ketakutan dan pingsan begitu?" Pak Slamet mencoba melepaskan diri dari pelukan Bu Ratih.
Tak enak rasanya ia dipeluk di depan Pak Sholeh seperti itu.
Sadar akan apa yang telah ia lakukan, Bu Ratih juga buru buru melapaskan pelukannya pada laki laki itu. Wajahnya bersemu merah karena menahan malu.
Sadar akan apa yang telah ia lakukan, Bu Ratih juga buru buru melapaskan pelukannya pada laki laki itu. Wajahnya bersemu merah karena menahan malu.
"Sebentar, biar tak ambilkan minum dulu Met. Kemana lagi si Ramadhan tadi, mbakyunya pingsan begini kok malah ditinggal minggat," Pak Sholeh menggerutu sambil melangkah ke dapur.
"Maaf Pak, tadi saya ..." Bu Ratih semakin tertunduk, tak kuasa melanjutkan kata katanya.
"Maaf Pak, tadi saya ..." Bu Ratih semakin tertunduk, tak kuasa melanjutkan kata katanya.
"Iya Bu. Nggak papa. Ada apa sebenarnya, kenapa ibu sampai pingsan begini?" ujar Pak Slamet sambil duduk di kursi yang ada di kamar itu.
"Emmm, anu Pak, sebenarnya ..." Bu Ratih segera menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Suaranya terdengar gemetar.
"Emmm, anu Pak, sebenarnya ..." Bu Ratih segera menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Suaranya terdengar gemetar.
Masih terbayang jelas di pelupuk matanya wajah gosong meringis yang tadi dilihatnya.
"Setan gosong?!" Pak Slamet nampak terkejut mendengar penuturan Bu Ratih itu. "Jadi beneran setan gosong itu ada?"
"Saya melihatnya sendiri Pak, tepat di depan wajah saya," ujar Bu Ratih pelan.
"Setan gosong?!" Pak Slamet nampak terkejut mendengar penuturan Bu Ratih itu. "Jadi beneran setan gosong itu ada?"
"Saya melihatnya sendiri Pak, tepat di depan wajah saya," ujar Bu Ratih pelan.
"Dan, sore tadi, saat pulang dari rumah Wulan, saya juga mencium bau yang sama seperti yang tadi saya cium sebelum setan itu muncul."
"Aneh," gumam Pak Slamet pelan.
"Apanya yang aneh Met?" tanya Pak Sholeh yang telah kembali dari dapur dengan membawa segelas air putih.
"Aneh," gumam Pak Slamet pelan.
"Apanya yang aneh Met?" tanya Pak Sholeh yang telah kembali dari dapur dengan membawa segelas air putih.
"Eh, enggak Pak. Ini lho, aneh, kok tiba tiba Bu Ratih bisa pingsan begitu," jawab Pak Slamet gugup.
"Mungkin kamu kecapekan Tih. Nih, minum dulu, habis itu istirahat," Pak Sholeh memberikan gelas yang dibawanya kepada Bu Ratih.
"Mungkin kamu kecapekan Tih. Nih, minum dulu, habis itu istirahat," Pak Sholeh memberikan gelas yang dibawanya kepada Bu Ratih.
Perempuan itu segera menenggak isinya sampai tandas. Sedangkan Pak Slamet masih termenung di tempat duduknya. Memikirkan setan gosong yang telah berani meneror Bu Ratih.
Ini tidak bisa dibiarkan. Harus segera diselidiki. Bisa repot kalau sampai setan itu meneror warga yang lainnya. Aku harus segera bertindak, tekat Pak Slamet dalam hati.
Rasa penasaran yang berlebihan, terkadang membuat orang hilang ingatan.
Rasa penasaran yang berlebihan, terkadang membuat orang hilang ingatan.
Mungkin itu yang dirasakan oleh Pak Slamet. Malam itu, setelah berhasil menenangkan Bu Ratih yang sempat syok, laki laki itu pamit keluar. Katanya sih mau pulang karena hari memang sudah malam.
Namun, saat sampai di luar, laki laki itu justru melipir ke kebun samping rumah Pak Sholeh, tepatnya ke arah dimana terletak jendela kamar Bu Ratih. Ia mengendap endap diantara rimbunnya pepohonan, sambil matanya tak lepas memperhatikan situasi di sekelilingnya.
Setan atau bukan, Pak Slamet sudah bertekat untuk membongkar penampakan setan gosong yang sudah berani menganggu wanita pujaannya itu.
Dan sepertinya usaha Pak Slamet tak sia sia.
Dan sepertinya usaha Pak Slamet tak sia sia.
Meski ia tak menemukan petunjuk atau jejak setan gosong yang dicarinya, tapi ia melihat sekelebat bayangan yang menyelinap ke belakang rumah Pak Sholeh.
Jelas itu manusia, karena samar samar Pak Slamet mendengar suara langkah kakinya yang menginjak dedaunan kering.
Jelas itu manusia, karena samar samar Pak Slamet mendengar suara langkah kakinya yang menginjak dedaunan kering.
Tanpa membuang waktu laki laki itu kemudian mengikuti sosok itu secara diam diam.
Ini sangat mencurigakan, batin Pak Slamet sambil terus mengikuti sosok itu. Bukannya menuju ke jalanan desa yang terang, orang itu justru terus mengendap endap menyelinap dari kebun ke kebun,
Ini sangat mencurigakan, batin Pak Slamet sambil terus mengikuti sosok itu. Bukannya menuju ke jalanan desa yang terang, orang itu justru terus mengendap endap menyelinap dari kebun ke kebun,
milik warga yang gelap, sambil sesekali celingak celinguk memperhatikan situasi di sekelilingnya.
Sangat mencurigakan, gumam Pak Slamet dalam hati. Ia mulai menjaga jarak, agar tak sampai ketahuan kalau ia mengikuti orang itu.
Sangat mencurigakan, gumam Pak Slamet dalam hati. Ia mulai menjaga jarak, agar tak sampai ketahuan kalau ia mengikuti orang itu.
Sampai akhirnya, sosok yang diikutinya itu berhenti di salah satu teras rumah milik warga.
"Itu kan ..., rumah Pak Marto?" batin Pak Slamet sambil merunduk di balik semak semak. Lampu penerangan yang remang remang di teras rumah itu tak cukup membantu penglihatan Pak Slamet.
"Itu kan ..., rumah Pak Marto?" batin Pak Slamet sambil merunduk di balik semak semak. Lampu penerangan yang remang remang di teras rumah itu tak cukup membantu penglihatan Pak Slamet.
Hingga ia tak begitu jelas melihat wajah orang itu.
Sosok itu kembali mengedarkan pandangannya, seolah ingin memastikan bahwa tak ada orang yang melihatnya, sebelum akhirnya orang itu mengetuk pintu rumah Pak Marto pelan pelan.
Sosok itu kembali mengedarkan pandangannya, seolah ingin memastikan bahwa tak ada orang yang melihatnya, sebelum akhirnya orang itu mengetuk pintu rumah Pak Marto pelan pelan.
Ketukan yang unik, tidak seperti orang yang mengetuk pintu pada umumnya. Seperti sebuah kode yang hanya di mengerti oleh sang tamu dan tuan rumah.
Pelan pelan pintu terbuka. Pak Slamet semakin menajamkan pandangannya. Bias cahaya dari dalam rumah menerangi wajah tamu itu.
Pelan pelan pintu terbuka. Pak Slamet semakin menajamkan pandangannya. Bias cahaya dari dalam rumah menerangi wajah tamu itu.
Tak begitu terang memang, tapi cukup membantu pengelihatan Pak Slamet.
"Lho, itu kan ...," tak salah lagi. Orang yang sejak tadi ia ikuti itu adalah Ki Suryo, warga desa Ngantiyan yang dikenal sebagai dukun sakti itu.
"Lho, itu kan ...," tak salah lagi. Orang yang sejak tadi ia ikuti itu adalah Ki Suryo, warga desa Ngantiyan yang dikenal sebagai dukun sakti itu.
"Mau apa dia datang malam malam ke rumah Pak Marto? Dan kenapa sebelumnya tadi sempat mengendap endap di kebun Pak Sholeh?" rasa penasaran Pak Slamet tak terbendung lagi. Ia segera menyeliap ke samping rumah Pak Marto.
Kembali nasib baik berpihak pada Pak Slamet. Dinding rumah Pak Marto yang masih terbuat dari anyaman bambu itu membuatnya leluasa untuk mengintip ke dalam rumah, sekaligus mencuri dengar pembicaraan kedua orang mencurigakan itu.
Kedua orang itu berbicara dengan setengah berbisik, membuat Pak Slamet hanya bisa mendengar pembicaraan itu sepotong sepotong. Sepertinya Ki Suryo memberi sebuah tugas kepada Pak Marto, entah tugas apa, tak begitu jelas terdengar.
Si tuan rumah itu juga sepertinya sempat protes. Ia menyinggung soal Wulan, anaknya, tumbal, perjanjian, harta, dan entah apa lagi, tak begitu jelas di pendengaran Pak Slamet.
"Lakukan dengan hari hati Marto! Jangan sampai membuat orang lain curiga.
"Lakukan dengan hari hati Marto! Jangan sampai membuat orang lain curiga.
Aku memang sudah sedikit memberi peringatan halus kepada guru perempuan keponakan si Dul itu, tapi sepertinya kepala sekolah yang juga dekat dengan guru muda itu juga mulai ikut campur."
Deg! Terkejut Pak Slamet mendengar namanya disebut sebut.
Deg! Terkejut Pak Slamet mendengar namanya disebut sebut.
Dan kata kata Ki Suryo tadi, itu berarti teror setan gosong itu ada hubungannya dengan laki laki tua itu. Ini bukan hal yang bagus. Kata kata Ki Suryo tadi sedikit mengandung ancaman. Untuk Bu Ratih, dan juga untuk dirinya.
Aku harus tahu lebih banyak lagi, batin Pak Slamet sambil kembali menempelkan telinganya ke dinding anyaman bambu.
"Hei! Siapa disitu!" sebuah suara mengejutkan Pak Slamet, disusul dengan selarik cahaya senter yang menyorot ke arahnya.
"Hei! Siapa disitu!" sebuah suara mengejutkan Pak Slamet, disusul dengan selarik cahaya senter yang menyorot ke arahnya.
"Sial! Petugas ronda! Bisa gawat kalau aku sampai ketahuan!" Pak Slamet buru buru menyelinap ke semak semak untuk menghindari sorotan cahaya senter itu.
"Hei! Jangan lari! Maling ya!"
"Hei! Jangan lari! Maling ya!"
"Wedhus! Malah dikira maling!" umpat Pak Slamet sambil terus mengendap endap menjauh dari pekarangan rumah Pak Marto, melompati pagar dan berlari secepat yang ia bisa.
"Woi! Maling ...! Jangan lariii ...!Kejar ...! Kejar ...! Jangan sampai lolos!"
"Woi! Maling ...! Jangan lariii ...!Kejar ...! Kejar ...! Jangan sampai lolos!"
"Djanc*k!" umpat Pak Slamet sambil terus berlari dan mencari tempat persembunyian. Tanpa pikir panjang, Pak Slamet menerobos rimbunan kebun jagung milik salah seorang warga.
Tanaman jagung yang sudah mulai meninggi itu sangat rapat, cukup untuk menyembunyikan tubuh Pak Slamet.
Tanaman jagung yang sudah mulai meninggi itu sangat rapat, cukup untuk menyembunyikan tubuh Pak Slamet.
Tapi laki laki itu merasa belum sepenuhnya aman. Bisa saja para peronda itu ikut mengejarnya menerobos tanaman jagung itu.
Pak Slamet pun kembali mengendap endap diantara rimbunnya tanaman jagung, menuju ke arah utara.
Pak Slamet pun kembali mengendap endap diantara rimbunnya tanaman jagung, menuju ke arah utara.
Sementara suara peronda yang mengejarnya terdengar semakin mendekat.
"Kemana larinya tadi?"
"Aku yakin tadi ke arah sini!"
"Jangan jangan ngumpet di kebun jagung itu!"
"Ayo, kita coba cari disana!"
"Kemana larinya tadi?"
"Aku yakin tadi ke arah sini!"
"Jangan jangan ngumpet di kebun jagung itu!"
"Ayo, kita coba cari disana!"
"Sial! Betul kan dugaanku!" gerutu Pak Slamet sambil terus mengendap endap dan mempercepat langkahnya. Tak ads pilihan lain. Hanya ada satu tempat bersembunyi yang aman untuk menghindar dari para peronda itu. Kuburan!
Ya, tempat itu yang Pak Slamet tuju. Jadi begitu lolos dari rimbunan tanaman jagung itu, Pak Slamet kembali berlari ke arah kuburan desa yang jaraknya sudah tak jauh lagi. Sementara para pengejarnya masih terjebak diantara lebatnya tanaman jagung.
"Hups!" Pak Slamet melompati parit yang membatasi desa dengan area pemakaman, lalu segera menyelinap kedalam salah satu cungkup yang ada di kuburan itu.
"Hufth! Aman!" Pak Slamet menarik nafas lega. Ia tahu siapa siapa saja yang bertugas ronda malam itu.
"Hufth! Aman!" Pak Slamet menarik nafas lega. Ia tahu siapa siapa saja yang bertugas ronda malam itu.
Mereka orang orang penakut. Tak mungkin berani mengejarnya sampai ke pemakaman ini.
"Kemana ya larinya?" sayup sayup Pak Slamet masih bisa mendengar suara para peronda itu.
"Nggak tau. Di kebun jagung sudah kita cari tapi nggak ada."
"Apa jangan jangan ke kuburan ya?"
"Kemana ya larinya?" sayup sayup Pak Slamet masih bisa mendengar suara para peronda itu.
"Nggak tau. Di kebun jagung sudah kita cari tapi nggak ada."
"Apa jangan jangan ke kuburan ya?"
"Ah, ndak mungkin lah, mana berani ngumpet di kuburan malam malam begini."
"Atau jangan jangan larinya ke arah lain?"
"Ya sudah, ayo kita cari di tempat lain, nanti keburu jauh."
Hampir tertawa Pak Slamet mendengar percakapan para peronda itu.
"Atau jangan jangan larinya ke arah lain?"
"Ya sudah, ayo kita cari di tempat lain, nanti keburu jauh."
Hampir tertawa Pak Slamet mendengar percakapan para peronda itu.
Dasar orang orang penakut, ejek Pak Slamet dalam hati.
Suara para peronda semakin menjauh, dan akhirnya tak terdengar lagi. Sepertinya keadaan sudah aman. Pak Slamet bermaksud untuk bangkit dan kembali ke desa.
Suara para peronda semakin menjauh, dan akhirnya tak terdengar lagi. Sepertinya keadaan sudah aman. Pak Slamet bermaksud untuk bangkit dan kembali ke desa.
Namun baru saja ia hendak bangun dari duduknya, tiba tiba ada tangan yang menyentuh pundaknya.
"Eh, ini .!" Pak Slamet tertegun. Bulu kuduknya mulai merinding, seiring dengan terciumnya bau sangit bercampur dengan aroma busuk yang memualkan perut yang menusuk indera penciumannya
"Eh, ini .!" Pak Slamet tertegun. Bulu kuduknya mulai merinding, seiring dengan terciumnya bau sangit bercampur dengan aroma busuk yang memualkan perut yang menusuk indera penciumannya
"Bau sangit busuk, ini seperti ...," pelan pelan Pak Slamet menengok ke belakang. Benar saja, meski suasana gelap, tapi ia masih bisa menangkap sosok bayangan hitam gosong dengan wajah meringis ke arahnya.
"Set ..., tan ..., gos ..., song!" gagap suara Pak Slamet, sebelum akhirnya tubuh laki laki itu ambruk tak sadarkan diri.
Gema adzan shubuh membangukan Pak Slamet. Laki laki itu menggeliat, lalu membuka matanya. Eh, dimana ini? Kok gelap? Mana dingin banget lagi? Dan kenapa aku tidur di ubin begini?
Seribu satu pertanyaan memenuhi benak laki laki itu.
Seribu satu pertanyaan memenuhi benak laki laki itu.
Ia meraba raba, sambil mencoba mengingat ingat kenapa ia terbangun di tempat asing seperti ini.
Lho, ini kan ..., batu nisan?! Pak slamet tersadar, ingatannya sedikit demi sedikit mulai terkumpul.
Lho, ini kan ..., batu nisan?! Pak slamet tersadar, ingatannya sedikit demi sedikit mulai terkumpul.
Dari saat ia memergoki Ki Suryo, mengikutinya sampai ke rumah Pak Marto, lalu dikejar kejar para peronda malam, dan ..., Hiiiii!!! Pak Slamet bergidik saat teringat wajah gosong yang semalam dilihatnya.
"Asem!" sungut laki laki itu sambil bergegas melangkah meninggalkan area pemakaman. Ia sengaja memilih lewat jalan setapak di tepi desa, untuk menghindari bertemu dengan orang yang hendak berangkat ke sawah atau ke pasar.
Bisa heboh orang sekampung kalau sampai ada yang melihat ia tidur di kuburan seperti itu.
Sampai di rumah, laki laki itu segera mandi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Ia ingin cepat cepat bertemu dengan Bu Ratih.
Sampai di rumah, laki laki itu segera mandi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Ia ingin cepat cepat bertemu dengan Bu Ratih.
Selain ingin mengetahui keadaan Bu Ratih yang semalam juga kena teror dari setan gosong, ia juga ingin membicarakan soal kejadian yang ia alami semalam.
Sambil bersiul siul kecil Pak Slamet mematut diri di depan cermin. Lho, kok wajahku?
Sambil bersiul siul kecil Pak Slamet mematut diri di depan cermin. Lho, kok wajahku?
Ah, ini pasti gara gara semalam menerobos ladang jagung itu. Ada luka sayatan sayatan kecil di wajahnya. Mungkin karena tergores daun daun jagung yang diterobosnya semalam. Pantas saja tadi saat mandi sedikit terasa perih.
Ah, tak apalah. Hanya luka goresan kecil ini, nggak akan mengurangi aura ketampanannya. Justru akan menambah kesan jantan, dan itu bisa ia banggakan di depan Bu Ratih. Pak Slamet tersenyum simpul, membayangkan wanita pujaannya itu.
Namun saat sampai di sekolahan, Pak Slamet harus menelan kekecewaan. Ternyata hari ini Bu Ratih ijin tak masuk mengajar dulu. Lagi kurang enak badan katanya. Wah, pasti ini gara gara peristiwa semalam itu.
Mau tak mau Pak Slamet yang harus menggantikan Bu Ratih mengajar di kelasnya, karena guru guru yang lain juga sibuk mengajar di kelas mereka masing masing.
Tak apa, batin Pak Slamet. Menggantikan tugas orang yang ia sukai bukanlah hal yang merepotkan.
Tak apa, batin Pak Slamet. Menggantikan tugas orang yang ia sukai bukanlah hal yang merepotkan.
Soal niatnya untuk mendiskusikan pengalamannya semalam dengan Bu Ratih, bisa ditunda sampai siang nanti. Dan ini kesempatan emas baginya. Dengan alasan menjenguk Bu Ratih yang sedang tak enak badan, ia bisa datang ke rumah perempuan itu tanpa canggung canggung lagi.
Namun lagi lagi Pak Slamet harus kembali menelan kekecewaan, karena ternyata beberapa orang guru juga punya niat yang sama. Jadilah setelah bubaran sekolah mereka berombongan datang ke rumah Bu Ratih. Praktis, Pak Slamet tak punya kesempatan untuk bicara berdua dengan Bu Ratih.
Sementara para guru perempuan masuk menjenguk Bu Ratih ke dalam kamar, Pak Slamet justru dihadapkan pada wajah masam Pak Sholeh yang sepertinya sejak pagi belum mandi. Apes! Laki laki itu menggerutu dalam hati.
***
***
Sementara itu di pondoknya, Mas Joko kedatangan tamu. Pak Marto. Tak biasanya laki laki itu datang berkunjung ke podok itu. Bahkan dengan keluarga Mas Jokopun, hubungan Pak Marto tak begitu akrab. Hanya sebatas kenal saja sebagai sesama warga desa Kedhung Jati.
Hal ini membuat Mas Joko sedikit heran. Meski begitu, Mas Joko yang memang terkenal ramah dengan semua orang itu menyambut baik kedatangan Pak Marto.
"Wah, pantesan dari semenjak pagi burung prenjak di depan rumah itu terus terusan berkicau, mau ada tamu agung rupanya.."
"Wah, pantesan dari semenjak pagi burung prenjak di depan rumah itu terus terusan berkicau, mau ada tamu agung rupanya.."
"..Mari Pak, silahkan masuk. Kok tumben lho, main kesini. Ada perlu atau cuma sekedar berkunjung nih," ramah sambutan Mas Joko, mempersilahkan masuk tamunya itu.
"Ah, Mas Joko ini bisa saja. Kebetulan ini tadi lewat, kok tiba tiba pengen mampir. Dan ada sedikit perlu juga sebenarnya," agak segan juga Pak Marto mendapat sambutan sehangat itu.
"Mari, silahkan duduk. Maaf lho, tempatnya berantakan begini.."
"Mari, silahkan duduk. Maaf lho, tempatnya berantakan begini.."
"..Ada perlu apa nih, sampai Pak Marto bela belain datang kemari," ujar Mas Joko setelah tamunya itu duduk.
"Begini lho Mas, sebenarnya ..., aduh, gimana ya? Agak nggak enak juga saya ngomongnya. Saya ..., anu, cuma mau minta maaf, soal perlakuan saya terhadap Wulan.."
"Begini lho Mas, sebenarnya ..., aduh, gimana ya? Agak nggak enak juga saya ngomongnya. Saya ..., anu, cuma mau minta maaf, soal perlakuan saya terhadap Wulan.."
"..beberapa hari yang lalu di kali Salahan itu. Saya kok jadi merasa bersalah banget, memperlakukan anak kecil sampai seperti itu. Beruntung ada warga yang mencegah saya. Kalau tidak, entah apa yang akan saya lakukan terhadap Wulan waktu itu.."
"..Saat itu saya memang benar benar lagi emosi Mas, jadi ndak bisa mikir lagi."
"Oalah, soal itu to. Sudah, lupakan saja Pak. Saya mengerti kok perasaan bapak. Kehilangan anak satu satunya, pastinya bapak sangat terpukul.."
"Oalah, soal itu to. Sudah, lupakan saja Pak. Saya mengerti kok perasaan bapak. Kehilangan anak satu satunya, pastinya bapak sangat terpukul.."
"..Justru saya yang minta maaf Pak, kalau sebelumnya anak saya sempat berantem dan mengata ngatai anak bapak."
"Ya, namanya juga anak anak Mas, saya paham kok. Dan justru karena itu saya datang kemari. Selain untuk minta maaf, saya juga ingin membicarakan soal si Wulan, anak Mas Joko itu."
"Soal yang mana lagi ya Pak?"
"Soal yang mana lagi ya Pak?"
"Pasti Mas Joko juga sudah mendengar kan desas desus yang beredar di desa? Mereka mengait ngaitkan meninggalnya anak saya, dan juga meninggalnya keluarga Pak Darsa yang kemarin itu dengan Wulan. Apalagi belakangan ini muncul desas desus tentang kemunculan setan gosong.."
".. yang meneror warga. Banyak yang bilang, kalau setan gosong itu jelmaan dari keluarga Pak Darsa yang ingin menuntut balas kepada Wulan. Saya sendiri sih sebenarnya tak percaya dengan desas desus itu.."
"..Sangat kejam rasanya kalau menuduh anak seusia Wulan dengan tuduhan yang seperti itu. Tapi Mas Joko tau sendiri kan, sikap warga desa kita ini seperti apa. Saya kadang sampai tak habis pikir lho, kok bisa bisanya warga punya pemikiran seperti itu."
"Oh, soal itu to. Saya sebenarnya juga sudah mendengar tentang semua omongan warga itu Pak. Tapi biarkan saja lah. Toh semua itu cuma tuduhan yang ndak ada buktinya. Saya juga ndak merasa sakit hati kok."
"Saya tau Mas, sifat sampeyan memang seperti itu. Tapi apa sampeyan ndak kasihan sama si Wulan, anak sampeyan itu. Saya dengar Wulan sampai ndak mau sekolah gara gara mendengar desas desus itu."
"Ya mau gimana lagi Pak. Kalau saya tanggapi semua omongan warga itu, nantinya malah tambah rumit masalahnya. Jadi lebih baik saya pura pura tidak tau saja kan. Soal Wulan, dia baik baik saja kok.."
"..Meski dia sampai ndak mau sekolah, toh gurunya masih berbaik hati mau mengajarnya di rumah."
"Lha apa nantinya akan terus terusan begitu to Mas? Maaf lho ini, saya bukannya mau sok mengajari atau apa, tapi kalau terus terusan begini, nantinya bisa ndak baik buat ke depannya.
"Lha apa nantinya akan terus terusan begitu to Mas? Maaf lho ini, saya bukannya mau sok mengajari atau apa, tapi kalau terus terusan begini, nantinya bisa ndak baik buat ke depannya.
"..Mungkin di saat sekarang, sampeyan sama anak sampeyan itu ndak papa, tapi lama kelamaan anak sampeyan rak makin besar to, dia akan semakin ngerti dengan sikap warga yang kurang baik itu terhadapnya.."
"..Kalau boleh, ini saya cuma ngasih saran lho, anak sampeyan itu kan cuma satu satunya. Bocah ontang anting kalau istilah jawanya. Dalam adat desa ini, bocah ontang anting begitu kan harusnya diruwat to. Bisa sial seumur hidup kalau sampai ndak diruwat.."
".. Kata orang orang tua dulu begitu. Jadi apa sampeyan ndak ada niat buat meruwat anak sampeyan itu?"
"Niat sih ada Pak, tapi biayanya yang belum ada. Mengadakan acara ruwatan itu kan biayanya ndak sedikit, harus nanggap wayang segala, itupun dalangnya ndak bisa sembarangan.."
"Niat sih ada Pak, tapi biayanya yang belum ada. Mengadakan acara ruwatan itu kan biayanya ndak sedikit, harus nanggap wayang segala, itupun dalangnya ndak bisa sembarangan.."
"..Harus dalang sepuh yang sudah paham cara meruwat. Saya duit darimana kalau mau menggelar acara ruwatan begitu. Mungkin nanti Pak, kalau saya sudah punya biayanya baru bisa menggelar acara ruwatan untuk Wulan."
"Kebetulan kalau begitu Mas. Ini saya cuma mau membantu lho ya, itu juga kalau Mas Joko tidak keberatan. Sebagai tetangga sudah sepantasnya to untuk saling membantu, dan anggap saja ini sebagai wujud permintaan maaf saya kepada sampeyan, soal yang kemarin itu.."
"..Jadi begini, saya punya kenalan seorang dalang sepuh, dan kebetulan masih kerabat saya juga. Kalau Mas Joko mau, saya bisa menghubungi kerabat saya itu. Soal biaya ndak usah terlalu dipikirkan. Kalau saya yang meminta, kerabat saya itu ndak akan pernah mikirin masalah biaya.."
Ibaratnya, dibayar pakai daun pun dia mau kalau saya yang meminta. Dia itu bukan dalang sembarang dalang lho Mas, tapi sudah benar benar berpengalaman. Sedikit sedikit punya ilmu kebatinan juga. Bahkan sudah punya padepokan. Muridnya juga sudah banyak.."
".. Jadi Mas Joko ndak usah ragu lagi. Dijamin beres deh pokoknya."
"Waduh, bagaimana ya Pak? Saya sebenarnya ndak enak kalau sampai harus merepotkan orang begitu. Apalagi ...."
"Waduh, bagaimana ya Pak? Saya sebenarnya ndak enak kalau sampai harus merepotkan orang begitu. Apalagi ...."
"Ndak usah dipikirin Mas. Kan sudah saya bilang tadi, anggap saja ini sebagai tanda permintaan maaf saya kepada sampeyan. Bagaimana? Kalau sampeyan mau, nanti biar orangnya saya ajak kesini, biar lebih enak lagi ngobrolnya sama sampeyan."
"Emmm, gimana ya Pak? Biar saya pikir pikir dulu deh, nanti sekalian saya bicarakan dulu sama istri saya."
"Ya sudah kalau begitu. Tapi jangan lama lama mikirnya, mumpung kerabat saya ini lagi ada waktu senggang.."
"Ya sudah kalau begitu. Tapi jangan lama lama mikirnya, mumpung kerabat saya ini lagi ada waktu senggang.."
"..Biasanya dia ndak pernah sepi job lho, bahkan sering diundang ke luar pulau segala."
"Iya Pak, nanti biar saya hubungi Pak Marto lagi kalau sekiranya istri saya sudah setuju. Dan terima kasih banyak lho Pak sebelumnya."
"Iya Pak, nanti biar saya hubungi Pak Marto lagi kalau sekiranya istri saya sudah setuju. Dan terima kasih banyak lho Pak sebelumnya."
"Ya sudah kalau begitu, saya pamit dulu ya Mas, masih banyak kerjaan di rumah. Saya tunggu kabarnya dari Mas Joko. Ingat, jangan lama lama lho mikirnya, dan jangan bilang siapa siapa dulu soal ini. Tau sendiri kan, warga sini kayak gimana.."
"..Bisa heboh nanti kalau warga tau rencana kita ini."
Pak Martopun akhirnya pulang. Mas Joko mengantar sang tamu sampai di depan pintu. Ah, ternyata, masih ada warga yang baik dan peduli dengan keluargaku, batin Mas Joko sambil melepas kepulangan Pak Marto.
Pak Martopun akhirnya pulang. Mas Joko mengantar sang tamu sampai di depan pintu. Ah, ternyata, masih ada warga yang baik dan peduli dengan keluargaku, batin Mas Joko sambil melepas kepulangan Pak Marto.
Mas Joko duduk termenung dibawah teduhnya pohon mahoni di tengah ladangnya. Cangkul dan sabit yang sedianya ingin ia gunakan untuk membersihkan rerumputan di ladang itu, ia biarkan tergeletak begitu saja di hadapannya. Pikiran laki laki itu berkecamuk.
Matanya menerawang jauh, menatap mega mega yang berarak nun di kejauhan sana, seolah ingin mencari sebuah jawaban dari masalah yang sedang dihadapinya.
Angan laki laki itu mengembara jauh, menelusuri kisah kehidupannya yang kian hari kian terasa rumit.
Angan laki laki itu mengembara jauh, menelusuri kisah kehidupannya yang kian hari kian terasa rumit.
Semenjak kepindahannya dari kota ke desa itu, masalah demi masalah yang menimpanya seolah datang bertubi tubi tiada henti. Seolah kehadirannya memang tak diinginkan di desa ini.
Masih terbayang jelas di pelupuk matanya, bagaimana dulu perjuangannya saat pertama kali pindah ke desa ini. Sambutan yang kurang mengenakkan justru datang dari sanak saudaranya sendiri. Lalu saat kelahiran Wulan, nyaris saja ia kehilangan segala galanya.
Dan sekarang, anak semata wayangnya yang belum mengenal dosa itu juga ikut menanggung beban yang sangat berat.
Ia tak munafik. Anaknya memang sedikit bandel dan keras kepala. Tapi itu hanyalah kenakalan khas anak kecil.
Ia tak munafik. Anaknya memang sedikit bandel dan keras kepala. Tapi itu hanyalah kenakalan khas anak kecil.
Tuduhan tuduhan tanpa bukti yang jelas dari sebagian warga yang diarahkan kepada Wulan rasanya terlalu berlebihan. Apalagi setelah berita tentang kemunculan setan gosong yang sering meneror warga itu semakin santer, Wulan seolah dijadikan kambing hitam oleh warga.
Bocah yang bahkan belum bisa buang ingus sendiri itu dituding sebagai sumber dari semua masalah yang menimpa warga desa.
Sempat ia berpikir, bahwa keputusannya dulu untuk pindah ke desa ini adalah keputusan yang salah. Namun dimana letak kesalahannya?
Sempat ia berpikir, bahwa keputusannya dulu untuk pindah ke desa ini adalah keputusan yang salah. Namun dimana letak kesalahannya?
Desa ini adalah tanah kelahirannya. Dan ia datang juga dengan tujuan yang baik. Tak ada niat sama sekali untuk mengusik kehidupan warga desa yang lainnya. Apa karena masa lalu orang tuanya yang membuat warga jadi membencinya? Tapi apa salah dan dosa kedua orang tuanya?
Yang ia dengar justru dulu bapaknya adalah pahlawan desa yang sudah beberapa kali menyelamatkan desa ini dari berbagai macam marabahaya dan bencana.
Mas Joko tersenyum. Ia tersadar dari lamunannya, saat sayup sayup dari arah pondok terdengar celotehan Wulan yang sedang asyik bermain dengan Lintang, lalu disusul dengan omelan Romlah yang menyuruh Wulan untuk segera mandi, karena hari sudah semakin sore.
Ya, hari memang semakin sore, dan sebentar lagi malam akan menjelang. Waktu terus berjalan. Ia tak boleh membuang buang waktu hanya untuk menyesali nasib. Ia harus berusaha. Ia harus berikhtiar. Apapun caranya, masalah yang datang harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya.
Mas Joko bangkit dari duduknya, lalu membereskan semua peralatan berkebunnya dan melangkah pulang. Tekadnya sudah bulat. Tawaran dari Pak Marto beberapa hari yang lalu, tak ada salahnya untuk dicoba.
Siapa tahu setelah Wulan diruwat nanti, nasib keluarganya akan sedikit bisa berubah. Ya, malam nanti aku harus menemui Pak Marto, batin laki laki itu.
***
***
Malam semakin larut. Suasana desa telah sepi. Hanya suara nyanyian jengkerik dan belalang yang menemani kesibukan Pak Slamet di malam itu. Juga secangkir kopi yang ia seduh semenjak sore tadi, namun belum sempat ia sentuh. Tangan asyik mencoret coret selembar kertas di atas meja.
Sesekali ia tertegun, berpikir sebentar, lalu kembali membuat coretan coretan di kertas yang baru.
"Wulan. Tumbal. Doni. Perjanjian. Tugas. Imbalan." mulut kepala sekolah itu menggumam tak jelas.
"Wulan. Tumbal. Doni. Perjanjian. Tugas. Imbalan." mulut kepala sekolah itu menggumam tak jelas.
Menggumamkan kata kata yang ia dapat dari hasil menguping pembicaraan Pak Marto dan Ki Suryo beberapa malam yang lalu.
Sudah beberapa hari Pak Slamet mencoba merangkai kata kata itu agar menjadi sebuah kalimat yang bisa memberinya sedikit petunjuk.
Sudah beberapa hari Pak Slamet mencoba merangkai kata kata itu agar menjadi sebuah kalimat yang bisa memberinya sedikit petunjuk.
Namun sampai detik ini belum juga membuahkan hasil. Ia memang menaruh kecurigaan yang besar terhadap kedua orang itu.
Ki Suryo yang mengendap endap di pekarangan rumah Pak Sholeh, lalu datang secara diam diam ke rumah Pak Marto dan berbicara dengan berbisik bisik di tengah malam buta, benar benar sangat mencurigakan.
Belum lagi ia juga sempat mendengar kedua laki laki itu menyebut nyebut nama Bu Ratih dan juga namanya.
Ah, Bu Ratih, kira kira sedang apa ya dia sekarang? Tiba tiba bayangan perempuan cantik itu melintas di pikiran Pak Slamet. Jam segini, pasti dia telah tertidur lelap.
Ah, Bu Ratih, kira kira sedang apa ya dia sekarang? Tiba tiba bayangan perempuan cantik itu melintas di pikiran Pak Slamet. Jam segini, pasti dia telah tertidur lelap.
Seperti apa ya perempuan cantik kalau sedang tidur? Pasti wajahnya akan terlihat semakin cantik. Andai saja ia bisa melihat Bu Ratih saat sedang tidur, pasti ia bisa puas menikmati wajah cantiknya, tak harus dengan mencuri curi pandang seperti yang selama ini ia lakukan.
"Ah, sial! Kenapa aku malah memikirkan Bu Ratih sih?" desah Pak Slamet sambil meremas rambut di kepalanya.
"Konsentrasi! Konsentrasi! Aku harus bisa memecahkan teka teki ini," gumam Pak Slamet lagi sambil meraih ballpoint dan kembali mencoret coret selembar kertas di hadapannya.
"Konsentrasi! Konsentrasi! Aku harus bisa memecahkan teka teki ini," gumam Pak Slamet lagi sambil meraih ballpoint dan kembali mencoret coret selembar kertas di hadapannya.
Mencoba merangkai kata kata yang didapatnya dari hasil menguping pembicaraan Ki Suryo dan Pak Marto tempo hari.
"Lho? Kok?! Asem tenan ki!" Pak Slamet melempar ballpointnya ke atas meja,
"Lho? Kok?! Asem tenan ki!" Pak Slamet melempar ballpointnya ke atas meja,
saat menyadari kalau bukan untaian kalimat yang berhasil ia torehkan di atas kertas itu, tapi justru sketsa wajah Bu Ratih yang sedang tersenyum manis.
"Tapi cantik juga ia kalau sedang tersenyum begini," Pak Slamet tersenyum.
"Tapi cantik juga ia kalau sedang tersenyum begini," Pak Slamet tersenyum.
Matanya tak lepas menatap sketsa wajah yang baru saja ia buat, sambil tangannya meraba raba mencari gagang cangkir kopi yang tadi ia letakkan si sudut meja.
"Klotak!"
"Klotak!"
"Waduh! Malah tumpah!" gerutunya saat tanpa sengaja tangannya justru menyenggol cangkir kopi itu hingga terguling diatas meja. Isi dari cangkir itupun tumpah dan dengan cepat meluber di permukaan meja, membasahi kertas bergambar sketsa wajah Bu Ratih yang baru saja ia buat.
"Wah, apes tenan ki," laki laki itu segera menyambar beberapa lembar kertas tissue dan membersihkan tumpahan kopi di atas meja kerjanya.
Kertas bergambar sketsa wajah Bu Ratih itu ia angkat dan ia kibas kibaskan, berharap gambar yang ia buat secara tak sengaja itu tak sampai rusak oleh tumpahan kopi
"Hmm, nasib nasib," kembali ia menggerutu sambil bangkit dari duduknya dan melangkah ke dapur. Ia memang tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya itu. Jadi apa apa juga harus ia kerjakan sendiri. Termasuk untuk sekedar menyeduh kopi.
"Ah, andai aku punya istri, tentu aku tak harus menyeduh kopi sendiri malam malam begini," batin Pak Slamet sambil menuangkan beberapa sendok kopi dan gula kedalam cangkir, lalu menyeduhnya dengan air panas dari dalam termos.
"Ummm, harumnyaaa ...," laki laki itu mengirup aroma wangi kopi yang baru saja diseduhnya, sambil kembali melangkah ke ruang depan. Namun baru saja ia berbalik, sebuah suara ketukan dari arah pintu dapur yang tembus ke sumur di belakang rumah mengagetkannya.
Cangkir yang ia bawa nyaris terjatuh dari genggamannya.
"Brakkk ...!!! Brakkk ...!!! Brakkk ...!!!" Bukan! Itu bukan suara ketukan, tapi gebrakan yang sangat keras. Pak Slamet tertegun sejenak. Ia merasakan firasat yang tak enak.
"Brakkk ...!!! Brakkk ...!!! Brakkk ...!!!" Bukan! Itu bukan suara ketukan, tapi gebrakan yang sangat keras. Pak Slamet tertegun sejenak. Ia merasakan firasat yang tak enak.
Siapa yang menggedor gedor pintu rumah orang di tengah malam buta begini? Pasti orang yang punya niat tak baik. Kalau berniat baik, tak mungkin menggedor gedor pintu belakang rumah orang.
"Siapa?!" sentak Pak Slamet sambil pelan pelan meletakkan cangkir kopinya.
"Siapa?!" sentak Pak Slamet sambil pelan pelan meletakkan cangkir kopinya.
Ia lalu menyambar gagang sapu yang tersandar di dinding dapur.
"Siapa he?!" sentaknya lagi. Namun tak ada jawaban.
"Siapa he?!" sentaknya lagi. Namun tak ada jawaban.
Pelan pelan sebelah tangan Pak Slamet membuka grendel pintu, sedang tangan satunya lagi mengangkat tinggi tinggi gagang sapu yang dibawanya, bersiap memukul siapapun yang telah berani kurang ajar kepadanya.
"Whussss ....!!!" sekali sentak pintu itupun terbuka. Dan Pak Slametpun terkesima. Ia berdiri mematung dengan tubuh kaku di depan pintu. Gagang sapu yang dipegangnya masih teracung ke atas tanpa sempat ia ayunkan kearah sosok hitam gosong yang berdiri di hadapannya.
"Wedhus!!!" sadar bahwa yang mengganggunya bukan manusia, laki laki itu secepat kilat membanting pintu dan menguncinya kembali, lalu lari terbirit birit masuk ke dalam kamar, melompat ke atas tempat tidur,
dan meringkuk di bawah selimut dengan tubuh gemetar, tanpa ingat lagi dengan secangkir kopi yang baru saja ia seduh.
***
"Wulan! Tunggu!" Bu Ratih berusaha mengejar Wulan yang sedang berlari lari kecil mengikuti langkah seorang nenek tua bungkuk memasuki sebuah hutan.
***
"Wulan! Tunggu!" Bu Ratih berusaha mengejar Wulan yang sedang berlari lari kecil mengikuti langkah seorang nenek tua bungkuk memasuki sebuah hutan.
"Mau kemana kamu?" seru Bu Ratih begitu sudah dekat dengan Wulan.
"Mau ikut nenek Bu," Wulan berhenti dan menoleh sejenak, lalu kembali berjalan dengan gayanya yang sangat khas, berjingkat jingkat, setengah berlari setengah melompat lompat.
"Mau ikut nenek Bu," Wulan berhenti dan menoleh sejenak, lalu kembali berjalan dengan gayanya yang sangat khas, berjingkat jingkat, setengah berlari setengah melompat lompat.
"Tunggu dulu Wulan, dengarkan dulu kata kata ibu. Jangan ikut nenek itu! Dia orang jahat. Ayo kembali ke desa bersama ibu," tak mau menyerah, Bu Ratih kembali mengejar Wulan.
"Orang orang desa itu yang jahat Bu. Mereka membenci Wulan.
"Orang orang desa itu yang jahat Bu. Mereka membenci Wulan.
Nenek itu baik sama Wulan, dia nggak benci sama Wulan. Jadi mendingan Wulan ikut nenek itu saja." Wulan berkata tanpa menoleh, bahkan tanpa menghentikan langkahnya.
"Jangan percaya sama dia Wulan! Dia itu jahat! Dia bohong sama Wulan. Percaya sama ibu. Ayo kembali ke desa."
"Jangan percaya sama dia Wulan! Dia itu jahat! Dia bohong sama Wulan. Percaya sama ibu. Ayo kembali ke desa."
"Bu Ratih yang bohong! Nenek itu tidak jahat. Warga desa itu yang jahat! Kalau Bu Ratih bilang nenek itu jahat, berarti Bu Ratih juga jahat karena sudah membohongi Wulan!" kali ini Wulan berkata dengan beteriak.
"Wulan, dengarkan ibu dulu, ibu sayang sama Wulan, percaya sama ibu. Nenek itu ...
"Jangan ikut campur kau anak ingusan!"
Langkah Bu Ratih tertahan. Bahkan ia terjajar beberapa langkah ke belakang, saat tiba tiba si nenek bungkuk itu telah menghadang tepat di hadapannya.
"Jangan ikut campur kau anak ingusan!"
Langkah Bu Ratih tertahan. Bahkan ia terjajar beberapa langkah ke belakang, saat tiba tiba si nenek bungkuk itu telah menghadang tepat di hadapannya.
"Kau yang jangan ikut campur dengan urusan manusia Nek. Mau kau bawa kemana Wulan?" meski sedikit takut melihat sosok si nenek yang begitu menyeramkan, namun Bu Ratih mencoba memberanikan diri untuk bertanya.
"Bukan urusanmu!" ketus jawaban si nenek.
"Bukan urusanmu!" ketus jawaban si nenek.
"Ini menjadi urusanku Nek, karena dia adalah muridku."
"Anak bodoh! Sudah kubilang jangan ikut campur!"
"Kembalikan anak itu padaku Nek."
"Tidak akan!"
"Kalau begitu akan kurebut dia dari tanganmu!"
"Hihihihi ...! Kau anak kemarin sore mau menantangku hah?!"
"Anak bodoh! Sudah kubilang jangan ikut campur!"
"Kembalikan anak itu padaku Nek."
"Tidak akan!"
"Kalau begitu akan kurebut dia dari tanganmu!"
"Hihihihi ...! Kau anak kemarin sore mau menantangku hah?!"
"Demi anak itu, apapun akan kulakukan!"
"Kalau begitu, bersiaplah untuk mati!"
"Herrrrggghhh ...!" Bu Ratih tercekat saat tiba tiba, dengan sangat cepat kedua tangan si nenek yang berkuku tajam itu telah mencengkeram lehernya dengan sangat kuat.
"Kalau begitu, bersiaplah untuk mati!"
"Herrrrggghhh ...!" Bu Ratih tercekat saat tiba tiba, dengan sangat cepat kedua tangan si nenek yang berkuku tajam itu telah mencengkeram lehernya dengan sangat kuat.
"Heeegghhhh ...!!!" Bu Ratih meronta ronta. Kedua tangannya mencoba melepaskan cengkeraman tangan si nenek di lehernya. Namun cengkeraman itu justru semakin kuat, membuat Bu Ratih semakin tak bisa bernafas. Tubuhnya mengejang.
Kedua matanya terbeliak lebar, seolah hendak terlepas dari tempatnya. Sempat diliriknya Wulan yang justru tersenyum melihat ke arahnya yang sedang meregang nyawa.
"Matilah kau anak ingusan!!!"
"Arrrrrrggggghhhhhh ....!!!"
"Gubraaaakkk!!!"
"Matilah kau anak ingusan!!!"
"Arrrrrrggggghhhhhh ....!!!"
"Gubraaaakkk!!!"
"Awwwww ...!!!" Bu Ratih merintih lirih sambil memegangi lehernya yang terasa sangat perih. Ia melihat ke sekeliling.
"Lho, ini kan ..., Ah, ternyata cuma mimpi," desah Bu Ratih lega, saat menyadari dirinya masih terbaring di atas ranjang.
"Lho, ini kan ..., Ah, ternyata cuma mimpi," desah Bu Ratih lega, saat menyadari dirinya masih terbaring di atas ranjang.
Malam hari di rumah Pak Marto. Tiga orang laki laki nampak serius berbincang dengan nada setengah berbisik. Nyata kalau mereka sedang membicarakan masalah yang sangat serius, atau merencanakan sesuatu yang sangat rahasia.
Ketiga orang itu adalah Pak Marto sendiri selaku tuan rumah, Ki Suryo, dan seorang pemuda bertubuh kerempeng yang tak lain adalah keponakan Pak Marto yang tinggal di kota.
"Bagaimana, kalian sudah siap?" samar samar terdengar suara Ki Suryo.
"Bagaimana, kalian sudah siap?" samar samar terdengar suara Ki Suryo.
"Siap Ki," sahut Pak Marto dan si pemuda kerempeng itu hampir serempak.
"Bagus! Laksanakan rencana kita sebaik mungkin. Dan usahakan jangan sampai gagal. Sebab, kalau sampai rencana kita gagal atau tak tepat waktu,
"Bagus! Laksanakan rencana kita sebaik mungkin. Dan usahakan jangan sampai gagal. Sebab, kalau sampai rencana kita gagal atau tak tepat waktu,
itu berarti kita harus menunggu sampai bulan purnama bulan depan lagi untuk mengulangnya. Dan aku tak mau menunggu selama itu. Aku sudah gerah terus terusan didesak oleh perempuan siluman itu."
"Kenapa kita harus bersusah payah melakukan sandiwara ini Ki?
"Kenapa kita harus bersusah payah melakukan sandiwara ini Ki?
Bukankah kalau tujuannya hanya menculik seorang anak perempuan, lebih mudah kalau kita menyergapnya secara diam diam dan membawanya lari? Saya sanggup kalau hanya sekedar menculik anak tanpa ketahuan oleh warga." tanya si pemuda kerempeng.
"Hmmm, sepertinya keponakanmu ini belum tau banyak ya soal anak itu. Coba kau jelaskan kepadanya, Marto!" dengus Ki Suryo.
"Andai saja bisa semudah itu Jo, aku tak akan jauh jauh menjemputmu ke kota. Anak ini bukan anak sembarangan. Kalau dilakukan seperti yang kau rencanakan itu, aku jamin, bukan kamu yang berhasil menculik anak itu, tapi justru anak itu yang akan menculik nyawamu!" jelas Pak Marto.
"Jangan meremehkanku Lik. Apa susahnya menculik seorang anak kecil, apalagi anak perempuan. Tanganku ini ....!"
"Sudah! Tak perlu kau jelaskan aku juga sudah tau! Bajing*n sepertimu sudah pasti sering menyakiti orang to dengan tangan kotormu itu?
"Sudah! Tak perlu kau jelaskan aku juga sudah tau! Bajing*n sepertimu sudah pasti sering menyakiti orang to dengan tangan kotormu itu?
Tapi ini ceritanya sedikit berbeda. Dan kau cukup mengikuti rencana yang sudah kami buat. Tugasmu hanya meyakinkan kedua orang tua itu, agar mereka mengijinkan kita membawa anaknya, seperti yang sudah kujelaskan beberapa hari yang lalu.
Kau pura pura jadi dalang sepuh yang sanggup meruwat anak itu, dan karena anak itu adalah anak yang istimewa, maka sebelum meruwatnya kau harus terlebih dahulu membersihkan anak itu dari pengaruh jahat yang bersemayam dalam tubuhnya. Dan itu hanya bisa dilakukan di padepokanmu.
Jadi mau nggak mau kita harus membawa anak itu ke padepokanmu. Anak itu hanya patuh kepada kedua orang tuanya, jadi kalau bukan orang tuanya yang menyuruh dia untuk ikut kita, mustahil anak itu bisa kita bawa. Kamu paham to?
Secara tidak langsung, keberhasilan rencana kita ini berada di tanganmu. Jadi besok beraktinglah sebaik mungkin," kembali Pak Marto menjelaskan.
"Sebentar Lik, tadi Lik Marto bilang kalau anak itu bukan anak sembarangan. Bagaimana kalau dia ternyata sudah mengetahui rencana kita?" tanya si pemuda kerempeng lagi.
"Itu urusanku," Ki Suryo yang kini menjawab.
"Itu urusanku," Ki Suryo yang kini menjawab.
"Rencana ini sudah ku pertimbangkan masak masak, termasuk segala kemungkinan dan resiko yang akan timbul. Jadi kalian tak perlu khawatir. Aku juga akan memberi sedikit bekal padamu."
Ki Suryo mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah keris kecil atau yang biasa disebut cundrik. Laki laki tua bertubuh kurus itu komat kamit sebentar sambil memejamkan matanya, lalu mengeluarkan cundrik itu dari rangkanya.
"Sini, keluarkan lidahmu," seru Ki Suryo kepada si pemuda bertubuh kerempeng.
"Eh, mau diapain Ki?!" sedikit pucat wajah pemuda kerempeng itu saat melihat Ki Suryo menghunus cundrik dan memintanya untuk mengeluarkan lidahnya.
"Eh, mau diapain Ki?!" sedikit pucat wajah pemuda kerempeng itu saat melihat Ki Suryo menghunus cundrik dan memintanya untuk mengeluarkan lidahnya.
"Sudah! Jangan banyak tanya! Keluarkan saja lidahmu!" sentak Ki Suryo.
Meski sedikit ragu, akhirnya si pemuda kerempeng itupun menjulurkan lidahnya keluar.
"Diam! Jangan bergerak sedikitpun!" Ki Suryo memegang kepala si pemuda kerempeng itu,
Meski sedikit ragu, akhirnya si pemuda kerempeng itupun menjulurkan lidahnya keluar.
"Diam! Jangan bergerak sedikitpun!" Ki Suryo memegang kepala si pemuda kerempeng itu,
lalu pelan pelan mengerik lidah si pemuda yang terjulur keluar dengan cundrik yang dibawanya, sambil mulutnya terus berkomat kamit mengucapkan kata kata yang tak begitu jelas.
"Sudah, dengan begini, si Joko itu akan lebih mudah terpengaruh dengan kata kata yang kau ucapkan,"
"Sudah, dengan begini, si Joko itu akan lebih mudah terpengaruh dengan kata kata yang kau ucapkan,"
Ki Suryo kembali menyarungkan cundriknya, lalu menyelipkannya di balik baju lusuhnya.
"Dan ingat," Ki Suryo menyambung ucapannya, setelah terlebih dahulu menyalakan rokoknya.
"Dan ingat," Ki Suryo menyambung ucapannya, setelah terlebih dahulu menyalakan rokoknya.
"Kalian harus berhati hati dengan anak itu. Sebisa mungkin usahakan agar kalian jangan sampai menatap matanya, kalian paham?"
"Paham Ki," hampir serempak Pak Marto dan si pemuda keeempeng menjawab.
"Paham Ki," hampir serempak Pak Marto dan si pemuda keeempeng menjawab.
"Bagaimana dengan imbalan yang dijanjikan oleh perempuan siluman itu Ki? Saya sudah terlanjur ...."
"Kamu ini, kerja saja belum kok sudah memikirkan soal imbalan," sungut Ki Suryo memotong ucapan Pak Marto.
"Bukan begitu Ki, tapi ...."
"Kamu tak percaya padaku?!"
"Kamu ini, kerja saja belum kok sudah memikirkan soal imbalan," sungut Ki Suryo memotong ucapan Pak Marto.
"Bukan begitu Ki, tapi ...."
"Kamu tak percaya padaku?!"
"Eh, enggak Ki. Bukannya tak percaya, tapi ...."
"Sudahlah! Percaya padaku. Setelah tugasmu ini selesai, jangankan harta, kau ingin membeli separuh isi jagad ini juga nanti bakalan kesampaian. Aku yang menjamin.
"Sudahlah! Percaya padaku. Setelah tugasmu ini selesai, jangankan harta, kau ingin membeli separuh isi jagad ini juga nanti bakalan kesampaian. Aku yang menjamin.
Soal anak, setelah kau kaya nanti, apa yang tidak bisa kau miliki? Kau bisa kimpoi lagi kan, dan bikin anak sebanyak yang kau mau!"
"Baik Ki, saya mengerti!" menunduk Pak Marto, saat teringat sang anak yang telah tewas mengenaskan tempo hari.
"Baik Ki, saya mengerti!" menunduk Pak Marto, saat teringat sang anak yang telah tewas mengenaskan tempo hari.
"Ya sudah, aku mau pulang. Masih banyak hal yang harus aku persiapkan. Ingat, besok jangan sampai gagal. Aku tunggu di tempat yang telah kita sepakati," Ki Suryo bangkit dan meninggalkan kedua orang paman dan keponakan itu.
***
***
Keesokan paginya, rencana yang sudah disusun rapi itupun dilaksanakan. Berdua dengan sang keponakan, Pak Marto pagi pagi sekali sudah datang ke pondok Mas Joko.
Dan seperti yang telah dikatakan oleh Ki Suryo semalam, dengan sangat mudahnya mereka bisa mempengaruhi Mas Joko dan Mbak Romlah.
Mungki karena efek dari lidah si pemuda kerempeng (yang pagi itu menyamar menjadi seorang dhalang sepuh, lengkap dengan kumis dan jenggot palsunya),
Mungki karena efek dari lidah si pemuda kerempeng (yang pagi itu menyamar menjadi seorang dhalang sepuh, lengkap dengan kumis dan jenggot palsunya),
yang telah dikerik dengan cundrik oleh Ki Suryo, Mas Joko dan Mbak Romlah percaya begitu saja dengan semua yang diucapkan oleh si pemuda kerempeng.
"Jadi hanya untuk semalam ini saja, anak sampeyan akan saya bersihkan di padepokan saya, sebelum acara ruwatan nanti digelar.
"Jadi hanya untuk semalam ini saja, anak sampeyan akan saya bersihkan di padepokan saya, sebelum acara ruwatan nanti digelar.
Besok pagi juga sudah saya antar pulang kembali kesini. Ini semua juga demi kebaikan sampeyan sekeluarga, terutama anak sampeyan itu. Sampeyan ndak perlu ikut, cukup bantu dengan doa saja dari rumah." kata si pemuda kerempeng sambil mengelus elus jenggot palsunya.
"Iya Mbah, saya manut saja gimana baiknya. Yang penting anak saya bisa segera diruwat, dan ndak terus terusan dimusuhi sama warga," ujar Mas Joko.
Jadilah, pagi itu Wulan dibawa oleh Pak Marto dan keponakannya pergi dengan sebuah mobil milik si pemuda kerempeng.
Jadilah, pagi itu Wulan dibawa oleh Pak Marto dan keponakannya pergi dengan sebuah mobil milik si pemuda kerempeng.
Entah mau dibawa kemana, gadis kecil itu tak mengetahuinya. Dan tak seperti biasanya, gadis itu manut manut saja saat sang bapak menyuruhnya untuk ikut dengan Pak Marto. Tak ada kata penolakan sama sekali.
Namun ada hal kecil yang lepas dari pengawasan Pak Marto. Begitu masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku belakang, gadis itu tersenyum samar. Kedua mata beningnya tak lepas menatap kedua orang yang duduk di bangku depan mobil itu, dengan tatapan yang penuh misteri.
Sementara agak jauh dari mobil yang mulai berjalan pelan itu, Lintang yang hendak berangkat ke sekolah dan melihat Wulan pergi dengan Pak Marto, merasakan firasat yang tak enak.
Diam diam anak itu kembali ke rumah, mengambil sepedanya, dan tanpa sempat berpamitan lagi dengan sang emak yang masih sibuk di dapur, Lintang mengikuti mobil itu dari jarak yang agak jauh. Ia harus tahu, mau dibawa kemana si Wulan oleh kedua laki laki itu.
Lintang menghentikan sepedanya si sudut perempatan di depan pasar kota kecamatan. Nafas anak itu terlihat memburu, setelah mengayuh sepeda sejauh hampir empat kilometer. Baju seragamnya sudah basah oleh keringat yang membanjir dari sekujur tubuhnya.
Sementara mobil yang dikejarnya sudah menghilang dari pandangan.
Lintang menghela nafas. Anak itu sedikit bingung untuk menentukan arah. Kemana kira kira mobil yang membawa Wulan itu berbelok di perempatan ini? Ah, iya. Kenapa aku tak bertanya kepada orang saja?
Lintang menghela nafas. Anak itu sedikit bingung untuk menentukan arah. Kemana kira kira mobil yang membawa Wulan itu berbelok di perempatan ini? Ah, iya. Kenapa aku tak bertanya kepada orang saja?
Anak itu mengayuh sepedanya, mendekati pangkalan ojek yang berada tak jauh dari perempatan itu. Ditanyakannya soal mobil yang membawa Wulan itu.
"Mobil apa Le? Banyak mobil yang lewat di sini," ujar salah seorang tukang ojek itu.
"Mobil apa Le? Banyak mobil yang lewat di sini," ujar salah seorang tukang ojek itu.
"Mobil yang bentuknya seperti itu Pak," Lintang menunjuk sebuah mobil jeep warna merah yang terparkir di depan pasar. "Tapi warnanya hitam Pak. Diatasnya banyak lampu lampunya."
"Wah, sepertinya aku ndak lihat Le," jawab tukang ojek itu sambil melihat ke arah teman temannya.
"Wah, sepertinya aku ndak lihat Le," jawab tukang ojek itu sambil melihat ke arah teman temannya.
Tapi semua tukang ojek yang ada di situ hanya menggeleng, tanda tak melihat mobil yang disebutkan oleh Lintang.
Lintang meninggalkan pangkalan ojek itu dengan membawa rasa kecewa. Tak ada petunjuk yang ia dapat dari para tukang ojek itu.
Lintang meninggalkan pangkalan ojek itu dengan membawa rasa kecewa. Tak ada petunjuk yang ia dapat dari para tukang ojek itu.
Lintang sadar, jalanan depan pasar ini memang sangat ramai. Tak mungkin juga para tukang ojek itu memperhatikan mobil yang lewat satu persatu.
Sejenak anak itu terdiam di atas sadel sepedanya. Matahari sudah semakin tinggi. Panasnya mulai terasa menyengat kulit.
Sejenak anak itu terdiam di atas sadel sepedanya. Matahari sudah semakin tinggi. Panasnya mulai terasa menyengat kulit.
Aku harus berpikir, kira kira ke arah mana mobil itu berbelok, kata Lintang dalam hati. Anak itu memejamkan matanya, sambil membayangkan, seandainya ia yang menyetir mobil itu, kira kira kemana ia akan membelokkannya?
Belok kiri! Entah itu bisikan atau suara hati Lintang. Tapi anak itu segera memutuskan untuk berbelok ke arah kiri, menyusuri jalan yang lebih sempit daripada jalan yang ada di depan pasar. Jalanan yang membujur ke arah selatan.
Ia mengayuh sepedanya secepat yang ia bisa, sambil matanya terus menatap ke depan, berharap bisa menemukan mobil yang dicarinya.
Lintang sudah hafal jalan yang ia lalui itu. Melewati dua desa sebelum akhirnya bercabang menjadi sebuah pertigaan.
Lintang sudah hafal jalan yang ia lalui itu. Melewati dua desa sebelum akhirnya bercabang menjadi sebuah pertigaan.
Belok kiri berarti akan tembus ke desanya, desa Kedhungsono. Tak mungkin mobil itu mengambil arah ke kiri. Maka Lintangpun mengambil jalan yang lurus ke arah selatan.
Di kiri kanan jalan, rumah rumah penduduk sudah semakin jarang, berganti dengan area persawahan dan ladang milik warga. Dan di depan sana, lebatnya hutan Tawengan sudah mulai terlihat. Hutan lebat yang kata orang sangat angker, dan jarang dijamah oleh manusia.
Sampai di tepi hutan, Lintang menghentikan sepedanya. Jalan beraspal sudah berganti dengan jalan tanah yang ditumbuhi rerumputan setinggi mata kaki. Lintang tersenyum, sambil menyeka keringat yang membasahi keningnya.
Ada jejak ban mobil yang mengarah ke hutan diantara rerumputan yang tumbuh di jalan tanah itu. Ini pasti jejak mobil yang membawa Wulan.
Anak itu kembali mengayuh sepedanya, memasuki lebatnya hutan Tawengan yang jarang di jamah orang.
Anak itu kembali mengayuh sepedanya, memasuki lebatnya hutan Tawengan yang jarang di jamah orang.
Mengikuti jejak ban mobil yang semakin lama semakin nampak jelas menggilas rerumputan. Tanpa memikirkan bahaya yang mungkin bisa mengancamnya.
***
***
Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Mungkin hal itu yang dirasakan oleh Pak Slamet saat ini. Menunggu jam istirahat, agar bisa secepatnya bertemu dengan Bu Ratih.
Kemarin, rencananya untuk berdiskusi dengan guru muda itu gagal total, gara gara guru guru yang lain ikut datang menjenguk Bu Ratih. Pun setelah para guru itu pulang, Pak Slametpun menjadi enggan untuk mengganggu waktu istirahat sang guru muda itu,
mengingat kondisinya yang masih syok dan butuh istirahat.
Dan hari ini Bu Ratih sudah mulai mengajar kembali. Ini waktu yang tepat untuk bicara dengannya. Segala uneg uneg yang semenjak kemarin hanya ia simpan sendiri di dalam benaknya, harus segera ia keluarkan.
Dan hari ini Bu Ratih sudah mulai mengajar kembali. Ini waktu yang tepat untuk bicara dengannya. Segala uneg uneg yang semenjak kemarin hanya ia simpan sendiri di dalam benaknya, harus segera ia keluarkan.
Siapa tau guru muda yang terkenal cerdas dan memiliki naluri tajam itu bisa sedikit membantu memecahkan masalah yang sedang dipikirkannya.
"Tengg ...!!! Tengg ...!!! Tenggg ...!!!" lonceng tanda istirahat berdentang, menyadarkan Pak Slamet dari lamunannya.
"Tengg ...!!! Tengg ...!!! Tenggg ...!!!" lonceng tanda istirahat berdentang, menyadarkan Pak Slamet dari lamunannya.
Segera laki laki itu memperbaiki posisi duduknya. Menunggu Bu Ratih yang sebentar lagi akan memasuki ruang kerjanya. Tadi ia memang sudah berpesan kepada penjaga sekolah, agar menyampaikan pesannya pada Bu Ratih.
Benar saja, tak lama terdengar suara pintu diketuk, disusul oleh suara merdu Bu Ratih yang mengucap salam.
"Masuk Bu," Pak Slamet mempersilahkan. Guru muda itupun segera memasuki ruangan kepala sekolah itu dengan langkah pelan.
"Masuk Bu," Pak Slamet mempersilahkan. Guru muda itupun segera memasuki ruangan kepala sekolah itu dengan langkah pelan.
"Silahkan duduk Bu," Pak Slamet mempersilahkan dengan ramah.
"Terimakasih Pak," Bu Ratihpun duduk dengan sopan.
"Bu Ratih sudah benar benar sehat?" ujar Pak Slamet berbasa basi. Matanya tak lepas memandang leher jenjang Bu Ratih. Ada beberapa plester yang menempel disana.
"Terimakasih Pak," Bu Ratihpun duduk dengan sopan.
"Bu Ratih sudah benar benar sehat?" ujar Pak Slamet berbasa basi. Matanya tak lepas memandang leher jenjang Bu Ratih. Ada beberapa plester yang menempel disana.
"Maaf, itu kenapa Bu?"
"Oh, ini," Bu Ratih meraba lehernya. "Sepertinya semalam tanpa sengaja saya mencakar leher saya sendiri Pak."
"Lho, kok bisa?!" tanya Pak Slamet heran.
"Oh, ini," Bu Ratih meraba lehernya. "Sepertinya semalam tanpa sengaja saya mencakar leher saya sendiri Pak."
"Lho, kok bisa?!" tanya Pak Slamet heran.
"Semalam saya mimpi buruk. Dan, ya beginilah. Tanpa sengaja saya menggaruk atau mencakar leher saya sendiri, sampai ada beberapa luka lecet begini." Bu Ratih menjelaskan.
"Mimpi buruk macam apa yg bisa membuat Bu Ratih sampai mencakar leher sendiri begitu?" tanya Pak Slamet lagi
"Mimpi buruk macam apa yg bisa membuat Bu Ratih sampai mencakar leher sendiri begitu?" tanya Pak Slamet lagi
"Ah, hanya sebuah mimpi Pak. Mungkin karena saya terlalu banyak pikiran, sampai sampai terbawa dalam mimpi."
"Apa ada hubungannya dengan sosok gosong yang beberapa hari lalu meneror Bu Ratih?"
"Apa ada hubungannya dengan sosok gosong yang beberapa hari lalu meneror Bu Ratih?"
"Sama sekali tidak Pak. Saya mimpi soal Wulan, dan juga seorang nenek tua yang mencoba mencelakai saya," Bu Ratih lalu menceritakan mimpi yang dialaminya itu kepada Pak Slamet. Laki laki itu mendengarkan dengan sangat serius.
"Aneh," gumam Pak Slamet.
"Apanya yang aneh Pak?" tanya Bu Ratih heran.
"Entah kebetulan atau tidak, tapi saya merasa sepertinya mimpi yang ibu alami itu ada hubungannya dengan apa yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ratih," ujar Pak Slamet.
"Apanya yang aneh Pak?" tanya Bu Ratih heran.
"Entah kebetulan atau tidak, tapi saya merasa sepertinya mimpi yang ibu alami itu ada hubungannya dengan apa yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ratih," ujar Pak Slamet.
"Oh, iya. Sampai lupa, ada hal penting apa yang ingin bapak sampaikan, sampai memanggil saya kemari?"
Pak Slametpun segera menceritakan kejadian kejadian yang ia alami mulai dari mengikuti Ki Suryo yang mengendap endap di kebun rumah Bu Ratih,
Pak Slametpun segera menceritakan kejadian kejadian yang ia alami mulai dari mengikuti Ki Suryo yang mengendap endap di kebun rumah Bu Ratih,
lalu menguping pembicaraan Ki Suryo dan Pak Marto, sampai saat ia didatangi sosok setan gosong di dapur rumahnya sendiri. Tentu saja Pak Slamet tak menyertakan bagian yang saat ia dikejar kejar peronda malam dan pingsan di kuburan itu.
"Kenapa bapak baru menceritakannya sekarang?" tanya Bu Ratih.
"Sebenarnya sudah dari kemarin saya ingin menceritakannya pada ibu, tapi belum ada waktu yang tepat."
"Sebenarnya sudah dari kemarin saya ingin menceritakannya pada ibu, tapi belum ada waktu yang tepat."
"Sedikit banyak saya tau soal Ki Suryo itu Pak. Saya pernah melihatnya saat meninggalnya keluarga Pak Darsa dulu. Dan firasat saya mengatakan, laki laki tua itu memang sedikit mencurigakan."
"Saya juga berpikir begitu Bu. Dan saat saya menguping pembicaraannya denga Pak Marto itu, saya sedikit gelisah. Ia sempat menyebut nyebut nama Wulan.Juga nama ibu.Sayang, saya tak begitu jelas mendengar percakapan mereka. Hanya ini kata kata ini yang bisa saya dengar dan ingat."
Pak Slamet memberikan sebuah map yang berisi beberapa lembar kertas dengan coretan coretan tak jelas. Ada kata Wulan, tumbal, perjanjian, dan entah apa lagi, Bu Ratih tak memahami isi coretan coretan itu.
"Sepertinya mereka merencanakan sesuatu Pak. Dugaan saya, ini semua mengarah kepada Wulan. Mengingat kedua orang itu memiliki masalah dengan Wulan. Ki Suryo dan Pak Marto, keduanya sempat menuduh Wulan yang menjadi biang keladi meninggalnya kerabat dan keluarga mereka.
Dan ..., lho, yang ini apa Pak?" Bu Ratih mengerutkan dahinya, saat tiba pada lembaran kertas yang terakhir. Kertas bergambar sketsa dirinya yang sebagian telah luntur seperti tersiram air.
"Eh, emmm, itu ..., bukan apa apa Bu. Maaf, saya salah menaruh kertas sepertinya," buru buru Pak Slamet mengambil kertas itu dari tangan Bu Ratih. Wajahnya memerah menahan malu.
"Emm,anu Bu,nanti,apa Bu Ratih ada jadwal mengajar Wulan ke rumahnya?"Pak Slamet mencoba mengalihkan pembicaraan
"Sepertinya begitu Pak,"Bu Ratih mencoba menahan senyum saat melihat Pak Slamet masih nampak gugup. Tangannya sibuk memasukkan kertas bergambar sketsa itu ke dlm laci
"Sepertinya begitu Pak,"Bu Ratih mencoba menahan senyum saat melihat Pak Slamet masih nampak gugup. Tangannya sibuk memasukkan kertas bergambar sketsa itu ke dlm laci
"Boleh saya ikut Bu? Saya juga ingin bertemu dengan Wulan."
Bu Ratih mengangguk sambil tersenyum.
Jadilah, siang harinya selepas bubaran sekolah, Bu Ratih dan Pak Slamet berangkat ke Tegal Salahan, menuju ke pondok Mas Joko.
Bu Ratih mengangguk sambil tersenyum.
Jadilah, siang harinya selepas bubaran sekolah, Bu Ratih dan Pak Slamet berangkat ke Tegal Salahan, menuju ke pondok Mas Joko.
Selain untuk mengajar Wulan yang memang sudah menjadi tanggung jawab Bu Ratih, mereka juga ingin memastikan bahwa Wulan baik baik saja.
Insting Bu Ratih yang tajam memang sudah mengendus sesuatu yang tak beres. Ada bahaya yang mengancam Wulan.
Insting Bu Ratih yang tajam memang sudah mengendus sesuatu yang tak beres. Ada bahaya yang mengancam Wulan.
Tapi sayang, mereka datang terlambat. Saat sampai di pondok Mas Joko, Wulan sudah dibawa oleh Pak Marto. Bu Ratih semakin curiga, dan yakin kalau Pak Marto memang punya niat jahat terhadap Wulan. Tapi guru muda itu tetap berusaha untuk bersikap tenang.
Ia tak ingin membuat kedua orang tua Wulan itu panik.
Bu Ratih berpikir keras, sementara Pak Slamet masih asyik berbincang dengan Mas Joko.
Bu Ratih berpikir keras, sementara Pak Slamet masih asyik berbincang dengan Mas Joko.
Guru muda itu mencoba memusatkan konsentrasinya, mempertajam mata batinnya seperti yang dulu pernah diajarkan oleh Uwaknya, agar bisa menemukan keberadaan Wulan.
Keringat dingin mengalir membasahi kening Bu Ratih, saat rasa pening yang sangat menyerang bagian kepalanya.
Keringat dingin mengalir membasahi kening Bu Ratih, saat rasa pening yang sangat menyerang bagian kepalanya.
Sementara Pak Slamet dan Mas Joko masih terus asyik berbincang.
"Arrrggghhhh ...!!!" suara erangan Bu Ratih mengalihkan perhatian Pak Slamet dan Mas Joko.
"Bu, kenapa Bu?" panik Pak Slamet menguncang bahu guru muda itu.
"Arrrggghhhh ...!!!" suara erangan Bu Ratih mengalihkan perhatian Pak Slamet dan Mas Joko.
"Bu, kenapa Bu?" panik Pak Slamet menguncang bahu guru muda itu.
"Wu ... Lan!!! Ki Sur ...yo a...kan meng...habisinya! Ma...lam. i...ni! A...las ... Ta...wengan!!!" terbata bata bisikan keluar dari mulut Bu Ratih. Sementara mata guru muda itu terpejam rapat dengan keringat dingin yang mengucur deras di wajah cantiknya.
"Eh, maksudnya ...?!" Mas Joko tercekat mendengar kata kata Bu Ratih.
Tiba tiba guru muda itu bangkit dari duduknya. Matanya yang semula terpejam kini terbuka lebar. Tatapan matanya yang biasanya lembut kini berubah tajam. Begitu juga dengan suara yang keluar dari mulutnya.
Tiba tiba guru muda itu bangkit dari duduknya. Matanya yang semula terpejam kini terbuka lebar. Tatapan matanya yang biasanya lembut kini berubah tajam. Begitu juga dengan suara yang keluar dari mulutnya.
"Kita harus cepat kesana! Alas tawengan! Jurang bangkai! Sebelum tengah malam! Atau nyawa Wulan akan melayang!" ujar Bu Ratih tajam.
Pak Slamet dan Mas Joko saling pandang, lalu "Kita kesana sekarang!" tegas Mas Joko sambil menyambar kunci mobil tuanya.
Pak Slamet dan Mas Joko saling pandang, lalu "Kita kesana sekarang!" tegas Mas Joko sambil menyambar kunci mobil tuanya.
Bergegas mereka, termasuk Mbak Romlah juga yang sudah mulai terlihat panik, masuk dan berdesak desakan di dalam mobil tua itu. Mobil itupun meluncur meninggalkan halaman pondok, menuju ke arah jalanan dan nyaris menabrak Mbak Patmi yang berjalan dari arah berlawanan.
Mas Joko menjalankan jeep tuanya bagai orang kesetanan. Jalanan berbatu itu diterabas dengam kecepatan tinggi, hingga membuat mobil itu terombang ambing dan sesekali nyaris terguling.
Mbak Romlah yang duduk di sebelah bangku pengemudi berpegang erat pada dashboard, meski tubuhnya telah terikat erat oleh tali sabuk pengaman. Sedang di bangku belakang, Pak Slamet menggeerutu panjang pendek.
Tubuh kurusnya nyaris tak bisa bergerak, karena terhimpit oleh tubuh Bu Ratih yang terkulai lemas di sebelah kirinya, dan tubuh Mbak Patmi yang agak melar di sebelah kanannya.
Ya, Mbak Patmi yang semula hendak mencari Lintang yang tak kunjung pulang, memutuskan untuk ikut begitu mendengar bahwa Wulan hilang diculik orang. Apalagi setelah mendengar dari Pak Slamet bahwa hari ini Lintang tak masuk sekolah.
Padahal sudah jelas jelas tadi pagi pamit mau berangkat sekolah. Perempuan itu menduga bahwa Lintang pasti telah melihat Wulan dibawa orang, lalu mengikutinya.
Sempat Mas Joko menghentikan mobilnya di depan rumah Pak Modin, bermaksud untuk mengajak laki laki setengah baya itu.
Sempat Mas Joko menghentikan mobilnya di depan rumah Pak Modin, bermaksud untuk mengajak laki laki setengah baya itu.
Namun ternyata orang yang dicari tak ada di rumah. Kata istrinya sedang ada urusan di kota. Sempat terjadi perdebatan, antara menunggu Pak Modin atau langsung berangkat ke alas Tawengan.
"Tak ada waktu! Kita hanya punya waktu sampai tengah malam, dan uwak belum jelas kapan pulangnya. Lebih baik kita segera berangkat saja," Bu Ratih menengahi perdebatan itu.
"Apa tidak sebaiknya kita juga singgah dulu di rumah Pak Marto?" usul Pak Slamet.
"Apa tidak sebaiknya kita juga singgah dulu di rumah Pak Marto?" usul Pak Slamet.
"Ya. Kita pastikan apakah orang itu berada di rumah atau tidak,"sahut Mas Joko.
"Atau kita lapor polisi saja?" Mbak Patmi ikut bicara.
"Tak ada gunanya Mbak! Waktu kita tidak banyak. Dan kita juga tak punya bukti apa apa.Nanti malah bisa jadi ribet urusannya," sergah Pak Slamet
"Atau kita lapor polisi saja?" Mbak Patmi ikut bicara.
"Tak ada gunanya Mbak! Waktu kita tidak banyak. Dan kita juga tak punya bukti apa apa.Nanti malah bisa jadi ribet urusannya," sergah Pak Slamet
"Kalau begitu kita ke rumah Pak Marto dulu, setelah itu baru ke alas Tawengan," ujar Mas Joko.
Akhirnya setelah menitip pesan pada istri Pak Modin, agar nanti kalau pulang segera menyusul ke alas Tawengan, merekapun segera berangkat.
Akhirnya setelah menitip pesan pada istri Pak Modin, agar nanti kalau pulang segera menyusul ke alas Tawengan, merekapun segera berangkat.
Mobil tua itu kembali melaju kencang menuju rumah Pak Marto. Dan seperti sudah diduga sebelumnya, rumah itu kosong. Akhirnya Mas Joko kembali melajukan mobilnya ke arah utara, lalu berbelok ke arah barat saat memasuki jalan beraspal di utara desa Tarumas.
Laju mobil semakin kencang. Berbelok tajam di perempatan jalan depan pasar ke arah selatan. Melewati desa demi desa dan area persawahan, sampai tibalah mereka di mulut hutan Tawengan.
Mas Joko mengurangi laju kendaraannya, saat jalan beraspal yang mereka lewati berganti dengan jalan tanah yang ditumbuhi rerumputan setinggi mata kaki. Samar samar masih terlihat rerumputan yang rebah bekas terlindas roda kendaraan.
"Itu pasti bekas jejak roda mobil yang membawa Wulan," ujar Pak Slamet.
"Lihat! Itu mobilnya!" Mbak Romlah menunjuk ke depan, ke arah sebuah mobil jeep warna hitam yang terparkir diantara lebatnya pepohonan.
"Lihat! Itu mobilnya!" Mbak Romlah menunjuk ke depan, ke arah sebuah mobil jeep warna hitam yang terparkir diantara lebatnya pepohonan.
"Kita berhenti disini," Mas Joko menghentikan laju kendaraannya, lalu membuka pintu dan turun, diikuti oleh yang lainnya.
"Bu Ratih nggak papa?" Pak Slamet mencoba membantu Bu Ratih yang berjalan sedikit terhuyung huyung.
"Bu Ratih nggak papa?" Pak Slamet mencoba membantu Bu Ratih yang berjalan sedikit terhuyung huyung.
Sepertinya perempuan itu masih kepayahan karena terlalu banyak menggunakan energinya tadi saat melacak keberadaan Wulan.
"Nggak papa Pak, hanya sedikit pusing saja," guru muda itu memegangi pelipisnya dengan salah satu tangannya, sedang tangan sebelahnya lagi bertumpu pada body mobil.
"Sebaiknya Bu Ratih tunggu disini saja bersama Mbak Romlah dan Mbak Patmi. Biar saya dan Mas Joko memeriksa mobil itu," ujar Pak Slamet lagi.
Bu Ratih hanya mengangguk, lalau duduk di bawah sebuah pohon besar yang berada tak jauh dari tempat itu.
Bu Ratih hanya mengangguk, lalau duduk di bawah sebuah pohon besar yang berada tak jauh dari tempat itu.
Sedangkan Pak Slamet dan Mas Joko segera mendekati mobil jeep hitam itu.
"Kosong Pak, tak ada siapa siapa," kata Mas Joko sambil melongok kedalam mobil itu.
"Iya. Apa mungkin mereka telah masuk ke dalam hutan dengan berjalan kaki ya?"
"Kosong Pak, tak ada siapa siapa," kata Mas Joko sambil melongok kedalam mobil itu.
"Iya. Apa mungkin mereka telah masuk ke dalam hutan dengan berjalan kaki ya?"
Pak Slamet ikut memeriksa bagian dalam mobil itu dari kaca jendela.
"Sepertinya begitu Pak! Mobil hanya bisa sampai sisini, karena jalanan semakin sempit, dan, lihat, ada jejak jekak kaki samar samar diantara rerumputan. Sepertinya jejaknya menuju ke dalam hutan."
"Sepertinya begitu Pak! Mobil hanya bisa sampai sisini, karena jalanan semakin sempit, dan, lihat, ada jejak jekak kaki samar samar diantara rerumputan. Sepertinya jejaknya menuju ke dalam hutan."
Mas Joko memperhatikan permukaan tanah berumput tebal itu. Memang ada bekas jejak jejak kaki yang mengarah ke dalam hutan.
"Sebaiknya kita segera menyusulnya Mas, mumpung hari masih terang. Dan sebaiknya kita membawa bekal secukupnya.
"Sebaiknya kita segera menyusulnya Mas, mumpung hari masih terang. Dan sebaiknya kita membawa bekal secukupnya.
Paling tidak lampu penerangan dan sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Hari sebentar lagi malam. Tentu akan sangat gelap di dalam hutan sana. Belum lagi kalau ada binatang buas yang berkeliaran," usul Pak Slamet.
"Di mobil saya ada senter Pak.
"Di mobil saya ada senter Pak.
Tapi kalau untuk senjata, sepertinya ndak ada," kata Mas Joko.
"Ya sudah, senterpun jadilah lah. Soal senjata, bisa kita pikirkan sambil jalan. Lebih baik kita segera bergegas Mas, sebelum hari menjadi gelap,"
"Ya sudah, senterpun jadilah lah. Soal senjata, bisa kita pikirkan sambil jalan. Lebih baik kita segera bergegas Mas, sebelum hari menjadi gelap,"
kata Pak Slamet sambil melangkah kembali ke tempat mobil Mas Joko di parkir. Mas Jokopun mengikutinya dari belakang.
"Bagaimana dengan para perempuan itu Mas? Agak riskan juga kalau kita mengajak mereka masuk ke dalam hutan," kata Pak Slamet sambil berjalan.
"Bagaimana dengan para perempuan itu Mas? Agak riskan juga kalau kita mengajak mereka masuk ke dalam hutan," kata Pak Slamet sambil berjalan.
"Kita masih butuh Bu Ratih Pak. Dan soal Romlah dan Mbak Patmi, sepertinya kita tak punya pilihan lain. Lebih berbahaya kalau kita meninggalkan mereka di mobil hanya berdua. Jadi mau ndak mau kita harus mengajaknya." kata Mas Joko.
Setelah berembuk sejenak, akhirnya mereka berjalan beriringan memasuki area hutan. Mas Joko berjalan paling depan, diikuti oleh Bu Ratih sebagai pemandu jalan, lalu di belakangnya menyusul Mbak Romlah, Mbak Patmi, dan terakhir Pak Slamet yang berjalan paling belakang.
Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, suasana semakin gelap. Selain karena hari memang sudah menjelang sore, lebatnya pepohonan membuat sinar matahari tak leluasa menerangi langkah mereka.
Jejak kaki yang mereka ikutipun semakin lama semakin samar, untuk kemudian menghilang sama sekali.
"Jejaknya semakin samar Pak, gimana ini?" ujar Mas Joko sambil menyorotkan senternya kesana kemari.
"Jejaknya semakin samar Pak, gimana ini?" ujar Mas Joko sambil menyorotkan senternya kesana kemari.
"Terus saja Mas, firasat saya mengatakan, orang orang itu menuju ke jurang bangkai," Bu Ratih yang menjawab.
"Jurang bangkai?!"
"Ya! Di jantung hutan ini ada tempat yang dinamakan jurang bangkai.
"Jurang bangkai?!"
"Ya! Di jantung hutan ini ada tempat yang dinamakan jurang bangkai.
Konon katanya, dulu huran ini dikenal angker, siapapun yang masuk ke huran ini, tak akan pernah bisa keluar hidup hidup. Dan di jurang bangkai itulah mayat mayat mereka akan membusuk dan bergelimpangan.
Kata orang, penghuni hutan inilah yang mengumpulakn mayat mayat itu disana," jelas Bu Ratih.
"Sepertinya Bu Ratih tau banyak soal hutan ini," gumam Mas Joko sambil terus berjalan.
"Wak Dul yang bercerita Mas."
"Lalu dimana letak jurang bangkai itu Bu?" tanya Mas Joko lagi.
"Sepertinya Bu Ratih tau banyak soal hutan ini," gumam Mas Joko sambil terus berjalan.
"Wak Dul yang bercerita Mas."
"Lalu dimana letak jurang bangkai itu Bu?" tanya Mas Joko lagi.
"Saya juga kurang tau persisnya Mas," jawab Bu Ratih. "Tapi kata orang di dekat pohon randhu alas raksasa yang dibawahnya ada makam keramat. Kita terus berjalan saja. Alam dan seisi hutan ini yang akan menuntun kita kesana, begitu yang saya dengar dari Wak Dul.
Siapapun yang masuk ke hutan ini, pasti akan berakhir di sana." kembali Bu Ratih menjelaskan.
"Waduh! Apa itu berarti kita juga tak akan bisa keluar hidup hidup dari hutan ini?" seru Pak Slamet yang berjalan paling belakang.
"Bapak takut ya?" sela Mbak Patmi.
"Waduh! Apa itu berarti kita juga tak akan bisa keluar hidup hidup dari hutan ini?" seru Pak Slamet yang berjalan paling belakang.
"Bapak takut ya?" sela Mbak Patmi.
"Bukannya takut, tapi ...."
"Mudah mudahan sih tidak," potong Bu Ratih. "Selama kita bisa menemukan Wulan dan Lintang, sepertinya semua akan baik baik saja."
"Eh, tunggu! Itu kan sepeda Lintang!" seru Mbak Romlah sambil menunjuk ke depan.
"Mudah mudahan sih tidak," potong Bu Ratih. "Selama kita bisa menemukan Wulan dan Lintang, sepertinya semua akan baik baik saja."
"Eh, tunggu! Itu kan sepeda Lintang!" seru Mbak Romlah sambil menunjuk ke depan.
Benar saja, diantara rimbunan semak semak nampak sepeda Lintang tergeletak tanpa sang pemilik.
"Lho, iya, benar. Itu sepeda Lintang! Ya Allah, anakku ...! Kalau sepedanya disini, berarti ...."
"Tenang Mbak," Bu Ratih menyela.
"Lho, iya, benar. Itu sepeda Lintang! Ya Allah, anakku ...! Kalau sepedanya disini, berarti ...."
"Tenang Mbak," Bu Ratih menyela.
"Anak sampeyan pasti baik baik saja kok, dan kita pasti akan segera menemukannya."
"Kenapa sampeyan begitu yakin Bu? Ini di hutan lho, mana angker pula hutannya!"
"Saya kenal betul dengan Lintang Mbak," kata Bu Ratih lagi.
"Kenapa sampeyan begitu yakin Bu? Ini di hutan lho, mana angker pula hutannya!"
"Saya kenal betul dengan Lintang Mbak," kata Bu Ratih lagi.
"Anak sampeyan itu bukan anak yang lemah. Percaya sama saya, dia pasti akan baik baik saja."
Kata kata Bu Ratih yang penuh keyakinan itu sedikit banyak bisa menenangkan teman teman seperjalanannya.
Kata kata Bu Ratih yang penuh keyakinan itu sedikit banyak bisa menenangkan teman teman seperjalanannya.
Mereka tidak menyadari, bahwa sejak tadi guru muda itu telah memaksakan dirinya untuk melacak jejak Wulan dan Lintang dengan mata batinnya. Rasa pening yang semakin terasa menggit di bagian belakang kepalanya tak ia hiraukan sama sekali.
Hanya sesekali ia menyeka hidungnya yang mulai meneteskan cairan merah berbau amis.
"Astagfirullaaaahhhh....!!!" tiba tiba Pak Slamet yang berjalan paling belakang berseru sambil mengarahkan senternya ke atas pohon.
"Astagfirullaaaahhhh....!!!" tiba tiba Pak Slamet yang berjalan paling belakang berseru sambil mengarahkan senternya ke atas pohon.
"Ada apa Pak?" serempak mereka semua berhenti dan menoleh ke arah laki laki itu.
"Eh, ndak papa. Cuma monyet yang bergelantungan di pohon," jawab Pak Slamet.
"Oalah Pak Pak, bikin kaget saja sampeyan ini. Masa sama monyet saja kok takut," gerutu Mbak Patmi.
"Eh, ndak papa. Cuma monyet yang bergelantungan di pohon," jawab Pak Slamet.
"Oalah Pak Pak, bikin kaget saja sampeyan ini. Masa sama monyet saja kok takut," gerutu Mbak Patmi.
"Hehe, bukannya takut Mbak, cuma kaget saja kok. Ya sudah, ayo jalan lagi," Pak Slamet terkekeh untuk menutupi kegugupannya. Atau lebih tepatnya untuk menutupi rasa khawatirnya.
Karena semenjak mereka berjalan tadi, entah sudah berapa ekor monyet yang ia lihat duduk diam diatas pepohonan seolah sedang mengawasi mereka. Monyet monyet itu mengingatkan Pak Slamet pada cerita orang orang tentang monyet siluman penghuni hutan Tawengan ini.
Lintang menghentikan larinya, lalu membungkuk dengan kedua tangan bertumpu pada lutut, berusaha mengatur nafasnya yang nyaris putus. Entah sudah seberapa jauh ia memasuki area hutan itu, ia tak tahu pasti.
Bahkan sepertinya ia sudah tak ingat lagi jalan untuk kembali keluar dari hutan ini.
Sejenak anak itu menengadah, melihat posisi matahari yang nyaris tak terlihat karena terhalang lebatnya pepohonan.
Sejenak anak itu menengadah, melihat posisi matahari yang nyaris tak terlihat karena terhalang lebatnya pepohonan.
Namun di arah sebelah kirinya, nun jauh di ujung cakrawala, samar samar terlihat semburat warna jingga, tanda matahari sudah mulai bersiap untuk kembali ke peraduannya. Senja hampir menjelang.
Lintang mendesah, lalu duduk bersandar pada sebuah batang pohon besar yang tumbuh di dekatnya. Rasa pegal di kakinya akibat hampir seharian bersepeda dan disambung dengan berlari memasuki hutan, mulai terasa.
Juga rasa lapar yang mulai menyerang perutnya. Lintang baru ingat, semenjak pagi ia belum makan.
Segera Lintang membuka tas sekolah yang disandangnya. Beruntung, selama ini ia terbiasa membawa bekal ke sekolah.
Segera Lintang membuka tas sekolah yang disandangnya. Beruntung, selama ini ia terbiasa membawa bekal ke sekolah.
Segera ia mengeluarkan kotak bekal dari dalam tas, berikut sebotol air minum. Aroma ayam goreng segera menguar begitu kotak bekal itu ia buka, membuat cacing cacing di dalam perutnya memberontak. Lintangpun mulai makan dengan sangat lahapnya.
Suapan suapan besar nasi ia jejalkan ke dalam mulutnya.
Tengah asyik menikmati makan sorenya, tiba tiba ada seekor anak monyet yang melompat turun dari atas pohon dan menghampirinya. Sepertinya anak monyet itu tertarik dengan aroma ayam goreng yang tengah dikunyahnya.
Tengah asyik menikmati makan sorenya, tiba tiba ada seekor anak monyet yang melompat turun dari atas pohon dan menghampirinya. Sepertinya anak monyet itu tertarik dengan aroma ayam goreng yang tengah dikunyahnya.
"Kamu mau?" Lintang menyodorkan sesuwir daging ayam ke arah anak monyet itu. Namun binatang itu hanya diam sambil menatap ke arah kotak bekal milik Lintang. Ada dua buah pisang disana.
"Ah, iya. Kamu nggak suka ayam goreng ya? Kalau ini kamu pasti suka kan?" Lintang melemparkan dua buah pisang itu, yang langsung ditangkap dengan sigap oleh anak monyet itu.
"Haha, kamu juga kelaparan ya? Dimana ayah dan ibumu?" Tentu saja anak monyet itu tak bisa menjawab.
"Haha, kamu juga kelaparan ya? Dimana ayah dan ibumu?" Tentu saja anak monyet itu tak bisa menjawab.
Lintang tertawa geli melihat anak monyet itu dengan cepat mengupas dan mengunyah buah pisang itu dengan sangat cepat.
Selesai makan, Lintang kembali menyandarkan tubuhnya pada batang pohon. Pikirannya kembali tertuju kepada Wulan.
Selesai makan, Lintang kembali menyandarkan tubuhnya pada batang pohon. Pikirannya kembali tertuju kepada Wulan.
Anak monyet yang juga sudah selesai makan itu masih tetap duduk diam di hadapannya, seolah menunggu untuk diberi makanan lagi. Lintang tak mengacuhkannya.
"Wulan? Dimana kamu?" desah anak itu dalam hati, sambil memejamkan matanya.
"Wulan? Dimana kamu?" desah anak itu dalam hati, sambil memejamkan matanya.
Rasa khawatirnya terhadap keselamatan Wulan mengalahkan rasa cemasnya terhadap keselamatan dirinya sendiri. Wulan sahabat satu satunya yang ia miliki. Dan Pak Marto yang membawa Wulan ke tempat ini, sudah jelas jelas sangat membenci Wulan.
Lintang yakin, Pak Marto pasti punya niat yang tak baik terhadap Wulan.
Ingat akan hal itu, semangat Lintang kembali bangkit. Ia bergegas bangun dari duduknya, lalu kembali melangkah. Tak jelas arah mana yang akan ia tuju, karena ia memang sudah tak tahu arah lagi.
Ingat akan hal itu, semangat Lintang kembali bangkit. Ia bergegas bangun dari duduknya, lalu kembali melangkah. Tak jelas arah mana yang akan ia tuju, karena ia memang sudah tak tahu arah lagi.
Yang ia tahu hanya arah depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan ia memilih untuk terus melangkah ke depan, menuruti apa kata hatinya. Anak monyet yang tadi ia beri pisang itu juga berjalan mengikutinya.
Bahkan kini mendahului dan berjalan di depannya, seolah ingin menunjukkan jalan. Lintang tak terlalu memperdulikannya. Pikirannya hanya terfokus kepada Wulan.
Sesekali anak itu berhenti dan memperhatikan sekeliling, saat telingannya mendengar suara bergemerisik, seperti suara dedaunan kering yang terinjak oleh langkah kaki di belakangnya. Sedikit merinding bulu kuduk anak itu, mengingat ia kini berada di tengah hutan belantara.
Bukan hal yang mustahil kalau di tempat seperti ini masih banyak binatang buas dan berbahaya.
Ingat akan hal itu, Lintang segera memungut sepotong kayu yang tergeletak di dekatnya. Ditimang timangnya dahan kayu itu sambil menoleh ke belakang.
Ingat akan hal itu, Lintang segera memungut sepotong kayu yang tergeletak di dekatnya. Ditimang timangnya dahan kayu itu sambil menoleh ke belakang.
Tak ada apapun selain lebatnya pepohonan.
Kembali Lintang melangkah, mengikuti anak monyet yang berjalan di depannya. Batang kayu masih tergenggam erat di tangannya. Entah kenapa, perasaannya mengatakan kalau ada sesuatu yang sedang mengikuti dan mengawasinya,
Kembali Lintang melangkah, mengikuti anak monyet yang berjalan di depannya. Batang kayu masih tergenggam erat di tangannya. Entah kenapa, perasaannya mengatakan kalau ada sesuatu yang sedang mengikuti dan mengawasinya,
meski saat ia menoleh tak ada sosok apapun yang terlihat di belakangnya. Hanya lebatnya pepohonan, dengan beberapa ekor monyet yang bergelantungan di atasnya.
Hari semakin gelap. Mungkin malam sudah mulai menjelang.
Hari semakin gelap. Mungkin malam sudah mulai menjelang.
Sulit sekali untuk menentukan waktu di tengah lebatnya rimba belantara seperti ini. Dan Lintang sama sekali tak membawa alat penerangan. Hanya ada beberapa lembar buku dan alat tulis di dalam tas sekolahnya. Tentu saja benda benda itu tak bisa banyak membantu.
"Ah, bagaimana ini? Aku tak bisa melihat apa apa selain kegelapan?" batin Lintang sambil menghentikan langkahnya. Anak monyet yang berjalan di depannya melompat naik ke atas sebuah batu, lalu melengking pelan, seolah hendak memberitahukan sesuatu kepada Lintang.
Sejenak Lintang menatap binatang kecil itu, dan sekejap kemudian matanya berbinar. Dari balik batu besar itu nampak samar bias cahaya. Segera Lintang ikut melompat naik ke atas batu besar itu.
"Ups!" nyaris saja Lintang jatuh terjerumus, andai saja ia tak segera menahan bobot tubuhnya dengan kedua tangan yang bertumpu pada permukaan batu. Ternyata ada jurang yang menganga dalam di balik batu itu.
Andai saja tadi ia sampai terjerumus, entah bagaimana nasibnya, mengingat di dasar jurang itu dipenuhi oleh bebatuan karang yang runcing dan tajam.
Ada cahaya samar dari sudut dasar jurang yang menerangi tempat itu. Seperti sebuah nyala api.
Ada cahaya samar dari sudut dasar jurang yang menerangi tempat itu. Seperti sebuah nyala api.
Tapi tak begitu jelas, karena jaraknya yang lumayan jauh. Lintang berpikir cepat, jika ada nyala api, berarti ada orang yang menyalakannya. Bukan tidak mungkin mereka adalah Pak Marto cs yang membawa Wulan. Aku harus menyelidikinya, tapi bagaimana caranya?
Tebing yang menjadi dinding jurang itu semuanya terlihat terjal. Tak mungkin ia turuni dengan mudah.
"Aku harus mencari jalan untuk turun. Jika orang itu bisa sampai ke sana, berarti pasti ada jalan yang bisa dilalui untuk turun sampai ke dasar jurang," pikir Lintang.
"Aku harus mencari jalan untuk turun. Jika orang itu bisa sampai ke sana, berarti pasti ada jalan yang bisa dilalui untuk turun sampai ke dasar jurang," pikir Lintang.
Terlalu sibuk berpikir, membuat kewaspadaan anak itu sedikit berkurang. Lengkingan anak monyet di belakangnya tak ia hiraukan. Hingga saat ia berniat untuk bergerak turun dari batu itu, sebuah tangan besar telah membekap mulutnya, sedang tangan yang satunya meringkus tubuhnya.
Lintang mencoba memberontak. Tapi usahanya sia sia. Tangan tangan yang meringkusnya itu begitu kuat. Rasa takut mulai menjalar di hati anak itu. Dan sekejap kemudian semua menjadi gelap, saat Lintang merasakan sebuah pukulan menghentak mendarat di bagian belakang kepalanya.
***
***
Sementara itu rombongan Mas Joko juga sudah semakin jauh memasuki area hutan, saat hari mulai menjelang malam. Mereka semua berjalan dalam diam. Hanya sesekali saling berbisik jika memang ada sesuatu yang perlu dibicarakan.
Lampu senter yang berada di tangan Mas Joko dan Pak Slamet menari nari kian kemari, mencoba mencari petunjuk, arah mana yang harus mereka tuju.
"Ada apa Mas?"terdengar suara Pak Slamet yang berjalan paling belakang, saat Mas Joko yg berjalan paling depan menghentikan langkahnya.
"Ada apa Mas?"terdengar suara Pak Slamet yang berjalan paling belakang, saat Mas Joko yg berjalan paling depan menghentikan langkahnya.
Mas Joko tak menjawab. Laki laki itu justru mengarahkan sorot senternya ke bawah sebuah pohon besar. Ada sedikit jejak disana. Rerumputan dan semak yang rebah seperti habis diduduki orang.
Juga ada sepotong tulang ayam dan sedikit nasi yang tercecer, serta dua buah kulit pisang yang sepertinya masih baru.
"Ada jejak, sepertinya masih baru," kata Mas Joko akhirnya.
"Ada jejak, sepertinya masih baru," kata Mas Joko akhirnya.
"Ya Allah! Ini pasti Lintang! Saya ingat Mas, tadi pagi saya memberinya bekal ayam goreng dan buah pisang!" seru Mbak Patmi, lalu disambung dengan teriakan memanggil manggil nama sang anak.
"Lintaaaannggg ...!!! Dimana kamu Nak? Ini emak disini mencarimuuuu ...!!!"
"Lintaaaannggg ...!!! Dimana kamu Nak? Ini emak disini mencarimuuuu ...!!!"
"Hush, jangan teriak teriak Mbak. Ini di dalam hutan lho!"hardik Pak Slamet.
"Eh, apa itu Mas?" bisik Mbak Romlah yang melihat sesuatu yg berjalan melompat lompat mendekat ke arah mereka.
"Anak monyet," desis Mas Joko sambil mengarahkan sorot senternya ke arah makhluk kecil itu
"Eh, apa itu Mas?" bisik Mbak Romlah yang melihat sesuatu yg berjalan melompat lompat mendekat ke arah mereka.
"Anak monyet," desis Mas Joko sambil mengarahkan sorot senternya ke arah makhluk kecil itu
Bukannya takut, anak monyet itu justru semakin mendekat, lalu menyambar kulit pisang yang tergeletak tak jauh dari kaki Mas Joko, lalu membawanya kabur ke arah dari mana tadi ia datang.
"Kita ikuti anak monyet itu," seru Bu Ratih memberi komado.
"Kita ikuti anak monyet itu," seru Bu Ratih memberi komado.
Lintang menggeliat, lalu membuka matanya. Rasa pening yang teramat sangat terasa menusuk nusuk bagian belakang kepalanya, membuat pandangannya sedikit mengabur.
"Aku, dimana ini?" batin anak itu saat menyadari bahwa kini ia berada di tempat yang asing. Ah, iya, ia ingat.
"Aku, dimana ini?" batin anak itu saat menyadari bahwa kini ia berada di tempat yang asing. Ah, iya, ia ingat.
Tadi ia mengikuti Wulan yang dibawa pergi oleh Pak Marto, kehilangan jejak, lalu masuk ke hutan, bertemu dengan anak monyet yang menunjukkan jalan ke tepi jurang, lalu ....
"Sial! Pasti aku tertangkap oleh mereka!" maki Lintang saat menyadari bahwa kini tubuhnya terikat erat pada sebuah batang pohon.
Lintang meronta, mencoba melepaskan diri. Namun ikatan di tubuhnya itu sangatlah kuat.
Lintang meronta, mencoba melepaskan diri. Namun ikatan di tubuhnya itu sangatlah kuat.
Jangankan untuk membebaskan diri, untuk sekedar bergerak saja ia sedikit kesulitan.
"Aku harus mencari akal! Aku harus bisa bebas!" anak itu mengedarkan pandangannya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melepas ikatan itu.
"Aku harus mencari akal! Aku harus bisa bebas!" anak itu mengedarkan pandangannya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melepas ikatan itu.
Pendar cahaya api unggun yang menyala beberapa jengkal di depannya, sedikit membantu pengelihatannya.
"Lho, itu kan ..." Lintang tercekat. Tak jauh dari nyala api unggun itu, tepatnya diatas sebuah batu besar yang berpermukaan rata, nampak sesosok tubuh tergolek diam.
"Lho, itu kan ..." Lintang tercekat. Tak jauh dari nyala api unggun itu, tepatnya diatas sebuah batu besar yang berpermukaan rata, nampak sesosok tubuh tergolek diam.
"Wulan!" desis Lintang. Ia sangat mengenali sosok itu. "Jangan jangan dia ..., Ah, tak mungkin! Ini tak mungkin terjadi!" rasa khawatir mulai menghantui Lintang, melihat Wulan yang terbaring diam tak bergerak sama sekali.
Ada empat sosok hitam gosong berdiri mengelilingi tubuh Wulan. Masing masing dari sosok itu memegangi pergelangan tangan dan kaki Wulan. Sedang seorang laki laki tua berbadan kurus kering nampak duduk bersila tepat disisi tubuh Wulan.
Kedua tangan laki laki itu terentang ke depan dengan telapak tangan terbuka, mengambang sejengkal diatas perut Wulan. Mata laki laki tua itu terpejam, mulutnya komat kamit seperti sedang membaca mantera.
Bau pepak asap kemenyan tercium dari dupa yg dibakar di keempat sudut batu besar itu.
Lintang mempertajam pengelihatannya. Pelan namun pasti tubuh Wulan bergetar, disusul dengan keluarnya selarik cahaya tipis berwarna kemerahan yang keluar dari bagian pusarnya.
Lintang mempertajam pengelihatannya. Pelan namun pasti tubuh Wulan bergetar, disusul dengan keluarnya selarik cahaya tipis berwarna kemerahan yang keluar dari bagian pusarnya.
Cahaya itu seolah tersedot kedalam telapak tangan si lelaki tua itu. Tangan si lelaki tua ikut bergetar hebat, seolah sedang menahan dorongan yang sangat kuat dari dalam perut Wulan.
"Jangan, jangan sampai ini terjadi! Aku harus bisa bebas. Aku harus segera menyelamatkan Wulan!"
"Jangan, jangan sampai ini terjadi! Aku harus bisa bebas. Aku harus segera menyelamatkan Wulan!"
Lintang mendesis sambil terus meronta ronta. Rasa perih yang ia rasakan di pergelangan tangannya akibat luka lecet karena bergesekan dengan tali tambang sama sekali tak ia hiraukan. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar ia bisa bebas dari ikatan yang membelenggunya itu
"Eh," Lintang nyaris bersorak saat menyadari bahwa tali yang mengikatnya mulai terasa longgar. Usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil juga. Dan begitu ia merasa benar benar bebas dari ikatan itu,
Lintang segera melompat bangkit dan bermaksud mendekat ke arah batu besar dimana sang kakek tua melakukan ritual terhadap Wulan. Namun niatnya tertahan saat sebuah tangan kecil berbulu menahan lengannya.
"Lho, kamu?" sedikit terkejut Lintang, saat mendapati seekor anak monyet yang menahan lengannya. "Jadi kamu yang melepaskan ikatanku?"
Anak monyet itu menyeringai lebar, lalu menarik tangan Lintang menjauh dari tempat itu.
Anak monyet itu menyeringai lebar, lalu menarik tangan Lintang menjauh dari tempat itu.
"Tunggu! Aku harus menyelamatkan temanku dulu," protes Lintang. Namun anak monyet itu seolah tak memperdulikannya. Ia terus menarik tangan Lintang menuju ke balik semak semak.
"Anak cerdas," sebuah suara yang sangat dikenali oleh Lintang terdengar dari balik semak semak.
"Anak cerdas," sebuah suara yang sangat dikenali oleh Lintang terdengar dari balik semak semak.
"Lho, Bu Ratih?!" kok bisa ada disini?" belum hilang rasa terkejut Lintang, sebuah tangan terjulur dan menarik telinganya kuat kuat, membuat Lintang meringis kesakitan.
"Bocah bandel! Kenapa pergi ndak pamit sama emak?"
"Bocah bandel! Kenapa pergi ndak pamit sama emak?"
seru Mbak Patmi tanpa melepaskab tangannya dari telinga Lintang.
"Aduh! Ampun Mak! Sakit!"
"Ssstttt ...!!! Sudah sudah, jangan berisik! Bisa ketahuan kita nanti!" jelas itu suara Pak Slamet.
"Aduh! Ampun Mak! Sakit!"
"Ssstttt ...!!! Sudah sudah, jangan berisik! Bisa ketahuan kita nanti!" jelas itu suara Pak Slamet.
Selain itu Lintang juga mendapati bapak dan emaknya Wulan yang sedang mengintip dari balik semak semak. Anak itu menghela nafas lega. Akhirnya ada bantuan yang datang juga.
"Apa yang dilakukan oleh si tua bangka itu?" bisik Mbak Patmi.
"Apa yang dilakukan oleh si tua bangka itu?" bisik Mbak Patmi.
"Sepertinya ia sedang berusaha untuk menarik energi yang berada di tubuh Wulan," jelas Bu Ratih, juga dengan berbisik.
"Energi? Maksudnya apa Bu?" Mbak Romlah ikut berbisik.
"Energi? Maksudnya apa Bu?" Mbak Romlah ikut berbisik.
"Ya semacam ilmu kanuragan atau kekuatan yang dulu pernah dititipkan oleh kakeknya Wulan ke dalam tubuhnya," jelas Bu Ratih lagi.
"Apakah itu berbahaya buat Wulan Bu?" Mas Joko kini yang bertanya.
"Apakah itu berbahaya buat Wulan Bu?" Mas Joko kini yang bertanya.
"Berbahaya kalau menyerapnya dengan cara dipaksa begitu. Tapi kita lihat saja dulu. Sepertinya kakek tua itu sedikit kesulitan.Wulan memang sedang dalam keadaan tidak sadar.Tapi alam bawah sadar anak itu sepertinya mencoba menahan energi itu agar tak sampai keluar dari tubuhnya."
"Hebat! Sepertinya Bu Ratih tau banyak soal Wulan," bisik Pak Slamet.
"Tentu saja Pak, karena saat saya kecil dulu juga tak jauh berbeda seperti Wulan. Karena itulah saya mencoba mati matian untuk menyelamatkan Wulan.
"Tentu saja Pak, karena saat saya kecil dulu juga tak jauh berbeda seperti Wulan. Karena itulah saya mencoba mati matian untuk menyelamatkan Wulan.
Saya tau bagaimana rasanya saat energi yang ada di dalam tubuh kita ditarik secara paksa seperti itu."
"Eh, jadi ibu juga ..."
"Itu dulu Pak Slamet. Sekarang saya sudah tak memiliki apa apa lagi. Hanya ada sedikit yang tersisa."
"Kok bisa Bu?"
"Eh, jadi ibu juga ..."
"Itu dulu Pak Slamet. Sekarang saya sudah tak memiliki apa apa lagi. Hanya ada sedikit yang tersisa."
"Kok bisa Bu?"
"Panjang ceritanya Pak, dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk menceritakannya."
Pak Slamet hanya bisa garuk garuk kepala, saat mengetahui bahwa dulu semasa kecil guru muda itu juga sama seperti Wulan. Pantas saja sikapnya sedikit misterius.
Pak Slamet hanya bisa garuk garuk kepala, saat mengetahui bahwa dulu semasa kecil guru muda itu juga sama seperti Wulan. Pantas saja sikapnya sedikit misterius.
Pak Slamet tersenyum tipis, sambil menyenderkan tubuhnya pada sebatang pohon. Rasa kagumnya kepada guru muda itu semakin bertambah. Aku harus bisa mendapatkannya, aku harus bisa memilikinya. Apapun akan kulakukan demi mendapatkanmu, Bu Ratih, gumam Pak Slamet dalam hati.
"Tesss ..., tessss," eh, apa ini? Pak Slamet meraba kepalanya, saat ia merasakan ada cairan yang menetes jatuh tepat di ubun ubunnya. Benar saja, rambutnya sedikit basah.
"Apa ini?" laki laki itu memperhatikan telapak tangannya.
"Apa ini?" laki laki itu memperhatikan telapak tangannya.
Ada cairan kental dan sedikit lengket menempel disana. Di dekatkannya telapak tangannya ke depan hidung. Busuk dan agak amis!
"Jangan jangan ....," sebuah pikiran buruk melintas, membuat laki laki itu mendongak ke atas.
"Jangan jangan ....," sebuah pikiran buruk melintas, membuat laki laki itu mendongak ke atas.
Dan benar saja, sesuatu yang ia lihat sedang duduk di atas dahan dengan kaki menjuntai, membuat sekujur tubuh Pak Slamet bergetar hebat. Rasa takut menjalar. Ingin rasanya ia berteriak, namun niat itu ia urungkan, mengingat saat ini mereka sedang dalam misi pengintaian.
Alhasil, laki laki itu hanya mundur pelan pelan, dengan kepala tetap mendongak menatap makhluk menyeramkan itu. Tangannya menggapai gapai, mencoba meraih tangan Bu Ratih untuk sekedar memberi kode.
Dapat, serunya dalam hati, saat tangannya berhasil meraih sebuah tangan. Masih dengan kepala mendongak Pak Slamet meremas tangan yang digenggamnya itu.
"Eh, nakal!" Mbak Patmi menampar keras tangan Pak Slamet yang sedang meremas tangannya.
"Eh, maaf, saya kira ...."
"Eh, nakal!" Mbak Patmi menampar keras tangan Pak Slamet yang sedang meremas tangannya.
"Eh, maaf, saya kira ...."
"Jangan mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan Pak!" bisik Mbak Patmi tajam, setajam lirikan matanya kepada kepala sekolah itu, membuat wajah Pak Slamet menjadi merah padam karena menahan malu.
"Maaf Mbak, saya ...!"
"Gawat!!!" seruan Bu Ratih memotong ucapan Pak Slamet. Laki laki itu segera mengalihkan pandangannya ke arah batu besar tempat diadakannya ritual aneh itu. Ia begidig ngeri, saat menyaksikan si kakek tua itu mengeluarkan sebilah keris dari dalam rangkanya.
"Gawat!!!" seruan Bu Ratih memotong ucapan Pak Slamet. Laki laki itu segera mengalihkan pandangannya ke arah batu besar tempat diadakannya ritual aneh itu. Ia begidig ngeri, saat menyaksikan si kakek tua itu mengeluarkan sebilah keris dari dalam rangkanya.
"Apa yang akan dilakukannya?" bisik Mas Joko bernada cemas.
"Sepertinya ia sadar kalau tak akan sanggup menarik energi dari dalam tubuh Wulan. Dan hari sudah hampir tengah malam. Waktunya sudah habis, lalu ...."
"Lalu apa Bu?!" sentak Mas Joko tak sabar.
"Lalu ....!!!"
"Sepertinya ia sadar kalau tak akan sanggup menarik energi dari dalam tubuh Wulan. Dan hari sudah hampir tengah malam. Waktunya sudah habis, lalu ...."
"Lalu apa Bu?!" sentak Mas Joko tak sabar.
"Lalu ....!!!"
"Hiaaaaaaa ....!!!" diiringi teriakan keras, laki laki tua itu mengangkat kerisnya tinggi tinggi, lalu dengan sekuat tenaga menghunjamkannya ke tubuh Wulan.
"WULAAAAANNNNN .....!!!"
"WULAAAAANNNNN .....!!!"
"Hiaaaaa ...!!!" diiringi dengan teriakan keras, laki laki tua itu mengangkat kerisnya tinggi tinggi, lalu dengam sekuat tenaga menghunjamkannya ke tubuh Wulan.
"WULAAAANNN ...!!! Manusia biadab! Beraninya kau menyakiti anakku!"
"WULAAAANNN ...!!! Manusia biadab! Beraninya kau menyakiti anakku!"
hampir serempak Mas Joko dan Mbak Romlah berteriak sambil melompat keluar dari tempat persembunyiannya.
"Tunggu! Jangan ...."
"Pembunuh!!!" belum sempat Bu Ratih menyelesaikan kalimatnya, Lintang juga ikut melompat keluar.
"Tunggu! Jangan ...."
"Pembunuh!!!" belum sempat Bu Ratih menyelesaikan kalimatnya, Lintang juga ikut melompat keluar.
"Lintaaannggg...!!! Dasar bocah gemblung!" Mbak Patmi menyincingkan rok panjangnya, agar bisa mengejar Lintang.
"Hei! Tunggu! Jangan gegabah!" teriakan Bu Ratih sepertinya sudah tak dihiraukan lagi oleh keempat orang itu.
"Hei! Tunggu! Jangan gegabah!" teriakan Bu Ratih sepertinya sudah tak dihiraukan lagi oleh keempat orang itu.
Pak Slamet yang melihat kejadian itu hanya berdiri terbengong bengong sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia bingung harus berbuat apa.
Kehadiran keempat orang yang tiba tiba muncul dari balik semak semak itu tentu saja mengejutkan Ki Suryo.
Kehadiran keempat orang yang tiba tiba muncul dari balik semak semak itu tentu saja mengejutkan Ki Suryo.
Pak Marto dan sang keponakanpun tak tinggal diam. Mereka segera menghadang keempat orang itu. Perkelahian sengitpun tak dapat dihindarkan.
"Gawat! Ini benar benar gawat!" desis Bu Ratih saat melihat keatas batu dimana tubuh Wulan dan Ki Suryo berada.
"Gawat! Ini benar benar gawat!" desis Bu Ratih saat melihat keatas batu dimana tubuh Wulan dan Ki Suryo berada.
Tubuh anak itu mulai menggeliat. Keris yang tadi dihunjamkan oleh Ki Suryo kini tinggal menampakkan bagian gagangnya saja. Bilahnya telah tertanam dalam di perut Wulan. Anehnya, tak ada luka sedikitpun di tubuh gadis itu.
Pelan namun pasti, gagang keris itu mulai masuk ke dalam tubuh Wulan, seperti tersedot, hingga lenyap tanpa meninggalkan sisa sama sekali.
"LEPASKAAAAANNNN ....!!! terdengar jeritan Wulan, diiringi dengan gerakan tubuhnya yang mengejang.
"LEPASKAAAAANNNN ....!!! terdengar jeritan Wulan, diiringi dengan gerakan tubuhnya yang mengejang.
Ki Suryo tergagap, lalu melompat turun dari atas batu besar itu.
" AKU BILANG LEPASKAAANNNN ...!!!" kembali Wulan menjerit, lalu tiba tiba tubuhnya melesat keatas, terbang dengan membawa serta keempat setan gosong yang masih memegangi kedua kaki dan tangannya.
" AKU BILANG LEPASKAAANNNN ...!!!" kembali Wulan menjerit, lalu tiba tiba tubuhnya melesat keatas, terbang dengan membawa serta keempat setan gosong yang masih memegangi kedua kaki dan tangannya.
"Wuuuusssss ...!!!" tubuh yang melayang itu lalu berputar dengan sangat cepat, melemparkan keempat sosok setan gosong hingga terpental ke segala arah.
Dan belum sempat keempat sosok itu mendarat di tanah, selarik sinar merah memancar dari tubuh Wulan yang masih berputar dan menyambar keempat sosok setan gosong itu.
"Bluuurrrbbbb ...! Wusssss ...!" api berkobar, membakar keempat sosok itu hingga hancur menjadi debu.
"Bluuurrrbbbb ...! Wusssss ...!" api berkobar, membakar keempat sosok itu hingga hancur menjadi debu.
Ki Suryo menggeram marah, saat melihat keempat makhluk ciptaannya hancur tak bersisa. Segera mulutnya komat kamit, sambil mengacungkan tangannya ke arah Wulan.
"Whuuuussss ...!!!" sebuah bola cahaya berwarna kemerahan melesat dari tangan kurus keriput itu, menghantam tubuh Wulan yang masih mengambang di udara.
"Jleeegggaaaarrrr ...!!!" ledakan keras terdengar. Bola cahaya itu meledak dan hancur menjadi serpihan serpihan cahaya kecil yang beguguran ke tanah. Sedang tubuh Wulan masih berdiri tegak di udara. Matanya menatap nyalang le arah Ki Suryo.
"KALIAANNN! BERANI KALIAN MENGUSIKKU! AKAN KUBUNUH KALIAN SEMUAAAA ...!!!" jerit anak itu sambil merentangkan kedua tangannya. Suasana hutan yang semula sepi menjadi bergemuruh. Angin tiba tiba bertiup dengan sangat kencang.
Udara malam yang semula dinginpun berubah menjadi sangat panas.
"HIHIHIHIHIHI ...!!!" Wulan tertawa melengking. Kedua matanya menyala terang, memancarkan sinar keputih putihan. Rambutnya yang panjang tergerai berkibar kibar dipermainkan angin.
"HIHIHIHIHIHI ...!!!" Wulan tertawa melengking. Kedua matanya menyala terang, memancarkan sinar keputih putihan. Rambutnya yang panjang tergerai berkibar kibar dipermainkan angin.
Masih dengan tangan terentang, tubuh anak itu kembali berputar pelan, lalu semakin cepat, cepat dan cepat, hingga tubuh anak itu tak terlihat lagi. Hanya terlihat cahaya putih berpendar yang berputar dengan sangat cepat.
Seiring dengan gerakan berputar itu, angin juga bertiup semakin kencang, menimbulkan suara berdesing seperti suara ribuan pedang tajam yang berterbangan. Ranting ranting berguguran, bagai ditebas oleh ribuan pedang yang tak terlihat.
Batang batang pohon tersayat sayat, & bebatuan tergores, meninggalkan bekas yang sangat dalam.
"Arrrrggghhh ..!!!" suara jerit kesakitan terdengar dari mulut orang orang yang sedang berkelahi.Pakaian mereka terkoyak koyak. Kulit mereka tersayat sayat. Darahpun tumpah berceceran.
"Arrrrggghhh ..!!!" suara jerit kesakitan terdengar dari mulut orang orang yang sedang berkelahi.Pakaian mereka terkoyak koyak. Kulit mereka tersayat sayat. Darahpun tumpah berceceran.
"Cepat! Berlindung kemari!" teriak Bu Ratih sambil menarik tangan Pak Slamet menuju ke sebalik batu besar. "Cari tempat yang terlindung dari angin!"
Mas Joko terseok seok memapah Mbak Romlah menghampiri Bu Ratih. Tubuh mereka sudah penuh dengan luka.
Mas Joko terseok seok memapah Mbak Romlah menghampiri Bu Ratih. Tubuh mereka sudah penuh dengan luka.
Demikian juga dengan Lintang dan Mbak Patmi. Sedang Pak Marto dan keponakannya, mereka tak punya pilihan lain. Menyadari bahwa situasi sudah tak menguntungkan, mau tak mau mereka mengikuti langkah Mas Joko. Namun sepertinya mereka terlambat.
Deru angin yang semakin kencang membuat langkah mereka tertahan.
"Arrrrggghhh ...!!!" jerit kematian terdengar sangat memilukan, saat tubuh paman dan keponakan itu tercabik cabik. Darah membanjir. Pak Marto dan keponakannya tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan.
"Arrrrggghhh ...!!!" jerit kematian terdengar sangat memilukan, saat tubuh paman dan keponakan itu tercabik cabik. Darah membanjir. Pak Marto dan keponakannya tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan.
Tubuh keduanya nyaris hancur terpotong potong.
"Ap .., apa yang ..., terjadi?" Mas Joko tersengal. Tubuhnya sudah penuh dengan luka sayatan. Begitu juga dengan Mbak Romlah, Lintang, dan Mbak Patmi.
"Ap .., apa yang ..., terjadi?" Mas Joko tersengal. Tubuhnya sudah penuh dengan luka sayatan. Begitu juga dengan Mbak Romlah, Lintang, dan Mbak Patmi.
"Ini sudah diluar kendali Mas!" Bu Ratih serengah berteriak untuk mengimbangi suara gemuruh desingan angin.
"Maksudnya Bu?!" tanya Pak Slamet.
"Maksudnya Bu?!" tanya Pak Slamet.
"Wulan sudah diluar kendali! Kekuatan yang keluar dari tubuhnya sudah diluar batas! Ia bahkan sudah tak bisa mengenali siapa lawan siapa kawan! Ia belum bisa mengontrol kekuatannya! Jika dibiarkan ...."
"Jika dibiarkan kenapa Bu?"
"Jika dibiarkan kenapa Bu?"
"Kita semua akan mati disini! Dan Wulan sendiri juga akan hancur!"
"Ya Allah! Wulaaannn ...!!!" tangis Mbak Romlah pecah seketika mendengar penjelasan Bu Ratih barusan.
"Bu, tolong lakukan sesuatu Bu! Selamatkan anak saya," Mas Joko memohon.
"Ya Allah! Wulaaannn ...!!!" tangis Mbak Romlah pecah seketika mendengar penjelasan Bu Ratih barusan.
"Bu, tolong lakukan sesuatu Bu! Selamatkan anak saya," Mas Joko memohon.
"Yah, akan saya coba Mas. Tapi saya butuh bantuan Lintang. Dan Pak Slamet, tolong bawa Mas Joko, Mbak Romlah, serta Mbak Patmi menjauh. Syukur syukur bisa kembali ke desa."
"Tapi Bu, ..."
"Jangan membantah Pak. Waktu kita tidak banyak!" tegas Bu Ratih setengah membentak.
"Tapi Bu, ..."
"Jangan membantah Pak. Waktu kita tidak banyak!" tegas Bu Ratih setengah membentak.
"Eh, tapi ..."
"CEPAT!" kali ini Bu Ratih benar benar membentak.
"I ..., iya ..."
Pak Slamet segera mengajak Mas Joko, Mbak Romlah, dan Mbak Patmi menjauh dari tempat itu. Mereka berjalan setengah merayap untuk menghindari tiupan angin dahsyat yang bisa saja melukai mereka.
"CEPAT!" kali ini Bu Ratih benar benar membentak.
"I ..., iya ..."
Pak Slamet segera mengajak Mas Joko, Mbak Romlah, dan Mbak Patmi menjauh dari tempat itu. Mereka berjalan setengah merayap untuk menghindari tiupan angin dahsyat yang bisa saja melukai mereka.
"Lintang, kamu bantu ibu ya," bisik Bu Ratih kepada Lintang.
"Apa yang bisa kubantu Bu?" tanya Lintang.
Bu Ratih membisikkan sesuatu ke telinga Lintang. Anak itu terlihat mengangguk, tanda mengerti dengan apa yang dibisikkan oleh sang guru.
"Bu ....!"
"Apa yang bisa kubantu Bu?" tanya Lintang.
Bu Ratih membisikkan sesuatu ke telinga Lintang. Anak itu terlihat mengangguk, tanda mengerti dengan apa yang dibisikkan oleh sang guru.
"Bu ....!"
"Lho? Kenapa Bapak belum juga pergi?!" sentak Bu Ratih saat menyadari bahwa Pak Slamet masih merunduk di belakangnya.
"Saya tak mungkin meninggalkan ibu sendirian disini. Biar Mas Joko saja yang mengantarkan Mbak Romlah dan Mbak Patmi kembali ke desa." ujar Pak Slamet.
"Saya tak mungkin meninggalkan ibu sendirian disini. Biar Mas Joko saja yang mengantarkan Mbak Romlah dan Mbak Patmi kembali ke desa." ujar Pak Slamet.
"Isshh! Sial! Merepotkan saja!" gerutu Bu Ratih kesal. "Ya sudah! Bapak berlindung saja disini! Biar saya dan Lintang yang menyelamatkan Wulan!"
Pak Slamet hanya tersenyum masam sambil garuk garuk kepala. Belum pernah ia mendengar Bu Ratih berkata sekasar itu.
Pak Slamet hanya tersenyum masam sambil garuk garuk kepala. Belum pernah ia mendengar Bu Ratih berkata sekasar itu.
Sementara itu pertarungan sengit antara Wulan dan Ki Suryo masih terjadi. Ternyata laki laki tua itu lumayan tangguh juga. Meski tubuhnya sudah dipenuhi luka, namun gerakannya masih terlihat lincah. Jual beli serangan terjadi diantara keduanya.
Suara desingan angin semakin bergemuruh. Menerjang apa saja yang berada di dasar jurang itu. Beberapa pohon tercabut dan terlempar dari akarnya, bebatuan karang yang berada di dekat keduanya bertarungpun hancur berkeping keping.
Bahkan api mulai terlihat menjalar, membakar rumpun rumpun semak yang mengering. Bu Ratih mendongak ke atas, melihat bulan purnama yang berada tepat di tengah tengah cakrawala.
"Sekarang saatnya Tang. Kamu siap?" guru muda itu menoleh ke arah Lintang.
"Sekarang saatnya Tang. Kamu siap?" guru muda itu menoleh ke arah Lintang.
"Siap Bu." jawab anak itu pelan.
"Baiklah. Mari kita mulai. Pak Slamet jangan melihat kemari ya," Bu Ratih duduk bersila diatas tanah. Sejenak guru muda itu mengatur nafasnya, lalu pelan pelan tangannya melepas kancing kemeja yang dikenakannya.
"Baiklah. Mari kita mulai. Pak Slamet jangan melihat kemari ya," Bu Ratih duduk bersila diatas tanah. Sejenak guru muda itu mengatur nafasnya, lalu pelan pelan tangannya melepas kancing kemeja yang dikenakannya.
Diturunkan bagian bahu kemeja itu hingga sampai ke siku tangannya, hingga sebagian punggungnya yang berkulit putih mulus bak batu pualam itu terbuka.
Pak Slamet menelan ludah.
Pak Slamet menelan ludah.
Meski tadi Bu Ratih berpesan agar ia tak melihat, tapi rasa penasarannya membuat laki laki itu sedikit mencuri curi pandang. Dan apa yang dilihatnya, membuat kedua lutut laki laki itu bergetar.
Bukan! Bukan karena melihat kulit putih mulus punggung Bu Ratih yang membuat lutut Pak Slamet gemetar. Tapi karena melihat apa yang tercetak di punggung perempuan cantik itu.
"Itu kan ..." sedikit banyak Pak Slamet tahu.
"Itu kan ..." sedikit banyak Pak Slamet tahu.
Rajah di punggung Bu Ratih itu adalah susunan huruf jawa yang ditulis secara terbalik, diawali dengan huruf nga dan diakhiri dengan huruf ha.
Belum habis rasa heran Pak Slamet, Bu Ratih yang tak menyadari kalau sedang diperhatikan oleh Pak Slamet, kembali melakukan gerakan aneh.
Belum habis rasa heran Pak Slamet, Bu Ratih yang tak menyadari kalau sedang diperhatikan oleh Pak Slamet, kembali melakukan gerakan aneh.
Guru muda itu menggigit pergelangan tangannya sendiri. Kulit mulus di pergelangan tangan itu terkoyak. Darah mengucur membasahi tanah. Lintang segera menampung kucuran darah itu dengan kedua telapak tangannya, lalu mengoleskannya pada rajah yang ada di punggung Bu Ratih.
"Sang Hyang Candra! Bantu aku melepaskan segel ini!" desis Bu Ratih.
Sangat pelan suara Bu Ratih. Namun suaranya yang pelan itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Waktu seolah berhenti berputar. Angin berhenti bertiup.
Sangat pelan suara Bu Ratih. Namun suaranya yang pelan itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Waktu seolah berhenti berputar. Angin berhenti bertiup.
Alampun menjadi sangat sunyi. Tak ada suara apapun yang terdengar.
Pak Slamet kembali terperangah, saat melihat sinar bulan seolah tersedot kedalam rajah yang berada di punggung Bu Ratih.
Pak Slamet kembali terperangah, saat melihat sinar bulan seolah tersedot kedalam rajah yang berada di punggung Bu Ratih.
Tulisan rajah yang awalnya berwarna kemerahan itu kini seolah memancarkan cahaya keemasan, lalu secara perlahan rajah itu memudar, dan akhirnya lenyap seolah meresap masuk kedalam kulit Bu Ratih.
Bu Ratih bangkit. Waktu kembali berjalan. Alam kembali normal.
Bu Ratih bangkit. Waktu kembali berjalan. Alam kembali normal.
Desingan angin kembali melanda. Dan suara pertarungan di depan sana kembali terdengar.
Pelan Bu Ratih melangkah maju. Deru angin kencang yang mampu mengoyak segala yang diterpanya itu seolah tak berpengaruh pada perempuan itu.
Pelan Bu Ratih melangkah maju. Deru angin kencang yang mampu mengoyak segala yang diterpanya itu seolah tak berpengaruh pada perempuan itu.
"Wulan! Hentikan Nak! Cukup sampai disini saja!" seru Bu Ratih diantara suara desingan angin.
Cahaya putih berpendar yang berputar itu mulai melambat, seolah memahami ucapan Bu Ratih. Samar samar tubuh Wulan yang melayang mulai terlihat.
Cahaya putih berpendar yang berputar itu mulai melambat, seolah memahami ucapan Bu Ratih. Samar samar tubuh Wulan yang melayang mulai terlihat.
Matanya yang memancarkan sinar keputih putihan itu menatap tajam ke arah Bi Ratih.
"Bagus! Kau mendengarku Nak? Kemarilah! Peluk ibu Nak, dan sudahi semua ini," Bu Ratih mengulurkan kedua tangannya, seolah siap memeluk Wulan.
Pelan tubuh Wulanpun melayang turun.
"Bagus! Kau mendengarku Nak? Kemarilah! Peluk ibu Nak, dan sudahi semua ini," Bu Ratih mengulurkan kedua tangannya, seolah siap memeluk Wulan.
Pelan tubuh Wulanpun melayang turun.
Deru angin berangsur melambat. Udara panaspun kembali berangsur angsur menjadi sejuk. Bu Ratih tersenyum. Sepertinya rencananya berhasil. Namun diluar dugaan, Ki Suryo yang melihat Wulan sedikit lengah, tak mau menyia-nyiakan kesempatan.
Dengan sisa sisa tenaga yang dimilikinya, laki laki tua itu diam diam kembali melancarkan serangan, membokong Wulan dari belakang.
"Hiyaaaahhh...!!!" disertai teriakan lantang, Ki Suryo mengibaskan kedua tangannya, melontarkan dua bola api tepat ke arah Wulan.
"Hiyaaaahhh...!!!" disertai teriakan lantang, Ki Suryo mengibaskan kedua tangannya, melontarkan dua bola api tepat ke arah Wulan.
"Sial!" sentak Bu Ratih.
"PENGECUUUTTT ...!!!" Wulan kembali melayang naik, kedua tangannya menyambar bola api serangan dari Ki Suryo.
"PENGECUUUTTT ...!!!" Wulan kembali melayang naik, kedua tangannya menyambar bola api serangan dari Ki Suryo.
"KUBAKAR KALIAN SEMUAAA ...!!!" bola api di tangan Wulan semakin membesar & membesar, hingga menyelimuti seluruh tubuhnya,lalu dengan cepat tubuh yg telah terbungkus api itu kembali berputar cepat, melemparkan bola api bola api kecil ke segala arah,membakar semua yang ditimpanya.
Kebakaran hebatpun tak terelakkan. Semak semak terbakar. Pepohonan terbakar. Seluruh penjuru hutan, semua berkobar. Termasuk tubuh renta Ki Suryo. Dukun tua itu kini tumbang dengan tubuh hangus tak bernyawa.
"Lintang! Pak Slamet! Lariii ..!!! Selamatkan diri kalian!" teriak Bu Ratih sambil merentangkan kedua tangannya. Pelan tubuh guru muda itu juga melayang naik, lalu dengan cepat melesat menerjang tubuh Wulan yang masih berkobar.
"Wulan! Dengarkan ibu Nak! Sudahi semua ini!" bisik Bu Ratih sambil memeluk tubuh Wulan. Pelan namun pasti tubuh guru muda itu ikut berkobar terbungkus api.
Api dengan cepat menjalar, membakar apa saja yang dilandanya. Semak belukar, rerumputan, ranting dan dahan pohon, bahkan batang batang pepohonan berukuran raksasa, tak luput dari amukan Wulan yang terus saja melontarkan kobaran kobaran api ke segala penjuru hutan.
"Pak Slamet, cepat bawa Lintang pergi! Tinggalkan tempat ini!" teriak Bu Ratih tanpa menoleh.
"Tapi Bu ...."
"Cepat! Jangan membantah!"
"Bagaimana dengan rencana kita Bu?!" seru Lintang.
"Lupakan saja! Itu sudah tak ada gunanya!" Bu Ratih nampak merentangkan kedua tangannya,
"Tapi Bu ...."
"Cepat! Jangan membantah!"
"Bagaimana dengan rencana kita Bu?!" seru Lintang.
"Lupakan saja! Itu sudah tak ada gunanya!" Bu Ratih nampak merentangkan kedua tangannya,
lalu tiba tiba tubuhnya melesat keatas dan menerjang tubuh Wulan yang masih berkobar kobar diselimuti oleh api.
"Wulan! Maafkan ibu Nak! Tapi ibu tak bisa membiarkanmu membunuh lebih banyak orang lagi. Kalau memang masih ada yang harus mati, lebih baik kita berdua saja yang mati
"Wulan! Maafkan ibu Nak! Tapi ibu tak bisa membiarkanmu membunuh lebih banyak orang lagi. Kalau memang masih ada yang harus mati, lebih baik kita berdua saja yang mati
. Kita akhiri ini semua Nak!" Bu Ratih membisikkan kata kata itu ke telinga Wulan, sambil memeluk tubuh anak itu yang masih diselimuti oleh kobaran api. Air mata mulai mengalir dari kedua sudut mata Bu Ratih yang pelan pelan mulai terpejam.
Tubuh guru muda itu juga mulai berkobar diselimuti oleh api.
"Edan! Apa apaan ini?! BU RATIIIIHHHH ...!!!" Pak Slamet menjerit sambil melompat keluar dari balik batu besar tempatnya berlindung, bermaksud untuk menolong Bu Ratih.
"Edan! Apa apaan ini?! BU RATIIIIHHHH ...!!!" Pak Slamet menjerit sambil melompat keluar dari balik batu besar tempatnya berlindung, bermaksud untuk menolong Bu Ratih.
Namun kobaran api yang terlempar dari tubuh Wulan nyaris saja menyambarnya, andai saja Lintang tidak segera menarik lengan laki laki itu.
"Jangan gegabah Pak!" seru Lintang.
"Jangan gegabah Pak!" seru Lintang.
"Gegabah dhengkulmu itu! Kamu nggak lihat Bu Ratih terbakar seperti itu?! Aku harus segera menolongnya!" sentak Pak Slamet sambil mengucek ucek kepalanya. Ada sebagian rambutnya yang terbakar akibat sambaran api tadi.
Andai Lintang tak sigap menariknya tadi, mungkin sekarang kepala laki laki itu sudah gosong dilalap api.
"Saya tau Pak, tapi kita bisa apa? Bapak lihat sendiri, ada hujan api seperti itu. Seluruh penjuru hutan juga sudah terbakar.
"Saya tau Pak, tapi kita bisa apa? Bapak lihat sendiri, ada hujan api seperti itu. Seluruh penjuru hutan juga sudah terbakar.
Kita hanya akan mati konyol kalau nekat. Mungkin benar kata Bu Ratih. Kita harus cepat pergi dari sini," seru Lintang tak mau kalah.
"Arrrggghhh ...!!! Bodoh! Bodoh! Bodoh!" gusar Pak Slamet, sampai laki laki itu memukul mukul tanah tempatnya berpijak.
"Arrrggghhh ...!!! Bodoh! Bodoh! Bodoh!" gusar Pak Slamet, sampai laki laki itu memukul mukul tanah tempatnya berpijak.
"Kenapa di saat seperti ini aku justru menjadi pecundang? Andai ada yang bisa aku lakukan. Andai saja ...., eh, Lintang, apa yang kau maksud dengan rencana tadi?" Tiba tiba mata Pak Slamet berbinar, seolah ia telah mendapat ide cemerlang.
"Rencana?" Lintang mengerutkan keningnya, tak paham akan arah pembicaraan Pak Slamet.
"Kau bilang tadi soal rencana dengan Bu Ratih! Apa yang kalian berdua rencanakan?"
"Kau bilang tadi soal rencana dengan Bu Ratih! Apa yang kalian berdua rencanakan?"
"Oh, tadi Bu Ratih bilang, kalau ia telah berhasil membawa Wulan turun ke tanah, Bu Ratih menyuruhku untuk memakaikan kalung ini kepada Wulan."
"Kalung?" Pak Slamet menoleh ke arah Lintang. "Kalung apa?"
"Kalung?" Pak Slamet menoleh ke arah Lintang. "Kalung apa?"
"Kalung yang kupakai ini Pak," Lintang menunjukkan kalung benang lawe berbandul bungkusan kain kumal yang melingkar di lehernya.
"Kalung apa itu?" tanya Pak Slamet heran.
"Kalung apa itu?" tanya Pak Slamet heran.
"Aku juga nggak tau Pak, kata emakku sudah semenjak bayi aku memakai kalung ini. Katanya kalung ini bisa menjagaku dari ...."
"Aku ada ide," Pak Slamet memotong ucapan Lintang.
"Ide apa Pak?" tanya Lintang.
"Ya kalungmu itu, kita pakaikan saja kepada Wulan sekarang!"
"Aku ada ide," Pak Slamet memotong ucapan Lintang.
"Ide apa Pak?" tanya Lintang.
"Ya kalungmu itu, kita pakaikan saja kepada Wulan sekarang!"
"Bagaimana caranya Pak? Wulan masih melayang layang begitu. Terlalu tinggi, saya tak bisa meraihnya."
"Kamu mungkin tak bisa. Tapi aku bisa Tang!"
"Bagaimana caranya Pak?"
"Berikan saja kalung itu padaku!"
"Kamu mungkin tak bisa. Tapi aku bisa Tang!"
"Bagaimana caranya Pak?"
"Berikan saja kalung itu padaku!"
Lintang nampak masih sedikit ragu. Ditatapnya Pak Slamet dengan pandangan nanar.
"Kenapa malah menatapku seperti itu?" sentak Pak Slamet.
"Kamu nggak percaya sama bapak?"
"Kenapa malah menatapku seperti itu?" sentak Pak Slamet.
"Kamu nggak percaya sama bapak?"
"Bukannya tak percaya Pak, tapi tadi Bu Ratih bilang kalau aku harus memakaikan kalung ini kepada Wulan, hanya kalau Wulan sudah turun menginjak tanah. Dan kalung ini milikku Pak, jadi harus aku yang memakaikannya."
"Harus seperti itu ya?"
"Pesan Bu Ratih sih begitu Pak."
"Harus seperti itu ya?"
"Pesan Bu Ratih sih begitu Pak."
"Arrrggghhh ...!!!" Pak Slamet menggeram kesal sambil menggaruk garuk kepalanya. "Kalau aku yang memakaikan kalung itu kepada Wulan, apa rencana itu tak akan berhasil Tang?"
"Saya juga nggak tau Pak, tadi nggak sempat bertanya pada Bu Ratih!"
"Saya juga nggak tau Pak, tadi nggak sempat bertanya pada Bu Ratih!"
"Hmmm, begitu ya? Kalau begitu tak ada cara lain! Kita harus pancing Wulan agar mau turun ke tanah."
"Bagaimana caranya Pak?"
Pak Slamet membisikkan sesuatu ke telinga Lintang. Lintang sedikit terperanjat mendengar rencana Pak Slamet yang menurutnya sedikit konyol itu.
"Bagaimana caranya Pak?"
Pak Slamet membisikkan sesuatu ke telinga Lintang. Lintang sedikit terperanjat mendengar rencana Pak Slamet yang menurutnya sedikit konyol itu.
"Bapak yakin?"
"Ya. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana?"
"Emmm ..., bagaimana ya?" Lintang nampak berpikir sejenak.
"Jangan terlalu banyak mikir Tang! Lihat, Bu Ratih sudah hampir menjadi daging panggang tuh!" sentak Pak Slamet.
"Baiklah Pak. Mari kita coba."
"Ya. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana?"
"Emmm ..., bagaimana ya?" Lintang nampak berpikir sejenak.
"Jangan terlalu banyak mikir Tang! Lihat, Bu Ratih sudah hampir menjadi daging panggang tuh!" sentak Pak Slamet.
"Baiklah Pak. Mari kita coba."
"Bagus! Kamu tunggu disini ya. Sekarang giliranku untuk beraksi!" kata Pak Slamet mantab. Laki laki itu segera beranjak keluar dari tempat mereka berlindung. Kembali sambaran bola api menyambutnya, namun laki laki itu kini lebih waspada dan berhasil menghindar.
"Woooiiiiii ...!!! Wulan anaknya Mas Joko cucunya Mbah Kendhil gondhal gandhil ...!!! Lihat! Aku disini! Kau marah kan?! Kau ingin membakar orang kan?! Ayo, bakar aku kalau kau bisa, biar ...!!!"
"Whuuuusssss ...!!!" sebentuk bola api terlempar dari sosok Wulan yang masih melayang dan berputar putar di udara, mengarah tepat kepada Pak Slamet.
"Hait ...!" dengan sigap Pak Slamet melompat menghindar.
"Hait ...!" dengan sigap Pak Slamet melompat menghindar.
"Yeeeee ...!!! Nggak kena! Nggak kena!!!" Pak Slamet menari nari kegirangan seperti anak kecil. "Ayo, serang lagi! Bakar aku kalau bisa! Mendekat kemari kalau berani!"
"Whuuusss ...!!! Whuuussss ...!!!" kini dua buah bola api yang melesat menerjang Pak Slamet.
"Whuuusss ...!!! Whuuussss ...!!!" kini dua buah bola api yang melesat menerjang Pak Slamet.
Dan kembali laki laki itu berhasil menghindar.
"Hahahaha ...!!! Nggak kena!!! Nggak kena!!! Weeeekkkkk ...!!!" Pak Slamet berjingkrak jingkrak sambil menjulurkan lidahnya.
"Ayo! Serang lagi! Mendekat kemari! Jangan beraninya dari kejauhan!"
"Hahahaha ...!!! Nggak kena!!! Nggak kena!!! Weeeekkkkk ...!!!" Pak Slamet berjingkrak jingkrak sambil menjulurkan lidahnya.
"Ayo! Serang lagi! Mendekat kemari! Jangan beraninya dari kejauhan!"
"Whuusss ...!!! Whuuusss ...!!! Whuuusss ...!!!" geram, kini Wulan menghujani Pak Slamet dengan kobaran kobaran api dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Namun laki laki itu cukup lincah juga ternyata.
Ia berhasil menghindari serangan itu sambil terus berjoget joget dan berjingkrak jingkrak.
"Hahaha ....!!! Nggak kena woooyyy ...!!!" kini Pak Slamet membungkuk membelakangi Wulan sambil menepuk nepuk pantatnya, berusaha memancing anak yang sedang dilanda amarah itu.
"Hahaha ....!!! Nggak kena woooyyy ...!!!" kini Pak Slamet membungkuk membelakangi Wulan sambil menepuk nepuk pantatnya, berusaha memancing anak yang sedang dilanda amarah itu.
Dan karena posisi Pak Slamet yang membelakangi Wulan itu, membuat laki laki itu sedikit lengah. Wulan yang merasa sangat dilecehkan, tiba tiba melesat cepat menerjang ke arah Pak Slamet, membawa serta tubuh Bu Ratih yang masih tetap memeluknya.
"Pak Slamet ...!!! Awaaaasssss ....!!!" teriak Lintang dari balik batu besar tempatnya berlindung.
Pak Slamet menoleh, dan matanya terbelalak seketika begitu melihat serangan Wulan yang menerjang ke arahnya dengan sangat cepat. Refleks laki laki itu mencoba berkelit.
Pak Slamet menoleh, dan matanya terbelalak seketika begitu melihat serangan Wulan yang menerjang ke arahnya dengan sangat cepat. Refleks laki laki itu mencoba berkelit.
Tapi terlambat. Meski tubuh Wulan yang berkobar itu tak mengenainya dengan telak, namun tak urung api sempat menyambar dan membakar celananya di bagian pantat.
"Aaaaaaarrrrgggghhhh ...!!! Panaaaassss ...!!! Panaaassss ...!!! Lintaaannggg..., lakukan sekaraaaannngggg...!!! Cepaaattt ...!!!" Pak Slamet berteriak lantang sambil beguling guling diatas rerumputan, berusaha memadamkan api yang membakar pantatnya.
Lintang tanggap dengan tugasnya. Anak itu segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya, sambil melepas kalung yang dipakainya.
Ia tak tahu persis mana tubuh Wulan dan mana tubuh Bu Ratih, karena keduanya masih diselimuti oleh api yang berkobar kobar dengan posisi saling berpelukan.
Lintang menggenggam erat kalung itu. Matanya menatap nanar kearah dua sosok berkobar yang saling berpelukan itu.
Lintang menggenggam erat kalung itu. Matanya menatap nanar kearah dua sosok berkobar yang saling berpelukan itu.
Sepertinya sosok itu kembali hendak menerjang Pak Slamet.
"Wulan!!! Kau masih ingat denganku?!" seru Lintang sambil melangkah mendekat ke arah sosok berkobar itu.
"Aku Lintang, sahabatmu Lan! Kita teman! Apa yang kau rasakan, aku juga ikut merasakan!
"Wulan!!! Kau masih ingat denganku?!" seru Lintang sambil melangkah mendekat ke arah sosok berkobar itu.
"Aku Lintang, sahabatmu Lan! Kita teman! Apa yang kau rasakan, aku juga ikut merasakan!
Jika kau menderita saat ini, bagilah penderitaan itu denganku, sahabatmu ini! Jangan kau simpan deritamu seorang diri Lan! Jika kau merasakan panasnya dendam dengan api yang membungkus tubuhmu itu, aku juga berhak merasakannya! Mendekatlah kemari!
Peluk aku Lan! Agar aku juga merasakan apa yang kau rasakan!"
Kata kata Lintang sepertinya sedikit berpengaruh terhadap Wulan. Sosoknya yang berkobar itu kini terdiam, mengurungkan niatnya untuk kembali menyerang Pak Slamet. Lintang merasa, sosok itu kini menatap ke arahnya.
Kata kata Lintang sepertinya sedikit berpengaruh terhadap Wulan. Sosoknya yang berkobar itu kini terdiam, mengurungkan niatnya untuk kembali menyerang Pak Slamet. Lintang merasa, sosok itu kini menatap ke arahnya.
Terdengar geraman lirih, lalu sosok itu melengos, beranjak menjauh dari Lintang dan kembali melayang ke udara.
"Arrrggghhh ...!!!" sosok itu menggeram, saat niatnya untuk kembali terbang seolah tertahan. Samar samar, dari dalam kobaran api itu memancar cahaya keemasan.
"Arrrggghhh ...!!!" sosok itu menggeram, saat niatnya untuk kembali terbang seolah tertahan. Samar samar, dari dalam kobaran api itu memancar cahaya keemasan.
Awalnya samar samar, lalu semakin lama semakin jelas dan terang.
"Lakukan sekarang Tang! Ibu hanya bisa menahannya sebentar!" terdengar rintihan suara Bu Ratih dari balik kobaran api itu.
"Lakukan sekarang Tang! Ibu hanya bisa menahannya sebentar!" terdengar rintihan suara Bu Ratih dari balik kobaran api itu.
Lintang tersadar. Kini ia tahu, mana sosok Wulan dan mana sosok Bu Ratih. Segera anak itu berlari mendekat ke arah dua sosok berkobar yang saling berpelukan itu,
dan mengalungkan kalung benang lawe berbandul bungkusan kain kumal itu ke leher sosok berkobar yang tak memancarkan cahaya keemasan.
Terdengar suara rintihan lirih, diiringi bunyi gemeretak seperti kobaran api yang tersiram air.
Terdengar suara rintihan lirih, diiringi bunyi gemeretak seperti kobaran api yang tersiram air.
Kobaran api yang menyelimuti kedua tubuh itu kian memudar, lalu perlahan lahan padam, menyisakan dua sosok tubuh perempuan yang saling berpelukan, yang pelan pelan terhuyung lalu roboh ke tanah.
"Wulan! Bu Ratih!" hampir serempak Lintang dan Pak Slamet menghambur mendekati kedua sosok itu.
"Astaghfirullah!!!" Pak Slamet berseru sambil buru buru melepas baju dan celana jeans yang dikenakannya.
"Astaghfirullah!!!" Pak Slamet berseru sambil buru buru melepas baju dan celana jeans yang dikenakannya.
Kini, laki laki itu nyaris telanjang, hanya tersisa celana kolor yang bolong pada bagian pantatnya yang membungkus tubuhnya. Dengan buru buru juga laki laki itu segera memakaikan baju dan celana jeans miliknya pada tubuh Bu Ratih yang kini benar benar telanjang bulat,
tanpa ada sehelai benangpun yang menutupi tubuhnya. Sepertinya pakaian perempuan itu telah habis dilalap api. Tapi Pak Slamet bersyukur, tak ada luka yang serius di tubuh guru muda itu.
"Bagaimana ini Pak?" isak Lintang cemas, melihat Wulan dan Bu Ratih yang tergeletak diam tak bergerak.
"Tenang Tang. Sepertinya mereka hanya pingsan. Kita berhasil Tang. Semua sudah selesai. Ayo, kita sadarkan mereka, lalu kita pulang," desah Pak Slamet lega.
"Tenang Tang. Sepertinya mereka hanya pingsan. Kita berhasil Tang. Semua sudah selesai. Ayo, kita sadarkan mereka, lalu kita pulang," desah Pak Slamet lega.
"Syukurlah kalau begitu Pak. Boleh kulepas kalung ini sekarang Pak?" tanya Lintang.
"Kenapa?" Pak Slamet balik bertanya.
"Kata emakku, aku tak boleh terlalu lama melepas kalung ini dari leherku."
"Kenapa?" Pak Slamet balik bertanya.
"Kata emakku, aku tak boleh terlalu lama melepas kalung ini dari leherku."
"Ah, iya. Sepertinya nggak papa Tang. Coba saja kau lepas," ujar Pak Slamet sambil merogoh saku celananya yang kini telah terpakai di tubuh Bu Ratih.
"Apa yang bapak lakukan?" tanya Lintang heran, sambil melepas kalung di leher Wulan dan kembali mengenakannya di lehernya.
"Apa yang bapak lakukan?" tanya Lintang heran, sambil melepas kalung di leher Wulan dan kembali mengenakannya di lehernya.
"Sepertinya aku menyimpan balsem di ..., nah, ketemu," Pak Slamet mengeluarkan sebotol kecil balsem dari saku celana jeans itu. "Mudah mudahan ini bisa menyadarkan mereka."
Ah, dasar orang tua, ledek Lintang dalam hati. Ada untungnya juga keman mana dia selalu bawa balsem.
Ah, dasar orang tua, ledek Lintang dalam hati. Ada untungnya juga keman mana dia selalu bawa balsem.
Pak Slamet segera mengoleskan balsem di kedua lubang hidung Bu Ratih dan Wulan. Tak lama, kedua tubuh itu mulai menggeliat sadar. Dan ....
"Aaaaaaaaa ....!!!" Bu Ratih menjerit sambil menutupi kedua matanya dengan telapak tangan, saat melihat Pak Slamet yang nyaris telanjang berjongkok di hadapannya.
"Eh, tenang Bu, tak apa, ini hanya ...."
"Pak, apa yang sampeyan lakukan? Kenapa ...."
"Eh, tenang Bu, tak apa, ini hanya ...."
"Pak, apa yang sampeyan lakukan? Kenapa ...."
"Ndak papa Bu! Maaf, saya terpaksa, pakaian saya ..., pakaian saya, sementara saya pinjamkan dulu buat Bu Ratih. Soalnya tadi ....,"
Bu Ratih tertegun, lalu memperhatikan tubuhnya yang memang kini telah terbalut pakaian milik Pak Slamet.
Bu Ratih tertegun, lalu memperhatikan tubuhnya yang memang kini telah terbalut pakaian milik Pak Slamet.
Perempuan itu lalu menatap ke arah Pak Slamet dengan tajam.
"Jadi?"
"Iya, pakaian ibu habis terbakar tadi, jadi terpaksa saya ....!!!"
"Siapa yang memakaikan pakaian ini padaku?" dengus Bu Ratih.
"Jadi?"
"Iya, pakaian ibu habis terbakar tadi, jadi terpaksa saya ....!!!"
"Siapa yang memakaikan pakaian ini padaku?" dengus Bu Ratih.
"Eh, it ..., itu, Lintang. Iya, Lintang yang tadi memakaikan Bu. Iya kan Tang?" jawab Pak Slamet gugup, sambil memberi kode kepada Lintang dengan kedipan mata.
"Eh, anu Bu, iya, saya yang tadi memakaikan pakaian itu," seru Lintang gugup. "Maaf kalau saya lancang, karena ...."
"Eh, anu Bu, iya, saya yang tadi memakaikan pakaian itu," seru Lintang gugup. "Maaf kalau saya lancang, karena ...."
Bu Ratih hanya mendengus keras dengan wajah memerah. Entah karena kesal atau malu. Sedangkan Wulan yang juga sudah sadar nampak masih terbengong sambil melihat ke sekelilingnya.
"Lho, Lintang, Pak Slamet, Bu Ratih, kita dimana?
"Lho, Lintang, Pak Slamet, Bu Ratih, kita dimana?
Kenapa semua terbakar seperti ini?" tanya anak itu bingung.
"Nggak papa Wulan. Kita ..., kita tadi sedang jalan jalan, lalu tersesat di hutan yang terbakar. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini, sebelum api semakin membesar," jawab Pak Slamet.
"Nggak papa Wulan. Kita ..., kita tadi sedang jalan jalan, lalu tersesat di hutan yang terbakar. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini, sebelum api semakin membesar," jawab Pak Slamet.
"Kamu kenapa Lintang?" Wulan menatap ke arah sahabatnya itu.
"Eh, iya, kamu kenapa Tang?" Pak Slamet juga ikut bertanya heran, melihat Lintang memegangi bandul kalung yang dipakainya. Wajah anak itu terlihat sedikit tegang.
"Eh, iya, kamu kenapa Tang?" Pak Slamet juga ikut bertanya heran, melihat Lintang memegangi bandul kalung yang dipakainya. Wajah anak itu terlihat sedikit tegang.
"Eeee ..., saya merasakan firasat yang tak enak Pak. Seperti ada ...."
"HIHIHIHIHIHI ...!!! KAU MILIKKU SEKARAAANNNNGGG ...!!!" belum selesai Lintang bicara,
"HIHIHIHIHIHI ...!!! KAU MILIKKU SEKARAAANNNNGGG ...!!!" belum selesai Lintang bicara,
tiba tiba terdengar suara tawa mengikik, di sertai kelebatan bayangan hitam yang terbang dari atas pohon dan menyambar tubuh Wulan, membawa tubuh anak itu terbang menjauh.
"WULAAAANNNN ....!!!"
"WULAAAANNNN ....!!!"
hampir serempak Bu Ratih, Lintang, dan Pak Slamet berteriak dan mengejar sosok itu. Namun gerakan sosok hitam itu sangat cepat. Ia membawa Wulan terbang semakin tinggi, hingga menghilang dari pandangan ketiga orang itu.
"Sial! Kenapa bisa ....!"
"Sial! Kenapa bisa ....!"
"Bu Ratih! Lihat!" seru Lintang memotong ucapan Bu Ratih. Guru muda itu segera mendongak, mengikuti arah telunjuk Lintang.
"Apa itu?" Pak Slamet bergumam heran, melihat pemandangan ganjil diatas sana. Setitik cahaya terang nampak berputar putar tak tentu arah.
"Apa itu?" Pak Slamet bergumam heran, melihat pemandangan ganjil diatas sana. Setitik cahaya terang nampak berputar putar tak tentu arah.
Semakin lama titik cahaya itu semakin jelas dan membesar, untuk kemudian terpecah menjadi dua. Satu melesat ke arah kiri, membentuk gumpalan cahaya kemerahan yang semakin membesar, sedang satunya lagi melesat ke arah kanan, berubah menjadi kobaran api berbentuk tubuh manusia.
"Sial! Jangan lagi ...!"
"Wulaaannn ....!"
"Hahaha ...!!!" terdengar suara tawa anak perempuan yang menggema di atas sana. "Kau salah Nenek peot! Kau yang justru menjadi mainanku sekarang!"
"Wulaaannn ....!"
"Hahaha ...!!!" terdengar suara tawa anak perempuan yang menggema di atas sana. "Kau salah Nenek peot! Kau yang justru menjadi mainanku sekarang!"
kobaran api berbentuk tubuh manusia itu kembali melesat, menerjang gumpalan cahaya kemerahan yang juga melesat menyambut serangan si bola api.
Dentuman keras terdengar, saat kedua sosok itu saling berbenturan di angkasa.
Dentuman keras terdengar, saat kedua sosok itu saling berbenturan di angkasa.
Percikan percikan api dan kilatan kilatan cahaya kemerahan berterbangan memenuhi angkasa malam yang temaram. Suara jeritan dan tawa melengking menggema ke seluruh penjuru cakrawala.
"Sial! Sial! Sial! Sia sia usaha kita meredam kekuatan Wulan tadi! Dia semakin tak terkendali sekarang!" geram Bu Ratih sambil meninju batang pohon yang ada di dekatnya.
"Apa yang bisa kita lakukan sekarang Bu?" Pak Slamet bertanya pelan sambil terus mengawasi kedua sosok yang saling sambar diatas sana.
"Tak ada lagi yang bisa kita lakukan Pak. Dengan keadaan Wulan yang seperti sekarang ini, kalung Lintangpun sepertinya tak akan bisa membantu lagi." desis Bu Ratih.
"Lalu?!"
"Lalu?!"
"Kita tunggu saja, apa yang akan terjadi selanjutnya. Mudah mudahan hal buruk tak sampai terjadi terhadap Wulan."
"Hal buruk?! Hal buruk seperti apa maksud ibu?"
"Ibarat sebuah balon yang terus menerus diisi angin dengan tekanan tinggi, menurut bapak apa yang akan terjadi?"
"Hal buruk?! Hal buruk seperti apa maksud ibu?"
"Ibarat sebuah balon yang terus menerus diisi angin dengan tekanan tinggi, menurut bapak apa yang akan terjadi?"
"Eh, balon itu akan meletus?"
"Ya, seperti itu yang akan terjadi pada Wulan!"
"Jadi ....?!"
"Bu Ratih! Pak Slamet! Awaaaassss....!!!" Lintang tiba tiba berteriak, saat melihat sosok kobaran api itu menyambar sosok cahaya kemerahan dan membawanya melesat cepat ke arah mereka.
"Ya, seperti itu yang akan terjadi pada Wulan!"
"Jadi ....?!"
"Bu Ratih! Pak Slamet! Awaaaassss....!!!" Lintang tiba tiba berteriak, saat melihat sosok kobaran api itu menyambar sosok cahaya kemerahan dan membawanya melesat cepat ke arah mereka.
"Gawat! Cepat menghindar!" teriak Bu Ratih sambil melompat menjauh dari tempat itu. Pak Slamet dan Lintangpun melakukan gerakan yang sama.
"JEDHUUUAAAARRRRR ...!!!" kembali ledakan keras terdengar saat kedua sosok terang itu menghantam sebuah pohon besar.
"JEDHUUUAAAARRRRR ...!!!" kembali ledakan keras terdengar saat kedua sosok terang itu menghantam sebuah pohon besar.
"KRAAAKKKK ...!!!"
"BRUUUSSHHHH ...!!!" "WHUUUSSSS ...!!!"Batang pohon seukuran drum minyak itupun tumbang dan terbakar.
"Kurang ajar! Beraninya kau ...!" sosok cahaya kemerahan itu kini memudar, berubah menjadi sosok nenek tua menyeramkan yang terkapar diatas tanah.
"BRUUUSSHHHH ...!!!" "WHUUUSSSS ...!!!"Batang pohon seukuran drum minyak itupun tumbang dan terbakar.
"Kurang ajar! Beraninya kau ...!" sosok cahaya kemerahan itu kini memudar, berubah menjadi sosok nenek tua menyeramkan yang terkapar diatas tanah.
Sedang kobaran api berbentuk tubuh manusia itu juga kian meredup, menampakkan tubuh Wulan yang sedikit terhuyung ke belakang beberapa langkah. Lintang tercekat saat melihat darah segar mengalir dari sudut bibir dan kedua lubang hidung Wulan.
"Hihihi ...!!! Kenapa Nek? Masih ingin bermain main denganku?" dengan langkah tertatih Wulan mendekati sosok nenek tua yang tengah berusaha bangkit berdiri itu.
"Anak kurang ajar! Kubunuh kau!" teriak nenek tua itu sambil melesak maju.
"Anak kurang ajar! Kubunuh kau!" teriak nenek tua itu sambil melesak maju.
Tangannya yang berkuku runcing tajam itu mengarah lurus ke arah Wulan yang masih terus melangkah maju, seolah tak mengindahkan serangan itu.
"Jreeebbb ...!!!" tak ayal, kuku kuku runcing tajam di jari si nenek tua itu mendarat tepat di dada Wulan, menusuk hingga tembus sampai ke punggungnya. Daras segar mengalir deras dari ujung kuku kuku itu.
"Wulaaannn ...!!!" Lintang menjerit menyaksikan kejadian itu.
"Wulaaannn ...!!!" Lintang menjerit menyaksikan kejadian itu.
"Diam! Jangan mendekat kesana! Berbahaya Tang!" Bu Ratih menahan lengan Lintang yang bermaksud untuk mendekat ke arena pertarungan.
"Tapi Bu, Wulan ...." Lintang terisak, tak sanggup lagi menahan air matanya.
"Tapi Bu, Wulan ...." Lintang terisak, tak sanggup lagi menahan air matanya.
"Coba kau lihat kesana," Bu Ratih menunjuk ke arah Wulan yang kini diam tertunduk dengan kuku kuku jemari si nenek yang masih menancap di dadanya.
"Hihihi ...!!!" Wulan tertawa sambil mengangkat wajahnya. "Kau pikir semudah itu untuk menghabisiku Nek? Sekarang giliranku!"
"Hihihi ...!!!" Wulan tertawa sambil mengangkat wajahnya. "Kau pikir semudah itu untuk menghabisiku Nek? Sekarang giliranku!"
Pelan tangan Wulan terangkat, menggenggam pergelangan tangan si nenek yang masih menancapkan kuku kuku tajamnya di tubuhnya.
"Arrrrggghhh ...!!! Apa yang kau lakukan?!" si nenek mengerang, saat Wulan pelan pelan menarik tangan si nenek,
"Arrrrggghhh ...!!! Apa yang kau lakukan?!" si nenek mengerang, saat Wulan pelan pelan menarik tangan si nenek,
hingga kuku kuku tajam yang menghunjam di tubuhnya terlepas. Bekas luka tusukan itu pelan pelan kembali mengatup, lalu menghilang tanpa meninggalkan bekas sama sekali.
"Apa yang ingin kulakukan?!" Wulan tersenyum sinis. "Tentu saja melanjutkan permainan ini Nek."
"Apa yang ingin kulakukan?!" Wulan tersenyum sinis. "Tentu saja melanjutkan permainan ini Nek."
"Kau ...! Arrrrggghhhh ...!!!" si nenek menggeram keras saat tiba tiba Wulan mengibaskan tangannya. Tubuh nenek tua itupun terlempar beberapa depa, menghantam sebuah batu besar hingga batu itu hancur berkeping keping.
"Malam ini kita tuntaskan dendam kita Nek!" Wulan melesat menerjang tubuh si nenek yang baru saja hendak bangkit berdiri, membuat si nenek kembali terpental beberapa depa ke belakang.
"Arrrggghhh ...!!!" geram si nenek keras.
"Arrrggghhh ...!!!" geram si nenek keras.
"Dendammu terhadap kakek moyangku!" Wulan kembali menerjang
"Ahhhhkkkkhhh ...!" si nenek kembali jatuh terhumbalang.
"Dan dendamku padamu karena kau telah memakan ari ariku saat aku lahir dulu!"
"Dhuaggkkhhh ...!!!" tendangan Wulan mendarat di dada si nenek.
"Ahhhhkkkkhhh ...!" si nenek kembali jatuh terhumbalang.
"Dan dendamku padamu karena kau telah memakan ari ariku saat aku lahir dulu!"
"Dhuaggkkhhh ...!!!" tendangan Wulan mendarat di dada si nenek.
"Huuuggghhh ...!!!" si nenek mendelik sambil mendekap dadanya.
"Kita selesaikan semuanya malam ini!"
"Bhuagghhkkk ...!!!" kembali kaki Wulan menyapu tubuh si nenek.
"Heeegggkkkhhh ...!!!" tubuh nenek gombel terlempar menghantam batang pohon.
"Aku akan mengadu jiwa denganmu!"
"Kita selesaikan semuanya malam ini!"
"Bhuagghhkkk ...!!!" kembali kaki Wulan menyapu tubuh si nenek.
"Heeegggkkkhhh ...!!!" tubuh nenek gombel terlempar menghantam batang pohon.
"Aku akan mengadu jiwa denganmu!"
"Bhuaaakkhhh ...!!!" kembali Wulan menerjang, kini kepalan tangannya mendarat tepat di dada si nenek.
"Hoeeekkkhhhh ...!!!" darah kental kehitaman muncrat dari mulut si nenek.
"Kita tentukan, siapa yang akan musnah malam ini!"
"Hoeeekkkhhhh ...!!!" darah kental kehitaman muncrat dari mulut si nenek.
"Kita tentukan, siapa yang akan musnah malam ini!"
"Dhuaagghhkkkk ...!!!" "Khraakkk ...!!!" terdengar suara berderak dari tulang tulang yang berpatahan, saat Wulan menghujani tubuh si nenek dengan tendangan dan pukulan.
"Hiaaaaahhhh ...!!!"
"Akkkhhhkkk ...!!!"
"Whuuuussss ...!!!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaa ...!!!"
"Hiaaaaahhhh ...!!!"
"Akkkhhhkkk ...!!!"
"Whuuuussss ...!!!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaa ...!!!"
Jeritan melengking mengakhiri pertarungan itu. Nyaris tak ada perlawanan yang berarti dari si nenek gombel. Serangan serangan balasan dari nenek itu seolah tak berpengaruh pada tubuh Wulan.
Beberapa kali kuku kuku tajamnya berhasil mencabik dan menusuk tubuh Wulan, namun luka luka yang dihasilkan oleh kuku kuku tajam itu dengan cepat kembali merapat dan hilang tak berbekas. Sedangkan Wulan dengan brutalnya terus melancarkan serangan serangan yang bertubi tubi.
Ia memukul, menendang, mencakar, membanting, melempar, menginjak injak, dan mencabik cabik tubuh si nenek gombel tanpa ampun lagi, sambil mulutnya tak henti hentinya mencaci maki dan mengumpat.
Anak itu seolah telah dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan yang bersemayam di dalam tubuhnya. Badannya yang kecil mungil mampu mengombang ambingkan tubuh si nenek gombel yang ukurannya jauh lebih besar darinya.
Lintang, Bu Ratih, dan Pak Slamet, bertiga mereka menundukkan kepala, tak sanggup menyaksikan kebrutalan Wulan malam itu. Sosok si wewe gombel sudah tak berbentuk kini.
Tercabik cabik dan terpotong potong menjadi onggokan daging cincang, yg kemudian hangus menjadi abu saat Wulan membakar onggokan daging itu dgn kobaran api yang keluar dari mulutnya.
"Benarkah ... itu Wulan Bu?" desah Lintang yang menyembunyikan wajahnya dalam pelukan Bu Ratih.
"Benarkah ... itu Wulan Bu?" desah Lintang yang menyembunyikan wajahnya dalam pelukan Bu Ratih.
"Entahlah Tang! Ibu berharap, dia masih tetap Wulan, sahabatmu dan juga murid ibu," Bu Ratih mengusap pelan kepala Lintang.
Sedang matanya tak lepas menatap ke arah Wulan yang kini melangkah terhuyung huyung ke arah mereka sambil tertawa lantang dan menunjuk ke arah mereka bertiga, seolah hendak merayakan kemenangannya, sekaligus mengancam mereka bertiga.
"Hahaha, kini giliran kalian! Kalian yang telah berani mencoba mengekangku! Kalian ju ..., ga a ...,kan ...., Bruuukkkk ...!!!" tubuh anak perempuan berusia sebelas tahun itu roboh ke tanah, tertelungkup dan tak bergerak gerak lagi.
"Wulaaannnn ...!!!" Lintang menjerit histeris, melepaskan diri dari pelukan Bu Ratih, lalu menghambur ke arah Wulan yang sudah tergeletak tak berdaya.
"Pak, ayo kita bantu Wulan," kata Bu Ratih sambil bergegas mengikuti Lintang.
"Pak, ayo kita bantu Wulan," kata Bu Ratih sambil bergegas mengikuti Lintang.
"Pak?!" Bu Ratih menghentikan langkahnya, saat sadar tak mendapat jawaban dari Pak Slamet.
"Se ..., seben ..., tar ..., Bu. Hoeeekkkk !!!" Pak Slamet membungkuk di bawah pohon sambil memegangi perutnya. Ditumpahkannya seluruh isi perutnya di pangkal pohon itu.
"Se ..., seben ..., tar ..., Bu. Hoeeekkkk !!!" Pak Slamet membungkuk di bawah pohon sambil memegangi perutnya. Ditumpahkannya seluruh isi perutnya di pangkal pohon itu.
"Bapak kenapa?" tanya Bu Ratih heran.
"Sssss ..., saya ..., ndak sanggup me ..., lihat ..., Hoeeeekkkkk ....!!!" lagi lagi Pak Slamet memuntahkan semua isi perutnya.
"Sssss ..., saya ..., ndak sanggup me ..., lihat ..., Hoeeeekkkkk ....!!!" lagi lagi Pak Slamet memuntahkan semua isi perutnya.
"Ish, dasar payah!" gerutu Bu Ratih dalam hati, sambil kembali mendekat ke arah Lintang yang kini telah menangis histeris sambil mengguncang guncang tubuh Wulan.
"Wulaaannn ...!!! Bangun Lan! Ini aku Lintang, sahabatmu! Buka matamu Lan! Jangan ... jangan ... huuuuu ...! huuu ...! huuu ...!" Lintang merengkuh dan memeluk tubuh Wulan yang masih saja diam tak bergerak.
Dari sudut bibir, lubang hidung, dan telinga anak perempuan itu masih mengalir darah kental kehitaman.
"Wulaaaannnn ...!!! Jangan ..., kau tega Lan, kau ...! Arrrggghhhh ....!!!"
"Tang, sudah nak, tak perlu kau tangisi," Bu Ratih menyentuh lembut bahu Lintang.
"Wulaaaannnn ...!!! Jangan ..., kau tega Lan, kau ...! Arrrggghhhh ....!!!"
"Tang, sudah nak, tak perlu kau tangisi," Bu Ratih menyentuh lembut bahu Lintang.
Suaranya terdengar serak. Guru muda itu sepertinya juga sudah tak sanggup lagi menahan air matanya.
"Wulan Bu, Wulan! Tak bisakah Bu Ratih menolong Wulan?!" Lintang meratap disela isak tangisnya.
"Wulan Bu, Wulan! Tak bisakah Bu Ratih menolong Wulan?!" Lintang meratap disela isak tangisnya.
"Tentu ibu akan membantunya Nak, semampu yang ibu bisa. Sini, biar ibu coba," Bu Ratih ikut berjongkok, lalu menyentuh lembut pergelangan tangan Wulan. Ada senyum tipis mengembang di bibirnya, saat ia merasakan masih ada denyut nadi di lengan anak itu, meski sudah sangat lemah.
Guru muda itu lalu duduk bersimpuh, lalu menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung gadis kecil itu.
"Mudah mudahan ini bisa sedikit membantumu Nak," bisik Bu Ratih dalam hati, sambil memejamkan kedua kelopak matanya.
"Mudah mudahan ini bisa sedikit membantumu Nak," bisik Bu Ratih dalam hati, sambil memejamkan kedua kelopak matanya.
Ia memusatkan konsentrasinya, mencoba menyalurkan energi yang dimilikinya ke tubuh Wulan. Hawa hangat mulai terasa menjalar di kedua telapak tangannya, merasuk pelan pelan ke tubuh Wulan yang masih terkulai dalam pelukan Lintang.
Hembusan nafas guru muda itu mulai terdengar sedikit memburu, saat ia memaksakan diri untuk menyalurkan sisa energi yang masih dimilikinya. Keringat dingin mengalir deras di dahi dan pelipisnya. Tenaganya sudah benar benar terkuras habis saat berusaha meredam amukan Wulan tadi.
Dan disaat tubuh Wulan mulai menggeliat, maka disaat itu juga tubuh Bu Ratih ambruk tak sadarkan diri.
"Bu ..., eh, Wulan?!" Lintang bingung, antara ingin menolong Bu Ratih atau Wulan. Beruntung Pak Slamet segera datang menolong guru muda itu.
"Bu ..., eh, Wulan?!" Lintang bingung, antara ingin menolong Bu Ratih atau Wulan. Beruntung Pak Slamet segera datang menolong guru muda itu.
Jadi Lintang kini bisa fokus untuk menolong Wulan yang telah tersadar.
"Wulan, syukurlah, kau sudah ...."
"Plakkkk ...!!!" Wulan tiba tiba mendorong tubuh Lintang yang sedang memeluknya, lalu menampar pipi anak itu dengan sangat keras.
"Wulan, syukurlah, kau sudah ...."
"Plakkkk ...!!!" Wulan tiba tiba mendorong tubuh Lintang yang sedang memeluknya, lalu menampar pipi anak itu dengan sangat keras.
"Apa yang kau lakukan Tang?! Beraninya kau memelukku!" sentak anak itu kasar. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terhuyung dan nyaris terjerembab andai saja Lintang tak segera menangkap lengannya.
"Jangan berdiri dulu Lan, kau masih lemah," Lintang membantu Wulan untuk duduk bersandar di batang pohon, lalu mengelus pipinya yang memerah bekas kena tamparan Wulan.
"Lemah? Aku kenapa Tang? Kenapa badanku sakit semua? Kenapa wajahku berdarah darah seperti ini? Dan itu, Bu Ratih ...."
"Tak apa Lan, semua baik baik saja. Kita akan segera pulang," bisik Lintang sambil ikut bersandar di batang pohon.
"Tak apa Lan, semua baik baik saja. Kita akan segera pulang," bisik Lintang sambil ikut bersandar di batang pohon.
"Kepalaku sangat pusing Tang," rintih Wulan sambil memijit mijit pelipisnya.
"Pejamkan saja matamu, lalu bernafas pelan pelan, biar pusingnya hilang. Aku bantu Pak Slamet dulu ya, kamu tunggu disini saja," Lintang bangkit,
"Pejamkan saja matamu, lalu bernafas pelan pelan, biar pusingnya hilang. Aku bantu Pak Slamet dulu ya, kamu tunggu disini saja," Lintang bangkit,
lalu beranjak mendekati Pak Slamet yang masih sibuk menyadarkan Bu Ratih.
"Bagaimana Pak?" tanya Lintang sambil ikut berjongkok di samping Pak Slamet.
"Nggak mau sadar juga Tang, padahal sudah aku olesin balsem di hidungnya," jawab Pak Slamet.
"Bagaimana Pak?" tanya Lintang sambil ikut berjongkok di samping Pak Slamet.
"Nggak mau sadar juga Tang, padahal sudah aku olesin balsem di hidungnya," jawab Pak Slamet.
"Apa Bu Ratih akan baik baik saja?"
"Sepertinya begitu Tang, dia cuma pingsan karena kehabisan tenaga."
"Ah, syukurlah kalau begitu. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang Pak?"
"Entahlah," Pak Slamet menghela nafas,
"Sepertinya begitu Tang, dia cuma pingsan karena kehabisan tenaga."
"Ah, syukurlah kalau begitu. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang Pak?"
"Entahlah," Pak Slamet menghela nafas,
"aku hanya ingin cepat cepat bisa keluar dari hutan terkutuk ini dan kembali ke desa Tang."
"Bapak masih kuat menggendong Bu Ratih?"
"Hah, menggendong Bu Ratih?"
"Iya, bapak gendong Bu Ratih, saya akan menggendong Wulan. Saya juga ingin cepat cepat kembali ke desa Pak."
"Bapak masih kuat menggendong Bu Ratih?"
"Hah, menggendong Bu Ratih?"
"Iya, bapak gendong Bu Ratih, saya akan menggendong Wulan. Saya juga ingin cepat cepat kembali ke desa Pak."
Pak Slamet tersenyum, menyambut ide briliant dari Lintang. "Aku justru khawatir kamu yang nggak kuat menggendong Wulan Tang."
"Jangan remehkan saya Pak," sungut Lintang.
"Hahaha..., ya sudah, ayo, kita pulang."
"Jangan remehkan saya Pak," sungut Lintang.
"Hahaha..., ya sudah, ayo, kita pulang."
Pak Slamet segera merengkuh tubuh Bu Ratih yang masih tergolek lemas dan menaikkan ke punggungnya. Sedangkan Lintang segera menghampiri Wulan yang masih duduk bersandar di bawah pohon. Ia lalu berjongkok membelakangi Wulan.
"Hei, apa yang kau lakukan Tang?" tanya Wulan heran.
"Hei, apa yang kau lakukan Tang?" tanya Wulan heran.
"Naik ke punggungku," ujar Lintang singkat.
"Naik ke punggungmu?"
"Iya. Cepatlah! Aku akan menggendongmu. Kita kembali ke desa!"
"Nggak mau! Jangan macam macam ya! Enak saja kau mau menggendongku. Aku masih bisa jalan sendiri!" seru Wulan sambil bangkit berdiri,
"Naik ke punggungmu?"
"Iya. Cepatlah! Aku akan menggendongmu. Kita kembali ke desa!"
"Nggak mau! Jangan macam macam ya! Enak saja kau mau menggendongku. Aku masih bisa jalan sendiri!" seru Wulan sambil bangkit berdiri,
namun tubuhnya yang memang masih lemah segera terhuyung dan jatuh menubruk Lintang yang berjongkok di hadapannya.
"Sudah kubilang kan, kau masih lemah. Pakai sok sokan mau jalan sendiri!" sungut Lintang sambil berdiri dengan Wulan yg akhirnya mau juga menggelayut di punggungnya.
"Sudah kubilang kan, kau masih lemah. Pakai sok sokan mau jalan sendiri!" sungut Lintang sambil berdiri dengan Wulan yg akhirnya mau juga menggelayut di punggungnya.
"Pegangan yang erat, biar nggak jatuh!"
"Sudah siap Tang?" seru Pak Slamet yang juga sudah menggendong Bu Ratih di punggungnya.
"Siap Pak! Bapak jalan di depan, biar saya mengikuti dari belakang," seru Lintang.
"Sudah siap Tang?" seru Pak Slamet yang juga sudah menggendong Bu Ratih di punggungnya.
"Siap Pak! Bapak jalan di depan, biar saya mengikuti dari belakang," seru Lintang.
"Ke arah mana kita jalan Tang? Bapak nggak tau arah jalan pulang," kata Pak Slamet lagi.
"Sepertinya ke arah kanan Pak! Kita ikuti saja jalan setapak itu!"
"Oke! Ikuti aku Tang, jangan jauh jauh dariku, biar nggak tersesat."
"Siap Pak!"
"Sepertinya ke arah kanan Pak! Kita ikuti saja jalan setapak itu!"
"Oke! Ikuti aku Tang, jangan jauh jauh dariku, biar nggak tersesat."
"Siap Pak!"
Merekapun segera berjalan tersaruk saruk menyusuri jalan setapak yang di kiri kanannya masih dipenuhi oleh nyala api dari semak dan pepohonan yang terbakar. Bukan hal mudah menyusuri hutan yang terbakar di tengah gelapnya malam.
Apalagi dengan tambahan beban di punggung mereka. Namun keinginan kuat untuk cepat cepat bisa kembali ke desa membuat semangat mereka kembali berkobar.
"Kenapa kau tertawa?" sungut Lintang saat mendengar Wulan yang berada dalam gendongannya tertawa tertahan.
"Kenapa kau tertawa?" sungut Lintang saat mendengar Wulan yang berada dalam gendongannya tertawa tertahan.
"Kau nggak lihat Tang? Itu celana Pak Slamet bolong di bagian belakangnya, sampai pantatnya kelihatan begitu," jawab Wulan sambil berusaha menahan tawanya.
"Aish! Bisa bisanya kamu mentertawakan orang disaat saat seperti ini," dengus Lintang kesal.
"Aish! Bisa bisanya kamu mentertawakan orang disaat saat seperti ini," dengus Lintang kesal.
Namun dalam hati anak itu justru bersyukur. Wulan sudah bisa tertawa, berarti anak itu telah kembali menjadi Wulan yang selama ini dikenalnya.
Gema suara kokok ayam jantan samar samar mulai terdengar. Pak Slamet masih terus berjalan tertatih tatih sambil menggendong Bu Ratih yang belum juga sadar. Sementara Lintang juga masih terus mengukutinya dengan Wulan yang kini telah tertidur pulas dalam gendongannya.
"Kenapa berhenti Pak?" tanya Lintang saat tiba tiba Pak Slamet menghentikan langkahnya.
"Sebentar Tang, perasaan kok dari tadi kita muter muter disini saja ya," jawab Pak Slamet sambil melihat ke sekeliling.
"Jangan jangan kita tersesat Pak?" suara Lintang terdengar panik.
"Sebentar Tang, perasaan kok dari tadi kita muter muter disini saja ya," jawab Pak Slamet sambil melihat ke sekeliling.
"Jangan jangan kita tersesat Pak?" suara Lintang terdengar panik.
"Entahlah Tang, mudah mudahan sih tidak. Kau juga dengar kan suara kokok ayam jantan itu? Itu berarti kita sudah tak jauh lagi dari desa." ujar Pak Slamet, mencoba menenangkan hati Lintang.
Laki laki itu sendiri sebenarnya tak yakin, apakah mereka benar benar sudah mendekati desa, atau justru semakin tersesat masuk ke dalam hutan. Sulit untuk menentukan arah ditengah hutan belantara begini.
Rasi bintang di atas sana juga tak bisa banyak membantu, karena tertutup oleh lebatnya dedaunan. Suara kokok ayam jantan juga bisa datang darimana saja, mengingat saat ini mereka berada di tengah rimba.
"Kalau begitu, ayo kita jalan lagi Pak, saya sudah ingin cepat cepat sampai di desa," kata Lintang penuh semangat.
"Jangan terburu buru Tang. Lebih baik kita istirahat dulu, sambil menunggu pagi datang. Kan lebih mudah kita menentukan arah kalau matahari sudah terbit.
"Jangan terburu buru Tang. Lebih baik kita istirahat dulu, sambil menunggu pagi datang. Kan lebih mudah kita menentukan arah kalau matahari sudah terbit.
Lagipula Bapak juga sudah lelah," Pak Slamet menurunkan tubuh Bu Ratih dari punggungnya, lalu menyandarkannya pada sebatang pohon. Beruntung api belum merambat sampai di tempat mereka yang sekarang ini, meski suara gemeratak api yang membakar hutan masih terdengar dari kejauhan.
Lintangpun segera mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Slamet. Ia menurunkan tubuh Wulan dari punggungnya, lalu menyandarkannya disamping tubuh Bu Ratih.
"Kalau kamu ngantuk tidur saja dulu Tang, biar bapak yang berjaga. Nanti kalau matahari sudah terbit bapak bangunkan," kata Pak Slamet lagi.
Tanpa menunggu perintah yang kedua kali, Lintang segera menyandarkan punggungnya pada batang pohon.
Tanpa menunggu perintah yang kedua kali, Lintang segera menyandarkan punggungnya pada batang pohon.
Ia memang sudah sangat mengantuk, lelah, dan juga lapar. Tak perlu menunggu lama, anak itupun segera terlelap.
Kini tinggal Pak Slamet yang terjaga. Laki laki itu kini duduk menyandar pada sebuah pohon, sambil menatap ketiga insan yang terlelap di hadapannya.
Kini tinggal Pak Slamet yang terjaga. Laki laki itu kini duduk menyandar pada sebuah pohon, sambil menatap ketiga insan yang terlelap di hadapannya.
Wulan nampak tersenyum dalam tidurnya, sedangkan Lintang, jelas nampak gurat kelelahan di wajahnya. Pak Slamet tersenyum, bangga dengan anak anak yang tangguh dan berbakat seperti mereka.
Pandangan Pak Slamet beralih kepada Bu Ratih. Hatinya berdesir. Dalam keadaan pingsanpun, perempuan itu masih terlihat cantik. Rambut panjangnya yang sudah berantakan, noda noda hitam yang banyak menempel di wajahnya, tak mampu menutupi rona kecantikan guru muda itu.
Pelan Pak Slamet beringsut mendekat ke arah Bu Ratih. Tangannya terjulur, menyibakkan beberapa helai rambut yang menutupi wajah perempuan itu, lalu membetulkan letak kacamatanya yang sedikit turun.
"Pak," Pak Slamet berjingkat kaget saat tiba tiba Bu Ratih membuka matanya.
"Pak," Pak Slamet berjingkat kaget saat tiba tiba Bu Ratih membuka matanya.
Dengan cepat laki laki itu segera menjauhkan tangannya dari wajah Bu Ratih.
"Eh, emmm, syukurlah, akhirnya ibu sadar," gugup suara Pak Slamet terdengar.
"Eh, emmm, syukurlah, akhirnya ibu sadar," gugup suara Pak Slamet terdengar.
"Jadi saya tadi ..., ah, maaf kalau saya telah merepotkan bapak," Bu Ratih menegakkan punggungnya, sambil menatap Pak Slamet yang duduk di depannya dengan hanya mengenakan celana pendek tanpa baju. "Ya ampuunn, baju ini ...! Maaf ya Pak, gara gara saya ...!"
"Tak apa Bu, tenang saja. Saya sudah biasa kok begini. Yang penting kita semua sudah selamat. Tinggal mencari jalan untuk kembali ke desa," kata Pak Slamet.
"Jadi kita masih berada di hutan ya Pak? Lalu bagaimana kondisi Wulan?" guru muda itu segera menoleh ke arah Wulan yang tertidur di sebelahnya.
"Iya Bu. Tenang saja. Berkat usaha ibu, Wulan selamat kok, dia baik baik saja," jawab Pak Slamet.
"Iya Bu. Tenang saja. Berkat usaha ibu, Wulan selamat kok, dia baik baik saja," jawab Pak Slamet.
"Syukurlah Pak," Bu Ratih menarik nafas lega. "Bagaimana dengan Mas Joko ya Pak? Apa mereka juga selamat sampai ke desa?"
"Mudah mudahan saja Bu," Pak Slamet kembali menyandarkan punggungnya ke batang pohon. "Mudah mudahan mereka juga selamat."
"Mudah mudahan saja Bu," Pak Slamet kembali menyandarkan punggungnya ke batang pohon. "Mudah mudahan mereka juga selamat."
"Iya Pak, saya juga berharap begitu. Kasihan Wulan dan Lintang, anak seumuran mereka sudah harus mengalami kejadian yang seperti ini," Bu Ratih juga kembali menyandarkan punggungnya pada batang pohon.
"Bagaimana kalau seandainya kita tak bisa keluar dari hutan ini Bu?" ujar Pak Slamet pelan.
"Kenapa bapak berpikir seperti itu?" Bu Ratih bertanya heran.
"Kabar yang saya dengar, hutan ini angker, orang yang sudah masuk ke hutan ini, tak akan bisa keluar hidup hidup."
"Kenapa bapak berpikir seperti itu?" Bu Ratih bertanya heran.
"Kabar yang saya dengar, hutan ini angker, orang yang sudah masuk ke hutan ini, tak akan bisa keluar hidup hidup."
"Bapak percaya dengan cerita itu?"
"Entahlah Bu, saya tak yakin."
"Jangan pesimis Pak. Saya yakin kok, kita pasti bisa keluar dari hutan ini."
"Ya mudah mudahan saja Bu. Oh, ya Bu, saya sama sekali tak menyangka lho, ternyata Bu Ratih punya kemampuan sehebat itu.
"Entahlah Bu, saya tak yakin."
"Jangan pesimis Pak. Saya yakin kok, kita pasti bisa keluar dari hutan ini."
"Ya mudah mudahan saja Bu. Oh, ya Bu, saya sama sekali tak menyangka lho, ternyata Bu Ratih punya kemampuan sehebat itu.
Saya benar benar kagum. Seperti mimpi rasanya, melihat Bu Ratih berubah menjadi seperti pendekar begitu. Darimana Bu Ratih belajar ilmu ilmu seperti itu? Dan rajah yang di punggung Bu Ratih itu, apakah ....!!!"
"Maaf Pak, soal itu, sepertinya saya tak bisa menceritakannya. Ini menyangkut masa lalu saya. Dan saya mohon, bapak bisa menyimpan rahasia ini. Cukup bapak dan Lintang saja yang tahu."
"Eh, iya, maaf Bu kalau saya terlalu lancang bertanya soal itu."
"Tak apa Pak," Bu Ratih tersenyum. "Saya maklum, semua orang pasti akan bertanya tanya kalau melihat apa yang terjadi pada saya tadi."
"Bu?"
"Ya?"
"Tak apa Pak," Bu Ratih tersenyum. "Saya maklum, semua orang pasti akan bertanya tanya kalau melihat apa yang terjadi pada saya tadi."
"Bu?"
"Ya?"
"Kalau nanti kita benar benar bisa keluar dari hutan ini, apa yang akan ibu lakukan?"
"Tentu saja saya akan kembali mengajar seperti biasanya Pak. Menjalani kehidupan seperti biasanya, ya pokoknya saya akan menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya Pak."
"Tentu saja saya akan kembali mengajar seperti biasanya Pak. Menjalani kehidupan seperti biasanya, ya pokoknya saya akan menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya Pak."
"Menjalani kehidupan normal ya?"
"Ya, begitulah Pak. Kenapa tiba tiba bapak bertanya seperti itu?"
"Eh, nggak papa kok, cuma pengen tau saja."
"Kalau bapak sendiri, apa yang akan bapak lakukan kalau nanti berhasil keluar dari hutan ini?"
"Ya, begitulah Pak. Kenapa tiba tiba bapak bertanya seperti itu?"
"Eh, nggak papa kok, cuma pengen tau saja."
"Kalau bapak sendiri, apa yang akan bapak lakukan kalau nanti berhasil keluar dari hutan ini?"
"Saya sudah terlalu tua Bu. Saya nggak mau lagi menyia nyiakan sisa hidup saya. Mungkin, kalau saya nanti bisa selamat keluar dari hutan ini, saya akan segera melamar perempuan yang selama ini telah memikat hati saya."
"Wah, surprise dong Pak. Kalau boleh tau, siapa perempuan yang beruntung itu Pak?"
"Bu," tiba tiba Pak Slamet mendekat dan menggenggam kedua tangan Bu Ratih, "apa selama ini ibu nggak merasa kalau saya selalu memperhatikan ibu?"
"Eh, ini maksudnya apa ya Pak?!"
"Bu," tiba tiba Pak Slamet mendekat dan menggenggam kedua tangan Bu Ratih, "apa selama ini ibu nggak merasa kalau saya selalu memperhatikan ibu?"
"Eh, ini maksudnya apa ya Pak?!"
"Malam ini, setelah mengalami kejadian yang sangat luar biasa bersamamu Bu, saya ingin berkata jujur, bahwa selama ini saya memang suka sama ibu. Terserah, Bu Ratih mau menanggapinya seperti apa.
Saya hanya mencoba untuk jujur, mengungkapkan perasaan yang telah sekian lama saya pendam. Jika ibu berkenan, begitu nanti kita berhasil keluar dari hutan terkutuk ini, saya akan segera melamar ibu."
Bu Ratih tercekat. Perempuan itu hanya bisa diam seribu bahasa.
Bu Ratih tercekat. Perempuan itu hanya bisa diam seribu bahasa.
Tak mampu lagi mengucapkan kata kata. Ia sama sekali tak menyangka, kalau kata kata yang telah sekian lama ia tunggu, akhirnya keluar juga dari mulut laki laki itu. Tanpa sadar, air mata mengembang diujung kedua kelopak mata Bu Ratih. Air mata bahagia.
"Eh, maaf, saya tak bermaksud untuk ..." seolah tersadar, Pak Slamet segera berusaha untuk melepaskan genggaman tangannya. Namun niatnya tertahan karena Bu Ratih justru membalas genggaman tangan itu.
"Kenapa Pak?"
"Maaf Bu, saya lancang ..."
"Kenapa bapak baru mengatakannya sekarang? Padahal sudah sekian lama saya menunggu ...."
"Jadi?"
Bu Ratih mengangguk sambil tersenyum, membuat Pak Slamet nyaris melompat kegirangan.
"Maaf Bu, saya lancang ..."
"Kenapa bapak baru mengatakannya sekarang? Padahal sudah sekian lama saya menunggu ...."
"Jadi?"
Bu Ratih mengangguk sambil tersenyum, membuat Pak Slamet nyaris melompat kegirangan.
Hampir saja ia menghambur untuk memeluk Bu Ratih, kalau saja ia tidak melihat Wulan yang menatap ke arah mereka dengan mata berbinar. Entah sejak kapan anak itu terbangun. Kedua sejoli itu sampai tak menyadarinya.
"Hayoooo ...! Pak Slamet sama Bu Ratih lagi pacaran yaaa?" seru anak itu sambil tertawa cekikikan, membuat wajah Bu Ratih dan Pak Slamet memerah menahan malu.
"Ah, enggak kok, ini lho, Ibu sama Bapak lagi berunding, nyari jalan buat kembali ke desa," Bu Ratih mendekati anak itu, lalu memeriksa sekujur badannya, "kamu nggak papa kan Lan? Ada yang sakit nggak?"
"Nggak papa Bu, Wulan baik baik saja kok. Memangnya Wulan habis kenapa? Kok ibu nanya begitu?" tanya anak itu keheranan.
"Enggak kok, kita hanya tersesat tadi di hutan. Tapi jangan khawatir ya, ibu dan Pak Slamet pasti akan segera menemukan jalan untuk pulang.
"Enggak kok, kita hanya tersesat tadi di hutan. Tapi jangan khawatir ya, ibu dan Pak Slamet pasti akan segera menemukan jalan untuk pulang.
Sekarang kamu bangunkan Lintang ya. Sudah pagi, kita harus segera melanjutkan perjalanan." ujar Bu Ratih lembut sambil mengelus kepala Wulan.
"Oke Bu," anak itu segera menghampiri Lintang yang masih terlelap dibawah pohon.
"Oke Bu," anak itu segera menghampiri Lintang yang masih terlelap dibawah pohon.
Diguncang guncangkannya bahu Lintang sampai anak itu terkaget kaget.
"Woy! Bangun Tang! Sudah pagi nih!" seru Wulan.
"Iya iya, ini sudah bangun. Kamu ini lho, bangunin orang kok pake teriak teriak kayak bangunin kambing saja!" Lintang menggerutu.
"Woy! Bangun Tang! Sudah pagi nih!" seru Wulan.
"Iya iya, ini sudah bangun. Kamu ini lho, bangunin orang kok pake teriak teriak kayak bangunin kambing saja!" Lintang menggerutu.
"Hehehe, habisnya kamu kalau tidur kayak kambing. Cepetan bangun! Sudah pagi lho ini. Kita harus segera pulang."
"Memangnya sudah ketemu jalannya?"
"Tenang saja, sebentar lagi ada yang datang kok buat menjemput kita."
"Memangnya sudah ketemu jalannya?"
"Tenang saja, sebentar lagi ada yang datang kok buat menjemput kita."
"Siapa memangnya yang mau menjemput kita?" tanya Lintang heran, sambil bangkit berdiri. Hari memang sudah terang. Dari arah sebelah kirinya terlihat bias sinar matahari yang menembus lebatnya hutan.
"Tuh!" Wulan memonyongkan bibirnya ke arah semak semak yang tiba tiba bergerak gerak seperti digoyang goyangkan oleh sesuatu yang menerobosnya. Dan tak lama kemudian, dari balik semak semak itu muncul seekor anak monyet berekor panjang,
yang kemudian diikuti oleh kemunculan Mas Joko, Mbak Romlah, serta Mbak Patmi.
Sontak mereka segera berhamburan memeluk anak mereka masing masing. Tubuh mungil Wulan tenggelam dalam pelukan Mas Joko dan Mbak Romlah.
Sontak mereka segera berhamburan memeluk anak mereka masing masing. Tubuh mungil Wulan tenggelam dalam pelukan Mas Joko dan Mbak Romlah.
Sedangkan Mbak Patmi tak henti hentinya menciumi pipi anak semata wayangnya itu.
Pak Slamet dan Bu Ratih yang melihat kejadian itu hanya saling pandang. Ada rona bahagia di wajah mereka, melihat bahwa akhirnya mereka semua selamat dan bisa berkumpul kembali.
Pak Slamet dan Bu Ratih yang melihat kejadian itu hanya saling pandang. Ada rona bahagia di wajah mereka, melihat bahwa akhirnya mereka semua selamat dan bisa berkumpul kembali.
Tanpa sadar tangan Pak Slamet merengkuh bahu Bu Ratih, dan dengan sukarela Bu Ratih menyandarkan kepalanya ke lengan laki laki itu.
"Syukur Alhamdulillah ya Bu, akhirnya semuanya selamat, dan kita bisa berkumpul kembali,"
"Syukur Alhamdulillah ya Bu, akhirnya semuanya selamat, dan kita bisa berkumpul kembali,"
bisik Pak Slamet, yang disahuti dengan anggukan kepala oleh Bu Ratih. Keduanya lalu melangkah pelan pelan menghampiri orang tua dan anak yang masih saling berpelukan itu.
"Kalian masih disini rupanya, saya kira sudah sampai di desa," ujar Pak Slamet memecah suasana haru itu.
"Kalian masih disini rupanya, saya kira sudah sampai di desa," ujar Pak Slamet memecah suasana haru itu.
"Iya Pak. Semalam kami tersesat, perasaan semalaman hanya muter muter saja di tempat ini. Beruntung kami bertemu dengan anak monyet ini, dan mengikutinya hingga sampai di tempat ini," jawab Mas Joko.
"Lho, kalau nggak salah ini kan anak monyet yang semalam menjadi penunjuk jalan itu?" Bu Ratih memperhatikan anak monyet yang kini tengah asyik menggerogoti buah jambu biji itu. Entah darimana binatang itu mendapatkannya.
.
.
"Sepertinya begitu Bu, dan kalau benar, mungkin binatang ini juga bisa menunjukkan jalan ke arah desa kepada kita," kata Mas Joko penuh harap.
"Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, lebih baik kita ..., Hey, mau kemana dia?"
"Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, lebih baik kita ..., Hey, mau kemana dia?"
Pak Slamet berseru saat tiba tiba anak monyet itu melompat dan berlari ke arah dimana tiba tiba muncul seorang anak yang berjalan menghampiri mereka. Seorang anak laki laki berambut gondrong berusia sekitar delapan belas tahunan.
Si anak monyet segera menggelayut dan naik ke bahu si anak berambut gondrong itu.
"Siapa anak itu Pak?" bisik Bu Ratih sambil memegang erat erat lengan Pak Slamet.
"Entahlah Bu, mungkin warga desa sekitar sini, atau ..."
"Siapa anak itu Pak?" bisik Bu Ratih sambil memegang erat erat lengan Pak Slamet.
"Entahlah Bu, mungkin warga desa sekitar sini, atau ..."
"Kalian! Cepat ikut aku!" si anak laki laki berambut gondrong berkata sambil melambaikan tangannya.
"Tunggu! Kamu siapa? Dan kenapa ...."
"Ndak usah banyak tanya! Ikut saja, itu juga kalau kalian mau selamat dan keluar dari hutan ini!"
"Tunggu! Kamu siapa? Dan kenapa ...."
"Ndak usah banyak tanya! Ikut saja, itu juga kalau kalian mau selamat dan keluar dari hutan ini!"
kata anak itu lagi sedikit ketus, lalu berbalik dan melangkah menjauh.
"Bagaimana ini Pak? Apakah kita ikuti saja anak itu?" bisik Mas Joko pada Pak Slamet.
"Bagaimana Bu?" Pak Slamet justru bertanya pada Bu Ratih.
"Bagaimana ini Pak? Apakah kita ikuti saja anak itu?" bisik Mas Joko pada Pak Slamet.
"Bagaimana Bu?" Pak Slamet justru bertanya pada Bu Ratih.
"Sepertinya tak ada pilihan lain Pak. Kita ikuti saja dia." jawab Bu Ratih, setelah berpikir sejenak.
"Bagaimana kalau ternyata dia orang jahat? Rampok misalnya?" Mbak Patmi ikut bicara.
"Bagaimana kalau ternyata dia orang jahat? Rampok misalnya?" Mbak Patmi ikut bicara.
"Apa yang mau dirampok dari kita Mbak, lagi pula, semenjak semalam anak monyet itu telah banyak menolong kita, dan kini anak monyet itu telah bersama anak itu. Jadi saya yakin anak itu juga berniat baik kepada kita," kata Bu Ratih meyakinkan.
"Ah, benar juga,. Kalau begitu, tunggu apalagi, ayo kita ikuti anak itu, sebelum ia terlalu jauh." ujar Pak Slamet.
Jadilah akhirnya rombongan kecil itu berlari lari mengejar anak berambut gondrong yang sedikit misterius itu.
Jadilah akhirnya rombongan kecil itu berlari lari mengejar anak berambut gondrong yang sedikit misterius itu.
Ya, misterius, karena setelah mereka berhasil menyusul dan mengikuti langkah anak itu, tak ada sepatah katapun yang keluar dari mulutnya. Pertanyaaan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Slamet dan Bu Ratih pun sama sekali tak ia hiraukan.
Mereka terus saja berjalan, sampai akhirnya tiba di sebuah sungai yang sepertinya menjadi batas antara hutan itu dengan sebuah desa. Rombongan Pak Slametpun bisa bernafas lega kini, karena telah berhasil keluar dari hutan.
Di kejauhan sana, nampak kelap kelip lampu sirine dari beberapa mobil pemadam kebakaran. Nampak juga beberapa anggota polisi dan warga yang saling bahu membahu untuk memadamkan kebakaran hutan.
"Lewat sini!" si anak laki laki berambut gondrong menuntun langkah mereka mengendap endap di jalan setapak yang di kiri dan kanannya dipagari oleh semak semak yang rimbun. "Jangan sampai orang orang itu melihat kehadiran kalian!"
Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya, rombongan Pak Slametpun mengikuti langkah anak itu tanpa banyak bertanya lagi. Toh semenjak tadi pertanyaan pertanyaan yang mereka ajukan tak pernah sekalipun dijawab oleh anak itu.
Sampai akhirnya, mereka sampai di sebuah kebun yang berada dibelakang sebuah rumah kayu sederhana. Mungkin itu rumah milik kedua orang tua anak itu. Masih dengan mengendap endap, si anak laki laki berambut gondrong segera membuka pintu belakang rumah itu,
lalu memberi isyarat kepada rombongan Pak Slamet agar segera masuk ke rumah itu. Lagi lagi mereka mengikuti perintah laki laki itu.
Ternyata yang mereka masuki adalah sebuah ruangan dapur yang lumayan luas, seperti dapur dapur yang ada di setiap rumah penduduk desa pada umumnya.
Ternyata yang mereka masuki adalah sebuah ruangan dapur yang lumayan luas, seperti dapur dapur yang ada di setiap rumah penduduk desa pada umumnya.
Si anak laki laki berambut gondrong itu terus melangkah, membuka pintu yang menghubungkan ruangan dapur itu dengan ruang utama.
Rombongan Pak Slamet sempat ternganga takjub saat mendapati ruangan utama rumah itu ternyata sangat luas, dan terkesan mewah untuk ukuran rumah di pedesaan. Dinding kayunya terlihat mengkilap, terbuat dari kayu jati pilihan.
Lantainyapun sudah bukan lantai tanah lagi, melainkan sudah dilapisi dengan ubin berwarna hitam mengkilat.
Di tengah tengah ruangan tersusun beberapa kursi rotan dengan meja kaca yang diatasnya telah tersedia beraneka hidangan makanan yang sepertinya sengaja telah dipersiapkan untuk mereka.
"Silahkan," seorang laki laki tua dengan rambut yang hampir memutih semua menyambut kedatangan mereka, lalu mempersilahakan tamu tamunya itu untuk duduk di kursi kursi yang telah disediakan.
Sedangkan si anak laki laki berambut gondrong nampak sibuk membuka pintu pintu dan jendela, hingga ruangan itu kini menjadi terang benderang.
"Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya lancang, tapi kalau boleh kami tau, siapa kisanak ini sebenarnya, dan kenapa kisanak membawa kami ke rumah ini?" tanya Pak Slamet setelah mereka semua duduk.
"Panggil saja saya Mbah Mo, sesepuh desa Patrolan ini, dan ini cucu saya, Permadi," kakek tua itu memperkenalkan diri, sambil menunjuk anak laki laki berambut gondrong yang kini telah ikut duduk di sebelahnya.
"Oh, Mbah Mo to," Pak Slamet mengangguk hormat.
"Oh, Mbah Mo to," Pak Slamet mengangguk hormat.
"Saya pernah dengar nama itu. Dan saya ucapkan banyak terimakasih, karena simbah sudah ...."
"Tak usah sungkan Pak, sudah menjadi kewajiban toh sebagai manusia untuk saling tolong menolong. Mari, sambil ngobrol kita nikmati hidangan yang hanya seadanya ini," ,
"Tak usah sungkan Pak, sudah menjadi kewajiban toh sebagai manusia untuk saling tolong menolong. Mari, sambil ngobrol kita nikmati hidangan yang hanya seadanya ini," ,
laki laki tua itu kembali mempersilahkan.
Merekapun tanpa sungkan sungkan segera menikmati hidangan itu dengan sangat lahap. Maklum, semenjak kemarin mereka memang sama sekali belum makan.
Merekapun tanpa sungkan sungkan segera menikmati hidangan itu dengan sangat lahap. Maklum, semenjak kemarin mereka memang sama sekali belum makan.
Dan sambil menikmati hidangan sederhana itu, semua pertanyaan yang diajukan oleh Pak Slamet kini terjawab sudah.
Mbah Mo, sesepuh desa Patrolan itu, sejak awal sudah tahu soal tragedi yang terjadi di tengah hutan tawengan yang dialami oleh Pak Slamet dan rombongannya.
Mbah Mo, sesepuh desa Patrolan itu, sejak awal sudah tahu soal tragedi yang terjadi di tengah hutan tawengan yang dialami oleh Pak Slamet dan rombongannya.
Anak monyet yang ternyata adalah peliharaan Permadi itu yang memberitahu.
Sedikit terdengar aneh memang, bagaimana seekor anak monyet bisa memberitahu tuannya tentang sebuah kejadian yang bahkan sulit untuk dipercayai oleh orang yang mengalaminya sendiri.
Sedikit terdengar aneh memang, bagaimana seekor anak monyet bisa memberitahu tuannya tentang sebuah kejadian yang bahkan sulit untuk dipercayai oleh orang yang mengalaminya sendiri.
Pak Slamet ingin bertanya lebih jauh, namun Bu Ratih memberi kode agar Pak Slamet mengurungkan niatnya untuk bertanya.
Sesepuh desa Patrolan itu lalu melanjutkan ceritanya, ia memang sengaja menyuruh Permadi untuk menjemput rombongan Pak Slamet dan membawanya ke rumahnya,
Sesepuh desa Patrolan itu lalu melanjutkan ceritanya, ia memang sengaja menyuruh Permadi untuk menjemput rombongan Pak Slamet dan membawanya ke rumahnya,
agar mereka tak dicurigai sebagai penyebab terbakarnya hutan Tawengan. Selain itu, Permadi sang cucu, entah kenapa semenjak kemaren selalu merengek untuk diijinkan masuk le hutan. Ingin bertemu dan berkenalan dengan Wulan katanya.
Lagi lagi terdengar aneh, bagaimana Permadi yang sama sekali tak saling mengenal Wulan, bisa tau kalau ada anak bernama Wulan didalam hutan?
"Jangan jangan dia naksir kamu Lan," bisik Lintang yang langsung dijawab dengan pelototan oleh Wulan
"Jangan jangan dia naksir kamu Lan," bisik Lintang yang langsung dijawab dengan pelototan oleh Wulan
Semua berawal dari sebuah mimpi, demikian penjelasan Pak Bayan. Semua kejadian yang terjadi di hutan semalam, sudah diketahui oleh Permadi lewat mimpi beberapa bulan yang lalu. Jadi tak heran kalau Permadi itu bisa dengan sangat mudah menemukan mereka.
Semakin terdengar aneh penjelasan dari Mbah Mo, sampai sampai Mas Joko harus minta pendapat Bu Ratih dulu sebelum mengijinkan Wulan untuk memenuhi permintaan Permadi.
"Tak apa Mas, ijinkan saja," bisik Bu Ratih.
"Tapi Bu ..."
"Tak apa Mas, ijinkan saja," bisik Bu Ratih.
"Tapi Bu ..."
"Sssttt, tak apa apa Mas, nanti kalau pulang akan saya jelaskan di jalan."
Mendengar bisikan Bu Ratih, akhirnya Mas Jokopun mengijinkan Wulan untuk berkenalan dengan Permadi.
Mendengar bisikan Bu Ratih, akhirnya Mas Jokopun mengijinkan Wulan untuk berkenalan dengan Permadi.
Tapi bukan Wulan namanya kalau tak bikin ulah. Anak itu mengajukan syarat sebelum memenuhi permintaan Permadi.
"Syarat apa yang kau minta? Katakan saja, apapun yang kau minta, akan kukabulkan." kata Permadi.
"Boleh aku minta ayam hitam yang kaukurung di dapur itu?
"Syarat apa yang kau minta? Katakan saja, apapun yang kau minta, akan kukabulkan." kata Permadi.
"Boleh aku minta ayam hitam yang kaukurung di dapur itu?
Aku ingin memelihara ayam." kata Wulan dengan polosnya.
"Anak pintar," Permadi mendengus. "Tentu saja, kau boleh membawanya pulang nanti, akan kuberi kau sepasang, biar nanti kalau kamu pelihara bisa beranak pianak menjadi banyak.
"Anak pintar," Permadi mendengus. "Tentu saja, kau boleh membawanya pulang nanti, akan kuberi kau sepasang, biar nanti kalau kamu pelihara bisa beranak pianak menjadi banyak.
Tapi janji, kau harus merawat ayam ayam itu dengan baik, karena itu bukan ayam sembarangan. Itu ayam cemani yang susah untuk didapatkan. Selain ayam, apalagi yang kau inginkan?"
Wulan berpikir sejenak, lalu melirik anak monyet yang masih nangkring di pundak anak laki laki berambut gondrong itu.
"Eh, jangan bilang kalau kamu juga ingin memelihara si Kliwon ini?" tanya Permadi.
"Eh, jangan bilang kalau kamu juga ingin memelihara si Kliwon ini?" tanya Permadi.
"Bukan buatku, tapi untuk temanku ini, boleh ya?," kata Wulan sambil melirik ke arah Lintang. Lintang tentu saja langsung melotot ke arah Wulan, seolah ingin memprotes.
"Hmmm, gimana ya? Sebenarnya Kliwon ini binatang kesayanganku. Tapi tak apalah, kamu juga boleh membawanya. Asal nanti dirawat dengan baik, dan sesekali nanti aku masih akan mengunjunginya di rumah kalian."
Jadilah, akhirnya keinginan Permadi dikabulkan oleh Wulan. Kedua anak itu saling berjabat tangan dan menyebutkan nama mereka masing masing.
"Kita sudah jadi teman sekarang. Kamu boleh main kesini sesukamu kalau kamu mau.
"Kita sudah jadi teman sekarang. Kamu boleh main kesini sesukamu kalau kamu mau.
Dan aku juga mungkin akan sering sering main kerumahmu, boleh kan?" kata Permadi. Wulan hanya mengangguk. Semua yang hadir hanya bisa tersenyum melihat tingkah kedua anak itu. Kecuali Lintang.
Entah kenapa ia merasa tak suka melihat keakraban yang mulai terjalin diantara Wulan dan Permadi.
Sampai siang menjelang, rombongan Pak Slametpun diantar sampai ke batas desa oleh Mbah Mo.
Sampai siang menjelang, rombongan Pak Slametpun diantar sampai ke batas desa oleh Mbah Mo.
Mobil Mas Joko ternyata sudah diamankan oleh sesepuh desa Patrolan itu, lengkap dengan sepeda milik Lintang. Sedang mobil milik keponakan Pak Marto, sengaja dibiarkan ikut terbakar di hutan, untuk memberi petunjuk kepada polisi tentang siapa penyebab kebakaran hutan itu.
Rona bahagia nampak terpancar dari wajah wajah di dalam mobil itu. Mereka akhirnya bisa kembali pulang dengan selamat setelah semalaman mengalami kejadian kejadian yg sangat menegangkan.
Mas Joko & Mbak Romlah bahagia, setelah nyaris kehilangan Wulan, anak semata wayang mereka.
Mas Joko & Mbak Romlah bahagia, setelah nyaris kehilangan Wulan, anak semata wayang mereka.
Demikian juga dengan Mbak Patmi. Wulan, meski belum sadar dengan apa yang terjadi, juga merasa bahagia, mendapatkan sepasang ayam cemani yang katanya spesial itu. Juga mendapat teman baru yang bernama Permadi itu. Meski sifatnya agak aneh, tapi sepertinya Permadi anak yang baik.
Lintang, meski sedikit kesal karena mendapat 'titipan' anak monyet dari Wulan, juga merasa bahagia, karena bisa mendapatkan kembali sahabat kecilnya. Dan yang paling merasa bahagia adalah Pak Slamet dan Bu Ratih.
Gara gara petualangan mereka malam itu, mereka jadi bisa mengetahui isi hati mereka masing masing. Dan masa depan yang cerah sepertinya telah menanti kedua pasangan yang sedang dilanda cinta itu.
Hari masih pagi, namun kesibukan mulai nampak di rumah Bu Ratih. Di dapur, nampak Mak Karni, istri Pak Modin, tengah sibuk menanak nasi dengan dandang besar di atas tungku. Juga ada Mbak Romlah yang tengah sibuk meracik bumbu bumbu,
dan Mbak Patmi yang tengah asyik membolak balik seekor ayam yang dipanggang diatas bara.
Sedang di ruang tengah, Mas Joko dengan dibantu oleh Pak Sholeh dan Ramadhan, juga sibuk membersihkan ruangan itu.
Sedang di ruang tengah, Mas Joko dengan dibantu oleh Pak Sholeh dan Ramadhan, juga sibuk membersihkan ruangan itu.
Meja dan kursi mereka singkirkan, lalu mereka ganti dengan beberapa lembar tikar yang mereka gelar diatas lantai. Alunan musik dangdut mengalun agak keras dari tape recorder milik Ramadhan, membuat suasana semakin semarak dan menambah semangat mereka dalam bekerja.
Pak Modin juga tak mau ketinggalan. Laki laki sepuh itu sibuk di halaman depan, berteriak teriak memberi komando kepada Wulan dan Lintang yang tengah asyik menyapu dan mencabuti rumput liar di halaman rumah itu.
Semua nampak sibuk, semua bekerja dengan wajah wajah yang gembira, karena hari itu adalah hari yang istimewa. Siang nanti, Pak Slamet akan datang membawa keluarganya, dengan maksud ingin meresmikan lamarannya terhadap Bu Ratih.
Bu Ratih sendiri, masih belum keluar dari kamarnya. Guru muda itu duduk termenung di depan meja riasnya, menatap dalam dalam pantulan wajahnya di dalam cermin. Berjuta perasaan campur aduk di dalam hatinya.
Ia seolah masih belum percaya, kalau laki laki itu akhirnya akan melamarnya, dan sebentar lagi ia akan resmi menjadi nyonya Slamet. Dan semua itu terjadi karena peristiwa buruk yang mereka alami beberapa hari yang lalu di hutan Tawengan.
Andai peristiwa itu tak terjadi, mungkin sampai detik ini mereka masih sama sama menahan ego untuk menyatakan perasaan.
Bu Ratih tersenyum, lalu perlahan tangannya mengusap tengkuknya, merasakan guratan guratan halus yang hampir memenuhi semua permukaan punggungnya.
Bu Ratih tersenyum, lalu perlahan tangannya mengusap tengkuknya, merasakan guratan guratan halus yang hampir memenuhi semua permukaan punggungnya.
Rajah itu telah muncul kembali kini, karena memang rajah itu hanya bertahan semalam saat dibuka. Begitu matahari terbit, maka otomatis rajah itu akan muncul kembali dengan sendirinya.
"Mudah mudahan ini yang terakhir kalinya, dan setelah ini aku tak akan pernah membuka segel ini lagi," gumam Bu Ratih pelan. Ingatannya kembali melayang pada peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu.
Sebuah tragedi berdarah yang memaksa orang itu menanamkan rajah gaib ini ke dalam tubuhnya.
"Ah, andai saja orang itu sekarang masih ada dan berada di sini, pasti peristiwa buruk di hutan Tawengan itu tak akan terjadi.
"Ah, andai saja orang itu sekarang masih ada dan berada di sini, pasti peristiwa buruk di hutan Tawengan itu tak akan terjadi.
Tapi, kalau peristiwa itu tak terjadi, mungkin hari ini Pak Slamet belum tentu melamarku," guru muda itu tersenyum tipis, menyadari bahwa angan angannya telah mengembara kemana mana.
"Nduk!" suara Mak Karni mengetuk pintu kamar membuyarkan lamunan Bu Ratih. "Sudah siang lho, cepetan kamu siap siap, sebentar lagi tamunya akan datang!"
"Iya wak, sebentar," buru buru Bu Ratih menyambar handuk dan bergegas keluar kamar.
"Iya wak, sebentar," buru buru Bu Ratih menyambar handuk dan bergegas keluar kamar.
Nyaris saja ia menubruk tubuh uwaknya yang ternyata masih berdiri di depan pintu.
"Cepetan mandi, terus dandan yang cantik. Kamu harus tampil mempesona di hadapan calon suamimu nanti. Jangan bikin malu bapakmu," goda perempuan setengah baya itu.
"Cepetan mandi, terus dandan yang cantik. Kamu harus tampil mempesona di hadapan calon suamimu nanti. Jangan bikin malu bapakmu," goda perempuan setengah baya itu.
"Ah, uwak apa apaan sih, tiap hari kan kami juga sudah ketemu di sekolah. Mungkin Pak Slamet malah sudah bosan melihat wajahku," jawab Bu Ratih dengan wajah memerah.
"Haha, makanya, khusus hari ini kamu harus tampil istimewa.
"Haha, makanya, khusus hari ini kamu harus tampil istimewa.
Dan jangan manggil Pak lagi sama calon suamimu itu, panggil dia Mas," Mak Karni tertawa lebar.
"Iya Waaakkkkk ...!!!" seru Bu Ratih sambil ngeloyor ke kamar mandi.
Singkat cerita, tepat jam sebelas siang, tamu yang ditunggu tunggupun datang.
"Iya Waaakkkkk ...!!!" seru Bu Ratih sambil ngeloyor ke kamar mandi.
Singkat cerita, tepat jam sebelas siang, tamu yang ditunggu tunggupun datang.
Laki laki itu terlihat sangat gagah, mengenakan setelan baju batik dan celana bahan, lengkap dengan sepatu kulit yang disemir mengkilap. Bersamanya juga datang sepasang suami istri setengah baya yang ternyata adalan paman dan bibinya.
Hanya mereka keluarga Pak Slamet yang masih tersisa. Kedua orang tua kandungnya memang sudah lama meninggal.
Acara lamaranpun berjalan dengan lancar dan khidmat. Rasa haru dan bahagia menyeruak di dalam hati semua orang yang hadir disitu.
Acara lamaranpun berjalan dengan lancar dan khidmat. Rasa haru dan bahagia menyeruak di dalam hati semua orang yang hadir disitu.
Bahkan Mbak Romlah dan Mak Karni sampai tak sanggup menahan air mata mereka. Air mata bahagia tentunya.
Selesai acara lamaran, dilanjutkan dengan acara makan makan, sambil ngobrol ngobrol ringan.
Selesai acara lamaran, dilanjutkan dengan acara makan makan, sambil ngobrol ngobrol ringan.
Banyak nasehat nasehat dan petuah berharga yang diberikan oleh para orang tua kepada kedua calon suami istri itu. Sedikit membosankan sebenarnya, karena baik Pak Slamet ataupun Bu Ratih bukanlah anak kecil lagi yang pantas untuk dinasehati. Tapi memang begitulah adat di desa itu.
Selesai acara makan makan, para orang tua masih melanjutkan obrolan mereka di ruang tamu. Sedangkan yang muda muda segera memisahkan diri ke teras rumah yang lumayan luas itu. Mereka punya tema obrolan sendiri yang tentunya berbeda dengan tema obrolan para orang tua.
"Selamat ya Bu Ratih, Pak Slamet. Ndak nyangka lho, kalau ternyata sampeyan berdua ini berjodoh. Semoga langgeng ya nanti rumah tangganya sampai menjadi kakek kakek dan nenek nenek," bergantian mereka yang hadir memberi ucapan selamat kepada kedua pasangan calon suami istri itu.
"Rencana pernikahannya kapan Pak? Pasti dirame ramein kan? Secara sampeyan berdua kan orang terpandang di desa ini, dan bla bla bla ....." banyak yang mereka obrolkan sore itu.
Suasana kekeluargaan begitu sangat terasa, meskipun sebenarnya mereka tak ada hubungan keluarga sama sekali.
"Oh ya Bu Ratih, dan juga Pak Slamet, saya juga mau mengucapkan banyak banyak terimakasih, atas apa yang telah sampeyan berdua lakukan tempo hari di hutan Tawengan.
"Oh ya Bu Ratih, dan juga Pak Slamet, saya juga mau mengucapkan banyak banyak terimakasih, atas apa yang telah sampeyan berdua lakukan tempo hari di hutan Tawengan.
Entah apa jadinya kalau seandainya kemarin itu ndak ada Bu Ratih dan Pak Slamet. Saya benar benar banyak berhutang budi kepada sampeyan berdua," kata Mas Joko, mengalihkan tema pembicaraan.
"Ah, tak perlu merasa berhutang budi Mas, saya ikhlas kok melakukan semua itu.
"Ah, tak perlu merasa berhutang budi Mas, saya ikhlas kok melakukan semua itu.
Wulan murid saya, bahkan saya sudah menganggapnya sebagai anak saya sendiri. Jadi saya juga merasa berkewajiban untuk membantu Wulan kalau ia sedang dalam kesusahan," sahut Bu Ratih sambil tersenyum.
"Oh ya Bu, sebenarnya apa yang terjadi saat itu setelah kami pergi menjauh dari jurang bangkai itu? Saya dengar dari Lintang, ibu sampai ....." Mbak Romlah tak melanjutkan kata katanya.
Perempuan itu justru melirik dan menyikut pinggang suaminya, seolah berharap agar sang suami menyambung kata katanya.
"Ada apa Mbak Romlah? Kok sepertinya ragu begitu. Kalau ada yang ingin disampaikan, katakan saja.
"Ada apa Mbak Romlah? Kok sepertinya ragu begitu. Kalau ada yang ingin disampaikan, katakan saja.
Tak usah sungkan. Kita kan disini sudah seperti keluarga sendiri, jadi tak perlu segan," ujar Bu Ratih.
Mbak Romlah kembali menyikut pinggang sang suami, membuat laki laki itu berjingkat kaget.
"Eh, jadi begini Bu Ratih, tapi mohon maaf lho sebelumnya,
Mbak Romlah kembali menyikut pinggang sang suami, membuat laki laki itu berjingkat kaget.
"Eh, jadi begini Bu Ratih, tapi mohon maaf lho sebelumnya,
kalau apa yang akan saya tanyakan ini kurang berkenan di hati Bu Ratih," kata Mas Joko sedikit gugup.
"Soal apa to Mas? Kok sepertinya penting banget? Katakan saja kalau memang ada yg ingin ditanyakan. Ndak perlu sungkan sungkan, saya ndak bakalan marah kok," kata Bu Ratih lagi.
"Soal apa to Mas? Kok sepertinya penting banget? Katakan saja kalau memang ada yg ingin ditanyakan. Ndak perlu sungkan sungkan, saya ndak bakalan marah kok," kata Bu Ratih lagi.
"Jadi begini bu, saya ingin menanyakan soal rajah yang Bu Ratih miliki itu. Kata Lintang, saat itu ..., emm, gimana ya ngomongnya? Saya ...." kembali Mas Joko terlihat sangat gugup, sampai tak mampu lagi melanjutkan kata katanya.
"Oh, soal itu toh," beruntung Bu Ratih segera memotong ucapan gagap Mas Joko, membuat laki laki itu bisa menarik nafas lega.
"Sebenarnya, ini sebuah rahasia yang sudah sangat lama saya simpan Mas, karena ini menyangkut masa lalu saya yang agak kelam.
"Sebenarnya, ini sebuah rahasia yang sudah sangat lama saya simpan Mas, karena ini menyangkut masa lalu saya yang agak kelam.
Namun sepertinya, kali ini saya harus membongkar rahasia itu, terutama kepada Mas Slamet yang sebentar lagi akan menjadi suami saya. Sampeyan perlu tahu semuanya kan Mas, soal calon istrimu ini," Bu Ratih diam sejenak, sambil menoleh kepada sang calon suami.
Jadi, begini ceritanya," Bu Ratih mulai melanjutkan ucapannya. "Dulu, semasa kecil, saya juga sama dengan si Wulan itu. Sering lepas kendali sampai beberapa kali nyaris mencelakai orang. Sampai membuat orang orang membenci saya. Hal itu membuat orang tua saya sangat khawatir.
Sampai akhirnya, saat tragedi itu datang, saya nyaris menmbantai seluruh warga kota tempat saya tinggal, kalau saja tidak tiba tiba datang orang misterius yang mengaku sebagai saudara seperguruan kakek saya. Dari orang itulah saya akhirnya mendapatkan rajah ini.
Rajah ini sendiri, berfungsi untuk menekan kekuatan saya yang terlampau besar dan tidak bisa saya kendalikan. Kekuatan yang sebenarnya sama sekali tidak saya harapkan, yang saya dapatkan semenjak saya masih bayi dari kakek saya.
Dan ternyata benar, setelah rajah ini ditanam di dalam tubuh saya oleh orang itu, saya tidak pernah lagi merasakan kekuatan itu muncul saat saya sedang marah." Bu Ratih menjelaskan secara panjang lebar.
"Kalau boleh tau, siapa orang itu Bu? Dan apakah bisa rajah seperti yang ibu miliki itu ditanam juga di tubuh anak saya? Saya sudah sangat khawatir dengan anak saya Bu. Saya tidak ingin peristiwa di hutan Tawengan kemarin itu sampai terulang lagi.
Saya ingin anak saya hidup normal seperti anak anak yang lainnya Bu," cecar Mbak Romlah.
"Sayangnya, saya sama sekali tak tahu menahu tentang orang itu Mbak. Saya masih kecil saat itu, dan hanya sekali itu saja saya bertemu dengannya. Siapa nama orang itupun saya tak tahu.
"Sayangnya, saya sama sekali tak tahu menahu tentang orang itu Mbak. Saya masih kecil saat itu, dan hanya sekali itu saja saya bertemu dengannya. Siapa nama orang itupun saya tak tahu.
Bahkan kedua orang tua sayapun, saat saya tanyai juga nggak tahu. Orang itu benar benar sangat misterius." jawab Bu Ratih.
"Ah, sayang sekali ya. Padahal saya sangat berharap bisa bertemu dengan orang itu," gumam Mbak Romlah sedikit kecewa.
"Ah, sayang sekali ya. Padahal saya sangat berharap bisa bertemu dengan orang itu," gumam Mbak Romlah sedikit kecewa.
"Kalau Bu Ratih sendiri, bisa nggak menanam rajah seperti itu? Tolonglah kami Bu, kalau ibu memang bisa, kami sangat berharap ibu bersedia membantu Wulan.
Apapun persyaratannya, akan kami penuhi, asal Wulan bisa menjadi anak yang normal seperti anak anak yang lainnya," kata Mas Joko penuh harap.
"Tadi sudah saya bilang Mas, Wulan itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri.
"Tadi sudah saya bilang Mas, Wulan itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri.
Apapun akan saya lakukan demi kebaikan Wulan, tapi kalau untuk yang satu ini, saya belum yakin. Memang saya pernah mempelajari cara menanam dan melepas segel rajah ini dari catatan lama yang ditinggalkan oleh orang misterius itu.
Tapi baru sekedar mempelajari, saya sama sekali belum pernah mempraktekkannya, kecuali kemarin saat di hutan Tawengan itu." kata Bu Ratih lagi.
"Dan yang kemarin itu berhasil kan Bu?
"Dan yang kemarin itu berhasil kan Bu?
Kalau malam itu berhasil, berarti ada kemungkinan Bu Ratih juga akan berhasil kalau mencobanya kepada Wulan," desak Mas Joko lagi, dengan mata berbinar penuh harap.
"Waduh, gimana yaa, saya nggak tega sebenarnya kalau harus menjadikan Wulan sebagai kelinci percobaan. Tapi ...."
"Waduh, gimana yaa, saya nggak tega sebenarnya kalau harus menjadikan Wulan sebagai kelinci percobaan. Tapi ...."
"Ayolah Bu, tolonglah kami. Kami janji, apapun yang ibu inginkan, akan kami penuhi, asal ibu mau membantu Wulan," nyaris saja Mas Joko bersujud di hadapan Bu Ratih, kalau saja guru muda itu tak segera mencegahnya.
"Ya ampun, Mas Joko! Nggak usah seperti itu Mas! Baiklah, baiklah, nanti akan saya coba. Akan saya usahakan!" seru Bu Ratih sambil membantu Mas Joko untuk bangun kembali.
"Sungguh Bu? Beneran ibu mau membantu Wulan?" tanya Mas Joko lagi seolah masih tak yakin.
"Sungguh Bu? Beneran ibu mau membantu Wulan?" tanya Mas Joko lagi seolah masih tak yakin.
"Iya Mas, akan saya usahakan. Mas Joko tinggal siapkan saja syarat syaratnya. Nanti di malam bulan purnama, kita mulai ritualnya." ujar Bu Ratih sambil tersenyum.
"Alhamdulillah! Terima kasih banyak ya Bu. Kebaikan ibu akan saya ingat sampai akhir hayat saya," kata Mas Joko penuh rasa syukur.
"Iya Mas, iya. Ayam cemani pemberian Permadi kemarin itu masih ada kan Mas? Nanti kita butuh darah ayam itu untuk melakukan ritualnya.
"Iya Mas, iya. Ayam cemani pemberian Permadi kemarin itu masih ada kan Mas? Nanti kita butuh darah ayam itu untuk melakukan ritualnya.
Soal syarat syarat yang lain biar saya yang urus. Saya juga harus puasa dulu sambil menunggu malam purnama tiba. Ada baiknya Mas Joko dan Mbak Romlah juga ikut puasa sampai malam purnama nanti."
"Iya Bu, kami akan lakukan semua saran Bu Ratih. Yang penting nantinya Wulan bisa hidup normal seperti anak anak yang lainnya."
"Oh ya Bu, soal Mbah Mo dan cucunya kemarin itu bagaimana? Saya kok merasa mereka sedikit aneh ya?" sela Mbak Romlah.
"Oh ya Bu, soal Mbah Mo dan cucunya kemarin itu bagaimana? Saya kok merasa mereka sedikit aneh ya?" sela Mbak Romlah.
"Nggak ada yg aneh mbak. Mereka orang baik kok. Ya anggap saja mereka juga orang yang spesial. Mbah Mo itu, sebagai seorang sesepuh desa pasti juga memiliki kemampuan lebih. Dan Permadi,menurut pengamatan saya, sedikit banyak dia juga mewarisi apa yang dimiliki oleh kakeknya itu.
Jadi jangan heran kalau mereka bisa tiba tiba muncul dan punya keinginan yang agak aneh." jelas Bu Ratih.
"Syukurlah kalau begitu Bu. Kemarin saya sempat khawatir saat anak bernama Permadi itu yang tiba tiba ingin berkenalan dengan Wulan.
"Syukurlah kalau begitu Bu. Kemarin saya sempat khawatir saat anak bernama Permadi itu yang tiba tiba ingin berkenalan dengan Wulan.
Saya takut terjadi sesuatu yang ndak baik." kata Mbak Romlah lega.
"Ya sudah kalau begitu Bu, hari sudah sore. Kami pamit pulang dulu. Besok kami kesini lagi. Siapa tau masih ada yang bisa kami bantu bantu," Mas Joko pamit undur diri.
"Ya sudah kalau begitu Bu, hari sudah sore. Kami pamit pulang dulu. Besok kami kesini lagi. Siapa tau masih ada yang bisa kami bantu bantu," Mas Joko pamit undur diri.
"Iya Mas, makasih banyak ya, Mas Joko, Mbak Romlah, dan juga Mbak Patmi. Hari ini sudah banyak membantu," kata Bu Ratih sambil berdiri, melepas kepulangan tamu tamunya.
Sepeninggal orang orang itu, suasana menjadi sepi. Hanya tinggal mereka berdua di teras itu.
Sepeninggal orang orang itu, suasana menjadi sepi. Hanya tinggal mereka berdua di teras itu.
Pak Slamet tersenyum sambil merengkuh bahu Bu Ratih, "nggak salah ya aku memilihmu untuk menjadi pendamping hidupku. Rasa pedulimu terhadap sesama, membuat dirimu seperti malaikat yang paling mulia. Aku semakin sayang padamu Dik," Pak Slamet mengecup lembut kening Bu Ratih.
"Ih, Mas apa apaan sih? Belum muhrim lho, sudah main cium cium aja," sungut Bu Ratih sengan wajah merona merah.
***
The End
***
The End
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh