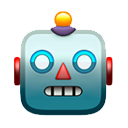(...)
yang Harry Potter kenakan setiap kali Ayah berpapasan denganku, pandangannya selalu lurus dan tidak mengedip sedikit pun saat aku lekat - lekat memelototitnya.
Aku tak tahu salah siapa dan berawal dari apa perang dingin di antara kami. Entah aku yang salah karena
(...)
mendiaminya terlebih dahulu atau dia yang salah karena mendiami aku, atau bahkan mungkin ini salah kami karena terpekur saat kesempatan untuk saling menyapa dan berbincang ada di depan mata. Ketidaktahuanku kurang lebih sama dengan ketidaktahuanku perihal ayam
(...)
dan telur, entah yang mana yang muncul duluan di permukaan bumi. Setiap pendapat terdengar benar dan salah di waktu yang bersamaan.
Bukan, aku tau benar ini bukan bawaan ayah, ini bukan setingan awal dirinya. Mungkin ia memang pendiam, tapi air mukanya dulu tidak
(...)
hambar begini. Aku lihat di foto - foto yang Ibu simpan, sorot matanya tegas dan senyuman tipis selalu terpatri di wajahnya. Kini senyuman itu tak ada, lebih buruk lagi sorot matanya pun tak lagi terang, sudah jadi keruh. Entah ini salah waktu atau salah aku.
(...)
Akan tetapi, aku tak pernah bisa membenci ayahku.
Setiap Sabtu, ia mengajakku keluar rumah di pagi hari, naik kereta yang bau tahi ayam, lalu naik bemo menuju Bendungan Hilir. Ia tak menjawab saat aku tanya tujuan jalan - jalan pagi kita. Menoleh pun tidak,
(...)
kakinya terus melangkah ke depan. Berjalan di depanku dengan jarak dua langkah dariku.
Setiap Sabtu, ia membawaku Bopet mini. Rumah makan padang yang kalah mewah dari RM. Surya atau Sederhana yang terletak di jalan yang sama, malah cendurung kumuh dan pengap.
(...)
Tapi aku tidak protes, karena mataku langsung dimanjakan dengan deretan lauk pauk, serta makanan penutup khas dari kampung ayahku, dari minang.
"Aruna, kamu sarapan pakai ________ lalu _______ ya, nak." adalah kalimat yang ia ucapkan tiap kali kami sampai.
(...)
kita sampai. Setiap minggu ia akan menyuruhku untuk memakan dua jenis makanan yang berbeda, makananya selaku makanan untuk sarapan, tak pernag sekalipun ia menyuruhku memakan lauk dan nasi.
Aku akan selalu menurutinya, membiarkan lidahku mencoba rasa yang asing
(...)
namun entah bagaimana mengingatkanku pada rumah.
Aku ingat pernah sekali ia menyuruhku makan bubur kampiun, lengkap dengan biji salak. Aku tak suka bubur kampiun. Rasa dari santan, gula merah, daun pandan seperti saling berkelahi adu dominasi — selalu mual aku
(...)
dibuatnya. Ayah seharusnya tau itu karena aku selalu mengacuhkan bubur kampiun setiap lebaran. Akan tetapi waktu itu, aku tak menolak dan melahap semangkuk penuh bubur kampiun tersebut.
Aku terhenyak. Barang kali biji salak yang tak ada rasa yang meredam manisnya
(...)
gula merah, atau gurih dari santan yang mengimbangi asamnya pisang kepok, atau mungkin kayu manisnya yang terasa serasi dengan daun pandan. Barangkali semua hal diatas bersatu membuat bubur kampiun di hadapanku menjadi bubur kampiun terenak sedunia.
Aku tak
(...)
mengatakan apa - apa. Mulutku terlalu sibuk mengunyah. Tanganku sibuk menyendoki bubur. Serta hidungku terlalu sibuk menghirup harum bubur di hadapanku.
"Pelan - pelan Aruna."
Pandanganku beralih dari mangkuk ke Ayah. Senyuman tipisnya serta sorot matanya sama
(...)
persis seperti di foto - foto lamanya. Bedanya kali ini, aku melihat secara langsung, serta pandangannya diperuntukkan untukku. Kami beradu pandang begitu singkat, sebelum kembali melahap makanan masing - masing.
Setiap Sabtu, Ayah menawarkan sepiring penuh sarapan
(...)
yang begitu kaya rasa. Aku pun akan selalu melahap makananku dengan sepenuh hati. Kegiatan kami di hari Sabtu adalah kegiatan yang sakral, karena setiap suap makanan yang kami lahap, tersimpan ucapan sayang yang meluap dan permintaan maaf sedalam - dalamnya.
(...)
Bagaimana bisa aku membenci ayahku ?