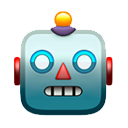"Ngeledek ..."
"Lah, muji aku ini, masa dibilang ngeledek."
"Abis kamu jarang muji."
"Berarti sekalinya muji itu jujur."
Si perempuan itu tertawa.
Perempuan itu masih tergelak.
"Kenapa sih? Tadi muji dibilang ngeledek, sekarang malah ngetawain."
"Muka kamu itu, Bagaaas."
"Muka aku kenapa, Nayla?"
"Memang serius mujinya ... memangnya kamu pikir nggak?"
"Bukan ... cuma, ya aku tadi ngerasa nggak bagus-bagus amat. Sempat sebel karena ada yg salah sebut."
"Tapi deal kan? Artinya bagus, La."
"Kesel sama siapa?"
"Sama diri aku sendiri, harusnya bisa lebih bagus dari itu. Masa yg paling pentingnya yg aku udah hafalin daei kemarin, udah sampe aku rehearse lagi, aku lupa bilang."
"Lebay nggak sembuh-sembuh ih!" Nayla terbahak lagi.
"Terpukau banget ya bahasanya."
"Emang."
Nayla menoleh ke Bagas. "Makasih ya."
"Bukan," Nayla tersenyum. "Makasih udah nemenin aku lembur ngerjain presentasinya."
"Nggak usah ge'er, aku ngincer uang lembur doang sih."
"Sial."
"Ngeselin kamu tuh kadang-kadang."
"Baguslah."
"Kok?"
"Ya bagus masih kadang-kadang. Kalo sering-sering ntar kamu muak liat aku."
"Baguslah."
"Bagus apaan?"
Bagas tertawa. Nayla yang tadi sengaja pasang raut kesal akhirnya juga tidak bisa menahan tawanya.
Nayla dan Bagas sama-sama menatap keluar jendela.
"Gas."
"Ya?"
"Andai lampu-lampu itu bintang ya."
"Aku kan bilangnya andai lampu-lampu itu bintang."
Bagas menoleh ke kiri, pandangan Nayla masih bertualang keluar jendela.
"Kamu ingat nggak waktu kita di Sumba?"
"Eh, nggak usah lebay ya, aku cuma muntah dua kali!"
"Tiga."
"Kan yang ketiga dikit doang, nggak dihitung."
"Perempuan nggak pernah salah memang."
"Kesel!"
"Gitu apaan?"
"Ngeselin."
"Untung sadar."
"... Tapi ngangenin."
"Bodo."
Tawa Bagas pecah.
"Aku kangen langitnya. Inget kan, waktu kita duduk di teras resort malem-malem ngeliatin bintang sampai jam 3 pagi?"
"Ingat."
Pipi Nayla bersemu merah. Bagas menatapnya dalam-dalam.
Obrolan mereka terhenti. Nayla menoleh. Di pintu pantry ada Yanto, pramubakti kantornya.
"Belum, To. Masih macet banget kayaknya di luar."
"Boleh deh, To, sekalian 2 ya. Buat Mas Bagas juga."
"Ha?"
"Dua. Buat saya dan Mas Bagas."
"Oh iya, Mbak. Monggo, saya ke dapur belakang dulu."
"Joke om-om banget kamu itu."
"Kan bener," Bagas tersenyum geli.
"Bodo ah."
Nayla menatap Bagas dengan tanda tanya.
"Permisi, Mbak, ini kopinya," Yanto kembali muncul dengan nampan, secangkor kopi diletakkannya di depan Nayla.
"Makasih ya, To."
"Ya itu, depan Mas Bagas."
"Yanto itu timing-nya pas banget ya," ujar Bagas setelah Yanto berlalu. "Pas aku mau ngomong serius, muncul aja."
Nayla tergelak.
"Warna lipstik kamu bagus."
"Apaan sih?"
"Ya itu, receh kan?"
"Ya Tuhan, ya nggak ngomongin warna lipstik jugaaa."
"Aku nggak ngalihin pembicaraan kok. Nggak di Sumba 2 tahun yang lalu, nggak juga malam ini."
"Kenapa ketawa?"
"Kita tuh memang aneh banget ya?"
"Aneh gimana?"
"Biasanya cewek yg suka sebel kalau perasaan itu nggak diucapkan, ini malah kebalikannya."
"Kamu?"
"Aku ada kerjaan dikit."
"Kok nggak bilang? Kan jadi makin lama pulangnya gara-gara nemenin aku ngobrol dulu."
"Kamu nggak mau pulang juga? Ngelembur di rumah aja gitu?"
"Nggak ah, di kantor aja. Nanggung."
"La, kalau mau minta temenin ke parkiran karena takut bilang aja kali, nggak usah pake muter-muter."
Nayla tertawa. "Tau aja."
"Ayuk."
Tidak ada kata-kata lagi di antara keduanya, cuma senyum dan tatapan.
Dia kembali ke atas, ke lantai 20, duduk di mejanya, kubikel tepat di sebelah meja Nayla.
Bagas tetap di tempatnya, dalam gelap. Menunggu sampai Nayla tidak perlu lagi ditemani. Menunggu sampai Nayla bisa melepas.
Menanti sampai Nayla bisa ikhlas.