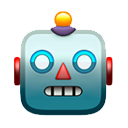.
.
Ini kisahku saat mengikuti Jumbara, disalah satu tempat yang sangat angker. Tempat bekas pembantaian PKI terbesar yang pernah terjadi dikotaku.
.
-A Thread-
.
.
@bacahorror #bacahorror #threadhorror

Harusnya sih. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita mau mengikutinya bukan?
PMR untuk tingkatan SMP disebut dengan PMR Madya.
Terkadang aku berteriak pada ibu, bertanya tentang barang-barang apa yang lupa kuletakkan.
Sekali lagi kutelusuri perlengkapan perang yang akan kugunakan selama 7 hari nantinya.
(Topi, slayer, badge, pin, buku saku, buku materi, rompi, seragam ... tiga, baju olahraga. Sudah siap semua).
Ucapku pada diri sendiri.
(Pasti sudah mulai ini pengarahannya).
Aku menyesali sifat burukku yang suka ngaret ini. Kudengar suara ibu yang lantang mengomel tentang angka jam dari luar kamar.
Suara klackson berbunyi beberapa kali. Seusai mencium tangan ibu takzim, kulihat muka sangar bapak yang sudah menunggu-
Bapak kebalikanku, tipe orang yang tak suka menunggu dan berlaku ngaret.
Dan benar saja. Dilapangan sekolah sudah berkumpul para PMR Madya yang membentuk barisan tiga banjar. Kebetulan sekolah kami terpilih mewakili kecamatan untuk acara Jumbara tingkat se-kabupaten kali ini.
"Wes ket maeng tah?"
(Sudah mulai dari tadi?)
Tanyaku sambil mengatur napas yang masih ngos-ngos an.
(Ya sudah dari tadi dheeeesss. Kamu kok sering telat sih?)
Aku meringis dan menunjukkan dua jari simbol perdamaian pada temanku Joko.
Dimana diantaranya bertugas untuk menata, sekaligus mengumpulkan perlengkapan kemah dan lomba.
(Ini bener jadi kesana? Apa namanya? Kebun Jengkol?)
Tanyaku pada Joko sembari memasukkan tali-tali tandu ke dalam kantung tas perlengkapan.
(Iya jadi. Lha mau dimana lagi?)
"Aku kok baru krungu yo? Ndak menurutmu akeh jengkol e nang kono? Ambune piye yo?"
(Aku kok baru dengar ya? Apa menurutmu di sana memang banyak jengkolnya? Baunya gimana ya?).
(Gak tau ya dhes. Aku juga belom pernah kesana).
(Dhasa dhess dhaaa dhesss. Kamu kira aku monyet. Dari tadi mulutmu kalau manggil gak sopan bener).
(Memang kamu kayak monyet).
Spontan ku toyor kepala Joko yang kurang ajar sekali itu.
Sedangkan anggota PMR Madya SMP Satu yang berjumlah lebih dari 20 orang beserta sang pembina, menaiki truk kemudian.
Karena lokasinya yang masih masuk kota, kupikir kami akan berada di wiliyah yang ramai.
Tapi perkiraanku salah.
Jarak rumah penduduk pun masih jarang-jarang. Yang kulihat hanya hamparan kebun-kebun tebu di samping kanan kirinya. Bukan jengkol juga.
Tak lama kemudian, truk melewati sederet bangunan rumah tua bergaya belanda, seperti wisma.
Rambutnya panjang berwarna pirang kecokelatan, hidung mancung, wajah kecil, kulit putih pucat, memakai pakaian terusan berwarna kuning dengan rok model mengembang.
Gadis kecil itu sepertinya memergokiku yang terus menatapnya. Ia pun menyunggingkan senyum seraya melambaikan tangan.
Gadis bermata biru itu berdiri seolah mengambang beberapa centi diatas tanah rerumputan. Aku merasa aneh, namun tetap berpikiran positif.
(Mungkin menginjak batu). Batinku kemudian.
"Jok... Joko.. ono bule ayu."
(Jok.. Joko ada bule cantik).
(Mana? Mana?)
Joko melongok, mengintip sekitar.
"Yo wes lewat goblok."
(Ya sudah lewat, bodoh)
(Halah kamu bohong. Mana ada bule di daerah pelosok gini).
"Gak ngandel yo wes. "
(Nggak percaya ya sudah).
**
(Bunga anggrek mulai tumbuh)
Kom dan toch terug bij mij
(Aku ingat padamu)
Nogmaals wil ik met je wezen,
(Waktu kita masih kumpul)
Zoveel leed is dan voorbij
(Kau duduk di sampingku)
(Engkau cinta kepadaku)
Ween ik haast van liefdes smart
(Bulan menjadi saksi)
(Dan engkau telah berjanji)
G’lijk weleer, mijn lieve schat
(Sehidup dan semati)
Judul lagu: "Als de orchideen bloeien" (Bunga Anggrek)
Acara terakhir adalah pembacaan susunan kegiatan dan lomba Jumbara selama sepekan dari ketua acara.
Kebetulan tenda kelompokku mendapat tempat tepat dipinggir jalan.
Para pembina mulai memberi arahan dimana seharusnya kami bisa membersihkan diri, dengan kata lain, mandi.
Ternyata antrian sudah memanjang seperti gerbong kereta api. Kurasa kelompok kami terlanjur telat mengantri
Menurut mereka kita bisa mengantri mandi di wisma. Jaraknya tak lebih dari 500 meter. Di sana kamar mandinya lebih banyak.
Tak sampai 5 menit kami sudah sampai. Kulihat bangunan rumah belanda yang kulewati tadi. Entah karena waktu sudah memasuki sore hari, wisma ini terlihat cukup menakutkan dibanding tadi.
Sudah hampir satu jam aku mengantri disalah satu bilik kamar mandi cewek. Namun antrian itu tak kunjung habis.
"Daripada awakmu kesuwen antri nang kene gak mari-mari."
(Daripada kamu kelamaan mengantri gak kelar-kelar antriannya).
Benar kata Tantri, dengan begini kami bisa selesai mandi lebih cepat.
Tak butuh waktu lama, tinggalah aku dan Tantri di sana. Tantri meminta masuk kamar mandi duluan. Karena ia bilang perutnya mendadak mulas.
"Als de orchideen bloeien ... "
"Kom dan toch terug bij mij ... "
Benar ada suara seseorang yang sedang bernyanyi. Lirih namun bernada riang.
"Tan... awakmu nyanyi ta?"
(Tan... kamu nyanyi ya?)
Tanyaku setengah berteriak.
"Haaa? Opoo?"
(Ha? Apaan?)
(kamu nya..nyiiiii kah???)
"Oraaa!"
(Nggak!)
Jawabnya lantang.
Rasa khawatir mulai menggelayuti
(Tan, cepetan kalau mandi. Gak usah lama-lama kayak putri ayu).
"Ween ik haast van liefdes smart ..
Want ik kan niet bij je wezen ..
G’lijk weleer, mijn lieve schat ... "
Hening...
"Hihihihi..."
Terdengar suara langkah kaki berlari kecil, seperti bolak-balik melewati luar kamar.
KRIEEEEET...
Ada seseorang yang duduk, diatas ranjang besi, dibelakangku. Aku tau, karena di rumah juga memiliki-
Aku melirik, tak benar-benar berani menoleh. Meski sekilas, kulihat seorang gadis berambut panjang duduk di atas sana. Kakinya mengayun secara bergantian.
"Kom dan toch terug bij mij ... "
(Dan kau telah berjanji padaku. Untuk selalu sehidup dan semati).
Tak lama kemudian sosok itu beranjak dari tempatnya. Berdiri dan berjalan mendekatiku.
Suara pintu terbuka. Tantri menampakkan diri dari sana.
Disaat yang sama aku langsung menoleh. Sosok itu menghilang. Aku ingat, pikiranku seperti melaju kencang di dalam kepala. Aku yakin telah melihat seseorang tadi. Mungkinkah itu hanya imajinasi.
"Awakmu kenopo?"
(Kamu kenapa?)
Tanya Tantri yang sepertinya menangkap ekspresi pucatku.
"Ora popo."
(Nggak apa-apa)
"Yowes ndang adus selak bengi."
(Ya sudah. Buruan mandi, keburu malam).
Setelahnya aku memasuki kamar mandi, melakukan ritual mandi secepat kilat. Di dalam sana, lagi-lagi aku merasa ada seseorang berdiri dibelakangku.
(Haduh. Mandi aja masih diintip setan)
Keluhku dalam hati.
Aku ketakutan. Namun tetap berusaha bersikap berani. Berharap sosok itu tak mencium rasa takutku. Setelah selesai dan berpakaian, cepat-cepat aku membuka pintu kamar mandi.
"Asem. Tantri ninggal aku." Umpatku kesal.
(Sial. Tantri ninggalin aku).
Sontak aku melangkahkan kaki setengah berlari, meninggalkan kamar itu secepatnya.
Kudengar langkah kaki berjalan di lantai atas mendekati tangga.
"Hadooh."
Dan benar saja, langit sudah benar-benar kelam. Kulihat masih ada yang mengantri di depan kamar mandi, meski sudah tak sebanyak tadi.
Mataku menelisik orang-orang. Berharap bisa menemukan seseorang yang kukenal.
"Loh Tan? Lapo awakmu nang kene? Jek kebelet ta?"
(Loh Tan? Ngapain kamu disini? Masih mules ya?)
"Lha nyapo maneh? Yo antri adus lah."
(Ngapain lagi? Ya antri mandi lah).
"Adus maneh? Bukane awakmu wes adus ya?"
(Mandi lagi? Bukannya kamu sudah mandi ya).
Tanyaku memastikan.
"Gundulmu. Aku ki jek antri ket maeng."
(Aku ini sudah antri dari tadi)
"Ojo goro. Bukane awakmu mari adus bareng aku nak lantai duwur? Awakmu sing ngejak malah."
(Jangan bohong. Bukannya kamu sudah mandi barengan aku tadi di lantai atas? Kamu yang ngajak malah).
Karena penasaran, aku berjalan kembali ke lorong,-
Yang kulihat disana memang gelap. Tak ada cahaya lampu sedikitpun.
Aku menepuk pelan kedua pipi dengan telapak tangan. Kudengar suara-suara aneh itu lagi. Aku pun bergegas kembali ke rombongan.
Di sana, di salah satu jendela. Kornea mataku menangkap satu sosok mengintip dibalik jendela.
Dimana mata indah itu sudah tak tampak. Berganti cekungan hitam yang kelam dan dalam.
***
Kini akan kuceritakan tentang para penunggu bilik kamar mandi di dekat bumi perkemahan. Ntah bangunan bilik itu masih ada atau tidak sampai sekarang. Aku tidak tahu.
Keesokan hari setelah seharian usai melakukan rentetan kegiatan Jumbara-
Alasannya kalian bisa kalian tebak dengan mudah. Tentu saja aku tidak mau bertemu dengan noni muda di wisma Belanda itu lagi.
Di depanku ada satu teman sekolahku, Irma namanya.
Tiba giliranku, Irma sudah berada diluar, menyuruhku segera-
(Cepat masuk ke dalam. Nungguin apa lagi sih kamu? Keburu makin gelap). Tegur Irma kemudian.
“Kosek.. kosek tow sabar.”
(Bentar.. bentar. Sabar dulu lah)
Mungkin hawa negatif yang sudah bertumbuh besar saat ini cukup bisa mempengaruhi Irma, apalagi aku. Melihat gelagat itu dengan terpaksa kakiku melangkah ke dalam.
(Beneran ya aku jangan ditinggal). Ucapku memastikan sebelum akhirnya menutup pintu bilik.
Tak kusangka bilik ketiga ini begitu luas. Tak seperti kamar mandi pada umumnya. Bahkan untuk berjalan mencapai arah bak mandi dari pintu,
Saat tangan mulai bergerak mengguyurkan air, saat itu juga ‘mereka’ muncul. Dugaanku salah jika di dalam bilik hanya ada satu.
Bagaimana aku bisa tau? Saat aku memejamkan mata demi melindungi kornea mata dari aliran air. Disaat itu juga, sosok mereka terlihat jelas. Ini bukan seperti kita mengkhayal atau membayangkan sesuatu.
Saat membuka mata, aku melirik sekilas. Benar saja ada sesuatu dibelakang sana. Lagi, aku memastikan dengan memejamkan mata sembari melanjutkan-
Aku keder dengan penglihatan yang sangat menyeramkan itu. Karena tensi ruangan yang semakin rendah.
Mereka tak mendekat seperti noni Belanda, tetap terdiam ditempatnya.
Kali ini terdengar suara rambut yang disisir, namun seperti tersendat beberapa kali.
SREETTT… SREEEETTTT….
Suara rambut yang disisir lagi.
Aku benar-benar berusaha menguatkan hati. Sosok-sosok itu sedikit banyak berhasil menyerang psikis.
Pintu kamar mandi menutup dengan sendirinya. Spontan aku yang terkaget langsung berlari. Ketika melewati tembok jalan keluar barisan bilik kamar mandi, aku menabrak seorang pemuda seusiaku.
Aku yang terpental ke tanah, dia yang mengumpat.
“Cuk!!!”
Aku sempat terbengong sepersekian menit. Bukan, bukan karena terpesona melihat si pemuda layaknya dalam adegan film-film romantis remaja.
Tepatnya dideretan bilik kamar mandi. Kemudian menatapku lagi.
Ia mengulurkan tangan. Namun aku berdiri sendiri sembari memunguti perlengkapan mandiku yang berserakan di tanah.
“Awakmu rapopo?”
(Kamu nggak apa-apa) tanyanya kemudian.
(Nggak apa-apa. Maaf nggak sengaja nabrak).
“Opo’ o? Bar ndelok demit a?”
(Kenapa? Habis liat hantu ya?)
Ntah iya memang bertanya atau hanya sekedar menebak-nebak, perkataannya cukup membuatku terkesiap.
“Anu… iku …” (Anuu.. itu..)
(Lha itu itu mbak kuntilanak dan hantu bocahnya ngeliatin kita dari sana)
Ia mengatakannya sembari tersenyum kecil.
Dadaku kembali berdegup kencang.
“Asem.” Ucapku lirih.
“Hai Ajiiiiiii.” Sapa mereka serentak, sembari tertawa-tawa kecil. Ekspresi mereka malu-malu dan terlihat riang, seolah sedang bertemu dengan seorang idola.
Tanya salah seorang perempuan berambut Panjang yang wajahnya lumayan.
“Ndelok engko.” (Lihat saja nanti).
“Main yo Ji. Mengko kene ndelok. Gitaranmu penak soale.”
Aku seperti mau muntah mendengarnya. Kali ini Aji hanya tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah katapun.
Kini aku memandang Aji lekat dengan mimik penasaran. Aji yang melihat ekspresiku menyipitkan mata.
“Lapo?” (Apa?)
(Kamu bisa liat kan?) Tanyaku penasaran.
“Ndelok opo?” (Lihat apa?)
Aku menoleh ke kanan dan ke kiri, sedikit mendekatkan diri. Aji melangkah mundur karena risih.
“Demit.” (Hantu) Bisikku kemudian.
“………………”
“Iyo kan?”
Ini adalah awal mula perkenalanku dengan salah satu teman indigo di Kebun Jengkol.
**
Aku mengamati pertunjukkan yang disajikan di atas panggung, diantara hiruk pikuk lautan peserta kemah malam itu. Tiap malam usai kegiatan dan lomba, panggung itu tak pernah sepi. Selalu saja ada yang menyumbangkan bakat-bakatnya untuk meramaikan malam perkemahan.
“Tumben awakmu nang kene? Biasane ngumpul nang jurit malam?”
(Tumben kamu nongkrong disini? Biasanya juga ngumpulnya di area jurit malam). Tanya Devi yang berada disampingku.
Aku melirik “Bariki arep cuss nang jurit malam owg. Ki yo karo ngenteni wong soale”
(Bentar lagi juga pindah ke area jurit malam kok. Ini juga karena lagi nunggu seseorang).
Alunan gitar itu terdengar enak sekali mengiri suara penyanyi pria yang cukup merdu di atas panggung. Kulihat orang-orang disekitarku juga sangat menikmatinya.
“Nang ndi aeeeeeeeeee?” (Kemana aja kamuuuuu kok baru tau) Cibir Devi kemudian. Kukibaskan tanganku padanya, karena suara cemprengnya yang cukup memekakkan telinga.
“Yess. Wayahe nang jurit malam saiki.” (Yess. Waktunya pergi ke jurit malam).
“Loh? Wes arep ngaleh saiki? Iki jek ono perform liyane loh. Gak kalah apik. Emang awakmu ngenteni sopo se iki?”
(Loh? Udah mau pergi sekarang? Ini masih ada perform yang lain loh. Gak kalah bagus juga. Emang kamu dari tadi nunggu siapa sih?)
“Karo arek kae.” (Sama tuh anak).
Devi memandang kearah Aji lalu bergantian padaku dengan tatapan tak percaya.
(Kamu kok bisa kenal dia?? Kok bisa kenal anak itu gimana ceritanya?)
Devi mengguncang-guncangkan pundakku dengan bar-bar.
(Ya kenal aja. Heh! Jangan guncangin badanku kayak gini nyet).
“Kenalke aku. Pokok e kudu ngenalke nang aku.”
(Kenalin ke aku. Pokoknya harus dikenalin ke aku). Ancam Farra.
“Yo.”
Aku tau, Devi memang tidak bisa melewatkan orang sebening apapun dari hadapannya. Saat Aji menghampiri, bisa kurasakan beberapa mata mengarah tajam pada kami. Ini lebih bikin merinding dari pada diliatin setan apapun.
(Ayo. Ayo cepet. Keburu ketinggalan banyak cerita horornya).
Aji tertawa “Lah awakmu ki seneng cerito medeni tapi kok yo wedi demit.”
(Lah kamu suka cerita horror tapi kok masih takut kalau diliatin setan).
(Iya sih. Aku emang takut, tapi nggak tau kenapa seneng aja kalau ada yang cerita horror misteri gitu. Seru dan bikin penasaran).
Salah seorang diantaranya tampak berdiri, serius menceritakan kisah seram miliknya.
Dari situ aku mulai merasakan hawa merinding. Bulu kudu tengkukku berdiri sempurna.
Secepat kilat Aji menarik lenganku kuat-kuat, hingga aku berdiri dengan sempoyongan. Berusaha mengatur keseimbangan.
Aku melihatnya, seorang peserta perempuan jumbara tampak mengamuk tiba-tiba. Dan langsung dipegangi beberapa peserta yang lain.
Gadis itu berteriak histeris, lalu berubah suara menjadi tawa cekikikan, dan berubah lagi merintih, mengerang kesakitan.
(Tolong. Tolong carikan kepalaku). Ucapnya di sela-sela rintihan.
Lalu datang seorang bapak-bapak setengah baya berpakaian komprang mendekati peserta yang kesurupan.
“Aku mung jaluk golekne sirahku. Lapo malah mbok usir.-
(Aku cuma minta dicarikan kepalaku saja. Kenapa malah diusir. Huaaa … Huaaaa… Aku panggil semua teman-temanku. Biar kalian semua rasakan akibatnya).
Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan lagi. Ada peserta lain yang juga kesurupan. Tak hanya perempuan namun juga laki-laki.
“Na… pikiranmu ojo sampe kosong yo? Dungo-dungo terus.”
(Na… pikiranmu jangan sampai kosong ya. Baca doa terus) Peringat Aji padaku.
“Ji.. Aji… “ Panggilku kemudian.
Aji menoleh “Lapo Na?” (kenapa Na?)
“Iki Ji… gegerku abot. Ono opo iki?”
(Ini Ji. Punggungku berat. Kenapa ini?)
Aku sampai terduduk saking lemasnya. Untungnya aku masih tersadar.
(Sebentar Na. Kamu diam dulu).
Aji memegang tengkuk belakang dan salah satu jempol tanganku, sembari membaca doa-doa. Aku bisa merasakan suatu energi saling tarik menarik disana.
“Weslah ayo. Tak terke balik nang tendo mu ae.”
(Ya sudah. Ayo balik ke tenda lagi).
“Hihiihihihiiiiiiii..”
Aku yang kaget langsung melangkah mundur seketika.
“Asem.” Umpatku.
Gadis itu masih tertawa melengking sembari menatapku ngeri.
(Ayo nak. Bantu aku mencari tanganku).
Gadis itu mengatakannya sambil menggoyang-goyangkan salah satu tangannya, menunjuk kearahku.
“Lha iku tanganmu!” Bantahku kemudian
“Minggat o awakmu.”
(Pergi kamu). Bentak Aji pada kemudian.
Akhirnya kami sampai ditenda. Kulihat beberapa temanku ternyata sudah tertidur di sana.
“Sopo yo kui?”
(Siapa itu?)
Gumamku heran.
***
Aku masih ingat waktu itu. Ketika petang menjelang dan hampir semua mata pasti terlelap. Aku mendengarnya, suara langkah kaki kuda, lalu roda-roda yang melaju melewati atas tanah. Sesekali terdengar kuda yang meringkik.
Dan benar saja, kulihat sekilas bayangan delman/ dokar yang melintas yang terlihat dari dalam tenda. Awalnya aku berusaha berpikiran positif.
Dan entah kenapa tiap delman itu lewat, aku selalu terjaga. Seolah-olah memang harus menyambutnya.
Bagaimana jika yang lewat itu memang manusia? Dan kusir delman itu memang kebetulan pulang di jam-jam dini hari karena jasanya masih diperlukan hingga larut malam?
Tak lama kemudian, terdengar langkah-langkah kuda, bergerak bergantian. Lalu suara gemericing.
Aku sangat yakin sudah tak ada yang terjaga lagi, mungkin. Kurasakan angin dingin sepoi-sepoi menerpa wajahku.
KRICINGGG KRICINGG KRICIIIINGG….
Aku menoleh dan bergerak keluar tenda akhirnya. Sepertinya delman itu sudah bergerak lumayan jauh dari tendaku. Dan itu memang benar-benar delman beserta kusirnya.
Samar kudengar suara wanita cekikikan, saling bersahutan. Hal itu cukup mengagetkan dan menakutiku. Hingga aku langsung saja berlari dan membelasakkan badanku ketika memasuki tenda.
“Hancikkk.. Ngageti ae. Lapo awakmu kok malah gedebugan ngene?”
(Sial! Ngagetin aja. Kamu habis ngapain memang?) Umpat Tantri setengah terjaga karena kupepet begitu saja.
“Sepurane. Ono demit nang njobo.”
(Maaf. Ada hantu diluar)
“Demit opo? Ojo meden-medeni awakmu.”
(Hantu apa? Jangan nakut-nakutin kamu)
“Wes … mbuh. Turuo ae pokok e.”
(Gak tau. Pokoknya tidur aja)
HIHIHIHIHIHIIIIIII
Tantri mulai capek sepertinya, lalu membiarkanku. Seiring berjalannya waktu, aku sudah tak mendengar suara tawa lagi,-
Malam keesokan hari aku mendengarnya, suara deru delman beserta loncengnya. Kali ini jam 2 dini hari. Mataku memang terbangun, tapi kubiarkan saja.
Kulihat sebuah bayangan berdiri di depan tenda. Masih dengan pencahayaan temaram-
Apa itu? Bayangan seorang lelaki? Berdiri mematung di depan sana. Tapi bayangan itu membuatku merinding dan membeku seketika.
Bayangan itu terlihat tidak utuh sempurna, kepalanya menghilang. Menyisakan setengah leher yang terputus. DItangan sebelah kanan seperti membawa pecut. Aku membaca doa-doa, anehnya bibirku tak mampu bergerak.
Bayangan itu semakin mendekat, mendekat, dan kini tepat berada diluar pintu tenda. Tak kudengar suara hewan malam apapun saat itu, bahkan suara angin yang biasa menggerisik dedaunan keringpun tak ada.
Baru kusadari bahwa aku mengalami 'Sleep Paralyze'.
AAAARRHHKKK AAARRRHHHKK…
Ntahlah.. Aku tak punya waktu memikirkan hal itu. Suara orang tercekik itu makin menambah kengerianku. Masih kupaksakan ujung jariku bergerak dengan susah payah.
Sosok itu sudah menghilang. Aku menoleh disekitar, hal apa yang akhirnya membuatku bisa bergerak.
Kali ini aku yakin dia manusia, meski samar aku cukup familiar dengan sosok itu.
“Awakmu lapo nang kene?”
(Kamu ngapain di sini?) Bisikku dengan nada mengancam. Sambil menoleh kanan kiri.
“Sakjane ki aku ngerungokne ‘matur suwun’ loh. Gak malah dicelatu ngene.”
Aku terdiam dan baru kembali bisa berpikir. Rasa panik yang ditimbulkan akibat sleep paralyze benar-benar membuat moodku kacau balau.
“Iyo Ji. Suwun. Hehe.”
(iya Ji. Makasih. Hehe.)
(iya aku paham kalau kamu takut tertangkap kamtib lalu kita dikira ngapa-ngapain. Tenang aja,-
“Aku temenan suwun Ji. Awakmu kok ngerti lek aku lagi kelindihen?”
(Aku beneran terima kasih JI. Kamu kok bias tau kalau aku lagi ketindihan?)
“Yo ngerti. Wong mbah (khadam) duduhi awakmu lek lagi kenopo-nopo. Ngunu awakmu kok gak cerito?”
(Ya ngerti. Dikasih tau sim bah (khadam) kalau kamu lagi kenapa-napa barusan. Kenapa kamu gak cerita sebelum-sebelumnya).
“Hehe. Iyo. Aku wedine nek dokar sing lewat kui kusire ancen manungso duk demit. Eh ternyata demit tenan. Pantesan kok ono dokar narik tengah wengi. Ehh ladalah lah kok…”
Aku tak mampu meneruskan ucapanku karena merasa sangat merinding saat mengingatnya.
“Makane ojo kemeruh. Ojo terlalu penasaran. Senajan wes kethok aneh gak usah diterusne. Sampe di intip baranng. Gantian kan akhir e dikinthili tenan.”
(Makanya gak usah sok tahu. Gak usah terlalu penasaran. Kalau dirasa sudah aneh jangan-
Aji menuturkan kata-katanya dengan serius tanpa ada nada bercanda sedikitpun. Aku hanya terdiam.
“Kapan-kapan tak critani tentang opo sing kedaden nang kene. Aku gak pengen meden-medeni.
(Kapan-kapan aku ceritakan tentang apa yang terjadi di sini. Bukan ingin menakuti. Hanya saja kedepannya agar lebih berhati-hati).
***
Aku memandang arloji di pergelangan tangan, jarum jam masih menunjuk angka 10 pagi, tapi langit malah menampakkan wajah mendung.
Aku menghela nafas. Kupandangi ketiga temanku yang masih berdikusi mengenai lomba Pertolongan Pertama,-
Tak lama kemudian terdengar suara sirine tanda waktu perlombaan sudah dimulai.
Para peserta Jumbara tingkat Madya gelombang kedua berkumpul ditengah lapangan sesuai kelompok.
“Ra jelas.”
(Dasar nggak jelas). Gumamku lirih.
Meski kami berteman baik tapi di medan perlombangan kami tetaplah lawan. Kini ganti kulihat Joko dengan ekspresi aneh, dia menatapku-
“Lapo?”
(Ada apa?) Tanyaku sinis.
“Ngaku wae.”
(Ngaku saja)
“Ngaku opo?”
(Ngaku apa?)
“Awakmu gendak’an karo arek kae tow? Arek sing ben bengi sering gitaran nang panggung?”
Aku langsung terbatuk-batuk seolah ada biji kedondong yang tiba-tiba saja menyangkut ditenggorokan. Aku dan Aji pacaran? Hahahahaha.
(Heh? Dengerin ya. Aku ini …)
Belum selesai aku berbicara terdengar suara peluit yang kencang, yang mana cukup membuat telinga para peserta berdenging seketika.
Bagaimana tidak? Suara peluit itu memang sengaja diarahkan kearah mikrofon-
Hingga akhirnya, para peserta gelombang kedua membubarkan diri menuju ke pos masing-masing.
Setelahnya, kupastikan bahwa bentuk simpul sudah benar dan kuat sesuai dengan SOP buku materi-
Kami pun mulai berjalan menuju pos kedua, mengambil perlengkapan P3K yang mana akan digunakan sebagai simulasi menolong si korban. Aku masih ingat, waktu itu kelompok kami mendapat tugas menolong korban kecelakaan lalu lintas.
Meski masih siang, bisa kurasakan hal yang kurang mengenakkan ketika melewatinya. Bulu kudukku sedikit meremang entah mengapa.
Akhirnya kami sampai juga di pos tiga. Kami melapor pada panita penjaga dari kelompok mana kami berasal.
Dalam rekontruksinya, Vita adalah seorang korban tabrak lari dari sebuah mobil yang melaju kencang.
Kami pun mendekati Vita lalu menganalisa seberapa parah lukanya. Kemudian memulai prosedur penyelamatan.
Kami menandu Vita tanpa kesulitan yang berarti dengan berat badannya. Karena badan Vita terbilang kurus dan kecil.
Aku sedikit terkejut, apalagi Vita yang hampir terhempas ke tanah.
“Heh? Opo’o?” Tanyaku spontan.
(Heh? Kenapa?)
“Cuk. Vita dadi abot?” Umpat Joko
(Cuk. Vita jadi berat)
(Sial. Berat badanku aja nggak sampe 37). Bantah Vita tak terima.
“Sumpah. Kok awakmu dadi abot ngene sih Vit? Bar mangan opo se?” Anwar ikut menimpali.
(Sumpah. Kamu kok jadi berat banget gini sih Vit? Habis makan apa kamu?)
Aku, Joko, dan Anwar saling berpandangan. Ya memang benar apa yang dikatakan Vita, kami tak ada masalah-
Hingga akhirnya entah mengapa pandangan mataku mengarah pada pohon besar yang berdiri kokoh tak jauh dari sana. Seolah ada sesuatu yang memberitahu bahwa kesulitan yang kami alami berasal dari sana. Aku menggeleng-gelengkan kepala
Bagaimanapun misi kami tak boleh gagal. Akupun ikut memegang salah satu pegangan bambu. Dan itu memang berat sekali, seolah kami memang sedang menahan berat beban orang dewasa.
(Udah, gak usah rebut. Ayo diteruskan lagi jalannya biar cepet nyampe pos. Sini aku bantu pegang penyangganya). Ucapku memberi sebuah ide.
“Heh? Nek weruh panitia kene iso didiskualifikasi.”
(Heh? Kalau sampai ketahuan panitia bisa-bisa kena diskualifikasi). Peringat Joko.
Joko dan Anwar saling berpandangan. “Wes, gak usah kakean mikir dhess. Ben ndang nyampe pos. Jare aku abooooot.”
Tampak ia masih kesal sekali karena menjadi yang tertuduh secara tiba-tiba.
Selama dalam perjalanan, beberapa kali tandu mengalami ketidakseimbangan dan hampir terjatuh, karena posisi menyangga yang tak sejajar disertai dengan berat Vita yang berubah-
Tak lama kemudian, beberapa meter di depan, pos keempat sudah mulai terlihat. Aku pun melepaskan pegangan secara perlahan.
Disana kulihat raut wajah Joko dan Anwar yang terlihat semakin menegang karena menahan beban yang semakin berat.
“Cukkk. Abot tenan.”
(Sial. Berat banget) Umpat Joko sekali lagi.
Aku hanya menghela nafas melihat ketiganya.
KRASAKKK.. KRASAKKK … KRASAKKK…
“Toloooooong! Toloooooooong!”
Spontan kami ber-4 menoleh kesumber teriakan.
"Asem! Opo maneh iki?"
(Sial! Apa lagi ini?)
**
Bukan! Lebih tepatnya panitia-panitia itu sedang menahan seorang peserta Jumbara yang kulihat berlari-
Matanya masih kosong namun menatap tajam pada sesuatu.
“Asu! Sopo sing dulinan karo sajen e? Ngaku!”
(Anjing! Siapa yang sudah bermain-main dengan sesajennya? Ngaku!)
Terjadilah keributan lain disana yang mengakibatkan panitia jadi bertambah bingung harus memisahkan siapa. Aku mencoba menerobos kerumunan dan yang kulihat Aji ternyata sudah memukul seeorang peserta laki-laki-
“Aku gak sengojo. Tak kiro yo gak bakal ngaruh opo-opo.”
(Aku nggak sengaja. Aku kira ya nggak bakal ngaruh apa-apa)
(Sial! Kamu harus ngerti tata krama yang bukan tempat asalmmu. Kamu kira hal itu tak berakibat dengan yang lain?)
(Kenapa sih? Kan itu Cuma tempeh berisi bunga dan jajanan pasar)
“Heh! Delok en kui kancamu sampe kayak ngunu.”
(Heh! LIhat temanmu sampai seperti itu) Tunjuk Aji pada peserta yang kerasukan.
(Nggak Cuma itu. Kamu sudah membuat marah yang punya tempat).
Laki-laki berkulit sawo matang itu tampak kebingungan mendengar ucapan Aji. Tak lama kemudian beberapa panitia langsung menarik Aji dan tiga peserta-
Keesokan harinya hal aneh lagi-lagi terjadi. Saat acara lomba dapur umum, hampir semua masakan peserta Jumbara menjadi basi.
Hingga akhirnya panitia memberi kriteria penilaian baru dimana penilaian rasa bukan menjadi salah satu-
Aku mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu dengan mencari Aji. Namun entah kenapa, aku malah jarang melihatnya. Bahkan ketika kita tak sengaja bertemu, Aji tampak sengaja menghindar.
Hingga di suatu siang menjelang sore dimana hari itu adalah hari terakhir bermalam Jumbara, Aji tiba-tiba saja mendatangi tendaku. Kebetulan waktu itu memang jam-jam kosong,-
Aku yang sedang asik berbaring sembari membaca sebuah komik yang kuarahkan tepat di depan wajah, menjadi terganggu karena suara siulan-
“Dikiro aku manuk opo yo diceluki karo suiwitan?”
(Dikira aku burung apa ya dipanggil dengan siulan?) Cibirku saat melongokkan kepalaku dari celah pintu tenda.
Aji tertawa dengan masih suara khasnya.
(Tetep aja ngambekan).
Akhirnya aku keluar seluruhnya dari tenda.
“Aku ra mutung Ji. Kirane awakmu wes ra gelem koncoan maneh karo aku.”
(Aku nggak marah Ji. Aku kira kamu yang malah gak mau berteman lagi sama aku). Ucapku dengan mimik serius.
(Ehem. Ya nggak gitu Na).
Aji tampak mengambil jeda beberapa saat, lalu melambaikan tangannya memanggilku. Aku pun mendekat.
“Yok melu aku, tak critani kabeh sing pengen mbok weruhi saiki. Tapi critone ojo nang kene.”
Mataku membulat dan tak bisa kutahan lagi senyuman yang tertarik begitu saja dibibirku.
“Tapi ceritane ngeri.” Jelas Aji.
“Ora popo.”
(Nggak apa-apa). Sahutku cepat
“Engko awakmu wedi terus malah sawan.”
(Nanti kamu takut terus malah kebayang-bayang).
“Iki engko pasti akeh loh bangsane demit buntung wingi sing melu ngerumpi pas aku nyeritakne iki.”
“Haduhh jek awan Ji. Aku wani. Untunge aku yo gak kethok. Hahaha. Iki asline niat pengen ngekek I weruh gak se, kok awakmu takoooooon ae?!”
Lagi-lagi Aji tertawa sembari menggelengkan wajahnya pelan. Ntah kenapa menurutku dia memang aneh.
“Yowes ayok.” Ajaknya kemudian.
“Nang ndi?” (Kemana?)
“Gendak'an! Jare pengen dicritani dheeeeees. Ojo nang kene tapi.”
“Oh iyo se.” Aku menepuk dahiku lalu melempar komikku serampangan kedalam tenda.
Akhirnya aku mengikuti langkah Aji dari belakang dan menjajarinya. Hingga akhirnya tibalah kami di sebuah bangunan gedung-
Bangunan ini adalah gedung kebun djengkol yang bersejarah itu.
***
Sabaaaaarrr readerku tercintah. Next update lebih panjang dan .... thread terakhir dari Kebun Djengkol.
Iya, Banana juga pengen segera nyeleseiin thread ini kok. Jadi.. Stay tune for the next Up!
“Awakmu pernah weruh ta sejarah e bangunan iki bekas e opo?”
(Kamu pernah tau tidak dulunya bangunan iki bekas apa?) Celetuk Aji tiba-tiba
Aku menggeleng. “Bekas opo emang e?”
(Bekas apa emang?)
Aji menoleh dan menatap serius padaku
“Sing nggenah?” (Yang bener?)
Aji mengangguk pelan tanpa mengucap sepatah kata pun. Seketika bulu kudukku meremang, perasaan tak nyaman yang kurasakan sebelumnya ternyata benar.
Pantas saja hawa kelam seolah menyelimuti tempat ini, membuatnya-
“Awakmu ngerti tekan endi Ji? Buku sejarah? Opo ono sing ngekeki weruh sak durunge?”
(Kamu tau dari mana Ji? Buku sejarah? Atau ada yang pernah memberitahu sebelumnya?)
(Biasalah. Sejak kaki ini menginjak tanah penataran perkebunan Jengkol ini pertama kali. ‘Mereka’ sudah berbondong-bondong membisikiku.)
“Loh? Ji? Aji?” Panggilku.
Aji menoleh sekilas dan memberi kode untuk mengikutinya.
Aji menatap bangunan tua itu dengan seksama, matanya meneliti setiap inchi sekat dan ruang-ruang yang tak utuh lagi. Sesekali tangannya meraba bagian tembok yang berdebu dengan-
Aku yang tak begitu mengerti apa yang dilakukannya, hanya mengikuti dalam diam. Meski tanganku terus-
Tak beberapa lama kemudian, Aji tiba-tiba saja menarik tanganku keluar dari bangunan itu. Sekali lagi aku menoleh kebelakang, menatap bangunan itu. Masih senyap, kosong,-
Hingga akhirnya kami kembali ke bumi perkemahan, hanya saja Aji malah mengajakku membeli sate bekicot di salah satu pedagang kaki lima.
Kami singgah di bawah pohon beringin yang cukup rindang sembari menikmati jajanan yang baru saja dibeli. Sedikit menjauhi hiruk pikuk manusia.
Hanya saja Aji memang begitu orangnya. Aku sengaja menunggu Aji memberi penjelasan sendiri, karena ia tak akan pernah mau menjawab pertanyaan jika bukan karena kehendaknya.
(Tadi rajanya tiba-tiba datang. Makanya kamu langsung kutarik pergi)
“Emang rojone kayak piye?”
(Memang wujud rajanya kayak gimana?)
(Naga raksasa. Naga itu tidak begitu suka dengan si ‘mbah’. Maka dari itu lebih baik pergi saja dari sana. Padahal tadi aku belum selesai-
Aku mengerjap penasaran “Cerito opo?” (Cerita apa?)
Aji hanya melirik sekilas, lagi-lagi tak menjawab pertanyaanku.
“Tak critani ae soal kejadian naas bien sing tau kedaden nang kene ae yo.”
“Emang ceritane bedo karo cerito sing mbok rungokne maeng?”
(Memang ceritanya beda dengan cerita yang tadi kamu dengarkan?)
“Bedo.” (Beda). Jawab Aji singkat.
(Emang kamu nggak mau ngasih tau aku gitu cerita yang satunya lagi?)
Aku menyunggingkan senyum semanis mungkin, namun sepertinya tak berefek apapun pada Aji.
(Lebih baik kamu tak perlu tahu!)
Aji memberi penekanan kalimat tentang cerita yang dimaksud. Jika memang demikian, meski dipaksa seperti apapun. Ia tak akan pernah membiarkan cerita itu keluar dari mulutnya barang sepatah katapun.
Jawabku sembari mengulum bibir membentuk mimik wajah masam.
“Eh, tapi mending entekne sik cilokmu.”
(Eh, tapi lebih baik habiskan dulu cilokmu). Peringat Aji.
Aku mengangkat sebelah alis. “Emang lapo?” (Memangnya kenapa?)
**
Dalam kisah ini, aku akan menjadi sudut pandang Aji, dan dalam beberapa kurun waktu menjadi sudut pandang orang ketiga. Sedikit peringatan, untuk kalian yang kurang menyukai cerita SADIS mungkin bisa men-skip dari sudut pandang Aji.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Namun ada yang sedikit berbeda, dari tempat yang sebelum-belumnya pernah kusinggahi. Aku bisa mencium bau anyir-
Bahkan ketika aku mulai membangun tenda bersama teman-teman, ‘mereka’ sudah mengerumuniku begitu saja. Membisikkan sesuatu yang lumrah kudengar, sebuah kata ‘minta tolong’.
Aku belum bisa menangkap objek mereka dengan sempurna,-
Malam hari seusai kegiatan Jumbara, aku menghabiskan waktu berjalan-jalan mengitari area perkemahan sendirian. Lalu kulihat sesosok gadis kecil mengintip dari balik pohon.
Aku bertanya apa yang membuatnya bersedih. Ia tak menjawab apapun, hanya memegang tanganku.
Gadis kecil itu terdiam, menatapku dingin. Lalu telunjuk tangannya mengarah pada sesuatu dibelakangku
Ada yang kepala, tangan, kakinya hilang. Ada yang penuh luka sayatan dan tusukan. Ada yang tubuhnya gosong terbakar.
“Tak kek’i weruh.”
(Akan aku tunjukkan).
Senjakala membawa gelap yang menyusup dari balik jendela.
Di sebuah rumah kecil berdinding anyaman bambu dan beratap rumbai daun kelapa,-
Seorang gadis kecil berkepang dua membuka tabung kaca yang terpasang di dalam kamar tidurnya.
Menyalakan sumbunya.
Kamar itu tak memiliki dipan, melainkan selongsor kasur kapuk tipis yang dimana isinya sudah hampir habis, terbentang di atas tanah.
Tak lama kemudian ia menutup jendela kayu kamarnya secara perlahan.
Tak lama kemudian, suasana malam yang tenang itu berubah mencekam. Mereka datang, segerombolan pria berselimutkan aura dendam dan mencekam.
Berbagai jenis senjata tajam, mulai dari parang, golok, kelewang, hingga celurit menggantung rapat ditangan masing-masing.
(Cepat Keluar Semua!)
Kudengar hardikan diantara mereka. Suaranya merambat dengan jelas diudara hingga menyentuh kasar gendang telinga.
Lalu menggedor paksa tiap pintu-pintu rumah. Tak pandang bulu, bisa kudengar kayu-kayu penghalang itu berderik hingga hampir-
“Nyuwun ngapunten. Kulo kalian keluarga kulo mboten PKI.”
(Saya mohon ampun. Kami sekeluarga bukan anggota PKI)
(Nggak usah kebanyakan alasan! Kalian semua sudah pasti para pembantu PKI. Djengkol sudah terbukti menjadi markas PKI.-
“Panguporane cak. Kulo mboten PKI. Kulooo mboten…”
(Mohon ampun. Saya bukan PKI. Saya bukaaan…)
BUGH!!!
“Wes gak usah kesuwen! Seret kabeh metu tekan omah e!”
(Jangan menghabiskan waktu! Seret semua keluar dari rumah masing-masing!) Perintah seseorang kemudian.
Mungkin mereka sadar bahwa sebentar lagi kejadian buruk akan segera-
Tak terelakkan, selang beberapa saat terdengar suara pekikan penuh kesakitan. Bersamaan dengan itu, kudengar suara layaknya seorang yang menebas batang pohon pisang berulang-ulang. Suara mengerikan itu terdengar diseluruh penjuru desa kurasa.
Nyatanya hunusan parang dan celurit mampu menebas beberapa anggota tubuh bahkan kepala manusia dengan mudahnya.
Entah mengapa aku mengikuti mereka meski sudah tahu hidup mereka tak akan selamat.
Langkah kaki kecil itu terseok-seok demi menyamakan langkah ibunya. Meski tertusuk duri, tertusuk kerikil tajam karena tak memakai alas, mereka menahan rasa sakitnya demi bertahan hidup.
Dan benar saja, tak butuh waktu lama mereka berhasil dicegat. Keduanya diseret dengan sangat kasar,-
Sang ibu memberontak sekuat tenaga demi menyelamatkan sang anak yang diseret sama sepertinya. Bisa kulihat kulit dibeberapa bagian tubuh mereka mengelupas hingga berdarah.
Gadis kecil itu meraung menangis sejadinya, bukan sebuah rayuan menenangkan, namun tendangan kasar yang didapatkan. Berhasil membuat tubuh kecil itu terpelanting hingga terhempas keras disebuah batang pohon.
bunya berteriak histeris saat si gadis kecil kembali ditendang karena tak mau berhenti menangis.
Hingga akhirnya kepala atas sang ibu dicengkeram kuat-kuat, belum sempat aku mengedipkan mata, sebuah parang telah menebas lehernya-
CLAKKKKK…. CLAKKKKK..
Aku berdiri disebuah bangunan besar beragaya belanda. Tak jauh berbeda dengan yang ada di desa, di sana suasana ramai nan mencekam telah berlangsung.
Lagi kusaksikan pemandangan mengerikan. Namun orang-orang ini saling balas tebas-menebas,-
Ada hal-hal aneh yang kulihat. Beberapa diantara mereka tak mudah mati. Ada yang sudah ditebas berulang kali, namun tak luka sedikitpun.
Beberapa orang tampak berulang kali menebas tubuh seorang pria tambun dengan kelewang, dibantu dengan temannya yang memegang parang berukuran besar, namun tak juga mempan.
Pria bertubuh tambun itu masih kuat bahkan membalas perlawanan dengan-
Tiba-tiba ia berhasil mencengkeram leher salah satunya, mencekik, lalu memutar kepala seorang pemuda jangkung hingga patah.
Senjata tajam tak mampu menembusnya, namun sebuah tongkat rotan-
Lalu salah seorang lagi mencengkeram rambut atasnya hingga-
(Mati kamu PKI!)
Dan benar kulihat sebuah kain merah berlambang palu arit terlilit disalah satu lengannya.
KLAKK! KLAKKKK! KLAAKKKK!
Sebuah kusen tampak bergerak kasar seolah mau dibuka paksa.
(Gerwaninya ada di sini!!!) Teriak salah seorang yang ada diluar.
Tak lama kemudian terdengar suara gebrakan, pintu didobrak dengan paksa dari luar. Para wanita itu mundur perlahan menempel didinding tembok paling belakang.
Sekumpulan orang yang berhasil menerobos masuk, menyeret beberapa gerwani.
Aku pun tak tahu apa yang mereka alami hingga hilang rasa kemanusiaan.
**
Aku juga tak bisa membayangkan berada diposisinya yang diberi penglihatan secara langsung, melihat pembantaian sadis di depan mata-
**
Tak terasa waktu berjalan cepat, langit berubah warna menjadi gelap seluruhnya. Untunglah bulan terlihat penuh dan bintang-bintang tampak lebih jelas dari bawah bumi perkemahan.
Malam ini adalah malam perpisahan Jumbara. Acara perpisahan tampak meriah,-
“Awakmu tampil bariki Ji?” (Kamu perform bentar lagi Ji?)
“Guayamu. Terus penyanyimu sopo?” (Sok iya banget deh. Lalu siapa vokalismu?)
“Uhmmm… sopo yo?” (Uhm… siapa ya?)
“Sopo?” (Siapa?) Tanyaku penasaran.
“Ra ha si a.” Jawabnya sok misterius.
Tak beberapa lama kemudian, kudengar MC dipanggung memanggil nama Aji untuk perform selanjutnya. Mendengar nama ‘Aji’ sontak kudengar suara tepukan nan riuh, bahkan diantaranya berteriak memanggil nama-
Aji sudah berdiri diatas panggung. Ia duduk disebuah kursi yang mana ada sebuah mic dan tongkat sebagai penyangganya. Kepalaku celinguk kesana-kemari menunggu siapa kali ini yang jadi si vokalis, namun setelah beberapa lama tak kutemukan-
Aji mulai memetik senar-senar gitarnya secara perlahan. Kepalanya mendekati mikrofon hitam yang ada dihadapannya, lalu menyebut sebuah judul lagu. Aku tercengang, sebuah suara merdu keluar dari bibir temanku yang satu itu.
Bahkan aku dengan pedenya sering meminta dia mengiringiku suara cemprengku yang bernyanyi asal-asalan saat-
Bahkan saat menyanyi lagu dengan nada tinggi, suaranya pun datar bahkan seolah hampir putus rasanya.
Namun bangga juga punya teman yang multitalent begini, pikirku.
“Ji… Awakmu iso nyanyi ternyata? Ngunu nek nyanyi nang ngarepku kok mbok fals-falsne?”
Aji kembali dengan cengir khasnya “Lapo? Aku dadi nambah ya ganteng e pas nyanyi?”
Aku memasang mimik ingin muntah saat mendengar pernyataannya, namun Aji kembali tertawa sembari mengusap rambutku.
Dan mungkin diantara kalian juga memiliki pengalaman menarik dan menegangkan diacara serupa yang tak terlupakan sepertinya Banana.
Sampai Jumpa di thread selanjutnya.
“KEBUN DJENGKOL” -TAMAT-